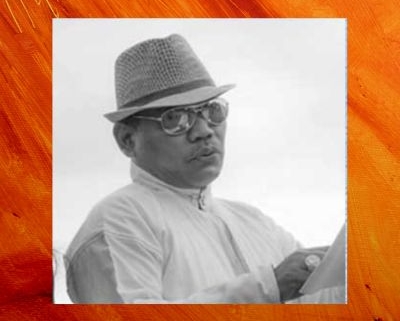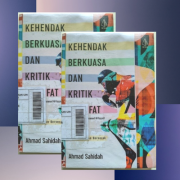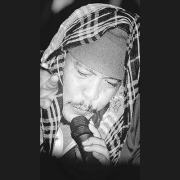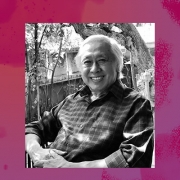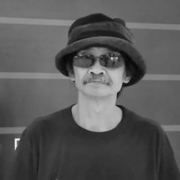Pesantren dalam Pusaran Filsafat Eksistensial dan Pendidikan Karakter
Oleh: Gus Nas Jogja*
Pesantren, secara harfiah, adalah tempat tinggal para santri. Namun, secara eksistensial, ia adalah sebuah Ruang Penyingkiran Diri atau Space of Self-Exile. Memilih Pesantren adalah sebuah keputusan radikal, sebuah penolakan sublim terhadap kepastian dunia luar yang didominasi oleh hiruk-pikuk materi dan gemerlap fatamorgana. Ini adalah langkah pertama menuju filsafat eksistensial khas Pesantren: pengakuan akan kefanaan diri dan pencarian makna (meaning-making) yang melampaui biologi, antropologi dan bahkan sosiologi.
Di gerbang Pesantren, seorang anak manusia menanggalkan identitas lamanya—status sosial, kenyamanan keluarga, pakaian bermerek—dan menerima seragam kesederhanaan (sarung dan peci). Momen ini adalah leap of faith eksistensial. Ia memasuki pondok, bukan sekadar asrama, melainkan “Kepompong Kontemplasi” tempat transformasi jiwa terjadi.
Ia datang dari rumah ke Pesantren membawa bekal cemas dan rindu. Menanggalkan warna-warna kota, kenyamanan, dan bahkan kemewahan untuk memeluk kain kusam di Pesantren. Di sinilah, di hamparan tikar lusuh, ia harus jujur: Siapa aku di antara tumpukan kitab dan debu subuh?
Pesantren bukan tembok, ia adalah cermin terjal, yang memaksa jiwa berhadapan dengan dirinya yang paling telanjang.
Eksistensi santri diatur oleh kedisiplinan waktu dan ruang yang ketat selama 24 jam dalam sehari. Ini bukan pengekangan, melainkan kerangka kerja eksistensial untuk melawan entropi batin. Waktu dipecah menjadi ibadah, belajar, dan khidmah. Ini adalah strategi Tafaquh Fiddin: mencari makna Tuhan bukan di ruang kosong, melainkan di dalam komitmen waktu yang terstruktur. Dalam filsafat eksistensial, Pesantren mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir dari komitmen radikal—komitmen terhadap Ilmu dan Adab.
Tafaquh Fiddin: Menanggulangi Kegelisahan Intelektual
Prinsip Tafaquh Fiddin (pendalaman ilmu agama) adalah jawaban Pesantren terhadap kegelisahan intelektual manusia (existential angst). Bagi santri, ilmu adalah alat untuk memahami kehendak Tuhan—satu-satunya Kepastian di lautan Ketidakpastian eksistensi.
Filsafat Keterasingan dan Kitab Kuning
Santri yang berkutat dengan Kitab Kuning—teks-teks klasik berbahasa Arab dengan coretan makna (pegon) khas Pesantren—mengalami bentuk keterasingan yang produktif. Mereka terasing dari bahasa, budaya, dan konteks zaman yang termuat dalam kitab-kitab tersebut, yang sebagian besar ditulis berabad-abad lalu.
Keterasingan ini bukan kebodohan, melainkan Latihan Ijtihad Awal. Santri dipaksa bertanggung jawab secara personal atas makna yang ia tarik. Kyai hanya memberikan kunci; membuka pintu makna adalah beban eksistensial santri itu sendiri. Metode Sorogan (membaca di hadapan guru) adalah praktik akuntabilitas eksistensial: setiap kata yang dibaca adalah penegasan atas pemahaman dan komitmen.
“Dalam sunyi subuh di bawah lampu teplok, santri itu bergumul dengan Ibarat atau frasa teks yang pelik. Ia bukan hanya menerjemahkan; ia sedang menafsirkan eksistensinya melalui lensa ulama berabad silam. Inilah hakikat Tafaquh: ia mengubah keterasingan tekstual menjadi jembatan spiritual.”
Bahtsul Masail: Dialektika Eksistensial
Bahtsul Masail (forum diskusi keagamaan) adalah panggung eksistensial bagi Tafaquh Fiddin. Ini adalah ruang di mana santri harus menghadirkan dirinya secara utuh—akal, emosi, dan adab—dalam perdebatan.
Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab. Santri didorong untuk berargumen, mencari dalil (bukti) yang paling kuat, bahkan jika argumennya berseberangan dengan teman sebaya atau pandangan populer. Ini menumbuhkan karakter keberanian intelektual dan otonomi berpikir. Namun, kebebasan ini disertai tanggung jawab untuk menjaga adab al-khilaf (etika perbedaan pendapat). Karakter toleransi lahir bukan dari paksaan, melainkan dari pengakuan eksistensial bahwa kebenaran itu berlapis dan manusia memiliki keterbatasan dalam menangkapnya.
Budi Pekerti: Proyek Eksistensi dan Estetika Moral
Jika Tafaquh Fiddin adalah pencarian makna kognitif, maka Budi Pekerti adalah proyek eksistensial untuk mewujudkan makna tersebut melalui tindakan dan estetika moral. Pesantren mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan indah—bukan indah fisik, melainkan indah etika.
Khidmah atau pengabdian adalah praktik eksistensial paling mendasar di Pesantren. Ia menantang ego dan nafsu kepemilikan. Santri membersihkan toilet, mencuci pakaian Kyai, atau menyapu halaman tanpa bayaran.
Khidmah adalah penegasan karakter keikhlasan dan kerendahan hati (Tawadhu’). Ketika seseorang melakukan pekerjaan tanpa motif pujian (riya’) atau imbalan materi, ia sedang melakukan tindakan murni yang hanya memiliki makna antara dirinya dan Tuhan. Ini adalah penemuan makna diri melalui pelayanan transenden.
“Santri itu menyeka keringatnya di atas tumpukan piring kotor. Di sudut itu, ia merayakan dirinya yang tak penting. Ia menanggalkan ‘aku’ yang sombong, menemukan keindahan dalam ‘kami’ yang melayani. Ia belajar bahwa karakter tidak terukir dalam piagam, tetapi dalam sunyi sikat dan bau sabun. Inilah keindahan zuhud.”
Kyai: Sang Murabbi sebagai Liyan (The Other) Eksistensial
Kyai adalah figur sentral yang melampaui peran guru. Ia adalah Murabbi (pendidik jiwa) dan Mursyid (pembimbing spiritual). Dalam filsafat eksistensial, Kyai berfungsi sebagai Liyan Transenden (Transcendent Other)—seseorang yang kehadirannya menuntut santri untuk terus menerus memperbaiki diri.
Kyai tidak banyak berkhotbah tentang karakter; beliau menghidupinya. Santri mengamati cara Kyai berjalan, berbicara, marah, dan berdoa. Karakter Sidiq (jujur), Amanah (terpercaya), Fathanah (cerdas), dan Tabligh (menyampaikan) diinternalisasi melalui proses imitasi yang sadar dan penghayatan (ta’dhim).
Diceritakan seorang Kyai selalu membiarkan santri terbaiknya membawa air minum untuknya, baik dingin maupun hangat, tanpa berkomentar. Namun, ia selalu mengucapkan terima kasih dengan intonasi yang berbeda. Ketika airnya dingin di musim hujan, ucapan terima kasihnya terasa mengandung pertanyaan sunyi. Santri itu, yang telah berbulan-bulan melayani, akhirnya menyadari bahwa Budi Pekerti yang sejati adalah kepekaan atas keberadaan liyan. Karakter bukan tentang mengikuti perintah, melainkan tentang membaca hati dan mengantisipasi kebutuhan orang lain. Sejak saat itu, ia selalu menyajikan air hangat di musim hujan. Kyai tersenyum dan berkata, “Karaktermu kini matang, Nak. Ia tidak hanya berisi air, tetapi juga cahaya empati.”
Karakter Pejuang: Eksistensi Melawan Kebatilan
Pesantren tidak hanya mencetak ahli ibadah, tetapi juga karakter pejuang yang sadar akan tanggung jawab historis dan politiknya.
Konsep Hubbul Wathan minal Iman (Cinta Tanah Air adalah bagian dari Iman) yang diperjuangkan oleh ulama seperti Hadratusyaih Hasyim Asy’ari adalah penegasan eksistensial: eksistensi spiritual tidak terpisah dari eksistensi teritorial.
Hadratusyaih Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad (1945), sebuah keputusan yang sangat berisiko, menuntut santri meninggalkan zona aman pondok untuk berjuang fisik. Ini adalah penegasan tertinggi dari karakter keberanian moral dan komitmen sosial. Beliau mengajarkan bahwa spiritualitas harus berwujud aksi konkret melawan kezaliman (kolonialisme).
Karakter Reformis: Dari Tradisi ke Transformasi
Tokoh-tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan ulama-ulama mutaqaddimin seperti Syekh Nawawi Al-Bantani menunjukkan karakter pembaruan dan integritas intelektual.
Kyai Ahmad Dahlan berani keluar dari kerangka Pesantren Salaf yang murni Kitab Kuning untuk mendirikan sekolah modern, menunjukkan karakter ijtihad dan responsif terhadap tantangan zaman. Beliau mengajarkan bahwa karakter harus adaptif, mampu menanggapi “kegelisahan historis” dengan solusi yang terorganisasi (amal saleh terstruktur).
Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menjadi Imam di Makkah, membuktikan bahwa komitmen pada tradisi tidak menghalangi pencapaian keilmuan global. Karyanya yang menjadi rujukan dunia menunjukkan karakter ketekunan literasi yang melahirkan otoritas transnasional.
Pesantren sebagai Janji Eksistensi
Pesantren, dalam paradigma pendidikan karakter, adalah sekolah yang mengatasi dualisme. Ia menyatukan filsafat eksistensial dengan teologi; spiritualitas dengan sosialitas; dan kebebasan dengan tanggung jawab.
Karakter yang dicetak Pesantren adalah karakter yang berani ada (dare to be):
1. Berani Sunyi: Melalui Riyadhah, ia menemukan dirinya dalam keheningan batin.
2. Berani Jujur: Melalui Sorogan dan Muhasabah, ia berhadapan dengan keterbatasannya.
3. Berani Melayani: Melalui Khidmah, ia menemukan makna diri di luar ego.
4. Berani Bertanggung Jawab: Melalui Tafaquh Fiddin dan Jihad, ia menyadari perannya dalam takdir kolektif.
Maka, Pesantren bukan sekadar tanah dan bangunan. Ia adalah Wadah Eksistensi tempat jiwa ditempa. Di mana sarung lusuh adalah bendera pengakuan atas ketidaksempurnaan. Di mana aroma kopi dan kitab adalah dupa bagi keikhlasan. Karakter sejati bukan warisan, ia adalah pilihan. Pilihan sunyi seorang santri untuk menjadi Cahaya, yang bersinar abadi di tengah kegelapan yang fana. Itu saja.
—-
*Gus Nas Jogja. Budayawan.