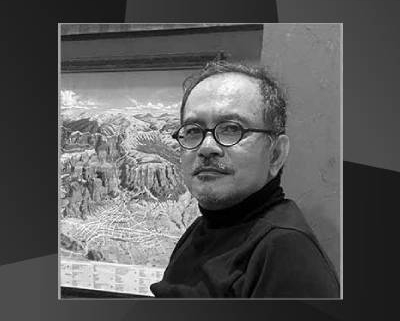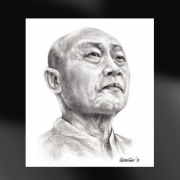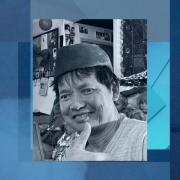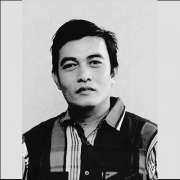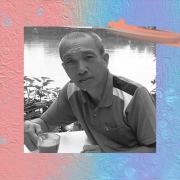Suku Digital dan Krisis Algoritma
Oleh Tony Doludea*
Unjuk rasa menolak tunjangan perumahan DPR di seputaran Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, berlangsung sejak Senin 25 Agustus 2025 siang hingga malam.
Mereka turun ke jalan karena tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR itu dinilai tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Emosi mereka kian tersulut setelah melihat pernyataan dan sikap dari sejumlah anggota DPR yang tidak empatik. Anggota DPR berjoget-joget saat Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 15 Agustus 2025 itu.
Unjuk rasa ini dipicu oleh undangan berdemonstrasi yang tersebar di media sosial selama beberapa pekan terakhir. Bukan hanya mahasiswa, juga para pelajar SMA, pengemudi ojek daring dan kelompok masyarakat lain.
Pada Selasa, 26 Agustus 2025 terindikasi ada pendengung yang mengampanyekan wacana bubarkan DPR. Seruan unjuk rasa 25 Agustus itu ditengarai pertama kali muncul lewat pesan berantai dari grup percakapan WhatsApp dan media sosial yang menyerukan untuk membubarkan DPR.
Pada Jumat 22 Agustus 2025, gagasan pembubaran DPR itu ditanggapi oleh Ahmad Sahroni, politikus Partai NasDem. Sahroni menyebut bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang tolol sedunia.
Pernyataan Sahroni itu membuat masyarakat merasa tidak puas dan bereaksi secara keras terhadap dirinya.
Pada Sabtu 30 Agustus 2025 sore, rumah Ahmad Sahroni di kawasan Jakarta Utara didatangi sejumlah orang tidak dikenal. Mereka merusak rumah, mobil, serta mengambil barang-barang berharga.
Kaca rumah pecah, furnitur hancur, serta mobil mengalami kerusakan parah dengan kaca pecah, bodi penyok, hingga bagian depan nyaris hancur.
Massa menjarah barang-barang di dalam rumah, termasuk perabotan, barang elektronik dan koleksi pribadi. Lemari, kursi, meja, kasur, TV, kulkas, mesin cuci hingga alat pendingin ruangan. Barang-barang pribadi seperti ijazah, pakaian, tas, surat tanah, SKCK, Kartu Keluarga dan pakaian.
Ketua RT setempat menyatakan bahwa massa yang menjarah itu bukan warga setempat, melainkan dari daerah lain. Mereka tidak menggenal massa penjarah itu, masih remaja-remaja semua.
Sekitar pukul 20.47 WIB. massa yang menjarah rumah Sahroni itu berangsur membubarkan diri.
Sementara rumah Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jakarta Selatan pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025 juga dijarah massa. Juga rumah Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Surya Utama dijarah pada hari yang sama.
Sedangkan Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tangerang Selatan, terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 sekitar pukul 01.00 hingga 03.00 WIB.
Para saksi mata mengatakan bahwa massa yang berjumlah ratusan itu rata-rata remaja.
Bareskrim Polri kemudian menangkap pelaku yang memprovokasi penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya.
Pelaku berinisial IS ditangkap pada Senin 1 September 2005. IS adalah pemilik akun TikTok @hs02775 dan berperan menyebar ajakan penjarahan rumah-rumah anggota DPR.
Perbuatan tersangka membuat dan mengunggah konten video melalui akun media sosial TikTok dengan tujuan menimbulkan rasa benci kepada individu dan kelompok masyarakat tertentu.
Selain IS, pasangan suami istri berinisial SB dan G yang menyebar hasutan untuk menjarah. SB pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Nannu dan tersangka G pemilik akun media sosial Facebook dengan nama akun Bambu Runcing.
SB juga berperan sebagai admin WhatsApp grup Kopi Hitam, yang berganti nama menjadi BEM RI dan berganti nama menjadi ACAB 1312.
Sementara CS selaku pemilik akun media sosial TikTok @Cecepmunich. CS membuat konten provokatif yang mengajak agar aksi demonstrasi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.
Para tersangka itu dijerat Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE nomor 1 tahun 2024 dan Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.
********
Stabilitas sosial adalah keadaan masyarakat yang stabil dan teratur, di mana norma, lembaga dan hubungan sosial berfungsi secara selaras. Ini memungkinkan kerja sama, penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
Lingkungan yang stabil itu akan menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga masyarakat dapat berfungsi dan berkembang secara berkelanjutan.
Jelas bahwa kejadian tersebut merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas sosial bangsa Indonesia. Ancaman tidak lagi datang hanya dari kerumunan massa di jalan, melainkan juga dari percikan di ruang siber.
Kejadian itu semua berasal dari disinformasi, berupa unggahan singkat, komentar spontan dan tagar populer, yang dirancang dengan bantuan algoritma Kecerdasan Buatan (AI).
Para pelakunya sebagian besar adalah remaja dan pelajar SMA. Prensky mengatogerikan mereka sebagai digital natives, yaitu generasi yang habitat aslinya adalah dunia digital.
Mereka dilahirkan dalam suatu keadaan, ketika teknologi terus berevolusi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seperti Hukum Moore yang mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor itu mengikuti rumusan eksponensial.
Digital Natives bertatap muka satu sama lain dan dengan dunia mereka melalui peralatan digital.
Mereka biasa dikategorikan sebagai Generasi Z, yang lahir antara 1995–2010 dan sekarang berusia antara 12–20 tahun. Generasi ini semakin bergantung pada teknologi, gawai dan internet. Mereka aktif “hidup” dan beraktivitas di media sosial dan mengakses media sosial mereka setiap jam.
Mereka juga dikategorikan sebagai Generasi Alpha, yang lahir antara 2011 sampai saat ini. Mereka hidup berdampingan dengan teknologi dan tidak bisa hidup tanpa alat digital.
Remaja dan anak generasi tersebut dikenal juga sebagai Suku Digital. Suku ini merupakan sekelompok manusia dengan satu budaya dengan ciri-ciri tertentu.
Suku Digital adalah kelompok sosial dengan ikatan budaya dan minat, tujuan serta pengalaman bersama yang kuat dalam dunia digital.
Teknologi digital membentuk kebudayaan mereka, yang berbeda dengan “budaya” generasi sebelumnya. Perbedaan dalam cara berpikir dan cara menggunakan pikiran untuk memproses informasi. Penduduk asli Suku Digital ini terpapar teknologi digital sejak lahir.
Mereka adalah penutur asli bahasa digital dari komputer, video game dan internet. Mereka terbiasa menerima informasi dengan sangat cepat dan instan.
Namun para remaja itu terbukti dalam kasus di atas, sangat mudah dimanipulasi dan digerakkan untuk melakukan kerusuhan, penjarahan dan pembakaran.
Pemanipulasi dan penggerak itu adalah algoritma Kecerdasan Buatan. Di mana konten yang provokatif diprioritaskan, sedangkan klarifikasi faktual ditenggelamkan.
Algoritma adalah seperangkat instruksi atau perintah yang dirancang untuk mengerjakan sesuatu dalam mesin Kecerdasan Buatan. Pengumpulan Data, Pra-pemrosesan Data, Pelatihan Model, Evaluasi Model, Implementasi dan Penyebaran, serta Pemeliharaan dan Pembaruan
Kecerdasan Buatan adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk meniru cara berpikir manusia.
Algoritma Kecerdasan Buatan adalah dasar sistem ini, yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, membuat keputusan dan melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
Krisis algoritma itu ditambah dengan muslihat disinformasi menggunakan Kecerdasan Buatan, yang mampu memproduksi konten palsu dalam jumlah banyak.
Misalnya, deepfake adalah salah satu bentuk Kecerdasan Buatan yang digunakan untuk membuat foto, audio, video hoax yang meyakinkan.
Deepfake dibuat menggunakan dua algoritma Kecerdasan Buatan yang saling bertentangan, yaitu generator dan diskriminator. Generator menciptakan data sintetis (gambar, suara) dari input acak. Sementara diskriminator berfungsi sebagai “kritikus” yang bertugas membedakan data asli dari data palsu yang dihasilkan generator.
Kemudian kedua jaringan saling meningkatkan, generator menghasilkan data yang semakin meyakinkan dan diskriminator semakin mahir dalam mendeteksi ketidaksempurnaan.
Satu deepfake, narasi palsu di dunia maya saja sudah dapat menggerakkan para remaja ini.
Disinformasi berbasis Kecerdasan Buatan terbukti dapat menggerakkan emosi massa dalam sekejap. Masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan rekayasa dunia digital.
Realitas manusia saat ini tidak lagi dibangun dari fakta, melainkan oleh algoritma. Algoritma media sosial seharusnya membantu orang menemukan informasi. Namun kini menjadi muslihat disinformasi dengan memprioritaskan konten yang provokatif, karena paling banyak menghasilkan klik dan interaksi. Satu video dapat langsung memicu kemarahan massa, sebelum kebenarannya sempat diverifikasi.
Masalah ini muncul secara tidak terduga pada era digital ini. Tentu saja ini sangat berdampak terhadap Suku Digital tersebut. Maka di sini diperlukan usaha literasi digital, sebagai keterampilan yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh mereka.
Literasi digital adalah pemahaman tentang dunia digital yang mencakup cara menggunakan perangkat digital, mencerna informasi, berinteraksi secara digital, hingga memahami risiko dunia digital. Bagaimana mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan menilai informasi secara kritis.
Dengan literasi digital, Suku Digital diharapkan dapat menghadapi risiko dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Bagaimana memilah informasi yang tepat, di antara arus informasi dan mampu membedakan konten positif yang bermanfaat dengan konten negatif yang merusak.
Literasi digital juga dapat meningkatkan kemampuan membaca, kemampuan verbal, daya fokus, konsentrasi, merangkai kalimat dan menulis informasi.
********
Kejadian itu juga dapat mengikis legitimasi pemerintah dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Maka pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah luar biasa untuk mencegahnya. Tanpa harus bersikap dan bertindak secara otoriter dan totaliter.
Keadaan sudah sangat mendesak jika masyarakat memperhatikan persitiwa-peristiwa di atas. Pemerintah dan masyarakat hendaknya segera menanggapi secara serius melalui regulasi algoritma.
Regulasi untuk mengatur platform digital agar transparan mengenai apa dan bagaimana cara kerja algoritma yang mereka gunakan. Regulasi ini juga untuk mengatur konten politik dan kepentingan keamanan publik.
Selain penguatan literasi digital dan fact-checking nasional. Di sini masih harus ditambah dengan revisi UU ITE dan memasukkan regulasi Kecerdasan Buatan.
Sehingga masyarakat secara tepat dapat membedakan antara konten asli dengan konten manipulatif. Regulasi juga mengatur tanggung jawab produsen teknologi maupun pengguna.
Dengan adanya regulasi yang lebih tegas, diharapkan pemerintah mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia dari ancaman deepfake yang semakin canggih dan meresahkan. Juga melindungi anak dari konten berbahaya di ruang digital.
Memang Indonesia telah mengambil langkah nyata dalam menanggulangi penyebaran deepfake melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.
Menurut UU PDP, pasal 66 dan 68 secara tegas melarang pembuatan data pribadi palsu dan mengancam pidana bagi pelanggar. Sementara itu, KUHP Baru juga merumuskan pasal-pasal yang mengatur deepfake dengan beragam sanksi pidana.
Deepfake yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik akan dikenai sanksi berdasarkan pasal 433, 434, 436, dan 441. Sedangkan deepfake yang berisi konten kebencian dan permusuhan diancam dengan pasal 243. Untuk deepfake berkonten pornografi, sanksi diberlakukan berdasarkan pasal 407.
Pemberlakuan KUHP Baru merupakan reformasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP Baru, beberapa pasal dalam UU ITE telah dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh pasal-pasal KUHP Baru, yang akan efektif berlaku pada 2 Januari 2026 nanti.
Meskipun teknologi dan sistem keamanan siber terus berkembang, namun ekosistem digital masyarakat Indonesia tetap harus dibangun dengan baik, untuk mengurangi risiko penipuan dan kejahatan siber.
Kenyataan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat empat besar dunia sebagai pengguna media sosial. Pada 2025 jumlah total pengguna media sosial di Indonesia sebesar 207 juta. Pengguna internet sebanyak 229,4 juta, 126 juta penggunanya berusia 18 tahun ke atas dan generasi muda mendominasi dunia siber ini.
Edukasi publik tentang pentingnya membangun ekosistem digital yang cerdas ini diharapkan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan krisis algoritma. Masyarakat pun diimbau untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam menggunakan media sosial.
Kepustakaan
Prensky, Marc. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Corwin Publishers, California, 2010.
Prensky, Marc. Don’t Bother Me Mom. Paragon House Publishers, Minnesota, 2006.
Prensky, Marc. From Digital Natives to Digital Wisdom. Corwin Publishers, California, 2012.
Prensky, Marc. Education to Better Their World: Unleashing the Power of 21st-Century Kids. Teachers College Press, New York, 2016.
Sumber Internet
——
*Tony Doludea, Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indo.