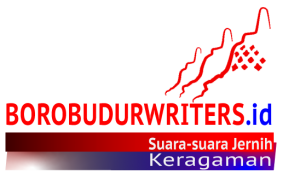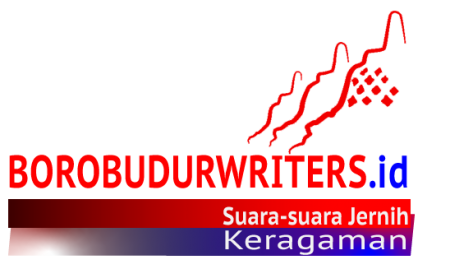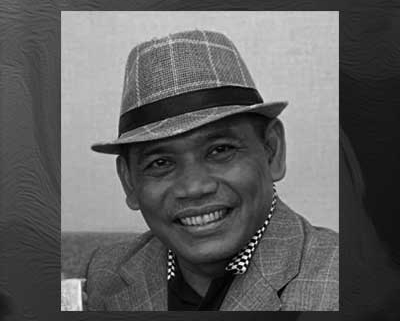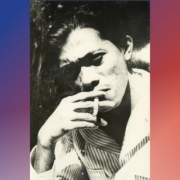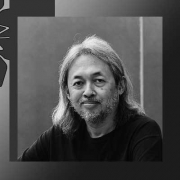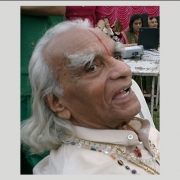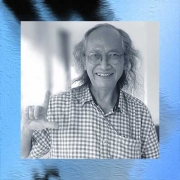Mimpi Toety Heraty Noerhadi
Oleh Gus Nas Jogya
Sebuah inisiatif dekolonial yang radikal
Penerbitan sebuah Ensiklopedia Filsafat Nusantara (EFN) bukan sekadar proyek keilmuan yang baru, melainkan sebuah inisiatif dekolonial yang radikal. Gagasan yang dicetuskan oleh Prof. Toeti Heraty Noerhadi ini muncul sebagai respons terhadap tindakan Dictionnaire des Philosophes, yang pada edisi 2009 menghapus 15 nama filsuf Indonesia. Tindakan ini, yang mungkin didasarkan pada asumsi bahwa pemikiran mereka tidak sesuai dengan kriteria filsafat Barat yang bertumpu pada tradisi rasional-dialektis Yunani Kuno, sesungguhnya adalah gejala kegagalan epistemologis: kegagalan untuk mengakui dan memahami sistem pengetahuan yang berbeda.
Epistemologi Kebudayaan Nusantara
Berbeda dengan filsafat Barat yang terstruktur dalam tradisi teks dan debat logis, epistemologi Nusantara adalah sebuah sistem pengetahuan yang terintegrasi, holistik, dan bersifat non-dualistik. Pengetahuan di sini tidak hanya bersumber dari nalar murni, tetapi juga dari pengalaman kosmik, spiritual, dan relasional. Pemikiran-pemikiran ini tidak selalu termanifestasi dalam bentuk traktat atau risalah filosofis layaknya di Barat, melainkan tersebar dan tersembunyi dalam berbagai artefak dan tradisi.
Data Manuskrip, Bukti Arkeologi, dan Tradisi Lisan
Untuk memahami kedalaman pemikiran filsafat Nusantara, kita harus merunut jejaknya dari era kerajaan-kerajaan kuno. Pemikiran para Empu di era Majapahit dan Kadhiri, seperti Empu Prapanca dalam Nagarakretagama dan Empu Tantular dalam Arjunawiwaha, menyematkan gagasan-gagasan tentang kepemimpinan yang ideal, kosmologi, dan etika kekuasaan. Ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cerminan filosofi negara. Sementara itu, Prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, meskipun singkat, memuat konsepsi kosmologis tentang hubungan antara kekuasaan raja dengan legitimasi dewa-dewa, menunjukkan fondasi pemikiran politik dan religius yang sudah mapan. Demikian pula, tradisi Kerajaan Salakanagara di Sunda, yang tercatat dalam Naskah Sunda Kuno, menunjukkan pemikiran filosofis tentang tatanan alam, hubungan manusia dengan lingkungan, dan kosmologi pra-Islam.
Selain itu, naskah I La Galigo (abad ke-13-15) dari Bugis, Sulawesi Selatan, adalah bukti otentik dari sistem filosofis non-Jawa. Epic ini menguraikan kosmologi, teologi, dan etika masyarakat Bugis dalam narasi yang padat, menunjukkan pemikiran yang kompleks tentang penciptaan, hubungan manusia dengan alam, dan tatanan sosial yang harmonis.
Filsafat dalam Perspektif Literasi Kesenian
Pemikiran filsafat Nusantara juga terartikulasi secara mendalam melalui berbagai seni pertunjukan dan sastra yang menjadi bagian dari literasi kebudayaan. Tari Bedhaya Srimpi dan Bedoyo Ketawang bukan sekadar tarian, melainkan representasi filosofis tentang harmoni kosmos dan mikrokosmos, serta perjuangan batin antara kebaikan dan keburukan. Gerak-gerik yang lambat dan penuh makna adalah simbol dari perjalanan spiritual yang tenang dan terkendali. Pencak Silat, di sisi lain, adalah manifestasi filsafat praktis. Gerakannya tidak hanya bertujuan untuk pertahanan diri, melainkan juga untuk mencapai keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Filosofi di baliknya adalah tentang penguasaan diri (tapa) dan penyatuan dengan alam semesta (manunggaling kawula-gusti).
Selain itu, tradisi sastra seperti Kidung Macapat dari Jawa, adalah wahana utama untuk mengajarkan filsafat hidup secara populer. Setiap metrum (bait) dan tembang (lagu) dalam Macapat memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri, melambangkan tahapan-tahapan kehidupan manusia, dari kelahiran hingga kematian. Melalui Macapat, pemikiran tentang etika, moralitas, dan spiritualitas diturunkan dari generasi ke generasi dengan cara yang mudah dipahami dan dihayati.
Dari Era Klasik hingga Modern
Transisi ke era modern juga memperlihatkan perkembangan filosofis yang luar biasa. Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) mengembangkan filsafat Islam modernis yang berupaya mensintesiskan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah dengan tantangan zaman, menekankan pentingnya amal saleh dan pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan. Di sisi lain, Ki Hadjar Dewantoro (1889-1959) merumuskan filsafat pendidikan yang humanis dan emansipatoris melalui konsep Tri Pusat Pendidikan dan semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang menjadi fondasi epistemologi pendidikan nasional. Sementara itu, Hadratusyaih Hasyim Asy’ari (1875-1947) mengembangkan pemikiran filsafat politik Islam tradisionalis yang berfokus pada pentingnya menjaga harmoni sosial dan peran ulama dalam membangun peradaban bangsa yang berlandaskan pada Ahlussunnah wal Jama’ah.
FGD: Langkah Awal yang Krusial
Oleh karena itu, gagasan Prof. Toeti Heraty untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada 4 September 2024 di Gedung Toeti Roosseno Plaza, Jakarta, dan dilanjutkan dengan FGD berikutnya di Gallery Cemara 6 yang saya dihadirkan sebagai salah satu Pemateri, adalah langkah yang sangat krusial. FGD ini tidak hanya berdiskusi tentang “daftar nama”, melainkan tentang metodologi: bagaimana kita akan mendefinisikan “filsafat” dalam konteks Nusantara, bagaimana kita akan menafsirkan artefak, manuskrip, dan tradisi lisan, dan bagaimana kita akan mengategorikan sebuah pemikiran yang mungkin tidak memiliki penulis tunggal atau sumber teks yang jelas. Ini adalah tantangan untuk tidak hanya memproduksi ensiklopedia, tetapi juga untuk menciptakan sebuah arkeologi epistemologis baru yang mampu menggali, memahami, dan memvalidasi kekayaan intelektual bangsa dari sudut pandang yang mandiri.
Kesimpulan
Maka, Ensiklopedia Filsafat Nusantara (EFN) adalah lebih dari sekadar buku; ia adalah sebuah tonggak sejarah bagi peradaban pikir bangsa Indonesia. EFN akan menjadi sumber pemikiran utama yang menegaskan kemandirian intelektual bangsa di hadapan peradaban dunia. Lebih dari itu, ia akan menjadi acuan nilai dalam Pendidikan Karakter yang berakar pada kearifan lokal, memberikan panduan bagi generasi penerus untuk memahami identitas mereka yang kaya dan terintegrasi. Mimpi Prof. Toeti Heraty adalah sebuah seruan untuk kembali ke akar, menemukan kembali kebijaksanaan yang tersebar di seluruh Nusantara, dan membangun peradaban bangsa yang kokoh di atas fondasi pemikirannya sendiri.
—–
*Gus Nas Jogya, budayawan.