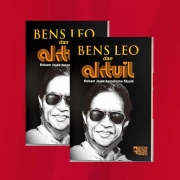Sains Dan Kematian Filsafat?
Oleh Dr. Soffa Ihsan*
Manusia pada fajar peradaban terpana pada alam semesta, khususnya pada sejumlah fenomena yang pada masanya tak sepenuhnya dimengerti. Kenapa ada hujan, banjir, gunung meletus, badai, wabah, penderitaan, kematian. Untuk menjelaskan misteri ini manusia menyusun cerita tentang adanya kekuatan tersembunyi, yang lebih besar dari manusia, dan mengatur alam di sekitarnya. Muncullah kisah-kisah dewa-dewi sebagai tafsir dan penjelasan. Apa saja yang tidak dimengerti manusia, dilimpahkan ke dewa-dewa. Apakah hujan itu, mengapa ada badai, mengapa ada wabah, bagaimana gunung meletus, manusia tidak tahu. Ya manusia kala itu hidup dalam sarwa kemisterian yang sesekali membuat ketakjuban dan juga mencekam (misterium tremendum).
Dari Mitos ke Logos
Upaya awal, dalam kesederhanaan cara berpikir, manusia memanusiawikan kekuatan alam sebagai ulah para dewa. Begitulah, pada masanya, cara termudah untuk menjelaskan hal-hal yang tak dipahami adalah menciptakan “agen” berkekuatan besar yang bisa melakukan berbagai hal di luar kemampuan manusia. Mengalihkan penjelasan sebab-musababnya ke dewa adalah jawaban termudah. Manusia bingung memahami, mengapa ada gempa, banjir atau juga wabah penyakit? Tak perlu repot memaknai atau menafsirkan, cukup dengan penjelasan: para dewa lah yang membuatnya.
Agama adalah kelanjutan cara berpikir mitologis politeistik itu. Upaya untuk menjelaskan segala sesuatu, dengan mengalihkan ke entitas supranatural sebagai jawaban. Tuhan adalah penggabungan dan penyatuan berbagai kekuatan dewa-dewa. Begitulah bahasa dunia era monoteisme.
Ibarat komputer, saat itu sistem operasi dan kapasitas memori otak manusia masih sangat terbatas. Operating system otak manusia belum mampu memproses secara baik begitu banyak informasi kehidupan alam di sekitar. Pertanyaan sulit tentang apa, bagaimana, mengapa, tentang fenomena alam yang dihadapi sehari-hari, lebih mudah diserahkan pada Tuhan, sebagai sumber segala pengetahuan. Dan Tuhan selalu menjawab, antara lain dengan menurunkan wahyu dan malaikatnya untuk membimbing manusia. Segala sesuatu terjadi semata-mata karena kehendak Tuhan, melalui konsep takdir.
Dengan turunnya agama, pertanyaan esensial, dari mana asal manusia dan kemana tujuannya, telah terjawab dengan pasti. Makna hidup “telah ditemukan” melalui agama. Hidup lebih mudah dipahami dan dijalani dengan hadirnya Tuhan selaku penentu takdir jalan hidup manusia. Agama menuntut keyakinan tanpa ada pertanyaan. Itulah kebutuhan manusia umumnya pada masa itu mendapat penjelasan yang memuaskan.
Namun bersamaan dengan turunnya agama dan hadirnya Tuhan, sebagian manusia menolak keyakinan dan memilih pemikiran. Sebagian manusia, yang menamakan diri “para pecinta kebijaksanaan”, memilih memakai penalaran, (logos) untuk menjelaskan hal-ihwal.
Kala itu manusia pada umumnya meyakini adanya kekuatan Tuhan monotheis yang menentukan segala hal. Di sebelah dunia lain di satu wilayah yang bernama Yunani juga di China dan India, sejumlah orang berpikir keras untuk mencari penjelasan alternatif. Mereka menebak-nebak tentang apa hakekat dunia, apa sebenarnya alam semesta, dan tersusun dari apa. Mereka adalah para filsuf yang menggunakan metode filsafat. Para filsuf klasik Yunani berspekulasi, memperdebatkan, apa esensi dibalik keberadaan alam semesta. Menurut mereka, alam semesta tersusun dari empat elemen tanah, air, api, dan udara. Thales menyebut air, Anaximenes menganggap udara, Empedokles menggabungkan api-udara-air-tanah, Anaxagoras menyebut pikiran dan Phytagoras memilih angka (matematika) sebagai esensi dunia. Begitulah filsafat, masing-masing filsuf bersikukuh dengan kebenaran spekulatifnya, yang terus terbawa hingga sekarang.
Sampai kemudian, sekitar 300 tahun lampau, muncul sains sebagai metode menguji fakta yang diperdebatkan para filsuf. Sains melanjutkan tradisi mempertanyakan, untuk mendapat penjelasan yang lebih pasti terkait dengan keyakinan (agama) dan keraguan (filsafat). Sains modern lahir dari pemikiran filsuf seperti Francis Bacon, Rene Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Auguste Comte, dan lain-lainnya, yang sering disebut Era Pencerahan.
Manusia menyusun cerita mitologi, agama, filsafat, dan sains sebagai navigasi agar hidup lebih mudah dijalani. Berbeda dengan mode cerita mitologi dan agama yang memiliki akhir, cerita sains tidak pernah tamat. Cerita sains terus bersambung, karena penjelajahan terra incognita, wilayah yang tak diketahui, terus dilakukan. Cerita sains selalu diperbarui, dilengkapi, dan diuraikan dengan semakin rinci. Tidak akan ada habisnya. Cerita sains adalah rangkaian sejarah afirmasi memilah cerita faktual dengan yang non-faktual seperti takhyul, mitos, occultisme, atau spekulasi.
Prinsip sains adalah melanjutkan rasa keterpukauan (sense of wonder) dan pertanyaan, yang diinisiasi oleh agama dan filsafat. Namun keterpukauan bukan lagi pada hal-hal yang agung seperti hakikat dan esensi alam semesta, melainkan pada hal-hal yang “remah-remah.” Sains modern muncul dari kegemaran para filsuf menyelidiki hal-hal yang bisa membantu sebagai pengetahuan praktis. Francis Bacon ingin mengawetkan daging agar tidak cepat membusuk, yang kemudian melahirkan teknologi lemari es pendingin modern. René Descartes bertanya-tanya mengapa lalat terbang masuk ke kamarnya tidak tersesat. Dengan mengamati lalat, Descartes merumuskan analisis geometri dan merumuskan metode sains modern awal.
Kesanggupan manusia untuk menangani urusan-urusan besar dan kecepatan menemukan informasi-informasi baru yang lebih akurat untuk pemecahan masalah adalah sebuah bukti kemajuan. Dalam urusan wabah umpamanya, kita tidak bisa menyamakan respon ilmu pengetahuan hari ini dengan keputusasaan manusia di abad ke14 menghadapi sampar yang berlangsung dua puluh tahun dan membunuh antara 75-200 juta orang. Atau membandingkannya dengan cara orang menangani wabah cacar dan dua kali pes di Meksiko sepanjang abad ke-16 yang membunuh 22 juta orang di negeri itu. Ataupun wabah abad pertengahan yang dikenal ‘black death’ yang membunuh puluhan juta manusia. Dengan bermodalkan ‘otoritas dogmatis’ tragedi hitam itu justru mengakibatkan persekusi terhadap kelompok lain yang divonis sebagai penyebab mewabahnya epidemi tersebut. Inilah yang membedakan antara wabah-wabah di masa lalu dan wabah dewasaini adalah kualitas informasi tentang cara menghadapinya.
Begitulah, di masa lalu informasi untuk menangani semisal wabah datang dari kalangan agama dan tindakan yang dilakukan bisa di luar nalar. Waktu yang panjang dan jumlah orang yang mati menunjukkan bahwa mereka membuat keputusan dengan informasi yang meleset. Di masa sekarang, informasi datang dari ilmuwan sains dan, berdasarkan itu, kita melakukan hal-hal yang relevan untuk mencegah penularannya.
Tentu masalah akan selalu ada. Selama manusia hidup dan melakukan aktivitas, selalu akan terbuka kemungkinan munculnya masalah, dan itu bahkan bisa terjadi dalam situasi normal, tidak hanya ketika terjadi ‘erupsi penyakit’ mematikan. Di masa mendatang banyak tengara-seperti Yuval Noah Harari- yang menyebutkan dunia akan menghadapi tantangan besar yaitu wabah penyakit, krisis pangan disamping perang dan terorisme.
Dari Nalari Ke Digitalisasi
Ray Kurzweil adalah saintis terpandang yang sekarang bekerja di Google dan merupakan salah satu nama inventor paling berpengaruh saat ini. Ia meramalkan selambat-lambatnya pada tahun 2045, akan tercipta manusia hibrid. Sulit dielak bahwa transhuman akan datang. Bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan.
Ada lagi nujuman akan ada ponsel yang telah terimplan dalam tubuh manusia secara komersial akan hadir di waktu yang tidak lama lagi. Saintis Jepang sudah bereksperimen ponsel yang bisa digerakkan dengan ‘gerak batin’ tanpa menggerakkan tangan. Sebagian prediksi itu bahkan sudah bisa kita lihat dan nikmati hari ini, yaitu tentang car-sharing, yang kemudian model bisnisnya terumuskan secara baik seperti cukup lewat aplikasi Gojek, Grab, atau inovasi aplikasi lainnya.
Dalam hal transportasi seperti Cina sudah menciptakan kendaraan nirsopir. Belakangan dan akan terus bergerak inovatif, mereka telah melahirkan teknologi bus tanpa supir ini dan sejak 2022 mengimplementasikannya di sejumlah rute. Cina pun sudah merancabg matahari buatan bahkan sudah bereksperimen menghidupkan orang mati. Imortalitas manusia menjadi kemungkinan yang bisa diwujudkan. Para pakar biologis seperti Richard Dawkin dan Sam Harris bahkan pula meyakini bahwa ‘manusia bisa menciptakan manusia’. Tehnologi kloning pernah berhasil diwujudkan pada domba yang diberinama Dolly beberapa tahun silam. Inovasi kloning sekarang sudah bukan lagi tehnologi yang canggih. Inovasi terus berkembang seiring kemajuan eksperimen biologi.
Elon Mask barusan berhasil menginplan ke otak manusia sebuah chip yang bisa membaca melalui pikiran.Ini menjadi proyek untuk melahirkan manusia supercerdas dan ke depan cukup dengan chip manusia tak perlu lagi sekolah. Disamping itu Elon Mask juga telah mempersiapkan membuat koloni baru di planet mars untuk ditinggali manusia. Ini tampaknya selaras dengan peringatan Stephen Hawking agar manusia segera mempersiapkan pindah dari bumi dan bisa mukim di planet lain. Bumi dirasa sudah sesak dengan manusia. Inovasi tehnologi lainnya, dan mungkin ini akan menjadi problem etis adalah 3D printing. Bikin rumah, bikin jantung palsu, tulang palsu, bisa menggunakan teknologi ini.
Dunia sains semakin menunjukkan etalase kemajuan mencengangkan. Berbagai wacana lama tentang realitas ontologis mendapatkan tafsir baru. Dunia artificial Intelligence (AI) tak pelak akan mengakselerasi berbagai penemuan teknologi dan pengetahuan baru.
Ilmu rasional berbasis nalar dan pikiran yang terelaborasi sejak Abad Pertengahan dan bahkan jauh sebelum itu telah mewariskan pencerahan. Dan semangat ini telah membawa manusia setahap lebih maju memasuki peradaban sains dengan berbagai turunan dan penemuan di banyak bidang, Para saintis berhasil membongkar rahasia semesta dan segala hal yang ada di sekelilingnya. Sebelumnya dilingkupi mitos dan cerita-cerita yang mengoreksi keyakinan dogmatis yang dicekokkan oleh agama. Manusia berhasil menemukan suatu pola-pola yang diterjemahkan dalam persamaan-persamaan matematika atau fisika, sehingga ada konsistensi yang dapat mempertahankan kebenarannya.
Proses itupun sesungguhnya tidak statis. Sebab dari masa ke masa selalu terjadi koreksi atas teori atau paradigma, dan itu dapat dibuktikan secara saintifik. Setiap teori terdahulu, didekati secara skeptisisme metodis dan dengan demikian menghasilkan teori yang terkoreksi. Para saintis berhasil membongkar dimensi terdalam sebuah benda sampai ke ujung paling kecil, atom. Atom ditandai dengan pola dan ciri tertentu, dan dibedakan berdasarkan satuan-satuan tertentu. Satuan yang paling umum dan paling dasar yang digunakan adalah massa. Jadi, tiap atom punya massa.
Jika setiap benda punya identitas, punya karakter, pola, bagaimana peradaban sains mampu mengubahnya menjadi digital? Nicholas Negroponte dalam Being Digital (1996) menjelaskannya sekaligus menunjukkan bagaimana ketika terkonversi ke dalam dunia digital, progresnya menjadi tidak lagi bisa terhentikan. Diperlambat pun tidak. Nicholas Negroponte dengan amat gamblang membedakan apa itu “atom” dan apa itu bilangan biner atau “bits” (binary digits).
Maharaja Sains?
Perang memang traumatik. Validkah menuding sains dan teknologi sinonim dengan perang? Bagi pemikir seperti Paul Virilio, teknologi memacu perang. Namun bisa dilihat sebaliknya: perang memacu inovasi teknologi. Manusia gemar berperang, dengan atau tanpa teknologi.
Kisah manusia adalah rangkaian peperangan tanpa henti, sejak perang batu zaman purba hingga perang dengan senjata modern. Alih-alih pemicu perang, sains dan teknologi boleh jadi akan menghentikan perang. Bom hidrogen yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki menghentikan perang dunia kedua:. Dengan adanya bom nuklir muncul kesadaran perang adalah kesia-siaan yang bisa membikin mega kehancuran.
Perang adalah soal hormonal manusia, teknologi dipakai untuk mengintensifkan agresivitas itu. Di masa depan, sains akan bisa menghentikan problem hormonal ini, dengan menemukan vaksin yang bisa mengendalikan agresivitas manusia. Perang suatu saat mungkin akan berhenti. Namun “war of ideas”, akan berlanjut.
Disinilah ada kecemasan, sains akan menjadi “maharaja” pengetahuan manusia. Kredo “Sains menjadi maharaja” adalah tampaknya hiperbola. Untuk saat ini, “maharaja” manusia tampak jelas masih politik dan politisi. Politik masih menjadi penentu arah pengetahuan. Contoh yang paling jelas adalah isu “climate change”. Sains sudah menjelaskan bahaya perubahan iklim ini, namun banyak negara masih abai dan tidak peduli. Donald Trump menuduh sebagai teori konspirasi yang disebarkan Tiongkok. Begitupun kita ingat di negeri kita saat pandemi covid 19 ada saja yang menganggap konspirasi dan juga kutukan.
Selain politik, agamalah yang selama ribuan tahun mengendalikan pengetahuan melalui doktrin dan dogmanya. Politik dan agama berkorelasi dan berkonspirasi menjadi “penguasa” sepanjang peradaban manusia. Dan itu diwujudkan reringkali dengan inkuisisi, persekusi, dan otokrasi. Sains modern selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik atau kepentingan bisnis. Riset sains yang begitu kompleks dan mahal saat ini memerlukan dukungan keputusan politik atau kepentingan bisnis agar bisa membiayai aktivitasnya.
Sains pada dirinya sendiri mungkin tidak pernah bisa menjadi kekuatan tunggal atau katakan sebagai panglima. Ketimbang sebagai panglima, sains lebih pas dianalogikan sebagai “alat penunjuk arah”. Seperti aplikasi penunjuk jalan Google-Map, Waze, atau MapQuest.
Sains membantu manusia mengetahui pilihan destinasi, arah, dan rute yang sebaiknya ditempuh. Namun ke mana manusia mau menuju—ke masjid, ke gereja, ke kampus, atau ke red district area—sepenuhnya keputusan manusia. Sains sebagai alat sering masih tunduk pada konsensus politik atau kepentingan bisnis. Sains sebagai metode untuk mendapat pengetahuan baru dipakai kurang dari 300 tahun, bandingkan dengan agama dan filsafat yang setidaknya sudah 2500 tahun. Sulit pasti membayangkan, penemuan dan pencapaian saintifik seperti apa 2000 tahun ke depan. Jangankan 2000 tahun, kita bahkan sulit memprediksi kemajuan sains 50 tahun ke depan.
Ujung remujungnya. pertanyaan dalam era transhuman ini, apakah filsafat akan mati, jika wilayahnya makin menyempit? Memang banyak saintis yang menvonis bahwa filsafat sudah mati. Stephen Hawking mendeklarasikan kematian filsafat disaat tehnologi telah mampu menyingkap tabir semesta secara empirik. Dr Ryu Hassan pakar neuro sains bahkan menyebut filsuf sebagai ‘tukang ngarang’ yang hanya berdiam di kamar lalu mengimajinasikan dunia kehidupan. Atau sejatinya sejak abad 18 ketika lahir ilmu-ilmu empirik seperti psikologi, sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya, filsafat telah mati.
Ya, filsafat tak lagi mampu ‘merubah’ dunia. Kerjanya hanya ‘merenung’ tanpa tindakan empirik-praktis. Terlebih saat ini trend dunia menuju inovasi tehnologi yang manfaatnya langsung bisa dirasakan. Bahkan dalam kehidupan keseharian filsafat semakin ‘ditnggalkan’ tidak lagi menjadi acuan hidup atau ‘tarekat’ dan ‘ordo’ yang memandu manusia untuk hidup bijaksana. Paling-paling ajaran hanya sebagai wishful thinking yang kadang diviralisasikan dengan harapan bisa menjadi petunjuk hidup yang praktis. Misalnya ajaran Stoisisme atau falsafah lokalitas yang ‘dipreteli’ ajarannya untuk disesap sebagai wisdom.
Kebijaksanaan yang dikandung filsafat bisa kita tatapi saat ini masih ‘ditaklukkan’ atau ‘disalip’ oleh ajaran spiritualitas keagamaan. Dewasa ini ada fenomena kebangkitan agama yang bahkan kerap mengarah pada ekstrimisme dan terorisme. Seiring itu ada kebangkitan spiritual yang menjadi bagian dari pencarian manusia moderen. John Neisbitt sejak lama lewat Megatrend 2000-nya meramalkan abad 20 ditandai oleh kebangkitan spiritual dan bebarengan dengan kemajuan sains terutama ilmu biologi.
Nah, inikah saat kematian filsafat? Saya yakin tidak. Hal-hal yang belum pasti tetap menjadi ‘prerogatif’ filsafat. Secara klinis, filsafat tidak akan mati sejauh masih ada pertanyaan manusia yang belum terjawab. Kontemplasi filsafat tetap akan penting untuk memperluas konsepsi berpikir, memperkaya imajinasi intelektual, dan mengikis keyakinan dogmatis. Dunia saat ini tengah mengalami lintang pukang makna. Kerapkali terjadi pendangkalan nilai, Ada kemajuan sains tapi juga kebangkitan agama atau spiritual yang sering melahirkan pandangan picik seperti terjadinya ekstrimisme dan terorisme. Mungkin ini tak hanya di wilayah keagamaan, bisa juga merambah dalam berbagai ranah kehidupan yang mengalami radikalisasi tanpa makna.
Menarik mencuplik Ludwig Wittgenstein dalam Philosophical Investigations (1953). Sang filsuf ini menandaskan bahwa tujuan filsafat bukanlah mencari kebenaran, namun memberikan kelegaan, the aim of philosophy is not to seek the truth but rather to provide relief. Wittgenstein menganalogikan manusia seperti lalat yang terjebak dalam botol, dan filsafat “menunjukkan lalat jalan keluar dari botol”. Ya, filsafat masih bisa diyakini mampu membebaskan dari penjara “pseudoproblem” berbagai pertanyaan manusia.
****
*Dr. Soffa Ihsan. Penggiat literasi Eksnapiter Rumah Daulat Buku (Rudalku).