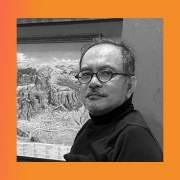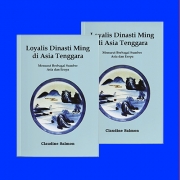One Piece dan Estetika Perlawanan
Renungan Kritis Menjelang 80 Tahun Kemerdekaan
Oleh: Prof. Dr. Kasiyan, M.Hum.*
“Setiap karya seni besar adalah pemberontakan terhadap keteraturan palsu dunia.”
—Albert Camus (The Rebel, 1951).
Ada hal-hal yang tak bisa diajarkan oleh buku teks sejarah. Seperti hasrat untuk melawan, menolak. Atau keberanian untuk berkata tidak—bukan sebagai sikap politik, tapi sebagai pengalaman eksistensial. Dunia modern hari ini penuh dengan tata yang mapan, tapi seringkali kehilangan makna. Dalam tatanan yang demikian, perlawanan bukan hanya persoalan ideologi, melainkan juga persoalan estetika.
Estetika—dalam pengertian yang tersublim—adalah cara kita merasakan dunia, menafsirkan keberadaan, dan menolak kejumudan hidup yang dirayakan.
Dan justru dalam ruang yang dianggap “remeh”, seperti kisah bajak laut dalam One Piece—manga dan serialanime, karya Eiichiro Oda, yang pertama terbit 22 Juli 1997 di majalah Weekly Shonen Jump (Shueisha, Jepang)—kita menemukan sebuah bentuk estetika yang subtil namun dahsyat: estetika perlawanan.
Kartun itu tak menggurui, tidak menyampaikan doktrin. Namun justru di situlah daya kritisnya. Dalam absurditas tokohnya, dalam patah-patah kisah petualangannya, dalam tubuh-tubuh luka yang terus berjalan, One Piece mengajukan satu pertanyaan eksistensial yang tak pernah selesai: apakah hakikat kebebasan, kemerdekaan itu, dan adakah jalan hidup yang tetap bermakna di tengah tatanan yang menindas?
Dunia sebagai Kekuasaan Simulakra
Dalam dunia One Piece, terdapat struktur kekuasaan yang sangat mirip dengan lanskap dunia pascamodern: kekuasaan hadir bukan sebagai representasi moral atau hukum, melainkan sebagai jaringan simbol, persepsi, dan manipulasi makna. Dunia dengan konstruksi absurd seperti ini, seluruh aparatusnya, bukan hanya mengatur, tapi menciptakan standar kebenaran yang culas. Ia mengarsiteki sejarah, menentukan siapa yang disebut penjahat, siapa yang layak dikenang, siapa yang dihapus.
Dalam perspektif Jean Baudrillard, ini adalah dunia simulakra—realitas telah digantikan oleh simulasi, dan kita hidup dalam ilusi dari sebuah sistem makna yang telah lama kehilangan acuan. Para “bajak laut” dalam One Piece, dalam posisi yang kontradiktif, justru mewakili kegelisahan akan kenyataan semu itu. Mereka adalah “penjahat” menurut narasi resmi, namun justru memikul nilai-nilai moral yang lebih manusiawi: setia, adil, rela berkorban.
Seperti tokoh-tokoh Dostoyevsky—orang-orang buangan, pencari, pelintas batas moral resmi—kru bajak laut ini bergerak dalam ruang-ruang liminal: mereka hidup di pinggir, di antara hukum dan anarki, di antara ketololan dan kebijaksanaan. Dalam estetika yang demikian, kita diingatkan akan konsep “kairos” dari filsafat Yunani: bukan waktu kronologis, tapi waktu eksistensial—momen ketika makna muncul dari retakan sistem yang tampak kekal.
Dalam zaman ketika kebrutalan kekuasaan menyamar sebagai kesederhanaan, kebengisan kebijakan dikamuflase sebagai kebajikan—maka para bajak laut ini menjadi pengganggu yang sangat diperlukan. Mereka mengacaukan, bukan untuk menghancurkan, melainkan agar kita bisa melihat ulang: siapa sesungguhnya kita, dan kepada siapa sebenarnya kesetiaan moral itu seharusnya berpihak?
Sebagaimana ditegaskan Max Horkheimer lewat Art and Mass Culture (1941), seni yang sejati dan autentik bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan bentuk protes terhadap kepahitan, ketakadilan kehidupan. Ia menolak seni yang hanya menjelma “hiburan-klangenan” atau “pengalih perhatian”, karena bisa menjauhkan manusia dari kritis kesadaran. Pun demikian halnya dengan One Piece, bahkan dalam ketidakseriusan tampilan estetisnya, ia menjadi sejenis gugatan terhadap dunia yang telah terlampau “serius” dalam menormalisasi ketidakadilan.
Ketololan sebagai Radikalisme Moral
Luffy, sang tokoh utama One Piece, bukan pahlawan dalam pengertian konvensional. Ia bahkan sering tampak bodoh, impulsif, bahkan tak logis. Namun justru dalam kenaifannya itulah letak daya radikalnya. Ia hidup bukan dengan strategi, tetapi dengan prinsip: kehidupan bukan soal menang, tapi soal tidak mengkhianati nurani.
Di dunia yang menuhankan keserakahan, One Piece menjadi lambang dari radikalisme yang naif. Tapi kenaifian itu bukan ketidaktahuan—melainkan keberanian untuk mempercayai dunia dari titik etis terdalam: pertemanan, kesetiaan, dan keberanian untuk menolak kompromi dengan kekuasaan.
Dalam setiap tindakannya, One Piece menghidupkan kembali yang dikatakan Simone Weil, dalam esainya Reflections on the Right Use of School Studies with a View to the Love of God (1942)—bahwa keadilan bukanlah pengetahuan, tetapi atensi. Untuk memperjuangkan keadilan, seseorang harus mampu mendengarkan jerit kesakitan yang tidak terdengar oleh kedegilan kekuasaan.
Kekuatan estetika perlawanan dalam One Piece bukan pada senjata, bukan pada taktik, melainkan lebih pada gestur tubuh jiwa yang luka, tapi terus berjalan sekuat daya. Mereka tidak membangun sistem baru. Mereka tidak ingin menciptakan negara. Tapi mereka menghadirkan wajah manusia—sebagaimana dikatakan Emmanuel Levinas, lewat Totality and Infinity: An Essay on Exteriority (1961), bahwa etika yang sejati adalah relasi dengan wajah orang lain, bukan ide-ide besar.
Dan barangkali, dalam wajah-wajah itulah, perlawanan justru menjadi paling murni. Ketika sistem terus memproduksi logika demi logika, prosedur demi prosedur, statistik demi statistik, Luffy dan kawan-kawan justru menawarkan tubuh-tubuh otentik alamiah: tertawa, lapar, menangis, luka, berdarah, tapi tetap berjalan tegak tak menyerah. Perlawanan mereka bukan dalam narasi besar, tapi dalam kesetiaan pada yang kecil, yang rentan, yang dianggap sepele oleh sejarah dan narasi besar.
Dalam keganjilan representasinya, di sinilah One Piece, justru dalam melampaui batas hiburan dan menjadi kritik sosial, mampu menyentuh akar realitas: bahwa manusia tidak boleh berhenti bermimpi tentang kebebasan, bahkan di tengah reruntuhan makna yang kerap mengerikan.
Kemerdekaan sebagai Proyek yang Belum Selesai
Menjelang 80 tahun kemerdekaan, bangsa ini seperti seorang tua yang duduk termenung di depan cermin. Ia melihat sejarah panjang perjuangan, darah, dan puisi—tapi yang terpampang kini adalah wajah yang lelah, penuh bedak program pembangunan, tapi dengan tatapan mata kosong penuh nanar kepiluan.
Kita hidup dalam masa yang aneh. Sejarah tidak lagi dipelajari, tapi dikutip seperti ayat. Ideologi tak lagi menyala, tapi menempe bak merek dagang. Keadilan terdengar seperti prosedur administratif, bukan rasa nyeri yang meminta pembebasan.
Dan anak-anak muda kita, alih-alih menyanyikan lagu perjuangan, memilih menyimak cerita tentang bajak laut yang tak ingin jadi raja—hanya ingin memaknai haikat bebas, hakikat merdeka.
Di sinilah kita perlu mulai bertanya: mungkin mereka menemukan sesuatu dalam fiksi, yang tidak mereka temukan dalam fakta keseharian dan dokumen negara. Mungkin One Piece—yang oleh narasi resmi disebut kriminal—justru sedang menyuarakan kebenaran, yang tidak bisa lagi diwakili oleh pidato dan jargon di baliho kekuasaan.
Karena negeri ini, seperti dunia dalam One Piece, telah lama hidup dalam simulasi. Kita katanya punya angka pertumbuhan, tapi tak punya waktu untuk mendengarkan rakyat yang lapar. Kita punya gedung pencakar langit, tapi tak punya tempat teduh bagi yang terusir. Kita punya indeks demokrasi, tapi tak punya keberanian untuk berkata: ini tidak adil.
Dan barangkali karena itulah, kita diam-diam tergetar melihat sekelompok bajak laut yang bodoh dan ceroboh, tapi terus berjalan. Luka, tapi tidak berhenti.
Luffy bukan revolusioner. Ia tidak memiliki program politik, tidak menulis manifesto, tidak tertarik mendirikan pemerintahan baru. Ia tidak ingin menggantikan sistem—ia hanya ingin tidak tunduk padanya.
Ada yang menyebut sikap seperti itu sebagai utopia kekanak-kanakan. Tapi, dalam dunia yang terlalu vulgar realitas kamuflase moralnya, sedikit kepolosan fiksi imajinasi adalah bentuk tertinggi dari hakikat kesadaran. Karena kepolosan tidak bisa berpura-pura. Ia tidak tahu cara berdiplomasi dengan kebohongan.
Mungkin karena itulah, estetika perlawanan tidak lahir dari podium, tapi dari tubuh-tubuh luka bernanah oleh tikaman sejarah, dan terus berupaya melangkah. Tidak dari buku tebal atau hasil riset kebijakan, tapi dari sorot mata yang menolak tunduk—meski dunia berkata: ini jalan satu-satunya.
Karenanya seperti kata Albert Camus dalam The Rebel (1951), setiap pemberontakan adalah upaya untuk mengatakan, bahwa dunia ini tidak cukup, dan perlu dinarasikan ulang. Camus tidak sekadar bicara tentang ketidakpuasan personal, melainkan tentang kesadaran kolektif eksistensial, bahwa tatanan yang ada—yang penuh absurditas, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan—tidak bisa diterima begitu saja. Maka, perlawanan adalah penegasan determinasi atas nilai-nilai, bukan sekadar penolakan.
Karenanya, estetika perlawanan One Piece menampar langsung ke inti problem ini: bahwa kemerdekaan bukanlah semata-mata status legal, melainkan perjalanan untuk tetap setia pada kebenaran eksistensial.
Luffy dan kawan-kawan dalam One Piece lebih menyerupai tokoh Kierkegaardian: mereka terus berjalan dalam dunia yang tak adil, namun tetap percaya bahwa hidup bisa dijalani secara autentik dengan segala keyakinan. Sebagaimana pernah dikatakan Søren Kierkegaard—filsuf, teolog, dan penulis asal Denmark—melalui Fear and Trembling (1843), bahwa iman adalah gairah terbesar manusia, dan tak seorang pun bisa mencapainya tanpa melewati pengorbanan batin dan atau pengunduran diri (infinite resignation) yang tak terhingga.
Penutup: Di Tengah Lautan Ketidakadilan
Delapan puluh tahun adalah waktu yang panjang untuk sebuah kemerdekaan. Tapi kemerdekaan bukan umur, ia bukan jumlah tahun. Ia adalah semacam luka yang tak pernah sembuh, karena selalu ada yang tersingkir, selalu ada yang ditindas, selalu ada yang dilupakan.
Dan barangkali karena itulah, kita memerlukan kisah fiksi. Karena kenyataan terlalu sering gagal menghibur. Kita perlu tokoh-tokoh yang bukan manusia biasa—karena manusia biasa terlalu sering harus menyerah.
Tapi saya tidak ingin mengajak kita melarikan diri. Saya hanya ingin mengingatkan: kadang yang fiksi bisa lebih jujur daripada yang realitas. Kadang dunia yang paling remeh—seperti cerita kartun—bisa menyimpan kebijaksanaan yang tak lagi bisa diucapkan secara institusional.
Karena ketika kebenaran telah dijual seperti saham, ketika keadilan dijelaskan dengan pencitraan, dan ketika kebrutalan kekuasaan menyamar sebagai kemaslahatan, maka satu-satunya tempat yang masih bisa kita percaya mungkin adalah yang absurd. Yang tidak logis. Yang tampaknya hanya untuk kekonyolan hiburan—tapi ternyata justru itu yang bisa membebaskan, memerdekakan.
Dalam konteks kita hari ini—ketika nasionalisme telah menjadi semacam banalitas nostalgia birokratik, dan kemerdekaan disulap menjadi produk dalam etalase kosmetik—One Piece justru mengembalikan perlawanan pada tempat asalnya: sebagai tindakan etis yang lahir dari keberanian manusia untuk setia pada suara hatinya.
Bahwa perlawanan tidak selalu berupa teriakan. Kadang ia muncul sebagai kesetiaan kecil pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan—sebuah suara sunyi dalam hati yang terus berkata: dunia ini mestinya bisa lebih baik adanya.
Bahwa perjuangan tak harus selalu disahkan oleh kemenangan. Bahwa keadilan bisa dimulai dari hal-hal kecil: menemani yang tertindas, menolak ikut arus, tidak tunduk pada ilusi manipulasi. Seperti yang selalu diteguhkan W.S. Rendra dalam nalar puitisnya: puisi bukan pelarian dari kenyataan, tapi pelarian dari kebohongan.
Dan mungkin—di titik inilah—kita bisa mulai kembali percaya. Bahwa kemerdekaan belum selesai. Dan bahwa estetika perlawanan belum mati. Abadi.
—–
*Prof. Dr. Kasiyan, M.Hum., Guru Besar Departemen Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta.