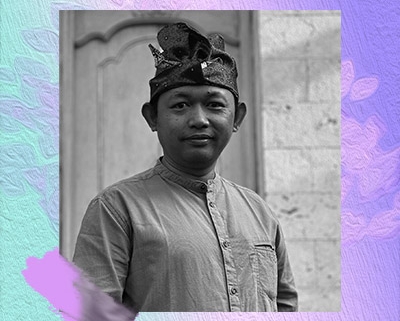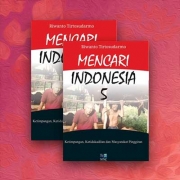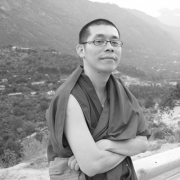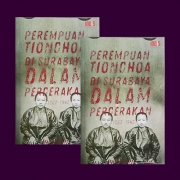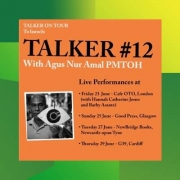Puisi yang Diperingati, Chairil yang Diberi Arti
Oleh Purnawan Andra*
Setiap tanggal 28 April, Indonesia memperingati Hari Puisi Nasional. Tanggal ini dipilih bukan sembarangan, melainkan menandai hari kematian Chairil Anwar, penyair terkemuka yang mati muda. Sosok cerdas dalam pikiran, bernas dalam berdiksi, sosok yang konon ingin “hidup seribu tahun lagi.”
Tapi peringatan hari penting ini, alih-alih jadi ruang refleksi kritis atas posisi, peran dan makna puisi dalam kehidupan publik, seringkali direduksi jadi seremoni. Puisi dibacakan dengan iringan musik yang menyentuh, diksinya dibingkai bunga dan lilin, sementara problem struktural kebudayaan yang lebih besar malah diabaikan.
Dalam situasi seperti itu, pertanyaan pun muncul: apakah peringatan Hari Puisi kita rayakan sebagai bentuk hidupnya puisi, atau justru pembalseman terhadapnya? Apakah kita sedang mengenang energi liar Chairil Anwar, atau mengurungnya dalam museum sastra yang steril?
Sikap Estetik-Politik
Chairil Anwar lahir dalam masa peralihan: kolonialisme sekarat, nasionalisme menggelora. Ia menulis bukan dari ruang tenang, tapi dari pusaran sejarah. Puisinya tidak netral, ia memberontak. Bukan hanya dalam isi, tetapi dalam bentuk: ia merombak sintaks, menolak idiom lama, dan menuliskan dunia baru dalam bahasa yang belum mapan.
Dalam “Aku,” kita tak hanya membaca pengakuan eksistensial, tetapi juga pembebasan bahasa dari kungkungan formal. Chairil menjadikan puisi bukan sekadar estetika, melainkan ledakan bahasa dalam dunia yang retak.
Namun kini, ketika puisi telah jadi bagian dari festival literasi yang difoto untuk media sosial, kita menghadapi situasi yang ironis. Di tengah krisis demokrasi, kerusakan ekologi, dan alienasi digital, suara puisi nyaris tak terdengar. Ketika korupsi merajalela, kekerasan terhadap perempuan meningkat, dan bahasa politik dipenuhi eufemisme, puisi justru lebih sering memproduksi metafora tentang patah hati dan kopi dingin. Kita sedang hidup dalam zaman bencana, tapi suara penyair justru terdengar makin lirih, seolah takut mengganggu ketertiban algoritma.
Maka penting kiranya menghidupkan kembali spirit Chairil, bukan dalam bentuk imitasi gaya, tapi sebagai sikap estetik-politik. Chairil tidak menulis untuk disukai. Ia menulis karena terdorong oleh kemendesakan zaman. Ia menyerap pengaruh dari Rilke, Marsman, dan Nietzsche, tapi membentuk suara yang khas Indonesia.
Ia menyampaikan penderitaan dan hasrat dalam bahasa yang tidak sopan, tidak lurus, dan tidak normatif. Ia tidak mencari pengakuan dari negara atau pasar. Dalam dunia hari ini, itu artinya menulis puisi yang tak bisa ditrendingkan, puisi yang terlalu tajam untuk dipanggungkan dalam seremoni kementerian.
Namun tentu saja, menyalahkan penyair semata terlalu simplistis. Ekosistem sastra Indonesia tidak pernah sehat. Sastra tidak diajarkan sebagai alat berpikir, melainkan sebagai hafalan nama tokoh dan bait puisi lama. Lembaga penerbitan lebih menyukai novel romantis atau buku pengembangan diri ketimbang kumpulan puisi. Kritik sastra terpinggirkan, dan media massa pun hanya menyisakan ruang kecil untuk suara penyair. Di tengah dominasi kapitalisme digital, puisi harus berjuang keras hanya untuk eksis.
Yang lebih menyedihkan: ketika puisi berhasil eksis, ia malah terjerembap ke dalam estetika dangkal. Banyak puisi hari ini lahir dari keinginan untuk “aesthetic,” bukan untuk menggugat realitas. Estetika patah hati lebih menjual ketimbang kritik struktural. Puisi jadi caption, jadi quote motivasi, jadi bahan konten. Ia dilucuti dari kemampuannya untuk mengganggu. Padahal, bukankah salah satu kekuatan puisi adalah kemampuannya menyelinap, menyusup, dan meledak dalam benak pembacanya?
Sejarah Puisi
Mari kita bandingkan dengan sejarah puisi kita sendiri. Di era kolonial, Amir Hamzah menggubah “Padamu Jua” sebagai pertempuran antara diri dan kekuasaan ilahi. Di masa pergerakan, puisi menjadi alat agitasi. Di era Orde Baru, Rendra menyulap puisi menjadi senjata panggung. Wiji Thukul menulis puisi dengan darah perlawanan. Semua ini menunjukkan bahwa puisi Indonesia tak pernah steril. Ia lahir dari konflik. Ia menegaskan yang tertindas, yang tak bersuara, yang dikubur sejarah resmi.
Bagaimana dengan sekarang?
Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi: dari erosi demokrasi, intoleransi agama, hingga krisis iklim dan perampasan ruang hidup. Namun, puisi seakan kehilangan daya radikalnya. Ia lebih sering tampil dalam format yang bisa diterima pasar—atau lebih tepatnya: bisa diverifikasi oleh algoritma. Puisi bukan lagi tempat menggodok gagasan politik, melainkan tempat mencari validasi personal. Penyair menjadi influencer kecil-kecilan, bukan agitator bahasa.
Tetapi ini bukan berarti harapan sudah mati. Justru di celah-celah marjinal, puisi menemukan bentuknya kembali. Di komunitas-komunitas kecil, di zona mandiri, di ruang alternatif, di media sosial yang digunakan secara subversif—kita bisa menemukan puisi yang mencakar. Puisi yang bicara soal evakuasi paksa, konflik agraria, suara perempuan di kamp pengungsi, atau kisah minoritas yang dibungkam negara. Mereka tak selalu muncul di panggung besar, tapi di sinilah warisan Chairil berdenyut: dalam keberanian untuk tidak tunduk.
Maka Hari Puisi harus dimaknai ulang: bukan sebagai monumen nostalgia, tapi sebagai pengingat bahwa puisi adalah bentuk perlawanan atas kekacauan makna yang diproduksi negara dan pasar. Puisi bukan hanya produk estetika, melainkan instrumen politik dalam pengertian yang luas—yakni sebagai praktik simbolik yang menantang relasi kuasa dan membuka kemungkinan dunia lain.
Karena ketika bahasa publik dirusak oleh jargon pembangunan dan populisme kosong, puisi hadir sebagai bentuk sabotase: ia mengacaukan, mengusik, dan mengungkap apa yang disembunyikan. Itulah peran historis puisi yang tak boleh dilupakan.
Di tengah bisingnya dunia yang dikendalikan angka, data, dan rating, puisi menawarkan ruang senyap yang tak bisa dikalkulasi. Ia memberi waktu untuk merenung, tapi juga menusuk. Ia bisa menenangkan, tetapi juga membakar. Chairil Anwar tahu itu. Dan kalau kita ingin puisi tetap hidup “seribu tahun lagi,” maka kita harus berani menuliskannya dengan risiko: risiko tak dimengerti, tak terjual, dan tak diundang ke panggung apresiasi.
Karena puisi yang benar-benar hidup, bukan yang sering dibacakan di acara televisi. Tapi yang dibaca diam-diam oleh seseorang yang sedang patah karena tanahnya dirampas, haknya dikhianati, atau harapannya dikubur negara.
Dan dari situ, puisi tak akan mati. Ia akan terus tumbuh, membentuk bahasa baru, menyuarakan luka yang tak bisa dilupakan. Ia akan menjadi “aku” yang lain: tak tunduk, tak selesai, dan selalu menggugat dunia.
——
*Purnawan Andra, alumnus Governance and Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.