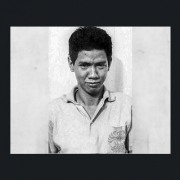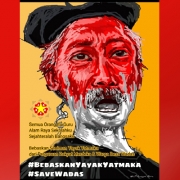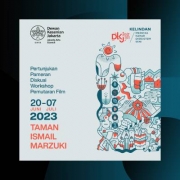Mudik: Antara Mitos dan Realitas
Oleh Tengsoe Tjahjono*
Mudik adalah ritus peralihan. Ia bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan sebuah momen liminal, sebuah batas antara yang lalu dan yang akan datang. Saat merayakan Idulfitri atau perayaan besar lainnya, seperti Chuseok di Korea, manusia sejenak kembali ke akar. Mereka mengunjungi orang tua, berziarah ke makam leluhur, dan merasakan kehangatan kampung halaman yang perlahan-lahan menjelma nostalgia. Namun, setelah semua salam perpisahan diucapkan, koper-koper dikemasi, dan kendaraan kembali mengarah ke kota, kehidupan yang lebih keras telah menunggu.
Dalam perspektif sosiologi kritis, mudik dapat dibaca sebagai sebuah siklus dari kontradiksi kelas. Pierre Bourdieu (1986) mengingatkan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya diwariskan melalui modal ekonomi, tetapi juga melalui modal sosial dan simbolik. Orang-orang yang mudik sering kali pulang dengan cerita keberhasilan—meskipun tidak selalu nyata—sebagai strategi simbolik untuk menjaga martabat di mata keluarga yang mereka tinggalkan. Namun, begitu kembali ke kota, mereka dihadapkan pada kenyataan: pekerjaan yang menjemukan, upah yang rendah, atau bahkan pengangguran yang membayangi.
Mudik, dalam pengertian ini, bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga sebuah mitos. Roland Barthes (1972) menyoroti bagaimana mitos bekerja sebagai alat legitimasi bagi struktur sosial yang ada. Narasi tentang “keberhasilan di perantauan” atau “mudik sebagai bukti kesuksesan” membentuk mitos yang mengaburkan kenyataan bahwa sistem sosial-ekonomi telah menciptakan jurang antara desa dan kota, antara kelas pekerja dan pemilik modal.
Di negara-negara lain, fenomena serupa terjadi, menegaskan bahwa mudik bukan hanya soal perjalanan pulang, tetapi juga refleksi ketimpangan struktural yang berlangsung secara global. Di Korea Selatan, Chuseok menjadi momen ketika para pekerja di Seoul pulang ke desa mereka, bertemu keluarga, lalu kembali ke ibu kota dengan beban kehidupan yang lebih berat. Namun, alih-alih menjadi kesempatan untuk membangun keseimbangan antara desa dan kota, migrasi musiman ini justru menegaskan bahwa desa adalah tempat nostalgia, bukan masa depan. Sistem ekonomi Korea yang berbasis pada sektor industri dan teknologi di pusat-pusat perkotaan membuat daerah pedesaan tertinggal, baik dari segi peluang kerja maupun pembangunan infrastruktur. Akibatnya, para perantau yang kembali ke desa hanya menemukan bahwa rumah masa kecil mereka semakin sepi, ditinggalkan generasi muda yang enggan hidup di tempat tanpa prospek.
Mudik juga terjadi di Tiongkok. Fenomena serupa terlihat dalam arus balik pekerja setelah perayaan Tahun Baru Imlek. Jutaan pekerja migran yang tergabung dalam kelas nongmingong pulang ke kampung halaman mereka di pedesaan setelah setahun bekerja di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, atau Guangzhou. Menurut sosiolog Pun Ngai (2005), kaum pekerja migran di Tiongkok hidup dalam kondisi yang terfragmentasi: mereka bekerja di kota tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian darinya karena status hukum dan sosial mereka yang tetap dianggap sebagai warga desa. Setelah mudik, mereka kembali ke realitas pekerjaan industri yang keras, di mana upah rendah dan jam kerja panjang menjadi norma. Bahkan, bagi sebagian besar pekerja ini, kembali ke desa bukanlah pilihan realistis, karena desa telah kehilangan daya dukung ekonominya.
Di India, peristiwa mudik massal terjadi setiap kali perayaan Diwali dan festival lainnya, di mana pekerja urban kembali ke desa mereka untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, sama seperti di negara lain, desa di India juga mengalami stagnasi ekonomi yang membuat para perantau harus kembali ke kota, sering kali untuk bekerja dalam sektor informal dengan kondisi yang jauh dari layak. Ketimpangan antara desa dan kota semakin diperparah dengan kebijakan ekonomi neoliberal yang mempercepat urbanisasi tanpa memberikan jaminan bagi pekerja migran. Jean Drèze dan Amartya Sen (2013) dalam An Uncertain Glory: India and its Contradictions menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi India menciptakan ilusi kemajuan, tetapi gagal mengangkat kondisi kehidupan jutaan pekerja migran yang terus-menerus berpindah antara desa dan kota tanpa kepastian masa depan.
Sementara itu, di Amerika Latin, khususnya di Meksiko, migrasi musiman sering kali dikaitkan dengan perayaan Natal, ketika para pekerja yang bekerja di kota-kota besar seperti Mexico City atau bahkan di Amerika Serikat kembali ke kampung halaman mereka. Namun, setelah liburan berakhir, mereka harus kembali menghadapi kerasnya kehidupan urban, sering kali dalam bentuk pekerjaan upahan yang tidak menentu di sektor konstruksi atau manufaktur. Dalam studinya tentang pekerja migran Meksiko, Alejandro Portes (2006) menunjukkan bahwa migrasi dari desa ke kota dan bahkan lintas negara bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana identitas sosial terbentuk. Para pekerja yang pulang dari Amerika Serikat dengan sedikit tabungan sering kali dianggap “sukses,” meskipun kenyataan hidup mereka di kota-kota industri penuh dengan eksploitasi dan ketidakpastian hukum.
Dari berbagai kasus ini, terlihat pola yang berulang: desa bukan lagi tempat yang dapat menopang kehidupan ekonomi secara berkelanjutan, sementara kota tidak menawarkan kepastian bagi para pekerja yang datang. Mudik, yang seharusnya menjadi momen kebersamaan dan pemulihan identitas, justru semakin memperjelas bahwa dunia modern telah menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang “asal” dan yang “harus ditempuh” demi bertahan hidup
Kembali ke Kota: Eksploitasi dan Alienasi
Dalam “The Condition of the Working Class in England” Friedrich Engels (1845) menggambarkan bagaimana kaum pekerja di kota-kota industri mengalami alienasi yang mendalam. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang kembali dari mudik: mereka kembali ke kota bukan sebagai subjek yang berdaulat, tetapi sebagai bagian dari roda produksi. Karl Marx (1867) dalam Das Kapital menjelaskan bahwa kapitalisme menciptakan kondisi di mana tenaga kerja menjadi komoditas yang dipertukarkan di pasar. Pekerja tidak memiliki kendali atas hasil kerja mereka, melainkan hanya menjual tenaga mereka kepada pemilik modal.
Bagi banyak perantau, kembali ke kota berarti kembali ke ritme yang mencekik: bangun pagi, menembus kemacetan, bekerja selama delapan hingga dua belas jam, lalu pulang ke kos sempit yang semakin mahal sewanya. Mereka yang belum memiliki pekerjaan lebih terpukul lagi—resume harus diperbarui, wawancara kerja harus dihadapi, dan ketidakpastian harus ditelan setiap hari.
Realitas ini semakin kentara dalam konteks perekonomian pasca-pandemi. Fleksibilitas tenaga kerja yang didorong oleh digitalisasi justru memperburuk ketidakamanan kerja. Guy Standing (2011) dalam The Precariat: The New Dangerous Class menyoroti bagaimana kelas pekerja baru—yang ia sebut precariat—hidup dalam ketidakpastian permanen. Mereka tidak memiliki jaminan pekerjaan, tidak ada kepastian kontrak, dan sering kali harus menerima upah rendah demi bertahan hidup.
Masa Depan: Melawan atau Menyerah?
Hari-hari setelah mudik adalah hari-hari ketidakpastian. Sebagian kembali ke rutinitas lama dengan rasa pasrah, sebagian lagi berusaha mencari pekerjaan baru, dan tidak sedikit yang mulai mempertanyakan: apakah ada jalan keluar? Di sinilah muncul pertanyaan sosiologis yang lebih besar: apakah kita akan terus menerima logika eksploitasi ini sebagai sesuatu yang tak terelakkan, atau kita akan mencari alternatif? Antonio Gramsci (1971) dalam Prison Notebooks menekankan bahwa dominasi kelas tidak hanya terjadi melalui ekonomi, tetapi juga melalui hegemoni budaya. Selama ideologi tentang “keharusan kembali bekerja” tetap diterima tanpa perlawanan, eksploitasi akan terus berlanjut.
Namun, ada tanda-tanda resistensi. Di berbagai negara, kesadaran akan hak-hak pekerja mulai meningkat, dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap ketimpangan struktural mulai bermunculan, baik melalui gerakan sosial, kebijakan ekonomi alternatif, maupun strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh komunitas pekerja migran itu sendiri. Di Korea Selatan, gerakan buruh telah lama menjadi salah satu pilar utama dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi pekerja urban, terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan bekerja dalam kondisi rentan. Organisasi seperti Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) secara aktif menuntut peningkatan upah minimum, perlindungan bagi pekerja kontrak, dan perbaikan kondisi kerja di sektor manufaktur serta jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula protes dari pekerja pengiriman dan sektor teknologi yang merasa dieksploitasi oleh sistem ekonomi yang semakin berbasis pada tenaga kerja fleksibel. Gerakan ini menunjukkan bahwa meskipun kota menarik tenaga kerja dari desa, eksploitasi yang terjadi di dalamnya semakin memicu kesadaran akan pentingnya solidaritas kelas pekerja.
Sedangkan di Indonesia muncul diskusi tentang ekonomi berbasis komunitas, di mana desa tidak hanya menjadi tempat pulang, tetapi juga tempat membangun kehidupan yang lebih berdaulat. Gerakan koperasi, pertanian organik, dan ekowisata berbasis masyarakat semakin berkembang sebagai respons terhadap kegagalan kota dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi semua orang. Konsep desa membangun yang dikembangkan oleh para ekonom dan aktivis agraria mulai mendapatkan tempat, dengan gagasan bahwa desa harus menjadi pusat produksi dan kesejahteraan mandiri, bukan sekadar pemasok tenaga kerja bagi industri di kota. Kebijakan seperti Dana Desa juga menjadi alat bagi komunitas untuk membangun infrastruktur ekonomi lokal yang lebih kuat.
Meskipun rezim politik secara ketat mengendalikan gerakan sosial di Tiongkok , para pekerja migran mulai menemukan cara untuk menuntut hak-hak mereka. Salah satu bentuk resistensi yang paling menonjol adalah gelombang pemogokan di pabrik-pabrik besar, terutama di sektor elektronik dan otomotif. Beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di Tiongkok, seperti Foxconn dan Honda, telah menghadapi aksi mogok kerja yang menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Meskipun negara sering kali menekan gerakan ini, tekanan dari buruh telah berhasil mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk peningkatan upah minimum di beberapa provinsi.
Lan halnya di India, perlawanan terhadap sistem ekonomi eksploitatif juga muncul dalam bentuk gerakan tani dan buruh. Protes besar-besaran oleh para petani yang menentang Undang-Undang Pertanian pada tahun 2020-2021 menjadi simbol bagaimana masyarakat pedesaan tidak ingin terus-menerus menjadi korban kebijakan ekonomi neoliberal yang menguntungkan kota dan korporasi besar. Selain itu, serikat buruh di sektor informal, seperti pekerja konstruksi dan pekerja domestik, semakin aktif dalam menuntut hak-hak mereka melalui aksi kolektif.
Berbeda lagi dengan di Amerika Latin, resistensi terhadap urbanisasi paksa dan eksploitasi pekerja juga terjadi di berbagai sektor. Di Meksiko, misalnya, komunitas pekerja migran yang kembali dari Amerika Serikat mulai mengembangkan model ekonomi berbasis remitan, di mana uang yang mereka hasilkan di luar negeri digunakan untuk membangun usaha kecil di kampung halaman. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang mengharuskan mereka untuk terus-menerus berpindah demi bertahan hidup. Sementara itu, di Brasil, gerakan seperti Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) telah lama berjuang untuk reforma agraria dan hak atas tanah bagi masyarakat desa, sebagai bagian dari upaya membangun alternatif terhadap migrasi paksa ke kota-kota besar seperti São Paulo dan Rio de Janeiro.
Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa meskipun kota masih menjadi magnet bagi tenaga kerja, desa tidak harus selalu menjadi tempat yang ditinggalkan. Resistensi yang muncul dari berbagai komunitas buruh dan petani di berbagai negara memperlihatkan bahwa ada upaya untuk menata ulang hubungan antara desa dan kota, bukan dalam logika ketergantungan, tetapi dalam kerangka keberlanjutan dan keadilan sosial.
Hari-hari setelah mudik adalah refleksi dari dunia yang tidak adil, tetapi juga kesempatan untuk membayangkan dunia yang lebih baik. Sejauh mana kita mampu melawan struktur yang menekan, itulah yang akan menentukan masa depan. Apakah kita akan kembali ke kota hanya untuk bekerja lagi, atau kita akan mencari cara untuk mengubah sistem? Tanda tanya itu masih menggantung di udara.
Malang, 27 Maret 2025
* sastrawan dan dosen FIB Universitas Brawijaya Malang