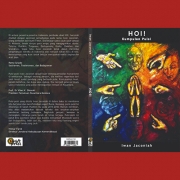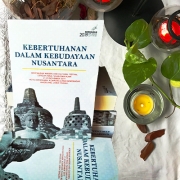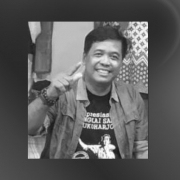Era Digital, Sastra pada Era Digital, dan Spesies Sastra Digital
Oleh Prof Djoko Saryono
/1/
Kini kita memasuki zaman yang selalu lolos dinamai. Pernahkah Anda merenungi, lantas bertanya? Dunia dan zaman macam apakah yang sedang kita hidupi dan menghidupi kita? Kita sekarang sedang memasuki dunia dan zaman serba tak pasti, tak terduga, penuh kesemrawutan, dan sarat kemenduaan (ambiguitas). Dunia dan zaman macam begini acap disebut VUCA World — volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity world. Sedemikian tak pastinya, tak terduganya, semrawutnya, dan ambigunya sehingga nyaris tak ada perspektif, kerangka pikir, paradigma, atau pendekatan konseptual atau teoretis yang dapat dipakai untuk menangkap dan menggambarkannya, apalagi menamainya secara komprehensif dan holistis.
Tak heran, kita menghadapi dan berhadapan dengan dunia dan zaman yang selalu lolos, senantiasa mrucut, untuk kita konseptualisasi dan formulasikan. Pinjam frasa Amir Hamzah, kita seolah senantiasa ‘bertukar tangkap dengan lepas’. Itu sebabnya, kita menjumpai bermacam-macam, malah berpuluh konstruk dan nama dunia dan zaman yang sedang kita hadapi dan hidupi sekarang ini. Dunia dan zaman pun terfragmentasi dan tersegmentasi sedemikian rupa. Kita merasa hidup sebatang kara di tengah keramaian dan kehiruk-pikukan.
/2/
Mengapa dunia kita menjadi sedemikian tak pasti, tak terduga, tampak semrawut, dan mendua sehingga sulit kita gambarkan dan rumuskan? Itu karena dinamika perubahan luar biasa dahsyat, datang dari sembarang arah, dan juga melesat ke sembarang arah. Ringkas kata, dunia kita — kebudayaan dan peradaban manusia — sedang mengalami tsunami perubahan yang sangat besar dan luar biasa — tengah mengalami transformasi fundamental. Memang, kita kini hidup dalam zaman dipimpin oleh hemat sains dan teknologi.
Transformasi fundamental yang dahsyat itu dihela oleh perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi. Dengan kata lain, sains dan teknologi harus diakui menjadi determinan (faktor penentu atau pendorong) transformasi fundamental dan dahsyat kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dan peradaban manusia dalam pengertian umum sedang bertransformasi secara fundamental dengan dipimpin oleh hikmat sains dan teknologi.
Paling tidak ada 5 bidang sains dan teknologi yang menjadi pendorong atau pemicu utama transformasi fundamental yang dahsyat dan luar biasa. Lima bidang itu boleh dibilang berkembang dan maju begitu pesat berkat ledakan kreativitas, yang melahirkan invensi-invensi dan inovasi-inovasi. Ledakan kreativitas, invensi, dan/atau inovasi (1) ilmu kealaman dasar, (2) bioteknologi, (3) teknologi informasi dan komunikasi, (4) teknologi transportasi, dan (5) teknologi digital harus dicatat telah mendisrupsi dan merevolusi sendi-sendi kebudayaan dan peradaban. Kelima bidang tersebut juga saling berkelindan, berinterseksi, dan berinfusi mempercepat dan memperlanjut transformasi mendasar sendi kebudayaan dan peradaban.
Di antara lima bidang sains dan teknologi tersebut, harus diakui bidang teknologi digital bukan hanya berkembang maju luar biasa pesat-cepat, namun juga berdampak nyata paling kuat dalam kehidupan kita — berdampak konkret pada kebudayaan dan peradaban. Dengan kata lain, teknologi digital berkembang eksplosif dan revolusioner menciptakan (apa yang sering disebut) revolusi digital. Revolusi digital bukan hanya mengalihmediakan dan mengalihwahanakan, tapi juga memperluas dan mengubah lanskap dan ruang kebudayaan dan peradaban.
Lanskap dan ruang kebudayaan dan peradaban tak hanya yang alamiah dan konvensional, tapi juga yang virtual dan digital. Di sinilah terjadi perluasan dan penambahan lanskap dan ruang kebudayaan. Sekadar contoh, augmented reality telah menambah realitas alamiah di dalam sendi-sendi kebudayaan kita. Demikian juga, terutama juga karena didorong pandemi korona, digitalitas dan virtualitas telah menjadi alternatif ‘tanah air’ kebudayaan — setidaknya memperluas ‘tanah air atau dunia’ kebudayaan kita. Kecanduan dan keriuhan kita ber-zoom, meet, dan sejenisnya saat pandemi korona meruyak, telah mempertegas perluasan dan perubahan ‘tanah air’ kebudayaan.
Selain itu, revolusi digital juga mengubah, memperluas, dan memperkompleks lapisan kebudayaan. Lapisan-lapisan simbolik, sosial, dan material kebudayaan telah didisrupsi atau diubah oleh digitalitas dan virtualitas. Pikiran digital, pola pikir digital, dan nilai digital — sebagai contoh — merupakan penambahan realitas simbolik kebudayaan kita. Interaksi virtual, komunikasi virtual, etika digital, kemanan digital, dan komunitas digital merupakan realitas sosial yang memperkaya lapisan sosial kebudayaan kita. Platform digital, ekonomi digital, teknologi keuangan, dan kantor digital — sekadar contoh — merupakan lapisan-baru material kebudayaan kita.
Itulah sebabnya, dapat kita katakan bahwa kita sedang berhadapan dengan dan memasuki kebudayaan baru, yaitu kebudayaan digital (digital culture). Hadirnya kebudayaan digital tak berarti dan tak harus diartikan kebudayaan sebelumnya hilang atau diganti. Sejarah telah mengajarkan kearifan kepada kita bahwa galaksi atau semestaan hidup manusia tak hanya berisi satu corak atau lapis kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan naskah tidak serta-merta menghancurkan kebudayaan lisan. Begitu juga hadirnya kebudayaan cetak atau literati tak menggusur kebudayaan lisan dan naskah. Di sinilah kita perlu memahami bahwa hadirnya kebudayaan digital tak serta-merta menghancurkan kebudayaan sebelumnya. Memang, mungkin saja menggerus, memoles, dan memperluas kebudayaan sebelumnya. Apa pun konsekuensinya, yang jelas kita sedang memasuki era digital dengan penanda eksistensinya alam digital dan kebudayaan digital.
/3/
Revolusi digital beserta segenap dampaknya membuat kita — kebudayaan kita — memasuki era digital. Lanskap era digital tentulah beda dengan era-era sebelumnya. Istilah era digital menjadi kunci perbincangan kebudayaan dan lanskap era digital menjadi payung nyaris seluruh sektor kebudayaan. Pendeknya, tak ada sektor kebudayaan yang tak dilekatkan, dipayungi, atau dibingkai lanskap era digital. Lanskap era digital menjadi superordinat, menjadi payung utama, perbincangan nyaris tentang apa pun. Misalnya, agama, ekonomi, pendidikan, keluarga, bahkan soal buku dan persuratan. Kita pun menjumpai frasa-frasa baru seperti ‘agama pada era digital’, ‘jumatan digital’, ‘buku pada era digital’, ‘pendidikan pada era digital’, bahkan ‘cinta pada era digital’. Segala nyaris serba digital dan direngku digital.
Di situlah kita menyaksikan gerbong zaman dan kebudayaan kita bergerak fundamental kembali. Bertambahlah tahapan atau babakan perkembangan kebudayaan kita. Berdasarkan tonggak digitalitas dan virtualitas, kita dapat membaginya menjadi babakan (1) era lisan, (2) era naskah/manuskrip, (3) era cetak-tulis, dan (4) era digital. Keempat babakan zaman ini muncul secara kronologis, bukan simultan — muncul bergiliran, bukan berbarengan atai serempak. Namun, perlu dipahami, kemunculan satu zaman tak berarti mematikan zaman sebelumnya. Ambil misal, munculnya era naskah tak mematikan era lisan — munculnya era cetak-tulis ala Gutenberg tak mematikan era lisan. Memang, di sana-sini terjadi penggerusan, penggusuran, dan pergantian peran dan fungsi. Tak ayal, kita pun tercempung ke dalam empat gugusan kebudayaan dan peradaban.
Empat era tersebut mempengaruhi, malah ikut menentukan corak kebudayaan. Di sinilah kita mendapati adanya empat corak atau gugusan kebudayaan, yaitu (1) kebudayaan lisan, (2) kebudayaan naskah, (3) kebudayaan cetak- tulis ala Gutenberg, dan (4) kebudayaan digital. Kebudayaan lisan tentu saja disangga penuh oleh kelisanan; kebudayaan naskah ditopang oleh kelisanan melalui keaksaraan; kebudayaan cetak-tulis Gutenberg disangga literasi dengan aksara sebagai penentu; dan kebudayaan digital ditopang oleh kelisanan sekunder. Meski sekarang sedang ‘naik daun’ era digital dengan kebudayaan digitalnya, tapi keempat rupa kebudayaan tersebut tetap ada di Indonesia. Begitulah, empat kuadran kebudayaan kini ada atau hidup di Indonesia.
Indonesia kita sangatlah luas dengan derajat perbedaan yang tinggi. Sebab itu, kondisi empat kuadran tersebut tidak sama pada setiap daerah atau ruang budaya di Indonesia. Ringkas kata, sapuan warna empat gugusan kebudayaan tersebut tak sama. Misalnya, ada wilayah yang masih tipis sapuan warna kebudayaan digitalnya dan masih sangat tebal sapuan warna kebudayaan lisannya. Ada satu wilayah yang sapuan warna kebudayaan cetak dan digital sama-sama tebal. Meski begitu, kesan sepintas saya, semua wilayah Indonesia sudah mulai memasuki era digital dengan sapuan kebudayaab digitalnya. Begitulah, kita menyaksikan lanskap kebudayaan digital yang berbeda-beda di Indonesia.
/4/
Revolusi digital telah melahirkan dunia dan kebudayaan digital. Kehadiran kebudayaan digital ini telah memperluas, memperkaya, menggeser, mempengaruhi, dan/atau menggantikan (mensubstitusi) kebudayaan sebelumnya. Di sinilah kita kemudian dapat mengategorikan adanya (a) kebudayaan lisan, (b) kebudayaan naskah, (c) kebudayaan cetak-literasi, dan (d) kebudayaan digital. Keempat kebudayaan tersebut bertumpang tindik, saling menyisip dan menyusup, dan saling menyerbuki dan menggendong.
Kebudayaan digital menghidupi sekaligus ditopang oleh kelisanan kedua (pinjam istilah Walter J Ong). Tak jarang ada yang menyebut era pasca-literat (post-literate era). Era pasca-literat atau kelisanan kedua lebih lanjut menyangga berkembangnya masyarakat pasca-literat (pasca-literasi). Hal ini berarti, masyarakat digital merupakan masyarakat pasca-literasi dan kebudayaan digital merupakan kebudayaan pasca-literasi. Pertanyaan kita: adakah dan bagaimanakah tatanan-baru kebudayaan digital yang nota bene pasca-literasi? Apakah lapisan dan sektor (unsur universal) kebudayaan pada umumnya sudah terpadu-terlebur digitalitas — sudah terdigitalisasi? Apakah bahasa dan sastra juga sudah terdigitalisasi sehingga menimbulkan bahasa digital sekaligus sastra digital.
Dapat dikatakan ringkas di sini bahwasanya bahasa dan sastra — termasuk bahasa dan sastra Indonesia — telah mendapat ‘tanah air baru’, yaitu ‘tanah air digital’. Tanah air digital bahasa dan sastra itu menumbuhkan dan mengembangkan (apa yang dapat disebut sebagai) bahasa dan sastra digital. Tengara dan amatan kemunculan dan kehadiran bahasa digital sekaligus sastra digital telah dilakukan oleh berbagai pihak.
Sampai sekarang sudah muncul dan kita harap terus berkembang ke depan konseptualisasi, formulasi, dan kajian tentang bahasa sekaligus linguistik digital. Para pengguna bahasa akan makin banyak menggunakan bahasa digital seiring dengan demikian masifnya digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Generasi pribumi digital (native digital) niscaya akan makin akrab menggunakan bahasa digital. Karena itu, para sarjana, akademikus, dan para ahli perlu memformulasikan sosok linguistik digital, bahkan berkewajiban mengembangkan dan mengaji linguistik digital. Bahasa dan linguistik digital ini merupakan ‘dunia masa depan’ para pengguna dan peneliti bahasa.
Seiring dengan itu, juga mulai muncul dan berkembang sastra digital (puisi dan naratif digital) di samping puitika, estetika, dan kajian sastra digital. Di situ digitalitas bukan hanya medium dan/atau wahana, tetapi juga menjadi substansi atau minimal elemen yang melekat alamiah (inheren) sastra (puisi, fiksi, dan atau naratif). Sebab itu, sastra digital dapat disebut ‘spesies’ baru sastra hasil ‘mutasi literer’ akibat hadirnya dunia dan kebudayaan digital. Sampai di sini kita mungkin bertanya: seperti apakah sosok sastra digital?; seperti apakah karakteristik sastra digital?; dan bagaimanakah eksistensi sastra digital? Tiga pertanyaan kini kapan-kapan saja saya ulas.
Dengan muncul dan hadirnya sastra digital, dalam perspektif kuadran kebudayaan, kita dapat membuat kategori sastra menjadi empat. Pertama, sastra lisan yang sudah ada sangat lama seiring dengan berkembangnya kelisanan dan budaya lisan. Kedua, sastra naskah yang juga sudah amat lama selaras dengan adanya era manuskrip dan budaya manuskrip. Ketiga, sastra cetak-tulis yang hadir seiring dengan eksisnya keaksaraan dan budaya baca-tulis. Inilah yang biasa kita pahami sebagai tradisi dan budaya literasi. Terakhir, keempat, sastra digital yang mulai berkembang sejalan dengan maraknya digitalisasi segala sektor kehidupan dan kebudayaan digital. Keempat kategori sastra tersebut tetap ada atau eksis pada era digital sekarang. Jadi, sastra pada era digital terdiri atas sastra lisan, sastra manuskrip, sastra cetak-tulis, dan sastra digital.
***
*Prof. Dr. Djoko Saryono merupakan guru besar Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia Universitas Negeri Malang. Telah menulis dan menerbitkan beberapa buku mengenai linguistik, sastra, dan pendidikan, seperti Linguistik Bandingan (2011), Dasar Apresiasi Sastta (2009), Tata Kalimat Bahasa Indonesia (2012), Model-model Pembelajaran Mutakhir (2001), dan lainnya. Ada pula karya fiksi, seperti Kemelut Cinta Rahwana (2015) dan Arung Cinta (2015).