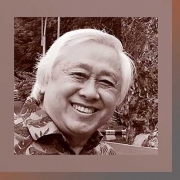Memasuki Rel yang Sama, atau: Upaya Seorang Outsider untuk Memahami Pendirian Arkeologi tentang Pemasangan Chatra di Borobudur Berdasarkan Disiplin Ilmu Arkeologi
Oleh Stanley Khu*
Belakangan ini, terutama sejak bergulirnya kabar tentang keputusan pemasangan chattra di Candi Borobudur, terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara dua kubu, yakni: antara pihak yang membela keputusan ini dan pihak yang menentangnya. Aneka argumen dan kontra-argumen dilontarkan silih-berganti, dan hampir mustahil kiranya untuk merekam secara lengkap segala sesuatu yang telah beredar baik di media-media sosial atau forum-forum yang mempertemukan kedua pihak. Mudah ditebak bahwa perdebatan ini tak akan ada ujungnya. Alasannya sederhana: kedua pihak dapat diibaratkan berada di dua rel yang berbeda dan, lebih parahnya lagi, bergerak ke arah yang sepertinya juga berlawanan. Akibatnya jelas: semakin lama debat ini berlangsung, suara dari masing-masing pihak akan semakin sayup-sayup sampai akhirnya pihak yang satu tidak akan bisa lagi mendengar apa yang dikatakan pihak yang lain. Setidaknya, begitulah kesan yang saya peroleh belakangan ini.
Untuk mengatasi semakin renggangnya kesalingpahaman ini, maka saya memutuskan untuk keluar dari perspektif yang selama ini saya anut dan beralih ke perspektif dari pihak yang kontra dengan apa yang saya yakini. Maksudnya, saya memutuskan untuk berusaha menyelami dan memahami bagaimana sebuah disiplin ilmu yang bernama arkeologi memandang isu chattra. Tujuannya jelas: saya hendak mengetahui apakah gerangan yang melatarbelakangi penolakan yang gencar sekali di kalangan arkeolog dalam menanggapi rencana pemasangan chattra. Logika di balik keputusan saya ini juga kiranya cukup jelas: saya ingin memosisikan diri saya, mengikuti pendekatan verstehen [pemahaman empatik] yang disodorkan oleh sosiolog Max Weber, sebagai arkeolog. Dengan kata lain, saya ingin mencoba melihat fenomena yang sama yang selama ini terus saya lihat dari kacamata filosofis-teologis melalui sebuah kacamata yang baru, yakni: kacamata arkeologis. Secara personal, saya berharap bahwa usaha ini akan lebih mendekatkan saya pada rel lain di sebelah saya, yang selama ini hanya dapat saya lihat berlalu menjauh dari gerbong kereta saya tanpa menuju titik temu.
Demi menjangkarkan fokus argumentasi, tulisan ini hanya akan meninjau satu isu yang memiliki gaung paling besar dalam apa yang, tanpa melebih-lebihkan, boleh digambarkan sebagai huru-hara chattra. Isu yang saya soroti adalah usaha dari pihak yang pro (termasuk saya, salah satunya) untuk membenarkan pemasangan chattra dengan melakukan komparasi atas stupa Buddhis di tempat lain. Argumennya kira-kira seperti ini: karena stupa Buddhis di tempat-tempat lain di dunia memiliki chattra, maka logikanya stupa di Borobudur juga harus dipasang chattra. Pendirian ini mendapat bantahan dari pihak yang kontra (terdiri dari, utamanya, para arkeolog dan sebagian umat Buddhis Indonesia), dengan argumen kira-kira seperti ini: hanya karena stupa-stupa di tempat lain memiliki chattra, tidak lantas berarti bahwa stupa di Borobudur juga harus dipasang chattra. Untuk lebih jelasnya, pihak yang kontra menjabarkan pendiriannya sebagai berikut.
Poin pertama dapat dirumuskan menjadi pertanyaan berikut: kenapa komparasi tidak dilakukan dengan menimbang kesamaan konteks (spasial dan temporal) antar stupa-stupa? Konteks temporal bermakna bahwa stupa-stupa yang diperbandingkan harus berasal dari periode yang sama, sementara konteks spasial bermakna bahwa stupa-stupa yang diperbandingkan harus berasal dari tempat-tempat yang memiliki kaitan historis dengan Nusantara dalam konteks temporal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih gampangnya, diandaikan bahwa tidaklah masuk akal bagi stupa di Borobudur untuk dipasang chattra dengan meniru praktik dari tempat-tempat yang peradabannya eksis jauh setelah Borobudur. Singkat kata, buat apa Borobudur mengikuti fenomena yang terjadi lebih belakangan alih-alih mempertahankan autentisitasnya?
Poin kedua terkait erat dengan poin pertama. Argumennya berbunyi bahwa perwujudan stupa yang saat ini terlihat di Borobudur adalah karakteristik khas dari peradaban Nusantara sehingga merupakan bagian integral dari peninggalan budaya, atau dengan kata lain, sesuatu yang secara kultural ditinggalkan atau dititipkan atau diwariskan oleh generasi lampau untuk dijaga atau dipertahankan atau dilestarikan oleh generasi saat ini dan, mudah-mudahan, oleh generasi di masa depan. Beberapa kata kunci yang dapat merangkum poin kedua ini adalah keaslian, kemurnian, kearifan lokal, warisan adiluhung, pelestarian, dan seterusnya.
Kedua poin ini dilatarbelakangi oleh semangat yang meyakini bahwa ada sesuatu yang ajeg, kekal, konstan, permanen, atau abadi dari sebuah gagasan abstrak (bisa juga, entitas konkret) yang kita namakan Nusantara atau Indonesia. Terutama sekali dalam konteks itikad baik untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia sebagai landasan bagi karakter bangsa, terdapat usaha intensif untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengklasifikasikan tiap-tiap objek sehingga batasan-batasannya tergambar dengan jelas dan satu objek dapat dirumuskan kekhasannya secara akurat terhadap objek lainnya.
Akan lebih mudah untuk memahami pemaparan di atas melalui analogi yang konkret, dan saya akan menyodorkan makanan khas sebagai contoh kasus. Lebih tepatnya, saya akan menyodorkan soto sebagai alat bantu untuk memudahkan apa yang hendak saya sampaikan di sini. Sebagai makanan, soto sungguh menarik karena setiap daerah mengklaim memiliki resep khas mereka masing-masing dalam mengolah masakan yang hasil akhirnya adalah soto. Untuk sekadar mengutip beberapa contoh, kita mengenal ada yang namanya Soto Medan, Soto Bandung, Soto Betawi, Soto Lamongan, dan masih banyak lagi varian soto lainnya. Pelabelan nama-nama soto ini berdasarkan asal regionalnya masing-masing bukan perkara main-main, karena terdapat asumsi implisit bahwa sebuah soto dari Medan dinamakan Soto Medan karena teknik dan bahan bakunya berbeda dari, katakanlah, sebuah soto dari Bandung yang dinamakan Soto Bandung. Misalnya, Soto Medan boleh dikatakan berciri khas karena memakai tauge, sementara ciri khas Soto Bandung adalah pemakaian lobak. Semangkuk Soto Medan yang menyertakan lobak akan dipandang ganjil, semata-mata karena lobak tidak pernah dikenal sebagai bahan baku dalam memasak dan menyajikan Soto Medan. Dengan kata lain, penyertaan lobak dalam sajian Soto Medan bukanlah bagian dari peninggalan budaya dalam wujud tradisi kuliner Medan.
Sampai di sini, barangkali pembaca sudah bisa menebak arah yang hendak disasar tulisan ini: bahwa argumen yang kontra terhadap pemasangan chattra di Borobudur, baik dalam hal logika dan semangat, tidak bisa dibedakan dari argumen yang menekankan kekhasan dari soto tiap-tiap daerah di Nusantara. Maksudnya, terdapat fitur-fitur dari kedua kasus yang sama-sama dibekukan secara spasio-temporal untuk menyajikan sebuah argumen tentang keajegan linear dari sesuatu yang lantas digunakan untuk membenarkan keunikannya – dalam hal ini, keunikan dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda dari sesuatu lainnya berdasarkan ketidakberubahan fitur-fitur yang menyusun keberadaan dari sesuatu itu.
Macam-macam Pendekatan Arkeologi
Melalui hasil pembacaan saya, bukan sebagai arkeolog profesional melainkan sebagai outsider yang terdorong untuk menekuni literatur arkeologi demi memahami alasan di balik pendirian pihak yang kontra terhadap pemasangan chattra, saya mendapati bahwa satu pendekatan yang kemungkinan besar melandasi pendirian ini (entah secara implisit atau eksplisit) adalah apa yang dikenal sebagai arkeologi kultural-historis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelompokkan masyarakat manusia ke dalam kelompok-kelompok kultural yang khas menurut kebudayaan material yang ditemukan dalam kelompok yang bersangkutan.
Motif utama pendekatan ini adalah semangat untuk mencari variasi dan kemudian melakukan klasifikasi. Artinya, peninggalan material yang ditemukan atau tidak ditemukan di dalam sebuah masyarakat akan menentukan ke dalam kelompok manakah masyarakat tersebut berada. Dalam konteks kontroversi ada tidaknya chattra di Borobudur, arkeologi kultural-historis akan berargumen bahwa bukti tentang ketiadaan chattra menunjukkan bahwa ketiadaan inilah yang mencirikan keunikan dan mendefinisikan “Nusantara”. Di sisi lain, usaha-usaha untuk menambahkan chattra atau ornamen-ornamen lain ke stupa Borobudur justru berisiko membongkar ke-Nusantara-an dan menjadikannya sebelas dua belas dengan kelompok kultural lain (Indocina, Indik, dst.). Singkat kata, Nusantara adalah Nusantara karena stupanya, meskipun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kebudayaan asing, pada akhirnya tetap memiliki sebuah ciri khas yang membedakannya dari stupa di tempat-tempat lain – dalam hal ini, ciri khas yang dimaksud berupa sebuah negasi: bahwa Nusantara adalah unik karena apabila stupa di tempat lain ber-chattra, maka stupa di Nusantara justru tidak (perlu) ber-chattra.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan arkeologi kultural-historis sungguh bernuansa nasionalistik, dan memang faktanya acapkali dipakai sebagai ideologi untuk menyambungkan negara modern dengan kisah asal-usul yang seringkali bercorak primordial dan mitis. Dalam studinya tentang praktik arkeologis di Israel, antropolog Nadia Abu El-Haj menunjukkan bahwa klaim-klaim teritorial yang dilakukan negara Israel sangat dipengaruhi oleh kesimpulan dan temuan dari tim arkeolognya yang secara sepihak dan manasuka mengklasifikasikan hasil-hasil ekskavasi sebagai bercorak Israel/Yahudi, dan dengan demikian menafikan kemungkinan bahwa sebuah objek arkeologis pernah dipakai bersama oleh aneka bangsa yang berbeda. Studi lain dari antropolog Gary Feinman dan Jill Neitzel mencatat bahwa tafsir arkeologis tentang migrasi massal dan pergerakan populasi di kalangan orang Amerika Asli telah menjadikan klaim mereka atas tanah adat tidak valid, karena migrasi massal bermakna bahwa leluhur orang-orang ini telah mengabaikan area yang saat ini mereka klaim sebagai milik mereka. Konsekuensinya, orang Amerika Asli yang hendak mengklaim tanah adat harus mampu membuktikan kehadiran permanen mereka di sebuah teritori kepada pemerintah A.S. serta pengadilan. Padahal, semua orang awam juga tahu bahwa leluhur mereka telah mendiami benua Amerika jauh sebelum kedatangan Columbus!
Dengan demikian, tepatlah arkeolog Ulrike Sommer ketika menyatakan bahwa mitos tentang asal-usul nasional seringkali lebih relevan secara politis bagi orang-orang dari masa kini dan masa depan ketimbang bagi orang-orang dari masa lalu yang justru hidup di dalam periode yang digambarkan oleh mitos tersebut. Dan dalam hal ini, tidaklah sulit untuk menerka bahwa kemungkinan besar isu tentang chattra dan Borobudur di Nusantara abad ke-8 sampai 10 tidak akan seheboh kontroversi yang dimunculkannya saat ini.
Kontra argumen boleh jadi menjawab bahwa orang-orang dari masa itu tidak ambil pusing dengan ada tidaknya chattra karena mereka sudah bersepakat bahwa tidak perlu ada chattra di Borobudur (kalau tidak, maka bukti tentang keberadaan chattra sudah akan ditemukan oleh arkeologi, dan tulisan ini tidak perlu dibuat!). Di sini, saya akan mencoba memberikan kontra atas kontra argumen ini. Pertama-tama, mari kita tetapkan isunya, yang berbunyi kira-kira begini: jika memang chattra sedari dulu sudah ada di Borobudur, kenapa kita sampai sekarang tidak juga menemukan bukti keberadaannya?
Pertanyaan yang demikian kemungkinan besar akan dimunculkan oleh mereka yang menganut pendekatan kedua, arkeologi prosesual. Secara pribadi, saya percaya bahwa kalangan arkeolog di Indonesia kemungkinan besar menganut pendekatan ini, karena arkeologi kultural-historis sarat nuansa politis dan, faktanya, sudah ketinggalan zaman sejak lebih dari setengah abad silam. Alasan lain untuk meyakini bahwa arkeologi di Indonesia menganut arkeologi prosesual adalah akar pendekatan ini yang berjangkar pada positivisme, yang dibuktikan dengan sangat gamblang oleh desakan untuk menerapkan metode saintifik dan empirik dalam mengkaji arkeologi. Niatnya tentu baik, yakni untuk menemukan kebenaran objektif tentang masyarakat manusia pada suatu masa melalui pengumpulan dan analisis data secara mendetail.
Niat untuk menemukan kebenaran objektif adalah baik karena tujuannya adalah meminimalisir ruang-ruang bagi mis-interpretasi dalam studi arkeologi. Akan tetapi, satu pertanyaan yang segera muncul adalah: Bagaimana cara membedakan antara mis-interpretasi dan multi-interpretasi? Apa indikator untuk menyatakan dengan tegas bahwa sebuah tafsir adalah benar secara mutlak (baca: objektif) di atas tafsir-tafsir lain sehingga pada akhirnya multi- menjadi bersinonim dengan mis-? Dalam kapasitas saya sebagai insider di disiplin ilmu sosiologi dan antropologi, saya dapat dengan percaya diri berkata bahwa positivisme, seperti halnya arkeologi kultural-historis, sudah ketinggalan zaman. Dan lebih buruk lagi, paham ini tidak hanya usang, tetapi juga berbahaya karena mengandung bias dari epistemologi Barat yang mengklaim kebenaran universal secara sepihak sembari menafikan alternatif dari sistem pengetahuan non-Barat. Pertanyaan yang kemudian meneruskan rasa penasaran saya adalah: tidak adakah respons intelektual yang sama di dalam disiplin ilmu arkeologi? Atau, jangan-jangan, arkeologi sebagai disiplin ilmu memang sudah mencapai titik final perkembangannya dengan positivisme?
Pembacaan saya atas literatur arkeologi, untungnya, tidak menuntun pada kesimpulan ini. Saya menemukan bahwa arkeologi faktanya memiliki sebuah pendekatan lain yang dikenal dengan nama arkeologi post-prosesual. Bahkan, faktanya, tercatat bahwa arkeolog kenamaan sekelas Ian Hodder sekali waktu pernah menganut arkeologi prosesual sebelum akhirnya merasa kecewa dengan pendekatan ini dan lantas berpaling ke arkeologi post-prosesual. Baginya, peralihan ini sungguh logis: pendekatan lama tidak memberikan ruang atau suara bagi orang-orang yang kebudayaannya dikaji secara ilmiah oleh ilmuwan untuk menawarkan pandangan emik mereka sendiri, sementara di sisi lain, pendekatan baru seperti arkeologi post-prosesual menolak elitisme profesional ini dan berusaha merangkul suara-suara marjinal secara empatik alih-alih membungkamnya dengan aneka alasan (misalnya: ancaman bahwa status world heritage akan dicabut oleh UNESCO, dst.).
Pendekatan arkeologi post-prosesual membangkitkan secercah harapan dalam diri saya. Bagaimana tidak? Pendekatan ini menggugurkan imajinasi saya tentang dua rel dengan dua gerbong kereta yang bergerak menjauhi satu sama lain. Sebaliknya, saya malah didorong untuk membayangkan satu jalur rel yang sama di mana dua gerbong kereta dapat saling bergandengan, yang entah kenapa mengingatkan saya pada ungkapan bijak tentang sains dan agama (bunyinya kira-kira begini: sains tanpa agama akan lumpuh, agama tanpa sains akan buta).
Arkeologi post-prosesual memiliki sejarah yang panjang, tapi secara singkat, satu kata kunci yang kiranya dapat merangkum semangat dari pendekatan ini adalah multi. Untuk lebih jelasnya, beberapa contoh kasus konkret yang didasarkan pada komentar-komentar kontra yang hari-hari belakangan berseliweran di berbagai media akan saya sodorkan.
Kasus pertama adalah pandangan bahwa arkeolog, selaku ilmuwan atau akademisi, memiliki monopoli pengetahuan atas sebuah objek yang sudah terlebih dahulu dilabeli sebagai objek kajian arkeologis (baca: Borobudur). Jika arkeologi prosesual tidak ambil pusing terhadap pelabelan satu pihak ini, arkeologi post-prosesual justru mempertanyakan bias inheren yang kemungkinan besar dimiliki oleh peneliti dalam merumuskan tafsir, argumentasi, dan kesimpulannya. Saya memilih frasa bias inheren karena alasan berikut: tak ada seorang arkeolog pun yang akan secara terbuka mengamini bahwa dirinya memegang monopoli eksklusif atas pengetahuan tentang sesuatu, tapi faktanya, berdasarkan apa yang secara aktual dituturkan dan dilakukan, tampak jelas bahwa terdapat sebuah bias profesional atau akademis. Bukti paling sederhana tentu saja keengganan untuk mempertimbangkan bahwa sebuah objek kajian dapat dikaji baik secara arkeologis maupun non-arkeologis, apalagi jika kita turut menimbang fakta bahwa objek kajian yang dimaksud masih memiliki orang-orang yang menyematkan signifikansi padanya. Ini tercermin, misalnya, oleh gambar muram Borobudur dengan pita berkabung yang belakangan ini sedang trendy. Misal lain adalah ungkapan “Pray for Borobudur” yang juga tidak kalah trendy, yang memicu diadakannya FGD atau forum dadakan untuk menanggapi apa yang dipahami oleh pihak-pihak yang mendoakan Borobudur ini sebagai situasi darurat nasional. Dalam hal ini, perspektif non-sains tidak dikategorikan sebagai multi-, tapi mis-interpretasi.
Arkeologi post-prosesual tidak akan kalang-kabut atau kebakaran jenggot melihat isu ini, semata-mata karena ia merangkul perspektif dari kaum marjinal yang suaranya selama ini tidak didengar (dan yang sekalinya terdengar malah buru-buru hendak dibungkam lagi untuk menjaga garis batas sakral antara sains dan non-sains).
Kasus kedua adalah usaha dari pihak yang kontra untuk mencocokkan bentuk stupa di relief Borobudur dengan stupa induk di puncak candi. Argumennya adalah: stupa yang digambarkan di relief tidak ber-chattra, sehingga tidaklah valid untuk memasang chattra pada stupa induk. Argumen ini secara eksplisit memakai relief candi sebagai landasannya, sehingga marilah kita asumsikan juga bahwa relief candi adalah landasan yang sahih dalam berargumen. Pada relief-relief candi, memang faktanya stupa-stupa tidak digambarkan ber-chattra. Namun, patut dicatat bahwa pada relief-relief yang sama, tergambar pula aneka simbol chattra dengan aneka konteks ceritanya. Di sini, kita dihadapkan pada dua kesimpulan. Pertama, chattra digambarkan sebagai objek persembahan yang baik, dan kedua, stupa digambarkan sebagai tidak ber-chattra. Dua kesimpulan ini pada dasarnya bisa saja berdiri sendiri-sendiri, tapi akan menjadi kontradiktif satu sama lain apabila, katakanlah, ada pihak (nyatanya memang ada) yang berkomentar: karena chattra adalah objek persembahan yang baik, maka saya ingin mempersembahkannya kepada stupa induk Borobudur. Dihadapkan pada komentar yang sebenarnya bernada polos dan berniatan baik ini, ketegangan yang tadinya tersembunyi kini menyeruak lagi ke permukaan. Satu pihak akan menekankan pada gambar stupa yang menjadi sorotannya, sementara pihak lain akan lebih berfokus pada chattra.
Sekali lagi, arkeologi post-prosesual tidak akan kalang-kabut atau kebakaran jenggot melihat isu ini, semata-mata karena ia mengakui bahwa manusia di masa lalu tidak hanya meninggalkan artefak fisik yang dapat dibekukan begitu saja dengan menyedot habis muatan simboliknya; sebaliknya, pendekatan ini mengakui makna-makna subjektif dan personal dari sebuah objek yang pastinya tidak akan kentara apabila dilihat secara material belaka. Objek yang saya maksud adalah stupa, yang jika dilihat secara impersonal barangkali tidak akan mengesankan apa-apa selain ketakjuban pada aspek arsitekturalnya, tapi yang apabila dilihat secara personal (dari kacamata umat) akan secara langsung menyimbolkan perlambang batin Sang Buddha. Ajakan untuk melihat stupa sebagai perlambang batin Buddha bukanlah ajakan untuk menjadi Buddhis, melainkan ajakan untuk ber-verstehen pada pemahaman emik pihak lain, yang merupakan prasyarat bagi setiap sosiolog dan antropolog dan, mudah-mudahan, juga arkeolog.
Tulisan ini sebenarnya ingin menyajikan lebih banyak kasus lagi, tapi karena keterbatasan spasio-temporal, maka kasus ketiga akan sekaligus juga menjadi kasus terakhir yang dibahas. Kasus ini barangkali adalah yang terpenting, tidak hanya karena substansinya, melainkan juga karena miskomunikasi yang dikandungnya. Kasus yang dimaksud adalah rencana pemasangan chattra di Borobudur yang, konon jika nantinya terlaksana, akan memakai chattra batu warisan Van Erp. Sudah tidak terhitung banyaknya pendapat yang menyoroti ketidaksesuaian antara chattra ini dengan stupa induk Borobudur.
Pendapat ini bukannya keliru, tapi sepertinya agak salah alamat. Izinkan saya menjelaskannya lebih jauh. Secara personal, saya tidak pernah bertemu atau mendengar pihak yang pro pemasangan chattra yang menyatakan bahwa chattra warisan Van Erp-lah yang harus dipasang di stupa induk. Dengan kata lain, saya tidak pernah mendengar ada individu yang menyerukan “chattra Van Erp harga mati!” Kalaupun ada pendapat-pendapat yang secara tersirat mengacu pada atau membayangkan chattra Van Erp di benaknya saat menyampaikan dukungan atas pemasangan chattra di stupa induk Borobudur, cukup adil kiranya untuk berasumsi bahwa pendapat tersebut muncul semata-mata karena belum dilengkapi oleh data tentang kesesuaian antara bentuk chattra dan bentuk stupa. Bagi saya, situasinya gampang saja. Bagi orang-orang yang baru belakangan mendengar dan belajar tentang sejarah chattra dan Borobudur, besar kemungkinan bahwa satu-satunya model chattra yang ada dalam bayangan adalah chattra warisan Van Erp. Akan tetapi, ini tidak lantas berarti bahwa mereka menyematkan label “harga mati” pada chattra Van Erp. Satu-satunya perhatian dari umat Buddhis Indonesia yang mendambakan pemasangan chattra adalah terpasangnya chattra; soal model chattra yang bagaimana atau soal harus permanen atau tidaknya pemasangan, itu bukanlah urusan utama. Lagipula, umat Buddhis yang pro pemasangan chattra sedari awal paham bahwa chattra adalah simbol; dengan demikian, hal terpenting di sini adalah bahwa simbolnya teraktualisasikan, bukan model simbol atau tata-cara pemasangan seperti apa yang harus digunakan.
Sekali lagi, arkeologi post-prosesual tidak akan kalang-kabut atau kebakaran jenggot melihat isu ini, semata-mata karena fokusnya pada pemahaman multidimensional akan mencegahnya untuk secara reaktif menyikapi polemik chattra dan, sebaliknya, justru mendorongnya untuk menilai situasi yang ada secara berimbang. Mengakui keberimbangan aneka pendapat adalah mengakui kemungkinan adanya bias personal dalam sebuah usaha akademik yang, idealnya, impersonal. Dalam hal ini, arkeologi post-prosesual mengajarkan kerendahan hati yang, idealnya, dimiliki oleh para pemilik pengetahuan.
***
Dalam tulisan ini, tujuan saya adalah menjawab sebuah pertanyaan pribadi yang, saya duga, juga telah muncul dalam benak orang-orang belakangan ini: apakah benar adanya bahwa arkeologi dan Buddhisme tidak bisa didamaikan sehingga keduanya akan terus bersilang pendapat sampai akhir zaman?
Penelusuran saya atas literatur arkeologi, untungnya, tidak berujung pada suatu kesimpulan yang suram. Alih-alih menemukan sebuah kesenjangan yang mustahil dijembatani, apa yang saya temukan justru ruang dialog potensial yang bukan hasil transplantasi paksa dari filosofi-teologi ke sains, tapi sesuatu yang memang eksis dalam disiplin ilmu arkeologi itu sendiri. Dengan kata lain, tanpa perlu mencocok-cocokkan dua gagasan dari dua tradisi pemikiran yang berbeda (meski saya yakin ini pun tidak mustahil), arkeologi pada kenyataannya memiliki perangkat di dalam tradisi akademiknya sendiri untuk memandang huru-hara chattra melalui sebuah sudut pandang yang lain. Artinya, kalaupun arkeologi bersikeras untuk mempertahankan pendirian saintifiknya, pendirian ini tidak lantas harus bersinonim dengan positivisme. Arkeolog dapat tetap bersetia pada arkeologi sembari berjalan beriringan dengan tradisi non-arkeologi.
Sebagian pihak yang pro mengatakan bahwa Borobudur adalah milik umat Buddhis, sementara sebagian pihak yang kontra mengatakan bahwa Borobudur bukan milik umat Buddhis saja. Saya kira poin pentingnya bukan soal Borobudur adalah milik siapa. Bagi saya pribadi, Borobudur adalah milik siapapun yang merasa ingin memilikinya. Akan tetapi, mengklaim Borobudur juga berarti mengklaim tanggung jawab yang menyertai klaim kepemilikan ini. Dan itu bisa dimulai dengan mencoba memahami Borobudur melalui multi-perspektifnya.
——
Sumber Rujukan
Abu El-Haj, Nadia. 2002. Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society. Chicago: University of Chicago Press.
Feinman, Gary M. and Jill E. Neitzel. 2020. “Excising Culture History from Contemporary Archaeology.” Journal of Anthropological Archaeology 60: 1–13.
Hodder, Ian (ed.). 2001. Archaeological Theory Today. Cambridge: Polity Press.
Sommer, Ulrike. 2017. “Archaeology and Nationalism.” In Key Concepts in Public Archaeology, edited by Gabriel Moshenska, 166–186. London: UCL Press.
*Stanley Khu (Dosen Universitas Negeri Semarang, Editor Senior Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lamrim Nusantara)