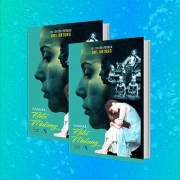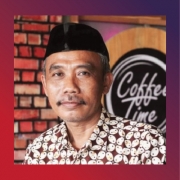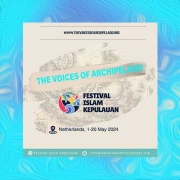Meme yang Kita Jalani
Oleh Nizar Machyuzaar*
Media sosial telah menjadi bagian hidup kita dalam berinteraksi. Bahkan, media sosial telah mengubah arah komunikasi kita dalam memperoleh informasi. Setiap orang yang memiliki akun di platform media sosial adalah sekaligus agen pemroduksi informasi. Mereka tidak hanya menjadi pengonsumsi informasi yang pasif, tetapi juga pengonsumsi dan sekaligus pemroduksi informasi yang aktif manakala menggunggah konten atau mengunggah ulang konten.
Dengan begitu, konten bukan hanya dimiliki sekelompok orang yang berfungsi menilai kelayakan publikasi pesannya. Selama ini, fungsi tersebut dimiliki oleh para redaktur media massa mainstream. Warganet adalah pemilik media sekaligus penilai kelayakan publikasi pesan konten. Dengan begitu pula, media sosial memiliki kekuatan massif untuk meningkatkan kesadaran publik, membentuk opini publik, menciptakan gerakan sosial, dan memengaruhi media mainstream dalam preferensi isu.
Replikasi | Barangkali, kita masih ingat bagaimana pengaruh daya kritis warganet pada media sosial dalam kasus Ahok pada pilkada DKI Jakarta, UU Cipta Kerja yang kemudian direvisi, dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan pengusaha, candaan pendakwah yang dianggap kasar, dan sebagainya. Yang baru-baru ini masih hangat menjadi perhatian warganet adalah kasus perselingkuhan sekaligus korupsi seorang mantan gubernur.
Kodifikasi massif unggah dan unggah ulang potongan konten dapat bersifat faktual dalam kemasan berita, faksional dalam kemasan ulasan, atau fiksional dalam kemasan reka kreasi konten. Bahkan, replikasi konten dengan tujuan tertentu dapat membuat konten bermuatan tendensius alias tidak berimbang, berita bohong, atau ujaran kebencian.
Tujuan dan pesan pembuat konten dapat disertakan dalam takarir secara lugas. Lebih dari itu, unggah dan unggah ulang konten dapat berbentuk reka kreasi konten dengan pengurangan, penambahan, bahkan pembuatan konten baru sebagai tanggapan atas konten sebelumnya. Kurang lebihnya, konten seperti ini yang lebih banyak diproduksi dan dikonsumsi warganet. Konten viral yang kita kenal dengan istilah meme. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawskin dalam buku The Selfies of Gene (1976). Meme dimaksud sebagai alih-alih istilah gen yang diwariskan, tetapi dalam evolusi budaya.
Dalam replikasi konten ini terdapat situasi komunikasi yang khas, yakni realitas objektif yang terdokumentasikan dalam konten pertama dan realitas simbolik sebagai hasil reka kreasi dalam konten kedua. Hubungan dialektis kedua realitas tersebut bersifat substitusi, yakni penggantian secara paksa konten pertama dengan konten kedua. Bagaimana meme yang merupakan realitas baru dapat berterima dengan pemahaman dan pengetahuan pengonsumsinya?
Setidaknya, kita dapat mengurai kembali kedua realitas yang tesertakan dalam meme. Langkah ini dapat dilakukan dengan menganalisis aspek kewacanaan meme, yakni pemroduksi, konten, pengonsumsi, dan situasi komunikasi yang melingkungi ketiga aspek terbicarakan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penafsiran atas fitur kewacanaan meme yang menyertakan gambar dan teks yang berhubungan dengan pilihan gaya tutur, yakni sindiran.
Narasi Metaforis | Aspek dan fitur kewacanaan meme yang terbicarakan berhubungan dengan struktur tanda dan penandaannya dalam hubungan kausalitas atau kronologis. Penjelasan atas rangkaiannya dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu tanda, yakni semiotika atau semiologi. Sementara itu, pemahaman atas makna rangkaiannya dapat dilakukan dengan pendekatan semantik, yakni interpretasi dalam hermeneutika. Kedua pendekatan ini mengandaikan meme sebagai teks yang memiliki struktur ketandaan baku sekaligus menghubungkannya dengan sesuatu di luar ketandaan, yakni peristiwa.
Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa memahami meme tidak hanya memetakan situasi komunikasi dalam aspek dan fitur kewacanaannya, tetapi juga mengidentifikasi posisi, reposisi, dan disposisi wacana yang menyertakan penggantian paksa dua kode sosial dan budaya, yakni kode sosial dan budaya pada realitas pertama (bahan baku meme) dan kode sosial dan budaya pada realitas kedua (meme). Dengan begitu pula, pemahaman atas meme berhubungan juga dengan tujuan dan pesan (subjektif) pembuat meme.
Lebih dari itu, kita dapat melekatkan aspek ideologi pembuat meme melalui identifikasi tujuan dan pesan meme. Narasi baru meme berasal dari tegangan di antara narasi konten pertama sebagai bahan baku dan narasi konten kedua sebagai metaforanya. Konkretisasi makna diproduksi sebuah meme manakala pengonsumsi meme mampu mengidentifikasi proses substitusi dua narasi dan mampu mengodifikasi tegangan di antara kode sosial dan budaya kedua konten. Hal ini dapat dianggap sebagai alih-alih dari perluasan metafora sebagai karakter dasar pembangun pengetahuan manusia, sebagaimana prasaran Paul Riceour dalam The Rule of Metaphor (1975).
Akhirnya, kita dapat menempatkan meme sebagai tindakan sosial warganet melalui akun platform media sosial. Meme menjembatani dua konten dengan ungkapan-ungkapan metaforis. Jalan penafsiran sering memerangkap warganet ke dalam narasi metaforis berlapis yang tujuan dan pesannya tersembunyi dalam humor menyindir atau satire. Bisa jadi, tujuan dan pesan subjektif pembuat meme tidak teridentifikasi manakala kita mengonsumsi meme yang berkonten hoax, hate speech, dan black champagne.
Mangkubumi, 17 April 2025
—-
*Penulis,Mahasiswa Magister Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya Unpad