Tamansiswa, Quo Vadis?
Memberi kepercayaan diri pada perjuangan. Betul pendapat yang disampaikan secara virtual oleh Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Prof Dr Muhadjir Effendy dalam perayaan 100 tahun Tamansiswa di Pendapa Agung di Yogya 3 Juli lalu. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa di tahun-tahun awal pendiriannya Tamansiswa mampu memberikan kepercayaan diri yang luar biasa pada banyak pemikir dan aktivis pergerakan.

Foto acara peringatan 100 tahun Tamansiswa di Pendapa Agung di Yogya tanggal 3 Juli 2022. (Sumber: Arsip BWCF)
Sekolah-sekolah menengah pada saat itu hanya didirikan oleh pemerintah kolonial. Mereka-mereka yang bisa masuk hanyalah anak-anak kalangan kolonial dan hanya terbatas lapisan atas pribumi. Munculnya Tamansiswa yang membuka pendidikan tanpa pandang kelas, semua kalangan tanpa membeda-bedakan golongan baik dari kalangan buruh sampai priyayi mendobrak elitisme pendidikan kolonial. Lahirnya Tamansiswa seolah membuat kalangan pribumi yang sadar akan perlunya kemerdekaan mendapat angin kepercayaan diri yang luar biasa. Dibukanya sebuah sekolah modern tapi sistem pendidikannya juga berakar dari akar- akar kebudayaan luhung sendiri melahirkan semangat untuk merealisasikan sikap-sikap anti kolonialisme. Kita tahu pada awalnya Tamansiwa oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai sekolah liar.
Harus diakui sampai saat ini membaca tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara di tahun 30 an demikian sangat menggetarkan. Tulisan-tulisan itu tetap memiliki relevansi tinggi di masa kini. Ki Hadjar seolah mengingatkan kita bahwa inti pendidikan adalah pembebasan manusia, pemerdekaan manusia. Tujuan pendidikan bukan mencetak manusia-manusia kerdil yang sekedar terseret menjadi manusia massa dan tak punya keberanian untuk keluar dari lingkaran konservatisme dan hipokrisi. Pendidikan budi pekerti, sikap batin yang terbuka kepada spiritual dan kodrat alam adalah hal yang dimuliakan dalam Tamansiswa. Sikap-sikap seperti ini bahkan disadari oleh Tamansiswa harus diberikan sejak anak-anak. Pendidikan anak-anak sangat diperhatikan oleh Tamansiswa. Suara Ki Hadjar ini di masa itu mendahului zaman. Lebih dulu dari pemikir-pemikir pendidikan progressif di Amerika Latin tahun 70 an seperti Paolo Freire atau Ivan Illich.
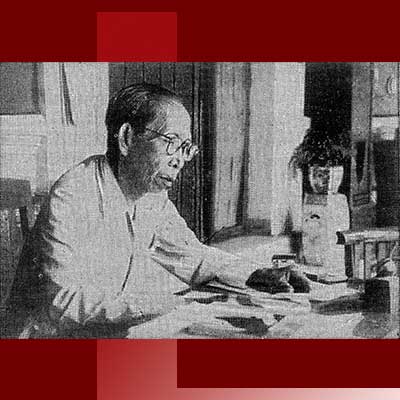
Foto Ki Hadjar Dewantara (Sumber: https://id.wikiquote.org)
Bacalah kritik Ki Hadjar terhadap sistem pendidikan kolonial pada artikelnya yang berjudul: Pengajaran Bagi Rakyat Kita Kurang dan Mengecewakan yang dimuat di Majalah Wasita Jild I no 5 –Februari 1929 atau Protes Persatuan Guru Hindia Belanda atau Hancurnya Sistem H.I.S Kolonial yang diterbitkan pada Majalah Pusara November 1931, Jilid 1 No 3-4-5. Betapa di kedua artikel tersebut Ki Hadjar sangat tepat merumuskan apa itu perbedaan utama pendidikan nasional dan pendidikan yang dioperasionalisasikan pemerintah kolonial. “Sudah seringkali kita menerangkan bedanya Pengajaran Nasional dan Kolonial. Yang pertama berkehendak mendidik intelek orang-orang Indonesia, supaya mereka kelak itu menjadi rakyat (staatsburger) yang menjadi tiang atau penegak keluhuran tanah dan bangsa kita; yang kedua yaitu berkehendak mendidik rakyat kita supaya cakap jadi pembantu kekuasaan kolonial…”
Beberapa tulisan Ki Hadjar bahkan seolah-olah baru saja ditulis tahun-tahun belakangan karena demikian pas menyikapi fenomena kejahatan kontemporer. Dalam tulisannya yang dimuat di Majalah Pusara Agustus 1933, jilid III no 11 berjudul: Tabiat Pengrusak Lahir dan Pengrusak Batin. Vandalisme dan Terorisme, misalnya Ki Hadjar berbicara tentang masalah genting yang kita hadapi kini yaitu merebaknya terorisme di mana-mana. Dalam tulisan itu Ki Hadjar menekankan bahwa terorisme dan vandalisme adalah dua penyakit manusia yang merusak masyarakat. Ki Hadjar menekankan bahwa sedari dini, pada pendidikan anak-anak harus ditanamkan suatu sikap aktif untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan publik. Ki Hadjar melihat banyak hal kejahatan dibiarkan saja dalam masyarakat atau masyarakat tahu adanya kejahatan tapi diam saja, itu lantaran sedari kecil, masyarakat tidak dididik untuk mencegah hal demikian. Misalnya anak melihat pancuran kran waterleiding tidak tertutup, sehingga airnya mancur terus, tapi dia tidak menutup kran itu atau tidak mengindahkan sama sekali karena menganggap hal tersebut bukan tanggung jawab dia. Hal demikian menurut Ki Hadjar menanamkan watak pasif sedari kecil yang kemudian di kelak kemudian hari dapat merugikan masyarakat.
Sering tulisan Ki Hadjar bila kita baca lagi membuat kita spontan merefleksikan hubungan kembali kondisi relasi antar negara dalam kapitalisme global. Kita tahu meski kita sudah lepas dari era kolonialisme namun karena segala persoalan finansial sebuah negara selalu kait mengkait dengan fluktuasi keuangan dinamika internasional, maka sebuah negara dituntut untuk selalu hati-hati agar senantiasa waspada, lincah, tidak terjebak dalam trap utang internasional dan hubungan yang tidak setara dengan negara lain atau korporatisme raksasa global. Renungkanlah kalimat panjang Ki Hadjar di Majalah Wanita, edisi Desember 1947 Tahun I no 1 – yang sesungguhnya diperuntukkannya untuk situasi tak menentu sesudah kemerdekaan tapi masih mengena saat ini :
“…Berdiri sendiri dalam soal kemerdekaan itu tidak hanya berarti “berdiri” yang tak berdaya, berdiri asal berdiri, dalam arti yang sempit. Berdiri sendiri harus diartikan sebagai ketegakan berdiri karena kekuatan sendiri. Berdiri karena kekuatan orang lain, baik yang dipinjamkan, maupun yang bersifat tuntunan atau perlindungan (yang biasanya tidak nampak dengan terang) belum merupakan “merdeka” sejati. Itulah kemerdekaan-pulasan yang tak bersifat mandiri, pun tak akan mendatangkan kebebasan. Itulah kemerdekaan kanak-kanak atau kemerdekaan boneka.
Berdiri sendiri dalam soal kemerdekaan harus diartikan sebagai kekuatan untuk berdiri serta bertindak pula. Dalam arti yang luas ialah kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Juga dalam hal ini janganlah hak dan kewajiban mengurus hidupnya sendiri itu diartikan sebagai “mengurus asal mengurus” saja, tetapi mengurus dengan “beres”; yaitu dapat mewujudkan tertib dan damai di dalam hidup dan penghidupannya. Kemerdekaan yang tak dapat mewujudkan hidup lahir yang tertib, dan hidup batin yang damai, bukan kemerdekaan sejati tetapi kemerdekaan anak-anak belaka…”
Untuk mampu menciptakan gaya pendidikan yang dicita-citakan, Tamansiswa lalu membuat sebuah model pendidikan kurikulum yang kita tahu – memiliki corak tersendiri. Salah satunya yang khas Tamansiswa adalah sistem pendidikan yang selalu menekankan keberpihakan kepada rakyat dan apresiasi kesenian. Kesenian dipandang mampu menghaluskan jiwa. Kesenian dianggap mampu menumbuhkan rasa kebatinan suci. Halusnya budi, cerdasnya otak, sehatnya badan adalah tujuan pendidikan Tamansiswa. Ki Hadjar berpendapat sistem pendidikan yang terlalu berat kepada intelektualisme, kurang memperhatikan keluhuran budi nantinya akan mengakibatkan kegoncangan kemanusiaan dalam pertumbuhan masyarakat. Menurut Ki Hadjar, pendidikan itu dituntut untuk menghasilkan pertama, pengetahuan yang mencerdaskan pemikiran, kedua, pengetahuan yang mempunyai daya yang memperdalam dan memperhalus budi. Keduanya itu menurutnya tercakup dalam istilah Jawa; Sastra Gending. Pendidikan yang mengasah sekaligus nalar dan budi.

Foto murid-murid sekolah Tamansiswa (Sumber: www.stamaka.my.id)
Resapkan ulang tulisan-tulisan Ki Hadjar yang berbicara tentang pendidikan kesenian seperti: Olah Gending Minangka Panggulawentah (Gending Sebagai Pendidikan) di Majalah Wasita Jilid I no 1, Oktober 1928, Gunanya Wirama di Dalam Pendidikan dan Hidup Manusia di Majalah Keluarga Tahun ke 1 No 5 April 1937, Permainan, Tari dan Lagu di Dalam Pendidikan yang dipublikasi Majalah Keluarga Tahun ke II no 8, Agustus 1938, Kultur dan Kunst di Dalam Perguruan, Majalah Pusara, Agustus 1940, Jilid X No 8, Pendidikan dalam Sandiwara, Majalah Nasional 8/15 Desember 1951 Th II No.35/36 dan sebagainya. Di situ secara panjang lebar Ki Hadjar mengemukakan argumentasi-argumentasinya tentang kesenian dan kebudayaan.
Pengajaran tari dan olah gending maka dari itu dalam sistem pendidikan Tamansiswa dianggap memiliki kedudukan utama. Dengan latihan tari, nembang, belajar gamelan para siswa diharapkan akan mendapatkan rasa-wirama dan solah-bawa. Rasa wirama dalam Jawa adalah rasa atau kepekaan terhadap ritme. Kepekaan terhadap ritme menurut Ki Hadjar akan membuat seseorang berkemampuan untuk mengharmonikan hal yang satu dengan yang lain. Ki Hadjar sampai mengutip pendapat tokoh antroposofi Jerman, Rudolf Steiner yang juga memiliki pemikiran bahwa pelatihan kepekaan ritme sedari anak-anak akan banyak membuat kehidupan kita lebih baik. Rudolf Steiner sebagaimana dikatakan Ki Hadjar percaya bahwa orang-orang yang biasa hidup dengan wirama umumnya mereka berkarakter: teguh dan tahan, berani, sejuk jiwanya, tentram, sabar. maka dari itulah siswa di Tamansiswa dalam kelas atau luar kelas sehari-hari untuk bercerita, mendongeng, atau bermain-main dibiasakan dengan cara menyanyi atau berlagu. “Sekolah di Tamansiswa dulu antara kesenian dan pelajaran sehari-hari sangat membaur. Seolah tidak ada batasnya. Tari, gamelan, nembang, seni rupa sehari-hari dapat kita lihat di pendapa. Kesenian sudah menjadi atmosfer setiap waktu,” kata seorang alumnus Tamansiswa yang pernah sekolah tingkat SMP di Tamansiswa Yogja tahun 60 an.
Tentang pentingnya kesenian dalam kurikulum pendidikan Tamansiswa ini secara terang benderang pernah diuraikan Ki Hadjar dalam sebuah artikelnya berjudul: Dasar-dasar Umum dan Garis-garis Besar Pendidikan Kesenian di Taman Siswa yang dimuat di Majalah Pusara Juni-Juli Agustus, 1954, Jilid XVI, no 3/4/5. Artikel ini semula adalah pidato Ki Hadjar pada Permusyawaratan Pendidikan Kesenian Tamansiswa di Yogjakarta pada tanggal 14 Mei 1954. Demikian pentingnya pidato Ki Hadjar ini maka tak berlebihan bila tajuk ini ingin mengutip agak panjang pasasinya di bawah ini untuk Anda:
“…Saudara Ketua, kita memulai pendidikan kita dengan mengutamakan pelajaran kesenian, malah kalau saudara membaca tulisan di tangga pendapa ini sebagai tanda sengkala akan membaca: Ambuka Suwara Angesti Wiji (membuka suara, menembang, menyanyi, melakukan kesenian) sebagai pepucuk daripada angesti wiji (mendidik). Malah yang pertama kali sejak tahun 1922 (tahun kelahiran Tamansiswa-red) menarik perhatian, yaitu pemberian pengajaran permainan anak-anak dengan tembang dan pemberian pengajaran tembang kepada anak-anak, yang sebagai metode kita namakan metode sariswara. Jadi sariswara itu tidak hanya pelajaran menyanyikan nyanyian Jawa dengan angka, tetapi metodenya adalah memberi pengajaran yang pendek kata boleh disebut sastra gending, kepada anak-anak, dan ini berhubungan dengan uraian dari saudara Padmopuspito tentang adanya hubungan yang erat antara bahasa dan seni.
Memberi pelajaran bahasa tidak dengan seni boleh dikatakan hanya memajukan kekuatan berpikir, sedangkan kalau “sinawung resmining kidung” (berbentuk lagu) lalu hati kita terbuka. Bahwasanya tembang gending (sastera gending) di India misalnya sangat diutamakan Rabindranath Tagore, teranglah daripada ucapannya: “Kita memberi pengajaran bahasa kepada anak-anak tetapi kita menjauhkan mereka daripada keindahan bahasa.” Sehingga anak-anak tidak suka kepada bahasa, karena bahasa diberikan sebagai bahan pengajaran “pikiran”, tidak sebagai bahan pengajaran “seni”.
Jangan dikira bahwa kita hanya melihat Rabindranath Tagore. Jangan dikira pula tidak ada petunjuk-petunjuk mengenai hal itu dalam hidup kebudayaan kita sendiri. Petunjuk-petunjuk itu ada! Yaitu yang terkenal dalam pelajaran Sastra Gending dari Sultan Agung Mataram. Pendidikan sastra dang ending adala budi pekerti. adalah menjadi satu; itulah pendidikan intelek dan perasaan, dan karenanya merupakan pendidikan budi pekerti. Kalau sastra dan gending dipisahkan satu dengan yang lain, maka lalu tidak ada dayanya, tidak ada pengaruhnya. Tembang, sastra, gending oleh Sultan Agung dianggap sebagai sembahyang. Tidak ada perlunya sembahyang yang tidak meliputi sastra dan gending….”
Dan juga yang amat khas dari Tamansiswa adalah: tradisi kepamongan. Tamansiswa menumpukan hubungan guru dan murid dengan cara kepamongan. Seorang guru tidak bisa melepaskan dirinya dengan muridnya. Dia harus memberikan contoh-contoh yang menggugah intelektualitas dan sensibilitas estetis muridnya. Dia harus membimbing dan mengamati perkembangan jiwa muridnya tahap demi tahap. Tradisi relasi guru-murid yang sangat saling memperhatikan demikian sesungguhnya di Jawa berakar dari tradisi kebatinan. Ki Hadjar betapapun demikian tetap seorang yang terbuka. Ia membebaskan para pamongnya untuk memeluk afiliasi politik kebangsaan yang berbeda.
Bagi Ki Hadjar tak masalah para pamongnya ada yang berasal dari PSI, PNI, NU, Masyumi, bahkan saat itu PKI asal prinsip-prinsip Tamansiswa tetap menjadi panduan utama. Ki Hadjar sendiri luas diketahui sebagai seorang sosok yang menerjemahkan Mars kaum kiri yaitu Mars Internasionale. Ia akrab dengan kakaknya R.M Suryopranoto yang aktif menggalang pemogokan buruh-buruh di pabrik gula Yogja sehingga dijuluki pers Belanda sebagai Raja Mogok. Tapi ia pun aktif dalam dunia kebatinan. Ki Hadjar misal dikenal aktif dalam paguyuban Selasa Kliwon yang dipimpin spiritualis Ki Ageng Suryomentaram.
Tamansiswa tak syak dengan semangat paedagogik yang memberi perhatian pada dunia batin dan intelektualisme yang membumi semacam itu pada masa kolonial sampai masa awal-awal kemerdekaan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang penuh karisma, penuh martabat dan terhormat serta memberi pengaruh besar pada dunia pergerakan. Sayangnya pada masa Orde Baru kualitas demikian merosot. Memasuki pertarungan global dan abad digital ini Tamansiswa seolah tersingkir dari percaturan wacana pendidikan. Sistem pendidikan yang menjadi keunggulan Tamansiswa seperti kepamongan seolah tergagap-gagap menghadapi era digital. Adakah kualitas kualitas pamong pamong Tamansiswa di era digital ini mumpuni? Apa yang membuat sistem kependidikan kepamongan di Tamansiswa di era sekarang lebih istimewa daripada sistem kependidikan lainnya? Bukankah sitem kepamongan secara tidak langsung di masa kini juga diterapkan di boarding-boarding school berkelas yang dikelola banyak lembaga swasta internasional tanpa mengacu kepada model Tamansiswa dulu?
Adakah mutu kualitas kesenian di Tamansiswa masih ada? Mengapa Tamansiswa yang dulu dikenal melahirkan maestro-masestro seni rupa Indonesia seperti Sudjojono, Rusli, Basuki Resobowo dan sebagainya malah di masa sekarang sama sekali terlihat tidak terlibat aktif dan tak menyumbang apapun dalam dunia seni rupa kontemporer Indonesia? Di kala maraknya dunia seni rupa Indonesia dan begitu banyaknya pameran-pameran seni rupa kontemporer besar di Yogja muncul secara regular tiap tahun seperti Artjog, Tamansiswa hampir tidak terlihat memiliki perhatian sama sekali dan pasif . Tidak terlihat Tamansiswa memiliki progam-progam bersama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi seni seperti ISI (Institut seni Indonesia) Yogja, ISI (Institut Seni Indonesia) Solo, IKJ (Institut Kesenian Jakarta), prodi seni rupa ITB, jurusan desain interior Trisakti dan lain-lain.
Tidak terlihat juga Tamansiswa pernah mengelar pertunjukan-pertunjukan tari atau festival-festival koreografi yang bermutu atau mengadakan kolaborasi dengan koreografer-koreografer dan lembaga-lembaga festival tari ternama Indonesia seperti Sardono W Kusumo apalagi angkatan koreografer masa kini seperti Fitri Setyaningsih, Melati Suryodarmo, Eko Supriyanto, IDF (Indonesia Dance Festival) dan lain-lain. Tidak terlihat juga Tamansiswa pernah menggagas pementasan gamelan yang dahsyat, padahal komunitas-komunitas gamelan internasional sekarang banyak bermunculan di negara-negara bagian Amerika, Jepang, London, Australia, Selandia Baru dan sebagainya. Tidak pernah sekalipun Tamansiswa melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas gamelan di atas seperti kelompok Southbank Gamelan dari London Inggris, Komunitas Gamelan San Fransisco, Komunitas Gamelan Lambang Sari Tokyo dan lain sebagainya.
Adakah sekarang Tamansiswa memiliki relasi-relasi kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negri? Harap diingat Tamansiswa pernah memiliki hubungan baik dengan Rabindranath Tagore dan dr Maria Montessori, dua tokoh paedagogik yang memiliki visi-visi pendidikan yang memikat dunia. Keduanya mengritik gaya pendidikan barat yang terlalu menekankan kepada pencapaian intelek tapi mematikan perasaan. Tagore kita ketahui adalah sastrawan Bengali, yang mendapat hadiah nobel di tahun 1913 karena kumpulan puisinya Gitanjali yang menyerukan keindahan perdamaian. Sementara Montessori adalah seorang dokter dari Italia. Ia pindah dari Italia ke India karena saat itu Italia di bawah keditaturan fasime. Ia ia merasa tidak bisa mengembangkan metode pendidikannya di Italia sana dan kemudian itinggal di Pusat Perkumpulan Teosofi di Adhyar India.
Baik Tagore maupun Montessori, keduanya pernah mengunjungi Tamansiswa. Bahkan Tagore datang ke Tamansiswa hanya lima tahun setelah Tamansiswa didirikan tahun 1922 yaitu pada tahun 1927. Hal itu membuka mata pemerintah kolonial bahwa Tamansiswa sesungguhnya – istilah Ki Hadjar: “sekolah liar yang tidak buas.” Kunjungan Tagore ke Tamansiswa mampu menyebabkan terjadinya pertukaran siswa antara Shantiniketan, India – sekolah terkenal yang didirikan Rabindranath Tagore dan Tamansiswa. Ki Hadjar mengirim beberapa pamongnya untuk belajar di Shantiniketan di antaranya pelukis Rusli dan Rabindranath Tagore mengirim Miss Mrinalini, Swaminadan dan Shantidev Gose untuk tinggal di asrama Tamansiswa belajar batik dan tari.
Silakan baca tulisan-tulisan Ki Hadjar tentang Rabindranath Tagore atau Montessori seperti artikel: Hubungan Kita Dengan Tagore yang dimuat Majalah Pusara Agustus 1941 Jilid XI no:8, Tamansiswa dan Shantiniketan, di Majalah Kebudayaan, 16-6-1950 atau artikel: Metode Montessori , Frobel dan Taman Anak di majalah Wanita Jilid I no I Oktober 1928. Di situ dapat diraba bagaimana Ki Hadjar senantiasa memantau perkembangan pemikiran-pemikiran alternatif dari dunia. Ki Hadjar dan Tamansiswa tidak kuper dari ide-ide global pendidikan. Tamansiswa bahkan berupaya mengolah banyak pemikiran dunia itu untuk disesuaikan dengan misi Tamansiswa. Dulu Ki Hadjar sampai tertarik mempelajari sistem pendidikan di negara-negara Skandinavia. Mengapa pendidikan di negara-negara Skandinavia sangat berkualitas tinggi (sampai sekarang sistem pendidikan di negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Denmark, Swedia masih tetap dianggap sangat berkualitas) ? Ki Hadjar sampai mengirim seorang pamong Tamansiswa ke Swedia untuk mengamati pendidikan di sana. Hal-hal seperti demikian juga tidak dilanjutkan sekarang di Tamansiswa.
Banyak yang melihat Tamansiswa mengalami kemunduran intelektualitas karena energinya pernah terserap ke perpecahan internal. Adalah kenyataan sejak berdirinya Tamansiswa, keluarga besar Tamansiswa Pamong terdiri baik dari pamong-pamong kiri dan non kiri. Semuanya ditampung oleh Ki Hadjar. Baik pamong-pamong non kiri dan kiri sesungguhnya sangat memberikan sumbangan intelektualitas berharga kepada Tamansiswa. Tatkala Ki Hadjar masih hidup ketegangan-ketegangan antara pamong kiri dan non kiri dapat diredam semuanya kompak dan harmoni. Namun selepas Ki Hadjar wafat di tahun 1959 mulailah muncul konflik yang tajam antara pamong kiri dan non kiri. Puncaknya adalah tragedi 1965 yang mengakibatkan penyingkiran besar-besaran para pamong Tamansiswa yang ditenggarai kekiri-kirian. Hampir lebih lima puluh persen para pamong tamansiswa yang terkategori kiri dibersihkan, ditangkap, dipenjara, dibunuh.
Sungguh sebuah tragedi luar biasa. Persoalannya selama Orde baru, mereka yang mewarisi tampuk kepemimpinan Tamanisiswa – setelah malapetaka itu terjadi nampak tidak bisa mengembangkan lebih jauh Tamansiswa. Seorang pengamat Tamansiswa mengatakan, setelah Orde Baru, Tamansiswa tidak mampu melepaskan diri dari ketakutan-ketakutan, Tamansiswa lebih banyak tiarap, kompromis dan tidak lagi memiliki pendirian. Akibatnya Tamansiswa seolah berjalan di tempat tak mampu memajukan diri. Di zaman Orde Baru tersebut, Tamansiswa yang semula cemerlang kemudian menjadi sebuah lembaga yang konservatif. Majelis Luhur Tamansiswa tidak lagi menghasilkan pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran ekonomi dan kebudayaan yang orisinil. Suara Tamansiswa juga jarang terdengar menanggapi kemelut pendidikan di tanah air. Tidak ada buah buah pikiran dan gebrakan-gebrakan apapun dari Tamansiswa.
Kini 100 tahun sudah Tamansiswa. Tentu saja Tamansiswa belum habis. Salah apabila menyebut Tamansiswa sudah memasuki senjakala atau tamat. Tidak. Tamansiswa bukan sebuah artefak. Dikemukakan oleh Ketua Majelis Luhur Prof Edi Swasono bahwa meski cabang-cabang Tamansiwa di segala penjuru nusantara jumlahnya merosot tapi tetap ada harapan. Belakangan ini misalnya baru saja didirikan sekolah Tamansiswa di Morotai. Tamansiswa kembali menjangkau daerah-daerah terpencil nusantara. Meski di banyak daerah, bangunan-bangunan sekolah Tamansiswa terlihat agak kumuh, kusam dibanding sekolah-sekolah swasta lainnya hingga seolah kehilangan kepercayaan diri dan minder tetapi di Yogya kini, Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa memiliki gedung baru dan memiliki mahasiswa sekitar sepuluh ribu. Rektor Tamansiswa Prof Pardimin Phd-seorang guru besar matematika optimis bahwa Tamansiswa bisa berkembang dan tak tergilas. Ki Pardimin bahkan ingin membuka Fakutas Kedokteran di universitasnya.
Dalam diri Tamansiswa sesungguhnya terlihat masih tersimpan potensi yang menggelegak meski magma itu masih belum mendidih dan belum keluar. Siapapun yang melihat acara Aubade (paduan suara) para alumni Tamansiswa di Titik Nol Yogya (perempatan Malioboro di depan Bank-Indonesia dan Museum Vredeburg) pada hari perigatan 100 tahun Tamansiswa akan merinding. Acara itu walau sederhana demikian menggugah. Para alumni bersama-sama menyanyikan lagu-lagu Tamansiswa memperlihatkan rasa cintanya yang besar terhadap sejarah Tamansiswa. Di tengah koor, tia-tiba Yuli, istri almarhum penari Miroto – yang juga alumnus Tamansiswa menari bersama putrinya. Itu sangat mengharukan.

Foto acara Aubade (paduan suara) para alumni Tamansiswa di di Titik Nol Yogya pada hari peringatan 100 tahun Tamansiswa (Sumber: Arsip BWCF)

Tampak Yuli (tengah), istri almarhum penari Miroto – yang juga alumnus Tamansiswa (Sumber: Arsip BWCF)
Kesadaran para alumni Tamansiswa masih terasa mengetarkan. Semoga hal tersebut menunjukkan bahwa semangat untuk mengembangkan dan mengembalikan lagi Tamansiswa menjadi perguruan kerakyatan yang bergigi masih terus menyala. 100 tahun Tamansiswa yang jatuh pada bukan Juli tahun ini agaknya bisa menjadi momentum untuk kebangkitan Tamansiswa. Majelis Luhur harus meakukan perubahan diri agar kembali Tamansiswa memiliki terobosan-terobosan kebudayaan. Majelis Luhur Tamansiswa harus membuktikan bahwa Tamansiswa bukan sebuah perguruan nostalgia. Tapi harus mampu ikut ambil bagian dalam isyu-isyu kebudayaan dan kesenian kontemporer. Jangan sampai misalnya orang melihat bahwa ide-ide kemajuan dan nilai-nilai pendidikan kerakyatan dan kemandirian yang pernah dimiliki Tamansiswa sesunguhnya di masa sekarang ini lebih bisa dimanifestasikan negara lain misalnya Cina. Taman siswa, Quo vadis?
BWCF-2022













