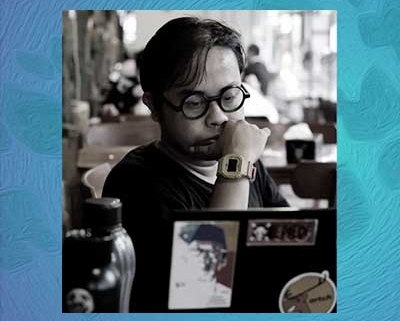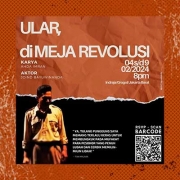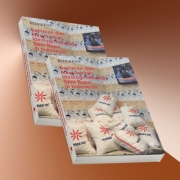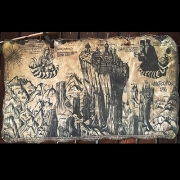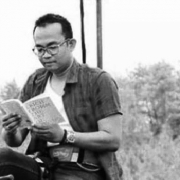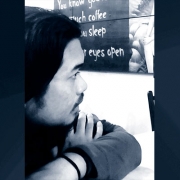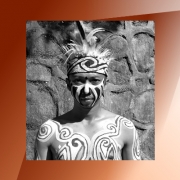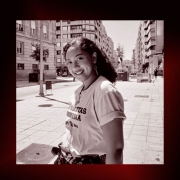Perempuan dan Estetika Perjuangan: Membaca Feminisme dalam Kritik Seni dan Teater Tubuh
Oleh Galang Mario*
Tubuh perempuan, sepanjang sejarah, tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Tubuhnya kerap dijadikan kanvas untuk citra, objek dalam sistem nilai, simbol dalam narasi budaya, dan pusat tarik ulur kuasa yang tak berkesudahan. Dalam dunia seni, tubuh perempuan bahkan sering kali tampil tanpa suara: diposisikan sebagai indah, namun diam; menggoda, namun tak berdaya. Tapi kini, kita menyaksikan sesuatu yang berbeda. Dari panggung-panggung teater kecil hingga forum akademik, tubuh-tubuh itu mulai bicara, menolak dan merespons. Ia menulis dirinya sendiri bukan dalam bahasa laki-laki, melainkan dalam tulisan yang lahir dari luka, gairah, dan keberanian untuk menggugat.
Feminisme dan Nilai Estetis
Perjalanan Estetika klasik dalam buku sejarah estetika martin suryajaya (2016), wacana keindahan nyaris selalu disuarakan oleh laki-laki dan sering kali keindahan dianggap netral. Namun netralitas tersebut menipu, bagi Carolyn Korsmeyer dalam Gender and Aesthetics (2004) menyatakan bahwa wacana estetika tidak pernah bebas gender, bahwa konsep estetis justru lahir dari sensibilitas maskulin yang penuh dengan simbol secara implisit memposisikan perempuan sebagai hal lain, misalnya keindahan digambarkan sebagai karakteristik yang dilekatkan pada sosok perempuan yang lembut, mungil, menyenangkan bahkan pasif. Dalam wacana estetika barat, Keindahan itu menunjukkan bahwa kategori estetis seperti indah, halus, atau agung lahir dari struktur sosial patriarki yang melekatkan sifat-sifat feminin pada keindahan dan sifat maskulin pada kekuasaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Edmund Burke dalam bukunya A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, misalnya, dalam membedakan antara keindahan (beauty) dan kesubliman (sublime), ia mengasosiasikan keindahan menjadi representasi kelembutan feminin, sedangkan kesubliman mewakili kekuatan maskulin. Tak heran bila perempuan dalam seni klasik hadir hanya sebagai objek untuk dipandang, bukan sebagai subjek yang menciptakan makna.
Kritik tajam-pun datang dari pakar teori film feminis inggris, Laura Mulvey dalam artikelnya Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) melalui konsep Male Gaze-nya menyatakan bahwa sinema menjadikan tubuh perempuan sebagai objek erotis dan estetis bagi laki-laki. Jelas bahwa memicu tatapan laki-laki dalam film atau kesenian yang memposisikan perempuan sebagai objek kenikmatan visual. Menurutnya, kenikmatan estetis bersumber dari voyeurism, menikmati sesuatu secara diam-diam tanpa terlihat. Pola ini terus berulang dalam sejarah estetika, di mana penilaian karya seni dianggap objektif, padahal menyembunyikan bias maskulin di balik klaim universal. Akibatnya, perempuan mengalami tiga tingkat objektifikasi yakni sebagai objek dalam tatanan sosial-politik, sebagai objek dalam karya seni, dan sebagai objek dalam refleksi estetis atas karya tersebut. Ia menjadi “objek dari objek” yang terperangkap dalam lapisan ganda penyingkiran (Suryajaya, 2016). Kita mengira sedang menikmati seni, padahal sebenarnya tengah menyaksikan representasi kekuasaan. Tubuh perempuan di layar atau panggung menjadi milik mata laki-laki; ia tampil untuk dilihat, bukan untuk melihat. Namun gerakan feminis tidak tinggal diam. Mereka mulai mengintervensi ruang-ruang ini, bukan dengan menciptakan estetika tandingan, melainkan dengan mendobrak batas-batasnya. Patut menjadi perhatian pada sisi lain bahwa setiap sisi kehidupan bisa menjadi inspirasi, dan Perempuan adalah salah satu yang paling Istimewa, dari dirinya lahir banyak karya sastra legendaris denan kisah tak pernah habis untuk diceritakan. Perjalanan hidupnya penuh tantangan dari penjarian jati diri, mencintai dan dicintai, hingga luka, air mata, dan kebahagiaan yang semuanya menjadi sumber yang memikat.
Perempuan Dalam Teks dan Teater
Menolak objektifitas pada Perempuan, para estetikawan feminis salah satunya dari Hélène Cixous yang menyerukan pentingnya écriture féminine atau tulisan feminim, cara menulis yang berasal dari tubuh, dari pengalaman perempuan yang tidak terwakili oleh bahasa logosentris laki-laki atau logika patriarki. Dalam esainya Le Rire de la Méduse (1975), Cixous menolak bahwa tulisan bersifat netral, baginya netralitas merupakan ilusi patriarkis yang menyamar sebagai universalitas. Selain itu juga menolak klaim semua tulisan sudah feminim atau sebaliknya. Baginya tulisan feminim merupakan Tindakan politik, sebuah praktik penolakan akan kurungan dalam kategori sebab Perempuan itu singular, unik dan tak tereduksi. Dalam hal ini ia menegaskan bahwa struktur bahasa feminim dan menyerukan agar perempuan menulis dirinya sendiri, bukan untuk dikodifikasi, tapi untuk didengar dan dirasakan.
Tubuh Perempuan dan seksualitasnya tidak lagi ditentukan oleh doktrin luar, melainkan oleh pengalaman dari dalam, seperti yang dalam karya novel Perempuan di titik nol oleh Nawal el-Saadawi dan Eve Ensler dengan vagina monolognya, menyuarakan perlawanan terhadap patriarki dengan cara yang kerap dianggap kontroversial. Namun, pilihan-pilihan itu menampilkan realitas yang tak bisa diabaikan. Teater pun mengambil peran penting dalam membuka kesadaran publik menjadi medium untuk memahami luka dan ketimpangan yang dialami perempuan dalam sistem yang menindas.
Hubungan antara perempuan dan teater bukan sekadar artistik, melainkan simbiosis eksistensial yang merekam penderitaan sekaligus merawat perlawanan. Disana perempuan menulis tubuhnya sendiri. Tulisan feminin tak sekadar hadir dalam teks, tapi juga menjelma di atas panggung. Dalam teater tubuh kontemporer, tubuh perempuan menjadi ruang perlawanan. Ia bukan lagi objek tontonan, melainkan subjek yang bersaksi. Tubuh-tubuh yang menari, berteriak, bahkan menggeliat tak karuan yang semuanya menjadi bahasa yang melampaui kata.
Teater, dalam konteks ini, bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang politik tempat tubuh bersuara. Seperti yang dikatakan Julia Kristeva “RLE Feminist Theory” dalam buku John lechte (1990), tubuh adalah ruang semiotika yang penting, tidak hanya sebagai entitas biologis tetapi sebagai tempat terjadi proses penandaan dan pembentukan subjek yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan bahasa. Dalam hal ini, tubuh sebagai ruang semiotik yang mampu mengacaukan struktur dominan dan memunculkan kekuatan yang bersumber dari luar tatanan simbolik. Contoh-contoh praksis ini bisa kita lihat dalam karya-karya teater seperti milik Marina Abramović, yang mengeksplorasi batas tubuh dan penderitaan, menggunakan tubuh sebagai media seni yang berfokus pada eksplorasi batas-batas fisik dan emosional serta interaksi dengan penonton pada karya “rhythm 0” yang cukup terkenal, atau dalam pertunjukan-pertunjukan teater perempuan indonesia seperti karya ratna riantiarno, happy salma atau djenar maesa ayu dan lain sebagainya yang menggunakan tubuh sebagai ekspresi dalam mengangkat isu-isu sosial, dimana bahasa tubuh kerap menjadi medium utama dalam menyampaikan pesan. Mereka menghadirkan tubuh perempuan bukan hanya sebagai tubuh yang sempurna atau molek, tapi juga menghadirkan tubuh yang retak, penuh luka, dan tetap hidup.
Estetika dalam kerangka ini bukan lagi soal keindahan yang terbingkai rapi. Ia adalah estetika luka, estetika kegelisahan, estetika tubuh yang tak ingin ditertibkan. Ini bukan tentang menciptakan definisi baru tentang perempuan, tapi tentang membuka ruang agar setiap perempuan bisa bicara dari tubuhnya sendiri. Seperti tulis Susan Sontag, “The camera makes everyone a tourist in other people’s reality, and eventually in one’s own” Kini, perempuan tak lagi jadi lanskap untuk ditonton. Ia menjadi penggagas realitasnya sendiri. Tubuh perempuan bukan hanya titik awal perlawanan, tapi juga peta yang merekam sejarah penghapusan dan keberanian. Di dalamnya ada ingatan akan penjajahan, penghilangan, kekerasan, namun juga ketangguhan dan gairah hidup. Dan ketika tubuh itu menulis, entah lewat pena, panggung, atau performa, maka ia sedang menciptakan dunia baru. Dunia di mana estetika bukan lagi milik patriarki, tapi milik semua yang berani berkata: “Ini tubuhku, ini suaraku. Dengarkan!”
Feminisme dan Spirit Keadilan
Saat ini, di banyak ruang dari kampus hingga komunitas akar rumput, dari panggung parlemen hingga media sosial kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi bagian dari diskursus publik. isu-isu feminisme kerap hadir sebagai suara yang membicarakan keadilan. Keadilan tak dapat dipisahkan dengan feminisme sebab feminisme adalah keadilan. Bagi Rocky Gerung pada Jurnal Perempuan (2016) menegaskan dalam pandangannya dari segi teoritis, feminisme melampaui seluruh teori sosial tentang keadilan sekaligus kemampuannya membongkar sistem bahasa yang kemudian menghasilkan bahasa baru.
Identitas Perempuan berhubungan dengan cara dia mengucapkan bahasanya, bahasa yang datang dari pengalaman keadilan, ketimbang bahasa laki-laki yang selalu logis, terstuktur dan koheren. Bahasa laki-laki tentang etika hak (ethic of right) sedangkan bahasa Perempuan etika tentang kepedulian (ethic of care). Distingsi itu jelas, dimana Jika seorang laki-laki mengalami ketidakadilan, mungkin hanya mengalami kemalangan (misfortune) sedangkan bagi Perempuan, ketidakadilan merupakan penderitaan, sebuah konsep yang tidak mungkin dipahami laki-laki. Penderitaan laki-laki yakni karena kekurangan hak sedangkan penderitaan Perempuan merupakan kulminasi dari semua jenis penderitaan termasuk penderitaan terhadap harapan akan masa depan. Namun masyarakat yang patriarki terkadang menganggap seolah feminisme adalah ancaman terhadap laki-laki, padahal hendak dilakukan feminisme yakni mengatur ulang relasi, bukan menjadikannya unggul bagai ratu, sebuah keprihatinan dimana laki-lakipun mungkin merasakan beban psikis akan obsesi, jika terus dalam posisi selalu kuat, berpikir rasional, menahan emosi, dan menjaga tubuhnya agar tetap kekar. Justru dengan etika feminisme tersebut menjadi cara baru.
Perempuan kini tidak hanya hadir sebagai simbol, tapi sebagai pelaku perubahan: memimpin organisasi, menggugat kebijakan diskriminatif, menciptakan ruang aman bagi sesama, dan menyusun narasi baru tentang siapa diri mereka. Namun pencapaian ini bukan tanda bahwa perjuangan telah usai. Di balik angka statistik partisipasi dan representasi, masih mengintai ketimpangan upah, kekerasan berbasis gender, dan standar ganda yang membebani tubuh dan moralitas perempuan. Justru karena itu, seni dan teater tubuh menjadi semakin penting sebagai ruang dimana kesadaran politik bisa menjelma menjadi pengalaman afektif; sebagai pengingat bahwa tubuh perempuan bukan hanya medan tempur, tetapi juga rumah bagi kemerdekaan yang terus diperjuangkan, dan Perempuan adalah citra keadilan tertinggi.
Ad Maiora Nastus Sum!
—-