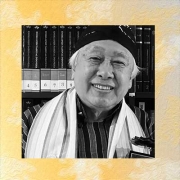Matinya Sang Komponis
Oleh Joko S Gombloh
Seorang teman dosen periklanan di universitas terkemuka di Surakarta bilang, mahasiswa sekarang semakin canggih dalam menyelesaikan Adwork media. Penguasaanya pada media digital mengatasi hampir setiap renik proses produksi iklan yang dibuatnya. Tak terkecuali untuk scoring musik—satu keahlian yang mensyaratkan talenta musikal yang yahud. Mahasiswa periklanan itu tak perlu repot mencari komposer untuk membuat jingle, bumper, sound track atau theme song sebagai pengisi musik iklannya. Semua dibikin sendiri. Ia tidak minder dengan mahasiswa jurusan musik dari kampus seni yang bertetangga dengan kampusnya. Penting baginya adalah musiknya sesuai dengan mood iklan yang diproduksi. Tidak perlu benar salah atau baik buruk. Benar atau salah, katanya, hanya berlaku bagi mahasiswa jurusan musik—yang dikerangkeng oleh kurikulum berisi manifesto dan aturan estetika yang ketat.
Ketika diintip, ternyata mahasiswa periklanan tersebut cerdik memanfaatkan Soundraw, sebuah aplikasi Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkannya untuk berpetualang membuat musik sendiri. Aplikasi ini mempersilakan pengguna secara leluasa memilih bentuk, struktur, durasi, tema musik, suasana hati, bahkan juga gaya dari pemusik idolanya. Soundraw jelas tidak akan mempertanyakan latar belakang pengetahuan kompositorik pengguna. Ia hanya membutuhkan perintah dan bekal data yang dimilikinya. Dan, sim salabim, dalam sekejap, mahasiswa tadi langsung mendapatkan soundtrack yang memikat. Nada-nada yang disuguhkan tepat sebagaimana yang diinginkan dan sesuai dengan film atau video iklan yang dibuat. Lagi, si mahasiswa tak usah khawatir dengan masalah hak cipta dari situs web seperti YouTube!
Isu paling kontroversial dari fenomena di atas adalah matinya otoritas komponis dan digantikan oleh mesin yang mampu membuat musik dengan kualitas dan kompleksitas yang boleh jadi melampaui hasil karya manusia. Ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang masa depan musik, rezim dan manifesto estetika ke depan. Sebuah wacana musik post-human yang semuanya menyentuh inti dari apa arti menjadi manusia dalam konteks penciptaan artistik musik.
Gairah Rezim-rezim Keindahan
Sebelum segalanya serba dimudahkan oleh AI, musik diatur oleh berbagai konvensi, aliran, dan manifesto-manifesto keindahaan. Dimulai dengan “Concert Pitch”—satu aturan standar penalaan frekuensi bunyi yang menjadi referensi baku untuk menyetem alat musik bernada. Aturan yang ditetapkan dalam konvensi music di Wina, Austria, 16 dan 19 November 1885, ini menyatakan nada A (yang disetel pada frekuensi 440 Hz) sebagai standar yang digunakan dalam orkestra dan ensambel musik lainnya. Lalu, Erich Moritz von Hornbostel dan Curt Sachs mengusulkan sistem klasifikasi untuk instrumen musik berdasarkan cara memainkannya. Cara ini dikenal dengan Sachs-Hornbostel Classification. Instrumen musik yang diklasifikasikan disetem sesuai standar concert pitch. Keduanya, Sachs-Hornbostel dan concert pitch, menjadi entitas yang menyatu untuk memulai standar musik Barat dan diakui Masyarakat sedunia. Setelahnya, muncul beragam aturan lainnya seperti harmoni, bentuk, hingga struktur komposisi musik. Ini semua tonggak di mana estetika musik memasuki sebuah rezim yang mengatur secara rigid penggunaan elemen-elemen kompositorik. Melanggarnya berarti dosa besar, fals, bahkan dianggap bukan musik!
Aturan-aturan itu membangun asumsi dasar bahwa musik adalah ekspresi kecerdasan pengetahuan, emosi, budaya, dan pengalaman manusia yang mendalam. Sachs-Hornbostel membuat dinamika music di dunia semakin mengarah pada rezim estetika yang literal, formal, baku, dan hegemonik. Tradisi tulis dalam musik memperkokoh rezim yang mengonstruksi pengertian bahwa musik adalah keindahan yang agung, megah, kompleks, dan dalam. Di sini kecerdasan intelektual, keterampilan, pengalaman dan emosi yang lekat pada tubuh komponis adalah elan vital penciptaan musik.
Kecerdasan itu juga mendorong para komponis untuk tampil dengan gagasan-gasan musikal yang otonom dan kritis dalam menentukan visi estetis dan orientasi artistiknya. Mereka mulai menggoyang kemapanan konvensi yang diwajibkan oleh entitas Sachs-Hornbostel di atas. Mendobrak otoritas lama dengan menawarkan berbagai konsep atau bentuk-bentuk ekspresi yang sangat personal. Mereka berlomba menunjukkan geniusitasnya dalam berkarya. Tubuh musikal komponis bukan lagi sekadar terampil dalam berolah teknik, namun juga dalam membangun konsep yang semakin menyala.
Pada tahun 1950an, misalnya, muncul aliran ekspresionisme—dengan tokoh utama Arnold Schönberg dan Igor Stravinsky—yang menolak tonalitas nada dan suka sekali memainkan ritme-ritme tak beraturan. Lalu, Karlheinz Stochausen, bereksperimen dengan teknologi elektro-akustik yang mendasarkan pada “rumus” dan “meditasi”. Pemakaian rumus merupakan turunan dari aliran serialisme yang mendasarkan pada keteraturan karya yang bersifat matematis. Temuan elektro-akustik Stockhausen menandai perkembangan teknologi elektronik mulai digunakan untuk eksplorasi musik.
Musik dalam tataran konseptual kian riuh. Komponis mengendalikan bukan lagi dalam eksplorasi teknis seorang virtuoso, tapi pada perspektif yang mengintegrasikan nilai-nilai “Extraordinary” ke dalam bangunan musiknya. Terutama nilai-nilai filsafat Timur dan konteks sosial yang luas. Sebutlah Oliver Messiaen yang melahirkan ‘mantra’ musik yang melampaui dimensi formalisme. Musik Messiaen bergerak dalam pola-pola ekstrim, gairah religius, serta surialisme yang aneh. Ia juga dikenal dengan konsep “melodi burung”. Messiaen bilang, “The birds are the opposite of time. They represent our longing for light, for stars, for rainbows, and for jubilant song.”
Messiaen juga memperkenalkan “ritme aditif” kompleksitas Tala yang menyesap ke dalam dari India. Tala adalah konsep irama dari India yang berkarakter “personages rythmique” atau “individu-individu ritmis”, yaitu suatu ritme dengan himpunan berbagai motif dasar yang memiliki suatu identitas tersendiri. Struktur ritmis dan metriknya berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi tergabungkan. Messiaen mengambil motivasi, kekuatan, dan kesadaran religious Tala dengan sangat mendalam. Murid-murid Messiaen seperti Stochausen dan Pierre Baulez adalah para genius yang senang sekali mengenalkan hal-hal yang belum ada di dunia musik.
Musik para genius tersebut menunjukkan bahwa kekuatan musik ada pada bagaimana komponis membangun konsep dan gagasan musikal yang kadang melampaui teknis permainan. Seperti John Cage yang menjadikan Zen Budhism untuk musik 4:33’. Komposisi yang populer disebut “The Silent Music” ini selalu menjadi bahan diskusi di kelas-kelas musik sampai hari ini. Cage menawarkan fase baru dengan kredonya yang absurd: “Diam adalah akar bunyi. Bunyi dibiarkan pada bunyi itu sendiri. Para pendengar sendiri yang dapat menyelesaikan karyanya.” Cage menambah gempita aliran yang lahir kemudian, yaitu Fluxus, Concept Art, Mixed Media, Happening, dan Musik Minimalis yang secara umum dilandasi oleh pengaruh musik-musik tradisional India, Jepang, Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, serta Afrika. Aliran-aliran musik seperti ini, kata musikolog Dieter Mack, tidak berorientasi ke suatu gaya musik tertentu, melainkan suatu sikap atau cara komposisi. Satu upaya untuk mengobjektifir musik. Komposer merumuskan berbagai tindakan, proses, atau aturan yang harus dilakukan oleh pemusik.
Fenomena di atas merupakan gejala umum avant gardism yang beberapa kredonya masih dipakai para komponis saat ini. Hingga muncul bentuk-bentuk musik yang tercipta dari kemajuan mesin, yaitu Musik Elektronik. Ialah musik yang tak terelak dari imbas serbuan perangkat teknologi listrik ke dalam dunia musik. Gejala utamanya ditandai oleh perkembangan musik pop pada tahun 1960an yang semakin massif dan diasporanya mendunia. Para komponis musik elektronik lebih banyak bekerja di studio, melakukan eksperimen menggunakan alat-alat alektronik. Beberapa studio musik seperti Columbia Princeton Electronic Musik Center, Cooperative Studio for Electronic Musik, San Fransisco Tape Musik Center atau Bell Telephone Laboratories-nya Max Mathes adalah ruang laboratoriumnya.
Beberapa komponis juga menciptakan alat musik baru berkekuatan listrik, misalnya Buchla Synthesizer dan Robert Moog. Selain Stochausen yang menjadi pionir musik ini, tokoh-tokoh penting lainya yang penting disebut adalah Luc Ferrari, Iannis Xenaxix, juga Franco Evangelesti. Dari kalangan musik pop muncul Keith Noel Emerson (ELP), Richard Christopher Wakeman (Yes), atau John Douglas Lord (Deep Purple) yang mengembangkan musik elektronik dalam bingkai rock progresif. Campur tangan perangkat elektronis mulai dipertanyakan dalam penciptaan musik ini.
“Ternyata semakin mesin menjadi suatu ‘organisme’ tersendiri, semakin manusia menjadi tidak penting.” Demikian disampaikan oleh ahli musik dari Jerman, Fred K. Prieberg. Kritik ini jelas ditujukan untuk bentuk-bentuk musik yang terlahir dari kemajuan teknologi mesin. Terutama untuk para pemuja teknologi yang sampai mengombang-ambingkan aspek estetika dan hakekat karya komposisi.
Musik pascamanusia
Lebih dari apa yang disampaikan oleh Prieberg, munculnya kecerdasan buatan di dalam musik, semakin mengerdilkan manusia bukan saja menjadi tidak penting, tapi malah meniadakannya. Kecerdasan buatan memamerkan cara baru menggubah musik dengan mengandalkan algoritma yang dapat menganalisis dan mempelajari pola dari ribuan karya musik yang sudah ada untuk kemudian dijadikan sebagai bahan atau data produksi komposisi musik. Alih fungsi dan peran ini mengubur cara tradisional tentang kreativitas sebagai aktivitas yang eksklusif bagi manusia.
Soundraw yang dipakai oleh mahasiswa periklanan tadi pun ternyata tidak sendirian. Sebutlah yang lain misalnya MuseNet dan Magenta Studio. Keduanya tangkas memamerkan kecangihannya dalam menghasilkan komposisi musik yang kompleks, melintasi genre dan dapat meniru gaya pesohor musik yang diidolakan banyak orang. Aplikasi lainnya, AIVA (Artifical Intelligence Virtual Artist), memungkinkan siapapun dapat membuat soundtrack untuk iklan, video game, video, film, dan produksi media lainnya. Perangkat lunak yang dikembangkan pada tahun 2016 ini juga dapat mencipta musik dengan gaya prasetel yang tersedia atau dengan pengaruh dari artis musik lain. Atau, Soundful yang bukan hanya membantu membuatkan musik yang unik dan gratis, melainkan juga menyediakan fitur untuk mengatasi blok kreatif pengguna agar terhindar dari masalah hak cipta. Yang cukup intuitif adalah Ecrett Music. Ini sedikit lebih manusiawi lantaran basis kreatifnya menggunakan metode pembelajaran berjenjang, mulai dari pemula, menengah, hingga yang cukup mahir teori musik. Sentuhan ‘tangan manusia’ masih cukup berasa pada Ecrett Music.
Masih banyak aplikasi yang lain dan akan lahir aplikasi-aplikasi AI berikutnya ketika revolusi media digital seperti saat ini. Tantangan bagi para komponis adalah bagaimana mereka mampu menangkap dan beradaptasi dengan realitas baru ini. Apakah bentuk-bentuk estetika musik perlu diperluas untuk memasukkan karya yang diciptakan oleh entitas non-manusia? Atau, apakah secara naif mempertahankan argumen bahwa musik sejati hanya bisa diciptakan oleh manusia, bukan oleh AI yang tidak memiliki pengalaman dan emosi seperti manusia? Untuk pertanyaan yang terakhir ini, siapa punya kuasa untuk membendung karya-karya berbasis teknologi tinggi?
Hilangnya peran manusia adalah hilangnya emosi, mood, dan keunikan yang menyesap dalam sebuah karya. Ini tidak seperti tesis “The death of the author” yang disimpulkan oleh postrukturalis Jacques Derrida. Bukan! The death of the author adalah hilangnya otoritas nilai atau arti sebuah karya dari pengkaryanya, lantaran otoritas tersebut diambil alih oleh pembaca atau audiens. Sedangkan pada kasus music AI adalah “The death of the composer” di mana otoritas kemanusiaan (human) sang komponis yang manjing di dalam karya, diambil alih oleh mesin berteknologi super canggih. Mesin mengungguli kecerdasan dan virtuositas sang komponis. AI mengambil alih hasil kreatif manusia (human cteativity) ke dalam sistem kerja robotik.
Perlu ditegaskan ulang bahwa AI tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga membuka peluang bagi para amatir yang tidak memiliki latar belakang musik untuk terlibat dalam penggubahan. Meskipun kecanggihan AI hanya berbekal pola dan data yang dimilikinya—sehingga menghasilkan musik yang monoton, banal, kurang bervariasi, cenderung mengulang, hilang kekayaan dan keberagamannya—tapi jangan lupa, aplikasi ini senantiasa bergerak melesat untuk memastikan bahwa data-data selalu ter-update. Data-data baru ini yang akan memperkaya dan memperluas templete atau fitur-fiturnya.
Di sisi lain, penggunaan AI memiliki implikasi besar bagi industri musik, yaitu mengubah model bisnis menjadi kacangan, lantaran ongkos produksi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang konvensional. Tidak ada lagi label besar yang hegemonik. Tidak pula Glodok yang tempo dulu adalah “pusat” industri musik. Kini, setiap individu adalah produser. Surplus produksi musik, dapat mengarah pada penurunan upah dan kesempatan kerja dalam industrinya. Sungguh perayaan kemerdekaan kreativitas yang jauh dari kuasa rezim estetika, betapun ada getir dan pincang di dalamnya.
Ini dilema yang rumit. Dunia musik berada di ambang perubahan besar dalam cara memandang dan menilai estetika. Simpul yang bisa ditawarkan dari fenomena ini adalah peran manusia beralih dari pencipta menjadi kurator atau bahkan penonton pasif. Dulu Schönberg menganalogikan komponis itu pencuri yang genius. Adagium itu kini senyap, disergap oleh bilangan kata, “Komponis adalah amatir yang berpasrah pada kekuatan robotik.” Tabik!
—-
*Joko S Gombloh. Pengamat Musik