Puisi-Puisi DG Kumarsana
MENGUNJUNGI LUBDHAKA
Malam ini tepat di angka bumi yang tak berencana untuk mengikat bencana, aku datang mengunjungi lubdhaka..Tempat tinggal tepi sungai yang mati tanpa atap dan jendela.. hawa alam yang mendesir seperti berada di tengah bilik dengan pendingin yang selalu memanjakan setiap celah tubuh – terkadang rakus melahap kenikmatan. Segala yang memberi rasa serta keinginan tak habis. Memasuki halaman depan berlapis penjaga yang entah kukenal wajahnya, sebagian kabur dalam penglihatan, selebihnya pada beringas menatap kedatanganku. Salam persahabatan, aku mau mencari sorga disini, sapaku dengan sopan. Sang monobrata yang berada di pekarangan paling luar menatap dengan wajah tandus – seakan meneliti seukujur ingatanku. Mengurai segala bentuk tubuhku serta mengamati bagian terdalam seakan menyelam ke dalam setiap bagian pencernaan. Tangannya merogoh lambungku yang kenyal – entah kuburan yang keberapa ada di dalamnya, entah berapa nama tertulis di nisan. Beberapa nama binatang dan tumbuhan mulai mengeras- bisa pula manusia.
Oh, Ciwa.
Lambung tak pernah berasa dalam genggaman tangannya. Seandai tak rakus aku melahap semua, tentu saja barisan pertama di bagian luar pekarangan itu mampu aku lewati. Sang Monobrata telah menyatakan lambungku tidak lolos sensor – suatu pancaran keramahan mengalir di matanya memancarkan penolakan yang halus. Seandainya sekalipun sang Monobrrata mampu aku llewati, apa mungkin aku dipersiapkan untuk bercakap-cakap dengan sang upawasa maupun sang Jagra. Oh, tubuh dan ingatan melemah, tak mampu mempertahankan waktu atau menahan segala keinginan. Entah seandainya dapat aku lakukan langkah negosiasi bertemu langsung dengan sang jagra bertemankan untuk mempertahankan malam dalam setiap energi yang bakal ditularkan. Sang Monobrata tak beri aku lisensi dalam perjalanan berikutnya, apakah akan diijinkan singgah sejenak untuk bercakap tentang kebenaran? Dengan terbahak sang monobrata memamerkan lambungku yang terbuat dari kuburan. Aku tertunduk. Barangkali saja dengan tanpa persetujuan aku merapatkan bayangan sang Jagra untuk sekadar dapat menemani dalam kesuntukan hingga terbit saat puncak tilem kepitu. Sekadar bersanding tanpa menyatakan kebenaran : dharma entah adharma. Dilema pada perut yang senantiasa ngeroncong butuh diisi – dilema pada ingatan melalui pikiran-pikiran busuk – dilema pada setiap laku yang alpa waktu pun angkara – dilema pada setiap ujaranku yang terlampau giat mencemooh. Oh, Ciwa , maafkan.
Malam ini, tepat di angka bumi yang selalu menghindarkan bencana bersinergi dengan bumi dan penghuninya – itu doaku. Aku pulang melarikan perjumpaan dengan sang Lubdhaka. Katanya kebenaran ada di dalam hati, di dalam bumi tak terluka. Sorga itu ada di dalam hati, di dalam bumi tak terluka. Sorga melapisi selaksa kebenaran. Orang-orang kulihat menyusuri jalan yang pernah kulalui sebelumnya. Berbekal doa dan hati yang lebih bersih dari dugaanku.
Lereng pengsong, 2021
PEREMPUAN DAN SUNGAI YANG MATI
Perempuan itu sering berjalan menyusuri sawah menghabiskan waktu dengan diam. Mata yang mengaca bening tak meninggalkan gurat menua. Separuh waktu berjalan dengan pikiran-pikirannya – selebihnya mendahului waktu-waktu yang tidak henti untuk menahan pikirannya berlarian sendiri. Sepanjang jalan telah dilalui. Sepanjang sungai tak lelah dalam susuran. Perempuan kehabisan cita-cita, tak pernah bertanya, berapa keturunannya hingga kini, entah berapa pernah terlahir dari rahimnya. Tak pernah ada yang tahu ataupun mengusik talentanya.
“Bau amis keluar dari mulutku,” katanya di pagi penuh nalar membiarkan matahari merangkak perlahan ke arah barat. Entah berapa ikan melupakan siripnya, barangkali sungai ini melengkapi sirip untuk mengajarnya berenang.
Bulan jatuh pada hari kesembilan tepat memantul pada air bergerak pelan, sepanjang sungai yang telah berganti menyusurinya melahirkan anak-anak kembali. Air mengubah bening, sebening matanya yang tak pernah diam mengalirkan misteri. Tepat pada purnama ke sepuluh, bilangan usia telah menjaganya untuk terlahir hingga dia menganggap bau amis di mulutnya tak terasa lagi.
Perempuan itu meninggalkan sungai mati dengan limbah mengalir di segenap sisa pikirannya. Mengail bayang keemasan lewat kecemasan renta. Perempuan yang meleleh waktu-habisi sungai mati. Lakinya, seekor ikan keparat yang kehabisan air.
Lereng Pengsong, 2020
CAMAR PULANG SENJA
Senja lepas di matamu
sebentar lagi purnama
ketika kau kepak sayap, mampirlah – ini rumahmu
lewati perbincangan atau biarkan matahari menghilang
sampai peluh lelah jadi keluh, dalam hidup tak mengenal rentang
tak menjanjikan harapan, sebagaimana pernah engkau katakan
Setelah merapat, setelah sayapmu letih
selepas senja hilang di matamu
senyap melantunkan kesunyian senantiasa kau dendangkan
mari, kita tunggu, purnama itu
selalu sama pada setiap perbincangan tak mengenal waktu
dan tetap akan hadir
di matamu
senja lepas di matamu
entah mataku
Lereng Pengsong ,2020
*DG. Kumarsana lahir di Denpasar, 1965, menulis puisi, esai, cerita pendek, novel dan prosa. Tulisannya dimuat di beberapa media cetak.. Bukunya yang telah terbit ”Komedi Birokrat” (2010), ”Senggeger”(2010)” Kabinet Ngejengit” (2012). ”Mata Dadu” (2014). Penari ular (2019). “Nyoman dan Senggeger” (2020), “Pengkoak” (2020).
Mukim di desa Telagawaru Labuapi Lombok Barat



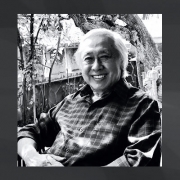









Luar biasa. Saya senang dan bangga bisa membaca karya-karya Pak Kum.
Limpah terima kasih dan sangat bersyukur bisa mengenal Pak Kum dan belajar dari penyair hebat ini.
Teruslah menjadi inspirasi