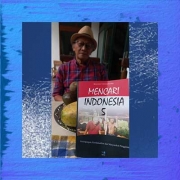Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.
BALADA SYAIKH MAKDUM WALI
1.
Pada senja yang pecah seperti buah delima,
Syaikh Makdum Wali melangkah dari arah barat.
Serayu membuka diri,
“Masuklah, kekasih Allah,” bisiknya pelan—pelan—pelan,
seakan takut membangunkan sejarah.
2.
Sarung sederhana berkibar perlahan,
seperti bendera yang tak ingin mengumumkan perang
kecuali perang melawan gelap di dada manusia.
Daun jambu bergerak tanpa angin,
seakan menunduk pada tamu yang membawa nur dari jauh.
3.
“Apa yang kautawarkan pada kampung ini, Wali?”
tanya bayang-bayang yang melompat dari akar beringin tua.
Makdum Wali tersenyum,
senyum yang lebih tua dari waktu.
“Hanya air bagi yang haus,
dan cahaya bagi yang tersesat.”
4.
Gunung Slamet mendengarkan dari kejauhan,
diam, namun penuh getar.
Awan-awan menggeser tubuhnya,
membuat langit tampak seperti kitab
yang hendak terbuka pada surat yang terlupakan.
5.
Ketika ia menjejak tanah,
suara bumi meletup pelan:
duk… duk… duk…
Seperti jantung bayi yang baru disapih.
Anak-anak kampung merapat,
mata mereka bening seperti mata air yang belum disentuh kabut.
“Ajari kami,” kata mereka tanpa suara.
6.
Makdum Wali mendongak,
dan rembulan, besar bagaikan piring perak,
melorot dari langit untuk duduk di pundak malam.
“Lihatlah,” katanya,
“cahaya tidak pernah tergesa.
Ia selalu menunggu manusia kembali.”
7.
Lalu ia berdzikir—dzikir—dzikir,
dan setiap dzikir menjadi burung,
setiap burung menjadi doa,
setiap doa menjadi anak panah
yang melesat ke dada langit.
8.
Di serambi langgar, lampu minyak gemetar,
bukan karena angin,
tetapi karena kedatangan sesuatu
yang tak terlihat oleh mata
namun dirasakan oleh seluruh tubuh kampung:
ketenteraman.
9.
“Kau datang dari mana, Wali?”
tanya seorang lelaki tua dengan suara patah.
Makdum Wali menjawab ringan,
“Aku datang dari jalan yang dilalui setiap orang,
jalan pulang.”
10.
Dan malam itu, Banyumas mencatat sesuatu
yang tidak dicatat oleh raja-raja:
cahaya kecil yang tumbuh
di dada manusia yang tersenyum
untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
2025
BALADA SYAIKH MAULANA RUMAINI
(Sumur Pasucen)
Di Dawuhan Banyumas,
air bukan sekadar air
ia adalah kitab basah
yang dibuka angin,
halaman demi halaman.
Setiap riak adalah huruf
yang melafalkan rahasia
lebih tua dari nama manusia.
Kabut turun rendah,
menyentuh Batu Pasujudan
yang berdiri seperti tulang belulang bumi,
mengingatkan bahwa di titik itu
Syaikh Maulana Rumaini, musafir dari Persia,
pernah menanam sunyi,
sunyi yang kemudian tumbuh
menjadi cahaya yang menyucikan tanah
bahkan dari kemarau paling panjang.
Ketika Maulana menancapkan tombak pusaka,
mata air Pasucen pun memercik,
mengalir deras dan jernih
menjadi sumber kehidupan
dan doa bagi penduduk Dawuhan.
Suara dzikirnya naik ke udara
seperti burung putih
yang mencari sarang
di rambut malam.
Di tepi lain,
Batu Kiblat berdenyut pelan,
bagai jantung yang menunggu panggilan.
Seusai perjalanan beliau,
datanglah para mursyid dan guru,
dan ketika mereka bershalat,
batu itu memercikkan cahaya
setipis mata pedang,
menusuk langit,
hingga bintang-bintang
berkumpul di atasnya
seperti jamaah yang tak terlihat.
Syaikh Maulana Rumaini
dengan sarung sederhana
yang menyimpan harum tanah basah
melangkah ke pertapaan perbukitan,
tempat angker menggeliat
seperti ular hitam terluka.
Namun ketika langkahnya menyentuh pintu,
angker itu lari
seperti bayangan ketakutan
yang kehilangan tubuhnya.
Sumur Pasucen pun menjadi panggung
dua arus jiwa:
putihan dari timur
membawa embun ayat,
dan abangan dari barat
membawa doa dan keris berdesis
antara gelap dan cahaya.
Kaum putihan membenamkan tangan
ke dalam mata air,
dan air itu memantulkan wajah mereka
seperti cermin yang baru disentuh malaikat.
Kaum abangan menjamas pusaka
di bawah bulan merah,
dan setiap tetes air
yang jatuh dari besi pusaka itu
menjelma bunga liar
yang tak dinamai siapa pun
kecuali angin.
Syaikh duduk di antara mereka,
bagai batu kecil
yang menahan pecahnya dunia.
Suara beliau lirih namun tegas,
menyusup ke dada
seperti gambang yang dipetik pelan:
“Air tidak memilih.
Yang membawa dendam
akan kehilangan bayangannya.
Yang membawa ikhlas
akan menemukan cahaya
yang bahkan malam
tak sanggup menyembunyikan.”
Kunang-kunang turun,
melingkari Batu Kiblat
sebagai mahkota kuning
untuk doa-doa yang belum selesai.
Angin menari di sekitar Batu Pasujudan,
seperti malaikat yang lupa
ke mana harus pulang.
Dan di saat tertentu,
ketika angin dari Slamet
datang membawa bau cemara dan rahasia,
orang-orang melihat Syaikh Maulana Rumaini
berjalan di atas air,
langkahnya tak menimbulkan riak,
seolah sungai menahan gelombang
agar tidak mengganggu para wali
yang sedang berbicara
dalam bahasa yang tak bisa dituliskan.
Sejak itu,
di tepi Sumur Pasucen,
putihan dan abangan
berdiri menghadap arah yang sama.
Mereka tidak lagi bertanya
jalan mana yang paling benar,
karena air telah mengajarkan
bahwa arah bukan sekadar timur
atau barat,
melainkan kedalaman hati
yang rela disucikan.
Dan mata air,
di bawah cahaya redup bulan,
terus mengalir sebagai saksi
bahwa di tempat itu
Syaikh Maulana Rumaini menanam cahaya,
yang terus menyala dari dalam senyap
bahkan setelah waktu
melupakan namanya.
2025
BALADA ADIPATI WIRASABA
Di tanah Wirasaba yang tua,
pagi mengibarkan kabut
seperti panji perang.
Di balik gerumbul bambu,
para leluhur berdiri tegak
menjaga nama yang diwariskan
dari Majapahit dan Pajajaran.
Adipati berangkat pulang,
di pundaknya bergetar kesetiaan.
Ia menatap lembah Serayu
seperti menatap masa depan
yang belum memberi tanda.
Di dadanya,
kehormatan berdenyut
seperti genderang perang
yang ditabuh perlahan.
Namun di Pajang,
istana menegang.
Sepotong kabar yang salah
jatuh seperti pedang dari langit.
Sultan murka
dan perintah meluncur
lebih cepat dari doa
yang belum sempat dibatalkan.
Dua utusan berangkat
menembus hutan, sungai, dan rawang:
yang satu membawa maut,
yang satu membawa ampun.
Kuda-kuda mereka meringkik,
membelah angin
yang menghitam oleh firasat.
Adipati tak tahu
bahwa ajal menyelinap
dalam jejaknya sendiri.
Ia berjalan seperti cahaya terakhir
yang terbungkus kesunyian.
Para prajuritnya membaca angin,
tetapi angin diam,
seakan seluruh semesta
menahan napas
pada satu titik
yang belum terlihat.
Di Desa Bener,
nasib tiba lebih dulu.
Prajurit pembawa maut
muncul dari bayangan
pohon randu.
Pertarungan singkat,
cemerlang,
dan getir
bagai kilatan baja
yang patah
di tengah udara.
Adipati Wirasaba tumbang
di atas tanah leluhurnya sendiri.
Darahnya mengalir pelan
menuju parit kecil
yang menuntun ke Sungai Serayu.
Air membawa warnanya
menuju hening
yang panjang.
Beberapa saat kemudian
prajurit pembawa ampun datang
terlambat satu hembusan angin,
terlambat satu degup jantung.
Mereka memeluk penyesalan
seperti memeluk bayangan
yang tak bisa
dihidupkan lagi.
Langit meremang.
Burung-burung menutup sayapnya.
Di antara pepohonan,
roh-roh Wirasaba melangkah turun,
membentangkan selendang kabut
di tubuh sang adipati.
Mereka menuntun ruhnya
ke jalan yang hanya dikenal
oleh arwah para prajurit mulia.
Di istana Wirasaba,
Jaka Kaiman berdiri
di depan para abdi.
Wajahnya bagaikan batu
yang setengah retak.
Air matanya jatuh sedikit,
cukup untuk menandai duka,
tidak cukup
untuk meluruhkan tekad.
Ia memecah tanah Wirasaba
menjadi empat bagian,
sebagai penebusan,
sebagai penanda,
sebagai sumpah,
agar darah ayahnya
tidak tenggelam
tanpa makna.
Sejak itu,
tiap malam di makam Wirasaba,
angin berbicara ritmis,
mengetuk batu nisan
seperti lagu perang
yang jauh:
“Hormatilah kehormatan,
jangan percaya kabar buta,
karena sebuah kata
dapat membunuh
seorang pemimpin.”
Hingga kini,
di lembah Serayu,
bayangan Adipati Wirasaba
berkuda dalam kabut pagi.
Ia tidak membawa dendam,
hanya membawa pelajaran:
bahwa seorang pemimpin sejati
mati bukan karena takdir semata,
tetapi karena kesetiaan
yang tak pernah
ia lepaskan.
2025
BALADA KALI KLAWING
Di hulu Klawing,
kabut turun seperti doa yang lupa pulang.
Air mengalir pelan,
membawa suara-suara lama
yang disembunyikan batu-batu purba
di dasar sungai.
Setiap riak adalah nama,
setiap pusaran adalah takdir
yang menunggu ditafsirkan manusia.
Para nelayan memandang air
seperti membaca kitab tua
yang ditulis dengan huruf-huruf cahaya.
Di tepian,
pohon-pohon nangka dan randu
menjuntai bayang-bayangnya,
seakan hendak meraih masa lalu
yang tercecer dalam arus.
Sungai bergetar
ketika angin datang dari Pegunungan Serayu,
membawa kabar dari langit
yang pernah bersujud di tanah ini.
Pada malam-malam tertentu,
ketika bulan condong seperti mata dewa,
kuda-kuda air muncul
dari balik gelap,
mengentakkan langkah halus
di permukaan sungai.
Mereka adalah penjaga rahasia,
roh yang lahir dari sejarah
kematian dan kelahiran
yang tak sempat dituturkan manusia.
Orang-orang tua
menyebut Klawing sebagai sungai
yang menakar keberanian.
Siapa pun yang menyeberang
harus membawa hati terbuka,
atau arus akan menelan
seluruh ingatan mereka,
meninggalkannya tanpa nama
di dasar yang tidak mengenal waktu.
Di desa-desa sepanjang bantaran,
anak-anak mandi
seperti menari bersama arwah leluhur.
Tertawa mereka pecah
di antara batu-batu sungai,
dan Klawing menyimpannya
sebagai mutiara suara
yang kelak akan kembali
menjadi nasihat.
Kadang,
air berubah gelap
bukan karena hujan,
tetapi karena cerita pahit
yang ditumpahkan manusia.
Dan sungai pun bergolak
bukan marah,
tetapi mengingatkan
bahwa tanah yang diinjak
punya nyawa
dan menuntut hormat.
Ketika fajar menyentuh permukaan,
Klawing memantulkan wajah-wajah
yang datang menziarahi diri sendiri.
Ia mengajar mereka
bahwa perjalanan manusia
sering seperti arus:
berliku, gelisah,
namun tetap menuju laut
yang menyimpan pulang terakhir.
Sungai ini bukan aliran biasa;
ia adalah saksi
dari ribuan langkah
yang pergi dan tak kembali,
dari doa-doa yang patah
dan kembali dibangun,
dari rahasia yang ditanam
dalam hati bumi.
Klawing mengalir
dan menghidupkan kampung,
tetapi ia juga mengingatkan
bahwa hidup bukan hanya berjalan
ia juga mendengarkan,
menunggu,
dan berserah
pada aliran yang lebih besar
dari apa yang terlihat mata.
Di bawah matahari pagi,
air berkilau
seperti ayat yang menuntun
para pejalan.
Dan siapa pun yang menatapnya
akan tahu:
bahwa Klawing
adalah sungai yang hidup,
mengalirkan sejarah manusia
sambil menjaga suaranya
di antara cahaya
dan bayangan.
2025
BALADA JENDERAL SOEDIRMAN
Di kaki Gunung Slamet,
pagi turun seperti biola pertama
yang digesek angin dari langit.
Kabut membuka sayap perlahan,
membawa bau tanah basah
dan doa-doa tua
yang belum pernah selesai dibacakan.
Dari kejauhan,
Soedirman muncul seperti huruf cahaya
yang menembus tirai kabut.
Langkahnya tenang,
namun bumi mengingat setiap hentakannya
seperti ketukan rebana
di sebuah majelis rahasia
antara manusia dan takdir.
Ia lahir dari kesunyian kampung,
namun jiwanya diasuh
oleh tangan-tangan gaib
yang menanam keberanian
di dalam dada seorang anak
yang lebih sering diam
daripada bicara.
Ketika perang tiba
seperti gerimis besi dari langit,
ia berdiri
tidak sebagai prajurit semata,
melainkan sebagai saksi
bahwa tanah air
adalah janji spiritual
yang tak boleh ditinggalkan
meski tubuh gemetar oleh sakit.
Di atas tandu,
ia bergerak melewati belantara,
bagaikan maqam panjang
yang disanyikan daun-daun
dan diiringi langkah para pengusung
yang menjadi sayap-sayap malaikat bumi.
Tiap ayunan tandu
menjadi ketukan ritmis
seperti gendhing yang lahir
dari jantung perlawanan.
Hutan membuka jalan,
burung-burung berhenti berkicau,
dan sungai-sungai menunduk,
karena mereka tahu
bahwa seorang hamba
sedang membawa amanah besar
menembus malam yang licin oleh ancaman.
Belanda mencari jejaknya,
namun mereka tak paham:
yang berjalan bukan daging dan tulang
yang bergerak adalah cahaya tekad
yang disimpan Allah
dalam seorang manusia
yang menolak menyerah.
Di malam terdalam,
ketika hujan merajam daun,
Soedirman berhenti untuk sujud.
Tanah basah mencium keningnya,
dan langit menutup rindu
yang bergetar di antara nafasnya.
Doanya naik perlahan,
membentuk lingkaran tak terlihat
yang menjaga para prajuritnya
dari arah-arah gelap.
Di lembah-lembah sunyi tanah Jawa,
angin menghafal suaranya.
Di antara nyala obor yang kecil,
ia menggambar peta
dengan gerakan tangan
yang lebih mirip zikir
daripada strategi perang.
Namun dari zikir itu,
lahirlah kemenangan
yang tak mampu dipatahkan senjata.
Ia kembali dalam tubuh yang letih,
tetapi jiwanya berdiri
setinggi pohon randu perkasa.
Bangsa ini menyambutnya
tanpa tahu bahwa seorang jenderal
telah menanggung badai
di dalam dada lebih dulu
sebelum badai itu datang ke republik.
Kini, ketika malam turun
di tanah Jawa,
angin dari Serayu dan Logawa
masih membawa gumam namanya
gumam yang bergetar
seperti senandung para sufi
yang mencari jalan pulang.
Dan siapa pun yang mendengar
akan tahu:
Soedirman bukan hanya pahlawan,
ia adalah perjalanan rohani
yang turun ke bumi
dalam bentuk keberanian.
Ia berjalan dalam tandu,
namun memimpin
dengan cahaya yang membuat langit
menunduk hormat.
2025
BALADA SYAIKH JAMBU KARANG
Hutan Cahyana bergetar dalam hening yang menelan suara,
daun-daun berbisik dengan lidah malam,
angin membelah pepohonan,
menyingkap tanah yang belum pernah dijamah kaki manusia.
Syaikh Jambu Karang melangkah perlahan,
tangan menabur doa seperti biji yang menembus bumi,
dan bayangan pepohonan menunduk,
memberi hormat pada kaki yang menapaki rahasia keheningan.
Dari kejauhan, sungai bergemericik,
bukan sekadar air
ia adalah nadi bumi yang menahan sejarah,
menyimpan bisik para leluhur
yang menunggu pendengar yang sabar.
Ia lahir dari Munding Wangi,
meninggalkan istana Pajajaran,
menyepi di hutan perawan,
menyimak suara yang lebih tua dari manusia,
mengikuti cahaya yang turun dari arah tak terlihat:
Syekh Atas Angin,
mengajari bahwa ilmu adalah doa yang bergerak di udara,
dan kesabaran adalah tombak yang menembus kegelapan.
Malam menebal, bintang-bintang menunduk,
Syaikh menabur dzikir, menenun udara menjadi harmoni,
daun, batu, dan sungai ikut menari,
mengikuti irama yang lahir dari ketulusan hati.
Putrinya, Rubiah Bekti, bersatu dengannya,
mengikat dzuriyah yang membawa sinar ke Cahyana:
Syekh Makdum Husain,
Syekh Makdum Madem, Syekh Makdum Omar,
Nyai Rubiah Raja, Nyai Rubiah Sekar
mereka menabur ilmu di tanah yang haus doa dan cahaya,
menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang tersesat.
Syaikh duduk di tepian sungai,
doanya memecah gelombang menjadi nyanyian,
setiap riak menulis sejarah dengan huruf cahaya,
hembusan angin menjadi dzikir yang bergetar di seluruh hutan,
dan bayangan pepohonan menari, mengikuti irama doa.
Anak-anak desa menatap, mata mereka bercahaya,
tangan mereka menyentuh air,
dan sungai menunduk,
mengukur kesungguhan hati mereka.
Kabut menebal, menyelimuti tebing dan batu,
dan dari riak muncul bayangan para wali,
membisikkan mantra yang menembus malam,
mengalir dari waktu ke waktu,
mengikat masa lalu dengan yang akan datang.
Syaikh berdiri, tubuhnya tenang,
langkahnya membelah malam,
mengajari bahwa kesabaran adalah jalan,
dan doa adalah pedang yang menundukkan gelap
tanpa membakar hati yang suci.
Bulan menunduk di malam terdalam,
mata yang menyimpan rahasia perlahan terbuka,
dzuriyah menyalakan lentera-lentera kecil di hati manusia,
menjadi cahaya bagi mereka yang berjalan dalam gelap,
mengalir, bergetar, hidup dalam gema yang mengulang diri
seperti nadi yang tak lelah berdetak.
Sungai Cahyana berputar, angin menari,
kata-kata Syaikh menjadi gema
yang menyatukan bumi, manusia, dan langit,
mengalir seperti doa, bernyawa, menembus ruang,
menjadi legenda yang meresap ke dalam hati yang sabar,
menghidupkan alam dan manusia dalam satu nada yang agung,
mengalun hingga ke cakrawala yang paling sunyi.
2025
BALADA SYAIKH MAKDUM HUSAIN RAJAWANA
Seribu seratus Masehi, Cahyana diselimuti kabut
yang menekuk lembah seperti kain hitam,
dan sungai berbisik dengan napas yang ditahan,
hanya terdengar oleh hati yang sabar.
Di tepian hutan, Raden Munding Wangi menapak,
meninggalkan istana Pajajaran,
akar dan batu tua menggema di bawah langkahnya,
dari arah angin muncul cahaya yang tak tampak:
Syekh Atas Angin, penunjuk jalan.
Ia menuntun Munding Wangi
ke sunyi yang lebih tua dari dunia,
mengajarkannya bahwa ilmu bukan sekadar kata,
tetapi doa yang berjalan di udara,
dan kesabaran adalah tombak yang menundukkan nafsu.
Putrinya, Rubiah Bekti, bersatu dengannya,
mengikat dzuriyah yang membawa sinar
ke setiap sudut Cahyana:
Syekh Makdum Husain, di Rajawana;
Syekh Makdum Madem, di Cirebon;
Syekh Makdum Omar, di Karimun Jawa;
Nyai Rubiah Raja, di Ragasela;
Nyai Rubiah Sekar, di Jambangan.
Mereka menabur ilmu,
menyulam doa,
dan menyalakan lentera bagi hati manusia.
Sungai Rajawana bergetar saat Makdum Husain melangkah,
setiap kaki menulis huruf cahaya di udara,
mengikat bumi, langit, dan manusia dalam satu tarian doa.
Angin menyalin kata-katanya menjadi benang cahaya
yang membelai pepohonan, batu, dan anak-anak desa,
sementara kabut menunduk,
membuka panggung bagi roh leluhur.
Mereka menari di riak sungai,
membisik mantra yang membelah malam,
dzuriyah menuntun langkah Syaikh
seperti lentera di jalan yang belum pernah ditapak.
Anak-anak desa menyentuh air yang berkilau,
dan sungai menatap balik,
mengukur keberanian yang lahir di antara bisik pepohonan.
Setiap malam, bulan menunduk,
mengintip rahasia yang dibawa oleh Syaikh,
sementara para wali terdahulu menyalakan cahaya
di tanah basah.
Kata-kata Syaikh menjadi gema, menari di udara,
mengetuk daun, batu, dan air,
menghidupkan doa yang terus berjalan
seperti nyanyian yang tak pernah berakhir.
Dzuriyah dan roh leluhur berbisik:
“Bacalah dengan hati,
hidupkan iman dalam setiap langkah,
dan jangan biarkan dunia menutup mata
terhadap cahaya yang lahir dari ilmu.”
Orang-orang menunduk di makam,
tanah bergetar di bawah kaki mereka,
dan angin membawa suara doa jauh ke hutan dan lembah.
Ilmu, keberanian, dan cahaya mengalir seperti sungai,
hidup, bernyawa, dan menyala,
menjadi legenda
yang meresap ke dalam setiap hati yang mendengar,
mengikat manusia, bumi, dan langit
dalam satu nadi yang abadi.
2025
BALADA K.H. ABDUL MALIK
Di Kedung Paruk, Purwokerto,
3 Rajab 1294 H
kabut menunduk, menekuk lembah,
angin membawa bisik langit,
dan bumi menahan napas.
Abdul Malik membuka mata
mata cahaya, mata doa, mata yang menulis sejarah.
Langkahnya menabur dzikir, dzikir, dzikir
di udara, di daun, di batu, di sungai.
Ia menimba ilmu dari ayahnya,
mengembara ke Mekkah,
menggenggam cahaya Naqsyabandiyah Khalidiyah,
menyatu dengan Syadziliyah,
dan pulang membawa dua cahaya dalam satu tubuh
cahaya yang menuntun manusia
ke jalan sunyi, jalan hening, jalan suci.
Di masjid-masjid dan rumah sederhana,
ia menabur dzikir, dzikir, dzikir
seperti biji yang jatuh ke tanah basah.
Kesabaran menjadi akar,
keikhlasan menjadi batang,
kebijaksanaan menjadi bunga harum
di setiap hati yang haus, setiap hati yang lapar,
setiap hati yang mencari.
Anak-anak duduk di tepian sungai,
tangan mereka menyentuh riak,
dan sungai menatap balik.
Dzikirnya menembus air, menembus tanah,
mengikat bumi, mengikat hati, mengikat langit.
Malam turun perlahan, kabut menebal,
bulan menunduk, mata yang menunduk pada doa.
Roh leluhur menari di riak air,
dzuriyah menuntun langkahnya,
lingkaran cahaya berputar
dzikir, dzikir, dzikir…
mengikat bumi dan langit dalam tarian.
Ketika hayat menutup mata, 2 Jumadil Akhir 1400 H,
tanah Kedung Paruk menadah tangan,
makam menjadi lampu,
angin menjadi guru,
dzikirnya mengalir seperti sungai Ilahi.
Dzikir… Cahaya… Doa…
menghidupkan yang mati dalam hati,
menyucikan yang gelap,
mengajar manusia bahwa ilmu, kesabaran, dan cahaya
adalah nadi yang menjaga manusia
tetap hidup dalam cinta, tetap hidup dalam doa,
tetap hidup dalam cahaya.
Siapa pun yang menatap makamnya
akan mendengar gumam lirih:
“Bacalah dengan hati…
Hidupkan dzikir dalam setiap langkahmu…
Jangan biarkan dunia menutup mata
terhadap cahaya yang lahir dari kesetiaan,
dari ilmu, dari doa,
yang menapak di bumi ini,
dari Purwokerto hingga langit.”
2025
BALADA HABIB HAMID SOKARAJA
Di Sokaraja, di lorong-lorong sunyi,
Habib Hamid berjalan di atas rumput basah,
tanpa alas kaki,
mendengar doa-doa yang menetes dari langit,
menyentuh bumi,
menyentuh hati yang lapar akan cahaya.
Ia tidur di lantai, di samping ibu yang renta,
menjadi penjaga kesetiaan yang tak terucap,
menjadi lentera yang menuntun malam
dengan bisik ayat-ayat yang mengalir
seperti sungai yang menembus akar dan batu.
Tidak ada kemewahan,
hanya wudlu yang menetes lembut,
hanya kesabaran yang bergetar,
mengalir di udara, di daun-daun, di rumah sederhana.
Gus Dur datang suatu siang,
mata haru, jiwa yang mencari,
Habib Hamid duduk di halaman,
menatap sesuatu yang tak kasat mata,
mengikat negeri dengan doa
yang menembus ruang dan waktu.
Ayat-ayatnya seperti tongkat Musa,
memisahkan gelap dan terang,
mengajarkan keberanian untuk melangkah
di jalan yang benar,
walau dunia berbisik fitnah dan dusta.
Tiap kata menimbulkan gema di daun,
di tanah, di sungai, di hati yang mendengar,
menghidupkan ritual yang tak tampak,
mengalir seperti cahaya
yang menembus setiap jiwa yang haus.
Kabut menari di halaman rumahnya,
angin menyalin doa menjadi benang cahaya,
mengikat pepohonan, batu, dan anak-anak desa,
mengajar bahwa ilmu, keberanian, dan kesetiaan
adalah jalan yang meniti malam,
bagi yang bersih hatinya.
Orang-orang menunduk,
tanah Sokaraja bergetar di bawah kaki mereka,
menjadi saksi
bahwa seorang guru bukan sekadar manusia,
ia adalah gema doa,
jalan cahaya,
dan lentera yang menuntun jiwa tersesat.
Dan siapa pun yang mendengar,
merasakan getarannya di dada,
bahwa Habib Hamid Sokaraja
adalah perjalanan rohani
yang mengalir seperti air,
membawa doa, ilmu, dan keberanian
ke setiap hati yang haus akan cahaya.
2025
—–
*Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, kemudian lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Abdul Wachid B.S. menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (2018), Bunga Rampai Esai Sastra Pencerahan (2019), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (2022). Melalui buku Sastra Pencerahan, Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).***