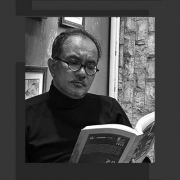Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.
BALADA KENDI YANG RETAK
Di sudut dapur
yang jarang disentuh cahaya,
sebuah kendi tua bersandar pada tembok,
retak di lehernya,
dan serpih kecil menganga
seperti luka yang tak kunjung sembuh.
Dulu,
ia ditempatkan di gubuk pesantren,
mengalirkan air untuk wudu
bagi para santri
yang menghafal Al-Qur’an
di sela desir angin dan suara jangkrik.
Setiap tetesnya
adalah zikir yang jatuh perlahan
ke telapak tangan yang gemetar karena malam.
Waktu berlalu,
sumur mengering,
dan keran-keran
menggeser tempatnya.
Orang-orang lupa,
bahwa kendi pun bisa mengerti
apa itu sabar
dalam menahan air dan kenangan.
Kini, ia hanya retak.
Tapi tak pecah.
Tak sekali pun ia minta dibuang
atau diganti.
Ia tetap di sana,
menampung embun malam
dan meneteskannya perlahan ke akar-akar rumput
yang tumbuh tanpa suara.
Kadang, seorang anak kecil
mendekat,
memutar-mutar retaknya
seperti membaca garis tangan.
“Apakah kendi bisa menangis?” tanyanya.
Dan suara lirih dari leher kendi menjawab:
“Bukan air yang kusembunyikan,
tetapi amanah dari yang Maha Mengalir.”
Dan malam itu,
ibu anak itu bermimpi:
sebuah kendi berjalan dalam cahaya,
retaknya bercahaya seperti sutra,
dan dari dalamnya
tumpah air yang tak kering
meski dunia terbakar.
2025
BALADA TEMBOK BERLUMUT DI SISI PESANTREN
Di sisi barat pesantren,
ada tembok yang tak dicat sejak zaman Kiai Umar wafat.
Tembok itu tidak tinggi,
hanya setinggi dada santri,
tapi menyimpan musim
dan dengungan doa yang tidak pernah usai.
Setiap habis subuh,
matahari menyentuh lumut-lumut yang tumbuh pelan
seperti ayat yang mengendap
dalam dada anak-anak
yang belum fasih membaca
tapi telah hafal irama-Nya.
Lumut itu tidak sekadar hijau.
Ia menyimpan jejak air wudu
yang tercecer
oleh santri yang tergesa
menuju langgar bambu.
Dan jika malam tiba,
tembok itu dingin
seperti zikir yang dilafazkan dalam hati,
berulang tanpa suara
sampai menusuk langit
dalam gelombang sunyi.
Pernah, seorang santri jatuh cinta pada lumut.
Ia menulis puisi di dalam hati:
“Engkau tak perlu bunga,
cukup embun dan kesetiaan
untuk menjadi indah.”
Mbah Sobari, penjaga malam pesantren,
sering berkata:
“Lumut itu penjaga,
ia tahu siapa yang shalat dengan sungguh,
dan siapa yang hanya melewati waktu.”
Lama-lama, lumut menjadi kitab diam,
merekam setiap langkah,
setiap air mata yang tak jadi jatuh
karena terlanjur ikhlas.
Dan pada suatu dini hari,
seorang anak yang selalu duduk di pojok
melihat tembok itu bersinar lembut.
Dari balik lumut,
muncul kalimat yang bukan dari tinta:
“Siapa yang menjaga zikir,
akan dijaga oleh waktu
dan disembunyikan dari kesia-siaan.”
Anak itu menangis,
tapi air matanya tak jatuh,
karena sudah lebih dulu
diserap oleh lumut
yang sabar dan setia
mengisap cahaya dari tiap zikir
yang kita lupakan.
2025
BALADA CELURIT DI BELAKANG PINTU
Di belakang pintu dapur
yang selalu menganga setengah
tergantung celurit tua
bermata tumpul
dan gagangnya mulai lapuk oleh musim.
Tak seorang pun tahu
kapan terakhir ia digunakan
mungkin saat musim tebu
masih diangkut dengan kereta sapi
dan doa dibisikkan ke mata bajak
sebelum menebas ilalang di ladang.
Tapi tiap subuh
ketika pintu berderit
dan angin dari surau kecil
membawa bau sajadah basah,
celurit itu bergetar lirih
seperti sedang mengaji
huruf-huruf yang tak tampak.
Dulu, kakek menyelipkannya di pinggang
bukan untuk menakut-nakuti
melainkan sebagai pengingat:
“Kadang setan tak datang dari luar,
tapi berbisik dari dalam dada sendiri.”
Celurit itu saksi
perang yang paling sunyi:
melawan dengki,
menebas malas,
menyerempet hawa nafsu
yang bersembunyi di sela niat baik.
Anak kecil pernah bertanya,
“Kenapa celurit tak pernah dibuang saja?”
Ibu menjawab,
“Karena ia bukan alat pembunuh,
tapi cermin bagi yang ingin kembali.”
Dan suatu malam,
ketika listrik padam
dan dunia diliputi diam,
celurit itu memantulkan cahaya lilin
ke arah dinding,
membentuk bayang seperti orang bersujud
dengan luka di punggungnya.
Malam itu,
ada bisikan dari balik bilik:
“Yang menang bukan yang menebas,
tapi yang menahan tangan
saat amarah hendak bicara.”
Celurit pun diam.
Dan pintu kembali tertutup
dengan perlahan,
seperti hati yang diajari sabar
oleh benda tajam
yang memilih tidak melukai.
2025
BALADA PADI YANG DITIUP
ANGIN SUBUH
Di hamparan sawah
yang menghadap ke timur pesantren,
padi-padi muda gemetar
ketika angin subuh datang
perlahan, tapi pasti,
seperti doa ibu
yang tak pernah putus
meski anaknya lupa sujud.
Tak ada dentang lonceng.
Tak ada azan dari pengeras suara.
Hanya desir dedaunan
dan desir dada para petani
yang bangun sebelum fajar
untuk menepikan kantuk demi ladang
yang mereka anggap bagian dari zikir.
Padi itu tak sekadar tumbuh,
tapi belajar tunduk.
Setiap butir yang merunduk
adalah ayat yang tak dibaca
tapi dipahami
oleh hati yang bersih dari pamrih.
Angin subuh
mengusap ubun-ubun padi
seperti seorang guru
mengusap kepala santri kecil
yang baru hafal tiga surat pendek
dan menangis karena belum sempurna.
Kadang, seorang anak desa
berdiri di pematang,
melihat padi yang seakan sujud
dan bertanya:
“Apakah mereka juga sedang shalat?”
Kakeknya menjawab dengan senyum:
“Ya. Mereka shalat sejak ditanam,
dan hanya berhenti jika dipanen
oleh tangan yang tidak lupa bersyukur.”
Ketika kabut masih menari di antara batang,
seekor burung pipit datang,
mematuk padi yang paling khusyuk.
Ia lalu terbang sambil membawa
sebutir hikmah
untuk ditanam di langit.
Dan pada malam harinya,
anak yang tadi bertanya bermimpi:
ia melihat sawah bersinar,
padi-padi berzikir
dengan bahasa angin,
dan setiap butirnya
memancarkan lafaz “Subhanallah”
yang menembus dadanya
seperti cahaya
dari langit yang rindu.
2025
BALADA PAYUNG TUA
DI TENGAH HUJAN KUBURAN
Payung tua
berdiri miring di antara batu nisan,
pegangan kayunya mengelupas
seperti kenangan
yang diseret waktu terlalu jauh.
Hujan turun
tanpa suara petir,
seperti doa-doa yang tak lantang
namun lebih didengar.
Bumi basah oleh air
yang turun dari langit
dan mata.
Seorang lelaki tua,
membungkuk di bawah payung itu
membaca Yasin
sambil jemarinya bergetar
di antara lembaran mushaf
yang hampir larut dalam gerimis.
Ia bukan hanya membaca untuk mayit,
tapi juga untuk dirinya sendiri
yang merasa mati
di sebagian hidupnya
yang tak pernah sempat ia tangisi.
Payung itu pernah dibawa
saat istrinya wafat,
dan kini ia memayungi
nama yang sama
di batu yang diam,
ditulisi tanggal,
dan sebait doa
yang telah luntur hurufnya.
“Kalau hujan adalah rahmat,” katanya lirih,
“maka biarlah ia membasuh
semua salah yang tak terucap.”
Kuburan menjadi taman zikir.
Bunga-bunga liar menggigil
tapi tidak rontok,
karena kasih sayang Allah
menetes di sela batu
dan akar yang menembus
tulang dan rindu.
Dan ketika lelaki itu pulang,
payung tua itu tertinggal
masih terbuka,
masih menadah langit,
seolah ingin menjaga
arwah yang mulai tenang
dan jiwa yang baru saja
dibasuh kembali
dalam hujan.
2025
—-
*Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, dan menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Abdul Wachid B.S. lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (15/1/2019). Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (2018), Bunga Rampai Esai Sastra Pencerahan (2019), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (2022). Melalui buku Sastra Pencerahan, Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).***