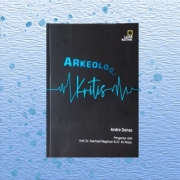Kunstkring dengan Dansa, Era Merdeka dengan Tuna Wisma
Pameran Seni Rupa Berbagai Era – Bagian 1
Oleh Agus Dermawan T.
Pada 100 tahun silam bentuk pameran sudah ditentukan oleh kebijakan pemilik lembaga pemamer. Ada suatu masa seniman memiliki otoritas untuk menentukan gaya pamerannya sendiri. Hendra Gunawan adalah contohnya.
————-
PERTUMBUHAN dan perkembangan seni rupa Indonesia tak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pameran yang diadakan oleh institusi pemamer. Karena dengan pameranlah karya-karya itu hadir ke mata publik. Dengan pameran gagasan perupa tersosialisasi ke tengah masyarakat, dan karya-karya perupa terdistribusi ke banyak pihak.
Dalam tilikan sejarah, pameran seni rupa Indonesia memiliki karakter dan gaya yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Tilikan bisa dimulai ketika Bataviasche Kunstkring mengawali kegiatan seni rupanya pada 1924. Seratus tahun yang lalu.
Kunstkring, dengan daftar harga
Bataviasche Kunstkring diresmikan pada April 1914, dengan menempati gedung yang dibangun oleh PAJ Moojen, di Heutszboulevard, yang kini jadi Jalan Teuku Umar, Jakarta. Seonggok gedung istimewa bergaya art nouveau yang kemudian dijadikan Kantor Imigrasi, lantas disulap jadi Buddha Bar yang kontroversial, dan berubah lagi menjadi Tugu Kunstkring Palais pada tahun 2000-an.
Pada mulanya gedung ini digunakan untuk pertunjukan musik, konferensi dan seminar. Namun pada 1924, sesuai dengan namanya, “Lingkaran Seni Batavia”, mulai dipakai untuk menggelar karya-karya seni rupa. Pada tahun 1925 eksistensi gedung kunstkring sebagai rumah seni rupa dirayakan lewat pameran besar arsitektur.
Pada tahun 1930-an Bataviasche Kunstkring – kita sebut saja BK – telah menjadi penyelenggara pameran paling dominan. Meski BK lebih mengutamakan karya para perupa Hindia Belanda, dengan sekali-sekali secara “sangat selektif” menyisipkan karya-karya seniman bumiputera.

Lukisan seniman Hindia Belanda G.Bettinger. Orang-orang bumiputera menonton seniman Belanda yang sedang melukis. (Sumber: Agus Dermawan T.)
Institusi ini merupakan lembaga puncak seni rupa Hindia Belanda, karena ia membawahi kunstkring-kunstkring lain di berbagai daerah, seperti Bandungsche Kunstkring, Surabayasche Kunstkring dan seterusnya. Sebagai kunstkring pusat, BK lantas sering memamerkan karya-karya terbaik dari anggota kunstkring dari berbagai daerah, dalam paket yang disebut “Bondscollectie – Schilderijen en Teekeningen”. Pameran gabungan yang cukup besar dan diingat sejarah adalah yang diadakan pada 11 Maret sampai 11 April 1937.
Pameran di BK sebagian besar prestisius. Bahkan institusi yang dikuratori Jan Frank dan dipimpin Nyonya J De Loos-Haaxman ini pernah menggelar koleksi PA Regnault, yang menyajikan lukisan Van Gogh, Pablo Picasso, Marc Chagall dan lain-lain. Sehingga pameran selalu menarik keinginan orang untuk menonton. Itu sebabnya pameran di sini mengenakan tiket 25 sen gulden sekali masuk. Sementara siapa pun yang berkunjung sedapat mungkin bisa berbahasa Belanda. Sehingga bumiputera yang jelata jangan harap bisa menonton.
Bagaimana dengan perangkat informasi dan apresiasinya? BK menerbitkan katalog hitam-putih sederhana, yang kala itu tentu dianggap bagus. Biasanya dalam katalog hanya terdapat sepercik prakata pengelola galeri. Namun dalam penulisan riwayat hidup mereka nampak bersungguh-sungguh, walaupun tidak dalam kolom besar.

Katalogus sederhana terbitan Bataviasche Kunstkring. (Sumber: agus Dermawan T.)
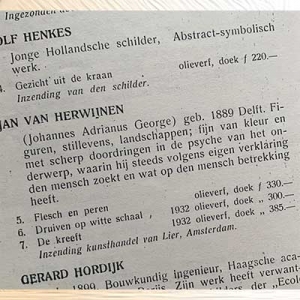
Isi katalog yang diterbitkan lembaga pemamer Hindia Belanda, dengan daftar harga.(Sumber: Agus Dermawan T.)
Yang menarik, di setiap sisi kanan judul lukisan selalu terdapat harga. Misalnya : Emil Rizek, Hanengevecht – Bali, olieverf, paneel…f.75,- L Van den Berg, Straatje in Oud-Batavia, olieverf, doek …f.125,- Frida Holleman, Kinderkopje, olieverf, doek….f.100,- Henri van Velthuysen, Soendaneesch meisje, olieverf, paneel….f.175,- Bagi mereka, pameran adalah juga forum penjualan.
Di Jakarta pada kurun itu juga bergiat galeri milik penerbit dan toko buku Kolff yang disebut Kunstzaal Kolff, di Noordwijk 13 (seberang Istana Negara, kini jalan Juanda, Jakarta). Sementara di Bandung yang paling terkenal adalah St Lucasgilde dan Hotel Savoy Homann. Di Surabaya dan di Malang ada Societeit Concordia. Oleh karena mereka mengacu kepada gaya penyelenggaraan BK, maka semua acara dan perangkat apresiasinya mirip-mirip saja.
Dalam acara pembukaan para tamu diharapkan berpakaian formal, menggunakan dasi, berpantalon necis ala hartawan borjuis. Yang perempuan hadir dengan gaun seperti yang dikenakan puteri bangsawan Eropa. Openingsceremonie itu tak jarang diisi acara dansa. Aturan berpakaian itu otomatis mencerminkan kebijakan diskriminasinya atas bumiputera. Suatu hal yang menyebabkan Sudjojono dan kawan-kawannya mengomel, dan lantas mendirikan Persagi (Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia) tahun 1938.

Gedung Bataviasche Kungstkring di Heutszboulevard, Batavia. Pembukaan pameran kadang dengan musik dan dansa di taman. (Sumber: Agus Dermawan T.)
“Tak banyak yang tahu, selain mewadahi para pelukis Indonesia yang ingin berjuang lewat seni lukisnya, Persagi juga menampung perasaan gondok para pencinta seni bumiputera yang tak dibukakan pintu oleh orang Belanda. Dalam seni rupa, rambu Verboden voor Honden en Inlander (Priboemi dan Andjing dilarang masoek) sangat tidak boleh berlaku!“

Papan peringatan diskriminatif “Verboden voor Honden en Inlander”. (Sumber: Agus Dermawan T.)
Era Jepang, pameran untuk masyarakat
Kegiatan pameran Bataviasche Kunsktkring berakhir tahun 1942 kala Jepang datang. Jepang melihat diskriminasi institusi Belanda tersebut, dan mereka lantas mendirikan Keimin Bunka Sidhoso. Dalam lembaga ini dibentuk pusat latihan melukis yang melibatkan seniman Indonesia sebagai pendidik, seperti Basoeki Abdullah dan Sudjojono. Bahkan lembaga budaya Jepang ini memberikan penghargaan kepada lukisan-lukisan terbaik yang dipamerkan.
Penjajah baru ini mengorganisasi pameran dengan semangat progresif. Jika Belanda merancang pameran eksklusif, maka Jepang justru membuka pintu pameran selebar-lebarnya untuk khalayak ramai. Agus Djaya dan kawan-kawannya di Persagi mengatakan bahwa cara Jepang ini untuk “mencari muka”. Semboyan politik Jepang yang didengungkan kala itu adalah “Bersatoelah Bangsa Asia”. Sementara semboyan spesifik yang berkait dengan kebudayaan adalah “Ajia-no Ajia” yang maknanya kebudayaan Asia untuk bangsa Asia.
Jepang memang sangat aktif bikin pameran di berbagai tempat yang gampang diakses publik. Sejak Maret 1942 sampai April 1944, ada 14 acara pameran besar digelar. Jumlah luar biasa untuk era itu. Pada zaman ini reputasi rekor penonton pameran juga terpecahkan. Pagelaran “Tenno Heika: Techo-setsu” 1944, atau pameran untuk memperingati ulang tahun Kaisar Jepang, misalnya, dalam tempo 10 hari ditonton oleh 11.000 orang! Pameran yang melibatkan 60 pelukis Indonesia ini diselenggarakan di gedung Keimin Bunka Sidhoso, Jalan Noordwijk 39 (di deretan Istana Negara, yang kini jadi Jalan Veteran, Jakarta).
Pameran di era Jepang juga menerbitkan katalog, walau dalam jumlah tak banyak dan dalam cetakan sederhana. Sehingga terkesan itu sebagai dokumen saja. Penjualan juga diadakan, meski masa itu keadaan ekonomi sungguh susah. Sehingga sungguh ajaib apabila dalam pameran Tenno Heika, ada sembilan lukisan Indonesia dibeli oleh Pemerintah Jepang, yang lantas diikutkan dalam pameran keliling Asia Timur Raya.
Semangat ala Jepang ini berhasil menghinggapi jiwa para seniman Indonesia di masa Indonesia merdeka. Sehingga para seniman pejuang tak terlampau ingin menggelar karyanya di gedung yang dianggap eksklusif. Andai di tempat khusus, seniman membuka pintu lebar bagi masyarakat banyak. Pameran Hendra Gunawan bisa diambil sebagai contoh.
Pelukis ini mengadakan pameran tunggal di Gedung Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), jalan Malioboro, Yogyakarta, 1946. Dalam acara ini Hendra melibatkan belasan gelandangan sebagai “pagar ayu” untuk menyambut Presiden Sukarno yang akan meresmikan pameran. Ide Hendra tentu bukan mencari sensasi, namun untuk meneruskan spirit keterlibatan seniman dengan rakyat yang masih menderita. Lalu, pameran pun menjadi seperti pesta rakyat.
Era 1950-1960, kembali eksklusif
Namun pameran bervisi kerakyatan seperti di atas pelan-pelan kikis setelah Indonesia memasuki tahun 1950-an. Sehingga visi kerakyatan ala Keimin Bunka Sidhoso dan Hendra terasa sebagai transisi saja. Faham modernisme yang memandang bahwa seni lukis dan seni rupa lainnya merupakan benda-benda eksklusif yang layak dilindungi dari jamahan publik massal, menyeret karya seni rupa ke tempat yang “lebih aman”. Karya seni pun kembali masuk wilayah yang relatif tertutup. Dengan begitu panitia juga mengundang penonton yang terseleksi. Kesimpulannya: tuna wisma tidak bisa masuk!
Maka sejak 1955 muncul lagi ruang-ruang seni eksklusif, yang sengaja memposisikan seni rupa (terutama seni lukis) sebagai konsumsi level sosial tertentu. Pemilik mengkondisikan bahwa seni rupa adalah benda berharga yang seharusnya mempunyai rumah, dan memiliki potensi hak tawar. Lukisan, karya seni yang paling populer waktu itu, bahkan diangkat sebagai “tanda mata budaya” yang harus dimiliki oleh orang-orang Indonesia berkelas sosial tinggi, berpendidikan, berwaswasan. Lebih jauh, seni lukis ditawarkan sebagai konsumsi ekspatriat dan turis kelas satu.
Menariknya, pemahaman yang mengembalikan seni rupa kepada komunitas kelas menengah ini justru disulut oleh pameran-pameran yang sifatnya politik. Misalnya pameran yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Di sini seni diposisikan sebagai anak budaya yang harus diserap oleh masyarakat Indonesia terpelajar. Sementara masyarakat terpelajar Indonesia adalah kelas menengah, bukan masyarakat kelas bawah.
Pemahaman ini kemudian juga merasuk ke dalam benak banyak komunitas intelektual. Seperti Sin Ming Hui misalnya, organisasi kelompok Tionghoa yang bermarkas di kawasan Jakarta Kota. Organisasi yang ditokohi Auwyong Peng Koen (PK Oyong, pendiri Kompas), pengamat politik Tjan Tjoen Hok (Harry Tjan Silalahi) dan dokter Loe Ping Kian ini pada medio 1950-an membentuk seksi pemamer yang mengundang apresiator kelas menengah kalangannya. Mereka mendirikan institusi Tjandranaja.
Di Jalan Gajah Mada, Hotel Des Indes aktif menyelenggarakan pameran. Hotel ini ditahbiskan sebagai tempat pagelaran prestisius, dan jadi barometer bagi para seniman yang sudah matang dan mapan. Hotel Des Indes senantiasa menghadirkan pameran besar yang diikuti oleh banyak pelukis. Andaipun pameran tunggal, yang ditampilkan adalah seniman yang benar-benar siap menggelar karya dalam jumlah banyak. Pembukaan pameran juga dihiasi para pria berdasi dengan jas licin serta para wanita yang dibalut kilau gaun satin.

Hotel Des Indes di Jalan Gajah Mada, Jakarta, yang sering menyelenggarakan pameran bergengsi tahun 1950-an. (Sumber: Agus Dermawan T.)

Presiden Sukarno dalam pembukaan pameran lukisan di Hotel des Indes. (Sumber: Agus Dermawan T.)
Apresiasi seni rupa ala komunitas kelas menengah ini mendorong Presiden Sukarno untuk meminta James Pandy, pengelola biro wisata Thomas Cook di Indonesia, agar membuat galeri di Pantai Sanur, Bali. Lukisan dipasok dari Jakarta, Surabaya dan Ubud. Galeri Pandy lantas acap menggelar acara pameran yang ramai dihadiri orang-orang kaya dan terpandang.
Kelahiran Galeri Pandy merangsang lahirnya galeri-galeri di Ibukota. Pada tahun 1958 lahir Galeri Merdeka di Jalan Tibah, Jakarta Selatan. Di kawasan Menteng ada Galeri Banowati, dan lain-lain. Galeri-galeri ini mulai memiliki program pameran berkala, dengan orang-orang parlente yang bisa masuk ke dalamnya. Namun meski punya tujuan jelas, institusi pemamer itu sengaja tidak memilih gaya dan selera seni rupa yang tegas. Lantaran tujuan utamanya adalah sekadar mendistribusikan seni rupa kepada para pencinta seni yang berbagai-bagai latarbelakangnya.
Tahun 1962 muncul Prasta Pandawa yang didirikan oleh arsitek Hoo Tjoe Heng, alias Hendra Hadiprana. Galeri ini memulai tradisi koleksi yang spesifik, dengan pilihan gaya dekoratif modern. Dalam berbagai event, galeri selalu menyuguhkan penyajian yang cantik, elegan, dengan pernak-pernik elemen tradisional Indonesia. Tamunya banyak ekspatriat kelas tinggi serta hartawan Indonesia. Status tamu ini mendorong galeri untuk membuat acara berkelas bangsawan. Katalog, brosur dan kitab penyerta pameran selalu diterbitkan dalam edisi luks. Galeri eksklusif ini pada kemudian hari berubah nama menjadi Galeri Hadiprana.

Hendra Hadiprana ditengah acara pembukaan pameran di Galeri Hadiprana. Semua berpakaian formal. (Sumber: Agus Dermawan T.)
***
*Agus Dermawan T. Pengamat Seni. Narasumber Koleksi Benda Seni Istana Presiden.