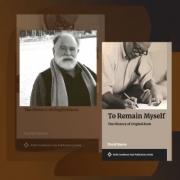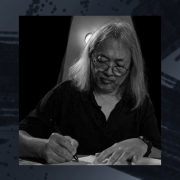Merawat Ingatan Dengan Berjalan Kaki
Oleh Razan Wirjosandjojo*
Sejak awal tahun 2024, saya memulai aktivitas yang membuat bangun tidur saya lebih pagi di hari Minggu. Waktu senggang di akhir pekan saya luangkan untuk mengikuti tur sejarah yang diselenggarakan oleh Soerakarta Walking Tour, sebuah komunitas yang secara rutin mengadakan tur keliling di kota Solo dan sekitarnya. Selain menjadi sarana sight-seeing, tur yang mereka adakan juga memberikan edukasi sejarah bagi peserta yang mengikuti. Pertama kali mencoba ikut dalam tur ini, saya ditemani oleh mas Apri, salah satu anggota Soerakarta Walking Tour yang berada dalam komunitas ini sejak awal terbentuknya pada tahun 2012.
Komunitas ini lahir dengan nama awal Blusukan, dengan anggota peggiat sejarah yang tertarik untuk menyusuri kota Solo. Pada tahun 2015, mereka mengganti nama menjadi Laku Lampah, untuk menghindari politisasi dikarenakan istilah “blusukan “menjadi jargon walikota Solo pada saat itu. Komunitas ini menajamkan fokusnya pada kunjungan situs-situs sejarah dengan durasi yang panjang. Soerakarta Walking Tour mulai terbentuk pada 2017 sebagai proyek sampingan. Setelah mengalami peralihan struktural dan pandemi, saat ini mereka mengalungi nama “Soerakarta Walking Tour” dan berkembang menjadi komunitas yang menyelenggarakan tur sejarah bagi publik umum di kota Solo. Rute yang mereka tawarkan melintasi sudut-sudut kota Solo yang jarang tampak ke “permukaan”. Keterlibatan saya di tur ini perlahan mengisi ketidaktahuan saya terhadap kota ini.

Instagram Soerakarta Walking Tour
Upaya mendaftarkan diri untuk mengikuti tur mereka selalu saya lalui dengan proses yang cukup menegangkan. Pengumuman tur yang mereka siarkan lewat akun Instagram @soerakartawalkingtour kerap ludes dalam hitungan menit. Kuotanya memang tidak banyak dibuka dan biasanya para peserta yang sudah akrab dengan tur ini akan bersiaga menjelang jam registrasi. Jika Anda ingin merasakan sensasi war ticket dengan skala kecil, Anda bisa coba mendapatkan slot tur keliling ini. Semisalpun tidak dapat, kekecewaannya tidak akan sebesar kehilangan kesempatan menonton konser favorit Anda. Selalu ada kesempatan di akhir minggu selanjutnya, atau mungkin bisa berkenalan dengan salah satu anggotanya agar mendapatkan lajur orang dalam.
Biaya untuk mengikuti tur ini juga terbilang mulia, yaitu seikhlasnya. Saya pikir keputusan itu menarik, ethos langka di kalangan pemuda yang kini semakin diimpit dengan orientasi keuntungan (profit). Sampai dengan tulisan ini selesai ditulis, saya belum sepenuhnya memahami “dapur” kerja mereka. Sekilas yang saya ketahui dari mas Wahid, hasil urunan peserta dikelola bersama dengan pemasukan dari tur-tur khusus seperti private tour dan special tour. Storyteller dan dokumentasi yang bertugas mendapatkan bagian, lalu sebagian disimpan ke dalam kas untuk biaya pengembangan rute, ataupun kegiatan lain. Bagaimanapun, aspek kesukarelaan tetap menjadi salah satu fondasi krusial dalam kelangsungan komunitas independen ini.

Mas Nino sedang menceritakan latar belakang dari satu pohon di daerah Kampung Sewu. (Sumber: Dok. Soerakarta Walking Tour)
Saat ini mereka memiliki puluhan rute yang tersebar di seluruh wilayah Solo Raya, dan masih terus berkembang. Tidak hanya di lingkar kota Solo, rute mereka merambah Klaten, Boyolali, dan sekitar Solo Raya. Semua rute merangkai titik-titik dan narasi kesejarahan, mengacu pada sumber-sumber kepustakaan dan bukti fisik yang dapat ditemukan. Pengalaman pertama saya mengikuti tur privat dengan mas Apri awalnya terkesan seperti tuntunan tour guide pada umumnya, karena lokasi yang saya pilih (atas permintaan teman yang saya ajak) adalah Pura Mangkunegaran yang sudah memiliki kesan turistik yang kuat. Namun ketika kami diajak masuk ke bekas kandang kuda yang telah “disulap” menjadi pemukiman warga, saya merasa ada pengalaman menarik yang ditawarkan melalui tur ini.

Kamera rusak saya mencoba menangkap lelucon mas Apri dan Wahid ketika mengikuti rute di sisi Utara Pura Mangkunegaran. (Sumber: Dok Pribadi)
**
Melihat yang Tidak Tampak
Pada tur-tur yang telah saya ikuti, kami dibawa berkeliling selama dua jam oleh para pemandu yang mereka sebut storyteller. Radius perjalanannya tidak terlampau jauh, cukup sebagai pemanasan pagi sambil menikmati suasana akhir pekan di wilayah tersebut. Satu rangkai perjalanan tersambung dari beberapa cerita / narasi sejarah. Cerita tersebut mereka sematkan pada artefak yang masih utuh atau tersisa di wilayah tersebut. Situs dan artefak sebagai “monumen historis” atas cerita yang dituturkan sering kali tampak tidak terawat secara khusus, baik oleh masyarakat umum atau pemerintah. Sering kali situs / objek tersebut berada berdampingan, menyatu, berhimpit, ndesel, nyelip, nyungsep, ndelik, bahkan “menguap” dengan keseharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Rangkaian cerita pada setiap tur tidak selalu bersambung/berkaitan. Kadangkala ada satu tema besar yang melingkari situs-situs yang dikunjungi, namun tiap-tiap situs juga dapat menyimpan cerita dari lini waktu yang berbeda, meskipun situs tersebut bersebelahan. Walaupun cerita tidak linear atau kadang bercampur-aduk, potongan-potongan informasi yang saya saksikan selama berjalan kaki dalam tur ini membentuk kolase, menjadi gambaran abstrak atas wilayah yang dikunjungi. Citra yang tergambar di dalam benak saya sering kali absurd karena melihat pergeseran nilai dan fungsi ruang di wilayah tersebut. Gesekan dan tarikan antara situs sejarah, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya memunculkan ketegangan dalam diri saya.
Artefak sejarah yang kami kunjungi di ruang publik sering sekali tampak dengan kondisi yang getir. Sumur Kamulyan (Kemuliaan) yang pernah dimaknai sebagai sumber air suci di daerah Kemlayan, kini dikelilingi oleh baju, keset, dan perlengkapan dapur kotor penduduknya. Kandang kuda yang dibangun di dalam kompleks Pura Mangkunegaran, disulap menjadi rumah-rumah liar, fondasi lamanya dibongkar agar bisa disemen menjadi dinding-dinding rumah. Makam-makam pun harus terimpit laju pembangunan rumah pemukiman. Ada yang kejepit di antara rumah, ada pula yang dibangun di tengah rumah, sehingga nyekar ke makam tersebut harus melalui teras rumah seseorang yang tidak ada hubungan apa pun dengan jenazah yang beristirahat di balik makam itu.

Kondisi makam yang terimpit realitas hari ini. (Sumber: Dok. Pribadi)
Tur ini juga kerap mengajak saya untuk melihat artefak atau situs sejarah yang wujudnya sudah tidak ada. Ketiadaan itu coba ditanggulangi oleh Soerakarta Walking Tour dengan menunjukkan foto, ilustrasi, atau catatan yang bisa dibayangkan. Baik melalui foto buram warna hitam-putih, atau layout peta lawas pada masa Hindia Belanda, saya mengandalkan imajinasi untuk membayang-bayang bentuknya seperti apa, dindingnya warna apa, besarnya seberapa. Secara tidak langsung, tur ini membangun kembali bangunan dan artefak tersebut di kepala setiap peserta dengan membebaskan bagaimana setiap peserta melihat dan membangun kembali situs itu di pikirannya.

Hasna dan Ayas sebagai storyteller sedang menjelaskan kilas sejarah maestro keroncong, Gesang di depan rumahnya di daerah Kemlayan. (Sumber: Dok. Pribadi)
Tur ini memainkan rantai cerita dengan cukup jenaka, walaupun terkadang kentara “berusaha”. Tutur sejarah yang diberikan juga cukup mudah untuk dipahami untuk khalayak umum. Terkadang bagi saya yang ingin tahu lebih menjadi tidak memuaskan, namun ketidakpuasan itu saya anggap sebagai siasat untuk menumbuhkan keingintahuan. Jika ingin tahu bisa tanya atau cari sendiri. Penuturan cerita juga tidak terkesan menceramahi, justru kerap dikembalikan kepada peserta melalui pertanyaan, atau justru peserta ikut bercerita dari pengetahuannya masing-masing. Sejarah tidak lagi menjadi dogma, diperkenalkan kembali sebagai sebuah siluet titik-titik yang garisnya bisa disambung bersama.
Suasana ringan dan menyenangkan yang tur ini tawarkan cukup melipur ketegangan peserta yang terus-menerus mengalami sejarah sebagai hantu, yang keberadaannya tidak dipercaya namun tetap dihadapi dengan rasa takut dan asing. Padu-padan antara humor dan kenyataan yang ironis sesekali mengubah ruang perjalanan menjadi jalan-jalan di dunia fantasi. Sedikit-banyak, tur ini mengajak saya merasakan kenyataan masyarakat kita yang memperlakukan sejarah seperti dongeng-dongeng masa lampau yang heroik dan romantis, namun tidak pernah dianggap berfungsi dan aktual.

Seekor burung bertengger di atas kepala patung Mangkunegara VII Di Pura Mangkunegaran. (Sumber: Dok. Pribadi) **
Melaku
Satu poin elementer yang hadir dalam tur ini adalah kesempatan untuk memaknai esensi laku jalan kaki. Kesan yang mendalam justru tumbuh tidak dari titik-titik kunjungannya belaka, namun dari peralihan antar titik-titik tersebut. Saya menikmati proses jalan kaki yang santai, melihat aktivitas akhir pekan penduduk hari Minggu yang lamban, terkadang dengan sedikit hajatan ala orang Jawa yang memang hobi pesta di akhir minggu. Semua diselimuti sinar matahari yang masih cukup nyaman memeluk kulit dan mata.

Ayam di Kemlayan pada hari Minggu (Sumber: Dok. Pribadi)
Pada pengalaman yang lebih umum, jalan kaki memberi saya waktu dan tenaga untuk mencerna informasi yang telah diterima. Tapak-tapak kaki di antara titik kunjungan menjadi waktu saya untuk mengolah dan berpikir ulang tentang informasi sejarah yang baru saja diceritakan atau yang lama tergenang di pikiran saya selama seminggu ke belakang. Jalan kaki menjadi piston yang menciptakan panas di dalam tubuh dan memproses seluruh bahan bakar pengalaman yang telah diisi sebelumnya menjadi energi pengetahuan dan wawasan, baik tersimpan di dalam kesadaran pikir atau kesadaran tubuh.
Kata “melaku” dalam bahasa Jawa berarti berjalan kaki, namun juga secara metaforis berarti suatu proses pergerakan/perjalanan dalam ruang dan waktu. Ungkapan “wes mlaku opo urung?” itu justru lebih sering saya dengar sebagai ungkapan untuk memastikan jika satu atau rangkaian subjek, objek, atau peristiwa sudah berjalan dengan semestinya (laras/leres). Jika itu satu pertunjukan, berarti sudah mulai pentas dengan lancar. Jika itu satu pekerjaan, berarti pekerjaan itu sedang dikerjakan tanpa terhambat. “Ora mlaku” juga akhirnya kerap digunakan untuk mengungkapkan bahwa komponen kerja tersebut menemui hambatan dan tidak bekerja dengan semestinya, bahwa komponen tersebut tidak menunjukkan keselarasan gerak dengan ruang dan waktu di tempatnya berada.
Saya sendiri memaknai kata tersebut dengan mengambil sumber kata “laku”. Melaku(kan) dapat berarti luas sekali, hampir merujuk pada setiap laku atau aksi yang bisa dikerjakan oleh gerak badan kita. Mlampah (versi alus dari melaku) juga merujuk pada pemaknaan yang serupa. Lebih jauh dari sekadar laku keseharian (laku pedinan), melaku dapat merujuk pada kualitas gerak (kerja) seseorang.
Jalan kaki sebagai laku yang sederhana dapat merangkul makna kerja gerak tubuh secara luas melalui kata “melaku”. Kita bisa membaca kemalasan seseorang dari seretan jalannya, gaya kepemimpinan dapat diperhatikan dari cara berjalan, pengkarakteran dalam tari klasik pula mendesain klasifikasi teknik berjalan. Mbak Melati sering mengomentari cara jalan saya yang sering cepat-cepat. Mengubah diri bisa berangkat dari memperhatikan cara kita berjalan kaki, dan sebaliknya. Jalan kaki dalam kehidupan yang serba oke gas saya maknai sebagai upaya untuk menyadari berbagai komponen dalam diri yang bergerak sebagai bagian dari jaringan hidup.
***
Belajar Jujur Dari Berjalan Kaki
Pada saat saya kecil, saya pernah ketahuan berbohong kepada ayah saya. Bekal yang ia buat selalu saya bawa kembali ke rumah dalam keadaan habis. Jika ditanya, saya bilang kalau saya yang makan dan menghabiskan. Pada kenyataannya sering saya tukar dengan bekal punya teman, jika ada sisa saya bagi ke anjing saya sebelum masuk rumah. Hal itu ketahuan dan membuat ayah saya marah besar. Saya dihukum selama 3 bulan untuk berangkat dan pulang ke sekolah dengan berjalan kaki. Sepanjang 4 kilometer, kepala saya hanya berisi ada rasa kapok dan takut dengan ayah saya, serta sedikit rasa malu karena sering ditanya teman sekolah dan guru kenapa tidak diantar-jemput. Pada saat itu sekolah saya tidak ada yang berangkat sekolah jalan kaki lebih dari 1 kilometer. Selain karena alasan keselamatan (tidak ada trotoar di jalan raya), semua orang tua murid lebih memiliki mengantar anak dengan opsi yang lebih cepat.
Pengalaman ini menjengkelkan ketika saya masih kelas 3 SD, namun berkembang menjadi obsesi ketika saya SMA. Saya jadi terbiasa berangkat tanpa kendaraan, selama satu tahun full saya berangkat sekolah dengan berlari. Jarak dari rumah ke sekolah kurang-lebih 7 kilometer, saya tempuh sekitar 30-45 menit. Kebiasaan yang tidak umum bagi guru dan teman-teman saya namun buat saya cukup menyenangkan, antusiasnya semakin besar karena saya aktif menari dan naik gunung, sehingga laku berlari mendukung keperluan saya untuk meningkatkan stamina dan daya serap oksigen (VO2 MAX). Pada saat itu, saya tidak begitu menggubris makna-makna yang dapat saya petik tentang berjalan kaki/berlari, saya lakukan hanya karena membuat hati senang.
Melihat pengalaman yang lalu pada hari ini, saya kira berjalan kaki tidak hanya memberi efek jera bagi Razan kecil, atau kebugaran bagi Razan remaja, namun juga memberikan kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan sekitar dengan lebih dekat dan rinci. Berjalan kaki membantu saya untuk melihat kaitan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya di jalan yang biasanya terlalu cepat lewat jika dilihat dari kendaraan bermotor. Saya bisa menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, mengamati hal-hal kecil yang saya lewati. Tidak hanya yang di luar diri, berjalan juga menjadi cara untuk melihat ke dalam. Berjalan kaki sering memberi saya inspirasi, mengingatkan pada apa yang sempat tergeletak di pojok pikiran.
Berjalan kaki juga membuat saya belajar mengendalikan rasa kesal karena di Jakarta (dan pada banyak jalan perkotaan di Indonesia) jalan kaki tidak pernah memiliki ruang yang aman dan nyaman. Pengalaman jalan kaki di Jakarta hampir selalu dilakukan di pinggir jalan atau di trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat jualan, parkiran, atau apa pun selain untuk pejalan kaki. Kadang saya bayangkan saja seperti halang rintang, agar merasa tertantang menembus tali-tali tenda lamongan, atau menggocek kursi-kursi penjual Sate Padang. Keserempet atau kesandung adalah hal yang terpaksa dibiasakan untuk tetap berjalan kaki di tengah kebudayaan masyarakat motor bebek. Kehilangan budaya berjalan kaki secara tidak langsung menjadi gejala bahwa ruang-ruang berbagi tidak lagi memiliki makna, semua menjadi serba privat, instan, dan immediate (langsung tanpa proses).

Performans “Kemboja Nestapa” saya lakukan dengan berjalan kaki mengantar pohon kemboja sepanjang 30 kilometer dari rumah menuju makam ayah saya, dilakukan untuk memberi kesempatan bagi tubuh untuk memproses duka. (Sumber: Dok. Pribadi)
Sejarah sebagai ingatan masa lalu tidak hanya tersimpan di buku atau prasasti candi, ia juga terukir di sudut-sudut tubuh kita. Terkadang menusuk karena ia tersebar pada setiap otot dan syaraf, terkadang menyesakkan karena ia mengendap di paru-paru dan kerongkongan, terkadang buat pusing karena ia menggumpal di tengkorak. Semuanya hidup bersama tubuh kita yang terus memahat sejarah baru di bagian tubuh yang lain. Maka bisa jadi kanker dan tumor adalah wujud dari ingatan-ingatan yang tidak terawat, trauma yang tidak pernah ditengok.
Kombinasi ingatan (sejarah) dan laku berjalan kaki memberikan saya pengalaman untuk menjenguk kembali ingatan tersebut, agar tidak hanya dimengerti (dalam pikiran). Melalui berjalan kaki saya bisa menyentuh kasarnya, menghirup wanginya, rasakan hawanya, mendengar desisnya, melihat panasnya, menangkap getarnya. Jalan kaki menjadi proses untuk merawat ingatan yang saya kandung di dalam tubuh.

Menghirup bunga Melati ketika mengikuti rute tur di daerah Pengging. (Sumber: Dok. Soerakarta Wlaking Tour)
—–
Sumber:
—-
*Razan Wirjosandjojo adalah seniman yang saat ini tinggal di Solo, Indonesia. Ia menyelesaikan studinya di Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta. Razan mulai aktif menari pada tahun 2010 dengan mempelajari berbagai disiplin gerak dari berbagai ruang dan komunitas di Jakarta hingga tahun 2017. Setelah pindah ke Solo, ia belajar bersama Melati Suryodarmo sejak tahun 2018 hingga sekarang. Sejak 2020, Razan mulai menciptakan karyanya sendiri dan memperluas sudut pandangnya dalam melihat tubuh sebagai poros gagasan dan mengembangkannya dalam berbagai wahana. Saat ini Razan merupakan murid dan staf paruh waktu di Studio Plesungan.