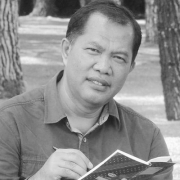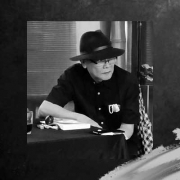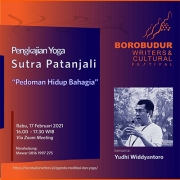Verba Volant, Scripta Manent
Oleh. Mudji Sutrisno SJ.*
Kata-kata melenyap,
terbang karena tak ditulis
sedangkan buku atau tulisan itu ‘kekal’.
Semboyan ini tak hanya berlaku bagi budaya yang memperjuangkan tulisan atau buku seperti Kompas, Media Indonesia, Kanisius penerbit serta pejuang-pejuang tulisan yang terus masih berjuang untuk ‘terbuka pula’ pada era digital di budaya digitalisasi kini juga terutama di media sosial. Bahkan sudah baik beranjak maju lagi dengan era AI (Artificial Intelligence) yang menuntut pertanyaan cerdas ke AI agar dijawab cerdas pula.
Namun didiskusikan akhir, didiskursus tetaplah subyek manusia yang pegang kendali, secanggih apapun AI. Sebab ketika seseorang mau cepat minta tolong ke AI untuk karangan atau tulisannya, akan cepat ketahuan bahasa standarnya beda dengan bahasa si subyek penulis aslinya. “Ah, kok ini aku menelisik, ‘ternyata’ bukan bahasamu yang biasa”.
Ketika pulang ngikut mobil wartawan tulis Kompas dari temu 15 tahun Aliansi Kebangsaan di Hotel Sutan 29 Oktober 2025, sekaligus pengenangan penting Hari Sumpah Pemuda tanggal berdirinya Aliansi Kebangsaan. Saat itu disadari (artinya, masuk ke dalam kesadaran kita) bahwa kita punya kewajiban untuk terus berkomunikasi pada gen Z dan sesudahnya, mengingat kita punya generasi dongeng dan lisan atau tutur, generasi tulis atau buku dan gen digital sampai AI.
Berkomunikasi, inilah satu-satu memakai ungkapan bahasa yang mengekspresikan identitas kita. Inilah yang dalam salah satu seminar, ada yang bertanya kritis: “apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita di situasi krisis ini?”. Jawaban yang muncul mencengangkan: “NARASI”. Bukankan lewat bahasa orang tua menarasikan literasi ke anak-anak? IBU, ibu aksara ini mengungkap bahwa tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini tanpa rahim ibu (dalam kerjasamanya dengan bapak dan Tuhan).
Kisah atau narasi itu adalah ungkap kisah semisal narasi yang mau mengatakan bahwa di Jalan Pegangsaan Timur 56, yang di lapangan proklamasi ada tanda halilintar, mau di narasikan bahwa disinilah 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Dan harus dicatat dalam konstitusi, diucapkan bahwa “Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini dinyatakan 2
kemerdekaan RI”. Dahsyat, kemerdekaan kita sebagai bangsa itu berkat rahmat Tuhan, anugerahNya. Maka dibela oleh pahlawan hebat tertulis, mau mereka yang tanpa kata, dengan diam menjadi “pahlawan”. Pada merekalah kita bersyukur dan bersyukur, “verba volant scripta permanent”, maka menarik dalam bimbingan skripsi mahasiswa, banyak ide-ide bagus tapi masih konsep di akal budi. Bagus, bagus diceritakan lisan. Dosen pembimbingnya menutup dialog itu dengan 3 kata singkat yaitu TULIS, TULIS dan TULIS. Lalu mahasiswa akan belajar dengan logika waras budinya, mengurutkannya dan mengkalimatkannya. Bila terpengaruh amat oleh tulisan model SMS maka pendek-pendek dan harus belajar diperpanjang dengan bahasa kalimat panjang urai. Saya teringat bahwa jauh sebelum Covid 19, di sekolah tinggi kami dikreasi mata kuliah baru tambahan yaitu bahasa Indonesia, yang isi substansialnya adalah karang mengarang yang logis, nalar dan teratur. Menarik untuk dicatat bahwa sampai tahun 2025 ini, mata kuliah itu masih terus ada. Mengingat bahwa skripsi tertulis baik dan logis mensyaratkan ini.
Ada 2 pembeda yang disepakati antara ciri budaya digital yang banyak ada bahkan berjibun di medsos dengan budaya tulis. Yang satu menekankan ciri proses: yang tak bisa tergesa-gesa ngawur! Yang satu itu instant, segera atau langsung hasil, langsung lompat. Apakah yang diajari bahwa hidup itu sebuah proses bisa menyadari (membatin dalam kesadarannya) sehingga menarasikan ke generasi lain soal proses itu. Bukankah 9 bulan dikandung, masa anak-anak, remaja dan masa dewasa, akil balik, menua dan masa senja usia dan tua, ini semua adalah sebuah proses kehidupan?
Bila itu dinarasikan ke generasi yang instant, mau hasil cepat dan kilat, inilah narasi itu, diwariskan! Namun, bagaimana bila narasi yang diwariskan ditanggapi dengan EGP (memang gue peduli?). Disinilah proses komunikasi kesadaran jadi penting. Adakah terjadi gap, jurang komunikasi? Kita sudah diwarisi dalam narasi oleh pendidik ulung kita: Ki Hadjar Dewantara “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” (baca: di depan (pemimpin) mencontohi, memberi teladan tekad, ditengah membangun kehendak (kuat), di’belakang’ meneguhkan, menguatkan). Masukkah dalam pendidikan kita?
Seumumnya kita banyak yang seperti “gajah diblangkoni, bisa kojah ora bisa nglakoni”. Bedanya tindak dengan kata. Ada jurang antara pidato dengan tindak laku. Kita krisis teladan dan disadarkan bahwa “ngelmu iku jalaran saka laku”. Ilmu (kehidupan) itu berdasrkan laku. Terpulang pada kita antara kata dan tindak. Semua adalah laku, laku adalah proses kehidupan. Bukankah Bung Hatta semasa hidup berkantor mobil kedatangannya ‘jadi patokan waktu’ untuk orang sekitarnya? Bukankah ketepatan jam waktu menjadi ciri khasnya, sampai-sampai saat HUT, Bung Hatta banyak menerima jam sebagai simbol ketepatan waktu? 3
Tulisan ini ingin diakhiri dengan warisan penulis tetralogi novel dan buku-buku lain, yaitu Pramoedya Ananta Toer yang bernarasi, tulislah dan tulislah agar tinggal tetap, sementara ide gagasan yang tak ditulis akan lenyap.
——
*Mudji Sutrisno SJ.*, Budayawan.