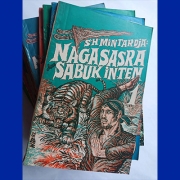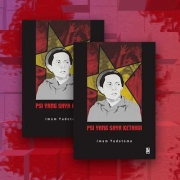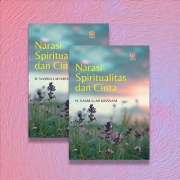Sastra Portugis dalam Dialektika Kebudayaan Global
Oleh: Gus Nas Jogja*
Sastra Portugis bukanlah sekadar kompilasi narasi, puisi, atau drama yang terbingkai dalam sempadan geopolitik Portugal Raya. Ia adalah sebuah logos yang terentang melintasi Atlantik dan samudra-samudra Afrika, sebuah peta spiritual yang disulam dengan benang-benang sejarah kolonialisme, diaspora, dan, yang paling esensial, Saudade—sebuah konsep kehilangannya. Sejak abad ke-16, Luís Vaz de Camões telah menetapkan etos bahasa Portugis sebagai bahasa yang menembus batas, mencatat epik Os Lusíadas yang merayakan penjelajahan dengan rasa melankolis yang mendalam. Ia menulis, “Jika saya menulis, itu adalah demi memberi Portugal sebuah bahasa yang lebih agung dari bahasa Latin…”[^1].
Ketika Indonesia, sebuah kepulauan yang secara historis memiliki poros maritim dengan bangsa-bangsa penjelajah, mulai mempertimbangkan pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolahnya, hal ini bukan hanya sekadar langkah diplomatik bilateral. Ini adalah sebuah keputusan epistemologis: upaya untuk menyuntikkan narasi global alternatif ke dalam diet intelektual yang didominasi oleh Hegemoni Anglophone.
Esai ini menelusuri Sastra Portugis bukan sebagai subjek filologis yang mati, melainkan sebagai medan dialektika kebudayaan global. Analisis mendalam akan dilakukan melalui tiga lensa: pertama, fondasi linguistik yang menyuguhkan bahasa sebagai “arkeologi jiwa”; kedua, dekonstruksi filosofis terhadap karya-karya intinya, terutama dalam konteks modernitas Barat; dan ketiga, relevansi pragmatis, namun spiritual, sastra ini bagi pencarian identitas kosmopolitan Indonesia. Sastra Portugis adalah saksi bisu atas pertarungan antara pusat (Portugal) yang terfragmentasi dan periferi (Brasil, Lusophone Afrika) yang memberontak—sebuah pertarungan yang kini harus kita dengarkan.
Landasan Linguistik Saudade
Setiap bahasa membawa serta kerangka filosofisnya sendiri, memaksakan cara pandang tertentu terhadap realitas, sebagaimana ditekankan oleh Hipotesis Sapir-Whorf. Bahasa tidak hanya mendeskripsikan realitas; ia juga menciptakan realitas yang dapat dipahami. Dalam ranah Lusofonia, kerangka filosofis ini diwakili oleh satu kata yang tak tertranslasikan: Saudade.
Secara linguistik, Portugis adalah turunan dari bahasa Romantis yang telah ditempa oleh keagungan dan kepahitan penjelajahan. Namun, Saudade melampaui etimologi. Ia bukanlah sekadar nostalgia atau kerinduan; ia adalah keadaan ontologis di mana subjek menyadari kehilangan, kerinduan terhadap sesuatu yang mungkin tidak pernah ada, atau sesuatu yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Ini adalah kerinduan meta-fisik—kerinduan terhadap Kesempurnaan yang telah hilang dari dunia yang terpecah. Manuel de Melo, seorang penulis abad ke-17, mendefinisikannya dengan puitis: “Saudade adalah kenikmatan dalam kesedihan, kegilaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang Portugis.”[^2]
Lusofonia sebagai Ruang Kosmik
Konsep Lusofonia (komunitas bangsa-bangsa berbahasa Portugis) adalah sebuah entitas linguistik-budaya yang unik. Tidak seperti Anglophone atau Francophone, Lusofonia selalu membawa beban sejarah yang berat, yaitu ketidakseimbangan kuasa dan trauma kolonial. Bahasa Portugis berfungsi sebagai kabel penghubung (lingua franca) yang kontradiktif: ia adalah bahasa penindas sekaligus bahasa perlawanan.
Dalam konteks sastra, hal ini menciptakan kondisi subur bagi hibriditas linguistik. Di Brasil, Portugis mengalami antropofagia (kanibalisme budaya) yang dipromosikan oleh gerakan Modernisme: mereka “memakan” budaya Eropa, mencernanya, dan memuntahkannya kembali sebagai sesuatu yang sama sekali baru dan khas Brasil. Di Angola dan Mozambik, bahasa Portugis direbut, dibengkokkan, dan diisi dengan sintaksis dan ritme asli Afrika, menjadikannya alat pembebasan.
Maka, belajar bahasa Portugis bukan sekadar menguasai tata bahasa, tetapi masuk ke dalam labirin Saudade dan menghadapi bagaimana satu bahasa yang sama dapat melahirkan begitu banyak “lidah” yang saling bertentangan dan kaya. Ia memaksa kita untuk melihat bahasa bukan sebagai struktur tetap, melainkan sebagai organisme yang terus-menerus bernegosiasi dengan trauma dan harapan.
Sastra Portugal inti, terutama dari abad ke-20, menawarkan dialog yang brutal dan mendalam dengan krisis eksistensial Modernitas Barat. Puncak dari dialog ini adalah sosok Fernando Pessoa (1888–1935), yang karyanya kini diakui sebagai salah satu monumen filsafat sastra abad ke-20.
Fernando Pessoa dan Keutuhan yang Terfragmentasi
Pessoa adalah seorang filsuf yang menyamar sebagai penyair. Kontribusinya yang paling radikal, dan paling relevan secara filosofis, adalah penciptaan heteronim—bukan sekadar nama samaran, tetapi pribadi-pribadi fiktif lengkap dengan biografi, gaya sastra, dan bahkan pandangan filosofis yang berbeda. Heteronimnya seperti Álvaro de Campos (insinyur Futuristik), Ricardo Reis (Stoik Klasik), dan Alberto Caeiro (pujangga pagan alam) adalah proyek dekonstruksi diri yang tiada banding.
Pessoa, melalui heteronimnya, mengaplikasikan prinsip filsafat Barat yang paling skeptis terhadap diri (subjek) itu sendiri. Ia menolak ego tunggal Cartesian, Cogito, ergo sum (Aku berpikir, maka aku ada), dan menggantinya dengan sebuah pengakuan yang menyayat: “Aku memecah-belah diriku untuk dapat merasakan diriku sendiri dalam banyak bagian.”[^3] Ini adalah penolakan radikal terhadap subjek monolitik. Ia menunjukkan bahwa keutuhan diri modern adalah ilusi, dan satu-satunya “rumah” bagi kesadaran yang terfragmentasi adalah bahasa itu sendiri.
Ini adalah respons sastra terhadap krisis identitas Eropa pasca-Nietzsche dan Perang Dunia I. Jika Tuhan sudah mati, begitu juga dengan individu yang utuh. Sastra Pessoa adalah tempat di mana semua fragmen ini berkumpul untuk berdebat tentang makna. Karya utamanya, The Book of Disquiet (Livro do Desassossego), yang ditulis oleh Bernardo Soares (salah satu semi-heteronimnya), adalah sebuah risalah panjang tentang keterasingan urban, keputusasaan intelektual, dan pengakuan jujur bahwa kehidupan hanyalah sebuah “opera besar yang terlalu panjang dan membosankan.” Soares/Pessoa dengan sinis mencatat: “Aku telah menciptakan untuk diriku begitu banyak kepribadian sehingga aku tidak dapat memiliki satu pun. Aku adalah penulisnya yang menulis dirinya sendiri; dan pada akhirnya, aku hanya bisa menjadi penulis dari apa yang aku tulis.”[^4]
Bagi mahasiswa filsafat, Pessoa adalah jembatan antara eksistensialisme awal dan postmodernisme. Ia menunjukkan bahwa kebenaran (keutuhan) tidak ditemukan dalam satu suara, melainkan dalam dialog polifonik dari kontradiksi. Sastra menjadi satu-satunya tempat di mana subjek yang hancur dapat menemukan semacam kebenaran estetika.
Jika Portugal menyediakan kanon tentang fragmentasi subjek di pusat kekuasaan yang mulai runtuh, maka sastra dari bekas koloninya menyajikan kontra-narasi tentang subjek yang muncul dari penindasan dan merebut kembali bahasa. Ini adalah medan di mana teori Pascakolonial menemukan resonansi sastra yang paling kuat.
Modernisme Brasil dan Antropofagia Budaya
Sastra Brasil, pasca-kemerdekaan dan puncaknya pada Gerakan Modernisme 1922 (Semana de Arte Moderna), adalah contoh cemerlang dari penolakan terhadap dialektika master-budak ala Hegel. Para penulis Brasil menolak untuk menjadi salinan pucat Eropa.
Manifesto Antropofagi oleh Oswald de Andrade adalah sebuah pernyataan filosofis radikal: “Tupi, or not Tupi, that is the question.”[^5] Budaya Brasil harus “memakan” budaya Eropa. Mereka tidak menolak pengaruh Barat; sebaliknya, mereka mengonsumsinya secara harfiah—seperti suku Tupi yang memakan musuh mereka untuk menyerap kekuatan spiritualnya—lalu mencampurnya dengan keunikan tropis, Amerindian, dan Afrika. Tujuan mereka adalah mendirikan sebuah kebudayaan yang dikonstruksi di atas kehancuran kolonial, bukan sekadar direformasi.
Sastra Afro-Brasil, yang fokus pada isu-isu sosial, ras, dan budaya yang mendalam, adalah hasil langsung dari Antropofagia ini. Penulis seperti Machado de Assis (meskipun lebih awal, ia juga dekonstruktif) atau João Guimarães Rosa (dengan bahasa yang sangat inventif) menggunakan Portugis untuk menciptakan dunia yang tidak bisa dibayangkan di Lisbon.
Ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan bahasa dapat dibalik. Bahasa kolonial, yang semula dimaksudkan sebagai alat kontrol, diubah menjadi alat defamiliarisasi (membuat yang akrab menjadi asing) dan kreasi yang khas.
Sastra Afro-Lusophone: Dari Perjuangan ke Hibriditas
Di Angola (misalnya, Agostinho Neto) dan Mozambik (misalnya, Mia Couto), sastra adalah arena perjuangan bersenjata kedua. Setelah perang kemerdekaan, tantangan sastra adalah mendefinisikan identitas pascakolonial—sebuah identitas yang terperangkap antara warisan Eropa (bahasa) dan akar Afrika (jiwa).
Mia Couto, khususnya, adalah maestro hibriditas linguistik. Ia menciptakan sebuah Portugis yang puitis dan baru, sering kali melanggar tata bahasa normatif untuk menangkap ritme dan kosmos Afrika. Ia menunjukkan bahwa bahasa harus tunduk pada realitas magis dan oralitas tradisi. Couto dengan tegas menyatakan: “Tugas sastra bukanlah menggambarkan kehidupan, tetapi menciptakannya kembali. Di tanah kami, kita harus menumbuhkan bahasa yang mampu mendengar sihir.”[^6]
Novel-novelnya adalah alegori tentang alam, sihir, dan sejarah yang bengkok. Ia menunjukkan bahwa kebenaran sebuah budaya terletak pada kemampuannya untuk mencampur, bukan untuk memurnikan. Secara filosofis, sastra Lusophone periferi adalah penolakan terhadap narasi tunggal (Hegemoni Barat) dan penegasan bahwa multikulturalisme bukanlah sekadar toleransi, melainkan sebuah kondisi kreatif yang esensial. Mereka berhasil mengubah bahasa dari “rumah penjara” menjadi “rumah perjumpaan.”
Relevansi Indonesia: Rekonstruksi Memori Maritim
Pertimbangan Indonesia untuk mengajarkan bahasa Portugis di sekolah adalah sebuah titik balik yang dapat dilihat melalui kacamata filosofis dan strategis. Ini adalah tuntutan sejarah dan kebutuhan kosmopolitan Indonesia yang mendalam.
Sejarah mencatat bahwa Portugis adalah salah satu bahasa Eropa pertama yang berinteraksi secara intens dengan kepulauan Nusantara, meninggalkan jejak linguistik dalam Bahasa Indonesia (misalnya, meja, sepatu, gereja, pesta). Mengkaji sastra Portugis adalah upaya untuk merekonstruksi memori maritim kita yang terputus, untuk memahami akar interaksi awal yang membentuk mozaik budaya Nusantara.
Portugis menawarkan lensa untuk melihat era penjelajahan bukan hanya dari sudut pandang Eropa Utara (Belanda/Inggris) yang mendominasi historiografi kita, tetapi dari sudut pandang Mediterania-Atlantik, yang lebih dekat dengan etos petualangan dan Saudade. Konsep Saudade—kerinduan transenden—beresonansi dengan konsep Jawa kangen atau Minang sansai (melankolia) yang menggarisbawahi kondisi manusia di hadapan alam yang luas dan tak terduga[^7]. Portugis memediasi rekoneksi kita dengan samudra, yang oleh Homi K. Bhabha disebut sebagai Third Space—ruang hibrid tempat identitas dibentuk melalui negosiasi budaya.
Secara filosofis, dunia akademik dan budaya Indonesia telah terlalu lama tenggelam dalam narasi dan paradigma Anglophone (Amerika/Inggris). Studi sastra Portugis, terutama dari Brasil dan Afrika, dapat berfungsi sebagai antidote terhadap monokultur intelektual ini, yaitu:
1. Pluralisme Epistemologis: Sastra Afro-Lusophone, dengan fokusnya pada hibriditas dan pasca-kolonialisme, menawarkan model kritik yang jauh lebih relevan bagi Indonesia—sebuah negara yang juga berjuang dengan identitas pasca-kolonial, pluralitas etnis, dan globalisasi yang tidak merata.
2. Peluang Pendidikan dan Soft Power: Kemampuan berbahasa Portugis membuka akses langsung ke pusat-pusat studi di Sao Paulo, Rio de Janeiro, atau Lisbon yang seringkali memiliki perspektif berbeda dari yang ditawarkan oleh akademi Amerika. Ini memperkuat soft power Indonesia dengan memungkinkan interaksi yang lebih cair dan otentik dengan aliansi Lusophone yang berpengaruh di PBB, G20, dan forum internasional lainnya.
Jika Brasil mengajarkan Indonesia tentang bagaimana “memakan” dan mengubah bahasa hegemoni, maka Indonesia dapat mengajarkan Lusofonia tentang bagaimana peradaban maritim bernegosiasi dengan pluralisme, menunjukkan bahwa Pusat dan Periferi adalah dua sisi dari sebuah koin yang berputar abadi.
Bahasa sebagai Etika Kehadiran
Sastra Portugis, dengan segala kekayaan dan kontradiksinya, adalah cerminan dari kondisi manusia yang terasing di tengah-tengah keberlimpahan. Krisis Saudade yang dialami oleh subjek modern, seperti alegori ibu konglomerat yang ditinggalkan, adalah versi modern dari krisis Saudade: kerinduan terhadap kehadiran yang telah digantikan oleh efisiensi modal.
Ketika Indonesia mempertimbangkan investasi dalam bahasa ini, kita tidak membeli sebuah bahasa asing, melainkan sebuah etika kehadiran. Kita belajar dari Pessoa bahwa diri itu terfragmentasi, dari Brasil bahwa budaya harus berevolusi secara agresif, dan dari Afrika bahwa bahasa adalah medan pertempuran untuk hak dan identitas. Seperti yang disimpulkan oleh filolog modern: “Sastra Portugis adalah arsip, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari bagaimana manusia mencoba menjadi utuh di dunia yang secara inheren terbelah.”[^8]
Dialektika kebudayaan global menuntut kita untuk mendengar sebanyak mungkin suara. Sastra Portugis adalah suara yang memohon untuk didengar, sebuah suara yang mengajarkan kita bahwa nilai sejati bukanlah pada kuantitas kekayaan, tetapi pada kualitas narasi yang mampu kita wariskan—narasi yang jujur, menyakitkan, dan, pada akhirnya, indah dalam kerinduannya yang tak tersembuhkan. Maka, pengajaran bahasa Portugis di Indonesia adalah investasi filosofis. Ia adalah langkah menuju status bangsa yang benar-benar kosmopolitan, yang tidak takut menghadapi Saudade-nya sendiri, dan siap memeluk kontradiksi-kontradiksi dunia dalam bingkai bahasa yang puitis dan universal.
Begitulah!
***
Catatan Kaki
[^1]: Kutipan ini merupakan sintesis dari semangat epik Os Lusíadas oleh Camões, yang tujuannya adalah memuliakan Portugal dan bahasanya, menempatkan bahasa Portugis setara atau lebih tinggi dari bahasa klasik.
[^2]: Melo, Manuel de (1660). Carta de Guia de Casados (Surat Panduan Pernikahan). Definisi ini merangkum Saudade sebagai kondisi psikologis yang unik bagi identitas Portugis.
[^3]: Pessoa, Fernando. Dikutip dari Selected Poems. Pernyataan ini secara radikal menolak keutuhan ego, merayakan keberadaan melalui multiplisitas suara, yang menjadi inti dari proyek heteronim.
[^4]: Soares, Bernardo (Fernando Pessoa). The Book of Disquiet (Livro do Desassossego). Sebuah refleksi esensial tentang eksistensi sebagai sebuah proses penulisan diri yang tak pernah selesai, menyoroti keterasingan modern.
[^5]: Andrade, Oswald de (1928). Manifesto Antropófago. Slogan terkenal ini (Tupi, atau tidak Tupi—merujuk pada suku asli Brasil—itulah pertanyaannya) adalah inti dari modernisme Brasil yang menuntut otonomi budaya dengan “memakan” dan mengubah Eropa.
[^6]: Couto, Mia. Pernyataan yang sering diulang dalam esai dan wawancaranya, yang menekankan peran sastra dalam menciptakan realitas baru yang dipandu oleh mitos dan spiritualitas Afrika.
[^7]: Perbandingan ini didasarkan pada studi komparatif linguistik-budaya mengenai emosi transenden yang dimiliki oleh masyarakat maritim di seluruh dunia.
[^8]: Kutipan sintesis ini mewakili pandangan umum dalam studi Lusofonia kontemporer, yang melihat sastra sebagai alat dekolonisasi dan re-konfigurasi identitas.
Rujukan Terpilih
Andrade, Oswald de. (1928). Manifesto Antropófago. (Manifesto Antropofagi).
Bhabha, Homi K. (1994). The Location of Culture. Routledge. (Mendukung konsep Third Space).
Camões, Luís Vaz de. (1572). Os Lusíadas. (Epik Nasional Portugal).
Couto, Mia. (2018). O Beijo da Palavra (Ciuman Kata). Editorial Caminho.
Melo, Manuel de. (1660). Carta de Guia de Casados.
Pessoa, Fernando. (2001). The Book of Disquiet: A Selection. (Diedit oleh Maria dos Anjos). Penguin Classics.
Pessoa, Fernando. (1998). Selected Poems. (Diedit oleh Richard Zenith). Grove Press.
Rosa, João Guimarães. (1956). Grande Sertão: Veredas. (Karya kunci Modernisme Brasil).
Steiner, George. (1975). After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford University Press. (Mendukung analisis linguistik-filosofis).
———-
*Gus Nas Jogja. Budayawan.