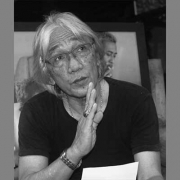Religiositas Seni (Rupa) atau Seni Religius?
Oleh: Mudji Sutrisno SJ.*
Hartojo Andangdjaja dalam bukunya “Dari Sunyi ke Bumi” (Grafiti, 1991, hal.18-19), menulis bahwa puisi religius dengan interpretasi puitik yang baik tidak pernah mendesakkan suatu kepercayaan apapun kepada pembacanya. Puisi itu ‘hanya’ menyatakan apa yang dihayati penyairnya. Bilapun termuat pengabaran atau ‘dakwah’ maka pengabaran dalam puisi religius yang baik akan terasa lebih intens karena kebenaran religi yang diungkapkan sudah menjadi milik rohani si penyair. Karena religi bersumber pada Tuhan, maka berciri impersonal, obyektif dan universal. Dan interpretasi puitik terhadap religi merupakan usaha kreatif penyair yang berciri personal, subyektif dan unik. Puisi religius yang baik memiliki kedua ciri atau watak itu, keduanya bertemu.
Ungkapan puisi religius diatas membuat terjadinya proses dialog antar penghayatan religi atau religiositas tidak hanya membuat Chairil Anwar mampu berpuisi dengan “Itu tubuh mengucur darah, mengucur darah …” (dalam sajak ISA untuk rekan-rekannya penganut nasrani). Tetapi juga dalam syair puisi yang dimelodikan dalam lagu-lagu Bimbo terutama lagu “Tuhan”. Terasa amat saling menyentuhkan pengalaman batin bersapa doa denganTuhan pencipta kehidupan. Maka tidak heran pula, saya mengalami dalam ziarah dari candi-candi atau dari stupa ke stupa manakala sketsa atau puisi batin yang mau digoreskan dalam hitam-putihnya warna atau simbol-simbol warna kehidupan dari stupa-stupa Asia Tenggara, disana seakan rasa religius itu menyatu dan menemukan makna stupa sebagai rahim atau garba kehidupan. Bukankah warna-warni lukisan dengan konsensus makna ‘hijau’ lambang syukur kehidupan atas alam ciptaan yang hijau; kuning lambang segar dan cerahnya matahari kehidupan; merah lambang daya dinamika gerak kehidupan dan putih perlambang hening sunyi yang berdoa syukur dalam diam. Ini semua merangkum dan menjelaskan betapa sumbernya sumber dari aneka ekspresi warna-warni estetika religius adalah kehidupan yang satu, yang diberikan oleh yang Ilahi dalam ungkapan kasih yangtidak terbatas pada umat manusia makhluk-makhluk ciptaanNya! Cara Tuhan memberikan kasihNya itu seperti matahari yang tidak diskriminatif memberikan sinar suryaNya. Kasih tak terbatas dan tidak menghitung-hitung seperti kalkulasi untung rugi; hitungan kepentingan atau kalkulasi sini kawan dan sana lawan menjadi ‘kasih tak bertepi’ yang memberi hujan air kepada semua ciptaan tanpa membeda-bedakan religi, rasa atau warna kulitnya. Hujan air penyubur adalah berkah kehidupan, namun bila manusia tidak mengolahnya karena sudah diberi akal budi dan hati nurani untuk berbagi dan membuatnya “sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran bagi sesamanya …”, maka yang terjadi adalah bencana banjir. Karena itulah ketika Affandi ditanya mengapa ia dengan seluruh energi sampai tuntas mencototkan warna-warna dominan kuning yang dahsyat? Jawabnya: Affandi mau mensyukuri matahari kuning Nusantara dan hamparan panen padi kuning sebagai ungkapan syukur ekspresinya. Karena itu pula dalam lukisan religius van Gogh ‘A Pair of Shoes’, sepasang sepatu tua yang dibawahnya bolong, orang hanya akan berdecak kagum karena lukisan itu bercerita mengenai pengalaman religius van Gogh ketika dengan sepatu bolong di musim salju dingin kelaparan dan mau mati, lalu beristirahat ternyata ada ibu tua datang memberi roti dan minum padanya. Dan ketika siuman bagun dari tidur, van Gogh mencari si ibu itu, ternyata ia sudah menghilang, dicari-cari lenyap seakan ia hanya hadir sekejap memberinya makan. ‘Kasih tak bertepi’, bingkai pameran lintas religi ini menjadi tenaga dan bernyawa karena sumber perekat kemajemukan religi, suku bangsa ini memang ‘religiositas’ itu. Inilah yang membuat indah tiap kali almarhum Gus Dur menyatakan Romo Mangunwijaya (alm.) sebagai beda agama tetapi satu keimanan, satu religiositas. Juga Cak Nur (Nurcholish Madjid) yang menamai setiap kita warga Negara Indonesia ini adalah sama-sama HANIF. Artinya, sama-sama saudara untuk kembali ke Tuhan sang sumber kasih yang tak terbatas.
Menghayati masuk ke stupa-stupa, masjid, katedral dengan sikap memuliakan Dia sebagai sumber kehidupan menjadi perjalanan pemuliaan cara Dia mencintai kita dalam keunikan-keunikan kita masing-masing sehingga pastilah antar seniman, penyair dan saudara-saudari semua (sebab pada dasarnya setiap orang adalah ‘seniman’) memuliakan kasihNya itu secara terbatas, artinya bertepi: seperti dikatakan di depan setiap lukisan, atau puisi atau instalasi seni tetaplah unik berharkat sebagai ungkapan pengalaman religius personal masing-masing. Namun justru keunikan masing-masing ekspresi syukur atas kehidupan atau gugat tanya atas ketidakadilan sebagai lawannya ataupun prostes mengapa kasihNya yang tak bertepi dimanipulasi oleh serakahnya manusia-manusia diteriakan-teriakan saling memusuhi, memaki di jalan politisasi sekarang ini membuat mata pandang jernih religius kita menjadi ‘buta’ atau rabun, sehingga hanya menangkap tepian-tepian kecil kasihNya kerena dirampas oleh keserakahan dan ambisi politik sesamanya.
Semoga mata hening yang kita pakai selama berkeliling melihat pameran ini menjadi mata syukur daripada mata cerah karena marah atau sakit mata!
Salam,
Mudji Sutrisno SJ.
***
*Mudji Sutrisno SJ., Budayawan.