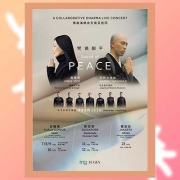Puasa, Lapar, dan Jalan Pulang Manusia: Suluk Kesadaran melalui Suara Puisi
Oleh Abdul Wachid B.S.*
1. Puasa sebagai Pintu Kesadaran Batin
Puasa sering muncul dalam kesadaran keagamaan sebagai sesuatu yang sudah “terjelaskan”. Hukum dan waktu ditetapkan, tata cara diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kerangka yang rapi ini, manusia cenderung menunaikan ritualnya seolah makna telah tersedia sepenuhnya; tanpa ruang untuk pengalaman pribadi. Kepastian yang tampak jelas itu justru menutupi dimensi terdalam yang hanya bisa disentuh dalam keheningan batin.
Bagian ini hadir bukan sekadar pembukaan, tetapi sebagai gerbang kesadaran. Sebuah peralihan halus: dari hukum menuju pengalaman, dari pengetahuan menuju perjumpaan, dari penjelasan menuju keheningan. Suluk bermula ketika manusia menyadari bahwa makna yang dipahami secara teori belum benar-benar dialami. Puasa bukan lagi sekadar kepastian, melainkan pintu yang membuka kedalaman diri.
Puisi hadir sebagai medium gerbang itu; tanpa suara, tanpa penjelasan normatif. Ia menghidupkan pengalaman batin, memberi ruang agar makna bernapas perlahan. Membaca puisi tentang puasa bukan membaca aturan, melainkan menyelami peristiwa batin yang sedang berlangsung; sunyi, pelan, namun diam-diam mengubah kesadaran manusia.
Di sinilah puasa, puisi, dan suluk menjadi satu kesatuan pengalaman batin: Puasa sebagai laku penahanan diri yang membersihkan ruang kesadaran. Puisi sebagai bahasa yang menyalurkan pengalaman halus tanpa mengurangi kedalamannya. Suluk sebagai perjalanan batin yang menghubungkan keduanya menuju perjumpaan Ilahi. Ketiganya tidak berdiri sendiri; mereka saling menerangi, menuntun manusia dari lahir menuju batin, dari batin menuju sumber cahaya.
Dalam “Seorang Lelaki yang Tujuh Tahun Bersimpuh” puisi saya, pengalaman batin itu dimulai dari citraan hening, bukan hukum:
“pohon yang seperti khuldi itu, mengapa
di tiap detak puasa dia justru menegak
sedangkan matahari maghrib masih jauh…”
(Abdul Wachid B.S., Penyair Cinta, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022:61)
Citra pohon ini menggeser fokus dari tubuh menuju kesadaran. Puasa tidak lagi soal menunggu maghrib, melainkan tegaknya sesuatu dalam diri, yang hidup ketika keinginan ditahan sampai ke akar. Puisi tidak memberi jawaban, tetapi menyalakan pertanyaan: mengapa penahanan justru membangkitkan kehidupan, dan mengapa kekeringan bisa menjadi ruang kebangkitan?
Pertanyaan semacam ini lahir dari refleksi batin, bukan penjelasan normatif. Puisi membuka ruang perjumpaan, tempat makna perlahan tersingkap di dalam diri pembaca.
Nada yang menuntun lebih jauh ke kedalaman terdengar pada “Nasihat Ramadhan” puisi K.H. A. Mustofa Bisri (Gus Mus) :
“Ramadhan adalah bulan antara dirimu dan Tuhanmu. Darimu
hanya untuk-Nya…”
(Pahlawan dan Tikus, Rembang, 2005:83)
Kesederhanaan suara ini menyimpan keluasan makna. Puasa ditempatkan bukan di ranah sosial atau penilaian manusia, tetapi di relasi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di sinilah makna puasa hanya bisa dipastikan oleh yang menjalaninya.
Pengalaman estetis puisi bersentuhan dengan dimensi etis. Sastra menumbuhkan kepekaan batin: kemampuan melihat kedalaman kemanusiaan yang tidak bisa dicapai rasionalitas semata. Puisi tentang puasa memperdalam kesalehan personal sekaligus memurnikan cara manusia memandang diri dan sesamanya.
Dari dua suara puitik tersebut tampak pergeseran halus namun mendasar: puasa bergerak dari wilayah hukum ke pengalaman. Fokusnya bukan sekadar pada apa yang ditinggalkan, tetapi pada apa yang ditemukan kembali: kejernihan melihat diri tanpa tirai, kesadaran yang bangkit ketika tubuh ditahan.
Di sinilah gerak suluk terasa: kegelisahan awal yang hening. Kepastian bergeser menjadi pencarian; pengetahuan menjadi kerinduan untuk mengalami. Kegelisahan ini bukan kehilangan arah, melainkan tanda bahwa perjalanan batin baru saja dimulai.
Dari gerbang kesadaran ini, langkah berikutnya menunggu: ketika lapar tubuh tidak lagi sekadar rasa kekurangan, tetapi membuka ingatan terdalam manusia tentang asal dan jalan pulangnya.
2. Dari Tubuh Menuju Ingatan Batin
Jika gerbang pertama membuka kegelisahan yang hening, gerbang berikutnya membawa kesadaran itu turun ke wilayah paling dekat dengan manusia: tubuhnya sendiri. Di sini suluk menempuh pengalaman nyata. Pertanyaan batin kini menjelma menjadi rasa lapar: sebuah kondisi yang meretakkan kebiasaan, membongkar kepastian, dan membuka ingatan yang lebih purba daripada pikiran. Lapar bukan sekadar fenomena fisik; ia adalah kelanjutan alami gerbang kesadaran: kesadaran yang menjadi rasa, dan rasa yang menuntun pulang ke asal ruhani.
Suluk pada tahap ini bergerak dari tubuh menuju ingatan terdalam. Lapar berbicara, bukan sebagai keluhan jasmani, melainkan sebagai retakan pertama kesadaran. Dari celah itu terdengar panggilan yang tak bersuara, tetapi terus memanggil pulang. Suara itu hadir getir dan inderawi. Dalam puisi “Lapar, Dahaga, Bianglala”, pengalaman fisik menyingkap kegagalan manusia:
Selain derita dan nestapa
Apa yang kuperoleh dari masokisme ini
Apa yang kuraih selain perih ini?”
(Abdul Wachid B.S., Wasilah Sejoli, Yogyakarta: Basabasi, 2022:62-63)
Tubuh menahan, batin berputar di lingkar diri:
“Aku tarawih tak berasa tarawih
Aku tadarus tak menggerus rakus yang lebih
Aku jamaah subuh tak ngurangi maksiat kambuh
Aku dengan keakuan yang tak sembuh-sembuh.”
(Ibid.)
Lapar menjadi cermin kegagalan spiritual. Namun dari kegagalan itulah pintu kesadaran mulai terbuka. Puisi menghadirkan ingatan purba, seperti suara seorang ibu yang menjelaskan rahasia lapar:
“Anakku, dalam lapar dan dahaga yang sempurna
Kelak engkau akan mampu terbang ke sana
Meniti tangga-tangga bianglala…”
(Ibid.)
Lapar pun berubah: dari rasa sakit menuju kemungkinan terbang, dari tubuh menuju asal.
Gerak serupa terlihat pada puisi “Puasa” karya Aspar Paturusi, yang menyingkap keterbatasan makna puasa bila hanya berhenti pada jasmani:
“bila hanya menahan lapar dan haus
kutahu, apalah arti puasa bagimu
lapar dan haus kau geluti setiap hari.”
(Aspar Paturusi, 2010);
https://www.sepenuhnya.com/2025/03/puisi-puasa-karya-aspar-paturusi.html
Di sini puasa sosial dan puasa spiritual bertemu. Bagi mereka yang miskin, lapar adalah kenyataan harian, bukan ibadah. Makna puasa bergeser dari menahan menuju menyadari. Kesadaran itu melahirkan doa sederhana yang mengguncang:
“tentu aku amat senang, Tuhan
jika semua bulan kami berpuasa.”
(Ibid.)
Doa ini bukan asketisme, melainkan kerinduan akan keadilan Ilahi: kesadaran bahwa lapar bisa menjadi jalan kedekatan, bukan sekadar kekurangan.
Di kedalaman ini pengalaman puitik bersentuhan dengan dimensi mistik. Dalam perspektif tasawuf, kekosongan bukan kehilangan, tetapi ruang penyingkapan. Seperti yang diungkap Ibnu ‘Arabi:
“Apabila engkau kosong dari dirimu,
maka engkau dipenuhi oleh-Nya.”
(Ibn ‘Arabi, Al-Futūḥāt al-Makkiyyah)
Kekosongan lapar menjadi ruang kehadiran. Tubuh yang ditanggalkan dari kepenuhan dunia membuka ingatan tentang asal ruhani manusia. Lapar bukan akhir penderitaan, tetapi awal pengenalan diri: jalan sunyi untuk kembali membaca jejak keberadaan sendiri.
Di titik ini gerak suluk bergeser. Gelisah tidak lagi berputar tanpa makna; ia menjadi pencarian. Tubuh yang kosong menyalakan ingatan purba: bahwa manusia pernah dekat, pernah penuh, dan kini sedang berjalan pulang.
3. Puasa sebagai Ruang Spiritual yang Tenang
Jika tahap sebelumnya lapar membuka ingatan purba tentang asal ruhani manusia, tahap ini membawa ingatan itu memasuki keheningan yang damai. Pencarian yang gelisah mereda; langkah-langkah batin tidak lagi tergesa, tetapi hadir dalam diam yang penuh kesadaran. Inilah ambang terdalam suluk: perjalanan dari ingatan menuju perjumpaan.
Gerak suluk tidak lagi digerakkan oleh tubuh atau oleh pertanyaan tentang makna. Kesadaran melambat, tenggelam ke dalam sunyi. Ia menoleh bukan ke luar, melainkan menyelam ke ruang batin yang tenang; tempat perjumpaan bisa terjadi tanpa kata.
Dalam perspektif mistik, keheningan bukan ketiadaan, tetapi kepenuhan yang belum terucapkan. Puisi-puisi Jalaluddin Rumi menyingkapkan pengalaman ini, di mana kekosongan menjadi pintu masuk bagi napas Ilahi:
“Anak ayammu gelisah di dalam telur
karena kamu terus makan dan tersedak.
Keluarlah dari cangkangmu agar sayapmu bisa tumbuh.
Biarkan dirimu terbang.”
(Rumi, 2002); Ghazal No. 2344, Divan-e Shams-e Tabrizi, Terj. Nevit Ergin (dari terjemahan Turki, dari teks asli Persia oleh Golpinarli), “Mevlana Jelaleddin Rumi: Divan-i Kebir,” Volume 18, 2002.
Puasa kini bukan sekadar menahan diri, melainkan pengosongan agar kehadiran Ilahi bisa menetap. Kesunyian itu sendiri menjadi resonansi; ruang yang kosong justru menampung keberadaan yang penuh.
Nada “kerendahan” yang sama hadir dalam karya Gus Mus, namun lebih personal. Puasa tidak dibicarakan sebagai kewajiban lahir, melainkan sebagai kegelisahan iman:
“ragaku berpuasa
dan jiwaku kulepas bagai kuda
ya Rasulallah…
sudah islamkah aku?”
(Pahlawan dan Tikus, 2005:86-87)
Pertanyaan ini menanggalkan kepastian lahiriah. Kesalehan sosial yang tampak sempurna belum menjamin kedekatan batin. Kesunyian menjadi ruang pengakuan: tempat manusia menatap diri tanpa tirai dan menemukan kebenaran yang lembut.
Dalam lapisan yang lebih dalam, puisi itu menuntun pada kerinduan akan cahaya:
“meski secercah, teteskan padaku
cahyamu
buat bekalku sekali lagi
menghampiri-Nya.”
(Ibid.)
Kerinduan ini menandai perubahan arah suluk. Pencarian eksternal berganti menjadi menunggu dalam hening. Kesunyian bukan kekosongan, tetapi ambang perjumpaan yang perlahan menyala.
Fenomena batin semacam ini sesuai dengan pemahaman William James tentang pengalaman religius: realitas langsung yang tidak sepenuhnya dapat dirumuskan oleh konsep, tetapi nyata bagi yang mengalaminya (The Varieties of Religious Experience, 1902). Bahasa hanya memberi isyarat, sementara wilayah rasa tetap sunyi dan terbuka.
Puisi menjaga sunyi itu tetap hidup. Ia tidak menutup pengalaman dengan kesimpulan; ia membiarkan perjumpaan bergetar di dalam kesadaran pembaca. Di sinilah puasa menjelma menjadi ruang spiritual yang tidak riuh; tempat manusia berbicara sedikit, karena kehadiran telah mulai terasa.
Gerak suluk pun beralih dari mencari menjadi menyadari. Kesunyian kini bukan menakutkan; ia menjadi awal jalan pulang manusia. Ketika keheningan berubah menjadi kehadiran, perjalanan pulang yang sesungguhnya telah dimulai.
4. Dari Kesalehan Personal Menuju Empati Sosial
Setelah kesunyian menghadirkan perjumpaan batin yang hening, pengalaman itu tidak berhenti sebagai sesuatu yang pribadi. Kesadaran yang menyentuh kehadiran Ilahi justru membuka mata terhadap luka dunia. Suluk kini bergerak keluar, bukan untuk melarikan diri dari batin, tetapi sebagai pancaran dari kedalaman ruhani. Kesalehan yang semula bersifat personal berubah menjadi empati yang nyata.
Kesadaran sejati tidak berhenti pada keselamatan diri sendiri; ia menuntun manusia untuk menyadari penderitaan orang lain.
Dalam puisi “Dia Lupakan Derita” karya Aspar Paturusi, pengalaman puasa menggeser pusatnya dari rasa sakit pribadi menjadi kepedulian terhadap sesama:
“Hari ke tujuh belas puasa
matahari beranjak naik
namun tak menyurutkan niat
seorang lelaki tua
menuju istana
…
dilihatnya bendera melambai
seolah memberi salam padanya
dengan sigap dia menghormat”
(Aspar Paturusi, 2011);
https://www.sepenuhnya.com/2020/09/puisi-dia-lupakan-derita.html?m=1
Lapar yang sebelumnya menjadi jalan pengenalan diri, kini menjadi kekuatan yang melampaui ego. Puasa menjelma kesetiaan, bahkan saat tubuh menanggung lelah, sementara kesadaran spiritual menuntun pada keteguhan kemanusiaan.
Nada yang lebih luas terdengar dalam puisi “Orang Indonesia Kontemporer” karya Binhad Nurrohmat. Luka di sini bukan sekadar pengalaman individual, tetapi kolektif, menyingkap beban sejarah dan tanggung jawab bersama:
“Orang Indonesia
menanggung hutang negara”
(Binhad Nurrohmat, 2008);
https://www.sepenuhnya.com/2025/04/puisi-orang-indonesia-kontemporer-karya-binhad-nurrohmat.html?m=1
Puisi menyingkap wajah kemanusiaan yang terluka oleh struktur sosial dan politik. Kesadaran puasa tidak berhenti pada asketisme pribadi; ia menuntut keberpihakan etis terhadap dunia.
Gerak etis ini sejalan dengan pemikiran Emmanuel Levinas: perjumpaan dengan wajah liyan adalah panggilan tanggung jawab yang mendahului konsep moral. Liyan hadir bukan sebagai objek pengetahuan, tetapi sebagai tuntutan etis yang tak terelakkan (Levinas, Totality and Infinity, 1961). Dengan demikian, pengalaman spiritual sejati selalu mengalir menuju kepedulian kemanusiaan.
Di lanskap ini, puisi saya selanjutnya menampilkan pergeseran halus dari kesadaran diri menuju kesadaran semesta. Simbol pohon khuldi dalam “Seorang Lelaki yang Tujuh Tahun Bersimpuh” menjadi lambang godaan sekaligus tegaknya ruhani, hingga kesadaran menegak dalam takbir:
“pohon yang seperti khuldi itu, mengapa
di tiap gerak puasa dia justru menegak
sedangkan perempuan penyiram ladang itu masih jauh
seorang lelaki yang tujuh tahun bersimpuh
kini dia bertakbir
mengacunglah
alif
yang tidak terbilang jumlahnya!”
(Ibid.)
Takbir di sini bukan sekadar ucapan ritual, melainkan tegaknya kesadaran tauhid yang membebaskan dari keterikatan ego. Huruf alif menjadi poros vertikal: dari luka dunia menuju makna langit.
Sementara itu, dalam “Lapar, Dahaga, Bianglala”, pengalaman lapar menemukan pelukan terhadap bianglala kehidupan:
“Hingga kelak
Aku tersungkur
Dan hanya
Memeluk bianglala”
(Ibid.)
Pelukan ini bukan kekalahan, melainkan penerimaan eksistensial terhadap perjalanan manusia. Kesadaran tidak lagi melawan luka, tetapi merangkulnya sebagai jalan pulang.
Gerak serupa hadir dalam “Puasa Puisi”, ketika tubuh yang lemah justru membebaskan ruh:
“betapa ketika tubuh lemas
ruhlah yang akan berjaga bebas”
(Abdul Wachid B.S., 2014);
https://nusantaranews.co/puisi-puasa-puasa-puisi-puisi-abdul-wachid-b-s/
Di sini puasa mencapai makna terdalamnya: pembebasan ruhani yang menumbuhkan kepekaan terhadap kehidupan bersama.
Dimensi etis ini juga bergema dalam karya Gus Mus. Dalam “Nasihat Ramadhan”, penyucian diri tidak berhenti pada tubuh, tetapi menuntut pembersihan batin demi Hadhirat Ilahi:
“Tidak.
Puasakan hasratmu
hanya untuk Hadhirat-Nya!”
(Ibid.)
Namun penyucian itu sekaligus menjadi kritik terhadap kesalehan yang melupakan tanggung jawab sosial. Puasa tanpa empati hanyalah ritual hampa.
Emha Ainun Nadjib memperdalam perspektif ini, mempertanyakan harga surga bila ibadah terlepas dari amanah kekhalifahan:
“Sementara kehidupan di Bumi sudah rusak serusak-rusaknya
Dan hamba lupa tidak Engkau tugaskan kami kecuali sebagai Khalifah”
(“Puasa Hanya Sekadar”, 2016);
https://dimadura.id/kumpulan-puisi-caknun-emha-tentang-puasa-dan-idulfitri/#google_vignette
Di sinilah suluk mencapai belokan penting: dari pengalaman Ilahi menuju tanggung jawab kosmik. Gerak suluk pada tahap ini dapat dirumuskan: menyadari → menyucikan → memikul luka kemanusiaan.
Kesadaran tidak lagi berpusat pada keselamatan diri; ia menjelma kasih yang bekerja di dunia. Ketika empati lahir dari kedalaman ruhani, puasa menemukan makna sosialnya yang paling sunyi, yakni menjadi jalan cinta bagi sesama. Luka kemanusiaan, pada titik ini, bukan sekadar penderitaan, melainkan pintu menuju rahmat yang hadir melalui manusia.
5. Estetika Penahanan dan Kejernihan Kata
Setelah tubuh dilatih oleh lapar dan batin dimurnikan oleh kesunyian, suluk bergerak ke lapisan yang lebih halus: bahasa. Di tahap ini, puasa tidak hanya terjadi di daging atau rasa, melainkan merambat ke kata-kata. Ucapan menahan diri, kalimat menipis, dan makna memadat di ruang yang sunyi.
Kesederhanaan di sini bukan kemiskinan ekspresi, melainkan kejernihan batin. Kata-kata yang berpuasa tidak kehilangan daya puitiknya; justru menemukan pusat cahaya yang sebelumnya tertutup keramaian retorika. Tiap kata berhenti menjadi hiasan bunyi dan menjadi ruang kehadiran.
(1) Bahasa dalam Puisi Abdul Wachid B.S.
Dalam “Puasa Puisi”, bahasa menahan diri dari retorika berlebihan:
Dalam “Puasa Puisi”, bahasa menahan diri dari retorika berlebihan:
“puasa puisi yang
menahan diri dari berporipori rasa ingin
hutan jati di musim kemarau mengugurkan daunnya
semaksemak terbakar terlihatlah ularular
lemaklemak terbakar hingga kau aku akan saksikan
betapa ketika tubuh lemas
ruhlah yang akan berjaga bebas”
(Ibid.)
Bahasa dipadatkan; tiap kata menuntun pembaca pada inti pengalaman batin, bukan sekadar citraan visual, tetapi ruang meditasi yang menghubungkan tubuh dan ruh.
“Aku tarawih tak berasa tarawih
Aku tadarus tak menggerus rakus yang lebih
Aku jamaah subuh tak ngurangi maksiat kambuh
Aku dengan keakuan yang tak sembuh-sembuh
Aku shalat lalu sujud
Tapi pikiran dan perasaanku saling berebut
Meminta ruang untuk dimanjakan
Meminta waktu untuk pesta perayaan …”
(Ibid.)
Kesederhanaan bahasa menebalkan makna; pengalaman spiritual hadir melalui kesadaran batin yang tenang.
(2) Kesederhanaan dalam Puisi Dimas Indiana Senja
Puisi “Buka Puasa” juga menunjukkan kesederhanaan bahasa:
“Kini, langkah kita hampir sampai di tempat matahari terbenam,
Saat selendang senja lebih dekat dari waktu yang kita janjikan,
Kita sama-sama menelanjangi mega yang tergurat di pelataran langit hati kita
Sesekali camar yang berputar-putar di perut kita
Mencericit dan hinggap di sebuah pohon yang tak jauh dari tempat kita terduduk.”
(Dimas Indiana Senja, 2012);
https://www.sepenuhnya.com/2025/03/puisi-buka-puasa-karya-dimas-indiana-senja.html?m=1
Kerinduan diungkapkan melalui tindakan kecil, bukan konsep besar. Bahasa yang bersahaja membiarkan pengalaman spiritual muncul lembut, dalam kesunyian yang dekat.
(3) Asketisme Bahasa dalam Puisi Emha Ainun Nadjib
Dalam “Puasa Baginda” menghadirkan dialog sederhana penuh makna:
“Aku duduk di beranda rumah selepas berbuka
Ketika mendadak muncul seorang tua renta …
Baginda Ayub Nabiyullah …
‘Apakah kau sudah berbuka puasa?’ beliau bertanya
‘Puji Tuhan, atas rizki dan perkenan-Nya,’ jawabku terpana …
‘Sungguh sangat berbeda puasamu dibanding puasaku’ …
‘Puasaku’, kata Baginda, ‘adalah puasa yang kujalani tanpa kepastian akan berbuka’ ”
(Emha Ainun Nadjib, 2016);
https://dimadura.id/kumpulan-puisi-caknun-emha-tentang-puasa-dan-idulfitri/
Bahasa yang sederhana memampatkan pengalaman spiritual; penahanan kata membuka kedalaman batin.
Puisi “Puasa Rindu dan Nafsu” menanggungkan kesadaran spiritual dan keserakahan duniawi pada bahasa padat:
“Hari-hari dan malam-malam Ramadlan kami masuki
Dengan hati yang dipenuhi oleh semangat kerinduan
Agar mendapatkan laba berkah sebanyak-banyaknya
Untuk kepentingan kejayaan dan kekayaan dunia kami
Lapar dahaga sepanjang hari kami setorkan
Menjelang berbuka kami semua menadahkan tangan.”
(Ibid.)
(4) Puisi Gus Mus: Bahasa sebagai Latihan Batin
Dalam “Nasihat Ramadhan”, repetisi sederhana menjadi latihan penyucian:
“Sucikan kelaminmu. Berpuasalah.
Sucikan tanganmu. Berpuasalah.
Sucikan mulutmu. Berpuasalah.”
(Ibid.)
Bahasa bukan sekadar menyampaikan pesan; ia menenangkan, memurnikan, dan menuntun kesadaran.
“Ya Rasulullah” menampilkan bahasa sebagai medium introspeksi:
“Aku ingin seperti santri berbaju putih
yang tiba-tiba datang menghadapmu…
Ya Rasulallah, sudah islamkah aku?
Ya Rasulallah, sudah imankah aku?
Ya Rasulallah, dapatkah aku berihsan?”
(Ibid.)
Kesederhanaan bahasa menumbuhkan pengalaman langsung, jernih, dan penuh penghayatan.
(5) Perspektif Filosofis: Heidegger
Martin Heidegger menegaskan: bahasa adalah rumah keberadaan. Ketika kata-kata dipenuhi kebisingan, keberadaan tertutup retorika. Ketika kata ditahan (seperti orang berpuasa) kehadiran menyingkap diri dalam kejernihan yang sunyi (Letter on Humanism, New York: Harper & Row, 1947).
Puasa bahasa bukan pengurangan estetika, melainkan pemurnian pengalaman. Sedikit kata memberi ruang bagi makna yang luas, keheningan bunyi memperdalam rasa hadir.
(6) Puisi Lain: Rumi, Aspar Paturusi, dan Binhad Nurrohmat
“Bibir Sang Guru kering
karena memanggil Kekasih.
Suara panggilanmu bergema
melalui tanduk perutmu yang kosong.”
(Ibid.)
Aspar Paturusi menekankan perhatian sederhana dalam “Puasa”:
“kau selalu gembira menyongsong puasa
makan minum lebih teratur, katamu
jelang buka kau telah bersila di mesjid
puasa pun jadi nikmat bagimu”
(Ibid.)
Binhad Nurrohmat menggunakan minimalisme untuk kritik sosial:
“Orang Indonesia
tak gentar hidup sengsara
Orang Indonesia
harus irit dan rajin puasa
Orang Indonesia
menanggung hutang negara…”
(Ibid.)
(7) Gerak Suluk: Dari Menyucikan Menuju Mendekat
Gerak suluk pada tahap ini menandai peralihan dari penyucian batin menuju kedekatan dengan Yang Ilahi. Bahasa menipis, makna menebal. Kata-kata tidak lagi menghalangi pengalaman Ilahi, tetapi menjadi jalan sunyi menuju-Nya. Puisi tidak lagi dibaca sebagai rangkaian bunyi, melainkan dialami sebagai kejernihan hadir.
Dalam keheningan nyaris tanpa suara, suluk mencapai batas terdalam: bukan berkata tentang Yang Ilahi, tetapi tenggelam perlahan dalam kehadiran-Nya.
6. Puasa sebagai Gerak Menuju Keutuhan Diri
Puasa dalam perspektif suluk bukan sekadar ritual yang dibatasi waktu dan kalender, melainkan perjalanan pulang batin. Ia menuntun manusia pada inti diri yang murni, kejernihan yang belum ternoda dunia, alif kesadaran yang tegak, dan keutuhan jiwa. Di sinilah puncak suluk tercapai: manusia kembali ke asalnya, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk memperbarui diri. Al-Ghazali menegaskan: “Penyucian jiwa adalah jalan menuju kedekatan Ilahi.” (Ihya Ulumuddin, Beirut: Dar al-Kotob, 1999).
Penyucian itu terjadi melalui praktik menahan lapar dan dahaga, yang menyiapkan tubuh, pikiran, dan roh untuk mengalami transformasi batin. Puasa menjadi tanda kesiagaan spiritual, latihan menegakkan alif dalam kesadaran yang menyeluruh.
(1) Tubuh, Rasa, dan Roh dalam Puisi
Puisi menjadi medium suluk yang paling nyata, mengekspresikan pengalaman batin dalam kata dan citraan. Dalam “Seorang Lelaki yang Tujuh Tahun Bersimpuh”, saya menegaskan bahwa tubuh yang menahan lapar menjadi saksi bagi roh yang berjaga:
“pohon yang seperti khuldi itu, mengapa
di tiap gerak puasa dia justru menegak
…
ada yang bergerak-gerak dari dahan-dahan pohon
padahal angin belum menyapa di dini hari itu
lalu, darimana datangnya gerakan?”
(Ibid.)
Kesadaran ini menegaskan keselarasan antara alam, tubuh, dan roh. Setiap gerak fisik menjadi tanda kesiagaan spiritual, menegakkan manusia pada tingkat kesadaran lebih tinggi. Lapar yang dirasakan tubuh juga menyalakan rindu batin:
“Di tiap lapis-lapis bianglala hidup ini
Ada lapar dan dahaganya sendiri
Yang meminta diri untuk menahan diri …”
(Abdul Wachid B.S., “Lapar, Dahaga, Bianglala”, Ibid.)
Rindu ini bersifat batiniah: keinginan untuk mendekat pada Yang Maha Esa. Inilah inti suluk puasa: kesabaran batin dan kesadaran diri yang mengalir menuju keutuhan jiwa.
(2) Dimensi Spiritual, Sosial, dan Eksistensial
Gus Mus menekankan puasa sebagai pengawasan total atas seluruh anggota tubuh dan pikiran:
“Puasakan tubuhmu
untuk meresapi Rahmat
Puasakan hatimu
untuk menikmati Hakikat
Puasakan pikiranmu
untuk menyakini Kebenaran
Puasakan dirimu
untuk menghayati Hidup.”
(“Nasihat Ramadhan Buat A. Mustofa Bisri”, Ibid.)
Aspar Paturusi menambahkan dimensi sosial: tubuh menahan lapar dan roh menahan dahaga, namun mata batin tetap menyaksikan realitas kolektif:
“dia menyaksikan para pejuang muda
dan barisan rakyat bergerak ke medan perang
dari balik kenangan, dia kembali tersenyum
Haus puasa tak dirasakannya
hari ini dia lupakan derita”
(“Dia Lupakan Derita”, 2011, Ibid.)
Dimas Indiana Senja menvisualisasikan pengalaman sosial puasa sebagai ritual bersama yang menguatkan kebersamaan:
“Orang-orang berpulang dari perjalanan mereka,
Tapi kita tak berani menanyai mereka,
Karena raut mereka telah mampu mengabarkan
Hasrat rindu untuk berpulang.”
(Ibid.)
Emha Ainun Nadjib menyoroti dimensi eksistensial: puasa adalah pengalaman menanti dengan ketidakpastian, bukan sekadar menahan lapar:
“Puasaku adalah puasa yang kujalani tanpa kepastian akan berbuka.”
(Ibid.)
Jalaluddin Rumi menegaskan dimensi sufistik: puasa sebagai pengosongan diri agar seluruh eksistensi diisi oleh kehadiran Ilahi:
“Jangan biarkan apa pun ada di dalam dirimu.
Kosongkan dirimu: berikan bibirmu kepada bibir alang-alang.
Ketika seperti alang-alang engkau dipenuhi dengan nafas-Nya,
maka engkau akan merasakan kemanisan.”
(Ibid.)
(3) Kesadaran Pulang
Dengan demikian, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Ia adalah praktik suluk menyeluruh, melibatkan seluruh eksistensi manusia: fisik, mental, dan spiritual. Puasa adalah gerak pulang batin, kembali ke alif kesadaran, ke inti diri yang murni.
Di titik ini, manusia belajar memeluk bianglala kehidupan dengan sabar, penuh rindu spiritual, menegakkan kesadaran, dan menempatkan seluruh keberadaan di hadapan Yang Maha Esa. Puasa menjadi gerak pulang yang bukan sekadar ritual, tetapi jalan menuju keutuhan diri.
7. Mengapa Puisi Diperlukan dalam Perjalanan Pulang Manusia
Di ujung perjalanan suluk, manusia tidak mencari kesimpulan definitif. Penutup bukan garis akhir, melainkan hening yang bercahaya: cahaya lahir dari kesadaran yang ditempa puasa, doa, dan penghayatan batin. Puisi berperan sebagai penjaga pengalaman, saksi perjalanan kesadaran, dan jembatan yang menuntun manusia menuju Tuhan. Ia membuka ruang refleksi yang terus bergerak, bukan sekadar menutup duniawi.
Horison akhir berbeda bagi tiap individu. Dalam sufisme universal, cahaya adalah cakrawala cinta Ilahi yang melampaui waktu dan ruang. Bagi saya, cahaya itu membumi, muncul dari pengalaman hening, rindu yang melekat pada tanah, tubuh, dan sejarah personal yang menyatu dengan kesadaran batin. Cahaya itu lahir dari kesejajaran tubuh, alam, dan roh dalam kehidupan sehari-hari, bukan dari simbol-simbol jauh dari pengalaman nyata.
Puisi memperlihatkan gerak suluk paling konkret: keterbukaan tanpa akhir. Transformasi terjadi di setiap bait, namun perjalanan batin tidak selesai meski tulisan berakhir. Dalam “Seorang Lelaki yang Tujuh Tahun Bersimpuh”, saya menegaskan:
“kini dia bertakbir
mengacunglah
alif
yang tidak terbilang jumlahnya!”
(Ibid.)
Dalam “Lapar, Dahaga, Bianglala”, saya menekankan kesabaran dan internalisasi batin:
“Ibu, kenapa aku harus lapar dan dahaga
Sedang gerimis senja itu tak pernah dahaga
Sedang tanah ini tak pernah lapar
Sedang hujan siapkan makanan air menghantar?
(Ibid.)
Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi menegakkan kesadaran, membiarkan pengalaman hadir dan mengalir tanpa batas. K.H. A. Mustofa Bisri menekankan fungsi puasa sebagai pengawasan total diri:
“Puasakan dirimu
untuk menghayati Hidup.
Tidak.
Puasakan hasratmu
hanya untuk Hadhirat-Nya!”
(Ibid.)
Emha Ainun Nadjib menambahkan dimensi ketidakpastian dan kerentanan dalam puasa:
“Puasaku adalah puasa yang kujalani tanpa kepastian akan berbuka.”
(biId.)
Dimensi sosial juga membingkai cahaya tersisa. Peluh, air mata, dan perjuangan kolektif menjadi resonansi batin yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Dimas Indiana Senja menulis:
“Tetapi, sekian lama terdiam, kita menjadi bagian dari mereka,
Kita menggendong peluh sehari ini,
Keringat dan airmata sama ngalirnya,
Tapi sesungging senyum kita temui, seusai kumandang adzan
Mencerua di penghujung senja.
Lalu kita meneguk air wudhu bersama, yang paling madu, yang paling
Rindu.”
(Ibid.)
Cahaya yang tersisa adalah saksi perjalanan manusia menuju inti diri yang murni. Ia mengalir dari hening ke hening, dari raga ke jiwa, dan dari batin menuju Tuhan. Puisi menegaskan perjalanan pulang manusia sebagai gerak yang tak pernah benar-benar selesai, karena kesadaran terus bergerak, memeluk kehidupan, dan menegakkan diri pada cahaya hakiki.
Rumi, melalui Divan-e Shams-e Tabrizi, memperluas pandangan ini ke pengalaman universal:
“Rayakan! Bulan puasa telah tiba.
Semoga perjalananmu menyenangkan menuju Yang Maha Esa
Siapakah rombongan orang-orang yang berpuasa itu?
Aku memanjat atap untuk melihat Bulan,
Karena aku sangat merindukan puasa,
sepenuh hati dan jiwa.”
(Ibid.)
Akhirnya, cahaya tersisa bukan hanya pengalaman individu, tetapi resonansi batin yang menghubungkan manusia dengan sejarah, alam, dan kehidupan kolektif. Puisi menjadi saksi dan penjaga perjalanan pulang batin: dari kesadaran sehari-hari menuju Cahaya yang hakiki, selalu menunggu di cakrawala kalbu.***
—-
Daftar Pustaka
Al-Ghazali. 1999. Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar al-Kotob.
Bisri, A. Mustofa. 1995. Pahlawan dan Tikus (Kumpulan Puisi). Cet.II, 2005. Yogyakarta: Hikayat.
Heidegger, Martin. 1947. Letter on Humanism. New York: Harper & Row.
Ibn ‘Arabi. Al-Futūḥāt al-Makkiyyah. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
James, William. 1902. The Varieties of Religious Experience. New York: Longmans, Green, and Co.
Levinas, Emmanuel. 1961. Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1961.
Nadjib. Emha Ainun. 2024. “Puasa Baginda” & “Puasa Rindu dan Nafsu”. Sumber: https://dimadura.id/kumpulan-puisi-caknun-emha-tentang-puasa-dan-idulfitri/
Nurrohmat, Binhad. 2008. Demonstran Sexy. Sumber : https://www.sepenuhnya.com/2025/04/puisi-orang-indonesia-kontemporer-karya-binhad-nurrohmat.html?m=1
Paturusi, Aspar. “Dia Lupakan Derita.” Sumber: https://www.sepenuhnya.com/2020/09/puisi-dia-lupakan-derita.html
Paturusi, Aspar. “Puasa”. Sumber : https://www.sepenuhnya.com/2025/03/puisi-puasa-karya-aspar-paturusi.html
Rumi, Jalaluddin. 2002. Ghazal No. 2344, Divan-e Shams-e Tabrizi, Terj. Nevit Ergin (dari terjemahan Turki dari teks asli Persia oleh Golpinarli), “Mevlana Jelaleddin Rumi: Divan-i Kebir,” Volume 18, 2002. Sumber: https://www-amaana-org.translate.goog/ismaili/2012/07/ramadan-fasting-by-rumi/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
Senja, Dimas Indiana. “Buka Puasa.” Sumber: https://www.sepenuhnya.com/2025/03/puisi-buka-puasa-karya-dimas-indiana-senja.html
Wachid B.S., Abdul. 2017. “Lapar, Dahaga, Bianglala”, “Puisi Puasa”, “Puasa Puisi”. Sumber : https://nusantaranews.co/puisi-puasa-puasa-puisi-puisi-abdul-wachid-b-s/
Wachid B.S., Abdul. 2022. Penyair Cinta. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
Wachid B.S., Abdul. 2022. Wasilah Sejoli. Yogyakarta: Basabasi.
———-
*Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.