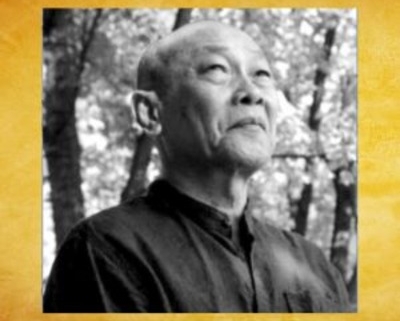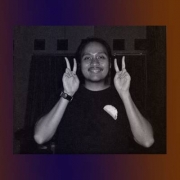Prasangka Aroma
Oleh Halim HD
Siapa bilang prasangka (prejudice) hanya muncul dari masalah ekonomi dan politik serta ideologi yang bersifat rasialis yang melatar belakanginya yang membuat seseorang atau sekelompok masyarakat memberikan penghakiman terhadap orang lain atau kelompok lainnya? Bahkan prasangka pula yang bisa membuat suatu partai yang menguasai suatu negara melakukan pembunuhan, seperti kasus di Jerman dan Spanyol. Juga di negeri ini masalah prasangka rasialis tak pernah surut dari lingkungan masyarakat. Prasangka selalu berkeliaran di lingkungan masyarakat kita. Dan itu lahir karena ada anggapan kepada diri yang berlebihan, mengukur diri lebih tinggi daripada orang lain. Sejenis narsisme dan megalomanian bersifat psikologis, membentuk sikap ekshibisionis secara politis dan ideologis yang merasuk dan menusuk pihak yang lain.
Di suatu warung di Dukuh Plesungan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pernah terjadi seorang ibu yang marah-marah gara-gara saya memakai minyak kayu putih yang saya borehkan di tangan dan wajah. Waktu itu pandemi dan saya selalu setiap hari memborehkan minyak kayu putih sebagai usaha saya untuk menangkal virus Corona. Apa yang saya lakukan datang dari informasi dari grup WA yang saya terima, ketika Prof. Paturusi, gurubesar Fakultas Kedokteran UnHas, Makassar, menyatakan bahwa minyak kayu putih bisa menangkal, tapi bukan untuk mengobati. Gagasan sederhana dan murah itu saya bagikan kepada teman-teman melalui WA. Di samping itu, juga tentang mengisap uap minyak kayu putih yang diteteskan ke dalam air panas, setiap pagi dan sore saya kerjakan.
Peristiwa di warung langganan saya yang tak jauh dari rumah itu, membuat saya terkejut, apalagi ketika ibu itu berkata, “mambu opo iki”, bau apa ini. Kata “mambu” dalam bahasa Jawa untuk menyatakan ada aroma yang sangat tak disukainya, sejenis berbau busuk. Saya bukan hanya merasa heran, tapi juga terkejut, bagaimana seseorang tinggal di desa dan di Jawa tak mengenal minyak kayu putih? Minyak kayu putih, sereh dan cengkeh serta balsam menjadi bagian dari diri saya, dari kehidupan kampung dari masa anak-anak, yang saya bawa hingga kini, seperti juga saya selalu membawa obat merah untuk luka, juga koyo dan tetes mata. Itulah perangkat medis yang menjadi bagian tubuh saya ketika berkeliling ke berbagai daerah-kota sepanjang hampir setengah abad dalam kaitannya dengan kegiatan saya di dunia kesenian dan aktifitas kebudayaan.
Pengalaman di warung langganan di Dukuh Plesungan itu, bukan yang pertama. Belasan tahun yang lalu terjadi di bandara Hasanuddin, Makassar. Karena saya melembur mengerjakan makalah untuk seminar teater dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Petra, Surabaya, dan subuh itu saya harus ke bandara, saya memborehkan perut saya dengan minyak kayu putih untuk menahan masuk angin. Setelah chek in dan boarding saya menuju kursi, seiring dengan saya seorang perempuan dengan dandanan yang nampak mewah duduk di window dan saya di sebelahnya. Beberapa menit kemudian terdengar: bau apa ini? Saya nggak ngeh, dan baru sadar setelah dia berulang kali mengucap yang sama, dan dia memanggil pramugari dan meminta memindahkan saya ke kursi yang lain. Pramugari datang dan meminta saya pindah. Saya menolak. Permintaan kedua pramugari membuat saya beranjak, berdiri sambil menyatakan dengan suara yang cukup keras: jika anda berhadapan dengan penumpang dengan kondisi yang tak cukup sehat, apa yang anda lakukan? Kenapa anda memindahkan saya, dan kenapa pula tak memindahkan ibu itu, sambil telunjuk saya menuding perempuan yang merasa terganggu oleh aroma minyak kayu putih di tubuh saya.
Pada tahun 1970-80-an terlalu sering saya mendengar ungkapan kaum laki-laki yang pongah walaupun dengan nada gurauan, jika mencium aroma parfum dari jenis merek tertentu: kok baumu seperti pelacur. Sama dengan gurauan yang berbau rasis melalui aroma parfum yang dipakai oleh mereka yang mau sembahyang Jum’at: baumu kok kayak Arab. Ungkapan dengan menggunakan kata “bau” atau dalam bahasa Jawa “mambu” sudah membuktikan suatu judgement, penghakiman melalui cara merendahkan orang lain melalui ukuran aroma parfum. Tapi aroma parfum juga bisa menjadi guyonan yang menyegarkan dan membuat banyak orang tersenyum ketika seorang aktivis kepada rekannya menyatakan: waah, parfummu sudah seperti lawyer kelas atas. Yang disindir ikut tersenyum dan bahkan bangga. Aroma mengantarkan siapa saja kepada klasifikasi sosial dan posisi profesionalisme.
Demokratisasi dan ujaran tentang keberagaman kultural dalam dunia panggung kesenian yang selalu disemburkan, bisa berbalik dengan ironis, ketika serombongan penari dari Suku Dani, di Papua, yang akan naik ke panggung Indonesia Kaya di Jakarta harus disemprot oleh parfum. LO yang menyemprot menyatakan, supaya bau tubuhnya tak tercium oleh penonton. Betapa tragisnya Indonesia Kaya yang konon memiliki program untuk menjadi jembatan bagi pertemuan berbagai sub-kultur di nusantara tak mampu menerima kehadiran tubuh-tubuh penari dengan seluruh dirinya. Saya tak percaya kepada nasib bahwa Suku Dani itu memiliki aroma yang harus dibentuk oleh pihak lain. Saya yakin ada politik kolonial yang tersembunyi yang disadari atau tidak terhadap berbagai suku di Papua yang selalu diidentikan dengan jenis aroma tertentu dan dihakimi. Hakim itu adalah imperium aroma yang menjadi perangkat kolonialisme kultural, seperti kaum Belanda di jaman lampau menuding: Kowe orang bau tauco. Kowe orang bau terasi. -o0o-
—
*Halim HD. Networker-Organizer Kebudayaan