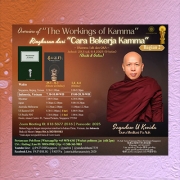Pentigraf dalam Dimensi Flash Fiction
Oleh Tengsoe Tjahjono*
Pentigraf merupakan salah satu fenomena paling signifikan dalam lanskap literasi kontemporer Indonesia, terutama ketika masyarakat bergerak memasuki era digital yang ditandai oleh percepatan informasi, fragmentasi perhatian, serta perubahan besar dalam pola konsumsi teks. Sebagai bentuk cerita tiga paragraf, pentigraf bukan sekadar inovasi formal atau variasi dari cerita pendek tradisional, melainkan sebuah respons kultural terhadap perubahan ekologi membaca dan menulis yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Pada era ketika layar ponsel menjadi medium dominan, dan ketika ritme hidup manusia diatur oleh notifikasi yang terus-menerus, bentuk sastra yang ringkas, padat, dan segera dapat diakses menjadi semakin relevan. Di sinilah pentigraf menemukan momentumnya: ia menjembatani kebutuhan estetik dengan kebutuhan pragmatis pembaca masa kini.
Fenomena pentigraf memperlihatkan kemampuan adaptif sastra dalam merespons transformasi sosial dan teknologi. Dalam perspektif ekologi media, sebagaimana dijelaskan oleh Neil Postman, setiap media baru mendesakkan perubahan tidak hanya dalam cara manusia berkomunikasi tetapi juga dalam cara manusia berpikir dan memaknai dunia. Pentigraf, sebagai teks yang sepenuhnya kompatibel dengan layar gawai dan kultur daring, menunjukkan bagaimana bentuk sastra dapat berinteraksi dengan media, bukan semata mengikuti, tetapi juga menciptakan budaya literer baru. Ia mengafirmasi bahwa sastra tidak statis; ia merupakan organisme kultural yang hidup, bergerak, dan terus bernegosiasi dengan konteks zamannya.
Pada saat yang sama, pentigraf mengungkap pergeseran psikologi pembaca. Di tengah fenomena information overload dan menurunnya rentang perhatian (attention span), pembaca cenderung mencari teks yang ringkas namun memiliki daya pukau intelektual dan emosional. Pentigraf memadukan keduanya melalui strategi pemadatan makna, intensifikasi konflik, dan ketepatan penggunaan bahasa. Bentuk ini memperlihatkan bahwa teks yang singkat tidak harus dangkal; sebaliknya, keterbatasan ruang naratif justru memungkinkan lahirnya intensitas dan kerapatan makna yang lebih tajam. Karena itu, pentigraf tidak hanya menyesuaikan diri dengan pembaca modern, tetapi juga mengedukasi mereka untuk membaca dunia dengan cara yang lebih reflektif meski dalam waktu singkat.
Untuk menempatkan pentigraf secara proporsional dalam wacana akademik, penting melihatnya dalam kerangka tradisi flash fiction, yakni genre fiksi mini yang berkembang di tingkat global dan berfokus pada kesingkatan ekstrem, efisiensi naratif, serta kekuatan suggestive meaning. Tradisi ini menjelaskan bahwa cerita yang sangat singkat bukanlah genre minor, tetapi genre yang memiliki prinsip estetik tersendiri dan perangkat naratologis yang berbeda dari cerpen konvensional. Di sinilah pentigraf dapat dibaca sebagai bagian dari jaringan global estetika flash fiction, namun dengan identitas lokal yang kuat melalui aturan tiga paragraf yang menjadi ciri khasnya. Dengan demikian, pentigraf bukan turunan dari cerpen maupun duplikasi flash fiction internasional, tetapi sebuah adaptasi kreatif yang menegaskan kemampuan sastra Indonesia untuk melahirkan bentuk-bentuk baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.
Lebih jauh, pentigraf dapat dipahami sebagai praktik literer dengan implikasi estetik, naratologis, dan sosio-kultural yang luas. Secara estetik, ia memadukan unsur minimalisme, intensitas konflik, dan kepadatan makna. Secara naratologis, ia mengonstruksi ritme dramatik mikro yang menantang batas-batas konvensi cerita pendek. Secara sosio-kultural, pentigraf telah memicu gerakan literasi akar rumput yang memperluas partisipasi publik dalam menulis, membaca, dan berdialog melalui teks. Dengan kata lain, pentigraf merupakan titik temu antara estetika modern, teknologi digital, dan dinamika sosial Indonesia kontemporer, suatu fenomena yang memperlihatkan betapa fleksibelnya sastra dalam merespons dunia yang terus berubah.
Pentigraf dalam Kerangka Flash Fiction
Dalam kajian sastra global, pentigraf dapat ditempatkan secara konseptual dalam rumpun flash fiction, sebuah genre fiksi ultra-pendek yang berkembang sejak abad ke-20 dan mendapatkan legitimasi akademis pada dekade 1980–1990 melalui antologi Sudden Fiction dan Flash Fiction yang disunting Robert Shapard dan James Thomas. Genre ini tidak hanya dibedakan oleh panjang teks, tetapi oleh cara kerja estetikanya: ia mengupayakan keterpaduan naratif dalam ruang yang ekstrem terbatas. Shapard menegaskan bahwa kekuatan flash fiction terletak pada “ketegangan antara keringkasan dan kelengkapan,” yakni bagaimana teks mampu memberi pengalaman cerita yang utuh dalam hitungan paragraf atau bahkan beberapa kalimat [1]. Thomas (2015) menambahkan bahwa flash fiction bekerja sebagai “narasi yang memadatkan dunia sebuah cerpen ke dalam satu ledakan kecil,” sehingga efek estetiknya tidak bergantung pada detail panjang, tetapi pada kepadatan dan kejutan makna [2].
Dari perspektif ini, pentigraf berdiri sejajar dengan prinsip-prinsip dasar flash fiction, tetapi menghadirkan struktur khasnya sendiri melalui aturan tiga paragraf. Pentigraf memanfaatkan ruang mikro ini untuk menegakkan narasi yang utuh, yang meliputi latar, konflik, dan titik puncak, namun dengan estetika yang jauh lebih padat dibandingkan cerpen konvensional. Berbeda dengan cerpen yang memungkinkan perkembangan psikologis tokoh secara gradual, pentigraf mengompresi konflik ke dalam satu momentum dramatik yang intens. Watak tokoh tidak dijelaskan secara rinci, melainkan ditampilkan melalui gestur, tindakan singkat, atau satu peristiwa kunci. Pola ini sejajar dengan observasi Nuala Ní Chonchúir (2012) bahwa fiksi mini beroperasi seperti “puisi naratif,” karena penulis harus mengandalkan ketajaman diksi, kekuatan gambar, dan simbolisme yang terkendali untuk menghasilkan resonansi emosional [3]. Dengan kata lain, pentigraf menghadirkan narrative minimalism, sebuah pendekatan naratif yang mengutamakan penyempitan fokus diegetik tanpa kehilangan tensi dramatik.
Secara naratologis, pentigraf menggunakan prinsip dense diegesis, yaitu gaya penceritaan yang memadatkan aksi, latar, dan konflik sehingga tidak ada ruang untuk eksposisi berlebih. Setiap kalimat harus berfungsi: membangun suasana, memperkuat konflik, atau mengarahkan pembaca pada titik pencerahan di paragraf akhir. Dengan demikian, tiga paragraf dalam pentigraf bukan sekadar batas teknis, tetapi bekerja sebagai struktur dramatik mikro: paragraf pertama menghadirkan orientasi dan ketegangan awal; paragraf kedua bertindak sebagai akselerasi konflik; paragraf ketiga menjadi tempat ledakan makna, ironi, atau twist. Ketiganya membentuk ritme naratif yang cepat dan padat, tetapi tetap menyisakan ruang interpretasi demi menciptakan efek sugestif, salah satu karakter utama flash fiction.
Batas tiga paragraf dalam pentigraf dapat dipahami melalui teori constraint aesthetic yang banyak dibahas dalam studi sastra dan seni. Italo Calvino dalam Six Memos for the Next Millennium (1988) menekankan bahwa keterbatasan formal bukanlah hambatan artistik, tetapi pendorong kreativitas: semakin ketat aturan bentuk, semakin besar kemungkinan munculnya inovasi [4]. Dalam konteks ini, pentigraf menggunakan keterbatasan ruang sebagai strategi estetik untuk memaksa penulis hanya memilih elemen yang benar-benar esensial. Narasi tidak boleh melebar; ia harus bergerak lurus menuju inti makna. Prinsip ini bukan sekadar bentuk penghematan bahasa, tetapi manifestasi pemadatan pengalaman manusia menjadi esensi naratif yang paling kuat.
Lebih jauh, pentigraf memperluas tradisi flash fiction ke dalam konteks Indonesia melalui proses lokalisasi. Jika flash fiction global sering mengeksplorasi absurditas, kejutan, atau kesunyian eksistensial, pentigraf Indonesia kerap menekankan ironi sosial, kritik moral, konflik domestik, hingga potret kehidupan sehari-hari masyarakat urban maupun rural. Dengan demikian, pentigraf bukan semata adopsi dari genre global, tetapi adaptasi kreatif yang memperkaya tradisi tersebut dengan idiom lokal, dinamika sosial Indonesia, serta sensitivitas budaya Nusantara. Dalam bentuk tiga paragraf yang ringkas, pentigraf berhasil memadukan ekonomi bahasa ala flash fiction dengan karakteristik estetik dan kultural sastra Indonesia kontemporer.
Aspek Estetika dan Naratologi Pentigraf
Dari perspektif estetika, pentigraf tidak dapat dipahami sekadar sebagai teks pendek; ia merupakan bentuk sastra yang mengandalkan prinsip compression aesthetics, yakni seni pemangkasan, pemadatan, dan penyaringan makna hingga mencapai esensi. Dalam pentigraf, tiga paragraf bekerja bukan sebagai batas mekanis tetapi sebagai kerangka dramatik mikro yang memiliki ritme internal yang sangat ketat. Paragraf pertama berfungsi membangun orientasi, latar, dan ketegangan awal dalam tempo yang cepat; paragraf kedua berperan sebagai akselerator konflik yang memperluas ketegangan atau memancing antisipasi; sementara paragraf ketiga menjadi titik ledakan makna, baik berupa resolusi, ironi, twist, maupun pencerahan eksistensial. Ketiga paragraf ini bukan sekadar bagian struktural, tetapi komponen dramatik yang harus saling menopang melalui hubungan kausal yang padat dan tajam.
Struktur dramatik ini menunjukkan bahwa pentigraf mengambil elemen-elemen fundamental dari Freytag’s triangle, eksposisi, rising action, dan climax, namun menerapkannya dalam skala yang sangat terkompresi. Di dalam cerpen konvensional, eksposisi diberikan ruang cukup untuk membentuk latar dan karakter; namun dalam pentigraf, eksposisi dan klimaks seringkali hampir bersentuhan karena keterbatasan ruang. Penulis harus mengelola keduanya dalam waktu singkat, sehingga muncul ritme naratif yang lebih cepat, kontras, dan intens. Hal ini menghasilkan model narasi yang tidak linear secara tradisional, tetapi spiral: informasi dan konflik muncul dalam putaran cepat yang langsung menuntun pembaca pada titik makna.
Implikasi naratologis dari bentuk mikro ini adalah dominasi unsaid meaning, atau makna yang tidak diucapkan secara eksplisit. Wolfgang Iser, melalui teori reader-response (1978), menegaskan bahwa teks sastra selalu mengandung ruang kosong (gaps) yang harus diisi oleh pembaca [5]. Dalam pentigraf, ruang kosong itu menjadi lebih besar karena keterbatasan ruang naratif; penulis harus memilih untuk tidak menjelaskan banyak hal. Akibatnya, pembaca dituntut melakukan kerja interpretatif lebih aktif: membayangkan latar yang tidak disebutkan, menangkap emosi tokoh dari satu gerak kecil, atau membaca ironi dari satu kalimat penutup. Inilah kekuatan estetika pentigraf: ia bekerja tidak hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi melalui apa yang sengaja dibiarkan tak terucap.
Pada konteks estetika sastra kontemporer, pentigraf juga selaras dengan kecenderungan minimalisme, sebuah tradisi yang menekankan pengurangan elemen naratif untuk mencapai akurasi ekspresi. Ernest Hemingway dengan teori “gunung es”-nya menegaskan bahwa bagian terpenting dari cerita sering kali tersembunyi di bawah permukaan teks, sementara Raymond Carver menunjukkan bahwa kesunyian, gestur kecil, dan dialog sederhana dapat menciptakan tensi emosional yang kuat. Spirit minimalisme ini diadopsi pentigraf melalui seni memilih kata secermat mungkin, menghapus bagian yang tidak esensial, dan menempatkan makna pada jeda, ironi, atau efek mendadak. Namun, pentigraf tidak hanya mengulang minimalisme Barat; ia menyesuaikannya dengan ekologi budaya Indonesia yang kaya dengan idiom lokal, humor sosial yang halus, metafora religius, dan konteks keseharian masyarakat urban maupun rural.
Dalam praktiknya, minimalisme pentigraf tidak bersifat dingin atau steril. Keringkasan bahasa sering dibarengi dengan lapisan makna yang berakar pada pengalaman sosial Indonesia: kemiskinan, relasi kuasa, tradisi, spiritualitas, atau problem ekologis. Oleh karena itu, estetika pentigraf merupakan perpaduan antara intensitas minimalis dan kedalaman kontekstual. Bentuk tiga paragraf menjadi ruang laboratorium kreatif tempat penulis melakukan destilasi pengalaman, menyaring yang tidak perlu dan mempertajam yang esensial, sehingga cerita pendek yang sangat singkat dapat menawarkan kedalaman emosional dan refleksi sosial yang tidak kalah dari cerpen panjang.
Dengan demikian, pentigraf sebagai bentuk estetis menghadirkan dua paradoks produktif: ia ringkas namun dalam, sederhana namun kompleks, terbatas namun sangat bebas. Dan di dalam paradoks inilah pentigraf memperoleh kekuatan naratifnya, mampu mengguncang pembaca hanya dengan tiga paragraf, tetapi meninggalkan gema makna yang jauh lebih panjang daripada ukuran teksnya.
Dimensi Psikologis dan Kreatif Penulisan Pentigraf
Secara psikologis, proses menulis pentigraf dapat dipahami sebagai bentuk distilasi pengalaman, yaitu upaya menyaring dan memadatkan peristiwa, emosi, dan refleksi menjadi struktur naratif yang sangat ekonomis. Penulis tidak sekadar merangkum, tetapi melakukan proses kognitif yang kompleks: menyeleksi detail yang esensial, memutuskan titik konflik yang paling representatif, dan menentukan momen dramatik yang membawa bobot makna terbesar. Aktivitas ini sejalan dengan konsep self-reflective writing yang dikemukakan Bolton (2010), yakni praktik menulis yang membantu individu mengolah pengalaman emosional menjadi wacana yang lebih tertata dan estetis [6]. Melalui proses ini, penulis tidak hanya menciptakan cerita, tetapi juga melakukan klarifikasi internal terhadap pengalaman hidupnya, sehingga menulis menjadi aktivitas terapeutik sekaligus kreatif.
Pada tingkat kognitif, penulisan pentigraf menuntut aktivasi higher-order thinking skills seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam ruang tiga paragraf, penulis harus memutuskan mana yang perlu dihadirkan dan mana yang harus dihilangkan. Ia harus mampu melakukan selective attention terhadap elemen naratif tertentu, sebuah kemampuan yang diperkuat oleh teori psikologi kognitif tentang cognitive load management. Bentuk pentigraf memaksa penulis membatasi beban kognitifnya dan memusatkan perhatian pada inti konflik. Keterbatasan ruang ini justru mempercepat proses kreatif karena penulis tidak tenggelam dalam kelimpahan detail yang tidak relevan.
Secara emosional, menulis pentigraf membuka ruang aman untuk eksplorasi diri. Banyak penulis pemula merasa terbebani ketika harus menulis cerpen panjang atau novel, karena mereka menghadapi tuntutan naratif yang kompleks. Namun pentigraf memberikan format yang lebih terjangkau: tiga paragraf yang ringkas, namun tetap menantang secara intelektual dan emosional. Format ini menciptakan psychological safety bagi penulis pemula untuk bereksperimen tanpa takut gagal. Mereka dapat menyelesaikan sebuah teks yang utuh dalam hitungan menit atau jam, sehingga muncul rasa keberhasilan yang memperkuat motivasi intrinsik. Proses ini dapat dibaca dalam kerangka empowerment, yaitu situasi ketika individu merasa memiliki kapasitas kreatif yang meningkat karena berhasil menuntaskan tugas yang bermakna.
Secara kreatif, penulisan pentigraf menempatkan penulis pada tensi antara pembatasan dan kebebasan. Batas tiga paragraf bukanlah pembatas estetis, melainkan pemicu kreativitas (creativity through constraints). Dalam teori kreativitas, keterbatasan ruang dan struktur justru mendorong individu untuk berpikir lebih orisinal, karena mereka dipaksa menemukan solusi ekspresif dalam kondisi yang tidak ideal. Hal ini sejalan dengan pandangan Stokes (2006) tentang constraint-based creativity, bahwa kreativitas berkembang ketika individu berhadapan dengan batasan formal yang menuntut inovasi dalam cara berpikir dan mengekspresikan ide.
Selain itu, pentigraf membuka kemungkinan bagi penulis untuk merengkuh flow experience, yaitu kondisi psikologis ketika seseorang begitu tenggelam dalam aktivitas kreatif sehingga waktu seolah berhenti (Csikszentmihalyi, 1990). Struktur singkat dan ritme cepat pentigraf memungkinkan penulis memasuki kondisi flow lebih mudah dibandingkan ketika menulis bentuk panjang, karena hambatan mental yang muncul lebih sedikit dan tujuan menulis lebih jelas. Kejelasan tujuan, yakni mencapai tiga paragraf yang efektif, menjadi pendorong kognitif yang menstabilkan fokus penulis.
Dalam perspektif kreativitas sastra, pentigraf juga mengaktifkan kemampuan imajinatif yang unik. Struktur mikro ini menuntut penulis untuk memvisualisasikan adegan secara cepat dan tajam, memilih metafora yang bekerja secara instan, serta menggunakan dialog atau gestur minimalis yang membawa beban emosional. Dengan demikian, menulis pentigraf melatih kecerdasan naratif yang sangat spesifik: kemampuan menciptakan dunia kecil yang signifikan. Pada gilirannya, proses ini meningkatkan kepekaan estetis penulis terhadap detail bahasa, ritme, pencitraan, dan ironi.
Lebih jauh, pentigraf memberi ruang bagi penulis untuk mengolah trauma, kegelisahan, atau pengalaman emosional yang sulit diungkapkan dalam bentuk panjang. Banyak penulis menemukan bahwa tiga paragraf memberikan jarak emosional yang cukup untuk berbicara tentang pengalaman sensitif tanpa harus membuka semuanya. Dengan demikian, pentigraf dapat menjadi medium untuk emotional regulation, kemampuan mengelola emosi melalui proses kreatif. Hal ini menjadikan pentigraf bukan hanya produk estetis, tetapi juga alat pembentukan diri.
Secara keseluruhan, dimensi psikologis dan kreatif pentigraf memperlihatkan bahwa menulis dalam bentuk ultra-pendek ini bukan pekerjaan sederhana, tetapi sebuah latihan mendalam dalam berpikir, merasakan, dan berkreasi. Ia menuntut kejelasan batin, ketajaman analitis, dan kepekaan estetis. Pentigraf bukan hanya menggerakkan pena, tetapi juga menggerakkan kesadaran; bukan hanya memadatkan cerita, tetapi juga memadatkan pengalaman manusia menjadi inti makna yang paling jernih.
Perhatikan contoh pentigraf ini:
Janji
Oleh: Dedeh Supantini
Lelaki itu membuka kancing bajunya berurutan, dari bawah ke atas. Masih seperti dulu. Hanya saja kali ini ia melakukannya dengan gerakan sangat lambat. Mungkin karena sebagian rambutnya telah memutih, dan tatapannya tidak setajam dulu. Namun ketika ia memandangku, aku menghindar, tidak siap menjawab permintaan maaf yang terlukis pada sinar matanya. Maaf adalah kata yang mudah diungkapkan bila ia sedang terdesak. Kini aku memilih diam. Sepuluh tahun tidak berjumpa dengannya membuatku lupa, sampai tahap mana sudah kumaafkan dia, dan aku tak mau memikirkannya.
“Lis,” bisiknya lirih. Suara itu pernah mengisi hari-hariku sepenuhnya, namun sekaligus membuat hidupku porak-poranda. Suara yang kini terdengar memohon, membuat hatiku bergetar.
Kubantu ia menyibakkan kemejanya, dan tampaklah perutnya yang tegang, penuh memar kebiruan. Siapa yang melakukannya? Dengan berbisik ia sebutkan anak tirinya. Aku sudah melihat hasil USG yang dilaporkan dokter jaga tadi, tampaknya terdapat luka dalam, dan harus segera dioperasi. Rasanya perih ketika kukatakan aku harus berbicara dengan keluarganya. Aku menelan ludah, membendung air mataku. Terbayang olehku wajah perempuan yang telah merebutnya dari anak-anakku, dariku. Dan ia menangis, ketika aku berbisik bahwa aku akan ada di sisinya sampai ia bangun dari operasi dan sembuh. Aku berjanji, sebagai dokter bedahnya.
Pentigraf “Janji” bergerak dengan logika khas flash fiction: ia tidak membangun cerita dengan deret kejadian panjang, tetapi mengandalkan satu momentum, pertarungan batin seorang perempuan ketika berhadapan dengan lelaki yang pernah menghancurkan hidupnya, dan mengembangkannya melalui detail-detail kecil yang menyimpan dunia besar di baliknya. Kalimat pembuka, tentang lelaki yang membuka kancing baju “dari bawah ke atas”, segera menjadi pintu masuk ke masa silam yang tak pernah benar-benar selesai. Sebuah gesture sederhana, tetapi dalam tradisi flash fiction, gesture inilah yang menjadi pemantik memori dan sekaligus prolog tanpa penjelasan. Tidak ada cerita tentang kapan mereka berpisah, bagaimana mereka bertengkar, atau apa penyebab retaknya rumah tangga; semua itu dibiarkan menjadi ruang kosong yang diisi oleh pembaca, sebagaimana prinsip flash fiction yang menuntut partisipasi imajinatif.
Ketika narator menghindari pandangannya, kita menangkap ketegangan yang berdenyut halus, bukan melalui narasi panjang, melainkan melalui satu gerak tubuh yang menandakan seluruh sejarah mereka. Flash fiction bekerja melalui showing yang hemat, bukan telling yang bertele-tele. Dalam satu kalimat, kita sudah merasa beratnya masa lalu sepuluh tahun itu. Bahkan kalimat “sampai tahap mana sudah kumaafkan dia” bukanlah penjelasan, melainkan pengakuan yang meluncur spontan, yang memperlihatkan bahwa pemaafan bukan proses linear.
Penyebutan nama “Lis” adalah teknik lain yang lazim dalam pentigraf: nama sebagai detonator. Satu panggilan membuka lapisan-lapisan ingatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Pembaca justru merasakan kegetiran yang ditahan, karena suara lelaki itu pernah “mengisi hari-hariku sepenuhnya, namun sekaligus membuat hidupku porak-poranda.” Dalam flash fiction, kalimat ini adalah jendela ganda: ia menunjukkan dua hal bertentangan secara bersamaan (cinta dan kehancuran), tetapi tidak merinci salah satunya. Kehematan justru membuat kedalaman emosi lebih kuat.
Ketika narator membantu menyibakkan kemeja lelaki itu, kita memasuki konflik yang lebih rumit. Flash fiction selalu mengandalkan detail tubuh untuk menghadirkan kedekatan tanpa melodrama. Dan di sini, tubuh lelaki itu, perut yang tegang, penuh memar, menjadi medan simbolik. Tidak perlu dijelaskan betapa keras hidup yang ia jalani kini; cukup dengan memar kebiruan itu, pembaca mengerti bahwa kehidupan baru lelaki itu tidak lebih bahagia dari kehidupan lamanya. Detail memar itu berfungsi sebagai twist emosional, bukan twist peristiwa. Seperti sebagian besar karya pentigraf yang kuat, twist di sini bukan tentang “kejutan cerita”, tetapi tentang pembalikan rasa.
Flash fiction sering menjadikan dialog sebagai pemicu perubahan suasana. Ketika lelaki itu menyebut anak tirinya sebagai penyebab kekerasan itu, emosi narator dan pembaca sama-sama bergetar. Ada ironi yang bekerja tanpa harus diteriakkan: lelaki yang dulu meninggalkan istrinya kini hidup dalam kekerasan rumah tangga yang dibangun oleh pilihannya sendiri. Pentigraf ini bergerak tidak dengan moralitas hitam-putih, tetapi dengan ironi senyap, salah satu kekuatan utama yang membuat flash fiction menyengat.
Bagian paling pentigrafik muncul ketika narator berkata ia harus berbicara dengan keluarganya. Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung ketegangan moral: ia harus menghubungi perempuan yang dulu merebut suaminya. Dedeh Supantini mengandalkan lubang-lubang naratif sebagai sumber ketegangan, karena dalam flash fiction, apa yang tidak dikatakan sering lebih berbicara daripada apa yang diucapkan. Kita tak tahu bagaimana hubungan mereka kini, tetapi kita merasakan getaran batin narator yang “menelan ludah, membendung air mata.”
Dan lalu, di titik puncak, muncullah inti khas flash fiction: pergeseran perspektif yang mengejutkan tetapi tak dipaksakan, narator ternyata adalah dokter bedahnya. Seluruh ketegangan batin itu bukan hanya tentang luka masa lalu, tetapi tentang profesionalisme yang berhadapan dengan trauma personal. Pentigraf sebagai bentuk memang sering mempertemukan private pain dengan public duty. Janji yang ia ucapkan bukan janji memulihkan hubungan lama, melainkan janji dalam kapasitasnya sebagai dokter: janji untuk berada di sisinya sampai ia sembuh.
Inilah puncak “ledakan senyap” yang menjadi prinsip utama flash fiction: bukan ledakan peristiwa, tetapi ledakan makna. Dalam ruang yang sangat sempit, kita melihat bagaimana seorang perempuan berdiri di tengah pusaran rasa, luka, dendam yang mengering, belas kasih yang tak hilang, dan etos profesi yang menuntut ia melampaui kepahitan masa lalu.
Flash fiction tidak meminta kita memahami seluruh kisah hidup tokoh-tokohnya; ia justru mengajak pembaca menyimpulkan “kisah besar” dari “fragmen kecil.” Pentigraf “Janji” berhasil memadatkan satu dekade luka menjadi beberapa paragraf yang terasa seperti satu tarikan napas—panjang, pahit, tetapi jujur. Dan di akhir, kita tidak hanya mengerti tokoh “aku”, tetapi juga merasa ia telah menang atas dirinya sendiri, tanpa perlu mengatakan apa pun secara berlebihan.
Begitulah pentigraf bekerja: ringkas, rapat, tetapi meninggalkan gema panjang.
Dimensi Sosial dan Kultural: Pentigraf sebagai Gerakan Literasi
Pentigraf tidak hanya beroperasi sebagai bentuk estetika, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang membentuk pola baru dalam praktik literasi di Indonesia. Dalam konteks pendidikan formal, pentigraf menunjukkan efektivitas sebagai alat pedagogis yang memadukan literasi fungsional dan estetis. Literasi fungsional berkaitan dengan kemampuan memahami, mengolah, dan memproduksi teks secara efisien; sementara literasi estetis menekankan penghayatan terhadap makna, rasa, dan keindahan bahasa. Pentigraf berada di titik temu keduanya: bentuknya yang ringkas memudahkan siswa memasuki dunia menulis tanpa hambatan teknis, tetapi tetap menuntut sensitivitas bahasa, ketepatan struktur, dan pengolahan gagasan yang mendalam. Dalam praktik, guru memanfaatkan pentigraf untuk melatih kreativitas, membangun kecakapan berbahasa, mengembangkan kemampuan menyusun gagasan secara sistematis, dan menumbuhkan critical thinking melalui pemadatan konflik dan refleksi.
Penggunaan pentigraf dalam lingkungan pendidikan juga berfungsi sebagai strategi inklusif untuk mengajak siswa yang biasanya enggan menulis panjang. Tiga paragraf memberikan ruang yang cukup sempit untuk mencegah rasa kewalahan, tetapi cukup luas untuk menyampaikan kisah. Dalam lingkungan perguruan tinggi, pentigraf digunakan tidak hanya dalam mata kuliah kepenulisan kreatif, tetapi juga untuk mendorong refleksi akademik, etnografi mini, hingga analisis fenomena sosial. Dengan demikian, pentigraf berperan dalam memperluas definisi literasi akademik yang tidak hanya berbasis argumentasi panjang, tetapi juga berbasis kejelian naratif dan ketajaman refleksi.
Lebih jauh, pentigraf membentuk sebuah ekosistem sosial yang memunculkan komunitas baru dan memperkuat budaya literasi akar rumput. Salah satu komunitas paling menonjol adalah Kampung Pentigraf Indonesia, yang menjadikan pentigraf sebagai sarana kolektif untuk menumbuhkan kebiasaan menulis, berbagi, dan berdiskusi. Dalam perspektif sosiologi budaya Pierre Bourdieu, kegiatan literasi semacam ini menghasilkan cultural capital, yaitu modal kultural yang diperoleh melalui interaksi kolektif dan praktik simbolik [7]. Melalui pentigraf, individu memperoleh modal dalam bentuk kemampuan menulis, kepercayaan diri kreatif, pengakuan sosial, serta jaringan yang memperkuat habitus literer. Komunitas pentigraf memperlihatkan bahwa literasi bukan hanya aktivitas individual, tetapi merupakan praktik sosial yang dibentuk oleh kebersamaan, partisipasi, dan persebaran nilai-nilai kultural.
Pentigraf juga berfungsi sebagai wahana demokratisasi sastra. Bentuknya yang ringkas dan mudah diakses membuka ruang bagi siapa saja, anak sekolah, guru, buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja pabrik, hingga pensiunan, untuk berpartisipasi dalam dunia kepenulisan. Dalam tradisi sastra yang sering dianggap eksklusif dan elitis, pentigraf memecah batas hierarki tersebut: ia menurunkan ambang masuk ke dunia menulis, tetapi tidak menurunkan kualitas refleksi atau kedalaman pesan. Fenomena ini sejalan dengan konsep participatory culture (Jenkins, 2006), yaitu budaya di mana individu bukan hanya konsumen, tetapi juga produsen konten kreatif. Pentigraf mendorong munculnya produsen sastra baru dalam skala luas, sehingga memperkaya khazanah naratif yang berasal dari berbagai latar sosial dan pengalaman hidup.
Di ruang digital, pentigraf menemukan habitat idealnya. Tiga paragraf memungkinkan teks dibaca dalam satu guliran layar ponsel, sehingga sangat selaras dengan logika micro-reading habits yang berkembang dalam era media sosial. Bentuk ini memperlihatkan bagaimana sastra dapat beradaptasi secara organik dengan ekologi digital. Dalam ruang digital, pentigraf tidak hanya berfungsi sebagai teks sastra, tetapi juga sebagai social object, sebuah objek yang mengundang interaksi, komentar, perbincangan, dan remiksasi. Pembaca menjadi peserta aktif yang menanggapi, mengadaptasi, atau bahkan menciptakan pentigraf tandingan. Hal ini menunjukkan bahwa pentigraf bergerak melampaui status sebagai karya seni individual, dan berkembang menjadi praktik sosial yang menegosiasikan makna secara kolektif.
Perkembangan pentigraf di platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan forum literasi daring memperlihatkan bahwa bentuk sastra ini telah bertransformasi menjadi modal budaya baru yang memperluas literasi digital. Sama seperti haiku yang menjadi bentuk populer dalam budaya Jepang atau microfiction yang tumbuh di Barat, pentigraf telah menemukan ruang publiknya sendiri dalam masyarakat Indonesia. Adaptasi sastra terhadap media digital tidak hanya menghasilkan perubahan bentuk, tetapi juga perubahan perilaku literer: orang membaca lebih sering, menulis lebih sering, dan berdialog lebih sering dalam durasi konten yang singkat namun sarat makna.
Dengan demikian, pentigraf sebagai gerakan literasi tidak hanya menegaskan relevansi estetiknya, tetapi juga signifikansi sosial dan kulturalnya. Ia menghubungkan ruang pendidikan, komunitas sosial, dan dunia digital dalam satu ekosistem literasi yang dinamis; memperluas partisipasi publik dalam kegiatan menulis; serta menegaskan bahwa sastra, sekalipun dalam bentuk yang sangat ringkas, tetap mampu menjadi kekuatan transformatif dalam kehidupan masyarakat kontemporer.
Fungsi Nilai, Moral, dan Kesadaran Sosial
Selain nilai estetis dan eksperimentasi bentuk, pentigraf mengemban fungsi moral dan sosial yang kuat. Ia bukan sekadar cerita tiga paragraf, tetapi juga ruang etis tempat penulis dan pembaca merenungkan nilai, konflik, dan tanggung jawab kemanusiaan. Dalam banyak pentigraf, kepekaan moral hadir bukan melalui kotbah atau nasihat langsung, tetapi melalui representasi situasi manusia yang getir, paradoksal, dan sering kali tragis. Struktur ringkasnya membuat pesan moral justru terasa lebih intens: satu gesture, satu dialog, atau satu ironi dapat menghadirkan kesadaran batin yang lebih tajam daripada uraian panjang.
Dalam konteks teori sastra Indonesia, pentigraf memiliki kedekatan dengan gagasan sastra profetik ala Kuntowijoyo (2006), yaitu sastra yang memikul tiga mandat: humanisasi, liberasi, dan transendensi [8]. Pentigraf dapat menggerakkan humanisasi melalui penggambaran penderitaan, empati, dan relasi antar-manusia dalam bentuk mikro; ia berperan dalam liberasi melalui kritik terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang timpang; serta menyiratkan transendensi melalui nilai reflektif atau spiritual yang sering hadir secara subtil. Meskipun tidak semua pentigraf bersifat profetik, banyak karya dalam bentuk ini mengandung kepekaan moral yang paralel dengan visi tersebut, terutama karena pentigraf bekerja dengan intensitas dan kepadatan makna.
Fungsi moral pentigraf juga dapat dilihat melalui perspektif narrative ethics, yang mempelajari bagaimana cerita mempengaruhi cara pembaca memahami tindakan baik-buruk, adil-tidak adil, benar-salah. Dalam ruang tiga paragraf, narasi sering menghadirkan situasi dilematis, ketegangan nilai, atau paradoks moral yang menuntut pembaca untuk melakukan refleksi. Ketika seorang tokoh hanya berkata satu kalimat pendek sebelum pergi meninggalkan rumah, atau ketika seorang anak menatap pohon gundul setelah banjir merenggut keluarganya, pembaca dipaksa masuk ke wilayah keputusan moral tanpa diberi penjelasan siap pakai. Inilah kekuatan pentigraf: ia menghadirkan moralitas sebagai pengalaman, bukan sebagai doktrin.
Dimensi sosial pentigraf juga sangat menonjol karena topik-topik yang diangkat sering berasal dari denyut kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Cerita tiga paragraf dapat menyorot isu kemiskinan struktural, ketidakadilan gender, pekerja informal, konflik antargenerasi, atau kesenjangan pendidikan. Pentigraf tidak hanya merekam realitas, tetapi menginterogasi realitas tersebut melalui sudut pandang yang tajam dan terkadang satir. Ia bekerja seperti potret sosial mini: kecil, tetapi sarat ketegangan.
Dalam ranah ekologis, pentigraf sering menjadi medium ekokritik yang efektif. Ketika pentigraf berbicara tentang banjir di Sumatera atau Kalimantan, misalnya, ia tidak berhenti pada gambaran air yang naik atau rumah yang hanyut. Dalam kedalaman simbolik dan metaforiknya, ia menyiratkan rantai sebab-akibat ekologis yang lebih luas: deforestasi, pembiaran korporasi tambang, korupsi struktural, serta ketidakmampuan negara menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam bentuk ringkas, kritik ekologis menjadi lebih telak: banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana moral dan politik.
Pada topik keluarga, pentigraf sering menyentuh trauma yang tersembunyi, kesenyapan yang tidak terucapkan, dan ironi kehidupan modern. Karena ruangnya yang terbatas, penulis memilih momen paling esensial: tatapan kosong seorang ibu, suara piring jatuh, pintu yang tertutup terlalu keras. Setiap detail kecil mengandung dunia emosional yang luas. Dengan demikian, pentigraf menjadi medium representasi psikososial yang kuat—ia menunjukkan bagaimana keluarga dapat menjadi ruang kasih, tetapi juga ruang luka.
Efektivitas pentigraf sebagai medium kesadaran sosial terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan kejernihan moral dalam bentuk yang sangat terkompresi. Pesan sosial dalam pentigraf tidak memerlukan deskripsi panjang; justru keringkasan memaksa moralitas tampil dalam bentuk yang langsung, tajam, dan sering kali menghunjam. Karena itu, pentigraf mampu menjadi katalis refleksi bagi pembacanya. Pembaca dipaksa berhenti sejenak, menatap ulang realitas yang mungkin selama ini diabaikan.
Lebih penting lagi, pentigraf memiliki potensi untuk menggugah kesadaran publik karena ia mudah disebarluaskan melalui media sosial. Cerita tiga paragraf yang mengandung kritik sosial atau nilai moral dapat berfungsi sebagai trigger awareness: pemantik diskusi, debat, advokasi, atau empati kolektif. Di sinilah pentigraf menunjukkan fungsinya bukan hanya sebagai produk sastra, tetapi sebagai praktik budaya yang ikut membentuk wacana publik.
Dengan demikian, fungsi nilai, moral, dan kesadaran sosial dalam pentigraf memperlihatkan bahwa bentuk sastra yang ringkas sekalipun mampu membawa beban etis yang besar. Pentigraf menjadi ruang di mana estetika bertemu etika, narasi bertemu refleksi, dan cerita kecil membuka pintu menuju kesadaran kemanusiaan yang lebih luas.
Sastra dan Pentigraf Berdampak
Dalam kajian humaniora modern, istilah sastra berdampak tidak hanya merujuk pada kualitas estetik sebuah karya, tetapi pada kemampuan karya itu menciptakan pengalaman transformasional bagi pembacanya maupun penulisnya. Sastra berdampak merupakan bentuk seni yang bekerja dalam ranah psikologis, kognitif, dan etis: ia mengubah cara seseorang memahami dunia, menata ulang sensitivitas terhadap realitas sosial, serta memperluas cakrawala empati. Wolfgang Iser (1978) menegaskan bahwa karya sastra yang baik selalu “menggerakkan kesadaran” pembaca karena ia menciptakan ruang untuk self-reflection, sebuah proses internal ketika pembaca tidak hanya menyerap makna, tetapi mengujinya dalam konteks pengalaman hidupnya sendiri [5]. Dengan demikian, sastra berdampak adalah sastra yang hidup dalam diri pembaca, menggugah, mengusik, atau bahkan mengganggu kenyamanan persepsinya.
Dampak sastra bekerja dalam dua arah yang saling berkait: bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis, proses kreatif sastra adalah bentuk self-reflective practice, yaitu praktik menata dan memahami diri melalui bahasa. Menulis memaksa penulis menyaring pengalaman, mengolah emosi, menstruktur gagasan, dan menentukan nilai yang ingin ditegaskan. Proses ini dapat dibaca melalui lensa psikologi sastra sebagai proses meaning-making, yakni usaha manusia memberi makna pada pengalaman yang kompleks atau traumatis. Ketika penulis merumuskan kisah, ia sebenarnya sedang membangun struktur makna untuk dirinya sendiri. Di sinilah terlihat bahwa sastra berdampak bagi penulis bukan hanya karena ia menghasilkan karya, tetapi karena proses kreatif itu sendiri adalah ritual pembentukan kedewasaan intelektual dan emosional.
Sebaliknya, bagi pembaca, sastra berdampak ketika teks mampu membuka ruang refleksi baru, memperkenalkan perspektif yang tidak dikenal sebelumnya, mengganggu asumsi yang mapan, atau memantik empati terhadap penderitaan dan pengalaman orang lain. Proses ini merupakan bagian dari dinamika hermeneutis: pembaca tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi menginternalisasi makna-makna simbolik hingga mempengaruhi sikap dan kesadarannya. Dalam hal ini, sastra berdampak memiliki fungsi etis dan sosial karena ia membentuk moral imagination, kemampuan membayangkan kemungkinan moral dalam situasi manusia yang rumit.
Pentigraf Berdampak sebagai Artikulasi Mikro dari Sastra Berdampak
Dalam kerangka tersebut, pentigraf berdampak dapat dianggap sebagai bentuk paling ringkas namun efektif dari prinsip sastra berdampak. Sebagai cerita tiga paragraf, pentigraf memadatkan konflik, emosi, dan gagasan ke dalam ruang ultra-singkat. Kompresi inilah yang menciptakan intensitas: pembaca tidak diberi kesempatan untuk menunda atau melarikan diri dari pesan cerita; ia dihantam sekaligus dalam tiga hentakan naratif. Prinsip flash fiction yang dikemukakan Thomas (2015)—bahwa kekuatan cerita ultra-pendek terletak pada “impact delivered in an instant”, bekerja sempurna dalam pentigraf.
Bagi penulis, pentigraf berdampak karena proses penciptaannya menuntut:
- kejernihan berpikir, penulis harus mengetahui inti konflik dengan presisi;
- ketepatan diksi, setiap kata memikul beban makna;
- keberanian menghapus, bagian yang tidak esensial harus dieliminasi;
- ketelitian dramatik, paragraf ketiga harus menghantarkan efek makna yang signifikan.
Menulis pentigraf menjadi latihan disiplin estetik dan intelektual. Ia menuntut penulis menangkap esensi manusia dalam tiga detik naratif. Proses ini meningkatkan sensitivitas kreatif, memperkuat intuisi dramatik, dan menumbuhkan kemampuan membaca kehidupan secara lebih reflektif.
Bagi pembaca, pentigraf berdampak karena ia menawarkan:
- pengalaman literer yang cepat namun tidak dangkal,
- kejutan kognitif melalui twist atau ironi di paragraf ketiga,
- ruang refleksi yang muncul dari kekosongan-kekosongan naratif yang harus diisi,
- pemicu empati melalui gambaran situasi manusia yang tajam dan padat.
Dalam satu guliran layar, pembaca memasuki dunia kecil yang kadang menampar, kadang menyadarkan, kadang menghangatkan, dan kadang menggelisahkan. Kompresi inilah yang membuat pentigraf menjadi medium efektif untuk menggugah kesadaran sosial dan moral.
Pentigraf Berdampak sebagai Demokratisasi Literasi dan Wacana Publik
Lebih jauh lagi, pentigraf berdampak karena ia menggeser praktik sastra dari ruang eksklusif ke ranah partisipatif. Bentuknya yang ringkas menjadikannya mudah dipelajari dan ditulis oleh berbagai kalangan, dari pelajar, guru, pekerja pabrik, ibu rumah tangga, para purnawirawan atau purnabakti, dokter, pengacara, mahasiswa, dosen, karyawan hingga komunitas digital. Ketika semakin banyak orang menulis dan membaca pentigraf, literasi tidak hanya menjadi kemampuan individual, tetapi menjadi gerakan kultural. Pentigraf mengubah menulis dari aktivitas sunyi menjadi aktivitas sosial: orang menulis, mengunggah, mengomentari, merefleksi, dan berdialog.
Dalam perspektif ini, pentigraf berdampak memperluas pengertian sastra berdampak. Dampak sastra tidak lagi terbatas pada efek estetik di ruang akademik atau kritik sastra, tetapi berwujud pada: kebiasaan membaca dan menulis yang meningkat, keberanian masyarakat mengekspresikan pengalaman, munculnya komunitas kreatif yang saling mendukung, dan penyebaran nilai-nilai empati, kesetaraan, dan refleksi sosial.
Dengan demikian, pentigraf berdampak adalah bukti bahwa karya yang sangat singkat pun dapat menjadi alat transformasi sosial dan psikologis. Ia membuktikan bahwa inti kekuatan sastra tidak ditentukan oleh panjang teks, tetapi oleh kedalaman resonansinya, oleh cara ia meresonansikan nilai, pengalaman, dan luka manusia ke dalam hati penulis maupun pembacanya.
Kesimpulan
Pentigraf merupakan salah satu inovasi sastra paling signifikan dalam ekosistem literasi Indonesia kontemporer. Sebagai bentuk cerita tiga paragraf, ia berdiri pada persimpangan antara estetika tradisi dan kebutuhan zaman modern: memadukan ketepatan struktur minimalis dengan kedalaman makna yang resonan. Dalam kerangka global, pentigraf dapat disejajarkan dengan tradisi flash fiction, namun tetap mempertahankan identitas lokal melalui idiom, metafora, dan persoalan sosial-budaya yang khas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pentigraf bukan sekadar adaptasi, melainkan kontribusi orisinal dalam percakapan sastra dunia mengenai narasi mikro.
Lebih dari sekadar bentuk estetik, pentigraf telah menjelma menjadi praktik kultural yang menghidupkan kembali semangat literasi publik. Penerapannya yang luas, dari ruang kelas, komunitas sastra, hingga media digital, membuktikan bahwa pentigraf mampu menjawab kebutuhan pedagogis dan kultural masyarakat. Ia memudahkan pengajaran menulis kreatif, melatih kepekaan bahasa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menumbuhkan kebiasaan membaca yang lebih berkelanjutan dalam era di mana perhatian manusia kian terfragmen. Dalam konteks ini, pentigraf memainkan peran strategis dalam memajukan literasi fungsional sekaligus literasi estetis.
Pada tingkat sosial, pentigraf menciptakan ruang yang inklusif dan egaliter. Sifatnya yang ringkas membuat kegiatan menulis menjadi lebih dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Pentigraf berhasil meruntuhkan mitos bahwa menulis adalah aktivitas eksklusif milik kalangan terdidik atau profesional sastra; siapa pun dapat menyusun tiga paragraf yang bermakna. Proses ini melahirkan bentuk demokratisasi sastra yang nyata: masyarakat tidak hanya menjadi konsumen narasi, tetapi juga produsen pengalaman, nilai, dan refleksi. Fenomena ini memperkuat posisi pentigraf sebagai agen pembentuk kesadaran kultural baru yang lebih dialogis, partisipatif, dan reflektif.
Dari sisi filosofis dan estetika, pentigraf membuktikan bahwa panjang teks tidak menentukan kedalaman pengalaman sastra. Justru kekuatan pentigraf terletak pada pemadatan makna, efektivitas simbolik, dan kemampuan memusatkan konflik dalam ruang naratif yang minimal. Tiga paragraf yang singkat itu menjadi wadah bagi energi dramatik yang intens, yang mampu menggugah, mengusik, bahkan mengubah cara pembaca memandang kehidupan. Pentigraf menunjukkan bahwa sastra tetap memiliki kemampuan untuk menyentuh inti pengalaman manusia, meskipun dibungkus dalam bentuk yang seolah sederhana.
Dengan demikian, pentigraf adalah bentuk sastra yang tidak hanya relevan secara estetis, tetapi juga strategis secara sosial, pedagogis, dan kultural. Ia menjawab tantangan era digital tanpa mengorbankan kedalaman refleksi, sekaligus membuka jalan bagi munculnya generasi baru penulis dan pembaca yang lebih peka terhadap realitas kehidupan. Pada akhirnya, pentigraf mengajarkan bahwa dalam tiga paragraf ringkas, sastra dapat tetap menjadi ruang penghayatan, medan pemaknaan, dan kekuatan transformasi. Ia membuktikan bahwa dalam kelincahan mikro-narasinya, sastra tidak kehilangan kemampuan untuk menyentuh manusia, menggugah kesadaran, dan menyeberangkan makna dari satu hati ke hati yang lain.
Surabaya, 6 Desember 2025
—-
Daftar Referensi
[1] Shapard, R., & Thomas, J. (1986). Sudden Fiction: American Short-Short Stories. New York: W.W. Norton.
[2] Thomas, J., Shapard, R., & Merrill, C. (2015). Flash Fiction International. New York: W.W. Norton.
[3] Ní Chonchúir, N. (2012). Flash Fiction: A Guide. Dublin: Arlen House.
[4] Calvino, I. (1988). Six Memos for the Next Millennium. Cambridge: Harvard University Press.
[5] Iser, W. (1978). The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
[6] Bolton, G. (2010). Reflective Practice: Writing and Professional Development. London: SAGE.
[7] Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood.
[8] Kuntowijoyo. (2006). Maklumat Sastra Profetik. Bandung: Mizan.
—-
*Tengsoe Tjahjono lahir di Jember 3 Oktober 1958. Penyair ini pernah mengajar di Hankuk University of Foreign Studies Korea (2014-2017). Sejak pensiun dari Universitas Negeri Surabaya (2023) ia mengajar di Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 2012 mendapat penghargaan sebagai Sastrawan Berprestasi dari Gubernur Jawa Timur. Buku puisinya Meditasi Kimchi memperoleh Anugerah Sutasoma 2017 dari Balai Bahasa Jawa Timur. Penggagas cerpen tiga paragraf (pentigraf). Atas dedikasinya berkarya 40 tahun di bidang sastra ia memperoleh penghargaan dari pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa pada tahun 2024. Tahun 2025 memperoleh Anugerah Sabda Budaya dari FIB Universitas Brawijaya Malang. Karya antologi puisi terbaru: Dari Menjerat Sepatu Sampai Membuka dan Menutup Jendela (2021), Pelajaran Menggambar Bentuk (2023), 17-an di Kampung Halaman (2024), Jenggirat (2025), Onggi (kumpulan pentigraf tentang Korea, 2025), dan Kursi Malas di Depan Jendela (kumpulan monolog, 2025).