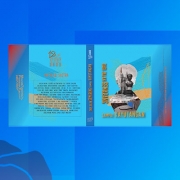Pengalaman Galeri Indonesia Kaya
Oleh Mike Hapsari*
Malam itu, di sebuah warung kopi saya duduk termenung, menatap kosong layar laptop sembari membayangkan susunan kata yang harus dituliskan pada lembar proposal. Buntu, malam itu sangatlah buntu, saya tidak tahu apa yang harus dijelaskan lagi. Beberapa menit berlalu masih dengan posisi yang sama, hingga pada akhirnya hp ini bergetar memecahkan pandangan. Terlihat ada telepon dari Alisa, dia menanyakan jadwal dan mengatakan bahwa ingin mengundang teman-teman Festival Mentari (projek Padang Panjang), untuk datang ke Jakarta dan pentas di Galeri Indonesia Kaya. Mendengarkan tawaran tersebut tanpa berpikir panjang saya langsung mengatakan, “gaasss!!”
Beberapa kali sebelum keberangkatan ke Jakarta, saya dan teman-teman yang lain dipertemukan secara online. Kami membahas tema yang akan digarap dan saling bertukar pengalaman mengenai sawah yang ada di tempat kami tinggal.
Kebetulan, saya dan keluarga merasakan perubahan yang sangat drastis selama mendirikan rumah di daerah ini. Kami adalah penghuni pertama lingkungan Bulak Indah di tahun 90’an. Rumah kami tepat berada di tengah hamparan sawah, tanpa tetangga. Teman kami hanyalah petani-petani yang biasa berlalu-lalang di depan rumah, dan para peternak kerbau dan bebek yang sering membuat gaduh anjing-anjing kami untuk menggonggongi mereka. Sinar matahari dari timur masih sering kami rasakan bila pagi datang. Udara sejuk dan embun pagi yang menaungi sinar mentari, memanggil kami untuk keluar dan berjemur sebelum memulai hari. Saat itu saya masih kecil, mungkin belum sekolah. Kedua kakak saya sudah remaja, dan sering mereka mengundang teman-teman sekolahnya untuk main ke rumah. Sebenarnya tidak main di rumah, tapi mereka main di sawah depan rumah untuk mencari keong dan kodok sebagai bahan masak mereka. Sering kali melihat gerombolan teman kakak-kakak saya datang merayakan ulang tahun, bukan ulang tahun biasa dengan kue, namun melemparkan orang yang sedang berulang tahun ke sawah yang masih basah, hingga akhirnya mereka bermain lumpur di sawah. Tawa mereka lepas, tidak ada rasa segan untuk sesekali berteriak. Hanya suara merekalah yang memecahkan keheningan rumah kami. Tidak hanya mereka yang kami kenal untuk datang masuk ke rumah tanpa diundang, namun seringkali tamu yang tidak kami kenal pun ikut mencari tempat nyaman di dalam rumah. Iya, kami berteman akrab dengan ular, garangan, tikus got raksasa, biawak dan beberapa hewan sawah yang masih berkeliaran. Ayam-ayam kami juga menghilang satu per satu, atau terkadang kami melihat kaki mereka terluka di pagi hari saat membuka kandang. Sering melihat ular yang sedang berkamuflase di tanaman anggur, ular yang sedang tidur melingkar di bawah tumpukan perkakas, ular yang sedang melata di tembok, terjatuh dari atap, hingga ular kobra yang sedang menyeberangi sawah sambil mengangkat kepalanya. Saking jengkelnya atas keberadaan mereka, kami pun memutuskan untuk mempertemukan mereka dalam satu tempat, galon minum Aqua. Satu bulan, kami bisa mengumpulkan lebih dari sepuluh ular yang mampir ke rumah.
Setiap hari saat musim panen tiba, suara penggiling padi dinyalakan hingga sore hari datang. Suara riuh mesin dan candaan para petani menemani saya saat ditinggal di rumah sendirian. Semasa kecil, saya sering ditinggal di rumah sendiri, karena kedua kakak saya sekolah dan orang tua bekerja. Tidak ingat, siapa yang mengasuh saya kala itu. Yang saya ingat, hanya dua anjing Rottweiler yang selalu berada di kanan kiri untuk menjaga. Saat mesin penggiling berhenti, samar-samar kegiatan mereka meninggalkan aroma jerami segar, serta tumpukan yang dibiarkan di samping rumah. Mengingatkan saya pada salah satu scene film Bollywood yang kala itu populer di masanya. Segerombolan orang berlari dan menari di atas tumpukan jerami sembari bernyanyi. Membawa tubuh ini untuk melakukan hal serupa seperti apa yang ada di dalam film yang saya tonton. Berguling kesana-kemari, melempari anjing-anjing saya dengan jerami, dan saking senangnya mereka menggigit dan menarik baju saya hingga bolong. Kami senang bisa bermain di luar rumah, terutama di tumpukan jerami sore itu. Namun kebahagiaan kami runtuh saat terdengar teriakan lelaki yang memanggil nama saya, “Mikeee!!”. Ya, itu Ayah saya yang sudah membawa sapu dan mulai mendekat sembari memarahi saya karena bermain di tumpukan jerami. Beberapa kali kaki ini mendapat pukulan yang diayunkan olehnya, menyuruh saya untuk mandi, dan tidak mengulanginya lagi. Namun, kalau sekarang saya memikirkan hal tersebut, rasanya apa yang dikatakan Ayah saya benar, kenapa Beliau melarang keras untuk gulung-gulung di jerami. Karena tidak terpikirkan oleh saya saat itu, bahwa ada kemungkinan ular-ular sedang bersembunyi dibawah tumpukan jerami yang pastinya membahayakan diri saya. Masih banyak pengalaman yang membekas dalam kepala saya mengenai suasana rumah kami saat itu.
Beberapa tahun mulai berlalu, hingga saya memasuki sekolah dasar di tahun terakhir. Saya ingat betul bahwa sawah-sawah di depan rumah kami telah dibeli dan akan diadakannya pembangunan perumahan. Awalnya saya senang, karena akhirnya kami memiliki tetangga yang menemani. Satu per satu rumah siap untuk ditempati, dan pendatang baru mulai bermunculan. Hampir setiap bulan ada tamu berkunjung ke rumah, sambil membawa bingkisan dan memperkenalkan diri bahwa mereka tetangga baru lingkungan ini. Kami hidup rukun dan damai hingga sekarang. Keluarga kami selalu dianggap tetua di lingkungan tempat kami tinggal. Bahkan terkadang mereka yang harus menyesuaikan kami, terutama dengan keberisikan anjing-anjing kami yang mulai banyak ini. Sekarang, banyak orang serta kendaraan seperti motor dan mobil yang berlalu-lalang di depan rumah, karena di sebalik perumahan yang berdiri di depan rumah kami sudah ada SMP Negeri 3, jadi tak heran bila siang hingga sore banyak anak-anak yang mulai menggoda anjing-anjing kami. Jalan di depan rumah kami sudah seperti jalan utama. Motor dan mobil melintas dengan kecepatan tinggi. Tepat di kanan kiri rumah kami ada tanah kosong milik orang. Sebelahnya lagi sudah berdiri rumah dan kost-kostan mahasiswa UMS. Warung makan, kafe, dan kost-kostan eksklusif sudah berdiri tegak untuk beberapa tahun belakangan ini. Menambah bangunan untuk memfasilitasi mahasiswa dan menghilangkan sawah-sawah yang ada. Kegiatan bercocok tanam sudah jarang terlihat, bahkan saya bertanya dimana kerbau-kerbau dan bebek-bebek sekarang mencari lahan untuk makan? Sekarang, saat kami berbicara pun tidak bisa selepas seperti dulu. Saya tidak bisa membayangkan bila tepat di sebelah kanan kiri kami sudah dibangun rumah, mungkin kami akan bisa mendengarkan apa yang sedang mereka lakukan di dalam rumah. Jujur, saya sangat stress dengan keadaan rumah saat ini. Saya merasa tidak memiliki privasi.
Ingatan diatas muncul, hanya dengan satu pertanyaan yang dilontarkan saat pertemuan online itu berlangsung. Kebetulan saya dan Alisa (Jakarta) akan bekerjasama dalam membuat karya duet. Kami memiliki latar belakang yang berbeda, serta tempat dimana kami tinggal pun berbeda. Saya merasakan adanya sebuah perubahan, sedangkan Alisa memang tinggal dimana tidak ada sawah atau kegiatan bercocok tanam di sekitarnya. Hal itu juga memberikan pengaruh pada orang-orang yang hidup dan berkembang di tempat tersebut. Saya harus beradaptasi dengan keadaan dan perubahan yang memang jalannya harus seperti itu. Satu per satu lahan dibeli dan diolah, hingga pada akhirnya pandangan mata itu tersekat oleh dinding-dinding tembok yang berdiri. Sedangkan Alisa sudah terbiasa dengan himpitan, dan segala sesuatu memang harus bergerak dengan cepat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Saat berada di Jakarta, proses kami sangat singkat. Kami bertukar pikiran dan pengalaman selama hidup dan berkembang di tempat kami tinggal. Kami memiliki kesamaan yang terjadi di lingkungan dimana kami tinggali saat ini. Walau terkadang kami tidak bertegur sapa dengan tetangga namun ada satu kegiatan yang mampu merekatkan komunikasi yaitu, dengan bermain badminton. Aktivitas tersebut kami tampilkan pada awal pembukaan karya kami yang berdurasi 15 menit. Dengan menggunakan setelan daster dan sandal jepit, kami berusaha bermain seserius mungkin menutupi ketidakmampuan kami dalam menangkis kok, diiringi dengan narasi mengenai perbedaan lahan di antara tempat kami tinggal. Alisa dan saya, sepakat untuk mencari dan merekam keadaan yang saat ini terjadi, serta perubahan yang kami alami di tempat tinggal masing-masing. Saya berusaha mencari lahan sawah yang tersisa di sekitar rumah, serta saya berusaha mencari keberadaan kerbau-kerbau yang biasanya lewat depan rumah. Ternyata saya menemukan mereka. Mereka berjalan cukup jauh dari tempat dimana mereka dikandangkan, dan tentu saja mereka mencari makan di lahan yang terhimpit rumah-rumah tinggi. Sungguh pemandangan yang cukup menyayat hati. Tempat mereka mulai mengecil, saya tidak bisa membayangkan dimana mereka akan mencari makan bisa suatu saat nanti lahan tersebut habis. Disisi lain, Alisa membawakan rentetan hasil rekamannya mengenai landscape Jakarta. Setelahnya adapun kumpulan video suasana sawah dan perkotaan yang ditembakan di belakang kami. Eksplorasi kami susun sedemikian rupa, mengingat pengalaman apa yang telah kami lalui di lingkungan tempat dimana kami tinggal. Kami mulai melihat material apa yang sekiranya sangat cocok untuk menggambarkan keadaan lingkungan dimana kami tinggal. Seperti contohnya, saya menganggap lumpur disawah merupakan material yang sangat cocok untuk menggambarkan tempat ini. Pergerakan perlahan tapi pasti, tetap cair namun memiliki berat yang mampu menggambarkan keadaan yang sedang mulai bergeser dengan durasi yang sangat lama. Sedang berkembang dengan durasi tertentu untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Alisa berusaha merasakan tubuhnya yang hidup dan berkembang dengan segala batasan dan pergerakan yang serba cepat. Menghantar tubuh Alisa untuk selalu berubah dalam segala situasi. Gerakan kami yang sangat kontras memberi kesan dua ruang yang sedang berusaha dijadikan satu. Imajinasi membawa tubuh kami untuk bergerak, berusaha untuk merasakan dan menjadi seperti apa yang kami bayangkan. Sesekali tubuh kami bergerak secara selaras. Walau kami memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda mengenai tari, namun kami mampu membuat sesuatu yang dapat membuka dan memberi ruang untuk penikmat seni.
Sebenarnya, dari semua proses pengalaman berkarya di Jakarta, saya justru lebih merasakan bagaimana tubuh saya beradaptasi di kota besar yang sangat padat ini. Saat itu, saya tinggal di daerah Tangerang Selatan dan harus ke Jakarta Pusat untuk latihan serta bertemu dengan teman-teman kolaborasi yang lain. Setiap pagi datang, saya harus menempuh perjalanan kurang lebih satu jam, dan harus berganti alat transportasi, gojek – KRL – transit KRL – gojek. Saya paham, mungkin cara tersebut adalah cara yang paling mudah untuk pergi, dan paling murah. Namun, saya merasa lelah harus menunggu dan gonta-ganti alat transportasi. Belum lagi saat itu cuaca sering hujan di Jakarta. Saat sore hari tiba, disaat waktu latihan kami selesai, tepat pukul 5 sore, saya harus pulang. Sering di sosial media saya muncul beberapa video mengenai usaha orang-orang untuk pulang di waktu itu, sehingga membuat mereka harus berdempetan untuk pulang ke rumah menggunakan KRL. Dengan bayang-bayang tersebut saya memutuskan untuk pulang menggunakan Gojek, satu alat yang langsung menuju ke rumah tanpa ada waktu tambahan untuk menunggu KRL dan berganti alat transportasi lain, bahkan harus berdempetan dengan orang lain. Memang tarif Gojek sore itu memang 30 ribu lebih mahal dari paket yang saya beli di setiap paginya. Ternyata saya salah, setiap sore tiba para pekerja pun juga turut pulang menggunakan transportasi pribadi mereka. Sehingga saya terjebak macet yang memakan waktu lebih dari dua jam di atas motor. Duduk tegak, dan harus mengendalikan tubuh agar tidak terperosok ke depan saat bapak gojek mengerem motornya. Sungguh pemandangan yang membuat saya pusing. Bapak gojek pun saat itu berusaha mencarikan jalan tikus agar kami sampai tujuan dengan cepat dan menghindari macet. Namun selama perjalanan, saya melihat potret lain dari Jakarta. Rumah-rumah tersusun berdekatan satu dengan yang lain, biasanya kawasan tersebut berdiri sangat dekat di pinggir jalan utama, sehingga mengurangi lebar jalan untuk lewat. Terlihat seperti Jakarta bebas untuk membangun rumah, dimana pun yang mereka inginkan. Seperti tidak ada celah sedikit pun yang saya lihat, kosong dan berdiri sebagai lahan kosong. Sekecil apapun ruang kosong yang tersedia, pasti ada saja yang membangun rumah atau tempat bisnis ‘ilegal’ di sana. Terkadang, saya berpikir, hal tersebut juga sering saya lakukan di rumah dengan barang-barang yang tidak semestinya ditempatkan di tempat tersebut. Memang sangat memudahkan saya untuk menyelipkan barang-barang kecil ke suatu ruangan agar terlihat efisien. Namun, pada kenyataannya barang-barang tersebut menumpuk dan membuat kesan tatanan rumah menjadi kumuh. Saya bahkan mempertanyakan, apakah pemerintah juga melihat kenyataan tersebut di pinggiran pusat kota yang biasa dibangun gedung-gedung pencakar langit? Apakah tatanan pusat kota sudah cukup baik dan pantas untuk dipamerkan kepada orang-orang yang datang ke Jakarta? Lalu bagaimana dengan kenyataan yang saya lihat, bahkan ruang tersebut tidak jauh dari pusat kota? Saya merasa aneh, seperti berada di dunia lain.
Mungkin Jakarta cocok untuk didatangi bila kita ada keperluan tertentu yang mengharuskan fisik ini hadir. Saya lebih suka tinggal di Solo, walau sekarang juga menjadi kota yang mulai berkembang, namun saya rasa setiap tempat perkembangan tersebut rata. Kemudahan untuk bepergian juga menjadi salah satu faktor yang membuat kota ini nyaman. Tidak ada salahnya juga bagi mereka yang ingin pindah dan tinggal di Jakarta untuk keperluan bekerja. Namun lagi-lagi saya rasa Solo menjadi tempat yang baik untuk ditempati.


Dokumentasi oleh Galeri Indonesia Kaya. (Sumber: Penulis)
*Anggota Studio Plesungan, Peserta Program Menulis dan Kajian Buku