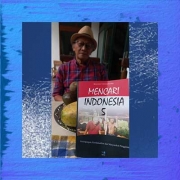Ngalah, Ngalih, Ngelih, Ngantuk
Arsitektur Kesadaran dalam Perjalanan Menuju Kosong
Oleh: Gus Nas Jogja*
Mukadimah:
Empat Gerbang Menuju Jati Diri
Dalam jagad pemikiran Jawa, eksistensi manusia tidak dipahami melalui *diktum Cartesian* _“Cogito Ergo Sum”_ yang maknanya “Aku berpikir maka aku ada”, melainkan melalui sebuah laku rasa yang dinamis dan melingkar. Hidup adalah sebuah orkestra perpindahan energi yang dirangkum dalam empat fase eksistensial: Ngalah (Mengalah), Ngalih (Berpindah), Ngelih (Lapar), dan Ngantuk (Kantuk).
Keempat kata ini, yang sering kali dianggap sebagai siklus biologis dan sosial yang remeh, sebenarnya merupakan manifestasi dari transformasi Atman menuju Brahman, atau dalam istilah Syekh Siti Jenar, kembalinya Kawula ke dalam Gusti. Dalam visi humanitarian, keempat pilar ini adalah protokol untuk memanusiakan kembali manusia yang telah terdehumanisasi oleh mesin. Esai ini akan membedah bagaimana keempat pilar ini merupakan struktur fundamental bagi kesehatan jiwa dan pencapaian makrifat manusia modern yang sedang terjebak dalam keriuhan teknologis yang tanpa jeda.
Ngalah: Ontologi Penundukan Ego dan Radikalisme Damai
Ngalah sering kali disalahpahami sebagai bentuk kekalahan, pasivitas, atau inferioritas. Namun, secara filosofis dan humanitarian, Ngalah adalah tindakan radikal untuk melampaui ego atau Kramadangsa. Ia adalah kemenangan atas diri sendiri sebelum mencoba memenangkan dunia.
*Baruch Spinoza* berpendapat bahwa manusia sering kali menjadi budak dari emosinya sendiri atau human bondage. Ngalah adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan manusia karena ia memilih untuk tidak dikendalikan oleh hasrat untuk mendominasi. Dalam tradisi Jawa, Ngalah adalah praktik dari prinsip Ngalah Tanpo Ngasorake –Mengalah tanpa merendahkan–.
Visi humanitarian dari Ngalah terletak pada pengakuan akan martabat liyan. Ketika seseorang Ngalah, ia memberikan ruang bagi orang lain untuk ada. Ini adalah antitesis dari “kehendak untuk berkuasa” yang destruktif. Friedrich Nietzsche mungkin akan mengkritik ini sebagai “moralitas budak”, namun dalam konteks pelestarian kemanusiaan, Ngalah adalah kekuatan yang mampu meredam konflik sebelum menjadi ledakan. Pemenang sejati dalam peradaban bukanlah yang berdiri di atas tumpukan mayat lawan, melainkan yang mampu melipat egonya demi keberlangsungan hidup bersama.
Ngalih: Dialektika Ruang, Hijrah, dan Transformasi Eksistensial
Setelah jiwa mampu mengolah egonya melalui Ngalah, ia harus melakukan Ngalih. Secara harfiah berarti berpindah tempat, namun secara filosofis-puitis, Ngalih adalah perpindahan kesadaran dari dimensi material yang sempit menuju dimensi spiritual yang tak terbatas.
*Martin Heidegger* berbicara tentang Dasein atau “Ada-di-sana” sebagai makhluk yang selalu “terlempar” ke dunia. Ngalih adalah upaya manusia untuk tidak sekadar “terlempar”, tetapi “melompat” secara sadar atau existential leap. Jika kita menetap di satu titik kesadaran atau fanatisme terlalu lama, jiwa akan membusuk dalam stagnasi. Ngalih adalah mesin penggerak kemanusiaan; ia adalah mobilitas vertikal menuju Tuhan dan mobilitas horizontal menuju empati.
Secara humanitarian, Ngalih mengajarkan kita tentang nasib para pengungsi, musafir, dan jiwa-jiwa yang terasing. Ia mengingatkan bahwa identitas manusia tidak terpaku pada koordinat geografis, melainkan pada perjalanan batin. Kita harus Ngalih dari kebencian menuju penerimaan, dari kegelapan nalar menuju terang budi. Tanpa Ngalih, manusia hanyalah artefak yang membatu di museum masa lalu.
Ngelih: Metafora Kelaparan Rohani dan Solidaritas Universal
Ngelih atau lapar adalah kondisi kekurangan yang paling asali. Secara biologis, ia adalah sinyal kelangsungan hidup. Namun secara filosofis, Ngelih adalah pengingat akan kefanaan dan ketergantungan kita pada semesta. Filsuf eksistensialis *Jean-Paul Sartre* menyebut adanya “lubang” dalam keberadaan manusia atau lack of being yang selalu ingin diisi.
Dalam visi humanitarian, Ngelih adalah jembatan solidaritas. Merasakan lapar bukan hanya tentang mengosongkan perut, tetapi tentang mengisi ruang empati bagi jutaan orang yang kelaparan secara sistemik. Ngelih secara sadar (puasa/laku prihatin) adalah metode untuk mempertajam sensitivitas sosial. Ketika perut kosong, telinga batin mulai mendengar jeritan dunia yang selama ini teredam oleh denting sendok dan garpu kemewahan.
“Manusia modern ketakutan pada ‘Ngelih’ fisik, sehingga mereka merampok alam dan sesama demi menimbun gudang. Namun, mereka abai bahwa jiwa mereka menderita busung lapar spiritual—mereka kaya secara materi namun kurus kering secara nurani.” Lapar adalah guru yang mengajarkan bahwa kita semua sama di hadapan kebutuhan primer; ia menghancurkan kasta dan kelas dalam satu tarikan napas yang perih.
Ngantuk: Gerbang Menuju Alam Suwung dan Kepasrahan Total
Fase terakhir yang paling sering disepelekan adalah Ngantuk. Dalam kacamata medis-kapitalistik, kantuk dianggap sebagai gangguan produktivitas. Namun, dalam ilmu jiwa Jawa, Ngantuk adalah fase transisi sakral antara alam Wadag (fisik) menuju alam Luhur (metafisik).
*Arthur Schopenhauer* memandang tidur sebagai “bunga dari kematian”. Ketika kita Ngantuk, kita dipaksa untuk melepaskan kendali. Ngantuk adalah puncak dari kepasrahan atau Sumeleh. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi membedakan antara si kaya dan si miskin, si perkasa dan si lemah. Semua kembali menjadi ketiadaan dalam dekapan tidur.
Secara puitis, Ngantuk adalah saat di mana logika manusia yang sombong menyerah pada irama kosmik. Visi humanitarian dari Ngantuk adalah pengakuan akan keterbatasan manusia. Kita bukan tuhan-tuhan kecil yang bisa terjaga selamanya untuk memanipulasi dunia. Kita butuh “mati sejenak” untuk menemukan kembali kesucian jiwa. Ngantuk adalah proses alamiah raga untuk memberikan ruang bagi sukma melakukan ruwatan mandiri dari polusi ego yang dikumpulkan sepanjang hari.
Kesimpulan: Manunggaling Ngalah, Ngalih, Ngelih, Ngantuk
Keempat pilar ini Ngalah, Ngalih, Ngelih, Ngantuk adalah sebuah sirkuit kesadaran yang utuh. Ngalah membersihkan hubungan antarmanusia; Ngalih membebaskan manusia dari kejumudan; Ngelih menyatukan manusia dengan penderitaan kosmik; dan Ngantuk mengembalikan manusia ke pangkuan Sang Pencipta.
Ini adalah manifesto untuk merawat tradisi lisan di tengah gempuran kiamat digital. Bahwa menjadi manusia yang utuh berarti berani untuk tidak selalu menang, berani untuk terus bergerak, berani untuk merasakan kekurangan, dan berani untuk menyerahkan kesadaran pada kegelapan malam yang suci. Hanya dengan cara inilah, bunga-bunga bangsa dapat tumbuh kembali dari sela-sela beton modernitas yang gersang.
Ngamuk: Puncak Ruwatan dan Amarah Suci
Namun, setelah melewati gerbang Ngalah, Ngalih, Ngelih, dan Ngantuk, manusia tidak berhenti pada kepasifan yang bisu. Ada satu fase puncak yang sering kali disembunyikan karena daya ledaknya yang dahsyat: *Ngamuk!*
Dalam konteks spiritual dan humanitarian, Ngamuk bukanlah kemarahan buta tanpa arah atau kekerasan hewani yang destruktif. Ngamuk di sini adalah “Amarah Suci” atau Holy Rage; ia adalah letupan nurani yang tak lagi sanggup melihat ketidakadilan. Ia adalah fase di mana seseorang yang telah selesai dengan egonya (Ngalah), telah berpindah pada kebenaran (Ngalih), telah merasakan perihnya rakyat (Ngelih), dan telah mendapat petunjuk dalam keheningan (Ngantuk), akhirnya bangkit untuk meruntuhkan berhala-berhala kezaliman.
Ngamuk adalah resonansi dari perlawanan Diponegoro, teriakan puitis Ranggawarsita atas zaman edan, dan amuk massa yang menuntut kedaulatan sukma. Ia adalah tindakan untuk “Mengamuk pada Nasib” yang digariskan secara sepihak oleh sistem yang opresif. Ketika kata-kata tak lagi didengar dan doa-doa hanya dianggap angin lalu oleh penguasa yang bebal, maka jiwa yang radikal akan memilih untuk Ngamuk—menjungkirbalikkan meja-meja judi kekuasaan demi mengembalikan martabat manusia.
Ini adalah amuk yang terukur, amuk yang lahir dari cinta yang mendalam terhadap kemanusiaan. Tanpa fase ini, empat pilar sebelumnya hanyalah jalan menuju pertapaan yang individualis. Dengan Ngamuk, perjalanan menuju kosong itu menjadi sempurna; karena ia membuktikan bahwa dalam kekosongan diri, tersimpan kekuatan semesta yang siap meledak untuk membela keadilan.
Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti
—–
Catatan Kaki & Rujukan Ilmiah
Heidegger, Martin. (1927). Being and Time (Sein und Zeit). New York: Harper & Row. Mengenai konsep Dasein dan keterlemparan manusia yang menuntut “perpindahan” (Ngalih) eksistensial.
Spinoza, Baruch. (1677). Ethics. Oxford University Press. Menjelaskan tentang penundukan afek dan emosi sebagai jalan menuju kemerdekaan jiwa (Ngalah).
Mangkunegara IV. Serat Wedhatama. Surakarta. Kitab standar kearifan Jawa yang membahas pengolahan batin (olah rasa) dan pengendalian nafsu.
Sartre, Jean-Paul. (1943). Being and Nothingness. Philosophical Library. Membedah konsep kekosongan eksistensial yang dianalogikan dengan kelaparan spiritual (Ngelih).
Suryomentaram, Ki Ageng. (1985). Kawruh Jiwa. Jakarta: PT Inti Idayu Press. Psikologi orisinal Jawa yang membedah tentang keinginan (karep) dan pengamatan diri.
Schopenhauer, Arthur. (1818). The World as Will and Representation. Dover Publications. Tentang kehendak yang tak pernah puas dan tidur sebagai manifestasi jeda dari penderitaan dunia (Ngantuk).
R.Ng. Ranggawarsita. Serat Kalatidha. Surakarta. Manuskrip yang menggambarkan kondisi zaman edan dan perlunya etika “Eling lan Waspada” yang terangkum dalam laku empat fase kesadaran ini.
Zuboff, Shoshana. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs. Sebagai rujukan kritis terhadap dunia modern yang menghancurkan jeda “Ngantuk” manusia demi ekstraksi data dan perhatian.
Fromm, Erich. (1955). The Sane Society. Routledge. Mengenai alienasi manusia dalam masyarakat industri yang melupakan kebutuhan spiritual dasar.
Lévinas, Emmanuel. (1961). Totality and Infinity. Duquesne University Press. Memberikan dasar humanitarian tentang “Wajah Liyan” yang mengharuskan kita untuk mengalah (Ngalah) sebagai tanggung jawab etis.
—-
*Gus Nas Jogja, Budayawan.