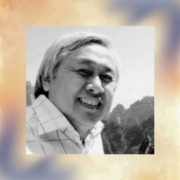Mitos di Tikungan Jalan: Logika Mitis dalam Ruang Publik
Oleh Purnawan Andra*
Jika Anda pernah melintasi jalanan berliku di kawasan pegunungan atau ruas jalan rawan di pelosok negeri, Anda mungkin akan menemukan papan pengumuman besar bertuliskan: “Hati-hati, di sini sering terjadi kecelakaan.”
Pengumuman ini tampak seperti bagian dari protokol keselamatan. Namun jika ditelaah lebih dalam, frasa tersebut menyimpan ironi kultural yang signifikan. Alih-alih menjelaskan penyebab kecelakaan atau memperingatkan tentang kondisi teknis jalan, pengumuman tersebut justru seperti mengamini keberadaan kekuatan supranatural.
Seolah-olah, kecelakaan yang sering terjadi bukan karena persoalan struktural atau teknis, melainkan akibat suatu “hal lain yang sulit diterangkan” yang melekat pada lokasi tersebut. Ini bukan sekadar komunikasi publik yang kurang pas, melainkan sebuah indikasi bahwa logika mitis masih mengakar dalam cara kita memahami dunia.
Nalar Kosmologis
Dalam perspektif antropologi budaya, pernyataan seperti itu mencerminkan bentuk penalaran masyarakat yang masih bercorak kosmologis. Clifford Geertz menyebut bahwa kebudayaan adalah sistem makna simbolik yang diorganisasi oleh masyarakat untuk memahami realitasnya. Maka, papan peringatan itu tidak hanya menyampaikan pesan literal, tetapi menjadi ekspresi dari cara masyarakat kita membingkai peristiwa melalui perspektif mitis.
Kecelakaan dipahami bukan sebagai hasil dari desain jalan yang buruk, lampu penerangan yang tak memadai, atau minimnya rambu lalu lintas, tetapi sebagai konsekuensi dari “energi gaib” yang mendiami wilayah tersebut. Dalam kerangka ini, realitas fisik bercampur dengan keyakinan metafisik. Jalan yang gelap, tikungan tajam, dan minim pengawasan tidak ditangani secara teknokratik, tetapi diselimuti oleh aura mistis.
Logika ini mengakar dalam struktur budaya masyarakat Indonesia yang sejak lama hidup berdampingan dengan dunia gaib. Dalam banyak tradisi lokal, tempat-tempat tertentu dianggap “angker” atau sakral. Ketika terjadi kecelakaan, narasi yang muncul bukan investigasi teknis, melainkan cerita rakyat tentang penunggu, roh halus, atau makhluk tak kasat mata.
Maka, solusi yang ditawarkan pun kadang bukan pembenahan infrastruktur, tetapi ritual sesajen, doa bersama, atau penempatan patung-patung tertentu sebagai penolak bala. Bahkan dalam konteks kota besar, tindakan ini bisa tetap ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur tidak serta-merta menghapus cara berpikir kosmologis.
“Infrapolitik”
Namun, dari sudut pandang tata kelola publik, situasi ini menimbulkan masalah serius. Ketika ruang publik dikelola dengan logika mitis, maka akuntabilitas menjadi kabur. Pemerintah atau otoritas setempat tidak bertanggung jawab atas kualitas infrastruktur, karena kecelakaan dianggap sebagai bagian dari takdir atau intervensi gaib.
Inilah yang disebut antropolog James Scott sebagai bentuk “infrapolitik”—sebuah wilayah di mana tindakan kekuasaan disamarkan dan tanggung jawab dialihkan pada kekuatan tak terlihat. Dengan kata lain, papan pengumuman tadi secara simbolik telah melegitimasi ketiadaan intervensi kebijakan publik yang berbasis data, desain, dan evaluasi.
Dalam tata kelola ruang, ada asumsi mendasar bahwa negara hadir untuk menjamin keselamatan warga melalui perencanaan dan pengawasan yang berbasis rasionalitas. Ketika logika ini digantikan oleh narasi-narasi mistis, maka ruang publik tak lagi menjadi ruang modern yang rasional, tetapi ruang simbolik yang dibentuk oleh keyakinan kolektif tak kasat mata. Ini bukan berarti dimensi spiritual masyarakat harus diabaikan, tetapi ketika narasi mistis digunakan sebagai pengganti analisis teknis, maka kita sedang membangun masyarakat yang melanggengkan mitos sebagai pengganti tanggung jawab struktural.
Kita bisa menyandingkan hal ini dengan konsep “performativitas simbolik” dalam antropologi. Ketika masyarakat atau negara menggunakan tanda-tanda simbolik seperti papan peringatan mistis, sesungguhnya mereka sedang membentuk persepsi kolektif tentang apa yang harus dipercaya dan bagaimana realitas harus ditanggapi.
Maka, alih-alih menjadi alat pencegah kecelakaan, papan peringatan itu menjadi instrumen yang memelihara tafsir budaya tertentu: bahwa yang harus diwaspadai bukan kecerobohan pengemudi atau kurangnya sarana pendukung jalan, tetapi kemungkinan “diganggu makhluk halus”. Ini tentu bukan bentuk mitigasi risiko yang layak dalam era tata kelola publik modern.
Dalam jangka panjang, logika mitis semacam ini menghambat lahirnya budaya keselamatan berbasis ilmu pengetahuan. Ia menunda intervensi struktural, melemahkan mekanisme tanggung jawab, dan memindahkan locus of control dari institusi manusia ke entitas imajiner.
Hal ini mempertegas bahwa krisis infrastruktur di Indonesia bukan semata masalah teknis, melainkan krisis kultural dalam memahami dan menyikapi realitas. Meminjam logika Victor Turner, kita terjebak dalam struktur liminal: situasi ambigu di mana modernitas dan tradisi bercampur, tanpa kejelasan arah.
Membongkar Mitos
Apa yang bisa dilakukan? Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa budaya memiliki daya kuat dalam membentuk persepsi dan tindakan. Namun, itu tidak berarti bahwa kebudayaan harus digunakan sebagai justifikasi atas kelambanan kebijakan publik.
Pemerintah, sebagai pengelola ruang publik, harus menyadari bahwa tata kelola yang efektif tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi juga membongkar mitos yang menghambat pembacaan rasional atas masalah publik. Ini membutuhkan kerja simultan antara rekayasa teknis dan pendidikan publik berbasis budaya.
Kedua, kampanye keselamatan harus memasukkan unsur kebudayaan yang bertransformasi. Alih-alih melawan kepercayaan lokal secara frontal, narasi keselamatan harus mampu menjembatani antara kearifan lokal dan pendekatan ilmiah. Misalnya, masyarakat yang percaya pada roh penunggu jalan bisa diajak untuk “menjaga” tempat itu dengan cara nyata: membersihkan, menerangi, dan mengawasi. Dengan cara itu, mitos tidak dihapus, tetapi diubah fungsi sosialnya.
Tulisan ini bukan hendak mengesampingkan logika mitis yang masih hidup dalam masyarakat kita. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa dalam kebudayaan, tak ada yang benar-benar mati. Yang ada adalah transformasi.
Maka tugas kita sebagai masyarakat modern adalah mentransformasikan warisan kosmologis itu menjadi energi sosial yang mendorong perbaikan, bukan melanggengkan kelalaian. Karena sesungguhnya, hantu yang paling berbahaya bukan yang tak terlihat, tetapi ketidakpedulian dan pengabaian tanggung jawab dalam tata kelola publik kita sendiri.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, bekerja di Kementerian Kebudayaan.