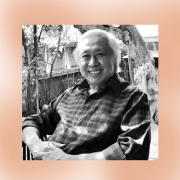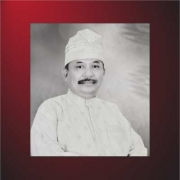Metamorfose Si Doel dari Wacana Sastra ke Wacana Politik
Oleh Tengsoe Tjahjono*
Si Doel Anak Betawi adalah kisah yang telah lama hidup di benak masyarakat Indonesia, sebuah narasi yang awalnya hadir dalam wacana sastra namun kemudian mengalami transformasi menjadi bagian integral dari wacana budaya populer dan politik. Dari tangan Aman Datuk Madjoindo, Si Doel lahir sebagai representasi perjuangan kaum marjinal dalam novel yang berjudul Si Doel Anak Betawi (1932). Novel yang lahir pada masa kolonial ini menawarkan lebih dari sekadar cerita anak-anak; ia adalah potret sosial masyarakat Betawi yang diwarnai oleh modernisasi, pendidikan, dan pergulatan identitas. Novel ini, seperti dikatakan oleh Pierre Bourdieu, “menciptakan ruang sosial” yang mempertemukan struktur masyarakat dengan agen individual seperti Doel, yang menjadi simbol perjuangan kelas bawah.
Novel ini membuka jalan bagi transformasi cerita Doel menjadi teks film pada tahun 1973. Dalam film Si Doel Anak Betawi yang disutradarai oleh Sjuman Djaya, cerita Doel mendapatkan dimensi baru: visualisasi budaya Betawi yang lebih nyata melalui bahasa, musik gambang kromong, dan lanskap Jakarta. Transformasi dari teks sastra ke teks film ini mempertegas habitus budaya Betawi di tengah modernisasi, menunjukkan bahwa identitas lokal masih dapat bertahan meski berada dalam sistem dominasi kapitalis. Antonio Gramsci menyebut ini sebagai “hegemonic negotiation,” di mana tradisi beradaptasi dalam ruang modern. Film ini tidak hanya menghidupkan cerita Doel dengan visualisasi, tetapi juga memperkaya narasi dengan elemen budaya yang lebih nyata: bahasa Betawi, musik gambang kromong, dan lanskap Jakarta yang berubah. Transformasi ini menciptakan Si Doel sebagai ikon budaya yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.
Kemudian, tokoh ini memperoleh kehidupan baru melalui adaptasi televisi yang digarap oleh Rano Karno pada era 1990-an, menghubungkan tokoh fiksional ini dengan realitas sosial dan politik Indonesia. Si Doel, dalam metamorfosisnya, menggambarkan dinamika sosial yang terus bergerak dari masa kolonial hingga pascareformasi, menjadikannya ikon yang melampaui sekadar tokoh fiksi.
Si Doel sebagai Representasi Kelas Subaltern
Dalam novel aslinya, Si Doel merupakan personifikasi kelas subaltern yang berjuang untuk mendobrak batas-batas struktur sosial kolonial. Aman Datuk Madjoindo, sebagai seorang penulis, tidak hanya menciptakan kisah seorang anak Betawi miskin yang bercita-cita tinggi, tetapi juga menawarkan kritik terhadap sistem yang menempatkan masyarakat pribumi dalam hierarki terendah. Pendidikan menjadi simbol perjuangan Si Doel, mencerminkan pandangan progresif penulisnya bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan adalah kunci menuju kebebasan sosial.
Namun, perjuangan Si Doel tidak hanya soal pendidikan. Ia juga bergulat dengan ekspektasi tradisional keluarganya, terutama sang ibu yang ingin ia menjadi “tukang kebon” seperti ayahnya. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara modernitas dan tradisionalitas, sebuah isu yang masih relevan dalam diskursus masyarakat Indonesia hingga hari ini. Novel ini, dengan demikian, bukan hanya sebuah cerita sederhana tentang mimpi seorang anak, tetapi juga potret sosial yang kompleks dari masyarakat Betawi pada masa itu.
Si Doel sebagai representasi kelas subaltern dalam novel karya Aman Datuk Madjoindo tetap relevan dalam membaca dinamika sosial masyarakat Jakarta saat ini. Sebagai ibukota, Jakarta tidak hanya menjadi pusat kekuasaan dan ekonomi, tetapi juga menyimpan ketimpangan sosial yang tajam. Dalam konteks ini, perjuangan Si Doel mencerminkan perjuangan kelas bawah yang berusaha mendobrak struktur sosial yang cenderung eksklusif.
Kisah Si Doel, yang menggambarkan perjuangan seorang anak Betawi dari kelas miskin untuk meraih pendidikan, menemukan paralel dengan realitas masyarakat Jakarta saat ini. Jakarta adalah kota dengan berbagai wajah: di satu sisi, ia adalah pusat kemegahan, dan di sisi lain, menyimpan kantong-kantong kemiskinan. Warga asli Betawi sering kali berada di posisi terpinggirkan akibat gentrifikasi, di mana tanah-tanah mereka diubah menjadi kompleks perumahan elite atau pusat bisnis. Seperti keluarga Doel yang harus berjuang mempertahankan identitas dan kelangsungan hidup di bawah bayang-bayang modernitas, masyarakat Betawi hari ini juga menghadapi tekanan serupa.
Perjuangan Doel untuk memperoleh pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan tetap relevan dalam konteks Jakarta masa kini. Pendidikan masih menjadi jalur utama bagi masyarakat kelas bawah untuk memperbaiki nasib. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas di Jakarta sering kali dibatasi oleh faktor ekonomi dan sosial. Sekolah-sekolah unggulan atau berbasis internasional banyak tersedia, tetapi hanya terjangkau oleh kalangan menengah ke atas, sementara sekolah negeri atau swasta dengan biaya rendah sering kali kekurangan fasilitas yang memadai. Ini menciptakan ketimpangan dalam kesempatan meraih mobilitas sosial, mirip dengan perjuangan Doel yang menghadapi hambatan struktural pada masanya.
Konflik Doel dengan ibunya yang menginginkan ia tetap menjalankan pekerjaan tradisional seperti ayahnya mencerminkan ketegangan antara tradisionalitas dan modernitas, sebuah isu yang masih relevan di masyarakat Jakarta. Dalam konteks masa kini, banyak keluarga Betawi di Jakarta yang menghadapi dilema serupa: mempertahankan identitas budaya mereka atau mengikuti arus modernisasi yang menuntut mereka untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial. Hal ini tampak dalam bagaimana kebudayaan Betawi, seperti seni lenong, ondel-ondel, atau kuliner khas, mulai tergeser oleh budaya urban global.
Aman Datuk Madjoindo melalui “Si Doel” menyentil sistem kolonial yang menempatkan pribumi di hierarki sosial terendah. Kritik ini dapat ditarik ke kondisi Jakarta hari ini, di mana sistem sosial yang tidak adil masih terasa melalui ketimpangan distribusi kekayaan, akses terhadap pelayanan publik, dan peluang ekonomi. Masyarakat kelas bawah kerap kali menjadi korban kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan kapital besar, seperti penggusuran lahan demi pembangunan infrastruktur atau properti komersial.
Novel “Si Doel” mengingatkan bahwa cerita perjuangan melawan subordinasi sosial bukan sekadar sejarah, melainkan kenyataan yang terus berulang. Dalam konteks Jakarta hari ini, Si Doel menjadi simbol perjuangan kelas bawah yang terus berusaha mendapatkan tempat dalam struktur kota yang semakin eksklusif.
Transformasi ke Televisi: Si Doel sebagai Fenomena Budaya
Ketika Si Doel Anak Sekolahan hadir dalam format sinetron (1994-2006), narasinya tidak hanya berkembang tetapi juga menjangkau audiens yang lebih luas. Televisi, sebagai medium populer, menjadikan Si Doel alat penting untuk merefleksikan isu-isu sosial seperti urbanisasi, pendidikan, dan pergeseran nilai keluarga. Sinetron ini tidak sekadar hiburan; ia adalah teks budaya yang menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional di tengah arus globalisasi.
Rano Karno, yang kembali memerankan Doel, membawa kedalaman emosional ke dalam karakter ini, mengaburkan batas antara aktor dan perannya. Seperti yang diungkapkan oleh Stuart Hall, “representasi adalah arena di mana makna dikonstruksi dan dinegosiasikan.” Doel, dalam hal ini, menjadi simbol kompleks masyarakat urban Indonesia yang mencoba mempertahankan akar tradisionalnya.
Saat Rano Karno mengangkat kisah ini ke layar televisi, Si Doel mengalami transformasi yang signifikan. Dalam versi sinetronnya, Si Doel bukan lagi sekadar anak kampung yang bercita-cita menjadi “orang,” tetapi menjadi representasi modern masyarakat urban Betawi yang terjebak di tengah arus globalisasi. Konflik yang dihadapi Doel tidak hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga mencakup dilema cinta, identitas budaya, dan aspirasi ekonomi.
Sinetron ini membawa pesan-pesan yang relevan dengan masyarakat urban Jakarta pada era 1990-an. Si Doel, dengan segala kesederhanaannya, menjadi cermin bagi jutaan penonton yang merasakan pergolakan yang sama. Dalam konteks ini, Si Doel tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga wacana yang membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mempertahankan identitas di tengah perubahan zaman.
Namun, transformasi ini juga membawa paradoks. Identitas Doel yang lekat dengan Rano Karno sering kali membuat masyarakat sulit memisahkan keduanya. Hal ini menimbulkan diskusi tentang bagaimana televisi sebagai medium dapat memengaruhi persepsi publik terhadap realitas dan fiksi, sebagaimana dijelaskan oleh Marshall McLuhan: “The medium is the message.”
Sosok Doel dan Rano Karno: Dua Identitas dalam Satu Cermin
Rano Karno bukan sekadar aktor yang memerankan Doel; ia adalah Doel itu sendiri. Dengan wajah polos, sorot mata penuh harapan, dan intonasi khas Betawi, Rano membawa karakter Doel ke dalam jiwa masyarakat Indonesia. Hubungan antara Doel dan Rano menjadi simbiosis yang unik: Rano memperkaya karakter Doel dengan kedalaman emosional, sementara Doel membentuk identitas publik Rano Karno.
Perjalanan ini semakin dalam ketika Rano membawa Si Doel ke medium televisi dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan (1994-2006). Sinetron ini menjadi fenomena budaya, menyuguhkan cerita keluarga sederhana yang sarat nilai, tetapi tetap relevan dengan isu-isu sosial seperti urbanisasi, pendidikan, dan pergeseran nilai tradisional. Peran Doel dalam sinetron ini memperluas pengaruhnya, menjangkau generasi muda yang mungkin belum mengenal versi film atau novelnya.
Namun, keterikatan ini juga menjadi paradoks. Rano Karno kerap diidentifikasi sebagai Doel, mengaburkan batas antara aktor dan karakter. Dalam beberapa wawancara, Rano mengakui bahwa Doel adalah bagian dari dirinya, sebuah identitas yang tidak bisa dilepaskan, bahkan ketika ia beralih ke dunia politik.
Metamorfosis Si Doel tidak berhenti pada ranah budaya populer. Pada era pascareformasi, tokoh ini dan cerita-ceritanya menjadi bahan diskusi dalam konteks politik identitas. Rano Karno, yang tidak hanya memerankan Si Doel tetapi juga menjadi produser, sutradara, dan politisi, membawa Si Doel ke panggung politik. Keputusan ini tidak terlepas dari keberhasilan Si Doel sebagai ikon budaya yang memiliki daya tarik lintas generasi.
Si Doel, yang selalu digambarkan sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan jujur, menjadi metafora yang efektif dalam kampanye politik. Identitas Betawi yang melekat pada Si Doel digunakan untuk menarik simpati masyarakat lokal, sementara narasi perjuangannya menjadi simbol harapan bagi mereka yang masih bergulat dengan kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, Si Doel tidak lagi sekadar tokoh fiksi, tetapi juga alat politik yang mencerminkan strategi memobilisasi emosi dan memanfaatkan nostalgia kolektif.
Dari Ruang Budaya ke Wacana Politik
Ketika Rano Karno memasuki dunia politik, ia membawa citra Doel sebagai simbol kesederhanaan dan perjuangan. Dalam kampanye politiknya, Doel digunakan sebagai metafora pemimpin yang merakyat dan memahami aspirasi rakyat kecil. Strategi ini mencerminkan gagasan Bourdieu tentang symbolic capital, di mana citra Doel memberi Rano keunggulan moral dan kultural dalam arena politik.
Namun, pendekatan ini juga memicu kritik. Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan citra Doel sebagai alat politik adalah bentuk romantisasi yang menyederhanakan realitas sosial. Misalnya, meskipun Doel adalah representasi perjuangan kelas bawah, kebijakan yang diambil dalam dunia politik sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara “teks politik” dan realitas sosial, seperti yang diingatkan oleh Gramsci: “Hegemoni harus selalu diimbangi dengan kepekaan terhadap tuntutan rakyat.”
Dari perspektif sosiologi kritis, metamorfosis Si Doel mencerminkan bagaimana wacana sastra dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Transformasi Si Doel dari novel ke sinetron, dan akhirnya ke panggung politik, menunjukkan bahwa budaya populer memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan menggerakkan massa. Namun, hal ini juga membuka ruang bagi kritik terhadap komodifikasi budaya. Apakah Si Doel, dalam perjalanannya, masih menjadi simbol perjuangan kaum marjinal, ataukah ia telah direduksi menjadi sekadar alat untuk kepentingan elit politik?
Selain itu, narasi Si Doel juga mengungkap paradoks dalam masyarakat Indonesia. Sementara ia mempromosikan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan, popularitasnya juga mencerminkan kenyataan bahwa masyarakat sering kali lebih terpesona oleh citra daripada substansi. Dalam konteks ini, Si Doel menjadi contoh bagaimana budaya populer dapat menciptakan ruang untuk refleksi kritis sekaligus reproduksi ideologi dominan.
Penutup
Si Doel adalah kisah yang terus hidup, beradaptasi dengan zaman, dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dari novel yang menggambarkan perjuangan kelas subaltern hingga sinetron yang merefleksikan dinamika masyarakat urban, dan akhirnya menjadi bagian dari wacana politik, metamorfosis Si Doel adalah bukti bagaimana sastra dapat menjadi cerminan sekaligus alat perubahan sosial. Namun, dalam perjalanan ini, penting untuk tetap kritis terhadap bagaimana wacana budaya digunakan dan siapa yang diuntungkan darinya. Si Doel, dalam segala kesederhanaannya, mengingatkan kita bahwa cerita, seperti halnya kehidupan, selalu memiliki lapisan yang lebih dalam untuk digali.
Metamorfosis Si Doel dari novel ke film, sinetron, dan akhirnya menjadi bagian dari wacana politik menunjukkan kekuatan cerita dalam membentuk identitas budaya. Doel adalah potret Indonesia yang terus berkembang: sederhana, penuh perjuangan, tetapi selalu mempertahankan akar budayanya. Dalam sosok Doel, masyarakat menemukan harapan, cermin diri, dan pelajaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional di tengah arus perubahan.
Rano Karno, sebagai wajah dari Doel, telah berhasil menjaga relevansi cerita ini lintas generasi. Doel bukan sekadar karakter fiktif, tetapi simbol yang hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Meski zaman terus berubah, Si Doel tetap menjadi kisah abadi tentang mimpi, identitas, dan perjuangan anak bangsa.
—
*Tengsoe Tjahjono, Dosen dan Sastrawan.