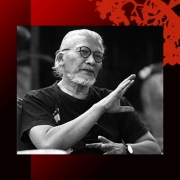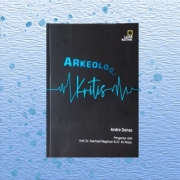Mens Rea Panggung Tunggal Penuh Kritik
Oleh Pietra Widiadi*
Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik Indonesia kembali dipenuhi oleh paradoks yang berulang: bencana struktural di Sumatra yang lahir dari kebijakan politik tak kunjung menemukan jalan pemulihan yang jelas, sementara kegagapan rezim pemerintah dalam mengelola negara justru menjelma tontonan. Negara seolah hadir bukan sebagai pengelola krisis, melainkan sebagai produsen absurditas. Di tengah kerusakan ekologis dan sosial yang dibiarkan tanpa arah pertanggungjawaban, perhatian publik dialihkan secara sadar atau tidak ke panggung lain yang lebih “menghibur”, namun sesungguhnya tak kalah politis.
Pada saat yang sama, konflik agraria dan penolakan tanah adat di Papua terus berlangsung sebagai praktik lama yang dibungkus bahasa dalam istilah hamper tak pernah basi, pembangunan. Atas nama kemajuan dan investasi, ruang hidup masyarakat adat dikorbankan demi akumulasi keuntungan segelintir elite. Di sinilah hegemoni bekerja secara halus bukan dengan represi malu-malu dengan dalih multi fungsi tentara, melainkan melalui narasi dominan yang menormalisasi ketimpangan. Penderitaan dipinggirkan, sementara wacana pembangunan diproduksi sebagai kebenaran tunggal yang sulit digugat.
Tulisan ini berangkat dari kegelisahan yang serupa, namun tidak identik, dengan tulisan saya sebelumnya di Berita Jatim berjudul “Mens Rea, Menyala Berubahnya Komunitas Masyarakat” (6 Januari 2026). Saya memanfaatkan momentum panas dari komedi tunggal Pandji Pragiwaksono stand-up comedy yang melampaui fungsi hiburan dan menjelma kritik sosial terbuka. Jika dibandingkan dengan buku Reset Indonesia yang sempat dilarang dibahas dalam diskusi di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari, Madiun yang kebetulan saya hadiri, celoteh Pandji terasa jauh lebih menyengat. Ia menyebut nama-nama besar tanpa tedeng aling-aling: dari Raffi Ahmad, Ahmad Dhani (Dewa 19), Ahmad Syahroni, Dharma Pongrekun, hingga Gibran, Prabowo Subianto, Bahlil, dan figur-figur lama seperti Sambo yang pernah menguasai ruang skandal nasional.
Di titik inilah komedi bekerja sebagai arena kuasa simbolik. Mengikuti kritik budaya populer, panggung stand-up menjadi ruang produksi makna yang mampu mengganggu hegemoni narasi resmi negara. Lelucon, satire, dan penyebutan nama bukan sekadar sensasi, melainkan strategi simbolik untuk membuka retakan dalam struktur kekuasaan yang selama ini tampak mapan. Komedi tidak lagi netral; ia menjadi medium perlawanan wacana, tempat akal sehat publik diuji dan dalam batas tertentu dinyalakan kembali. Justru karena hadir dalam bentuk yang ringan dan populer, kritik ini terasa lebih panas, lebih dekat, dan lebih sulit diabaikan.
Keberanian ini, pasti punya alasan dan punya bekal disampaikan dengan cermat dan tepat untuk seandainya akan dipolisikan dengan menggunakan KAHP atau KUHAP yang baru. Sebagai bahan candaan, apa yang disampaikan lebih banyak menunjuk-nunjuk keburukan, kejahatan dan kekacauan berpikir orang lain, pihak Liyan.
Bisnis Hiburan Kelas Menengah
Model komedi panggung tunggal sejatinya bukan barang baru di Nusantara. Dalam lanskap budaya Arek; Surabaya, Mojokerto, Jombang, Malang, hingga Sidoarjo tradisi komedi satir telah lama hidup melalui Markeso. Pertunjukan ini hadir sederhana, sering kali seperti orang ngamen di jalanan atau berpindah dari kampung ke kampung, dengan muatan kritik terhadap kelakuan menindas kolonialisme hingga ketimpangan sosial pascakolonial, terutama sebelum awal 1980-an. Cerita sejarah disampaikan melalui humor, parikan, dan ngandang, sebuah cara menertawakan kekuasaan tanpa harus berhadap-hadapan secara langsung. Dalam konteks ini, komedi bekerja sebagai praktik budaya rakyat yang lahir dari keterdesakan, bukan dari kemewahan.
Jika ditarik ke kerangka Antonio Gramsci, praktik Markeso dapat dibaca sebagai ekspresi counter-hegemony upaya kelompok subordinat untuk memproduksi makna tandingan terhadap dominasi wacana kolonial dan elite lokal. Humor menjadi alat untuk meretas “akal sehat” (common sense) yang dipaksakan oleh kekuasaan. Ia tidak menggulingkan struktur secara frontal, tetapi menggerogotinya dari bawah melalui ejekan, sindiran, dan tawa kolektif. Dalam bahasa Gramsci, panggung kecil Markeso adalah ruang perjuangan kultural, tempat hegemoni tidak diterima begitu saja, melainkan dinegosiasikan.
Pola yang secara kultural serupa kini muncul kembali dalam format yang jauh lebih mapan melalui komedi tunggal kontemporer yang dibawakan oleh Pandji Pragiwaksono, pada actor komika lainnya seperti Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Bene Dion (dari grup podcast Agak Laen) yang sukses besar lewat film Agak Laen, serta komika papan atas seperti Ernest Prakasa, Raditya Dika, Arie Kriting, Muhadkly Acho, Bayu Skak dan lain-lain. Dengan tekad dan materi kritik yang tajam terhadap kondisi politik mutakhir, Pandji menggunakan panggung stand-up sebagai arena kemegahan baru. Jika Markeso membangun wibawanya dari jalanan dan kampung, Pandji membangunnya dari gedung pertunjukandengan panggung megah, sistem tiket, dan sirkulasi media sosial. Di sinilah pergeseran penting terjadi: dari seni kritik rakyat ke seni kritik yang telah terintegrasi dalam industri hiburan.
Pergeseran ini menandai perubahan arena budaya sebagaimana dikemukakan Pierre Bourdieu. Stand-up comedy bukan lagi sekadar ekspresi kultural, melainkan bagian dari field (arena) yang diatur oleh modal ekonomi, modal simbolik, dan selera kelas. Pandji mengakumulasi symbolic capital otoritas moral, keberanian menyebut nama, dan citra intelektual kritis yang membuat kritiknya sah, populer, dan layak dikonsumsi. Komedi, dalam arena ini, menjadi komoditas yang tidak hanya menjual tawa, tetapi juga menjual keberpihakan simbolik.
Kesesakan politik, kebodohan dalam membangun birokrasi, dan kekacauan tata kelola negara di hampir semua level pemerintahan menyediakan bahan bakar yang sempurna. Kritik yang sebelumnya terpendam menemukan saluran yang aman: tertawa bersama. Dalam kerangka Gramsci, ini dapat dibaca sebagai momen krisis hegemoni, ketika narasi resmi negara kehilangan daya persuasinya. Namun alih-alih melahirkan perlawanan politik yang terorganisasi, krisis ini justru disalurkan ke dalam bentuk hiburan aman, terkontrol, dan berbayar.
Gayung pun bersambut. Harga tiket pertunjukan yang tidak murah dari kelas Silver Rp 450.000 hingga Diamond dengan harga Rp 1.800.000. Bahkan meningkat pada periode Gold hingga Rp 2.000.000 ini menunjukkan bahwa komedi ini secara jelas menyasar kelas menengah perkotaan. Inilah kelas yang, menurut Bourdieu, memiliki cukup modal ekonomi untuk membeli hiburan sekaligus cukup modal kultural untuk “memahami” kritik yang disajikan. Komedi menjadi katup pelepas tekanan: kemarahan politik dikonversi menjadi konsumsi simbolik.
Dengan demikian, bisnis hiburan kelas menengah ini berada dalam posisi ambigu. Di satu sisi, ia membuka ruang kritik dan mengganggu hegemoni wacana negara; di sisi lain, ia justru menstabilkan hegemoni itu sendiri dengan mengemas kritik sebagai tontonan. Dalam bahasa Gramsci, kritik telah dinegosiasikan agar tidak berubah menjadi tindakan politik yang mengancam. Sementara dalam kerangka Bourdieu, arena budaya ini memperlihatkan bagaimana kuasa simbolik bekerja: siapa yang boleh mengkritik, sejauh apa kritik itu boleh dilontarkan, dan kepada siapa kritik itu dijual. Komedi, pada akhirnya, bukan hanya soal tawa, komedi adalah tetap bisnis makna dalam struktur kekuasaan kelas menengah.
Apa yang akan berubah?
Panggung komedi hari ini telah menjadi ruang paling jujur untuk membaca wajah kekuasaan. Di sana, kebusukan yang selama ini disamarkan oleh bahasa negara dipertontonkan tanpa sensor: kebodohan, kemunafikan, dan kekerasan simbolik ditertawakan bersama. Komedi mempermalukan kekuasaan dengan cara yang tak mampu dilakukan pidato politik. Namun justru di titik ini paradoks muncul tawa yang meledak di ruang pertunjukan kerap berakhir sebagai pelampiasan, bukan perlawanan.
Bahaya terbesar dari komedi politik bukan pada keberaniannya, melainkan pada kemampuannya menjinakkan kemarahan. Ketika kritik cukup ditebus dengan tiket mahal dan tepuk tangan panjang, kekuasaan justru mendapat keuntungan: merekadikritik tanpa harus berubah. Pemerintahan yang konyol tidak runtuh karena ditertawakan; dan sering kali bertahan karena tawa itu sendiri menjadi katup pengaman sistem. Kritik berhenti sebagai konsumsi, bukan tuntutan.
Jika komedi ingin melampaui fungsi hiburan, ia harus berani keluar dari logika pasar dan kenyamanan kelas menengah. Komika, bersama komunitas budaya dan intelektual, perlu menggeser arena kritik dari gedung pertunjukan ke ruan-ruang di mana publik terbuka untuk berani. Lelucon tidak boleh selesai di punchline; dan harus diteruskan menjadi diskusi, kesadaran, dan keberanian kolektif untuk bertindak. Tanpa pengorganisasian, komedi hanya akan menjadi estetika kegagalan negara.
Perubahan struktur politik menuju yang lebih baik tidak lahir dari tawa yang aman, melainkan dari ketidaknyamanan yang dipelihara. Kritik budaya harus disambungkan dengan kerja politik yang nyata: membangun basis sosial, memperluas kesadaran kelas, dan menolak normalisasi kebodohan sebagai hiburan publik. Di sinilah tugas politik-kultural itu bekerjamengubah rasa muak menjadi posisi, dan posisi menjadi gerakan.
Jika tidak, kita hanya akan menyaksikan ironi yang berulang: panggung semakin megah, kritik semakin cerdas, tetapi negara tetap konyol dan struktur kekuasaan tak tersentuh. Komedi akan terus laku, sementara perubahan hanya menjadi bahan tertawaan berikutnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah komedi bisa mengkritik kekuasaan, melainkan apakah kita bersedia menjadikan kritik itu sebagai awal sebuah perubahan atau cukup puas menertawakannya sampai lupa untuk mengubahnya.
—-
*Pietra Widiadi, Petani kopi tinggal di desa Sumbersuko lereng Gunung Kawi, sedang menyelesaikan studi S3 dengan fokus metri, local knowledge practices.