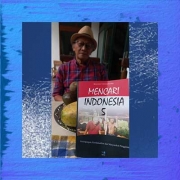Kelana Jejaka di Tanah Merah
Oleh FX Domini BB Hera
Tak ada yang lebih jujur sekaligus romantis, selain surat curahan hati seorang suami dalam pemenjaraan dan pengasingan kepada istrinya. Keduanya berbeda nasib dan sedang dipisahkan jarak lagi benua. Sang suami pejuang Indonesia Merdeka yang beristrikan seorang Belanda tulen.
Sutan Sjahrir (1909-1966) dirundung ujian. Sedari tahun 1934-1938, ia mengalami perpindahan hukuman sejak mendekam di Penjara Cipinang (Batavia, kini Jakarta), Kamp Boven Digoel di Tanah Merah (Papua), dan Banda Neira (Maluku). Ia tetap bersetia menjaga akal sehat serta kalut dipukul rindu akan Maria Johanna Duchateau (1907-1997), istrinya di Negeri Belanda melalui surat-surat yang ia tulis dengan penuh pelampiasan hasrat. Waktu itu Maria masih menjadi istri Sjahrir sebelum kemudian keduanya berpisah dan kelak Sjahrir menikah dengan Siti Wahjunah (1920-1999) yang akrab disapa sebagai Poppy Sjahrir, pasangan yang menemani si Bung Kecil hingga akhir hayatnya.
Rasa kasih, cinta, dan dukungan atas perjuangan suaminya mewujud semua dalam “Renungan Indonesia”, buku kumpulan surat Sutan Sjahrir yang dikumpulkan sendiri oleh Maria. Pertama kali terbit dalam bahasa Belanda, Indonesische Overpeinzingen (1945) lantas dalam tempo dua tahun berjarak edisi bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh H.B. Jassin (1917-2000), sang paus sastra Indonesia.
Beberapa tahun sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Renungan Indonesia banyak dipublikasikan ulang oleh beberapa penerbit Indie. Sebuah sinyalemen positif bagaimana setiap zaman berupaya membaca karya-karya pendiri republik. Sjahrir sendiri mulai dikenal oleh khalayak umum sezamannya ketika memimpin mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda bersama Mohammad Hatta (1902-1980).
Tanpa disangka, kini Maria turut dikenang sebagai arsiparis yang menyimpan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan ego document milik Sutan Sjahrir. Maria mengubah surat-surat pribadi itu menjadi bacaan kolektif yang dapat dinikmati secara umum. Tanpa disadari, sang istri telah bertindak sebagai arsiparis dan mewariskan pengarsipan itu dalam medium buku.

Salah satu penerbitan ulang Renungan Indonesia oleh penerbit Indie, Bunga Bakung (Yogyakarta, 2019). Foto sampul yang dipakai ialah potret Sjahrir ketika dalam suasana sidang BP KNIP (Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Poesat, 1947) bertempat di Gedoeng Rakjat (dahulu Sociëteit Concordia, kini Pertokoan Sarinah) Kota Malang.
Atas jasa Maria itulah, “Renungan Indonesia” menjadi kesaksian Sutan Sjahrir yang merekam pergumulannya akan Keindonesiaan dan Indonesia sejak dalam imaji hingga mewujud menjadi realita. Pergumulan yang tidak mudah, mengingat Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia turut mengalami nasib yang paralel sama seperti Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama itu. Ketiganya menjalani lelakon sebagai orang buangan semasa kolonial.
Nasib Sukarno (1901-1970) yang diasingkan di Ende dan Bengkulu agak berbeda dibandingkan M. Hatta dan Sjahrir di Boven Digoel hingga Banda Neira. Para pemimpin awal Indonesia rata-rata merupakan sesama alumnus politik pengasingan kolonial Belanda. Sebuah episode penempaan mereka di periode kritis yang kelak menjadi bekal untuk memimpin republik.
Penjara Tak Berjeruji
Kamp Boven Digoel merupakan noktah besar dalam sejarah politik pengasingan kolonial Belanda selama berada di Nusantara. Sjahrir menjadi salah satu tahanan politik (tapol) di sana. Ia menjadi satu di antara ribuan kaum yang dijuluki sebagai Digulis.
Boven Digoel dikelilingi parit yang luas dengan hamparan hutan belantara yang nampak tak berujung. Tidak jarang binatang buas seperti buaya disertai nyamuk malaria terbang meraung-raung. Hal ini yang menyebabkan Digoel jatuh menjadi pilihan pemerintah kolonial sebagai penjara alam yang terisolasi bagi mula-mula para tapol PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam peristiwa 1926/1927. Tak hanya bagi kaum komunis, para aktivis nasionalis progresif lain seperti Sjahrir sendiri yang menjadi pentolan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) turut di-Digul-kan.
Penjara tak berjeruji ini dirancang bukan sebagai tempat penyiksaan fisik melainkan hunian dan persinggahan akhir bagi para pembangkang nasionalis Indonesia. Sjahrir menulis bahwa ada dua tipe masyarakat yang tinggal dan bertahan hidup di Boven Digoel.
Pertama, tipe pekerja dan kedua, tipe naturalis. Tipe pertama adalah sekelompok orang atau perorangan yang mau bekerja untuk pemerintah kolonial. Mereka diberikan gaji perbulan atau bahkan harian diikuti jatah 18 kilogram beras setiap bulannya.
Tipe yang kedua yaitu mereka tidak mau bekerja kepada pemerintahan kolonial, yang pada dasarnya menurut Sjahrir baik tipe satu maupun dua tiada bedanya. Lantaran mereka pun harus bekerja lebih keras dengan cara keluar masuk hutan untuk mencari pohon sebagai pondok hunian.
Sjahrir menggambarkan keadaan masyarakat di pengasingan. Beban yang dirasakan mereka terlalu berat sekali. Beban itu bukanlah penderitaan kebendaan melainkan penderitaan batinnya.
Wajah-wajah lesu, mata yang liar dan terkadang seperti tidak normal, dikelilingi oleh lingkar hitam yang dalam. Orang-orang pengasingan secara fisik rata-rata memiliki badan kuat dan urat tangan yang tergurat lagi tegap karena banyak bekerja. Tapi, wajah orang-orang seperti itu lemas, matanya lesu.
Kelesuan itu juga nampak pada perempuan-perempuan dan anak-anak di tanah pengasingan. Hal itu akan menyebabkan masyakat bertindak primitif dan bereaksi membabi buta yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan perbuatanya.
Di Boven Digoel, kolonial Belanda benar-benar memenjarakan pikiran kaum intelektual seperti Sjahrir. Ia merasa jarak batin antara ia dengan bangsanya sangatlah jauh. Ia mengibaratkan bahwa pola pikirnya bak seorang kaum intelektual yang sejajar dengan orang yang tidak berpengalaman di Negeri Belanda pada umumnya.
Tentu bagi Sjahrir yang kritis dan rasional sejak kecil karena didikan ayah yang berprofesi sebagai jaksa menjaga diri agar tak terkoyak kehilangan semangat dan moralnya selama tinggal di Tanah Merah, Boven Digoel.
Kelana Jejaka
Secara umum, kebanyakan Digulis diasingkan beserta keluarganya. Sebut saja di antaranya Digulis terkenal seperti Mas Marco Kartodikromo (1890-1932) maupun Ali Archam (1901-1933) yang membawa istrinya masing-masing turut serta dalam pengasingan hingga keduanya menemui ajal dan dimakamkan di Digoel.
Sjahrir berbeda dengan mereka berdua. Ia sendirian tanpa Maria, istrinya yang nun jauh di Negeri Belanda. Ia mengisi hari-harinya dengan kegemarannya berjalan jauh seorang diri. Aktivitas mengisi kesendiriannya itu membuat ia mendapat julukan ‘Kelana Jejaka’ oleh sesama penghuni kamp.
Ia juga aktif mengunjungi rumah sesama tapol untuk bermain catur dengan mereka, ikut membantu memasak hingga mengayuh kano di sungai-sungai. Bukan iklim, kondisi alam ataupun ancaman penyakit yang lebih mengkhawatirkan bagi Sjahrir. Demoralisasi dalam masyarakat buangan menjadi ketakutan terbesarnya.
Pelbagai aktivitas sang ‘Kelana Jejaka’ itu dilakukan untuk menjaga api semangatnya tetap menyala sehat menghadapi bahaya demoralisasi seperti hidup yang saling curiga-mencurigai satu sama lain dengan kondisi psikis yang tidak stabil.
Secara jitu Sjahrir memberikan gambaran perbandingan kondisi pemenjaraan di Cipinang dengan kamp pengasingan Tanah Merah, Boven Digoel. Di Cipinang ia bisa hidup secara sehat, tidak perlu bayar air dan listrik. Hal yang berbanding terbalik dengan tanah pengasingan Digoel yang seringkali harus memaksa dirinya menjadi seorang arsitek tiban sekaligus tukang bangunan untuk merancang, membangun, dan memperbaiki pondok tempat tinggalnya sendiri yang terbuat dari kayu dan seng.
Sidang pembaca dapat turut merasakan apa yang Sjahrir lihat, dengar, dan rasakan secara langsung melalui buku Renungan Indonesia-nya. Berdasarkan pengalaman hidupnya itu, Sjahrir ingin memberikan sebuah renungan dari sudut pandang dirinya sebagai pembangkang kolonial Belanda sekaligus manusia baru beridentitas nasionalis Indonesia.
Pada awalnya memang “Renungan Indonesia” menjadi tempat bagi Sjahrir menumpahkan semua rasa dalam surat-suratnya untuk Maria, istri pertamanya. Surat-surat yang memuat cerita suka dan dukanya di tanah pengasingan.
Kini tumpahan renungan itu bukan lagi menjadi sekedar pelampiasan bagi sang istri melainkan menjadi podium kesaksian bagi segenap anak negeri akan penemuan Keindonesiaan yang ia perjuangkan hampir seumur hidupnya.

Pusara Sutan Sjahrir di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan. Akhir-akhir ini jagad media sosial ramai berhamburan kutipan dengan grafis yang mencuplik dari kalimat Sjahrir, “jangan mati sebelum ke Banda Neira.” Sebuah pesan yang kini dimaknai sebagai upaya menjelajahi Nusantara oleh generasi muda negerinya, termasuk berkunjung ke Banda Neira, salah satu tempat etape pengasingannya oleh pemerintah kolonial (Foto Koleksi FX Domini BB Hera, 23 Juni 2024).
—-
* FX Domini BB Hera. Sejarawan, Dosen Luar Biasa Universitas Ciputra Surabaya, dan Produser Film Dokumenter Pendek Selasih: Wanita dengan 11 Nama (2023).