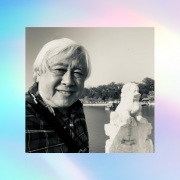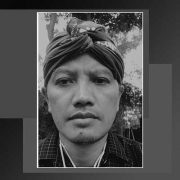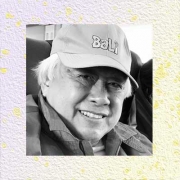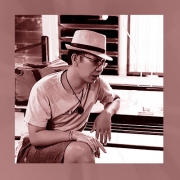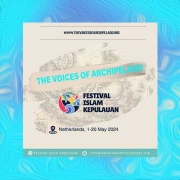Jalan Budaya
Oleh Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ.*
1. Manusia adalah makhluk yang berusaha terus menerus mencari “makna” dalam hidupnya. Dia juga terus menerus mengacu hidupnya pada apa yang dipandang berharga sebagai baik, benar dan indah dalam menghayati dan menapaki kehidupannya baik individual maupun sebagai komunitas. Dalam dirinya terdapat kemampuan untuk memahami secara akal budi (baca: kemampuan kognitif) mengenai kenyataan dan memaknainya untuk mengetahuinya secara kognitif. Ia mempunyai pula potensi “afektif”, rasa untuk mengagumi dan mengembangkan keindahan (rasa estetis). Di samping itu, manusia juga memiliki kemampuan religius untuk menghayati kehidupannya dalam menjawab dan mengartikan kemana arah perjalanan hidupnya dan dari mana asalnya. Pemikiran ini memandang kebudayaan sebagai “kemampuankemampuan dalam diri manusia perorangan”. Dengan kata lain, kebudayaan dalam diri manusia orang perorang dikatakan pula sebagai kemampuan “cipta” dalam budi, “rasa” dalam kedalaman hati dan nurani serta “karsa” dalam kehendaknya.
2. Ranah budaya. Raymond Williams menaruh Ranah Budaya” dalam 3 wilayah (“The Long Revolution 1975”; Culture 1981). Wilayah pertama merupakan “ranah konsep” yaitu ranah wilayah manusia memproses penyempurnaan diri teracu dan tertuju pada makna pokok universal tertentu. Rumusan ini mendeskripsi (memapar) kehidupan dan tata acuan makna universal yang selalu dihidupi, sistem kepercayaan dan keyakinan tentang arti atau makna hidup. Kedua, kebudayaan sebagai “ranah CATATAN DOKUMENTASI praksis kehidupan”, dimana kehidupan dihayati sebagai “teks” yang mencatat struktur imajinasi, pengalaman dan pemikiran manusia. Ketiga, ranah-ranah rumusan kemasyarakatan kebudayaan sebagai “penandaan” jagat hidup tertentu yang didalamnya kajian-kajian budaya merupakan usaha dan ikhtiar untuk mengontruksi perasaan dalam “adat”, kebiasaan dan struktur mentalitas yang dipakai untuk menghayati kehidupan. Karena itu, kebudayaan dipahami pula sebagai “tata acuan nilai-nilai hidup” perjalanan bermartabat bagi anak-anak dari rahimnya, baik individu perorangan maupun sebagai komunitas. Anyaman dan rajutan tata nilai untuk ziarah perjalanan hidup bersama dari individu-individu itu agar semakin bermartabat sebagai manusia telah membuat jalan kebudayaan menjadi jalan peradaban. Disitulah, kebudayaan merupakan “ruang hidup intuitif”, tempat cita rasa estetis yang merayakan dan memuliakan kehidupan dalam “tari” (ketika keindahan gerak alam dan gerak hidup ditarikan). Dalam “nyanyi”, manakala kehidupan disyukuri kidung berkidung. Itulah wilayah seni cita rasa dan intuisi religius serta estetis dari kebudayaan. Sebagai anak yang lahir dari rahim kebudayaannya, manusia sekaligus lahir dari kebatinan hening lokalitas sukunya, kearifan lokalnya dengan keragaman kekayaan kearifan mengenai kehidupan. Pepatah “tak ada rotan akar pun jadi” berarti daya arif kreatif berusaha untuk mencipta terus yang lahir dari rahim budaya agraris dan tanah sama bijaksananya dengan pepatah “dimana bumi dipijak disitu langit hendaknya dijunjung”, yang lahir dari kearifan untuk menghayati hormat pada langit yang di atas dan ramah pada sesama yang di bumi horisontal ini baik alam maupun antar sesama manusia. Dari paparan di depan, dapat dicatat bahwa jalan kebudayaan mempunyai kekuatan hakikinya karena kebudayaan dengan kemampuan-kemampuannya yang merawat, merayakan dan memuliakan kehidupan merangkumkannya dalam “sistem nilai”. Hakiki, karena kebudayaan menjadi sumber bahasan sebelum dibahasakan dalam aturan atau hukum mengenai apa yang baik (etika), apa yang benar (ilmu pengetahuan epistemologi) serta apa yang indah (estetika) serta yang suci (religiositas). Lalu apa itu “nilai”? Nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh seseorang atau kelompoknya yang dipakai setiap hari untuk acuan laku dan ia wujudkan dalam perilakunya. Rumusan ini sebenarnya abstraksi saja dari yang sudah terpaparkan di depan tadi yang dari kemajemukan penyusun keIndonesiaan disumbangkan oleh kekayaan religi bumi dan samawi, serta kearifan-kearifan lokal keragaman suku-suku Nusantara yang mengIndonesia setelah proklamasi politis bernegara Republik Indonesia dengan ranah kulturalnya yang “bhineka tunggal ika”. Pepatah, peribahasa, gurindam dan kisah-kisah kearifan lokal serta musik etnik, tari dan saga-saga folklore sekawanan jenisnya ini merupakan ungkapan pembatinan nilai-nilai yang diekspresikan untuk satu tujuan yaitu memuliakan hidup dan mengajak anggota-anggota masyarakatnya untuk merawat hidup ini dengan arah semakin bermartabatnya sebagai manusia dalam hidup bersama. Oleh Rokeach (1973, “The Nature of Human Values”), nilai merupakan “keyakinan yang dihayati dalam hidup seseorang didalamnya diyakini sebagai yang berharga dan ketika dihayati dalam hidup akan mewujud dalam perilakunya. Ada 3 sisi NILAI sebagai keyakinan. Pertama, kognisi tentang apa yang diinginkan, menjelaskan pikiran seseorang tentang apa yang diinginkannya. Kedua, nilai memuat sisi afektif dimana orang perorang atau kelompok memiliki rasa emosi mengenai yang baik, indah dan benar. Ketiga, nilai berunsur perwujudan dalam perilaku serta mempengaruhi tingkah lakunya.
3. Maka dari itu, ketika perjalanan hidup membangsa terlalu gaduh riuh menghayati jalan politik yang adu kekusaan dan rebutan kursi dengan nilai kalah menang yang tega untuk saling menyodok dan menjatuhkan, maka pilihan kembali ke jalan kebudayaan sungguh perlu diambil dan ditapaki. Pula ketika jalan ekonomisasi terlalu disempitkan dan direduksi pada apa yang bernilai menguntungkan ekonomis saja dan mencampakkan yang merugikan, maka bahaya homo economicus yang tega saling memakan untuk keuntungannya sendiri mesti dikritisi. Mengapa jalan kebudayaan harus dihayati sebagai solusinya? Sebab kerja-kerja kebudayaan sebenarnya merupakan kerja untuk membuat hidup bersama sebagai bangsa majemuk ini agar secara kultural, struktural semakin “manusiawi”. Artinya, semakin saling menyejahterakan satu sama lain dan negara dengan edukasinya, kesehatannya, hukum adilnya, program ekonomi pro rakyat dan bukan pro pasar melulu serta kerja-kerja penyejateraan sebenarnya menapaki jalan yang harus semakin menuju peradaban, artinya, dari kondisi tega saling mengerkah sesama bagai serigala (homo homini lupus) menuju ke kondisi hidup bersama dimana sesama adalah rekan atau sahabat untuk Indonesia yang adil, beradab dan sejahtera saling menghormati (homo homini socius) Disinilah pendekatan kebudayaan yang melihat realitas masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dari sudut pandang mentalitas manusianya, “nilai yang diacu” oleh individu maupun bersama menemukan relevansinya ketika kita sedang sulit untuk menghayati nilai saling percaya dan nilai mau peduli serta toleransi pada keragaman kita. Tidak cukup penyadaran sebagai pengetahuan atau kognitif. Tidak pula cukup hanya teknis instrumentalis pragmatis namun butuh jalan panjang menghayati proses pembatinan, keteladanan dan kerendahan hati mau saling belajar satu sama lain dan mau saling berbagi dan bukan rebutan tanah dan air serta kekayaan bumi pertiwi ini.
4. Secara reflektif mari kita tengok kembali perjalanan kita di bawah ini:
5. Politik, pada intinya merupakan setiap ikhtiar, usaha dan tindakan perjuangan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama dalam sebuah tata sosial agar hidup bersama sesama warga negara menjadi “lebih baik”.
Persyaratan pelaku-pelakunya adalah kesadaran matang setiap manusia yang dianugerahi Tuhan budi rasional yang cerdas dan hati nurani jernih untuk memilih pilihan tindakan dan penyingkapan pada realitas hidup nyata dalam ranah “moralitas”. Yaitu ranah yang bernilai sebagai “benar”, “baik”, “suci” dan “indah”.
Inilah “ranah etika” moralitas yang merupakan wilayah diskresi dan keputusan untuk memilih 2 energi budaya yang menentukan perkembangan dari tahap saling rebutan untuk bisa hidup (ekstrimnya dalam kondisi saling rebutan untuk bisa hidup dengan mengerkah sesamanya) menuju transisi peradaban, dimana sesama adalah rekan menuju peradaban. Dua energi budaya ini:
“life Culture” yaitu budaya yang merawat, memperjuangkan serta menjunjung tinggi kehidupan dalam “death culture” yaitu energi yang merusak dan hasrat untuk menghancurkan kehidupan.
Maka ranah moralitas atau etika ini adalah wilayah pertimbangan dan keputusan (baik individu maupun bangsa) untuk memilih hidup atau mati.
Sikap mau memilih nilai-nilai (= apa yang dipandang, dihayati sebagai berharga, bermakna dalam hidup sebuah masyarakat / bangsa), yang menopang dan merawat kehidupan atau “penghancuran” adalah pemilihan etis.
Sumber-sumber kultural dan religi yang memuliakan dan merayakan hidup akan memberi secara jernih sikap-sikap etis mengenai yang baik dan benar untuk kemaslahatan bersama.
Nilai-nilai apa yang baik dalam hidup yang benar, suci dan indah berasal dari kearifan hidup, yang ditradisikan dan dibatinkan melalui pepatah, peribahasa, gurindam, pantun, dongen, kidung nyanyi, musik, folklore, kearifan lokal, lalu religi bumi dan religi samawi, ini mempunyai ruang pertimbangannya pada “personal space” (forum internum, ruang pribadi). Dari ruang pribadi setelah melalui diskresi dibawa ke wacana menuju ruang publik.
Dalam sejarah peradaban, akhirnya disepakatilah penghormatan pada ruang pribadi dengan bahasa HARKAT dan MARTABAT kepribadian manusia yang unik, tidak boleh dikoyak bahkan “suci” karena religi mengasalkannya pada legitimasi Kitab Suci. Manusia adalah citra Allah sendiri, yang diciptakan serupa wajahNya. Ia adalah wakil Allah didunia ini. Karena itulah hormat pada martabat manusia menjadi dasar tata sosial dalam bernegara.
Secara padat, inilah penghayatan hidup bersama dengan dasar keyakinan dan pandangan bahwa sesama saya adalah manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan yang juga menciptakan saya, maka meminta saya (secara kesadaran etis) untuk saling menghormati agar hidup bersama damai.
6. Ketika ranah saling mengandaikan tumbuhnya kesadaran mau menghormati sesamanya sebagi berharga, sesama ciptaan Tuhan mengalami krisis sadar sendiri atau tahu sendiri dalam penghayatannya tidak muncul lagi maka peradaban budaya mau sadar sendiri memerlukan sistem hidup bersama.
Ini untuk mamaksa agar kebuasan HASRAT mau mengalahkan orang lain untuk diperalat demi kepentingan sendiri menumbuhkan hukum.
Budaya hukum diciptakan secara sadar oleh anggota-anggota komunitas hidup bersama, untuk menjamin perlakuan adil, hormat dan setara pada tiap orang kerena manusia ciptaan Tuhan. Jadi hidup bersama yang mau berkeadaan (dalam sejarah perkembangan peradaban), harus diberi bentuk aturan hukum. Bila tidak maka yang kuatlah yang menang dan yang lemah kalah.
Sesama adalah subyek, sama-sama manusia bermartabat karena itu hukum adalah bahasa perlakuan untuk setiap orang sesuai hak dan martabatnya. Namun dalam konsensus, dia mempunyai kewajiban menghormati hak dan martabat orang lain pula.
Ketika jaminan perlakuan yang sama dicarikan lembaga penjamin, mulailah negara dengan institusi hukumnya diberi wewenang untuk menjadi penjaga keadilan tersebut agar berlaku bagi tiap warga negara.
7. Menjadi bangsa Indonesia
Pengertian bangsa sebagai “nation” adalah memiliki kesamaan teritori tanah air dengan kesatuan rasa dan hasrat untuk tampil merdeka dalam identitas kemajemukan suku, agama, tetapi “ika” menyatu untuk secara politis menjadi sebuah negara berdaulat.
Kebersatuan itu disertai dengan kepastian hukum dan demokrasi sebagaimana diproklamasikan 17 Agustus 1945 yang merupakan proklamasi politis pemakluman kemerdekaan dari penjajah.
Wujudnya adalah sebuah negara berdaulat Republik Indonesia yang secara politis internasional diakui merdeka dan berdaulat, tetapi secara kultural masih berproses karena loncatan politis tidak serta merta bersamaan dengan proses budaya.
Pengertian bangsa dan pergulatannya merupakan pengertian budaya atau kultural. Artinya, Indonesia yang multietnik, multi agama, multi kearifan dan kejeniusan lokal merupakan proses kebudayaan yang terus menerus berkembang.
Energi dan daya-daya kreatif religiositas, estetika, kebijaksanaan hidup setempat memberikan sumbangan terbaiknya pada keIndonesiaan.
Inilah proses sejarah kebudayaan mengIndonesiakan sejak kemauan untuk pencerahan dan menempuh jalah peradaban modern dimulai dengan berorganisasi secara rasional, mendidik diri dalam cerdas budi dan bersama-sama secara organisatoris 1908.
Kemudian sejarah mencatat perjuangan bahasa sebagai komunikasi ekspresi diri sebagai bangsa. BAHASA merupakan perajut rasa menyatu dan saling peduli meski beda suku, beda bahasa etnik tetapi bersedia menegaskan bahasa Indonesia diatas bahasa-bahasa subkultur.
Dari ranah budaya pula dirangkum nilai-nilai perajut mengIndonesiakan untuk menjadi dasar acuan bangsa majemuk ini dalam negara RI yaitu religiositas sebagai bangsa Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam persatuan Indonesia, serta menghayati proses musyawarah untuk mufakat dalam sila berkedaulatannya rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
8. Fenomena-fenomena reduksi Pemiskinan makna dari nilai (reduksi)
8.1Pemiskinan makna dari nilai-nilai pokok hidup, awalnya menggejala dalam rancu acuan nilai-nilai lalu menjadi pengering makna
8.2 Yang spirit atau immaterial sudah direduksi nilainya menjadi hitung- hitungan material yaitu uang. Kesukarelaan tanpa ganti imbalan uang semakin tidak ditemukan lagi dalam keseharian hidup.
8.3 Essensi hidup sebagai proses direduksi dalam “jalan pintas”, mau hasilnya tidak mau keringatnya. Proses edukasi sabar dari umpama ulat sutera hanya mau tahap kupu indahnya tatapi tidak dihayati fase ulat, kepompong yang merajut “rumah dengan liur ludah” kemudian baru kupu-kupu. (sehingga trasformasi didalamnya tak dialami). Ranah atau wilayah politik dari cita-cita kenegarawanan dan politik sebagai ikhtiar perjuangan hidup bersama lebih sejahtera direduksi menjadi politik rebutan kekuasaan dan kursi. Etika politik perjuangan kesejahteraan rakyat atau publik dengan nafas untuk menuju keadilan dan kemakmuran serta merawat kemajemukan dan keikaan telah direduksi menjadi rebutan kuasa untuk kepentingan ego pribadi dengan kelompok tanpa etika.
8.4 Indikasi reduksionis NILAI sebagai harga dan makna acuan perilaku dan putusan hidup telah direduksi penghayatannya menjadi “sekedar kognitif”, pengetahuan, hafalan. Akibatnya tiada terjadi proses pembatinan “disgesti” (memamahbiaknya lembu).
8.5 Telah direduksinya penghayatan etis tentang yang baik menjadi ajaran- ajaran moralitas teks tulis. Hidup direduksi dalam moralitas “hitam- putih” baik dan buruk; neraka dan surga tanpa penghayatan hidup yang semestinya disyukuri kepada Sang Pencipta dalam suka dan duka. Akibatnya legalisme dihayati radikal dalam ketakutan akan hukuman neraka membuat indikasi-indikasi puritanisme saat di ruang doa namun di hidup sehari-hari punya wajah lain.
8.6 Disempitkannya kekayaan multidimensi kehidupan publik hanya dalam ruang publik ciptaan. Baudrillard menegasakan bahwa dalam dunia maya melalui revolusi teknologi informasi dan revolusi digital, “ruang hidup dimampatkan bahkan dilipat seperti kertas”. Sehingga tiada lagi ruang nyata natural untuk BERHENING, bersyukur secara alami dalam ruang-ruang ceria alami nyata digunung-gunung yang indah dan tak lagi hirup udara segar di taman-taman bunga nyata.
8.7 Reduksi waktu
Waktu dimampatkan dalam contoh nyata sekaligus mengendarai mobil dijalan menyetir dan mendengarkan musik pada saat yang sama melihat teve mobil dan ber-sms menggunakan ponsel. Dampak reduksi waktu ini
adalah tiadanya lagi atau habisnya waktu hening untuk mengolah pengalaman hidup. Semua informasi berhamburan ke mata dan telinga dengan kecepatan kilat sehingga tak ada waktu sunyi untuk mengheningi arti dan makna hidup.
9. Sumbernya: HASRAT yang harus dikendalikan oleh budi jernih dan nurani.
Victor E. Frankl di ranah-ranah budaya ditunjukkan hasrat-hasrat untuk terus hidup dalam 3 jenis.
9.1Hasrat untuk mencari dan memuasi nikmat (will to pleasure)
9.2Hasrat berkuasa (will to power = bahasa populernya syahwat kekuasaan)
9.3Hasrat untuk mencari dan memberi makna pada hidup (will to significance)
Orientasi nilai proses telah diperpendek oleh materialisme, uang, kenikmatan, kekuasaan sehingga hasrat yang ketiga untuk makna nyaris tidak diberi ruang untuk hidup.
9.4 Kendali dari hasrat:
Pengalaman Bung Hatta menemukan pentingnya rasionalitas budi sebagai pengendali ketika mengalami koyak dan keadaan parah di pembuangan Boven Digul sehingga tertulislah “Alam Pikiran Yunani” untuk mas kawin Rahmi Hatta ya untuk bangsa Indonesia agar “kedaulatan budi” dan daulat diri menyelesaikan mentalitas Inlander koeli dan budak.
9.5Hasrat untuk konsumsi terus inilah yang dipacu oleh konsumerisme. (bangsa ‘produktif’ abad 7-9 dengan Borobudur, Budhisme Sriwijaya yang menyumbang produktif kreatif untuk Tibet, untuk Ayyuttaya Thailand, Cambodia dengan Lingga- Yoni di Ankor Watt kini nyaris melenyap. Dan kita jadi pasar konsumsi mulai dari makanan, sandang, elektronik bahkan musik-musik hiburan.
Abad 7-9 pula kita sudah memberi sumbangan dengan Borobudur, Muara Jambi, dan hubungan dengan Nalanda sebagai tempat pendidikan Buddhisme dengan Attisa belajar.
—–
*Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ, Guru Besar STF Driyarkara, Dosen Pasca Sarjana UI, Budayawan.