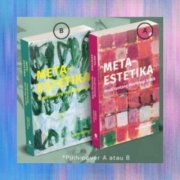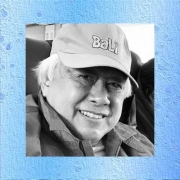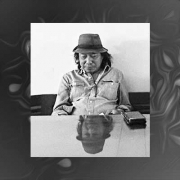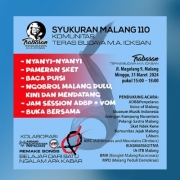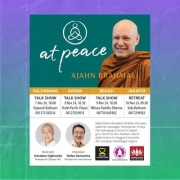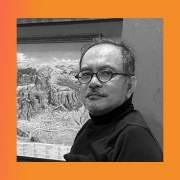Estetika Kesahajaan Transenden: Refleksi atas Puisi-Puisi M. Faizi sebagai Ibadah Estetik Santri Modern
Oleh: Abdul Wachid B.S.*
I. Pendahuluan (Objektivisasi)
Pesantren di Madura tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan religius, tetapi juga sebagai ruang kultural dan spiritual yang subur bagi tradisi kepenyairan. Dalam konteks ini, sastra santri berkembang sebagai medium ekspresi spiritual sekaligus refleksi sosial, di mana pengalaman religius sehari-hari, wirid, dzikir, dan kehidupan pesantren menjadi sumber inspirasi utama. Pesantren bukan sekadar tempat belajar kitab, tetapi juga laboratorium hidup bagi pembentukan kepekaan estetis, etis, dan spiritual.
Faizi, lahir di Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, pada 27 Juli 1975, dan menempuh pendidikan pesantren di Annuqayah Guluk-Guluk, Madrasatul Qur’an Jombang, Nurul Jadid Probolinggo, serta melanjutkan studi S-1 di IAIN Sunan Kalijaga dan lulus Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; muncul sebagai penyair yang menempuh jalur khas ini. Melalui kumpulan puisinya Sareyang, Lirik Penunggu Kesunyian (Jakarta: Pustaka Jaya, Cetakan I, 2005), Faizi tampil sebagai penerus tradisi kepenyairan Madura setelah generasi D. Zawawi Imron, namun dengan nuansa yang berbeda. Jika Zawawi Imron kerap menonjolkan heroisme religius dan retorika yang kuat, Faizi lebih menekankan refleksi kontemplatif, humor subtil, dan kesahajaan bahasa, tetap mempertahankan kedalaman spiritual yang akrab dengan kehidupan santri modern.
Tidak seperti tokoh-tokoh sastra pesantren yang dikenal luas karena ketokohannya, M. Faizi menulis dengan cara sunyi; puisi-puisinya adalah perpanjangan dzikir, bukan alat pencarian kemasyhuran. Nada kesederhanaan dan humor dalam puisinya bukan sekadar estetika, melainkan cerminan pengalaman hidup santri modern yang menyeimbangkan tuntutan religius, sosial, dan dunia kontemporer. Kesahajaan bahasa yang ia pilih menghadirkan suasana akrab dan kontemplatif, seolah pembaca diajak duduk bersama dalam wirid atau dzikir sehari-hari, meresapi setiap kata sebagai ibadah estetik.
Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk memahami puisi santri tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai manifestasi pengalaman religius yang hidup, di mana bahasa, ritme, dan humor menjadi medium refleksi spiritual sekaligus kritik lembut terhadap kompleksitas dunia modern. Puisi menjadi jalan sunyi, sekaligus dzikir yang menyatu dengan pengalaman sehari-hari, menegaskan bahwa keindahan bukan sekadar bentuk, tetapi juga ibadah.
II. Personalisasi & Argumentasi
1. Kesahajaan sebagai Estetika Dzikir
Muhammad Faizi, melalui puisinya “Lirik Sareyang”, menampilkan kesahajaan bahasa sebagai inti dari estetika dzikir. Kesederhanaan diksi, keakraban nada tutur, dan kelugasan ekspresi menjadi cara Faizi menyingkap pengalaman spiritual tanpa lapisan retorika yang berlebihan. Ia menulis seperti santri yang berdzikir dengan kata, bukan untuk mengagumkan pembaca, melainkan untuk merendahkan diri di hadapan Yang Maha Tinggi.
Dalam bait pembuka “Lirik Sareyang”, Faizi menulis:
Akulah Sareyang.
Akulah anak kecil dekil yang berjalan sendiri di pinggiran
sejarah. Tak ada orang yang menghiraukanku, kecuali dengan
sebelah mata memandang.
…..
(Sumber: https://kepadapuisi.blogspot.com/2015/08/sareyang.html)
Citra “anak kecil dekil” bukan sekadar representasi sosial dari sosok marginal, melainkan simbol spiritual dari fana’, keadaan di mana manusia menanggalkan keakuannya di hadapan Allah. Dalam tradisi tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din, perjalanan spiritual selalu dimulai dari takhalli (pengosongan diri) menuju tajalli (penyingkapan makna Ilahi). Kesahajaan ini menjadi bentuk takhalli estetik, di mana penyair menanggalkan segala bentuk kesombongan intelektual dan artistik agar makna dapat menyingkap sendiri dalam keheningan.
Faizi menegaskan semangat kerendahan hati itu dalam larik lain:
…..
Tapi, aku tak mau diam. Walau telinga tersumbat, biarpun
mata tersilap, aku akan tetap berdiri, sekalipun hanya seorang
diri di hadapan kebisingan dunia, walaupun serak suaraku,
hanya gumam, bahkan mungkin cuma bisikan yang lenyap
terbawa angin.
…..
Larik ini bukan sekadar pernyataan keberanian moral, melainkan ekspresi spiritual tentang istiqamah: keteguhan berdiri dalam sunyi. Kesahajaan gaya, di sini, berfungsi sebagai bentuk dzikir eksistensial; sebuah kesetiaan kepada kebenaran yang melampaui kemegahan bahasa. Faizi menulis bukan untuk memamerkan kemampuan berbahasa, melainkan untuk menghadirkan kesunyian yang berzikir di tengah kebisingan dunia.
Maka, kesahajaan dalam puisi-puisi Faizi menjadi jalan ibadah estetik. Ia menjadikan kata sebagai wirid, dan puisi sebagai mihrab tempat penyair menunduk. Dalam setiap larik, bahasa tidak meninggi untuk mendominasi makna, melainkan menunduk untuk mengabdi kepada Yang Maha Suci. Itulah estetika dzikir: kesahajaan yang memuliakan keheningan dan menjadikan kata sebagai bentuk sujud spiritual.
2. Ironi dan Humor Spiritual
Muhammad Faizi, dalam Sareyang, Lirik Penunggu Kesunyian, menempatkan ironi dan humor bukan sebagai ornamen estetis, melainkan sebagai perangkat spiritual dan etis. Humor dalam puisinya lahir dari kesadaran bahwa manusia modern sering kali lucu di hadapan Tuhannya; terlalu serius mencari kebenaran, namun justru tersesat dalam pencarian itu sendiri. Dalam kerangka sufistik, humor menjadi jalan tawadhu’: kerendahan hati yang tumbuh dari pengakuan akan kelemahan diri.
Puisi “Lirik Sareyang” menghadirkan tokoh eponim Sareyang yang bersuara seperti anak kecil “dekil” yang berjalan sendiri “di pinggiran sejarah”. Nada liris ini memadukan kesungguhan spiritual dengan kegetiran ironis: seorang yang mencari cahaya justru harus menempuh jalan sepi, bahkan kadang ditertawakan. Namun, dari ironi itulah muncul tawa batin yang lembut. Sareyang menertawakan dirinya sendiri karena tahu betapa kecilnya manusia di hadapan kosmos, betapa sia-sianya ambisi manusia ketika “hanya gumam, bahkan mungkin cuma bisikan yang lenyap terbawa angin.” Di sini, Faizi tidak sedang menulis satire sosial yang pahit, melainkan menampilkan humor batin, tawa yang tumbuh dari kesadaran fana’: pengakuan bahwa kebenaran tidak pernah dapat dimiliki, hanya bisa didekati dengan rendah hati.
Ironi Faizi mengandung dimensi ma’rifat: kearifan untuk menertawakan diri sendiri sebagai cara mendekat kepada Tuhan. Dalam “Kemelut Manusia”, misalnya, sang tokoh digambarkan terus “mencari” kebenaran, tetapi semakin jauh melangkah, semakin ia kehilangan arah. Bahkan ketika ia bertemu seorang tua yang mungkin “Khidir”, ia tetap merasa “tersesat”. Puisi ini adalah kisah lucu sekaligus getir tentang manusia yang menganggap dirinya pencari, namun sesungguhnya hanya berputar dalam labirin pikirannya sendiri. Faizi memantulkan wajah manusia modern yang terjebak dalam kemelut pengetahuan: terlalu banyak teori, terlalu sedikit hening. Humor di sini tidak muncul dari lelucon, tetapi dari ironi eksistensial: manusia yang mencari Tuhan dengan kepala, bukan dengan hati. Dalam kerendahan tafakkur semacam ini, pembaca justru diajak tertawa pada diri sendiri, lalu menunduk.
Humor Faizi sering juga menjelma dalam bentuk sindiran halus terhadap kerakusan dan kepongahan manusia. “Lirik Pengemis Loba” misalnya, adalah monolog seorang manusia yang tak pernah puas: meminta “batu permata”, lalu “intan”, lalu “berlian”, bahkan “lampu merkuri”. Dalam pengakuannya yang jenaka, “Aku adalah seorang pengemis yang rakus, tamak, dan loba”, tersimpan teguran sufistik: manusia bisa berdoa tanpa batas, tetapi tidak pernah merasa cukup terhadap pemberian Tuhan. Faizi menyindir dengan senyum, bukan amarah. Ia meminjam suara orang tamak untuk mengolok dirinya sendiri; humor di sini adalah kritik moral yang lembut, seperti pesan para kiai kampung yang menegur santri dengan guyonan agar tak melukai harga diri.
Demikian pula “Lirik Benda” menampilkan dialog satir antara manusia dan benda-benda duniawi. Penyair bertanya dengan nada heran: “Mengapa engkau begitu dahsyat memikat?/ Apakah rahasiamu hingga tampak penuh pesona?” Benda kemudian “menjawab”: “…/ Jangan salahkan aku dicipta./ …/ Miliki aku dan jadilah engkau tuan. Jangan jadikan aku/ berhala dan engkau menghamba…”
Dialog ini lucu sekaligus dalam. Benda “mengajar” manusia dengan kebijaksanaan yang menertawakan logika manusia sendiri. Humor di sini lahir dari pembalikan posisi: benda menjadi guru spiritual, sementara manusia justru murid yang bodoh. Humor semacam ini menegaskan kebalikan dari kibr (kesombongan); Faizi meminjam gaya gurauan untuk menumbuhkan tawadhu’ di hati pembaca.
Dengan demikian, ironi dan humor dalam puisi-puisi Faizi bukan sekadar hiburan rohani, melainkan bagian dari praktik tazkiyatun nafs: penyucian jiwa melalui kesadaran akan kelemahan diri. Ia menertawakan dunia bukan untuk meremehkannya, melainkan untuk mengendapkan pesonanya. Tawa menjadi zikir yang lembut, mengingatkan manusia agar tidak terlalu yakin pada keseriusan dirinya. Dalam dunia yang “bising” dan “gulita” sebagaimana dikisahkan dalam “Lirik Sareyang”, Faizi menemukan bahwa kebijaksanaan sering kali berawal dari senyum kecil atas diri sendiri: tawa yang menuntun kepada cahaya.
3. Musikalitas Dzikir dan Struktur Meditatif
Dalam buku Sareyang, Lirik Penunggu Kesunyian, M. Faizi memperlihatkan kemampuan mengubah bahasa menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Struktur puisinya tidak dibangun atas logika linear sebagaimana karya-karya modernis, melainkan melalui pola repetisi dan irama lembut yang mengingatkan pada wirid. Pola ini menandai dimensi meditatif dalam penciptaan puisi: sebuah cara dzikir melalui kata.
Faizi, sebagaimana para penyair sufi terdahulu, memandang bahasa bukan semata alat komunikasi, melainkan ruang untuk menemukan Tuhan. Hal itu tampak jelas dalam puisi “Aku Mengadu Pada-Mu”, di mana irama doa berpadu dengan perenungan eksistensial yang jujur dan rapuh:
Gusti, engkau satu-satunya tempat aku mengadu
Kadang aku ingin mengaku sungai yang bila mengalir,
Engkaulah lautnya. Dengan begitu, aku dengan-Mu bisa
menyatu. Tapi, betapa aku malu bila air hanya menyatu dengan
yang senyawa. Mungkinkah ia menyatu pada unsur berlainan?
Dan kalau dua unsur itu, Engkau dan aku, adalah serupa,
haruskah unsur yang satu menyembah unsur yang lainnya?
…..
Puisi ini bergerak seperti napas dzikir, teratur, pelan, dan terus mengalun menuju kesadaran ilahiah. Enjambemen di tiap larik mengalir lembut, memunculkan efek kontemplatif. Pembaca seolah diajak berdzikir bersama, larut dalam kerendahan hati seorang hamba yang menyadari kefanaan dirinya. Struktur semacam ini mengandung ritme rohani, bukan sekadar musikalitas bunyi. Ia menjadi bentuk doa yang menembus ruang estetika menuju pengalaman transenden.
Irama spiritual ini juga hadir dalam puisi “Pesan Sebelum Berjalan”, yang memadukan suara seorang ayah dengan hikmah perjalanan batin:
……
Tanpa menunggu puteranya bertanya, sang ayah menerus
kan pesannya, “Anakku, dalam diri manusia ada sebuah racun
yang lebih jahat ketimbang bisa, lebih getir daripada empedu,
lebih anyir daripada darah. Tapi, tak banyak orang yang sadar
bahwa racun itu selalu ada, bahkan membiarkan racun itu
menggerogoti dirinya tanpa sepengetahuannya. Itulah iri dengki.
Ia tidak seperti mengumpat, mengutuk, dan mencaci. Karena
ia tidak butuh lidah untuk menyakiti lawan bicara, tapi punya
banyak mulut di hati untuk membenamkanmu dalam celaka.”
…..
Nada pengulangan dan pola nasihat yang bertahap menjadikan teks ini seperti zikir kehidupan: mengandung peringatan, pengingat, dan penyerahan diri. Repetisi tematiknya membentuk semacam wirid moral, menegaskan bahwa setiap perjalanan manusia adalah perjalanan spiritual, dan setiap langkahnya adalah peringatan untuk menyucikan hati.
Sementara itu, dalam “Lirik Pekerja Keras”, Faizi menghadirkan irama yang lain: ritme kerja, gerak, dan ketekunan yang juga bersifat dzikir. Pengulangan kata “melihat” dan “kerja keras” menjadi mantra profetik yang menegaskan nilai spiritual dalam tindakan duniawi:
Aku melihat peluh yang mengucur dari pori-pori tukang
bangunan, para pemecah batu, kuli pelabuhan, abang-abang
becak di terik siang, saat panas memuncak, merembes di
punggung dan keletihan tergurat tegas wajahnya.
…..
Ritme pengulangan dan repetisi yang penuh energi itu membangun suasana zikir fi‘lī, yakni dzikir dalam tindakan. Dengan demikian, Faizi tidak hanya menulis tentang dzikir, tetapi menulis dalam bentuk dzikir itu sendiri.
Maka, struktur meditatif dalam puisi-puisi Faizi berfungsi ganda: sebagai bentuk estetika dan sekaligus jalan spiritual. Repetisi, irama lembut, dan jeda panjang bukan sekadar ciri formal, melainkan gerak jiwa yang menuntun pembaca untuk berhenti sejenak, merenung, lalu tenggelam dalam kesadaran akan Tuhan.
Membaca Faizi seperti membaca doa: kalimat-kalimatnya pendek, namun berlapis makna; setiap barisnya bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Dalam penghayatan seperti itu, puisinya menjadi zikir yang hidup: mengingatkan bahwa bahasa, bila disucikan, dapat menjadi jalan menuju Tuhan.
4. Puisi sebagai Jalan Keempat
Faizi dalam kumpulan puisinya Sareyang, Lirik Penunggu Kesunyian memandang kepenyairan bukan sekadar medium ekspresi artistik, melainkan sebagai jalan spiritual menuju Allah, setelah syariat, tarekat, dan hakikat. Faizi menulis dengan kesadaran bahwa kata, imaji, dan nada bukan hanya estetika, tetapi sarana dzikir yang menyempurnakan kesadaran batin. Penyair ini menempatkan puisi sebagai ibadah: aktivitas lahiriah dan batiniah yang menyatukan pengalaman hidup dengan refleksi spiritual.
Dalam puisi-puisinya, seperti “Pesan Sebelum Berjalan” dan “Aku Mengadu Pada-Mu”, Faizi menekankan perjalanan manusia melalui dunia penuh tantangan, tipu daya, dan dosa hati; iri, dengki, dan kesombongan. Melalui bahasa simbolik, ia menunjukkan bahwa ujian hidup adalah sarana pembelajaran spiritual, sedangkan doa dan pengaduan kepada Tuhan menjadi titik balik pengalaman estetis menjadi pengalaman ilahiah. Hal ini sejalan dengan konsep wahdatul wujud Ibn ‘Arabi, yang menekankan penyatuan antara pengalaman manusia dengan kesadaran Tuhan (The Bezels of Wisdom (Fusus al-Hikam), Translated by R. W. J. Austin, New York: Paulist Press, 1980). Misalnya, dalam “Puncak”, pendakian fisik dan mental menjadi alegori perjalanan menuju akhir hidup yang hakiki, yakni kematian, sekaligus pengakuan terhadap batas-batas kemampuan manusia dan keagungan ilahi.
Selain dimensi sufistik, Faizi juga menegaskan dimensi etis. Puisi-puisi seperti “Lirik Keadilan”, “Lirik Pekerja Keras”, dan “Lirik Palestina” menekankan tanggung jawab manusia terhadap sesama, penegakan keadilan, dan solidaritas kemanusiaan. Di sini, puisinya berperan sebagai medium profetik, di mana keindahan bahasa dan pengalaman estetis tidak terlepas dari tujuan etis dan moral. Faizi menulis bukan demi kemasyhuran atau pujian, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan melalui karya yang bersifat reflektif, edukatif, dan spiritual.
Simbolisme dalam puisi Faizi juga mencerminkan perjalanan batin menuju kesadaran ilahiah. Dalam “Lirik Santri”, kehidupan pesantren dijadikan metafora untuk perjalanan batin; dalam “Lirik Pohon Tua”, pertumbuhan, ketahanan, dan kematangan menjadi cerminan kesadaran spiritual yang bertumbuh seiring pengalaman hidup. Setiap lambang, mulai dari manusia, benda, hingga angin, tidak hanya menggambarkan fenomena fisik, tetapi juga mengandung hikmah yang menuntun pembaca memahami hakikat hidup dan tujuan keberadaan manusia.
Dengan demikian, puisi M. Faizi menghadirkan keindahan sebagai ibadah, di mana bahasa bukan hanya medium komunikasi, tetapi juga jalan pulang bagi jiwa yang mencari kebenaran, keadilan, dan kesadaran ilahiah. Melalui kata-kata yang dipilih secara cermat dan metafora yang alegoris, penyair menyatukan dimensi estetis, etis, dan spiritual, menjadikan puisinya sebagai sarana kontemplatif dan profetik bagi pembaca.
a. Perjalanan dan Kemelut
Dalam Sareyang, M. Faizi menempatkan perjalanan sebagai simbol pencarian spiritual. Puisi seperti “Pesan Sebelum Berjalan” dan “Puncak” menggambarkan perjalanan batin yang penuh tantangan, sekaligus menjadi metafora kehidupan manusia. Sang ayah yang memberi peringatan tentang “kerikil yang lebih tajam daripada pedang” atau “racun dalam diri manusia” (“Pesan Sebelum Berjalan”) menunjukkan bahwa ujian hidup bersifat internal maupun eksternal, yang memerlukan kesadaran dan ketabahan.
Faizi menekankan bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik, melainkan perjalanan menuju pemahaman diri dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam “Kemelut Manusia”, pencarian itu tampak jelas melalui pengalaman manusia yang tersesat dalam hutan kemelut, menapaki padang sabana, hingga berjumpa dengan sosok yang diibaratkan Khidir. Kegigihan pencarian ini menegaskan prinsip sufistik bahwa jalan spiritual adalah proses berkelanjutan, penuh sabar dan tafakur.
b. Keadilan dan Solidaritas
Tema etis dan sosial hadir dalam puisi seperti “Lirik Keadilan”, “Lirik Pekerja Keras”, dan “Lirik Palestina”. Keadilan digambarkan sebagai “sepercih cahaya dari api kebenaran” yang sulit dijangkau, namun harus diperjuangkan (“Lirik Keadilan”). Faizi menekankan bahwa manusia yang menentang tirani dan penindasan adalah insan mulia, karena mereka berusaha mewujudkan nilai kemanusiaan yang hakiki.
Sementara itu, puisi tentang pekerja keras menyoroti kesungguhan manusia dalam menjalani kehidupan, dari peluh tukang bangunan hingga ketekunan nelayan. Faizi menekankan bahwa kerja keras bukan sekadar usaha fisik, tetapi cara memahami makna hidup, menegaskan kesejajaran antara etika kerja dan spiritualitas. Puisi “Lirik Palestina” membawa dimensi solidaritas global, memadukan kesedihan dan empati, sekaligus menegaskan tanggung jawab manusia atas penderitaan sesama.
c. Kematian dan Kesadaran Ilahiah
Kesadaran akan kefanaan dan hakikat hidup menjadi tema utama dalam “Lirik Kematian”, “Lirik Pohon Tua”, dan “Aku Mengadu Pada-Mu”. Kematian bukan sekadar akhir biologis, tetapi batas yang mengingatkan manusia pada ketergantungan kepada Tuhan. Faizi menulis, “Dunia ini hanya tempat sekejab singgah. Tempat melepas suntuk dan sekadar lelah” (“Lirik Kematian”), menekankan bahwa hidup adalah sarana dzikir dan refleksi spiritual.
“Lirik Pohon Tua” menghadirkan metafora pertumbuhan manusia sebagai pohon yang menumbuhkan kebijaksanaan, melindungi generasi berikut, dan mengingatkan pada keteraturan kosmik. Sementara “Aku Mengadu Pada-Mu” menampilkan dialog batin dengan Tuhan, di mana pengakuan, kerendahan hati, dan pengaduan menjadi sarana untuk mengaktualisasikan cinta dan kepasrahan.
d. Refleksi Estetika sebagai Ibadah
Keseluruhan puisi M. Faizi menegaskan bahwa keindahan bahasa dan pengalaman estetis merupakan bentuk ibadah. Menulis bukan untuk kemasyhuran, melainkan sebagai penyempurnaan dzikir. Hal ini sejalan dengan konsep wahdatul wujud Ibn ‘Arabi, di mana pengalaman estetis berpadu dengan kesadaran ilahiah. Faizi memadukan dimensi spiritual dengan nilai etis, sehingga puisi menjadi medium untuk menegakkan kemanusiaan secara profetik. Dengan kata lain, bahasa dan puisi bukan sekadar ekspresi artistik, tetapi jalan menuju Allah, membimbing pembaca melalui keindahan yang mengandung hikmah dan moralitas.
III. Penutup: Subjektivikasi dan Hikmah
Faizi, melalui kumpulan puisinya Sareyang, Lirik Penunggu Kesunyian, menegaskan bahwa sastra dapat menjadi sarana penghayatan spiritual sekaligus etis. Dalam puisinya, kesahajaan menegaskan keikhlasan; bahasa yang sederhana namun penuh makna melahirkan kedalaman batin, dan humor, meskipun jarang muncul, menumbuhkan kebijaksanaan dalam membaca realitas. Faizi membuktikan bahwa bentuk yang minimalis bukan berarti miskin, melainkan mampu menampung kekayaan pengalaman batin yang luas. Dengan kata lain, nilai universal yang terkandung dalam puisinya tidak hanya estetis, tetapi juga moral dan spiritual, sehingga puisi menjadi medium untuk menegakkan etika kemanusiaan melalui bahasa dan pengalaman pribadi penyair.
Dalam konteks dunia sastra modern yang sering menyanjung inovasi bentuk, eksperimen struktur, dan gaya bahasa yang kompleks, M. Faizi memilih jalan sunyi. Puisi-puisinya sederhana, liris, tetapi berjiwa dzikir. Ia menunjukkan bahwa santri, meskipun hidup dalam tradisi keagamaan, tidak kehilangan kemampuan estetis. Justru, melalui ketekunan membaca alam, sejarah, dan pengalaman manusia, Faizi menghadirkan karya yang menegaskan spiritualitas berakar pada realitas sehari-hari. Kesederhanaan ini tidak mengurangi kedalaman pesan; sebaliknya, kesahajaan menjadi medium agar pembaca memahami hikmah melalui pengalaman dan refleksi, bukan sekadar pengamatan permukaan.
Secara esensial, puisi M. Faizi mengingatkan pembaca bahwa kreativitas bukan sekadar pencapaian duniawi, tetapi sarana untuk mengabdi kepada Tuhan. Dalam kesunyian kata, ia menulis bukan untuk dikenal manusia, melainkan untuk dikenal oleh Tuhannya. Dengan demikian, bahasa dan seni tidak semata sebagai ekspresi estetis, tetapi jalan pulang bagi manusia untuk menemukan makna hidup, kesabaran, dan kebijaksanaan. Hikmah ini memperkuat gagasan bahwa sastra, khususnya puisi, mampu menjadi jalan spiritual yang mengintegrasikan pengalaman estetis dan kesadaran ilahiah, selaras dengan ajaran sufistik dan nilai kemanusiaan universal.
***
—
*Abdul Wachid B.S., Penyair, Guru Besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.