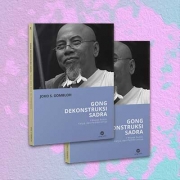Aceh Sebagai Kobokan
Ontologi Air Suci yang Dinistakan dalam Perjamuan Kekuasaan
Oleh: Gus Nas Jogja*
Prolegomena:
Metafora Kobokan dalam Perjamuan Negara
Dalam tradisi jamuan makan Nusantara, kobokan adalah air dalam mangkuk kecil yang disediakan bukan untuk diminum, melainkan untuk membasuh tangan yang kotor setelah atau sebelum menyantap hidangan utama. Ketika kita menyebut “Aceh sebagai Kobokan”, kita sedang membicarakan sebuah tragedi ontologis: bagaimana sebuah wilayah yang memanggul martabat “Serambi Mekkah” sering kali hanya dijadikan tempat pembersihan dosa-dosa politik dan ekonomi oleh pusat kekuasaan, tanpa pernah diizinkan menjadi hidangan utama dalam meja kemakmuran.
Aceh bukan sekadar titik koordinat di peta. Ia adalah sebuah Lokus Spiritual. Namun, dalam narasi politik ekstraktif, Aceh hanya dianggap sebagai penyedia “air basuhan” bagi dahaga industrialisasi global dan ambisi birokrasi yang rakus.
Historiografi Luka:
Dari Pedang Malahayati ke Teror DOM
Sejarah Aceh adalah sejarah perlawanan yang puitis sekaligus getir. Laksamana Malahayati pernah berkata melalui ketajaman pedangnya bahwa “Kedaulatan tidak diberikan oleh belas kasihan, melainkan direbut dengan darah dan harga diri.” Namun, historiografi modern mencatat Aceh dalam bab kelam bernama Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998.
Di masa Orde Baru, Aceh diperlakukan sebagai laboratorium kekerasan. Negara hadir bukan sebagai pengayom, melainkan sebagai mesin sensor yang mematikan saraf-saraf kritis. Tengku Umar pernah berpesan, “Beutoi tanyoe matee, tapi tanyoe matee lam keuadaan meunang” –Betul kita mati, tapi kita mati dalam keadaan menang–. Tragisnya, di masa DOM, rakyat Aceh dipaksa mati dalam kesunyian yang kalah, di bawah sepatu lars yang mencuci “kotoran” stabilitas nasional di tanah rencong.
Politik Chauvinistik: Sentralisme yang Menindas
Teungku Daud Beureueh pernah bermimpi tentang sebuah integrasi yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Namun, pusat kekuasaan sering kali terjebak dalam Chauvinisme Politik—sebuah keyakinan bahwa Jakarta adalah otak, dan daerah adalah otot.
Aceh dipaksa menekuk lutut pada regulasi yang seragam. Kebijakan otonomi sering kali terasa seperti “kobokan” yang hanya diberikan agar tangan-tangan yang protes menjadi basah dan diam, sementara substansi kekuasaan tetap berada di meja pusat. Hasan Tiro dalam kegalauan dan kesunyiannya di Amerika hingga pengasingannya di Swedia, sebagai alumni Fakultas Hukum UII di Jogja menggugat narasi ini dengan sangat puitis: “Indonesia adalah fiksi hukum yang digunakan untuk melegalkan perampokan atas hak-hak bangsa Aceh.” Meskipun nakal dan radikal, pemikirannya adalah cermin Chauvinistic dari rasa dikhianati oleh Orde Baru yang mendalam.
Ekonomi Ekstraktif: Menambang Syurga, Meninggalkan Neraka
Secara ekonomi, Aceh telah mengalami apa yang disebut sebagai Paradoks Kelimpahan atau Resource Curse. Sejak eksploitasi gas alam di Lhokseumawe (PT Arun) hingga tambang emas dan batu bara hari ini, ekonomi Aceh bersifat ekstraktif skala ekstrim.
Berdasarkan data empiris berupa laporan Walhi Aceh, kerugian ekologis akibat Illegal Logging dan konversi lahan hutan mencapai ribuan hektar per tahun di kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
Perusahaan besar multinational mengeruk ekonomi skala ekstrim perut bumi Aceh, mengirimkan royalti ke pusat, sementara angka kemiskinan di Aceh sering kali tetap menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Ini adalah logika “Kobokan”: Aceh diambil sarinya atau makanan utamanya, dan yang tersisa bagi rakyat hanyalah “air sisa basuhan” berupa limbah, degradasi lahan, dan konflik agraria.
Ekologi yang Merintih: Reruntuhan Leuser dan Banjir Air Mata
Secara ekologis, perusakan hutan di Aceh adalah sebuah Dosa Kosmik. Hutan Leuser bukan hanya paru-paru dunia, ia adalah sajadah tempat rakyat Aceh bersujud dan hidup. Ketika Illegal Logging dibiarkan atas nama pertumbuhan, kita sedang menyaksikan penghancuran atas “Kitab Suci Alam”.
Ijinkan saya kisahkan Anekdot Satire berikut:
Seorang pejabat lingkungan hidup duduk di restoran mewah Jakarta, mencuci tangannya di mangkuk kobokan yang wangi jeruk nipis. Ia tidak sadar bahwa air di mangkuknya itu berasal dari sungai di Aceh yang telah keruh oleh merkuri tambang ilegal, dan jeruk nipisnya dipetik dari lahan yang merampas tanah adat janda-janda korban konflik. Ia bersih, tapi Aceh tetap berlumpur.
Diksi Puitis: Perempuan-Perempuan Besi Aceh
Kita tidak boleh melupakan *Tjut Njak Dien*. Di pengasingannya di Sumedang, matanya yang buta tetap melihat Aceh yang merdeka dalam pikiran. Baginya, Aceh adalah ibu yang melahirkan martabat. Namun, hari ini, ibu itu sedang diperkosa oleh buldozer tambang dan gergaji mesin para kolonial domestik.
Ekologi Aceh bukan hanya soal pohon, tapi soal Marwah. Jika pohon terakhir ditebang, maka rencong tidak lagi memiliki gagang, dan doa tidak lagi memiliki keteduhan.
Narasi Spiritual: Kembali ke Meunassa dan Nalar Ketuhanan
Ulama-ulama Aceh selalu menekankan bahwa bumi adalah amanah. Eksploitasi yang merusak adalah bentuk pengingkaran terhadap tauhid. Jika pembangunan hanya menghasilkan gedung-gedung di Jakarta namun meninggalkan kawah-kawah raksasa di Meulaboh, maka pembangunan itu adalah Berhala Modern.
Aceh sebagai Kobokan harus didekonstruksi. Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi tempat pencuci tangan bagi dosa-dosa oligarki. Aceh harus menjadi subjek yang menentukan nasibnya sendiri, dengan air yang tidak hanya membasuh tangan, tapi menyucikan jiwa bangsa.
Anatomi Otsus: Emas di Menara, Lumpur di Desa
Setelah nota kesepahaman Helsinki 2005, Aceh dianugerahi status Otonomi Khusus (Otsus). Triliunan rupiah mengalir deras bagai air bah dari Jakarta ke Banda Aceh. Secara filosofis, Otsus seharusnya menjadi restorasi martabat—sebuah pengakuan atas luka sejarah yang dalam. Namun, secara empiris, Otsus justru menciptakan “Elitisme Baru” yang menjauhkan pemimpin dari rakyatnya.
Dana Otsus yang mencapai ratusan triliun sejak 2008 ternyata gagal membedah akar kemiskinan. Data BPS secara konsisten menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Mengapa? Karena Otsus dikelola dengan nalar Manajemen Proyek, bukan Manajemen Kesejahteraan. Ia menjadi “kobokan” bagi para elit lokal untuk mencuci tangan dari tanggung jawab moral mereka, sementara rakyat bawah hanya mendapatkan bau harum dari sisa-sarananya.
IX. Politik Chauvinistik Domestik: Penindasan dalam Selimut Saudara
Jika dulu *Hasan Tiro* menggugat chauvinisme Jakarta, kini muncul fenomena “Chauvinisme Internal”. Kekuasaan di Aceh sering kali terkonsentrasi pada faksi-faksi eks-kombatan atau elit birokrasi yang terjebak dalam romantisme masa lalu tanpa visi masa depan yang jelas.
Otsus seharusnya menjadi alat untuk membangun kemandirian ekonomi, namun yang terjadi adalah Ketergantungan Fiskal. Aceh menjadi daerah yang paling malas mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena terlalu asyik “mencuci tangan” di ember dana Otsus. *Tjut Njak Dien* jika melihat ini mungkin akan menangis; bukan karena musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam selimut sendiri. Kebanggaan sebagai bangsa Aceh (Chauvinisme identitas) sering kali digunakan sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan mengelola anggaran.
Ekonomi Ekstraktif Skala Ekstrim: Menjual Tanah Makam Pahlawan
Di bawah bayang-bayang Otsus, ekonomi ekstraktif justru semakin menggila. Izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan lindung terus keluar bagai rayap yang memakan tiang rumah sendiri.
Berdasarkan catatan GeRAK Aceh, terdapat ketidaksinkronan data izin tambang yang mengakibatkan kerugian negara milyaran rupiah, sementara dampak lingkungannya tak ternilai harganya. Di Nagan Raya dan Aceh Barat, pertambangan batu bara skala ekstrim telah merusak bentang alam, mencemari air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Bagaimana mungkin sebuah provinsi yang memiliki otoritas khusus untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, justru membiarkan korporasi besar (dan kaki tangannya) mengubah Ekosistem Leuser menjadi kawah-kawah raksasa yang kering? Ini bukan lagi ekonomi, ini adalah Ekosida atau pembunuhan ekosistem.
Anekdot Satire: Jamuan di Atas Banjir
Di sebuah hotel berbintang di Banda Aceh, para pejabat merayakan realisasi anggaran Otsus yang “terserap tinggi” (meski hanya untuk perjalanan dinas dan seminar). Di meja makan, mereka disediakan kobokan air mawar yang mahal. Di luar hotel, rakyat sedang mengungsi karena banjir bandang akibat hutan di hulu habis dibabat _illegal logging_. Saat pejabat itu mencuci tangan, ia berkata, “Ini air otonomi, sangat menyegarkan.” Ia tidak sadar bahwa air itu adalah air mata rakyat yang rumahnya tenggelam oleh lumpur pertambangan.
Narasi Spiritual: Gugatan dari Mimbar Meunassa
Para Ulama Aceh, dari era *Daud Beureueh* hingga kiai-kiai kharismatik hari ini, selalu mengingatkan tentang konsep Amanah. Harta Otsus adalah harta anak yatim korban konflik, harta para janda martir, dan harta masa depan generasi Aceh.
Jika Otsus hanya digunakan untuk membangun gedung-gedung megah yang kosong atau membeli kendaraan mewah bagi pejabat, maka itu adalah bentuk Korupsi Teologis. Spiritualitas Aceh yang berbasis pada syariat seharusnya melahirkan manajemen yang paling bersih dan transparan di Indonesia. Namun, ketika korupsi tetap merajalela di “Tanah Wali”, maka syariat sedang dijadikan kobokan untuk mencuci muka-muka munafik yang haus kekuasaan.
Historiografi DOM dan Trauma yang Tak Terobati
Kita tidak bisa melupakan bahwa Aceh hari ini adalah produk dari trauma Daerah Operasi Militer (DOM). Luka itu belum sembuh. Otsus seharusnya menjadi obat psikologis (trauma healing). Namun, kemiskinan yang tetap tinggi justru memicu “Trauma Baru”: rasa tidak percaya pada sistem.
Negara atau Pemerintah Pusat di Jakarta merasa sudah “lunas” membayar utang nyawa DOM dengan dana Otsus. Padahal, martabat tidak bisa dibeli dengan rupiah. Rasa sakit karena diculik, disiksa, dan diperkosa selama era Orde Baru tidak akan hilang hanya karena ada jembatan baru atau jalan aspal. Tanpa keadilan hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, Otsus hanyalah “kobokan” untuk membersihkan darah di tangan sejarah tanpa pernah mengobati lukanya.
Menjemput Aceh dari Mangkuk Kobokan
Aceh harus berhenti menjadi kobokan. Aceh harus menjadi hidangan utama yang mandiri, berdaulat, dan lestari melalui peta jalan berikut:
1. Transformasi Otsus: Dari konsumsi menjadi produksi. Dana Otsus harus dialokasikan untuk ekonomi hijau yang berbasis kerakyatan, bukan ekstraksi yang merusak.
2. Literasi Ekologi: Mengembalikan filosofi Uteuen (Hutan) sebagai titipan Tuhan, bukan komoditas.
3. Keadilan Sejarah: Menuntaskan kasus HAM agar nasionalisme Aceh berakar pada kepercayaan, bukan pada keterpaksaan fiskal.
Malahayati tidak bertarung di laut hanya agar keturunannya berebut sisa-sisa anggaran. Tengku Umar tidak syahid agar hutan Aceh dibabat habis. Saatnya Aceh kembali menjadi pedang yang tajam dan doa yang mustajab—menjadi Serambi Mekkah yang tidak hanya suci dalam kata, tapi juga adil dalam nyata.
Korupsi Kebijakan: Mencuci Tangan dengan Anggaran Rakyat
Jika korupsi konvensional adalah mencuri uang dari laci negara, maka Korupsi Kebijakan di Aceh pasca-Otsus adalah manipulasi regulasi demi kepentingan oligarki lokal dan pusat. Otsus yang seharusnya menjadi “payung hukum” untuk melindungi rakyat, justru sering kali dijadikan “mantel” untuk menyembunyikan transaksi gelap perizinan.
Laporan Transparency International Indonesia (TII) dan MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa, serta perizinan sumber daya alam, merupakan lahan basah korupsi kebijakan. Dana Otsus sering kali terserap pada proyek-proyek “mercusuar” yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, seperti pembangunan gedung yang terbengkalai atau infrastruktur yang hanya menguntungkan korporasi ekstraktif.
Kita melihat jalan-jalan aspal mulus dibangun menuju lokasi tambang batu bara, sementara akses jalan untuk petani kopi di Gayo atau nelayan di Simeulue tetap hancur. Ini adalah bentuk korupsi yang legal secara administratif, namun jahat secara ontologis.
Ekosida sebagai Kejahatan Negara: Ratapan Tanah Leuser
Dalam narasi ekologi, Aceh kini berada di titik nadir. Eksploitasi tambang emas di Beutong dan batu bara di pesisir barat bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan Ekosida. Ini adalah pembunuhan berencana terhadap masa depan ekosistem.
Menurut Global Forest Watch, Aceh kehilangan ratusan ribu hektar tutupan hutan primer dalam dua dekade terakhir. Hilangnya hutan ini berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi banjir bandang dan konflik manusia-satwa.
Hutan adalah “kitab suci yang tak tertulis” bagi ulama-ulama Aceh terdahulu. Menghancurkan hutan demi emas adalah tindakan menyobek halaman-halaman keberkahan. Otsus yang gagal memproteksi Leuser adalah Otsus yang telah kehilangan ruh spiritualnya.
Anekdot Satire: Robot Otsus dan Rakyat yang Lapar
Seorang insinyur menciptakan “Robot Otsus” yang diprogram untuk menyejahterakan rakyat. Namun, setiap kali dimasukkan data “Rakyat Miskin”, robot itu secara otomatis mengeluarkan output “Pembangunan Kantor Pejabat”. Ketika ditanya mengapa, robot itu menjawab, “Program saya diatur oleh dialektika kobokan: cuci tangan dulu di kantor mewah, baru sisanya (kalau ada) untuk rakyat.”
Manifesto Budaya: Bangkitnya Generasi “Pedang Nalar”
Kepada Aneuk Muda Aceh, masa depan tidak berada di dalam mangkuk kobokan para elit. Masa depan ada pada kemampuan kalian mendefinisikan ulang apa itu “Merdeka”. Merdeka bukan lagi sekadar lepas dari Jakarta, tapi merdeka dari kemiskinan struktur, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari ketergantungan pada ekonomi ekstraktif yang merusak.
Manifesto Generasi Baru Aceh:
1. Hentikan Romantisme Buta: Hormati sejarah perlawanan, tapi jangan jadikan ia alasan untuk memaklumi korupsi pemimpin lokal.
2. Literasi atas Ekosistem: Lindungi Leuser seolah kalian melindungi makam para Syuhada. Tanpa alam yang lestari, identitas Aceh akan lenyap.
3 bKedaulatan Intelektual: Gunakan dana pendidikan dari Otsus untuk menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, agar Aceh tidak hanya menjadi “kuli” di tambangnya sendiri.
4. Politik Berbasis Etika: Menolak menjadi “tim sukses” bagi para pencuci tangan yang menggunakan isu chauvinisme untuk menutupi ketidakmampuan.
Epilog: Menjadi Air Wudhu, Bukan Air Kobokan
Aceh harus kembali ke khittah “Serambi Makkah”nya sebagai Air Wudhu—air yang menyucikan, air yang mempersiapkan manusia untuk menghadap Sang Pencipta dengan wajah tegak dan hati bersih. Jangan biarkan Aceh ini terus-menerus menjadi mangkuk kobokan tempat para oligarki mencuci tangan dari dosa-dosa ekologis dan kemanusiaan mereka.
Kutipan terakhir dari *Tjut Njak Dien* saat ia ditangkap:
“Jangan kau sentuh aku dengan tanganmu yang berlumuran darah!”
adalah peringatan abadi bagi siapa saja yang mencoba mengelola Aceh dengan niat jahat. Aceh adalah tanah wali, tanah syuhada, dan tanah masa depan. Saatnya kita membuang mangkuk kobokan itu ke tong sampah sejarah dan membangun kembali peradaban yang adil, makmur, dan diridhai-Nya.
Daftar Pustaka dan Rujukan Ilmiah
Reid, Anthony. (2005). An Indonesian Frontier: Acehnese Notes on Memories of War and the Vicissitudes of Modernity. Singapore University Press. (Membahas historiografi perlawanan dan memori perang).
Tiro, Hasan di. (1984). The Price of Freedom: Unfinished Diary. (Analisis politik mengenai identitas dan kedaulatan).
Walhi Aceh. (2024). Laporan Tahunan Perusakan Ekosistem Leuser dan Dampak Tambang Ekstraktif. (Data empiris deforestasi dan kerusakan lingkungan).
Aspinall, Edward. (2009). Islam and Nation: Separatism and Return to Order in Aceh. Stanford University Press. (Analisis chauvinisme politik dan peran agama).
Siegel, James T. (1969). The Rope of God. University of Michigan Press. (Studi spiritualitas dan struktur sosial masyarakat Aceh).
BPS Aceh. (2025). Provinsi Aceh dalam Angka: Analisis Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. (Data statistik kemiskinan pasca-Otsus).
Walhi Aceh & GeRAK. (2024). Otonomi Rusak: Laporan Eksploitasi Tambang di Kawasan Hutan Lindung Aceh. (Data empiris kerusakan ekologi dan korupsi sumber daya).
Schulze, Kirsten E. (2004). The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization. East-West Center Washington. (Analisis latar belakang politik dan konflik).
McGibbon, Rodd. (2004). Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?. (Studi kritis atas kegagalan Otsus sebagai solusi tunggal).
Ibrahim, Alfian. (1999). Aceh di Mata Dunia. (Historiografi perlawanan dan identitas budaya).
Transparency International Indonesia (TII). (2024). Indeks Persepsi Korupsi Daerah: Fokus Otonomi Khusus Aceh dan Papua. (Analisis korupsi kebijakan).
MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh). (2024). Laporan Pemantauan Dana Otsus Aceh: Antara Proyek Fisik dan Kesejahteraan Rakyat. (Data empiris kegagalan fiskal).
Global Forest Watch. (2025). Aceh Forest Loss Analysis 2005-2025. (Data satelit deforestasi).
Hadi, Amirul. (2004). Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh. Brill. (Rujukan sejarah tentang integritas kepemimpinan Aceh).
*Gus Nas Jogja, Budayawan