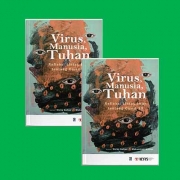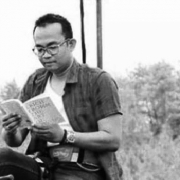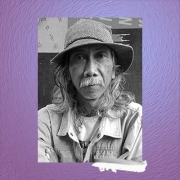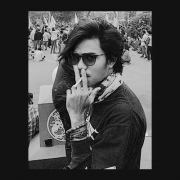Memetik Deviden Berkelanjutan : Pram di Tengah Masyarakat Cemas
Oleh Djoko Saryono
Mendengar, menyebut, dan/atau menyaksikan nama Pram beserta riuh rendah pelbagai diskursus tentangnya, seketika timbul pelbagai pertanyaan di kepala. Kenapa Pram beserta karyanya hingga sekarang tetap dihormati oleh banyak kalangan, tak lekang waktu meski waktu terus berlalu melintasi berlapis generasi. Kenapa Pram diapresiasi mulai generasi “boomers” hingga generasi milenial, bahkan gen z tanpa dimobilisasi dan diindoktrinasi? Kenapa negara, sekalipun telah berganti rezim, tetap saja cemas dan gemetar dengan Pram dan karyanya beserta amplitudo atau resonansi diri dan karyanya?
Kenapa ada kelompok-kelompok masyarakat yang terus mereproduksi kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang Pram dan karyanya hingga melakukan pelarangan ini-itu berkenaan dengan Pram? Apakah negara dan pemerintahan beserta elemen pendukungnya merasa kecil setara dengan seorang Pram dan karyanya? Ataukah justru Pram dan karyanya terus bertiwikrama alias menggelembung setara negara dan rezimnya? Terasa Pram dan karyanya menjelma sebagai institusi sosial budaya, yang seolah-olah berhadapan dengan negara.
Menurut hemat saya, Pram dengan karyanya lambat-laut bertransformasi menjadi institusi sosial budaya khususnya seni sastra beserta hal-hal terkait dengannya. Transformasi persona Pram ke arah institusi Pram itu bukan digerakkan oleh mobilisasi dan rekayasa artifisial oleh pihak-pihak tertentu, misalnya keluarga Pram, pencinta karya Pram, institusi pendukung dan pembela Pram, dan lembaga nasional dan internasional tentang HAM. Transformasi membesar Pram, dari persona ke institusi, itu lebih disebabkan imagologi para pihak yang kontra atau berseberangan dengan Pram: baik pihak negara maupun pihak masyarakat. Misalnya, kelompok tentara dan kepolisian serta pemerintahan.
Bayangan-bayangan atau citra-citra ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan tentang Pram dan karyanya, yang umumnya overgeneralisasi dan overintrepretasi, menjadikan negara mengambil posisi negasi terhadap Pram. Demikian juga ormas dan komunitas tertentu yang diuntungkan oleh negara terus-menerus mereproduksi bayangan berlebihan tentang Pram. Mereka menciptakan imaji mengerikan tentang Pram, lalu mereproduksinya dan menyebarkan ke masyarakat, lantas mengajak masyarakat ketakutan dengan Pram dan karyanya.
Kendati rezim dan pemerintahan berganti, bahkan generasi berganti, tabiat negara dan para penyokongnya untuk menghentikan, apalagi menghancurkan imagologi negatif tentang Pram dan karyanya, tentu juga kiprahnya, tak pernah berakhir. Negara tak hanya melakukan apatisme, malah cenderung antipati, tetapi melakukan reproduksi dan diseminasi ke kalangan luas akan bahaya Pram dan karyanya. Misal, rezim-rezim setelah Orde Baru beserta anasirnya tetap menyebarkan ketakutan dan kecemasan akan Pram dan karya beserta kiprah malunya. Anasir rezim-rezim ini seolah menjadi “homo Orba-icus” (makhluk Orba yang mewarisi ketakutan Orba) terus menyingkirkan rasa simpati dan empati terhadap Pram dan karyanya. Negara dan pemerintahan pasca-Orba beserta elemennya terus memperbesar penghantuan Pram dan karyanya. Tak ayal, terjadilah demonologi, yaitu proses pembentukan citra Pram dan karya beserta kiprah masa lalunya sebagai hantu menakutkan. Begitulah, Pram dijerat narasi demonologi sejak zaman Belanda, Orla, dan Orba oleh rezim pasca-Orba.
Pertanyaan strategisnya di sini adalah apakah proyek demonologi Pram dan karya beserta kiprah masa lalunya, yang cuma imagologi rezim dan elemen tertentu negara (baik negara Orba maupun pasca-Orba), berhasil membendung dan menghancurkan transformasi Pram dan karyanya menjadi institusi sosial budaya atau minimal komunitas sosial budaya? Sesudah Orba jatuh, negara pasca-Orba bercokol, kita menyaksikan proyek demonologi Pram dan karyanya bocor alias pretel di sana-sini. Soliditas negara dan elemennya menguatkan dan menyebarluaskan “demons” alias hantu Pram dan karya banyak retak di sana-sini.
Negara mengalami kegamangan, antara mau simpati dan empati terhadap arus balik kekuatan Pram dan karyanya ataukah tetap bertahan dalam apati dan antipati terhadap Pram dan karyanya. Kehadiran Menteri Kebudayaan ke puncak peringatan Seabad Pram di Blora menggambarkan keretakan dan kegamangan negara. Juga keharusan minta izin Polda dalam acara Seabad Pram di TIM beberapa hari lalu adalah wajah nyata kegamangan elemen negara. Demikian juga demo penolakan penamaan jalan Pram di Blora oleh ormas adalah wajah penyokong negara yang mulai rabun melihat sejarah dan realitas sosial — dan ormas itu tetap mendekap imagologi demonologi Pram dan karyanya yang dibentuk oleh negara. Dalam peringatan Seabad Pram kita telah menyaksikan kegalauan dan keganjilan kehadiran negara dalam gelaran akbar di luar negara.
Mengapa proyek demonologi Pram dan karyanya mulai kempes dan tampak kempes, tak bertaji sama sekali, pada momentum perayaan Seabad Pram? Selain disebabkan oleh perubahan sosial budaya, psiko-kognitif, dan ekonomis- teknologis, kempesnya proyek demonologi Pram dan karyanya disebabkan oleh bersatunya atau tumbuhnya soliditas elemen-elemen masyarakat di luar negara. Ringkasnya, berbagai individu dan kelompok di luar negara secara simultan spontan dan terorganisasi tersatu-padukan oleh kekuatan Pram dan karyanya yang tersusun dalam memori merdeka dan bebas dari cengkeram dan kendali negara bersama elemen yang mendukungnya.
Kita menyaksikan individu-individu dari berbagai generasi, dari generasi “boomers” sampai gen z (mulai Soesilo Toer, Astuti Pram, Hilmar Farid, Happy Salma sampai Rangga) tersatukan oleh Pram dan karyanya. Di berbagai tempat, mereka bergelombang menyelenggarakan acara Seabad Pram dengan dana patungan dan sederhana. Demikian juga kita melihat berbagai lembaga atau organisasi besar dan kecil ikut sibuk mengadakan berbagai kegiatan guna menyemarakkan Seabad Pram di berbagai tempat di Indonesia.
Mereka bersatu padu dengan ikatan bukan hanya oleh nama Pram, karya, dan kisah-kisahnya masa lalu, tetapi juga oleh keyakinan-kepercayaan bahwa gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang ditawarkan Pram baik dalam karya fiksi historisnya maupun karya non-fiksinya. Dalam istilah Peter M. Hass, seorang ahli hubungan internasional dari Eropa, baik individu maupun kelompok di luar negara telah membentuk komunitas epistemik. Dalam hal ini adalah komunitas epistemik Pram yang mempercayai gagasan dan pemikiran Pram dalam Arok Dedes, Arus Balik, Tetralogi Pulau Buru, Panggil Aku Kartini Saja, Korupsi, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, dan lain-lain mampu membersihkan kekotoran psikologis dan realitas sosial tentang Pram dan membawa kebaikan bersama. Komunitas epistemik itu sangat beragam (baik kelas sosial maupun status profesinya) sehingga menjadi tanggul kokoh yang tak mungkin goyang ditabrak demonologi Pram dan karyanya. Ini menandakan jug bahwa demonologi Pram dan karyanya justru telah memunculkan komunitas epistemik Pram dan karyanya.
Komunitas epistemik Pram dan karyanya — tentu juga kisah masa lalunya — di sini merupakan himpunan orang dan kelompok yang berasal dari berbagai pekerjaan, aktivitas, profesi, organisasi, dan kelas sosial yang meyakini gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran Pram dan kiprahnya dapat menjadi basis nilai untuk bertindak bagi mereka. Meskipun longgar ikatannya, mereka menjadi jaringan oleh karena gagasan dan pemikiran Pram dalam karya dan kiprahnya. Ini tampak dari rangkaian kegiatan di berbagai tempat di Indonesia yang mereka gelar dengan mengangkat berbagai tema dan aktivitas yang semuanya bersumbu pada Pram. Mereka menggelar diskusi buku, bazar buku, pentas teater, pameran sampul buku, orasi kebudayaan, dan lain-lain. Mereka pun berpatungan dan berarisan demi terlaksananya gelaran Seabad Pram.
Dalam hubungan ini negara absen baik sebagai inisiator, pengayom maupun maesenas atau sponsor. Badan Bahasa, misalnya, sebagai institusi negara lebih asyik menyelenggarakan peringatan lain dengan pengerahan berbagai sumber daya. Posisinya tak pernah bergeser signifikan sejak Orde Baru mulai berkuasa dan menciptakan proyek demonologi Lekra dan sejenisnya. Negara atau pemerintahan tampak gagu dan gamang akan peringatan dan perayaan Seabad Pram. Di sinilah kita melihat kekuatan sosial-kultural yang menjadi supremasi sipil atas negara di bidang penggelaran acara yang mereka yakini sebagai kontribusi bagi bangsa. Dalam hal ini juga kontribusi Pram dan karyanya bagi bangsa, yang berbeda diametral dengan demonologi Pram oleh negara.
Di antara ayunan demonologi Pram dan karyanya pada satu sisi dan pada sisi lain komunitas epistemik tersebut, Pram, karya, dan kiprah masa lalunya menjadi teks yang berpendar-pendar yang terbuka terus ditafsirkan. Teks berpendar itu disangga intelektualitas dan aktivitas Pram karena pada dasarnya Pram merupakan seorang intelektual dan aktivis. Dalam teks terbuka bersokoguru intelektualitas dan aktivitas yang terus berpendar itulah berpijaran gagasan dan pemikiran Pram. Gagasan dan pemikiran tentang sejarah Indonesia, nasionalisme Indonesia, feodalisme Indonesia (Jawa), eksistensi Cina di Indonesia, mistisisme Jawa (Indonesia), humanisme dan kosmopolitanisme, kolonialisme, etos perlawanan, penindasan koersif, makna kemerdekaan dan kebebasan, dan lain-lain berpijaran di dalam teks Pram yang terbuka.
Para pembaca dan/atau pencinta Pram bukan saja bisa menimba tanpa pernah habis, tetapi juga merawatnya hingga terus berpijaran tanpa pernah padam. Tak heran, berbagai generasi, kelas sosial, dan latar profesi terus tumbuh dan berkembang masuk ke dalam komunitas epistemik yang disatukan oleh teks Pram. Di sinilah kita menyaksikan transformasi Pram dari individu menjadi institusi di samping menyaksikan Pram yang terus membesar (bukan saja bergaung makin jauh secara kronologis dan spasial). Komunitas epistemik Pram bisa kita sebut sebagai penjelmaan transformasi persona Pram.
Di situlah bisa dikatakan Pram memetik deviden atau keuntungan yang terus-menerus alias berkelanjutan. Dalam masyarakat cemas, masyarakat tanpa kompas moral, masyarakat kehilangan teladan nyata (konkret), dan masyarakat di kepungan kepalsuan dan dusta, deviden berkelanjutan terus dinikmati Pram karena Pram menjelma menjadi medan magnetis. Bukan saja ahli waris Pram mendapat royalti buku Pram dan terkerek kemasyhuran Pram, namun juga Pram terus dicari oleh generasi yang tak pernah hidup bersama Pram selain menjadi teladan keberanian, ketabahan, dan penderitaan mempertahankan keyakinan pandangan dan gagasannya. Di sinilah kita menyaksikan matinya atau pelan-pelan terkuburnya proyek demonologi Pram pada satu pihak dan pada pihak lain makin kokohnya komunitas epistemik yang menjaga nyala gagasan dan pemikiran Pram yang sudah menjadi teks terbuka.
***
*Prof. Dr. Djoko Saryono* – Guru Besar FS-UM