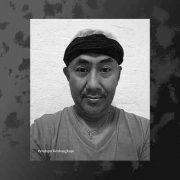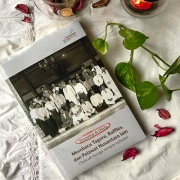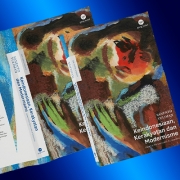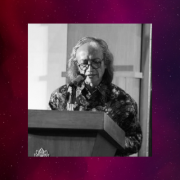Kreator Meme tidak Benar-benar Mati
Oleh Nizar Machyuzaar*
Manakala budaya tulis belum ajek memantapkan diri, apalagi budaya baca kian rapuh digoda budaya skrol gambar (bergerak), kita masih belum sungguh-sungguh meninggalkan kelisanan dalam berinteraksi sosial. Lebih dari itu, kelisanan ini terdukung oleh interaksi sosial yang disediakan platform media sosial.
Bagi para pengguna internet, konten atau informasi yang dihasilkan dari transmisi digital internet dapat diakses dengan cepat, luas, dan massif melalui ponsel. Konten yang menjadi perhatian masyarakat dapat diakses, disebar ulang, bahkan direkreasi untuk menjadi konten baru. Replikasi hasil modifikasi konten dengan tujuan tertentu ini dikenal dengan istilah meme.
Baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah meme. Keratan foto Prabowo dan Jokowi pada konten lain dimodifikasi sedemikian sehingga menjadi berciuman. Meme ini pertama kali diunggah pada platform media sosial X oleh SSS. Tentu saja, pembuatan meme ini dimungkinkan dan dimudahkan dengan berbagai aplikasi internet, terutama modifikasi melalui AI generatif gambar.
Barangkali, kita mesti memikir ulang konstruksi budaya lisan yang masih kuat dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia yang tergambar dalam konten, terutama pada media sosial. Bahkan pun, dalam budaya tulis seperti karya sastra dan karya akademik, konstruksi budaya lisan masih kuat terbaca. Lalu, bagaimana dengan meme digital yang lahir dalam budaya popular saat ini?
Arus Budaya Populer
Kontrovesi meme ini terjadi karena melibatkan dua tokoh, yakni presiden terpilih Prabowo dan mantan presiden Jokowi. Meme tersebut tidak menyertakan takarir. Bahasa visual menarasikan bahwa kedua tokoh memiliki intimasi yang digambarkan dengan fose berciuman. Pesan yang disampaikan bergantung pada bagaimana kita membingkai meme dengan sudut pandang tertentu.
Ketika meme diunggah pembuatnya melalui media sosial, meme telah telah memisahkan diri dengan makna dan pesan subjektif pembuatnya. Makna meme dijamin dengan komposisi dan visualisasi gambar meme. Sementara itu, pembingkaian meme dengan referensi atau sudut pandang tertentu menghasilkan pesan meme.
Kurang lebihnya, referensi yang dilekatkan pada meme inilah yang menimbulkan ambiguitas makna meme. Pada tingkat wacana, pembingkaian referensi atas meme ini akan menyertakan ambivalensi pesan. Hal ini disebabkan daya rekreasi meme pada referensi-diri yang dimodifikasi sedemikian sehingga meme mampu mengusulkan sebuah referensi baru alias sebuah dunia baru.
Pada tahun 1984, melalui buku Metaphor We Live By, George Lokaff dan Mark Jhonson memberi pandangan radikal atas peran bahasa dari sekadar alat pasif menyampaikan gagasan menjadi alat aktif membangun gagasan. Dengan studi kasus metafor, buku ini memberi daya baru atas bahasa yang mampu menyampaikan sesuatu (makna objektif) sekaligus tentang sesuatu (makna kontekstual).
Pada era digital, meme banyak dipilih warganet untuk mengekspresikan gagasan karena meme memang mampu merekreasi informasi ke dalam informasi baru sesuai dengan imajinasi pembuatnya. Tegangan di antara dua informasi ini mirip cara kerja metafor, yakni menghubungkan dua wacana yang sejatinya tidak berhubungan.
Kemampuan meme untuk mereplikasi diri dalam arus informasi digital berkelindan dengan budaya popular, baik bermotif ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Meme digital dapat menyebar cepat, luas, dan massif. Bahkan, ketika selesai diunggal di media sosial, meme telah mematikan sang kreatornya. Meme membangun horizon makna dan pesan di hadapan penanggapnya: berterima dengan selera masyarakat atau justru merugikan pihak tertentu sehingga kreator meme harus dijerat hukum.
Aras Budaya Lisan
Meme sering dihubungkan dengan konten humor, bisa bernada ironi, sinisme, atau sarkasme. Dalam tradisi lisan, percakapan yang diselingi anekdot, plesetan kata, atau kisah satire membumbui lalu lintas percakapan. Dengan terdukung internet, percakapan tersebut dipindahkan ke dalam lalu lintas percakapan, seperti pada platform media sosial atau berbagi pesan.
Dalam situasi percakapan, makna dan pesan subjektif partisipan percakapan dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi karena dapat langsung ditanyakan pada partisipan yang terlibat. Namun, beberapa kasus meme telah menyadarkan kita bahwa kreator meme tidak tidak benar-benar mati setelah mengunggah meme. Karakteristik ambivalensi meme dapat ditafsir beragam, mulai dari ujaran kebencian, konten hoaks, kampanye gelap, penggiringan isu, hingga pencemaran nama baik.
Pada bidang politik, misalnya, meme digunakan untuk menyebarkan informasi karena efektivitas dan fleksibilitas meme dalam menyampaikan pesan kritis. Tak jarang, meme bernada kampanye gelap dibuat untuk memojokkan lawan politik. Karakteristik meme metaforis dan bernada humor menciptakan komunikasi dan dinamika politik yang dialektis, santai, dan cair.
Setidaknya, dalih ini sahih juga dilekatkan pada kasus meme yang terbicarakan di atas. Ambivalensi meme tentu ditafsir berbeda, apalagi melibatkan dua tokoh publik yang sepuluh tahun ini menjadi pusat perhatian. Pada aras sebaliknya, kita meyakini bahwa kreator meme tidak benar-benar mati setelah mengunggah meme di media sosial. Sebab, kita tidak bisa memaksakan tafsir tunggal atas meme, baik kreatornya, masyarakat, maupun pemerintah.
Mangkubumi, 23 Mei 2025
*Penulis adalah penyair dan esais. Saat ini penulis sedang menamatkan program magister pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.