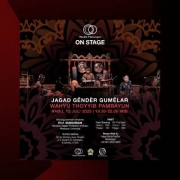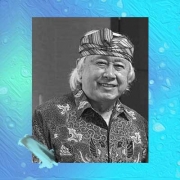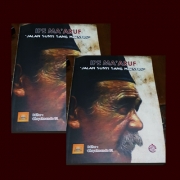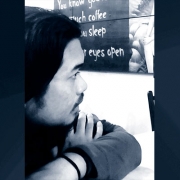Integrasi Nilai-nilai Islam dan Kejawen dalam Serat Sastra Gending Karya Sultan Agung Hanyakrokusumo
Oleh Dr. Mohamad Arief Khumaidi
A. Latar Belakang Masalah
Dr. Harun Hadiwijono dalam bukunya tentang ‘Konsepsi manusia dalam kebatinan Jawa’, mengungkapkan orang Jawa mengolah bahan-bahan kebatinan yang datang dari luar yang dibawa oleh agama Siwa dan Budha serta agama Islam. Orang Jawa mengolah bahan-bahan kebatinan yang datang dari luar, dibawa oleh agama Siwa dan Budha serta agama Islam. Ternyata, bahwa apa yang diucapkan di dalam kebatinan Islam di Sumatra, dan dikemukakan juga dalam pustaka Jawa (Serat Wirid dan Centhini), bahwa manusia sebenarnya ialah Allah sendiri. Sekalipun ajaran itu diberi “pakaian Islam”, namun sebenarnya yang menonjol adalah ajaran agama asli yang diberi bumbu Hindu dan Budha. Lapisan bawah kebatinan adalah Agama Asli, yang diberi bumbu Hindu Syiwa dan Budha. Lebih lanjut Harun menjelaskan rangkuman ajaran Serat Wirid karya R Ng Ranggawarsita mengenai Allah dan penjelmaan-Nya serta yang mengenai manusia, sebagai berikut. Allah atau Dzat Ilahi yang Mahasuci dan mutlak. Keadaan-Nya yang semula adalah Dzat, tidak dapat dikatakan bagaimana, dan tidak dapat disebut apa, sebab Ia sama dengan alam kosong yang sunyi senyap. Dzat yang demikian ini menjadi sebab adanya segala sesuatu. Ajaran tentang Allah yang demikian itu tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha. Melalui penjelmaan atau pengaliran ke luar, Yang Ilahi menjadi imanen di dalam segala sesuatu. Artinya Dzat Ilahi menyelami seluruh alam semesta. Lebih lanjuit dijelaskan bahwa secara khusus Dzat Ilahi itu berada di dalam diri manusia. Kediaman-Nya di dalam manusia, sehingga terjadinya manusia diungkapkan sama seperti penjelmaan Dzat Ilahi itu sendiri. Seluruh bagian tubuh manusia didiami oleh Dzat Ilahi. Dilihat sepintas lalu ajaran Serat Wirid itu tampak seperti ajaran kebatinan Islam, terlebih dengan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam kebatinan Islam. Namun pada hakikatnya ajaran Serat Wirid adalah suatu ajaran Hindu-Budha dengan “jubah Islam”.1
Pendapat Harun yang mengatakan ‘jubah’nya Islam dan ‘isi’nya atau lapisan dalam adalah agama asli, Hindu dan Budha kurang tepat. Harun tidak menjelaskan tentang telah terjadinya proses integrasi antara ajaran kejawen dan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya tasawuf. Sebagaimana kritik yang dikemukakan oleh Simuh terhadap pendapat Harun Hadiwijono dalam disertasinya yang berjudul ‘Men in the Present Javanese Mysticism’, (yang kemudian disadur dan diterbitkan dalam buku buku ‘Konsepsi manusia dalam kebatinan Jawa’). Simuh mengatakan bahwa pendapat Harun Hadiwijono tidak benar, karena keseluruhan ajaran dalam serat wirid hidayat jati dijiwai oleh ajaran tasawuf terutama dalam ajaran martabat tujuh. Banyak ungkapan dalam serat wirid yang bersifat antroposentris, namun sifat antroposentris dalam serat wirid tidak berarti meniadakan wujud Tuhan. Tuhan tidak identik dengan manusia. Ungkapan kesatuan manusia dengan Tuhan dalam serat wirid menunjukkan adanya konsep spiritual “roro ning atunggal”. Dalam konsep ini digambarkan bahwa manusia dan Tuhan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi bersatu dalam diri insan kamil. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Insan kamil merupakan proses upaya seorang hamba menuju Tuhan. Gagasan tentang Allah sebagai Dzat yang mutlak dalam diri manusia bersumber dari ajaran tasawuf, yaitu dalam rumusan ajaran martabat tujuh. Tuhan dalam serat wirid berpaham teisme. Pendapat bahwa Allah adalah kekosongan (awang-uwung) kurang tepat. Sebab awang uwung dalam serat wirid dihubungkan dengan keadaan sebelum penciptaan alam semesta, yaitu tahapan ahadiyah. Jadi Allah bukanlah kekosongan itu sendiri.2
Penelitian Simuh tersebut sangat berhasil membuktikan bahwa unsur tasawuf menjadi ‘content’ pada karya R Ng Ranggawarsita. Namun jauh sebelumnya pada awal Mataram masa kepemimpinan Sultan Agung telah ada Pustaka Jawa, yaitu serat sastra gending karya Sultan Agung. Serat sastra gending sebagai Pustaka Jawa yang berusia lebih tua yaitu jaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karya ini perlu dikaji untuk melihat unsur integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Serat sastra gending karya Sultan Agung sebagai Pustaka Jawa berusia lebih tua dibandingkan serat wirid hidayat jati, perlu dikaji untuk melihat unsur integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Kajian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan pendapat Harun Hadiwijono tentang “jubah Islam’ dan konten Agama Asli, Hindu Syiwa dan Budha tersebut yang telah mengesampingkan kenyataan adanya integrasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam.
Para sufi berjasa dalam mengintegrasikan ajaran Islam dan budaya lokal ini. Dialog antara ajaran tasawuf dan budaya lokal ini menjadi faktor yang menyebabkan Islam dapat terintegrasi dengan kebudayaan Jawa. Sebelum Jawa menjadi Islam, di wilayah Sumatera dan Jawa telah ada agama-agama, yaitu kepercayaan lokal Hindu dan Budha. Islam dapat dengan mudah masuk dan terintegrasi karena elastisitas yang dibawa oleh Islam sufistik. Keberhasilan integrasi Islam dan budaya Jawa karena Islam corak sufistik populer di masyarakat. Sebuah integrasi akan terbangun karena adanya unsur-unsur kesamaan pandangan keagamaan. Pendapat bahwa Islam populer karena sufistik ini mengingatkan pendapat Seyyed Hossein Nasr tentang kesatuan agama-agama. Menutur Nasr, mistik yang ada di dunia memiliki unsur yang sama, yaitu sebagai agama tradisional yang memiliki keyakinan terhadap kekuatan besar di dunia, yang disebut Yang Mutlak atau Tuhan. Kesatuan agama ditemukan dalam Yang Mutlak sebagai kebenaran dan realitas dan awal dari semua wahyu dan kebenaran. Ketika sufi-sufi mengklaim bahwa doktrin keesaan (al tauhid wahid), sesungguhnya mereka sedang menegaskan hal yang fundamental, yaitu pada tingkat Yang Mutlak ajaran agama-agama sama. Keragaman agama-agama seperti keberadaan berbagai ragam bahasa di dunia. Karagaman tersebut menjelaskan tentang kebenaran yang unik itu, yaitu ketika kebenaran memanifestasikan diri-Nya dalam dunia yang berbeda.
Pola dasar mistik ini adalah kesamaan batin, tetapi sintaksis dari bahasa-bahasa itu tidak sama. Karena setiap agama-agama berasal dari Yang Maha Benar, maka segala sesuatu dalam agama tersebut, yang diwahyukan dalam agama tersebut adalah suci, harus dihormati dan dihargai. 3
Pertemuan antara Islam sebagai agama pendatang dan budaya lokal di Jawa membentuk entitas baru yang dikenal dengan kejawen. Perkembangan Islam di tanah Jawa memperlihatkan adanya proses ke arah terbentuknya wajah Islam khas Jawa. Islam mengalami proses kontekstualisasi yang intensif yang diartikulasikan dalam term-term budaya Jawa. MC Rikles dalam buku Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, berpendapat bahwa islamisasi di Jawa banyak diwarnai proses penjawaan terhadap Islam daripada sebaliknya. Artinya penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa berlangsung melalui proses seleksi kontekstualisasi dan internalisasi terhadap ajaran Islam sesuai dengan sistem budaya Jawa. Perkembangan pada masa awal Islam di Jawa memperlihatkan perbedaan dengan perkembangan di dunia Melayu. Persamaan perkembangan Islam di Melayu maupun di Jawa adalah Islam memberikan legitimasi kepada kerajaan, dan keduanya juga bersikap toleran terhadap pembentukan kerajaan absolut. Perbedaannya adalah Islam di dunia Melayu lebih terintegrasi dalam proses perumusan budaya dan pembangunan sistem sosial masyarakat. Sementara kehadiran agama Islam di Jawa dihadapkan pada tantangan budaya yang tetap menghendaki pemberlakuan sistem dan nilai–nilai lokal pra–Islam. Kondisi seperti ini mempengaruhi perkembangan keagamaan di Melayu dan di Jawa. Islam di Melayu hadir sebagai identitas kesukuan, terintergrasi dengan kesukuan. Artinya ‘masuk Islam’ berarti masuk suku Melayu. Berbeda di Jawa, antara Islam dan ke–Jawa–an mengalami proses dialogis, tawar menawar, kadang terjadi pertentangan dalam perumusan identitas budaya Jawa.
Di Jawa pertemuan agama Islam sebagai agama pendatang dan budaya lokal mengalami penyesuaian atau pelenturan yang akhirnya membentuk entitas baru. Dadang Kahmad (2002) menyatakan apabila suatu agama pendatang masuk ke dalam masyarakat tertentu maka terjadi proses pelenturan atau penyesuaian dengan kebudayaan yang telah ada di wilayah tersebut. Terjadi dialog saling mempengaruhi antara budaya lokal dan agama pendatang tersebut. Menurut Joseph M. Kitagawa, bahwa pengaruh agama terhadap masyarakat bersifat ganda. Pengaruh agama terhadap masyarakat terlihat dalam pembentukan, pengembangan, mengubah tata yang sekuler sambil menciptakan struktur yang baru. Pengaruh masyarakat terhadap agama seperti memberi nuansa dan keragaman perasaan dan sikap keagamaan yang terdapat dalam kelompok sosial tertentu.4 Kemudian terjadi kompromi nilai dan simbol agama pendatang dengan budaya Jawa, sehingga muncul bentuk baru yang berbeda dari budaya asli maupun agama pendatang. Proses tersebut merupakan akulturasi yang terjadi secara perlahan sehingga pertemuan antara Islam dan budaya Jawa memunculkan sebuah entitas baru, yaitu Islam Kejawen. Islamisasi di Jawa relatif lebih mudah diterima oleh orang Jawa baik bagi orang awam maupun bangsawan, karena Islam yang datang berbau mistik, yaitu tasawuf. Pertemuan budaya Jawa yang bercorak mistik dan mistisisme Islam tersebut dapat dilihat dari pemikiran R Ng Ranggawarsita. R Ng Ranggawarsita seorang keturunan pujangga Keraton Surakarta Yosodipura I (wafat 1803M) yang dibesarkan dan dididik dalam lingkungan kepujanggaan dan kesustraan Jawa. Pengaruh keislaman pada R Ng Ranggawarsita ditengarai diperoleh dari pengalaman belajar di pesantren Gebang Tinatar Tegalsari, Ponorogo tahun 1813 M, yang sedikit banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Karya-karya R.Ng Ranggawarsita berisi usaha mempertemukan tradisi kejawen dengan unsur-unsur ajaran Islam, yaitu konsep tentang hubungan Tuhan dan manusia.5
Penelitian Simuh tersebut sangat berhasil membuktikan bahwa unsur tasawuf menjadi ‘content’ pada karya R Ng Ranggawarsita. Namun, jauh sebelumnya pada awal Mataram masa kepemimpinan Sultan Agung telah ada Pustaka Jawa yaitu serat sastra gending. Serat sastra gending sebagai Pustaka Jawa yang berusia lebih tua. Karya ini perlu dikaji untuk melihat unsur integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sebagai pembanding pendapat Harun Hadiwijono tentang “jubah Islam’ dan konten yang mengesampingkan adanya integrasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam.
Menurut A.H. Johns, ahli sufisme Asia Tenggara menyimpulkan bahwa sufisme berjasa dalam menjadikan Islam menjadi yang mudah diterima masyarakat. Sufi terlibat secara langsung dalam proses penyebaran secara langsung dunia Melayu dan termasuk Jawa. Sufi memainkan peranan penting dalam organisasi sosial di kota-kota pelabuhan, dengan memfasilitasi penyerapan komunitas non-muslim ke dalam ikatan Islam.6
Peran sufisme dalam Islamisasi di Jawa adalah keberhasilannya dalam merumuskan ajaran Islam yang sejalan dengan budaya lokal. Karena ajaran sufisme menekankan pada praktek-praktek ibadah untuk mencapai “derajat kesatuan” dengan Tuhan. Kesatuan manusia dengan Tuhan dianggap sebagai bentuk kesempurnaan dalam beragama. Sufi bergerak pada tujuan akhir beragama, yaitu rasa menyatu dengan Tuhan, sedangkan praktek–praktek ibadah yang ditentukan syariat sebagai cara atau jalan untuk menuju Tuhan. Dengan cara demikian sufisme menjadi mudah diterima masyarakat. Kedatangan sufisme di Jawa bersinggungan dengan agama Hindu dan Budha yang telah dipeluk oleh orang Jawa. Sufisme dalam banyak aspek sejalan dengan praktek dan pandangan dunia keagamaan masyarakat Jawa Hindu – Budha yang dipeluk masyarakat Jawa pada waktu itu, yaitu pada aspek manunggal kepada Tuhan. Pendapat A.H. Johns ini sesuai dengan fakta tentang Islam yang telah mendapatkan tempat di Jawa. Sejak abad ke-13, sufisme bersama dengan tarekat menguasai wacana intelektual keagamaan di dunia muslim, termasuk juga di Jawa. Tokoh-tokoh seperti Abu Hamid al-Gazali (w 1111), Ibnu Arabi (w. 1240). Abdul Qadir al-Jailani (w. 1166), adalah para sufi terkenal yang hidup dalam bentang waktu sejarah yang hampir sama dengan masa berlangsungnya proses islamisasi di Nusantara. Pada masa yang berdekatan muncul tokoh-tokoh pendiri Tarekat Kubrawiah dan Saziliah di Asia Tengah dan Afrika Utara, seperti Najmuddin al-Kubra (w. 1221) dan Abu Hasan as-Sazli (w. 1258).7
Fokus penelitian ini mengkaji hubungan antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan Jawa yang telah terpadu menjadi satu setelah melalui proses yang panjang dalam sejarahnya. Islam sebagai entitas yang berdiri sendiri berhadapan dengan budaya lokal sebagai variabel yang berdiri sendiri. Kedua kelompok tersebut bertemu dalam damai maupun konflik. Pertemuan antara Islam dan budaya Jawa terbentuk integrasi menjadi masalah yang menarik bagi penulis untuk menelitinya. Obyek kajian ini karya pustaka Jawa khususnya serat sastra gending untuk menjelaskan fakta-fakta tentang pertemuan antara kelompok santri dan kelompok pendukung budaya lokal pada jaman Sultan Agung. Diharapkan kajian penelitian serat sastra gending dapat menjelaskan hal tersebut. Pustaka Jawa serat sastra gending ini menjadi obyek penelitian dengan alasan, pertama: munculnya pustaka Jawa ini terjadi pada waktu berlangsung proses islamisasi di Jawa. Kedua, adanya kemungkinan adanya integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya kejawen. Untuk itu maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana serat sastra gending yang ada pada masa kepemimpinan Sultan Agung ini menjelaskan pertemuan antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa. Untuk melacak hasil pertemuan, dengan menggunakan metode hermeneutika, yang diharapkan dapat mengungkap bentuk integrasi Islam dan Jawa.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa nilai-nilai Islam dan budaya Jawa yang telah bertemu terpadu menjadi satu. Keterpaduan Islam dan budaya melalui proses panjang dalam sejarah sehingga mewarnai bentuk budaya Jawa. Bentuk pertemuan dua kelompok budaya tersebut perlu untuk ditelusuri dalam serat sastra gending. Sehingga objek penelitian adalah karya pustaka Jawa yang berjudul serat sastra gending yang muncul di Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Berdasarkan latar belakang pemikiran ini maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana integrasi antara nilai-nilai Islam dan kejawen dalam serat sastra gending. Apakah upaya-upaya Sultan Agung lainnya dalam melakukan integrasi di luar karya sastra gending yang dapat memperkuat adanya upaya integrasi yang dilakukan oleh Sultan Agung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sub-sub pertanyaan yang harus di jawab adalah:
• Bagaimana corak pemikiran dalam serat sastra gending?
• Bagaimana kebijakan integrasi yang dilaksanakan dalam pemerintahan Sultan Agung?
• Bagaimana bentuk Integrasi dalam karya serat sastra gending?
C. Pembahasan
1. Corak Pemikiran Serat Sastra gending
Serat sastra gending adalah karya yang ada pada jaman Sultan Agung, yang mengandung simbol dan bersifat filosofis yang intinya adalah menjaga nilai harmoni. Menurut Damarjati Supadjar serat sastra gending membicarakan hubungan dua hal, yakni sastra dan gending, yang masing-masing mewakili serangkaian pengertian konsepsional tertentu.8 Pemikiran Sultan Agung memiliki ciri harmoni atau selaras. Pengertian tentang istilah sastra dan gending menjelaskan tentang corak harmoni tersebut.
Sastra gending merupakan dua kata sastra dan gending yang memiliki banyak makna. Kata sastra dan kata gending merupakan dua kata yang secara diametral berbeda makna. Hubungan antara rangkaian dua kata tersebut memiliki pengertian bipolar, seperti ahli sastra di satu pihak berhadapan dengan ahli gending di pihak lain.9 Kata sastra bermakna Tuhan, gending bermakna mahluk Tuhan. Sastra bermakna tasawuf, gending bermakna syariat. Sastra bermakna Dzat Allah, gending adalah mahluk. Sastra adalah halus, abstrak, sedangkan gending adalah konkret/nyata. Sastra bermakna cipta, atau ide, gending bermaka ciptaan, ripta atau hasil karya. Hubungan kata-kata tersebut merupakan rangkaian yang berhadapan, seperti sastra (yang bermakna halus) dengan gending yang bermakna kasar.10
Konsepsi pemikiran dalam sastra gending tersebut adalah harmoni dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama. Sultan Agung memberikan ajaran moral sebagai panduan kehidupan manusia untuk hidup di dunia. Sudjak menyatakan bahwa sastra gending merupakan karya simbolik dan filosofis yang menunjukkan kedalamannya dalam memberikan dasar modal sebagai panduan kehidupan agar manusia senantiasa bertafakur kepada Allah yang Maha Bijak. Membawa suasana untuk bertafakur mendekatkan diri kepada Tuhan.11
Konsepsi pemikiran dalam sastra gending tersebut adalah harmoni dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama. Sultan Agung memberikan ajaran moral sebagai panduan kehidupan manusia untuk hidup di dunia.12 Suwardi Endraswara (2018) memahami sastra gending sebagai perwujudan mistik, yaitu bagaimana manusia menjalankan mistik. Maksud mistik dalam hal ini adalah upaya manusia untuk komunikasi langsung atau bersatu dengan Tuhan melalui tanggapan batin. Kesejatian hidup seseorang apabila dapat bersatu dengan Tuhan (manunggaling kawula gusti). Manunggaling kawula gusti merupakan perwujudan dari sikap manembah, yang maksudnya manembah adalah menghubungkan diri secara sadar, mendekat, menyatu dan manunggal dengan Tuhan.13
Sastra Gending menjadi simbol bagi manusia untuk menemukan Tuhan melalui batin. Sastra adalah simbol kehalusan, sebagai hal tidak mampu untuk dilihat oleh indera, adapun gending hal yang dapat dirasakan melalui keindahan. Sastra hal yang abstrak, sedangkan gending adalah hal yang kongkrit. Antara sastra dan gending menyatu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dan saling melengkapi. Gending tanpa sastra kurang terasa indah, sastra tanpa gending kurang menyakinkan dihadapan manusia. Gending menjadi mudah untuk dirasakan apabila menggunakan sastra.14 Gending menjadi sarana bagi sesorang menghayati keberadaan Tuhan, untuk mendekat sedekat mungkin sehingga mencapai penghayatan menyatu dengan Tuhan. Manusia diibaratkan sebagai gending ketika menjalankan upaya penyatuan kepada Tuhan melalui gerakan-gerakan tertentu sampai dengan keharuan dan menangis. Sastra membawa ke alam ketuhanan yang menjadi penghalus. Irama gending membawa ke ketuhanan yang menyebabkan manusia yang menghayati menangis rindu untuk manunggal kepada Tuhan.
Dalam pupuh Dhandanggula bait 3 dinyatakan:
[Gěndhingira mobah lawan nangis|dupi agěng ngakalnya binabar|kawajiban sakalire|panggawe kang mrih ayu| rahayune pratameng urip | urip prapteng kantaka|těkaping aluhur|kaluhuraning kasidan| tan lyan awit sarengat pranateng bumi|tumimbang glaring jagad|| Terjemahan: Lagunya bergerak dan menangis, oleh besarnya makna yang terhampar, kewajiban semuanya, berbuat kebajikan agar selamat, keselamatan keutamaan hidup, hidup sampai mati, asal dan tujuannya, yang demikian itu ketahuilah, tidak lain pokok syari’at itu terbentang di dunia, sebagai timbangan di dunia seisinya ini].15
Dari pengertian istilah sastra dan gending di atas akan memudahkan pemahaman tentang maksud serat sastra gending.
Kehalusan terkait dengan hal rasa. Rasa menjadi bahan pertimbangan terlebih dahulu. Rasa halus akan berhasil membawa ke alam Ketuhanan dibandingkan dengan melalui pikiran semata. Dalam pupuh asmaradhana bait 10 dijelaskan:
[Rasa pangrasa upami| yekti dhingin rasanira| pangrasku kahanane|kang cipta kalawan ripta|sayekti dhingin ripta|kang rinipta gendingipun|kang nembang dan kang sinembah|| Terjemahan: rasa dan pikiran ibaratnya, tentu lebih utama rasa yang ada dalam diri anda, karena pikiran adalah perbuatan, cipta dan karya, tentu dahulu cipta, yang di cipta itu gendingnya, yang menyembah dan yang disembah]16
Menurut Ibnu Arabi ‘rasa dan perasaan’ itu berada di hati. Ibnu Arabi mengatakan Allah yang menggerakkan rasa pangrasa tersebut. Allah bertajalli kepada kalbu-kalbu para arif di dunia. Sebenarnya yang bertajalli kepada manusia adalah hakikat-hakikat dari sifat-sifat Ilahi. Allah dapat dilihat di dunia melalui kalbu. Tetapi dengan diiringi peringatan dari-Nya, bahwa hamba-hamba tidak akan bisa mengetahui dan memahami Esensi-Nya atau bagaimana Dia sebenarnya dengan firman-Nya: “Dia tidak akan bisa dipahami /dicapai oleh penglihatan mata, sementara Dia bisa memahami/mencapai semua penglihatan. Dan Dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui secara langsung (QS6:103). Hak Allah memberikan hidayah-Nya menggerakkan rasa tersebut. Namun seorang hamba Allah perlu berusaha dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Agar Allah memberikan anugerah petunjukkan untuk membedakan jalan yang lurus dan bukan jalan yang bengkok, jalan orang-orang yang sesat.
Allah Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya melalui tajalli-Nya kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan Dia Maha mengetahui ketidakmampuan mereka untuk menerima tajalli-Nya yang paling suci sesuai dengan yang diberikan oleh Keilaihian, karena memang sesuatu yang baharu tidak mungkin mampu memikul keindahan sesutu yang kadim. Sama seperti Sungai yang tidak mungkin mampu memuat lautan akan menghilangkan entitasnya, baik jika lautan yang datang membanjirinya atau sungai yang datang mengalir padanya. Lautan tak akan meninggalkan sedikitpun bekasan sungai yang membuatnya bisa dilihat atau dibedakan.17
2. Integrasi dalam bidang sosial budaya
a. Integrasi huruf Jawa dan huruf Arab
Sultan Agung Hanyokrokusuma menunjukkan keinginan untuk melakukan integrasi dengan menyamakan fungsi huruf Jawa sebagaimana fungsi huruf Arab. Dalam serat sastra gending tampak upaya mengintegrasikan kedua huruf Jawa dan huruf Arab untuk menjelaskan keberadaan Dzat Mutlak. Menurutnya sastra Arab dan sastra gending pada dasarnya sama untuk membangun keluhuran budi manusia. Baik huruf Arab maupun huruf Jawa dapat menjadi simbol pengajaran dalam rangka menuju Tuhan. Sultan Agung senang dan bersyukur karena semua pihak baik santri maupun abangan setuju dengan pendapat sastra Arab dan sastra Jawa pada dasarnya sama, yaitu penjadi pedoman untuk menuju Tuhan. Pupuh Pangkur bait 1 Serat sastra gending versi Soetji Rahajoe.
[Kawoeri pangésthining bjat|toedoehirèng sastra kelawan gending| sokoer lamoen samja roedjoek|moefakat ing ngakatah |sastra Arab Djawa loehoer asalipoen |gending wit poerbaning akal |kadya kang woes kotjap ngarsi ||.Terjemahan: Telah berlalu pembahasan pergulatan pemikiran, tentang sebuah petunjuk sastra arab dan gending, syukur apabila semua pihak telah rujuk, orang banyak telah mufakat, sastra Arab atau Jawa pada asalnya luhur, kehidupan awalnya berasal dari kekuatan akal,sebagaimana telah di bicarakan di dèpan].18
Merenungkan isyarat Ketuhanan juga dapat melalui bahasa Arab. Hanya saja bahasa Arab memiliki kerumitan tata bahasa. Salah membaca tulisan Bahasa Arab berakibat merubah makna. Sastra Arab dapat membawa perenungan untuk menuju Tuhan. Kandungan isi sastra Arab dapat diperjelas dengan menggunakan sastra Kawi. Pupuh Sinom bait 6 serat sastra gending versi Soetji Rahajoe.
[Woes déné kang sastra Arab| jogja trang loengiding kawi| wilet loekitaning lafal| Kirkat myang pasekat tarki| bya jalal isim fingil| miwah ing saliyanipun| jer wewacaning lafal| dadi mikraji wong arif| geng bebaya lafal salin maknanira. Terjemahan: Adapun pada sastra Arab, agar terang sebaiknya dilakukan pendalaman makna melalui sastra kawi. Sastra Arab memiliki kerumitan kata-kata, panjang pendek dalam pengucapan, dan ke-faseh-an dalam pengucapan kata, letak nama Allah, letak kata benda dan kata kerja dan selainnya. Karena meski hanya tentang pembacaan kata-kata menjadi jalan bagi orang arif untuk naik. Besar bahayanya jika pengucapan salah yang akan berakibat berganti makna yang kau dapatkan].19
Untuk menuju Tuhan dengan cara merenungkan bahasa isyarat yang terdapat dalam pustaka-pustaka leluhur yang berbahasa Kawi. Sastra Jawa juga dapat membawa keselarasan untuk membawa ke alam Ketuhanan. Sebagaimana indah dan sahdunya irama gamelan akan membawa keterpesonaan yang menuju manunggal kepada Tuhan. Pupuh Sinom bait 7 serat sastra gending versi Soetji Rahajoe menyatakan.
[Tan paé rarasing Djawa| renggan wiramaning gending| kinarja ngimpoeni basa| mamanisé dèn reksani| lamoen boebrah kang gending| sastra ngalih raosipoen| kang toemrap ing pradangga |swara pinatoet ngresepi| manroes kongasroming langen kalenglengan.Terjemahan: Tidak berbeda dalam keselarasan dalam bahasa Jawa, indah-nya irama gending menjadi hiasan untuk mempercantik bahasa, manisnya keindahan bahasa dijaga, apabila gendingnya rusak, maka sastra berubah yang menjadi beda rasanya, bagi penabuh gamelan, suara gamelan tersebut harus diselaraskan agar benar dan menyenangkan, agar terus menyebar keharuman sehingga pendèngar terpesona dalam keindahan olah suara].20
b. Integrasi penanggalan Jawa dan Islam
Demi kesatuan negara agar tetap terjaga, Sultan Agung membuat kebijakan yang mengkompromikan dua sistem perhitungan penanggalan. Pada tahun 1633 Sultan Agung menyusun sistem perhitungan baru bagi seluruh kerajaan Mataram yang berdasarkan peredaran bulan.
Sebelum Sultan menciptakan kalender Jawa, Sultan dan rakyat Mataram menggunakan penanggalan kalender Saka yang mengikuti sistem solar (syamsiyah) (Partini, 2011: 263). Kemudian Sultan Agung merubah kalender Saka menjadi kalender Jawa yang berdasarkan pada perjalanan bulan mengitari bumi atau sistem lunair (komariyah). Perhitungan kalender yang menggunakan peredaran bulan ini merupakan sistem perhitungan pada kalender Hijriyah.
Bagi masyarakat pesantren, tidak ada masalah untuk menerima perhitungan tahun Jawa ciptaan Sultan Agung tersebut, karena tahun Jawa disesuaikan dengan tahun Hijriah, begitu pula dengan nama-nama hari dan bulan yang telah menggunakan khasanah pesantren. Sebaliknya bagi masyarakat kejawen, mengalami kondisi yang lebih rumit, karena perubahan dari perhitungan tahun Saka yang berdasarkan peredaran matahari, ke tahun Jawa yang berdasarkan peredaran bulan sebagaimana kalender hijriah. Namun Sultan Agung berhasil menyelesaikan kesulitan masyarakat kejawen tersebut, yaitu perhitungan yang dimulai dari awal tahun Saka. Dengan cara demikian Sultan Agung berhasil mengintegrasikan dua tradisi tanpa menimbulkan konflik. Sultan Agung berhasil menyeragamkan perhitungan tahun di antara masyarakat pesantren dan masyarakat kejawen. Di samping berhasil mengintegrasikan kedua kelompok masyarakat agamis dan masyarakat berlatar budaya lokal, pembaharuan perhitungan Jawa juga memberikan sumbangan yang penting bagi keberlangsungan proses Islamisasi tradisi dan kebudayaan Jawa, yang telah dirintis sejak berdirinya Kerajaan Demak.
c. Integrasi dalam Peradilan Surambi
Sultan Agung membangun Peradilan Surambi menggantikan Peradilan Pradata dengan mengambil nilai-nilai hukum Islam. Sultan Agung menjadi pemimpin peradilan ini, namun dalam pelaksanaan peradilan dilimpahkan kepada penghulu dan beberapa orang pembantu. Penghulu dan para pembantu peradilan merupakan majelis pengadilan surambi yang diangkat oleh Sultan. Keputusan majelis pengadilan surambi merupakan masukan bagi raja untuk memutuskan perkara. Masukan dari majelis dimanfaatkan Sultan untuk menetapkan keputusan suatu perkara. Keputusan yang diambil Sultan Agung tidak bertentangan atau menyimpang dari masukan yang diberikan oleh Majelis pengadilan Surambi.
d. Perayaan sekaten
Sultan Agung menyelenggarakan kembali perayaan sekaten setelah sempat berhenti pada masa kerajaan Pajang. Kegiatan sekaten bermula dari Kasultanan Demak Bintoro, kemudian dilaksanakan kembali pada Sultan Agung. Perayaan Sekaten juga dilaksanakan di Kesultanan Cirebon. Kegiatan sekaten sampai saat ini dilaksanakan di wilayah catur sagatra, meliputi Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangku-negaran, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekaten merupakan pesta rakyat. Rakyat dari berbagai pelosok datang untuk menikmati hiburan dan berbelanja dalam suasana riang gembira. Pada mulanya sekaten merupakan perayaan peringatan kelahiran (Maulid) Nabi Muhammad SAW. Perayaan sekaten berfungsi sebagai sarana dakwah yang bersifat populer. Dalam perayaan sekaten ditandai bunyi gamelan, yaitu gamelan Kyai dan Nyai Sekati. Gamelan Kyai dan Nyai Sekati ini mulai dikumandangkan dari awal perayaan Sekaten. Bunyi gamelan Kyai dan Nyai Sekati sebagai simbol panggilan untuk risalah shahadat, yaitu pengenalan tauhid yang merupakan sendi akidah Islam, yang menyatakan Tuhan itu Esa.
Sultan Agung menghidupkan kembali perayaan sekaten, yang artinya berhasil menyatukan dua hal, yaitu bentuk/wadah dan isi. Bentuk adalah aspek lahir (gending) dan isi adalah aspek batin (sastra). Wadah adalah budaya karya cipta manusia yang berkembang di masyarakat. Sedangkan isi adalah ajaran ketuhanan (tauhid). Ajaran Sultan Agung yang terdapat dalam serat sastra gending adalah kesatuan antara sastra dan gending. Gending adalah bentuk atau wadah, sedangkan isi adalah sastra. Tradisi perayaan sekaten merupakan wadah, sedangkan isinya adalah ajaran tauhid.
3. Integrasi dalam Serat Sastra Gendhing
a. Alif simbol kesatuan Hamba dan Tuhan
Sultan Agung menjelaskan konsepsi tauhid melalui simbol budaya yang telah ada. Dari simbol budaya tersebut diisi dengan nilai-nilai tauhid. Sultan Agung menjelaskan tentang angka satu menunjukkan isim (kata benda), dalam artian Allah Dzat-Nya satu. Dia adalah satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih. Pada waktu Tuhan bertajalli, maka Tuhan tetap Tuhan, Kita tetap tidak mengetahui. Mereka yang menjadi objek tajalli tampak dari perilakunya yang penuh dengan kualitas ketuhanan. Dalam pupuh durma bait 1 dan bait 2 serat sastra gending versi Soetji Rahajoe menggunakan Wisnu dan Kresna. Antara Wisnu dan Kresna maka yang ada Wisnu saja.
[Doermaning kang ngloehoerakěn gending akal| pangèstinireng tochid| Hyang Wisnoe lan Krěsna| moehoeng Wisnoe kéwala| Sri Krěsna datan pradoeli | nadyan loehoera| kang djagad tan ing ngèthi || terjemahannya: Tembang durma menceritakan tentang meluhurkan gending akal, dibanding yang memikirkan Tauhid, Hyang Wisnu dan Kresna, hanya ada Wismu saja, Sri Kresna tidak dipedulikan, walaupun unggul di alam semesta, tidak menjadi pemikiran]21.
Jèn meksiha njipta karo-karonira| Jekti goegoering tochid| temah toendha-bema| anane Dad-Wisesa| soengsoen-soengsoen kalih-kalih| lan sija-sija| mring kaanan sajekti. Terjemahan: Jika masih berpikir kedua-duanya, maka gugur tauhidnya, karena yang berkuasa hanya satu, adanya Dzat Yang Maha Kuasa yang bertumpuk dua, dan itu mengabaikan keadaan sebenarnya]. 22
Tokoh sufi bernama Ibnu Arabi menjelaskan Dzat Mutlak dengan menggunakan simbol alif. Bahwa Tuhan tidak dapat dipahami secara empiris karena Tuhan tidak nyata, bahkan tidak dapat dipahami melalui nalar sekalipun. Maka diperlukan alif sebagai petunjuk untuk memahami Tuhan dan menuju Tuhan. Persamaan dengan Sultan Agung dan Ibnu Arabi adalah Ibnu Arabi menjelaskan Dzat dengan menggunakan huruf hijaiyah yaitu alif. Menurutnya dalam dunia huruf, alif berlaku sebagai khalifah di alam huruf, sebagaimana manusia di alam semesta. Tuhan itu ada, Dia gaib dalam pengertian tidak dapat diketahui oleh indera. Dalam dunia huruf hijaiyah disebutkan bahwa huruf alif sebagai yang tidak bisa diketahui. Penggambaran Dzat yang gaib tersebut melalui huruf alif, sebagaimana adanya Dzat Allah tidak bisa diketahui selamanya. Huruf hijaiyyah dapat diketahui melalui pemberian harakat. Sebuah huruf hijaiyah tidak bisa diketahui jika belum diberi harakat. Sebuah huruf hijaiyah dapat dibedakan dengan yang lain melalui harakat yang sematkan kepada huruf itu, baik itu dhammah, fatah ataupun kasroh.
Huruf alif sebagai huruf yang tidak menerima pemberian harakat. Ia bagaikan Dzat Allah yang berdiri sendiri atau tidak bisa menerima adanya pergerakan (harakah) yang bisa dipahami akal.23 Sedangkan Dzat Mutlak (alif) dapat dipahami melalui ciptaannya (huruf yang diberi harakat) oleh hati mereka yang terbersihkan.
Serat sastra gending menggunakan simbol alif untuk menjelaskan ketuhanan. Pemikir dari Jawa Sosrokartono menjelaskan bahwa alif mempunyai makna, yaitu mengggambarkan tentang jumbuhung kawulo gusti. Alif sebagai pengganti kata ‘Aku’ atau Insun (huruf “A” besar yang diartikan Tuhan). Alif menggambarkan manunggaling kawulo gusti.24
Sifat-sifat Tuhan termuat dalam hakekat Dzat. Sifat melekat pada Dzat. Dzat ada terlebih dahulu, kemudian sifat. Dzat Mutlak melalui nama, sifat dan af’al, yang pada akhirnya tercipta alam semesta. Dalam serat sastra gending pupuh asmaradana bait 11 versi Soetji Rahajoe dijelaskan.
[Dad lawan sifat oepami| sajekti dingin Dadira| doepi woes ana sifaté| moela djamah kehanannja| awal mjang achirira| kang sifat tansah kawengkoe| marang Dad kadjatenira|| Terjemahan: Seumpama Dzat dan sifat, pasti lebih dahulu Dzatnya. Keadaannya kesatuan dalam kejamakan, awal dan akhir, sifat selalu dikuasai oleh Dzatnya].25
Keberadaan Tuhan tidak diketahui oleh indera dan bahkan rasio manusia. Apalagi mengetahui keberadaan Tuhan sebelum alam semesta tercipta. Namun alif ada dalam kenyataan, sebagaimana tanda-tanda keberadaan Tuhan tergelar dalam alam nyata. Pupuh Asmaradana bait 9 sastra gending versi Soetji Rahajoe menyatakan.
[Dad moetlak dipoen arani | mjang latakjoen ing ngaranan|doeroeng kaanan saliré|meksih wang-oewoeng kéwala | ikoe djatining sastra|ananing gending saestoe|doepi alif woes kanjatan. Terjemahan: Dzat mutlak sebutannya, yang disebut dèngan la takyun, keadaan belum ada apapun, masih kosong semata, itu sesungguhnya sastra, keberadaan gending (kehidupan) sebenarnya, merupakan perwujudan alif dalam kenyataan].
Huruf alif yang terdapat dalam pupuh Asmaradana bait 9, bahwa kehidupan merupakan perwujudan alif dalam kenyataan semakna dengan pendapat Ibnu Arabi. Kalimat: ‘iku jatining sastra|ananing gěndhing satuhu|dupi alip wus kanyatan. Terjemahan: Itu sesungguhnya sastra, keberadaan gending sebenarnya, merupakan perwujudan alif dalam kenyataan’.
Ibnu ‘Arabi menyatakan slif juga merupakan simbol Dzat yang tersucikan. Ia tidak memiliki entitas dan tempat di dalam benda-benda jadian. Alif adalah huruf keabadian dan terkandung dalam dirinya keazalian. 26 Menurut Ibnu ‘Arabi, bahwa bagi mereka yang mampu mencium aroma hakekat-hakekat, alif dari segi hakekatnya bukanlah semata huruf. Tetapi orang awam menamakan sebagai huruf. Huruf tersebut adalah perumpamaan dalam bentuk ungkapan kata-kata. Alif berada pada “maqam perpaduan (maqam al jami’). Nama ilahi yang ada padanya adalah nama “Allah”. Sifat ilahi yang ada padanya adalah “berdiri sendiri” (al-qayyumiyyah). Dari nama-nama af’al ia memiliki nama al-Mubdi (Maha Memulai), al-Ba’is (Maha Membang-kitkan), al-Wasi’ (Maha Luas), al-Hafiz (Maha Menjaga), al-Khaliq (Maha Mencipta), al-Bari’ (Maha Pembuat), al-Musawwir (Maha Pemberi Bentuk), al-wahhab (Maha Pemberi Anugerah), ar-Razzaq (Maha Pemberi Rezeki), al-Fattah (Maha Pembuka), al-Basit (Maha Membentangkan), al-Mu’iz (Maha Memuliakan), al-Mu’id (Maha Mengulang), ar-Rafi (Maha Mengangkat), al-Muhyi (maha menghidupkan), al-Wali (Maha Wali), al-Jami (Maha Menghimpun), al-Mugni (Maha Pemberi Kekayaan), dan an-Nafi (Maha Pemberi Manfaat). Dari nama-nama Dzat ia memiliki nama Allah, ar-Rabb, az- Zahir (Maha Lahir), al-Wahid (Maha Satu), al-Awwal (Maha Awal), al-Akhir (Maha Akhir), as-Samad (Maha Menopang Diri-Nya Sendiri), al-Gani (Maha Kaya), ar-Raqib (Maha Mengawasi), al-Matin (Maha Kokoh) dan al-Haqq (Maha Nyata/Benar).
Kata alif tersusun dari rangkaian huruf alif, lam dan fa’. Huruf ini dinamakan Alif karena darinya terangkai (ta’alluf) beberapa kalimat. Kebanyakan dari perkataan dan kata-kata mengandung huruf Alif. Ibnu ‘Arabi menyebut alif sebagai “akar tempat tegak beridirinya huruf-huruf” (qayyum alhuruf). Segala sesuatu bergantung pada alif, sementara alif tidak bergantung pada apapun”. Huruf alif lafalnya berasal dari: hamzah, lam, dan fa. Ia memiliki himpunan dari semua alam huruf dan level-levelnya, tetapi ia tidak berada di dalamnya juga tidak keluar darinya. Ia adalah titik pusat sekaligus periferi (batas garis luar) lingkaran, susunan sekaligus bentangan alam-alam. 27
b. HA-NA-CA-RA-KA dan martabat tujuh
Serat sastra gending menjelaskan kejadian alam semesta mengikuti ajaran martabat tujuh yang dikembangkan Muhammad Ibn Fadhullah al Burhanpuri di Asia Tenggara. Sultan Agung menjelaskan martabat tujuh dengan menggunakan huruf Jawa 20. Menurutnya Dzat Mutlak itu gaib tidak dapat digambarkan, tidak nyata, namun ada. Keberadaan Tuhan tidak diketahui siapapun. Keadaan-Nya telah ada sebelum adanya alam semesta, kosong semata, belum ada apapun, yang disebut la-ta’ayun. Pupuh Asmaradana bait 9 sastra gending versi Soetji Rahajoe.
[Dad moetlak dipoen arani | mjang latakjoen ing ngaranan|doeroeng kaanan saliré|meksih wang-oewoeng kéwala | ikoe djatining sastra|ananing gending saestoe|doepi alif woes kanjatan. Terjemahan: Dzat mutlak sebutannya, yang disebut dèngan la takyun, keadaan belum ada apapun, masih kosong semata, itu sesungguhnya sastra, keberadaan gending (kehidupan) sebenarnya, merupakan perwujudan alif dalam kenyataan].28
Serat sastra gending menyebutkan, dua puluh huruf Jawa mencerminkan tahapan penciptaan alam semesta atau asal mula kehidupan. Lajur pertama huruf Jawa yang berbunyi HA-NA-CA-RA-KA cerminan dari tahap ahadiyah, kemudian lajur DA-TA-SA-WA-LA cerminan tahap wahdah, dan PA-DA-JA-YA-NYA cerminan tahap wahidiyyah. Ketiga tahapan ini disebut sebagai martabat batin. Sedangkan kelompok huruf Jawa terakhir yang berbunyi MA-GA-BA-TA-NGA adalah alam arwah, alam mitsal, alam ajzam, alam Insan. Empat martabat yang terakhir ini merupakan martabat lahir.29 Martabat lahir dan martabat batin adalah simbol yang digunakan serat sastra gending. Representasi dari martabat batin adalah sastra, sedangkan martabat batin adalah gending. Martabat batin ini dapat disepadankan dengan istilah Ibnu Arabi martabat Dzati (Dzat), sedangkan martabat lahir sepadan dengan martabat shuhudi (tampak nyata). Pupuh Pangkur bait 2 dan bait 3 menjelaskan:
[Nadyan sastra kalih dasa| wit saèstoe toedoeh karěping poedji| poedji asaling toemoewoeh mirid sing achadiyat | ponang : HA NA TJA RA KA pitoedoehipoen| déné kang DA TA SA WA LA| kagěntyan kang pamoedji|| Terjemahan: Sastra dua puluh, sungguh benar sebagai suatu petunjuk untuk memuji, memuji asal mula kehidupan, yang diturunkan dari alam ahadiyah, wujud HA NA CA RA KA petunjuknya, adapun DA TA SA WA LA, berganti rindu kepada yang memuji].30
[Wahdad djati kang rinasan| ponang PA DA DJA YA NYA angjaktèni| kang toedoeh lan kang tinoedoeh| sami santosanira| kahanannja wakadiyat pambilipoen| déné kang MA GA BA TA NGA| woes kanjatan djatining sir|| Terjemahan: wahdah sejati yang dirasakan, wujud PA DHA JA YA NYA yang memberi bukti, yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk sama kekuatannya, keadaan wahidiyah yang dimaksudkan, adapun MA GA BA TA NGA, adalah telah mencapai kenyataan sir yang sejati]31
c. Tajalli Hyang Wisnu kepada Kresna
Integrasi tentang tajalli dapat dilihat dari penggunaan simbol-simbol lokal yang terdapat dalam dunia pewayangan. Sebagaimana tersebut dalam pupuh Pangkur bait 15, Hyang Wisnu menjiwai Sri Kresna. Hyang Wisnu menitis kepada Kresna. Hyang simbol dari Adikodrati dan Kresna simbol dari manusia yang sempurna. Dalam cerita pewayangan, perilaku hidup Sri Kresna selalu berada di jalan yang benar. Kresna berperilaku utama, selalu memperbaiki keselamatan mahluk hidup. Hal ini karena Hyang Wisnu menjiwai sri Kresna.
[Hyang Wisnoe noeksmèng Sri Krěsna|pinrih moelya goemlaring boemi-langit| majoerahajoe-ning toewoeh| andjaga djědjěging rat| Prabu Krěsna sapa ngréh noeksmeng ngaloehoer |loehoer wisésèng panjipta| tjipta nroes waspadèng gaib||. Terjemahan: Hyang Wisnu menjiwai diri Sri Kresna, agar mulia tergelarnya bumi langit, memperbaiki keselamatan semua mahluk hidup, menjadi tegaknya alam semesta. Prabu Kresna bertindak sesuai perintah dari yang menjiwai dari atas, dari atas dikuasai oleh pencipta, pikirannya terus tersambung pada yang gaib].32
Sosok Kresna ini merupakan contoh orang yang sudah mencapai tataran memadukan dimensi lahir dan batin. Orang seperti disebut sebagai orang sepuh. Dalam pupuh pupuh pangkur bait 8 dijelaskan:
[Sepoeh minangka taroena| kang taroena minangka anjěpoehi| pratjihna samaring pangwroeh| kaananing Wisésa| panersid sing Dad kenjatan Sang Hyang Wisnoe|winěnang kamot noegraha| Mangrèh ardjaning doemadi. || Orang tua berperilaku sebagai yang muda, yang muda bertindak sebagai orang yang sepuh, tanda samarnya pengetahuan, keadaan dari Yang Kuasa tersirat oleh Dzat kenyataan Sang Hyang Wisnu, diberi wewenang memuat anugerah mengatur kesejahteraan mahluk].33
Orang sepuh ini menjadi pembahasa dalam Pustaka Jawa terkait dengan Insan kamil, manusia sempurna yang bisa memadukan dua unsur dalam dirinya, yaitu dimensi lahir dan dimensi batin. Sebagaimana dijelaskan dalam serat wedhatama pupuh pangkur bait ke 12: ‘sopo tuk wahyuning Allah, gya dumilah mangulah ilmu bangkit, bakat mikul reh mangukut, kuktaning jiwangga, yang mengkono kena senebut wong sepuh, liring sepuh sepi hawa, awas roroning atunggal.34
Insan kamil merupakan tajalli Tuhan kepada insan yang dapat memiliki nama dan sifat Tuhan. Kualitas manusia yang utama, yang dalam serat sastra gending disebut orang yang sepuh. Orang sepuh adalah orang yang mampu menjadi sepuh (tua). Orang sepuh tidak tergantung usia. Orang muda dapat menjadi tua, sebaliknya orang tua dapat menjadi muda. Karena ukuran sepuh adalah kualitas spiritual yang dapat dicapai oleh seseorang. Tajalli yang terjadi pada manusia utama yang disebut dengan orang yang sepuh itu orang yang bisa nyawiji loroning atunggal. Orang yang mampu memanunggalkan unsur lahir dan unsur batin.
Ibnu Arabi menyatunya kualitas ketuhanan kepada manusia tersebut Ketika terjadi tajalli. Tentang proses tajalli tersebut dijelaskan melalui simbol huruf Lam Alief. Dilihat dari segi bentuk, Alif adalah huruf yang berbadan tegak, hal ini menandakan bahwa sebagai manusia harus teguh pendirian, teguh dalam beraqidah, dan kuat dalam beriman. Alif yang masuk dalam kategori ini adalah alif yang terdapat dalam lafadz basmallah. Dalam lafadz basmallah, alif yang semula berbadan tegak kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lafdzul jalalah (lafadz allah), hal ini menunjukkan bahwa alif melebur dalam manusia adalah hadits (baru). Segala sesuatu yang hadits apabila bersanding dengan Dzat yang Qadim (Allah), maka akan lebur, fana’ dan menyatu dengan-Nya. Peleburan bisa terjadi kepada para ahli makrifat billah. Karena mereka sadar bahwa sejatinya tiada sesuatu yang wujud di dunia ini kecuali Allah. Dalam maqam ini, sesorang bersama Allah di manapun ia berada. Firman Allah: ‘wa huwa ma’akum alnama kuntum’ (Allah selalu bersamamu dimanapun berada).35 Upaya yang dilakukan untuk mendekat Tuhan dengan bercermin pada nama, sifat, asma Tuhan.
Simbol yang digunakan Ibnu Arabi dalam menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan tersebut adalah huruf lam dan alif (لا). Ketika alif dan lam saling menemani, masing-masing dari mereka akan diiringi oleh sebuah kecenderungan, yaitu keinginan atau kehendak.
Ibnu ‘Arabi menggunakan simbol huruf lam dan alif (لا) dalam menjelaskan relasi antara manusia dan Tuhan. Ketika alif dan lam saling mendekat, masing-masing membawa kecenderungan, yaitu adanya keinginan untuk menyatu. Kecenderungan ini muncul dari dorongan “rasa cinta yang sangat” (isq), yang digambarkan dengan pergerakan huruf lam (ل). Gerakan huruf lam (ل) disebut sebagai gerakan Dzati (esensial), sedangkan pergerakan alif (ا) merupakan pergerakan aksidental (‘aradhi). Dalam dinamika pergerakan ini, terlihat jelas bagaimana lam (ل) memiliki kekuatan terhadap alif (ا), karena gerakan lam (ل) menyebabkan terjadinya pergerakan baru dalam diri alif (ا). Dalam hal ini lam (ل) lebih kuat untuk mendekat daripada alif (ا), karena rasa cintanya lebih kuat dan dalam, sehingga tekad serta kenginannya (himmah) yang lebih sempurna dari segi wujud dan lebih lengkap dari segi tindakan. Sebaliknya, ketika rasa cinta dalam lam (ل) melemah atau lebih kecil, maka daya tariknya terhadap alif pun turut melemah. Akibatnya lam (ل) pun lebih kecil, sehingga ia tidak mampi membelokkan tubuhnya untuk menjalin hubungan dengan alif.36
Dzat Mutlak adalah Mahakuasa dan tidak dipengaruhi oleh apa pun. Oleh karena itu, kecondongan huruf alif bukan disebabkan oleh tindakan huruf lam (ل) melalui himmah nya kepada-Nya, melainkan bentuk turunnya alif (ا) yang lembut, sebuah respon terhadap rasa cinta yang mendalam dari lam (ل) kepada dirinya. Seakan-akan, lam (ل) menekuk kakinya kearah garis lurus alif dan membelok ke arahnya karena rasa takut akan kehilangan kesempatan atau melewatkan kesempatan ini. Sementara itu, kecondongan huruf alif kepadanya merupakan sebuah bentuk penurunan, seperti turunnya al-Haqq ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sebagaimana para ahli malam (ahl al layl) bermunajat menemui-Nya. Adapun kecondongan huruf lam (ل), adalah akibat dari suatu dorongan yang yang tidak dapat dihindari. Lam (ل) menggambarkan kecondongan para ahli ekstase (al-wajidun) maupun mereka yang diusahakan ekstase (al-mutawajidun). Hal ini terjadi karena lam (ل) merealisasikan maqam (tingkatan spiritual), hasrat dan mencintai alif (ا). Kemudian, menjadikan kecondongan alif (ا) sebagai penyatuan. Pada akhirnya, kecondongan alif (ا) ini menjadi simbol penyatuan. Hal ini yang menyebabkan bentuk ke dua huruf menjadi identik satu sama lain, sebagaimana tercermin dari penulisan lam alif (لا) yang merefleksikan kesatuan antara keduanya.37 Inilah yang dikatakan dalam serat sastra gending ‘saling mengukuhkan’, atau adanya kehendak untuk saling menyambut.
d. Rasa dan Kamil Mukamil
Aspek rasa menjadi pembahasan utama dalam serat sastra gending. Rasa ini juga menjadi pembahasan dalam tasawuf. Nilai-nilai Islam beririsan dengan kejawen dalam pembahasan rasa ini. Sultan Agung melakukan integrasi aspek mengolah “roso” dengan membersihkan kalbu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Dalam pupuh dandhanggula bait 6 versi Musium Radya Pustaka menjelaskan:
[Dene khakekat asaling gendhing|wus kanyatan esmuning Pangeran| munggen pengrasa tuduhe|lir rasaning kumumu|kang pengarsa anertandhani |tuhu tungga pinangka|jinaten puniku|paworing rasa-pengrasa| pilih kang wruh ana ing nganakken yekti|awimbuh-kawimbuhan|| Terjemahan: Sedangkan hakikat asal usul gending sudah tampak mendekati Tuhan, hanya perasaan yang menujukkan dan menandai bahwa adanya kebenaran Yang-Tunggal. Kebenaran itu adalah percampuran rasa-merasakan dengan memilih yang ada dalam kesejatian. Hal ini disebut keimanan kepada Tuhan yang dapat bertambah dan bertambah dari arah yang tidak diketahui].38
Untuk mendekati Tuhan melalui cara rasa dan merasakan. Memilih kebenaran sejati dengan mempertimbangkan rasa dan perasaan. Rasa yang dapat menandai kebenaran sejati. Kemampuan rasa dan merasakan ini berhubungan dengan tingkat keimanan seseorang. Keimanan yang semakin tinggi akan semakin bertambah kemampuan rasa dan merasakan dalam memilih yang sejati.
Untuk itu perlunya mengolah rasa, sebagaimana pesan Sultan Agung dalam serat sastra gending pupuh sinom bait 5 agar keturunan Mataram untuk sungguh-sungguh dalam melakukan olah rasa. Rasa yang halus akan memudahkan dalam menangkap petunjuk dari Tuhan. Karena rasa merupakan perangkat untuk mendekat kepada Tuhan. Pentingnya olah rasa juga perlu diterapkan dalam menjalankan sholat. Sultan Agung memandang penting unsur rasa ini ketika mendirikan sholat. Sholat yang tidak dirasakan, tidak khusuk, maka sholat yang telah dijalankan tersebut berkurang nilainya. Sebagaimana dalam serat sastra gending pupuh sinom bait 9 dinyatakan:
[Pramila jèn gending boebrah|goegoer sembahè mring Widi| batal wisesaning salat, tanpa gawe ulah gending| déné ngran tembang gending| troesireng swara lioehoeng, pamoeji asmaning dzat| swara saking osik djati| osik moelya wentaring tjipta soerasa. Terjemahan: Maka apabila irama gending rusak, maka batal penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Benar. Batal maksud tujuan dari mengerjakan sholat itu, tanpa guna berolah gending. Adapun yang disebut tembang gending, terusan dari suara luhur pemujaan asma dari Dzat, suara Dzat yang muncul dari suara gerakan hati yang sejati, bisikan mulia yang keluar dari makna yang ada dalam pikiran].<sup39
Rasa dan perasaan itu berada di hati. Ibnu Arabi mengatakan Allah yang menggerakkan rasa pangrasa tersebut. Allah bertajalli kepada kalbu-kalbu para arif di dunia. Sebenarnya yang bertajalli kepada manusia adalah hakikat-hakikat dari sifat-sifat Ilahi. Allah dapat dilihat di dunia baik melalui kalbu. Tetapi dengan diiringi peringatan dari-Nya, bahwa hamba-hamba tidak akan bisa mengetahui dan memahami Esensi-Nya atau bagaimana Dia sebenarnya dengan firman-Nya: “Dia tidak akan bisa dipahami/dicapai oleh penglihatan mata, sementara Dia bisa memahami/mencapai semua penglihatan. Dan Dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui secara langsung (QS6:103). Hak Allah memberikan hidayah-Nya menggerakkan rasa tersebut. Namun seorang hamba Allah perlu berusaha dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Agar Allah memberikan anugerah petunjuk untuk membedakan jalan yang lurus dan bukan jalan yang bengkok, jalan orang-orang yang sesat.
Allah Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya melalui tajalli-Nya kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan Dia Maha mengetahui ketidakmampuan mereka untuk menerima tajalli-Nya yang paling suci sesuai dengan yang diberikan oleh Keilaihian, karena memang sesuatu yang baharu tidak mungkin mampu memikul keindahan sesuatu yang kadim. Sama seperti Sungai yang tidak mungkin mampu memuat lautan akan menghilangkan entitasnya, baik jika lautan yang datang membanjirinya atau sungai yang datang mengalir padanya. Lautan tidak akan meninggalkan sedikitpun bekasan sungai yang membuatnya bisa dilihat atau dibedakan.40
Ilmu adalah sebuah sifat, untuk mencapainya melalui kalbu. Objek ilmu (al ma’lum) adalah perkara yang dicapai oleh kalbu, yang mengetahui al alim adalah kalbu. Kalbu ibarat cermin yang terpoles dan mengkilap. Semua bagian dari cermin itu adalah wajah (wajh) atau permukaan dan sesungguhnya tidak akan pernah berkarat. Jika suatu saat wajah itu berkarat karena kita mengotorinya. Seperti sabda rasullullah “sesungguhnya kalbu-kalbu benar-benar bisa berkarat layaknya besi yang berkarat. Dalam hadist itu disebutkan bahwa “yang bisa membuat kalbu mengkilap adalah mengingat (zikr) Allah dan membaca tilawah al Quran. Keberadaan al-quran sebagai pengingat /zikir yang mengandung hikmah (az zikr al hakim (QS 3:58). Maksud dengan karat disini bukan kabut, berupa kebodohan, kekotoran, kesedihan atau kegelisahan (takha) yang menutupi permukaan kalbu. Kalbu melekat karena hati disibukkan oleh ilmu tentang sebab-sebab sekunder (asbab) sebagai ganti ilmu tentang Allah. Keterkaitan dan kecintaan (talluq) kepada selain Allah yang menjadikan karat menutupi wajah atau permukaan kalbu. Kotoran itu menjadi penghalang untuk tajalli al Haqq kepada Kalbu.41
Kehadiran ilahi senantiasa bertajalli terus tanpa henti. Tidak terdapat hijab yang dapat menghalangi dari-Nya. Kalbu tidak menerima tajalli kehadiran ilahi karena kalbu menerima sesuatu yang lain. Sehigga ada hijab yang menghalangi dirinya dari kehadiran Ilahi. Penerimaan kepada sesuatu yang lain itu diibaratkan sebagai karat (sada’), tutup (kinn QS 41:5), gembok (qulf QS47:24), kebutaan (‘ama QS: 22:46), kotoran yang menutup (ran QS 84 14). Di dalam kalbu telah ada ilmu dan ilmu itu adalah ilmu tentang sesuatu selain Allah. Argumen yang menguatkan hal ini adalah firman Allah QS 41:5) “Dan mereka berkata: kalbu-galbu kami berada dalam tutup yang menutupi dari apa yang kau serukan” (QS:41:5)42
Kalbu-kalbu itu tertutup, tertutupi dari yang diserukan oleh Rasulullah. Namun kalbu tidak tertutup secara mutlak. Kalbu terhalang karena telah terlekat kepada selain apa yang diserukan kepadanya. Kalbu-kalbu yang tertutup itu buta untuk melihat dan memahami apa yang diserukan kepadanya. Kalbu-kalbu telah terfitrahkan untuk senantiasa bersih, berkilau, mengkilap dan jernih. Setiap kalbu yang didalamnya ada kehadiran ilahi dapat bertajalli atau menampakan Diri-Nya sebagai Mutiara yang indah, bak “batu yakut merah”. Kualitas ini adalah tajalli Dzati, yaitu kalbu pemilik musyahadah (yakin berhadapan dengan Allah), insan yang tersempurnakan, pemilik ilmu (alim) yang tiada seorang pun lebih tinggi darinya dalam hal tajalli. Kemudian di bawahnya adalah tajalli sifat-sifat, dan dibawahnya adalah tajalli perbuatan-perbuatan (af’al). Bagi mereka yang semua hal di atas bertajalli kepadanya sebagai kehadiran ilahi, bukan kehadiran yang selain ilahi. Kehadiran yang lain itu menghalangi kalbu menerima kehadiran Ilahi, mengakibatkan kalbu lalai terhadap Allah dan tersingkir dari kedekatan dengan-Nya.43
SIMPULAN
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam serat sastra gending menggunakan simbol dalam membahas tema ketuhanan dan manusia. Simbol dan istilah berasal dari tradisi lokal untuk menjelaskan nilai-nilai agama Islam. Budaya lokal adalah wadah sedangkan isi adalah nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Corak Pemikiran Serat Sastra gending
Kosepsi serat sastra gending menggunakan bahasa simbol, yang intinya adalah menjaga nilai harmoni, baik harmoni dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama. Sastra Gending menjadi simbol bagi manusia untuk menemukan Tuhan melalui batin. Sastra adalah simbol kehalusan (batin), adapun gending sarana (lahir) untuk merasakan. Antara Sastra dan gending menyatu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Manusia diibaratkan sebagai gending ketika menjalankan upaya penyatuan kepada Tuhan sang Maha Halus (batin) melalui gerakan-gerakan tertentu sampai menimbulkan keharuan dan tangis bagi yang melaksanakan upaya penyatuan itu. Rasa halus akan berhasil membawa ke alam ketuhanan dibandingkan dengan melalui pikiran. Menurut Ibnu Arabi ‘rasa dan perasaan’ itu berada di hati. Allah yang menggerakkan rasa pangrasa tersebut. Allah bertajalli kepada kalbu-kalbu para arif di dunia, yang bertajalli kepada manusia adalah hakikat-hakikat dari sifat-sifat Ilahi. Allah Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya melalui tajalli-Nya kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan Dia Maha mengetahui ketidakmampuan hamba-Nya untuk menerima tajalli-Nya, seperti Sungai yang tidak mungkin mampu memuat jika lautan yang datang membanjirinya atau sungai yang datang mengalir padanya. Lautan tak akan meninggalkan sedikit pun bekasan sungai yang membuatnya bisa dilihat atau dibedakan.
2. Integrasi dalam bidang sosial budaya.
a. Integrasi huruf Jawa dan huruf Arab. Huruf Arab maupun huruf Jawa dapat menjadi simbol pengajaran dalam rangka menuju Tuhan. Sultan Agung senang dan bersyukur karena semua pihak, baik santri maupun abangan, setuju dengan pendapat sastra Arab dan sastra Jawa pada dasarnya sama, yaitu menjadi pedoman untuk menuju Tuhan.
b. Integrasi penanggalan Jawa dan Islam. Sultan Agung merubah kalender Saka menjadi kalender Jawa yang yang disusun berdasarkan perjalanan bulan mengitari bumi atau sistem lunair (komariyah). Perhitungan kalender yang menggunakan peredaran bulan ini merupakan sistem perhitungan pada kalender hijriyah. Bagi masyarakat kejawen, perubahan tersebut terasa rumit, karena dari perhitungan tahun Saka yang berdasarkan peredaran matahari, ke tahun Jawa yang berdasarkan peredaran bulan sebagaimana kalender hijriyah. Namun Sultan Agung berhasil menyelesaikan kesulitan masyarakat kejawen, yaitu perhitungan yang dimulai dari awal tahun Saka. Dengan cara demikian Sultan Agung berhasil mengintegrasikan dua tradisi tanpa menimbulkan konflik dan berhasil menyeragamkan perhitungan tahun di antara masyarakat pesantren dan masyarakat kejawen.
c. Integrasi dalam Peradilan Surambi. Sultan Agung mengintregasikan Peradilan Surambi menggantikan Peradilan Pradata dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam. Sultan Agung menjadi pemimpin peradilan ini, yang dalam pelaksanaan peradilan dilimpahkan kepada penghulu dan beberapa orang pembantu. Penghulu dan para pembantu peradilan merupakan majelis pengadilan surambi yang diangkat oleh Sultan. Keputusan majelis pengadilan surambi merupakan masukan bagi raja untuk memutuskan perkara. Masukan dari majelis dimanfaatkan Sultan untuk menetapkan keputusan suatu perkara. Keputusan yang diambil Sultan Agung tidak bertentangan atau menyimpang dari masukan yang diberikan oleh Majelis pengadilan Surambi.
d. Perayaan sekaten. Sultan Agung menyelenggarakan kembali perayaan sekaten setelah sempat berhenti pada masa kerajaan Pajang. Kegiatan sekaten bermula dari Kasultanan Demak Bintoro, kemudian dilaksanakan kembali pada Sultan Agung. Sekaten merupakan pesta rakyat. Rakyat dari berbagai pelosok datang untuk menikmati hiburan. Rakyat menikmati hiburan dan berbelanja dalam suasana riang gembira. Pada mulanya sekaten merupakan perayaan peringatan kelahiran (Maulid) Nabi Muhammad SAW. Perayaan sekaten berfungsi sebagai sarana dakwah yang bersifat populer. Dalam perayaan sekaten ditandai bunyi gamelan, yaitu gamelan Kyai dan Nyai Sekati. Bunyi gamelan Kyai dan Nyai Sekati sebagai simbol panggilan untuk risalah shahadat, yaitu pengenalan Tauhid sendi akidah Islam. Sultan Agung menghidupkan kembali perayaan sekaten, yang artinya berhasil menyatukan dua hal, yaitu bentuk/wadah dan isi. Bentuk adalah aspek lahir (gending) dan isi adalah aspek batin (sastra). Wadah adalah budaya karya cipta manusia yang berkembang di masyarakat. Sedangkan isi adalah ajaran ketuhanan (tauhid). Ajaran Sultan Agung yang terdapat dalam serat sastra gending adalah kesatuan antara sastra dan gending. Gending adalah bentuk atau wadah, sedangkan isi adalah sastra. Tradisi perayaan sekaten merupakan wadah, sedangkan isinya adalah ajaran tauhid
3. Integrasi dalam Serat Sastra Gendhing
a. Sultan Agung menjelaskan konsepsi tauhid melalui simbol budaya yang telah ada. Dari simbol budaya tersebut di isi dengan nilai-nilai tauhid. Sultan Agung menjelaskan tentang angka satu menunjukkan isim (kata benda) dalam artian Allah Dzat-Nya satu. Dia adalah satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih. Pada waktu Tuhan bertajalli, maka Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap tidak mengetahui. Manusia yang menjadi obyek tajalli tampak dari perilakunya yang sarat dengan kualitas ketuhanan. Dalam pupuh durma bait 1 dan bait 2 Serat Sastra Gending versi Soetji Rahajoe menggunakan Wisnu dan Kresna. Antara Wisnu dan Kresna maka yang ada Wisnu saja. Pendapat ini memiliki kesamaan dengan Ibnu Arabi yang menjelaskan Dzat Mutlak dengan menggunakan dengan menggunakan huruf hijaiyah alif. Dalam dunia huruf hijaiyah disebutkan bahwa huruf alif sebagai yang tidak bisa diketahui. Sebagaimana adanya Dzat Allah tidak bisa diketahui selamanya. Penggambaran Dzat Mutlak melalui huruf alif. Bahwa huruf alif sebagai huruf yang tidak menerima pemberian harakat. Artinya sebuah huruf hijaiyah tidak bisa diketahui jika belum diberi harakat. Huruf hijaiyah dapat dibedakan dengan yang lain melalui harakat yang sematkan kepada huruf itu, baik itu dhammah, fatah ataupun kasroh. Ia bagaikan Dzat Allah yang berdiri sendiri atau tidak bisa menerima adanya pergerakan (harakah) yang bisa dipahami akal. Dia dapat diketahui melalui ciptaanNya oleh hati manusia yang terbersihkan.
b. Serat sastra gending menggunakan simbol alif untuk menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang termuat dalam hakekat Dzat. Sifat melekat pada Dzat. Dzat ada terlebih dahulu, kemudian sifat. Dzat Mutlak melalui nama, sifat dan af’al Nya yang pada akhirnya alam semesta tercipta. [Dad lawan sifat oepami| sajekti dingin Dadira| doepi woes ana sifaté| moela djamah kehanannja| awal mjang achirira| kang sifat tansah kawengkoe| marang Dad kadjatenira|| terjemahan: Seumpama Dzat dan sifat, pasti lebih dahulu Dzatnya. Keadaanya kesatuan dalam kejamakan, awal dan akhir, sifat selalu dikuasai oleh Dzatnya/ pupuh asmaradana bait 11]. Kehidupan merupakan perwujudan alif dalam kenyataan semakna dengan pendapat Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi huruf Alif juga simbol Dzat yang tersucikan, Ia tidak memiliki entitas dan tempat di dalam benda-benda jadian. Alif adalah huruf keabadian dan terkandung dalam dirinya keazalian. Alif berada pada “maqam perpaduan (maqam al jami’).
c. HA-NA-CA-RA-KA dan martabat tujuh. Serat sastra gending menjelaskan kejadian alam semesta mengikuti ajaran martabat tujuh yang dikembangkan Muhammad Ibn Fadhullah al Burhanpuri di Asia Tenggara. Sultan Agung menjelaskan martabat tujuh dengan menggunakan huruf jawa yang berjumlah dua puluh. Dua puluh huruf jawa mencerminkan tahapan penciptaan alam semesta atau asal mula kehidupan. Huruf Jawa bait pertama ‘HA-NA-CA-RA-KA’ cerminan tahap ahadiyat, ‘DA-TA-SA-WA-LA’ cerminan tahap wahdat, dan ‘PA-DA-JA-YA-NYA’ cerminan tahap wahidiyat. Ketiga tahapan ini disebut sebagai martabat batin. Sedangkan kelompok huruf Jawa terakhir yang berbunyi MA-GA-BA-TA-NGA adalah tahapan dalam martabat tujuh berikutnya, yaitu tahapan alam arwah, alam mitsal, alam ajzam, alam Insan. Empat tahapan ini merupakan martabat lahir. Martabat lahir dan martabat batin adalah simbol yang digunakan sastra gending. Representasi dari martabat batin adalah sastra, sedangkan martabat batin adalah gending. Martabat batin ini dapat disepadankan dengan istilah Ibnu Arabi, yaitu martabat Dzati (Dzat), sedangkan martabat lahir sepadan dengan martabat shuhudi (tampak nyata).
d. Tajalli Hyang Wisnu kepada Kresna. Tajalli dapat dilihat dari penggunaan simbol-simbol lokal yang terdapat dalam dunia pewayangan. Sebagaimana tersebut dalam pupuh Pangkur bait 15, Hyang Wisnu menjiwai Sri Kresna. Hyang Wisnu menitis kepada Kresna. Hyang simbol dari Adikodrati dan Kresna simbol dari manusia yang sempurna. Sang Adikodrati bertajalli kepada Kresna. Nama, sifat dan perbuatan (af’al) Sang Adikodrati menjadi aktual dalam diri Kresna. Dalam cerita pewayangan, perilaku hidup Sri Kresna selalu berada di jalan yang benar. Kresna berperilaku utama, selalu memperbaiki keselamatan mahluk hidup. Ibnu Arabi menyatunya kualitas ketuhanan kepada manusia tersebut sebagai tajalli. Ibnu Arabi menjelaskan simbol yang terdapat huruf Lam Alif. Dilihat dari segi bentuk, Alif adalah huruf yang berbadan tegak, hal ini menandakan bahwa sebagai manusia harus teguh pendirian, teguh dalam beraqidah, dan kuat dalam beriman. Alif yang masuk dalam kategori ini adalah alif yang terdapat dalam lafadz basmallah. Dalam lafadz basmallah, alif yang semula berbadan tegak kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lafdzul jalalah (lafadz allah), hal ini menunjukkan bahwa alif melebur dalam manusia adalah hadits (baru). Segala sesuatu yang hadits apabila bersanding dengan Dzat yang Qadim (Allah), maka akan lebur, fana’ dan menyatu dengan-Nya. Peleburan bisa terjadi kepada para ahli makrifat billah. Karena mereka sadar bahwa sejatinya tiada sesuatu yang wujud di dunia ini kecuali Allah.
e. Rasa dan Kamil Mukamil. Aspek rasa menjadi pembahasan utama dalam serat sastra gending. Sebagaimana rasa juga menjadi pembahasan dalam tasawuf. Nilai-nilai Islam beririsan dengan kejawen dalam pembahasan rasa ini. Sultan Agung melakukan integrasi pada aspek mengolah “roso”, dengan membersihkan kalbu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Rasa dan perasaan itu berada di hati. Ibnu Arabi mengatakan Allah yang menggerakkan rasa pangrasa tersebut. Allah bertajalli kepada kalbu-kalbu para arif di dunia. Hak Allah memberikan hidayahNya menggerakkan rasa kepada mereka yang dikehendakiNya. Namun seorang hamba Allah perlu berusaha dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Agar Allah memberikan anugerah petunjuk untuk membedakan jalan yang lurus dan bukan jalan yang bengkok , bukan jalan orang-orang yang sesat.
Kebaruan Penelitian
Sepanjang yang penulis ketahui, ada kebaruan dalam penelitian ini, yaitu kandungan isi serat sastra gending mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan menggunakan khasanah budaya lokal. Simbol dan istilah dalam serat sastra gending berasal dari budaya dan tradisi lokal digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai Islam. Budaya dan tradisi local sebagai wadah (baju) sedangkan isinya adalah nilai-nilai Islam. Sehingga dapat dikatakan ‘jubah atau baju’ yang kenakan dalam serat sastra gending menggunakan memakai tradisi dan budaya lokal sedangkan isinya adalah nilai-nilai Islam.
*Dr. Mohamad Arief Khumaidi, Peneliti.
1 Harun Hadiwijono, Konsepsi tentang Manusia Dalam Kebatinan Jawa, (Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983), 89
2 Simuh. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabahi Ranggawarsita.(Jakarta, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 201)., 6
3 Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan kesucian, (Yogyakarta: penerbit Pustaka pelajar, 1997), 337.
4 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan, terjemahan dari The Comparative Studu of Religions oleh Drs Djamannuri. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1984), XXXVI
5 Dhanu Priyo Prabowo, Pengaruh Islam dalam Karya-karya R.Ng.Ranggawarsita, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2003), 7
6 Taufiq Abdullah,dkk, Ensiklopedia, 142
7 Taufiq Abdullah, dkk, Ensiklopedia, 142
8 Damardjati Supadjar, Unsur Kefilsafatan Sosial yang terkandung dalam “serat Sastra Gending”, (Yogyakarta, Fakultas Filsafat, 1978), 8
9 Moh.Fatkhan, Sastra Gending sebagai Konsep Pemikiran dan Paham Keagamaan Sultan Agung dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1613-1645), Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin Esensia Vol.5,No.1, Januari 2004 , UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta, , 79
10 Muhammad Zainal Haq, Nasionalisme,129
11 Sudjak, Serat Sultan, 77
12 Sudjak, Serat Sultan, 77
13Suwardi Endraswara, Mistik Kejawen, Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2018), 46
14 Suwardi, Mistik Kejawen, 95-96
15 pupuh Dhandanggula padha 3
16 Pupuh Asmaradhana bait 10
17 Ibnu Arabi, , 317
18 Pupuh Pangkur bait 1 Serat sastra gending versi Soetji Rahajoe
19 Pupuh Sinom bait 6 serat sastra gending versi Soetji Rahajoe
20 Pupuh Sinom bait 6 serat sastra gending versi Soetji Rahajoe
21 pupuh durma bait 1
22 pupuh durma bait 2
23 Muhyiddin Ibn al-Arabi, Futuhat Jilid 1, 249
24 Solichin Salam, Sebuah Biografi,.25
25 Pupuh asmaradana bait 11 versi Soetji Rahajoe
26 Ibnu Arabi, Futuhat Jilid 1, 269
27 Ibnu Arabi, Futuhan jilid 1, 270
28 Asmaradana bait 9 sastra gending versi Soetji Rahajoe
29 Maharsi, Martabat tujuh dalam Serat Sastra Gendhing, dalam bukuTuhan & Alam Membaca Ulang Pantheisme-Tantrayana dlam Kakawin dan Manuskrip-Manuskrip Kuno Nusantara sebuau bunga rampai tulisan, Penerbit Suluh Pustaka dan BWCF Society, 2019, ,133)
30 Pupuh Pangkur bait 2
31 Pupuh Pangkur bait 3
32 Pupuh Pangkur bait 15
33 Pupuh Pangkur bait 8
34 Yusro Edy Nugroho, Sastra Jawa Klasik Piwulang Raja-raja Mataram, Penerbit Unnes, tanpa tahun,,174
35 Ahmad Shofi Muhyiddin, Rahasia Huruf Hijaiyyah Membaca Huruf Arabiyah dengan Kacamata Teosofi, Penerbit Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015,, 8.
36 Ibnu ‘Arabi, Futuhat Jilid 1, 307
37 Ibnu ‘Arabi, Futuhat Jilid 1, 308
38 pupuh dandhanggula bait 6 versi Musium Radya Pustaka
39 Pupuh Sinom bait 9
40 Ibnu Arabi, Futuhat Jilid 1, 317
41 Ibnu Arabi, Futuhat Jilid 2, 38
42 Ibnu Arabi, Futuhat Jilid 2, 39
43 Ibnu Arabi, Futuhat jilid 2, 39
—————————-
Daftar Pustaka
Jurnal Manassa Manuskripkoi vol 2, No.1, 2021,
Perpustakaan Nasional, p. 39. (n.d.).
Mukaddimah. (2002). No.12 Th.VIII/2002, p. 58.
Abdur Rahim Yunus. (1995). Nazariyyat Martabat Tujuh di Nizam al Mamlakah al Butaniyyah. Studia Islamika, vol 2, no., 93–110.
Abusima Nasution. (2020). Ilmu Tashawuf. Penerbit Zahir Publising.
Adrianus Sunarko. (2016). Berteologi Bagi Agama di Zaman Post-Sekuler. Jurnal Dis, 38.
Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2022). Sejarah Masuknya Kristen di Maluku. Kompas. https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/24/070000179/sejarah-masuknya-kristen-di-maluku-?page=all
AFT. Eko Susanto, Ors. Soekardji Ors. Hengky Ismuhendro Setiawan, D. P. (ed). (n.d.). Pengkajian Nilai Nilai Luhur Bu Daya Spfritual Bangsa Daerah Jawa Timur 1. Departemen Pendidikan Dan Kebudaaanan.
Akilah Mahmud. (n.d.). Insan Kamil Perspektif Ibnu Arabi. Jurnal Sulesana, Volume 9 N, 35.
Al-Ghazali. (1994). Al Asma’ AlHusna: Rahasia Nama-Nama Indah Allah. Diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dari buku The Ninety nine Names of God (Al Maqshad Al Asma fi Syarh Asma’ Allah Al Husna). Penerbit Mizan.
Ali Masrur. (n.d.). Wahdatul Wujud Abdurauf Singkel. Khazanah Jurnal Ilmu Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati, Volume 2 N, 606.
Andrea Acri, dkk. (2019). Membaca Ulang Pantheisme-Tantrayana dalam Kakawin dan Manuskrip Manuskrip Kuno Nusantara, Penyunting Mudji Sutrisno dkk. Penerbit Sulur Pustaka, dan BWCF.
Azyumardi Azra. (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia. Penerbit Prenada Media.
Badan Pusat Statistik RI. (2021). Indeks Kebahagiaan 2021. Penerbit Badan Pusat Statistik RI.
Bauer, S. W. (2016). Sejarah Dunia Abad Pertengahan, Dari Pertobatan Konstantinus sampai Perang Salib Pertama (T. H. of the M. W.-F. the C. of C. to the F. C. Tterjemahan Aloysius Prasetya A (Ed.)). Penerbit PT ELex Media Komputindo.
Buchori, Z. (2012). Mistisisme Islam Jawa: Studi Serat Sastra Gendhing Sultan Agung. Penerbit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.
Budhy Munawar Rahman dkk. (2019). Karya Lengkap Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid Society (NCMS).
Clifford Geertz. (2013). Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. Penerbit Komunitas Bambu.
Cortesao, A. (2015). Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues. Penerbit Ombak.
CST Kansil dan Christine ST Kansil. (2007). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit PT Rineka Cipta.
Damarjati Supadjar. (1994). HANA CARAKA : Pemahaman Total-Integral Makna Kehidupan. Seminar Nasional Pengkajian Makna HA-NA-CA-RA-KA ,15-16 April 1004 Dalam Rangka Dasawarsa Lembaga Javanologi, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisonal Yogyakarta Bekerjasama Dengan Lembaga Javanologi Yayasan Panunggalan Yogyakarta, 13.
Dewantara, K. H. (2013). Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, buku II. Penerbit Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Eliade, M. (2002). Sakral dan Profan. Penerbit Fajar Pustaka Baru.
F.Budi Hardiman. (2009). Menuju Masyarakat Komunikatif. Penerbit Kanisius.
Fathurahman, O. (2012). Ithaf al Dhaki, Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara. Penerbit Mizan.
Fathurahman, O., & Masyi, T. al. (1999). Menyoal Wahdatu Wujud Kasus Abduraruf Singkel di Aceh Abda 17 (Bandung).
Fatimah Purwoko. (2020). Sultan Agung Sang Pejuang dan Budayawan dalam Puncak Kekuasaan Mataram. Penerbit Sociality.
Fisher, R. (2006). Approaches to the Study of Religion (C. Peter(ed) (Ed.)). The continuum International Publisisng Grup.
Franz Magnis Suseno. (1984). Etika Jawa, Sebuah Analisa Fasafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa. Penerbit Ikapi.
Geertz, C. (2013). Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. Penerbit Komunitas Bambu.
Geertz, H. (1983). Keluarga Jawa. Penerbit Grafiti Pers.
Gerardette Philips. (2016). Melampaui Pluralisme. Penerbit Madani.
Ghazali, I. al. (2011). Ihya’ulumiddin, Jilid 1 Jakarta. Penerbit Republika.
Habermas, J. (2008). Between Naturalism and Religion Philosophical Essays. In T. by C. Cronin (Ed.), Polity Press (This Engli). Polity Press.
Hardiman, F. B. (2009). Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmoderisme Menurut Jurgen Habermas. Penerbit Kanisius.
Hermawan, S. (n.d.). Mukaddimah, Jurnal Studi Islam, No.12 Th.VIII/2002, p. 58. Jurnal Studi Islam Mukaddimah, Koptertais Dan PTAIS DIY, 53.
Hodgson, M. G. . (1974). The Venture of Islam volume two The Expansion of Islam in The Middle Periods. The University of Chicago Press.
Huda, M. Di. (2015). Peran Dukun terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa. Sekolah Tinggoi Agama Islam Negeri Kediri, 0 4.
Imam al Ghazali. (n.d.). Ihya’ulumiddin, Jilid 1. Penerbit Republika.
Imam, K. (2017). Wacana Martabat Tujuh dalam Kesusutraan Jawa-Islam. https://ganaislamika.com/wacana-martabat -tujuh-dalam kesusatraan – jawa- Islam-1.
Jajang A Rohmana. (n.d.). Tasawuf Sunda dan Warusan Islam Nusantara: Martabat Tujuh dalam Dangiding Haji Hasan Mustapa, (1852-1930). Jurnal Al Turas, Vol.XX.No., 262.
Joachim Wach. (1984). Ilmu Perbandingan Agama Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan (terjemahan dari The Comparative Studu of Religions oleh Drs Djamannuri (Ed.)). PT Raja Grafindo Persada.
Jones, P., Bradbury, L., & Boutillier, S. Le. (2016). Pengantar Teori-teori Sosial (Achmad Fedyani Saifuddin (Ed.); Edisi kedu). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kahmad, D. (2002). Sosiologi Agama. Penerbit PT Remajarosdakarya.
Kansil, C. K. dan C. S. (2007). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit PT Rineka Cipta.
Khairul Imam. (n.d.). Wacana Martabat Tujuh dalam Kesusutraan Jawa-Islam (1). https://ganaislamika.com/wacana-martabat -tujuh-dalam kesusatraan – jawa- Islam-1
Kleden, P. B. (2010). Dialektika Sekulerisasi Diskusi Habermas-ratzinger dan Tanggapan. Penerbit LAMALERA dan Penerbit LEDALERO.
Koentjaraningrat. (1985). Pengantar Ilmu Antropologi. Penerbit Aksara Baru.
Kuntowijoyo. (1991). Paradiqma Islam Interpretasi untuk Aksi. Penerbit Mizan.
lichin Salam. (1994). No TitleDrs RMP Sasrokartono Sebuah Biografi. Penerbit Yayasan Sosrokartono.
Lombard, D. (2005). Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia 2, (D. terjemahan Winarsih Partaningrat Arifin (Ed.)). Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Maharsi. (2019). Martabat tujuh dalam Serat Sastra Gendhing, dalam buku Tuhan & Alam Membaca Ulang Pantheisme-Tantrayana dlam Kakawin dan Manuskrip-Manuskrip Kuno Nusantara sebuau bunga rampai tulisan. Penerbit Suluh Pustaka dan BWCF Society.
Marwati Djoned Poesponegoro. (1984). Sejarah Nasional Indonesia III (Edisi ke-4). PN Balai Pustaka.
Masrur, A. (2003). Wahdatul Wujud Abdurauf Singkel, dalam Khazanah. Jurnal Ilmu Agama Islam, 2(3), 606.
Media Zainul Bahri. (2004). Maqamat dan Ahwal Dalam Tasawuf. Jurnal Refleksi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 6, No., 81.
Menoh, G. A. B. (2015). Agama dalam Ruang Publik Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas,. Penerbit PT Kanisius.
Moh.Ardani. (n.d.). Makna HA-NA-CA-RA-KA Tinjauan dari segi Filsafat /sufisme. , Seminar Nasional Pengkajian Makna HA-NA-CA-RA-KA, Dalam Rangka Dasawarsa Lembaga Javanologi, 2–3.
Mohtar Mas’oed dkk. (2001). Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu. Penerbit Pusat Penelitian Pembanagunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
Muhammad Irfan Riyadi. (n.d.). Manunggaling Kawulo Gusti Konsep Wahdatul Wujud dalam Genelologi Theosofi Ibn Arabi dan R RG. Ronggowarsito. In Penerbit STAIN Ponorogo Press, 2014), 30-33.
Muhammad Irfan Riyadi, M. K. G. K. W. W. dalam G. T. (2014). Ibn Arabi dan R RG. Ronggowarsito. Penerbit STAIN Ponorogo Press.
Muhyiddin Ibn al-Arabi. (2018). Al-Futuhat Al Makkiyah Risalah tentang Ma’ifah Rahasia-rahasia Sang Raja dan KerajaanNya, Jilid 2 (T. H. N. Rosyid (Ed.)). Penerbit Darut Futuhat.
Mulder, N. (1983). Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa Kelangsungan dan Perubahan Sosial.
Murder, N. (2009). Mistisime Jawa ideologi di Indonesia (M. in J. I. in I. penerjemah Noor cholis (Ed.)). Penerbit LKiS.
Naim, A. S. (2010). Serat Sastra Gendhing dalam Kajian Strukturalisme Semiotik.
Nasr, S. H. (1997). Pengetahuan dan kesucian. Penerbit Pustaka pelajar.
Nasution, A. (2020). Ilmu Tashawuf. Penerbit Zahir Publising.
Niels Mulder. (1983). Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa Kelangsungan dan Perubahan Sosial (terjemahan Alois A Nugroho dar Mysticism & Everyday Life in Contemporery Jawa (Ed.)). Penerbit Gramedia.
Niels Murder. (2009). Mistisime Jawa ideologi di Indonesia, penerjemah Noor cholis, Mysticisme in Java Ideology in Indonesia. Penerbit LKiS.
Nurcholis Madjid. (2008). Islam Doktrin & Peradaban. Penerbit PT Dian Rakyat dan Paramadina.
Oman Fathurahman. (1999). Tanbih al Masyi, Menyoal Wahdatu Wujud Kasus Abduraruf Singkel diAceh Abad 17. Penerbit Mizan.
Oman Fathurahman. (2012). Ithaf al Dhaki, Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara. Mizan.
Pongsibanne, L. K. (2017). Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama. Kaukaba Dipantara.
Prabowo, D. P. (2003). Pengaruh Islam dalam Karya-karya R.Ng. Ranggawarsita. Penerbit Narasi.
Purwadi. (2011). Kajian Filosofis Sastra &Budaya Nusantara. Penerbit Putra Bangsa.
Rahman, M. T. (2011). Glosari Teori Sosial. Penerbit Ibnu Sina Press.
Rahman, N. M. dan B. M. (1994). Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina.
Riady, A. S. (n.d.). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perpektif Clifford Geertz. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia.
Riyadi, M. I. (2014). Manunggaling Kawulo Gusti Konsep Wahdatul Wujud dalam Genelologi Theosofi Ibn Arabi dan R RG. Ronggowarsito. STAIN Ponorogo Press.
Riyadi, M. I. (2018). Manunggaling Kawulo Gusti Konsep Wahdatul Wujud dalam Genelologi Theosofi Ibn Arabi dan R RG. Ronggowarsito. Penerbit STAIN Ponorogo Press.
Rob Fisher. (2006). Approaches to the Study of Religion (P. C. (ed) (Ed.)). The continuum International Publisisng Grup.
Rohmana, J. A. (2014). Tasawuf Sunda dan Warusan Islam Nusantara: Martabat Tujuh dalam Dangiding Haji Hasan Mustapa (Vol. 2).
RPM Sastrokartono. (n.d.). Laku dan Maksudipun.
S, S. I. (2005). Konsep Tuhan, Manusia, Mistik, Dalam Berbagai Kebatinan Jawa. PT RajaGrafindo Persada.
Sachlan, R. (1974). Arti Gamelan Sekaten Menurut Versi Notosoeroto. Mawas Diri, no 1 Maret, 50.
Sangidu. (2002). Wachdatul Wujud Polemik Pemikiran Sufistik antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as Samatrani dengan Nurrudin ar-Raniri. Penerbit GAMA MEDIA.
Sangidu. (2002). Konsep Martabat Tujuh dalam At Tuchfatul–Mursalah Karya Syaikh Muhammad
Fadhlulah al Burhanpuri”, Kajian Filologis dan Analisis Resepsi. Jurnal Humaniora, Volume XIV, 7–8.
Sangidu. (2018). Sastra Sufi di Ach Sufi Literature in Aceh. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.9. No.
Sangidu. (n.d.). Sastra Sufi di Ach Sufi Literature in Aceh. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.9 No.2, 208.
Seno Harbangan Siagian. (1989). Agama-agama di Indonesia. Penerbit Satya Wacana.
Seyyed Hossein Nasr. (2018). The Essential Seyyed Hossein Nasr ( foreword by H. S. Edited William C Chittick (Ed.)). World Wisdom, Inc.
Seyyed Hossein Nasr. (2007). Pengetahuan dan Kesucian (terjemahan oleh Suharsono (Ed.)). Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Centre for International Islamic Studies.
Shonhaji. (2010). Agama : Konflik dan Integrasi Sosial (Agama Jawa dalam Perpektif Clifford Geertz,. Jurnal Al Adyan, Vol, No.1.
Siagian, S. H. (1989). Agama-agama di Indonesia. Penerbit Satya Wacana Semarang.
Simuh. (2019). Mistik Islam Kejawen Raden Ngabahi Ranggawarsita. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
Simuh. (2019). Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam. Penerbit IRCiSoD.
Solichin Salam. (1994). Drs RMP Sasrokartono Sebuah Biografi. Penerbit Yayasan Sosrokartono.
Sri Wintala Achmad. (2019). Sejarah Agama Jawa Menelusuri Kejawen sebagai Subkultur Agama Jawa. Penerbit Araska.
Sudarto, D. (1996). Metodologi Penelitian Filsafat (Cetakan pe). PT RajaGrafindo Persada.
Sudjak. (2016). Serat Sultan Agung Melacak jejak Islam Nusantara. Kelompok Penerbit CV Bildung Nusantara.
Sugono, D. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Penerbit Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.
Sukidin. (n.d.). Pemikiran Sosiologi Kontemporer. Penerbit UPT Penerbitan UNEJ.
Sunarko, A. (2016). Berteologi Bagi Agama di Zaman Post-Sekuler. Jurnal Diskursus, Volume 15, 23–44.
Supadjar, D. (1978). UNSUR-UNSUR FILSAFAT SOSIAL DALAM SERAT SASTRA GENDING. Fakultas Filsafat UGM.
Susanto, A. E., Ors, O. S., Setiawan, H. I., & Pertiwintoro. (2018). Pengkajian Nilai Nilai Luhur Bu Daya Spiritual Bangsa Daerah Jawa Timur. Departemen Pendidikan Dan Kebudaaanan.
Suteja. (2016). Tasawuf Lokal Mencai Akar Tradisi Sufisme Lokal Cirebon,. Penerbit Pangger Publising.
Sutiyono. (2010). Benturan Budaya Islam, Puritan &Sinkretis. PT Kompas Media Nusantara.
Suwardi Endraswara. (2018). Mistik Kejawen, Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa. Penerbit Narasi.
Syeikh Abdul Karim ibnu Ibrahim al Jaili. (2014). Insan Kamil, Ikhtiar Memahami Kesejatian Manusia dengan Khaliq Hingga Akhir Zaman (L. Terjemahan oleh Misbah el Majid (Ed.)). Penerbit Pustaka Hikmah Perdana.
Tago, M. Z. (2013). Agama dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geerts. Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Volume 7.
Taufiq Abdullah, dkk. (2002). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara. Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Tjandrasasmita, U. (n.d.). Arkelogi Islam Nusantara. Penerbit KPG (Kepustakaan Islam Nusantara).
Wach, J. (1984). Ilmu Perbandingan Agama Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan ( terjemahan dari T. C. S. of R. oleh D. Djamannuri. (Ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
Woodward, M. R. (2008). Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan. Penerbit LKIS.
Yusro Edy Nugroho. (174 C.E.). Sastra Jawa Klasik Piwulang Raja-raja Mataram. Penerbit Unnes.
Zaenudin. (2013). Mistisisme Islam Jawa Analisis Hermeneutika Serat Sastra Gending Sultan Agung. penerbit RaSAIL.