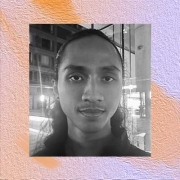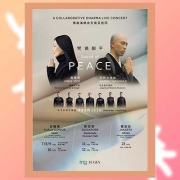Golem atau Parrhesiast
Oleh Tony Doludea
Pada akhir abad XVI di Prague, di bawah kekuasaan raja Rudolf II (1522-1612) orang-orang Yahudi saat itu sedang menghadapi penganiayaan (persecution). Penganiayaan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa orang Yahudi telah menculik dan membunuh anak-anak umat Kristen untuk dijadikan kurban dalam perayaan Hari Paskah agama mereka. Sementara jauh sebelum itu, di abad I dalam perkembangan awal agama Kristen, orang Yahudi dan penguasa Romawi melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Mereka menuduh orang Kristen melakukan kekejian yang luar biasa: flagitia, scelera dan maleficia, khususnya kanibalisme dengan cara membunuh anak-anak, meminum darah dan memakan dagingnya dalam upacara Misa, Perjamuan Kudus agama mereka.
Dalam kasus di Prague, Rabbi Judah Loew ben Bezalel (1512-1609) berusaha mengatasi penderitaan umatnya itu dengan menggunakan kekuatan magis. Rabbi Loew bersama muridnya pergi ke tepi sungai Vltava, membuat patung tanah liat dan membacakan mantra-mantra gaib Kabbalah untuk menghidupkan Golem (gumpalan) lempung tersebut. Golem itu diberi nama Yosef. Golem adalah manusia buatan yang dapat dikendalikan, namun juga dapat memberontak terhadap pembuatnya. Golem adalah seorang penolong, pendamping, pembantu dan pelindung. Golem adalah sebuah cerita rakyat di Eropa, bermula bahkan sebelum masuk pada Abad Pertengahan. Golem merupakan metafor dan simbol tentang perang, komunitas, keterasingan, harapan dan keputusasaan. Golem telah menginspirasi cerita lainnya, Faust, Frankenstein, Zombie, Pinokio, The Incredible Hulk, The Terminator, Blade Runner, Robot dan Artificial Intelligence.
Akhir-akhir ini orang sering sekali mendengar istilah persekusi (penganiayaan) di negeri ini. Bahkan tindakan penganiayaan itu sudah sangat nyata terjadi di kalangan umat beragama. Kiai Umar Basyri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung, dipukul orang gila di masjid pesantren pada Sabtu, 27 Januari 2018. Komandan Brigade Persis, Ustaz Prawoto tewas dianiaya Asep Maftuh, tetangganya di dekat rumahnya di Blok Sawah, Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung pada Kamis, 1 Februari 2018. Biksu Mulyanto Nurhalim, seorang ulama Budha di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi korban persekusi pada Senin, 5 Februari 2018. Empat orang, termasuk Pastor Prier mengalami luka-luka akibat penganiayaan dengan menggunakan parang panjang terjadi di Gereja St Lidwina, Jambon Trihanggo, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta, pada Minggu, 11 Februari 2018. Kiai Hakam Mubarok, pengasuh Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, diserang orang tak dikenal, pada Minggu, 18 Februari 2018. Tiga patung suci umat Hindu di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dirusak orang tak dikenal. Sebilah kapak tertancap di bagian kepala salah satu patung Dwarapala pada Minggu, 18 Februari 2018. Serangkaian tindakan penganiayaan tersebut telah memunculkan kecurigaan yang dapat memicu bertambahnya lagi kebencian antara umat beragama yang selama ini nampak sudah dikondisikan. Padahal yang harus segera disadari bahwa bukan salah satu umat beragama tertentu saja yang menjadi korban penganiayaan tersebut, namun semua umat beragama di Indonesia ikut serta mengalaminya.
Cherian George, seorang ahli Media dari Singapura, dalam bukunya: Pelintiran Kebencian Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi (2017) berpendapat bahwa hate spin, pelintiran kebencian yang menyebabkan penganiayaan di Indonesia itu bukanlah produk alami atau langsung dari keberagaman masyarakat, melainkan suatu yang sengaja dibuat oleh wirausahawan politik dalam upaya meraih kekuasaan. Para oportunis ini secara selektif memanfaatkan sentiment agama masyarakat dan mendorong pengekspresian kehendak massa, dalam rangka memobilisasi mereka ke arah tujuan-tujuan anti-demokratis. Pelintiran kebencian adalah penggunaan kekuatan rakyat untuk memperlemah kekuatan rakyat itu sendiri.
Menurut Cherian, pelintiran kebencian sengaja diciptakan dan digunakan sebagai strategi politik yang mengeksploitasi identitas kelompok tertentu guna memobilisasi pendukung untuk menekan lawan. Bagi Cherian tukang pelintir itu adalah wirausahawan politik yang memanipulasi emosi-emosi terdalam masyarakat. Mereka secara dingin menerapkan teknik-teknik persuasi, yaitu retorika biasa hingga bentuk terbaru dalam media sosial. Agen pelintiran kebencian ini biasanya adalah bagian dari kelompok elite -pemimpin organisasi politik atau agama, atau bahkan pejabat pemerintah-. Mereka diuntungkan dengan menyamarkan upaya mereka mencari kekuasaan di balik kedok sentimen populer berbasis agama. Para oportunis ini berusaha meraih kekuatan politik yang menggiurkan itu. Oleh sebab itu, pelintiran kebencian ini perlu dilawan, tegas Cherian, guna melestarikan pilar kembar demokrasi, yaitu kebebasan, termasuk kebebasan berbagi gagasan-gagasan provokatif; dan kesetaraan, juga kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, tanpa dihambat oleh diskriminasi atau intimidasi.
Bagi Cherian demokrasi menjadi cacat ketika mengutamakan kehendak orang banyak di atas hak individu. Demokrasi jenis ini adalah suara demokrasi minus nilai demokrasi. Memberdayakan banyak orang, tapi menutup mata terhadap ketidakadilan yang menimpa segelintir orang. Masyarakat demokratis harusnya tidak hanya tahu soal hak untuk memilih pemerintahnya saja, tapi juga paham akan syarat-syarat pokok dari kehidupan demokratis, termasuk nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut akan sulit berkembang di masyarakat yang sudah diliputi ketakutan dan kebencian terhadap “yang lain.” Dalam demokrasi yang cacat, lembaga-lembaga -keluarga, sekolah, organisasi keagamaan dan media- yang diharapkan dapat menanamkan nilai yang benar justru menanamkan kebencian dan fanatisme.
Sementara itu, Harry G. Frankfurt, dalam bukunya On Bullshit ingin menjelaskan tentang bullshit, omong kosong yang sedang terjadi di dalam budaya masyarakat kontemporer saat ini. Dalam suatu wawancara, Frankfurt menyatakan bahwa salah satu dasar budaya manusia adalah menghormati yang benar, kebenaran. Karena perbuatan yang benar (right) itu adalah selalu perbuatan yang menunjang yang baik (good). Namun Frankfurt sangat sedih dan prihatin dengan budaya masyarakat demokratis saat ini yang penuh berlimpah dengan omong kosong, bullshit.
Frankfurt membedakan antara omong kosong dengan dusta. Ketika orang jujur berbicara, ia mengatakan hanya apa yang benar. Demikian juga ketika seorang pedusta, penipu atau pembohong (liar) berbicara, ia mengatakan hanya apa yang tidak benar. Namun ia tetap memiliki kesadaran akan adanya kebenaran. Dia tahu apa yang dikatakannya itu tidak benar. Sebab ia sadar dan menghargai yang benar. Dia tahu kebenaran itu, peduli dan terikat untuk memegang teguh kepada yang benar, namun mereka dengan sengaja tidak mengatakan yang benar dan menutupinya. Penipu dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, serta menjadikannya sebagai suatu patokan penting. Penipu melalui dusta, tipu dan kebohongannya itu, dengan sengaja membawa orang lain untuk menjauh dan tersesat di dalam ketidakbenaran atau kesalahan.
Sebaliknya, menurut Frankfurt, si pengomongkosong (bullshitters) itu tidak mempedulikan, tidak menghargai dan tidak berpatokan sama sekali kepada yang benar dan yang salah. Meskipun mereka berkata yang benar dan mengatakan kebenaran. Sekalipun mereka bersikap dan bertingkah laku benar. Namun mereka sama sekali tidak tertarik dan tidak terikat kepada kebenaran, serta tidak perlu merasa tidak benar untuk segala omong kosongnya itu. Pengomongkosong tidak memperhitungkan yang benar dan yang tidak benar, sebagaimana orang jujur dan si penipu tadi memandangnya. Sebenarnya para pengomongkosong ini tidak hendak berbohong atau menipu (lie), namun mereka mengelabui (faking things). Apa yang mereka katakan, sikapi dan lakukan itu bukannya tidak benar (false), melainkan palsu (phony) dan tidak asli (not genuine).
Omong kosong itu sesuatu yang palsu, dan sesuatu yang tidak asli itu bukannya tidak benar (false) atau salah (wrong). Apa yang salah dengan omong kosong adalah bukan bentuknya, melainkan bagaimana ia dibuat (dari motif dan niat). Meskipun omong kosong dibuat tanpa mempedulikan kebenaran, tidak niscaya ia salah (wrong). Si pengomongkosong itu beromongkosong hanya untuk terpenuhinya ambisi atau keinginan kuat mereka akan sesuatu hal. Apakah itu uang, harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, kehormatan dan kemuliaan. Para pengomongkosong tertuju hanya untuk meraih apa yang diinginkannya. Bagi mereka, segala omong kosongnya itu adalah alat untuk memperalat orang lain supaya segala tujuan dan keinginannya tercapai dan terpenuhi melalui orang lain yang dikibulinya. Orang lain adalah objek demi tergenapinya keinginannya tanpa mempedulikan kemanusiaan sasamanya. Frankfurt menyatakan bahwa omongkosong itu berasal dari hanya sekadar omong-omong, karena dalam budaya dan masyarakat saat ini jika orang tidak ngomong dia tidak dapat uang.
Secara khusus, Frankfurt melihat bahwa dunia akademis pun telah menjadi pusat omong kosong. Para ahli yang terdidik dalam dunia ilmu pengetahuan melalui kemampuan perangkat pikiran dan bahasanya itu, justru memampukan mereka untuk menciptakan segala macam bentuk omong kosong, yang sulit untuk diragukan karena memiliki legitimasi akademis. Meskipun mereka itu meneliti, mengatakan, mengajarkan bahkan merasa telah menemukan kebenaran. Namun orang cerdik cendekia seperti mereka ini tidak tertarik kepada kebenaran itu sendiri. Mereka bahkan bersikap sangat congkak dan angkuh, yang membuat mereka meremehkan bahkan menolak perbedaan antara yang benar dan yang salah. Mereka terlalu percaya diri, pongah dan jumawa atas pendapat dan pengetahuan mereka sendiri, sehingga terciptalah semua omong kosong itu. Frankfurt tidak menyangkal bahwa beromong kosong itu membutuhkan imajinasi dan kreatifitas yang tinggi. Keahlian serta kecakapan seperti ini ditawarkan untuk dipelajari di berbagai perguruan tinggi.
Frankfurt menyadari bahwa hidup umat manusia saat ini berada di bawah ancaman bahaya omong kosong. Masyarakat modern ini berada dalam bahaya besar, karena telah menganggap omong kosong itu sebagai suatu hal yang sepele, biasa saja, bahkan lebih ringan daripada dusta. Omong kosong tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran atau ketidakbenaran dan kesalahan. Sekalipun orang masih tetap menganggap dusta itu sebagai suatu sifat atau perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan kebenaran. Namun pada kenyataanya, tingkat omong kosong pada saat ini makin meningkat tajam, penyebabnya adalah makin kuatnya motif pemasaran (marketing).
Masyarakat saat ini sibuk menjual atau memasarkan barang-barang, menjual program, memasarkan kebijakan politik, menjual sesamanya manusia, memasarkan apa saja yang dapat dijual. Mereka beromong kosong supaya orang membeli dan mengonsumsi apa saja yang mereka jual dan pasarkan itu. Saat ini omong kosong itu telah mewabah secara brutal dalam masyarakat dan sudah sampai pada suatu titik yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Masyarakat demokratis ini tidak menyadarinya, bahkan justru memperkuat terjadinya praktik omong kosong. Karena omong kosong itu lebih halus dan lebih berbahaya dibandingkan dusta. Maka omong kosong dianggap hal remeh dan biasa saja. Olehnya keadaan dapat berubah menjadi kacau dan tak terkendali. Sehingga kedamaian menjadi terancam serta kemajuan individu dan sosial menjadi runtuh.
Bullshitters yang diungkap oleh Frankfut itu memiliki kemiripan, kalau tidak ingin dikatakan sama dengan para pemelintir kebencian yang telah disebut oleh Cherian George di atas. Mereka ini bukan saja para elit politik, agama, pemerintah, namun juga para akademisi, seniman dan pengusaha serta media, sebagaimana telah disinggung juga oleh Cherian.
Pada Oktober-November 1983 di dalam sebuah seminar yang bertema “Discourse and Truth: The Problematization of the Parrhesia”, di Universitas California di Berkeley, Michel Foucault membahas persoalan tentang Parrhesia. Parrhesia ini merupakan hal yang mendasar dan menjadi ciri khas utama demokrasi Athena, di mana setiap warga menikmati demokrasi itu.
Demokrasi Yunani ini dibentuk oleh semua warga (politeia) berdasarkan jaminan atas: (1) hak yang sama di hadapan hukum (isonomia), yaitu memiliki hak yang sama dalam pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan (kratein). (2) hak yang sama untuk berbicara (isogoria). Isonomia dan Isogoria diakui secara formal oleh konstitusi. Namun parrhesia tidak memiliki dasar institusional maupun konstitusional dalam demokrasi.
Parrhesia adalah (1) tindakan berbicara bebas tentang kebenaran secara polos dan jujur, (2) melakukan kritik terhadap diri sendiri dan orang lain, untuk menolong dan mengambangkan diri sendiri dan orang lain, meskipun mengandung bahaya atas dirinya. Parrhesia terwujud dalam bentuk mengajar, berkhotbah, dialog atau diskusi yang bersemangat dan teladan hidup, yang akan menghantar orang untuk dapat mengubah hidupnya sendiri. Seorang parrhesiast adalah pribadi yang memiliki kualitas kebajikan moral. Seorang parrhesiast sangat penting dan dibutuhkan bagi kehidupan politik dalam sebuah negara.
Bekaitan dengan itu, Isokrates (436-338 SM), seorang orator terkenal saat itu, mengingatkan supaya orang-orang Athena untuk tidak mendengarkan para demagog. Tetapi mau mendengarkan para parrhesiast. Demagog adalah pemimpin/penghasut dalam sebuah pemerintahan/negara demokrasi, yang mendapatkan kekuasaan/dukungan dengan cara mengeksploitasi prasangka buruk, kebencian, kefanatikan dan kebodohan rakyat. Sebaliknya, para orator yang baik dan terhormat (parrhesiast) sanggup dan berani manantang rakyat. Mereka mampu mengritik, mendidik dan mengubah kehendak rakyat menjadi kepentingan bersama.
Foucault mengingatkan bahwa parrhesia adalah proses penguasaan diri yang menuntut usaha dan pengurbanan. Karena seorang parrhesiast akan menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Seorang parrhesiast adalah orang yang merupakan bagian dari suatu masyarakat dan yang melaksanakan perannya secara tepat di dalamnya.
George Carlin (1937-2008) seorang stand-up comedian, menyindir bahwa hampir di setiap lini kehidupan bermasyarakat saat ini, semuanya telah sungguh-sungguh full of shit, -dalam istilah Cherian- penuh pelintiran kebencian. Pelintiran kebencian tidak dapat dimusnahkan dengan membuat Golem. Golem masa kini dapat berupa kelompok ini-komunitas itu, jamaah ini-majelis itu, laskar ini-fornt itu, organisasi ini-forum itu, lsm ini-komisi itu, satgas ini, dll. Namun, seperti yang diusulkan oleh Cherian, pelintiran kebencian dapat disingkirkan dari arus utama politik dengan menerapkan pluralisme tegas (asseritive pluralism), yaitu menggabungkan mekanisme hukum, kepemimpinan politik, tindakan warga dan kerja sama media.
Menurut Cherian, hukum harus melarang penyalahgunaan kebebasan berekspresi untuk tujuan-tujuan diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Dan di sisi lain, hukum juga tidak boleh melayani ledakan ketersinggungan yang oportunistik dengan cara membatasi apa pun yang dianggap menyinggung. Demokrasi harus melindungi ruang publik untuk mewadahi perdebatan yang bermutu di antara pandangan-pandangan yang bertolak belakang –termasuk nilai-nilai agama– dan pada saat yang sama menjamin bahwa individu dari iman apa pun dapat menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, secara setara dan tanpa rasa takut. Nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi terganggu bukan saja ketika negara lalai menjalankan tanggungjawabnya menyediakan rasa aman bagi komunitas-komunitas paling rentan, namun juga saat ia secara serampangan melakukan intervensi guna melindungi perasaan kelompok-kelompok yang meneriakkan kemarahan terhadap hal-hal yang dianggap sebagai penghinaan.
Kebinekaan bagi manusia seperti halnya air, api, udara, tanah, dan angkasa, merupakan bahan baku yang mendasar bagi kehidupannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang menghadapi ancaman dan tantangan yang luar biasa hebat pada kebinekaannya. Namun ancaman dan tantangan tersebut sekaligus merupakan peluang besar yang sangat berharga untuk membuktikan bahwa kebinekaan itu harum dan nikmat sekali. Bahkan kemewahan nilai luhur kebinekaan umat manusia ini patut dirayakan dan terus diasuh. Jangan kapok menjadi warga negara Indonesia. Antagonisme dan paradoks ini merupakan kenyataan alamiah yang selalu akan menemani manusia. Tinggal orang memutuskan pilihan antara Golem atau Parrhesiast.
————————–
Kepustakaan
Beoang, Konrad Kebung. Michel Foucault: Parrhesia dan Persoalan
Mengenai Etika. Penerbit Obor, Jakarta, 1997.
Cairns, Earle E. Christianity Through the Centuries: A History of the
Christian Church . Zondervan, Grand Rapids, 1996.
Frankfurt, Harry G. On Bullshit. Princeton University Press, Princeton,
2005.
George, Cherian. Pelintiran Kebencian Rekayasa Ketersinggungan
Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, Jakarta, 2017.
Idel, Mosche. Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the
Artificial Anthropoid. State University of New York Press, Albany, 1990.
Salfellner, Harald. The Prague Golem. Jewish Stories of the Ghetto.
Vitalis, Prague, 2016.
*Penulis adalah seorang peneliti di Abdurrachman Wahid Center UI