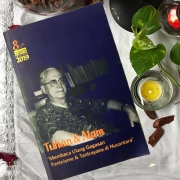“Chocolat” dan Cinta yang Dikomodifikasi
Oleh Purnawan Andra*
Di tengah malam Valentine 14 Februari lalu, saya menonton kembali “Chocolat” karya Lasse Hallström yang diputar oleh HBO. Film produksi tahun 2000 itu pernah meraih sejumlah nominasi Oscar dan Golden Globe tahun 2001, termasuk kategori Film Terbaik, Aktris Terbaik, Aktris Pendukung Terbaik, dan Naskah Skenario Terbaik.

Dibintangi Juliette Binoche sebagai Vianne Rocher, Johnny Depp sebagai Roux, Alfred Molina sebagai Comte de Reynaud, serta Judi Dench sebagai Armande, film ini bertumpu pada ketegangan psikologis dan sosial, bukan ledakan dramatik. Konfliknya sunyi, tapi tajam. Meskipun demikian, film ini bergenre drama romantis dengan visual hangat, penuh warna cokelat yang menggoda, musiknya lembut, dan suasananya intim.
Latar ceritanya sebuah desa kecil di Prancis tahun 1959. Warganya religius, tertib, dan memegang tradisi dengan disiplin. Struktur sosialnya rapi seperti rak buku yang tak pernah digeser. Ketertiban menjadi nilai utama.
Dalam suasana seperti itu, Vianne datang sebagai pendatang bersama putrinya dan membuka toko cokelat tepat saat masa Prapaskah, periode berpantang. Tindakannya ini dianggap provokatif. Dalam hal ini, cokelat bukan sekadar gula dan kakao, tapi menjadi simbol godaan yang menantang moral kolektif.

(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Namun Vianne tidak sekadar menjual produk. Ia membaca kebutuhan emosional setiap pelanggannya. Toko kecil itu perlahan menjadi ruang aman bagi perempuan yang terjebak dalam relasi penuh kekerasan dengan pasangannya, bagi lansia yang kesepian, bagi mereka yang tidak sepenuhnya diterima oleh desa. Cokelat menjadi medium percakapan dan pemulihan. Inilah yang membuat film tersebut relevan ketika dibandingkan dengan konteks Valentine di Indonesia hari ini.

(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Perbandingan
Setiap Februari, Valentine hadir dengan pola yang mudah ditebak. Diskon restoran, paket cokelat berbentuk hati, buket bunga, unggahan foto berdua, hingga promosi marketplace yang agresif. Di kota-kota besar Indonesia, pusat perbelanjaan mengusung tema romantis sejak awal bulan.
Di sisi lain, sebagian sekolah dan lembaga pendidikan justru melarang perayaan Valentine karena dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya atau agama. Di sini kita bisa melihat dua respons sekaligus: komersialisasi dan resistensi moral.

(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Di titik ini, perbandingan dengan “Chocolat” menjadi menarik. Dalam film, cokelat dipandang sebagai ancaman moral oleh Comte de Reynaud. Ia takut kenikmatan kecil itu akan merusak disiplin sosial.
Di Indonesia, Valentine sering dipersoalkan dalam kerangka serupa. Ada kekhawatiran bahwa ia membawa budaya asing, mendorong pergaulan bebas, atau menggeser nilai tradisional. Moralitas dan konsumsi berjalan berdampingan dalam ketegangan.
Namun ada perbedaan penting. Di desa dalam “Chocolat”, yang ditolak adalah kenikmatan sebagai bentuk kebebasan personal. Di Indonesia hari ini, penolakan terhadap Valentine kerap berjalan seiring dengan penerimaan terhadap industri konsumsi yang sama. Diskon tetap ramai, pusat belanja tetap penuh. Artinya, yang dipersoalkan bukan sekadar komoditasnya, tetapi maknanya. Ada tarik-menarik antara nilai budaya, agama, dan logika pasar.
Ekonomi Afeksi
Konsep ekonomi afeksi membantu menjelaskan fenomena ini. Sosiolog seperti Eva Illouz menunjukkan bahwa kapitalisme modern tidak hanya menjual barang, tetapi juga pengalaman emosional. Cinta dipaketkan, dipasarkan, dan distandardisasi.
Di Indonesia, media sosial memperkuat pola ini. Linimasa dipenuhi unggahan kejutan romantis, hadiah mahal, dan dekorasi makan malam. Perasaan menjadi tontonan publik.
Bandingkan dengan toko Vianne. Ia tidak menciptakan standar romantisme. Ia tidak menuntut pelanggannya membeli dalam jumlah tertentu agar dianggap pantas. Ia mendengarkan.

(sumber:imdb.com)
Dalam istilah Pierre Bourdieu, yang ia bangun bukan sekadar pertukaran ekonomi, tetapi modal sosial. Relasi, kepercayaan, dan rasa saling memahami menjadi nilai utama. Cokelat menjadi sarana memperluas jaringan empati, bukan mempertebal gengsi.
Di Indonesia, Valentine sering kali bekerja sebaliknya. Nilai perasaan kerap diukur melalui simbol yang terlihat. Semakin mahal hadiah, semakin dianggap serius.
Generasi muda yang kondisi ekonominya belum mapan bisa merasakan tekanan. Fenomena penggunaan paylater untuk membeli hadiah bukan sekadar anekdot. Ia mencerminkan bagaimana cinta masuk dalam mekanisme konsumsi yang kompetitif. Relasi menjadi panggung pembuktian.
Dalam film, konflik berkembang melalui gosip dan tekanan sosial. Di Indonesia, tekanan itu hadir dalam bentuk digital. Algoritma media sosial memberi visibilitas lebih besar pada konten yang dramatis dan visual.
Romantisme yang sederhana kalah oleh kejutan spektakuler. Cinta sebagai praktik sehari-hari menjadi kurang menarik dibanding cinta sebagai konten. Jika dalam desa kecil tekanan datang dari tatapan tetangga, hari ini ia datang dari ribuan mata virtual.
Inklusi Sosial
Dimensi kedua yang penting adalah inklusi sosial. Valentine di Indonesia hampir selalu diasosiasikan dengan pasangan romantis. Padahal cinta memiliki banyak bentuk. Dalam masyarakat yang semakin urban dan individualistik, kesepian menjadi isu nyata. Namun Valentine jarang memberi ruang bagi persahabatan, solidaritas komunitas, atau kasih keluarga sebagai tema utama. Ia lebih sering menjadi panggung relasi dua orang.
Di “Chocolat”, toko Vianne justru menjadi ruang inklusif. Ia menerima siapa pun tanpa syarat. Perempuan yang mengalami kekerasan menemukan dukungan. Armande, lansia yang hubungannya renggang dengan keluarganya, menemukan kebahagiaan kecil. Bahkan Roux, pendatang nomaden yang dicurigai, mendapat tempat. Cokelat memperluas lingkaran sosial. Ia menghubungkan yang berbeda, menautkan yang tak sama.


(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Jika ditarik ke Indonesia, pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: siapa yang merasa diwakili dalam Valentine? Mereka yang tidak memiliki pasangan sering berada di pinggir narasi. Bahkan dalam wacana publik, lajang kerap diasosiasikan dengan kekurangan.
Padahal status relasi tidak identik dengan kualitas hidup. Dalam perspektif Anthony Giddens, relasi modern bersifat refleksif dan dinegosiasikan, bukan semata-mata mengikuti pola tradisional. Namun representasi Valentine cenderung menampilkan pola yang homogen.
Ironisnya, Indonesia adalah masyarakat dengan budaya komunal yang kuat. Gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas sering dibanggakan. Namun dalam praktik Valentine, cinta dipersempit menjadi perayaan privat dua individu. Dimensi sosialnya mengecil. Ia menjadi ritual konsumsi, bukan peristiwa kebersamaan.
Di sini perbandingan dengan “Chocolat” semakin kontras. Film tersebut menunjukkan bahwa kenikmatan kecil dapat menjadi pintu masuk perubahan sosial. Cokelat membuka dialog lintas generasi dan kelas. Ia tidak berhenti pada romantisme, tetapi menyentuh struktur relasi dalam komunitas. Sementara Valentine di Indonesia lebih sering berhenti pada simbol dan transaksi.


(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Kesadaran Kritis
Tentu bukan berarti Valentine harus ditolak atau dirayakan secara seragam. Yang penting adalah kesadaran kritis atas cara kita memaknainya. Apakah cokelat menjadi alat untuk membangun percakapan yang jujur, atau sekadar bukti bahwa kita mampu membeli? Apakah ia memperluas lingkaran empati, atau justru mempertegas batas siapa yang dianggap “lengkap” dan siapa yang tidak?
“Chocolat” menawarkan gambaran bahwa manis bisa menjadi radikal ketika ia membuka ruang bagi yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, Valentine bisa saja menjadi momen refleksi kolektif tentang bagaimana cinta dipraktikkan di tengah tekanan moral dan pasar. Ia bisa menjadi kesempatan untuk merayakan berbagai bentuk kasih, bukan hanya yang romantis, fotogenik dan instagramable.

(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Pada akhirnya, perbandingan ini membawa kita pada satu simpul. Di desa kecil Prancis tahun 1959, cokelat dipandang sebagai ancaman karena ia membebaskan individu dari ketertiban yang kaku. Di Indonesia abad ke-21, cokelat Valentine justru sering menjerat individu dalam standar konsumsi dan representasi. Film itu mengajak kita melihat bahwa yang menentukan bukan bendanya, melainkan relasi yang dibangunnya.

(sumber: Youtube.com/Movieclips)
Jika cokelat menjadi jembatan percakapan, ia memperkaya ruang sosial. Jika ia menjadi alat ukur nilai diri, ia mempersempitnya. Di antara diskon restoran dan larangan moral, mungkin yang lebih penting adalah pertanyaan sederhana: cinta macam apa yang sedang kita pelihara setiap Februari?
—-
*Purnawan Andra, penonton film dan penyuka minuman cokelat yang kadang merasa dirinya adalah seorang yang romantis.