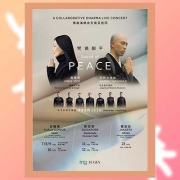Masyarakat, performance art dan Dunia Performatif
Oleh Purnawan Andra*
Belakangan ini, semakin sulit membedakan antara pertunjukan seni (performance art) dan kehidupan sehari-hari. Bukan karena seni semakin hidup di tengah masyarakat, melainkan karena kehidupan sosial itu sendiri bergerak seperti sebuah pertunjukan.
Sikap, emosi, kepedulian, bahkan penderitaan, hadir di ruang publik sebagai sesuatu yang dipamerkan, dinilai, dan segera digantikan oleh peristiwa lain. Dalam situasi ini, performance art bukan sekadar praktik kesenian yang eksperimental atau “aneh”, melainkan sebuah cara membaca dunia yang kian performatif.
Merespon Jaman
Afrizal Malna dalam bukunya Performance Art (dan Medan Pasca-Seni) (2023) menjelaskan bahwa performance art sejak awal memang tidak dimaksudkan sebagai tontonan estetis yang rapi. Ia tidak mengejar keindahan, harmoni, atau dramaturgi seperti yang biasa kita temukan dalam tari, teater, atau musik di gedung pertunjukan.
Performance art justru melepaskan diri dari logika estetika yang mapan. Tubuh tidak diperlakukan sebagai objek indah, melainkan sebagai medium pengalaman. Di dalamnya, tubuh, bahasa, ruang, waktu, teknologi, sejarah, bahkan luka sosial bertemu dalam satu peristiwa yang sering kali tidak nyaman.
Karena itulah performance art sejak awal dekat dengan dunia keseharian. Ia tidak berdiri di luar kehidupan, melainkan menyerap realitas apa adanya. Ruang publik bisa menjadi panggung, tubuh sehari-hari menjadi material, dan peristiwa sosial menjadi sumber utama. Dalam pengertian ini, performance art bukan hanya tentang seni, tetapi tentang cara manusia memahami dan merespons jamannya.
Di Indonesia, performance art tumbuh dalam konteks yang khas. Ia berkelindan dengan seni rupa, teater, dan situasi politik. Aksi-aksi seni di ruang publik pada masa reformasi—di Yogyakarta, Bandung, Jakarta—memperlihatkan bagaimana tubuh digunakan sebagai alat protes, bukan sebagai objek tontonan.
Performance art menjadi bahasa visual dan gestural untuk menyampaikan kritik ketika saluran politik formal macet. Seni tidak lagi berdiri sebagai hiburan, tetapi sebagai sikap.
Perkembangan ini semakin diperkaya oleh praktik lintas budaya yang dilakukan seniman seperti Sardono W. Kusumo, Didik Nini Thowok, atau Slamet Gundono. Tubuh, identitas, tradisi, dan modernitas tidak diperlakukan sebagai kategori tetap, tetapi sebagai sesuatu yang cair dan terus dinegosiasikan. Performance art di sini bukan soal gaya, melainkan soal cara membaca relasi manusia dengan tubuhnya, lingkungannya, dan sejarahnya.
Namun, memasuki era digital—terutama sejak pandemi Covid-19—terjadi pergeseran besar. Kehidupan sehari-hari berpindah ke ruang layar. Kehadiran tubuh digantikan oleh data, gambar, dan rekaman. Pertunjukan tidak lagi harus terjadi sebagai peristiwa fisik. Ia bisa hadir sebagai peristiwa media. Di titik ini, performance art mengalami negosiasi baru dengan teknologi. Batas antara seni, media, dan kehidupan sosial menjadi semakin kabur.
Kehidupan Sosial
Yang menarik, justru pada saat yang sama, kehidupan sosial masyarakat luas juga bergerak semakin performatif. Media sosial menciptakan panggung yang tidak pernah tutup. Semua orang menjadi penampil.
Kepedulian, kemarahan, solidaritas, bahkan duka, hadir sebagai ekspresi yang ditujukan untuk dilihat. Dalam konteks ini, apa yang sebelumnya menjadi strategi kritis dalam performance art—menjadikan tubuh dan pengalaman sebagai peristiwa—berbalik menjadi gejala sosial yang problematis.
Kepedulian sosial, misalnya, sering kali berhenti pada tampilan. Ketika terjadi bencana atau ketidakadilan, respons publik muncul cepat dan serentak. Unggahan solidaritas menyebar luas.
Namun, setelah perhatian bergeser, persoalan jarang diikuti secara serius. Kerja jangka panjang—pendampingan korban, pengawalan kebijakan, perawatan fasilitas—tidak sebanding dengan riuhnya ekspresi awal. Kepedulian menjadi singkat, dangkal, dan mudah digantikan isu lain.
Dalam konteks ini, kehidupan sosial kita justru menyerupai performance art versi paling dangkal yang penuh gestur, tetapi minim refleksi. Padahal, dalam praktik performance art yang kritis, gestur selalu diikuti oleh pengalaman, keterlibatan, dan risiko. Tubuh seniman hadir bukan untuk sekadar dilihat, tetapi untuk mengalami dan mengganggu kenyamanan penonton.
Logika performatif ini juga sangat terasa dalam praktik politik. Banyak tindakan politik hari ini lebih menyerupai pertunjukan simbolik daripada kerja yang sungguh-sungguh.
Kehadiran pejabat di lokasi bencana, pernyataan empati di hadapan kamera, atau unggahan keprihatinan sering kali berfungsi sebagai penanda moral, bukan sebagai awal perubahan kebijakan. Politik tampil, tetapi tidak bergerak jauh.
Masalahnya bukan pada simbol itu sendiri, melainkan ketika simbol menjadi tujuan akhir. Politik menjadi aman secara citra, tetapi miskin risiko. Keputusan sulit ditunda, persoalan struktural dibiarkan, sementara publik disuguhi kesan bahwa negara hadir. Dalam kondisi seperti ini, politik tidak lagi menjadi ruang penyelesaian masalah, tetapi panggung legitimasi.
Aktivisme sosial pun menghadapi dilema serupa. Banyak gerakan terjebak pada ritme reaktif: marah bersama, bersedih bersama, lalu berpindah isu. Ekspresi menjadi lebih penting daripada proses.
Padahal, perubahan sosial membutuhkan kerja yang pelan, konsisten, dan sering kali tidak menarik perhatian. Aktivisme yang terlalu performatif mudah melelahkan dan kehilangan arah.
Perbedaan
Di sinilah perbedaan penting antara performance art sebagai praktik kesadaran dan performance sosial sebagai gejala krisis. Performance art, dalam pengertian yang kritis, justru mengajak kita berhenti sejenak, merasakan, dan berpikir ulang.
Ia bekerja di “ruang antara”: antara peristiwa dan ingatan, antara tubuh dan lingkungan, antara pengalaman personal dan kesadaran kolektif. Ia memproduksi pengetahuan bukan lewat data statistik, tetapi lewat pengalaman yang dialami dan dibagikan.
Tubuh dalam performance art bukan tubuh yang dipamerkan, melainkan tubuh yang “menjadi”: menjadi ruang temu dengan yang lain, menjadi alat untuk memahami dunia.
Dalam pengertian ini, performance art mengajarkan cara hadir yang berbeda. Hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk terlibat. Bukan untuk mengisi linimasa, tetapi untuk membuka makna.
Sayangnya, dalam kehidupan sosial hari ini, kehadiran sering kehilangan kedalaman itu. Penderitaan orang lain mudah berubah menjadi latar cerita. Kemiskinan, bencana, dan ketidakadilan ditampilkan sebagai kisah menyentuh, tetapi jarang dibaca sebagai akibat dari struktur yang timpang. Konten bantuan sosial, misalnya, lebih menonjolkan siapa yang memberi daripada mengapa bantuan itu diperlukan. Yang hilang adalah konteks.
Di titik ini, kehidupan sosial kita justru menjadi pertunjukan yang lebih problematis daripada performance art itu sendiri. Jika performance art sering dianggap mengganggu dan tidak nyaman, maka pertunjukan sosial hari ini justru nyaman dan menenangkan. Ia memberi ilusi bahwa kita telah peduli, telah berpihak, telah melakukan sesuatu, padahal perubahan yang nyata belum terjadi.
Kritik pada Tampilan
Dengan membaca masyarakat sebagai performance bukan berarti menolak ekspresi atau teknologi. Yang perlu dikritik adalah cara kita berhenti pada tampilan.
Performance art, dalam sejarahnya, selalu berusaha melampaui tontonan. Ia mengganggu, memaksa berpikir, dan membuka pertanyaan. Sebaliknya, kehidupan sosial yang terlalu performatif justru menutup pertanyaan dengan kepuasan semu.
Mungkin di sinilah pelajaran penting dari performance art bagi kehidupan sosial kita hari ini. Bukan soal meniru bentuknya, tetapi menyerap etosnya. Yaitu keberanian untuk hadir secara utuh, kesediaan untuk mengalami, dan kemauan untuk tinggal lebih lama pada persoalan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh pertunjukan, sikap semacam ini justru terasa radikal.
Di tengah riuhnya panggung sosial dan politik, performance art mengingatkan bahwa tidak semua yang penting harus terlihat, dan tidak semua yang terlihat sungguh penting.
Kepedulian yang paling bermakna sering lahir dari kerja yang tidak ramai, tidak estetis, dan tidak mudah dikonsumsi. Dari situlah pengetahuan, kesadaran, dan perubahan pelan-pelan dibangun—bukan sebagai pertunjukan, tetapi sebagai cara hidup bersama.
—-
*Purnawan Andra, penerima fellowship Humanities & Social Science di Universiti Sains Malaysia