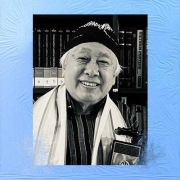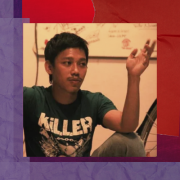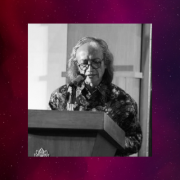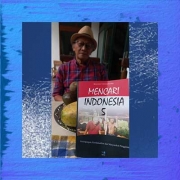Wisata Bencana: Ontologi Penderitaan di Era Tontonan
Oleh: Gus Nas Jogja*
Selamat Datang di Era Nir Empati
Di bawah langit Sumatera yang legam oleh mendung yang belum tuntas, air bah datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penagih utang atas keserakahan hutan yang digunduli. Namun, di antara isak tangis warga yang kehilangan ternak dan atap, muncul sebuah fenomena yang lebih “ajaib” daripada air yang membelah daratan: rombongan pejabat dengan sepatu bot mengkilap—yang tampaknya lebih mahal dari harga satu hektar sawah yang hancur—melangkah hati-hati di atas lumpur demi sebuah sudut pandang kamera yang presisi.
Ini adalah perayaan “Wisata Bencana”. Sebuah panggung di mana penderitaan diubah menjadi komoditas visual. Di sini, empati tidak lagi diukur dari berapa ton beras yang turun, melainkan dari berapa jumlah likes dan engagement pada unggahan Instagram sang pejabat yang sedang menatap nanar ke arah sungai (tentu saja dengan filter moody agar terlihat melankolis).
Estetika yang Mengerikan (The Sublime)
Secara filosofis, ketertarikan kita pada bencana berakar pada konsep The Sublime (Yang Maha Indah sekaligus Mengerikan) yang digagas oleh Edmund Burke. Burke berpendapat bahwa rasa sakit dan bahaya dapat menghasilkan kesenangan jika kita berada pada jarak yang aman [1]. Saat para pejabat berdiri di atas tanggul yang kokoh sambil menonton warga yang berjibaku dengan lumpur, mereka sedang menikmati sublime tersebut.
Penderitaan orang lain menjadi “pemandangan” yang menggetarkan eksistensi, namun karena mereka memiliki “jarak” (baik jarak fisik maupun jarak kelas sosial), bencana tersebut berubah menjadi hiburan intelektual dan materi kampanye. Immanuel Kant menambahkan bahwa sublime membuat kita menyadari keterbatasan fisik kita sekaligus keagungan akal budi kita [2]. Ironisnya, di Sumatera, “akal budi” ini sering kali absen, digantikan oleh naluri purba untuk mencari popularitas di atas puing-puing rumah rakyat.
Masyarakat Tontonan dan Matinya Empati
Guy Debord dalam The Society of the Spectacle mengingatkan bahwa dalam masyarakat modern, segala sesuatu yang dulunya dihidupi secara langsung kini telah bergeser menjadi representasi [3]. Bencana banjir bandang tidak lagi dianggap sebagai krisis kemanusiaan yang mendesak, melainkan sebagai “konten kreatif”.
Mari kita bayangkan sebuah anekdot satir: Seorang pejabat hampir terpeleset ke dalam arus banjir karena terlalu sibuk mencari sinyal 4G untuk melakukan Live Streaming. Baginya, banjir belum benar-benar terjadi jika belum di-tag ke akun resmi kementerian. Ia lebih khawatir pada ring light yang basah daripada warga yang kedinginan. Ini adalah puncak dari apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai Simulakra: citra tentang kepedulian telah menjadi lebih nyata daripada kepedulian itu sendiri [4]. Sang pejabat tidak hadir untuk membantu; ia hadir untuk terlihat membantu.
Banalitas Kejahatan dalam Bentuk Konten
Hannah Arendt pernah bicara soal “Banalitas Kejahatan” (The Banality of Evil). Kejahatan tidak selalu berupa rencana jahat raksasa, tapi sering kali berupa ketidakmampuan untuk berpikir dari sudut pandang orang lain [5]. Ketika seorang pejabat menggunakan latar belakang rumah hancur untuk membuat konten “A Day in My Life: Meninjau Banjir”, ia sedang melakukan kejahatan banal. Ia tidak jahat karena ia ingin warga menderita; ia jahat karena ia menganggap penderitaan itu hanyalah latar belakang artistik bagi narasi kepahlawanannya yang palsu.
Secara spiritual, ini adalah pengkhianatan terhadap khidmah (pelayanan). Dalam tradisi sufisme, membantu orang yang tertimpa musibah adalah cara untuk melenyapkan ego (fana). Namun, dalam wisata bencana pejabat, musibah justru menjadi ajang untuk mempertebal ego (isbat).
Menuju Etika Kehadiran
Jika kita ingin memulihkan makna kemanusiaan dari lumpur wisata bencana ini, kita harus kembali pada pemikiran Emmanuel Levinas tentang “Wajah” (The Face). Bagi Levinas, kehadiran orang lain yang menderita adalah perintah etis yang tak terbantahkan: “Jangan membunuh, jangan membiarkan mati” [6]. Menjadikan wajah-wajah kuyup pengungsi sebagai objek konten adalah bentuk pembunuhan karakter dan martabat.
Bencana di Sumatera bukanlah latar film pendek. Ia adalah luka yang menganga. Pejabat yang hadir tanpa solusi nyata, hanya membawa kamera dan janji manis sesaat, tak ubahnya seperti turis yang mengunjungi kebun binatang—hanya saja, “hewan” yang mereka tonton adalah saudara sebangsanya sendiri yang sedang sekarat.
Patologi Digital: Narsisme di Atas Puing
Secara psikologis, kehadiran pejabat di lokasi banjir bandang Sumatera dengan tim dokumentasi lengkap merupakan manifestasi dari Narsisme Komunal. Dalam psikologi sosial, ini adalah kondisi di mana individu mempromosikan diri sebagai sosok yang paling empatik dan berjasa demi mendapatkan validasi sosial [7]. Namun, literasi digital yang dangkal membuat mereka terjebak dalam “Performative Activism”.
Di sini, lensa kamera bukan lagi alat untuk merekam fakta, melainkan alat untuk mengonstruksi realitas. Secara deskriptif, kita melihat bagaimana sebuah sudut pengambilan gambar (low angle) digunakan untuk membuat sang pejabat tampak heroik di tengah genangan air, sementara di belakang layar, asisten sibuk memegangi payung agar riasan sang tokoh tidak luntur. Ini adalah distorsi kognitif; mereka mulai mempercayai bahwa “unggahan tentang bantuan” sama nilainya dengan “bantuan itu sendiri”.
Lensa Deskriptif: Estetika Penderitaan
Mari kita bedah secara fenomenologis. Literasi digital yang buruk mengubah empati menjadi eksploitasi visual. Dalam jurnalisme warga dan konten pejabat, sering kali terjadi apa yang disebut “Poverty Porn” (Pornografi Kemiskinan).
1. Framing Kontras: Kamera menangkap tangan keriput seorang nenek yang menggenggam tangan halus sang pejabat. Secara visual, ini adalah narasi “Penyelamat dan Yang Diselamatkan”.
2. Komodifikasi Air Mata: Zoom pada wajah korban yang menangis menjadi thumbnail yang memikat klik.
3. Saturasi Warna: Penggunaan filter warna yang sendu (desaturated) untuk menciptakan drama buatan, mengaburkan fakta bahwa yang dibutuhkan warga adalah ekskavator, bukan filter sinematik.
Satir Para Pemuja Algoritma
Bayangkan sebuah skenario di posko pengungsian: Seorang pejabat menolak memberikan sambutan sebelum lighting dari tim kreatifnya terpasang sempurna. Ia meminta seorang ibu yang rumahnya hanyut untuk “mengulang kembali” adegan menerima bantuan karena saat pertama kali, wajah sang pejabat tertutup bayangan pohon.
Ini adalah bentuk Disosiasi Psikologis. Sang pejabat mengalami keterputusan hubungan dengan realitas di depannya karena ia lebih hidup dalam realitas digitalnya. Baginya, banjir adalah “proyek konten” dengan KPI berupa jumlah share. Jika banjir surut terlalu cepat sebelum ia sempat mengunggah video reels dengan musik latar melankolis, ia mungkin merasa sedikit kecewa karena kehilangan momen viral.
Kritik Literasi Digital: Matinya Substansi
Literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan gawai, melainkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi dan dampak etisnya. Pejabat yang hobi “wisata bencana” gagal dalam literasi ini. Mereka tidak memahami bahwa setiap piksel penderitaan yang mereka unggah tanpa izin etis adalah pelanggaran martabat manusia.
Susan Sontag dalam Regarding the Pain of Others memperingatkan bahwa paparan terus-menerus terhadap gambar bencana dapat menyebabkan “anestesi psikologis” [8]. Masyarakat tidak lagi tergerak untuk menolong, melainkan hanya sekadar “menonton” bencana sebagai bagian dari aliran informasi harian. Pejabat, yang seharusnya menjadi pengambil kebijakan, justru ikut merayakan anestesi ini dengan menjadikan bencana sebagai latar belakang swafoto.
Memulihkan Martabat di Balik Lensa
Bencana adalah momen Memento Mori—pengingat akan kematian dan keterbatasan manusia. Secara filosofis, ia menuntut keheningan dan kerja nyata, bukan kebisingan konten. Wisata bencana yang dilakukan oleh para elit politik adalah sebuah “dosa estetika” yang melukai keadilan sosial.
Jika literasi digital tidak dibarengi dengan kecerdasan etis dan empati radikal, maka setiap banjir bandang di masa depan hanya akan menjadi ajang kontes fotografi bagi mereka yang memegang kuasa. Kita tidak butuh pejabat yang pandai memilih filter, kita butuh mereka yang pandai mengelola tata ruang agar air tidak lagi menjadi musuh bagi rakyatnya.
Ontologi “Selfie” di Atas Puing: Membedah Eksistensi Palsu
Secara eksistensial, fenomena pejabat yang berswafoto di tengah bencana Sumatera merupakan upaya putus asa untuk mengonfirmasi eksistensi diri dalam ruang publik yang semakin sesak. Merujuk pada pemikiran Martin Heidegger tentang Dasein (Keadaan-di-Dunia), manusia seharusnya hadir secara otentik [16]. Namun, para “Wisatawan Bencana” ini terjebak dalam apa yang disebut Heidegger sebagai Das Man—keberadaan yang tidak otentik, di mana seseorang bertindak hanya karena “begitulah yang dilakukan orang lain” atau karena tuntutan tren politik.
Analisis psikologis menunjukkan bahwa ini adalah bentuk Empathy Gap yang akut. Secara neurologis, ketika seseorang terlalu fokus pada sudut pengambilan gambar dan komposisi visual, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemrosesan emosi (amigdala dan insula) cenderung mengalami penurunan aktivitas. Mereka tidak lagi melihat korban sebagai subjek yang menderita, melainkan sebagai “properti” atau elemen estetika dalam bingkai (frame). Inilah yang secara sastrawi bisa kita sebut sebagai “Pengkhianatan Lensa”: kamera yang seharusnya mendekatkan jarak manusiawi, justru menjadi dinding kaca tebal yang memisahkan sang pejabat dari realitas sosiologis di bawah kakinya.
Satir Jeda Iklan: Antara Logistik dan “Likes”
Mari kita tinjau sebuah anekdot satir yang tajam. Di sebuah tenda darurat yang bocor, seorang pejabat berbisik pada ajudannya, “Pastikan sudut pengambilan gambarnya menunjukkan saya sedang memegang pundak bapak tua itu. Tapi tolong, jangan sampai tangan saya kotor terkena lumpur bajunya.” Sang bapak tua, yang baru saja kehilangan seluruh anggota keluarganya, menatap kosong ke arah kamera. Baginya, kilatan lampu flash itu bukan harapan, melainkan petir kedua yang menyambar harga dirinya. Ketika video tersebut diunggah dengan judul “Menyatu dengan Rakyat di Tengah Duka”, sang pejabat mendapat ribuan komentar pujian. Namun, secara diam-diam, bantuan logistik yang dibawa hanya cukup untuk durasi syuting. Begitu tombol stop ditekan, rombongan tersebut berlalu dengan mobil SUV mewah yang debunya mengotori wajah para pengungsi. Ini adalah Simulakra Kekuasaan yang paling vulgar: mereka memproduksi makna bantuan tanpa pernah memberikan substansi bantuan itu sendiri [17].
Literasi Digital: Membedah “The Clickbait Leadership”
Kritik terhadap literasi digital para elit ini harus sampai pada ranah Etika Algoritma. Dalam sistem kapitalisme pengawasan yang dijelaskan oleh Shoshana Zuboff, perhatian (attention) adalah emas baru [18]. Pejabat publik telah berubah menjadi pemulung perhatian digital. Mereka mengonsumsi penderitaan rakyat sebagai konten karena algoritma media sosial memberikan imbalan (reward) berupa visibilitas tinggi pada konten yang berbau “kemanusiaan”.
Kegagalan literasi digital di sini bukan pada ketidakpahaman teknis, melainkan pada ketidakmampuan membedakan ruang privat dan ruang publik. Duka adalah ruang privat yang sakral. Menjadikannya konsumsi publik tanpa tujuan mitigasi yang jelas adalah bentuk Pornografi Politik. Literasi digital yang sehat seharusnya mengajarkan bahwa ada momen di mana kamera harus dimatikan agar nurani bisa bicara. Namun, dalam logika “Wisata Bencana”, jika sebuah bantuan tidak di-posting, maka bantuan itu dianggap tidak pernah terjadi. Ini adalah bentuk Nilai Tukar Simbolis yang menghancurkan nilai guna dari kepemimpinan itu sendiri.
Lensa Deskriptif: Estetika Kebohongan yang Indah
Secara deskriptif, narasi digital para pejabat ini sering kali menggunakan teknik Sinetronisasi Realitas.
1. Slow Motion Pathos: Video pejabat berjalan di tengah hujan yang diperlambat untuk memberikan efek dramatis.
2. Soundtrack Manipulatif: Penggunaan instrumen piano minor yang memeras air mata penonton digital, mengaburkan fakta bahwa kebijakan pencegahan banjir mereka selama ini adalah kegagalan total.
3. Color Grading “Hope”: Mengubah warna lumpur yang cokelat kusam menjadi warna yang lebih “hangat” agar terlihat seperti perjuangan yang estetis.
Ini adalah bentuk Disinformasi Emosional. Publik tidak diberi informasi tentang mengapa banjir itu terjadi (misalnya karena izin tambang atau penggundulan hutan), melainkan hanya disuguhi tontonan tentang betapa “pedulinya” sang pemimpin.
Menagih Kejujuran di Balik Piksel
Sebagai pelengkap dari esai panjang ini, kita harus menyadari bahwa “Wisata Bencana” adalah cermin retak dari masyarakat kita sendiri. Kita adalah penonton yang turut memberi makan monster ini melalui setiap like dan share yang kita berikan pada konten-konten palsu tersebut.
Secara spiritual, bencana adalah saat di mana “Aku” seharusnya lebur menjadi “Kita”. Namun, di tangan para teknokrat narsistik, bencana justru menjadi panggung di mana “Aku” ingin tampil paling berkilau di atas penderitaan “Kalian”. Kita membutuhkan dekolonisasi terhadap cara kita melihat bencana. Kita butuh pemimpin yang berani hadir tanpa kamera, yang berani kotor tanpa tim dokumentasi, dan yang berani bekerja dalam sunyi.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa jumlah followers Instagram seorang pejabat, melainkan berapa banyak nyawa yang terselamatkan dan berapa banyak tangis yang benar-benar terhapus, bukan sekadar diusap demi kepentingan lensa.
Arkeologi Kebijakan: Di Balik Retorika dan Di Bawah Lumpur
Jika kita menggali lebih dalam dengan pisau bedah Michel Foucault, kita akan menemukan bahwa “Wisata Bencana” adalah salah satu bentuk Biopolitik [21]. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui represi fisik, melainkan melalui pengaturan narasi atas hidup dan mati. Pejabat yang hadir di lokasi banjir bandang Sumatera sebenarnya sedang melakukan “manajemen populasi” melalui citra. Dengan memamerkan diri di depan pengungsi, mereka sedang menegaskan siapa yang memiliki kontrol atas sumber daya dan siapa yang berhak menjadi objek belas kasihan.
Namun, ada ironi yang lebih gelap di sini. Sebagian besar bencana banjir bandang di wilayah tersebut adalah hasil dari kebijakan ekstraktif—pemberian izin tambang dan pembukaan lahan sawit yang serampangan. Secara filosofis, ini adalah lingkaran setan Dialektika Pencerahan menurut Adorno dan Horkheimer: kemajuan teknologi dan ekonomi yang seharusnya membebaskan manusia justru berbalik menghancurkan alam dan memperbudak manusia dalam penderitaan [22]. Pejabat tersebut datang untuk “menyembuhkan” luka yang sebenarnya ia buat sendiri melalui kebijakan yang ia tandatangani di kantor ber-AC.
Satir: Sayembara Konten di Atas Rakit
Mari kita pertajam anekdot kita. Bayangkan sebuah instruksi dari Kepala Biro Humas kepada para stafnya di lokasi bencana: “Cari warga yang paling terlihat menderita, tapi pastikan dia tidak marah-marah saat ditanya. Kita butuh narasi ‘Rakyat yang Tabah’. Oh, dan pastikan sepatunya Bapak Gubernur terlihat berlumpur sedikit saja, jangan sampai menutupi logo merk internasionalnya. Kita ingin kesan ‘merakyat’ tapi tetap ‘berwibawa’.”
Ini adalah Komodifikasi Tragedi. Dalam literasi digital yang kritis, kita menyebutnya sebagai Content Mining atau penambangan konten. Penderitaan manusia diperlakukan seperti bijih besi atau batu bara—sesuatu yang harus dikeruk, diolah, dan dijual kembali kepada publik dalam bentuk citra politik yang menguntungkan. Sang pejabat tidak sedang memimpin mitigasi; ia sedang memimpin photo shoot berskala besar.
Psikologi Massa dan “The Spectator’s Guilt”
Mengapa publik tetap mengonsumsi konten ini? Psikologi massa menjelaskan adanya fenomena Schadenfreude yang halus—rasa lega karena musibah itu terjadi pada orang lain dan bukan pada kita—yang dibalut dengan rasa iba palsu. Literasi digital masyarakat kita sering kali berhenti pada permukaan. Kita merasa sudah “membantu” hanya dengan memberikan tanda hati pada unggahan sang pejabat.
Jean-Paul Sartre dalam analisisnya tentang “Tatapan” (The Look) berpendapat bahwa ketika kita melihat orang lain, kita cenderung mengubah mereka menjadi objek [23]. Dalam wisata bencana ini, korban banjir kehilangan subjektivitasnya. Mereka bukan lagi manusia dengan cerita, sejarah, dan hak politik; mereka hanyalah latar belakang (background) bagi subjek utama: sang pejabat. Tanpa literasi psikologis yang kuat, masyarakat akan terus terjebak dalam tontonan ini, menjadi pendukung setia dari sirkus kemanusiaan yang dangkal.
Lensa Deskriptif: Tekstur Kehampaan
Secara deskriptif, marilah kita lukiskan kontras yang tajam itu.
Di Sisi Kiri Frame: Seorang anak kecil menggigil, memegang bungkusan mi instan yang sudah hancur. Matanya merah karena kurang tidur dan asap tungku darurat.
Di Sisi Kanan Frame: Seorang pejabat sedang tertawa kecil sambil memeriksa hasil jepretan fotografer pribadinya. Ia meminta retake karena kerutan di dahinya terlihat terlalu tua.
Lensa kamera hanya menangkap sisi kiri untuk diunggah, namun realitas yang utuh mencakup sisi kanan yang memuakkan. Inilah yang disebut “Gaps in the Narrative”. Literasi digital yang sejati adalah kemampuan untuk melihat apa yang tidak ditunjukkan oleh kamera.
Menuju Keheningan yang Radikal
Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pemikiran ini, mungkin yang kita butuhkan adalah kembali pada konsep Simone Weil tentang “Atensi” [24]. Atensi, menurut Weil, adalah bentuk doa yang paling murni. Ia menuntut pelepasan ego sepenuhnya untuk benar-benar mendengarkan penderitaan orang lain.
Wisata bencana adalah antitesis dari atensi. Ia adalah kebisingan ego di tengah sunyinya duka. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan Keheningan Radikal—hadir, bekerja, membangun tanggul, mereformasi izin lahan, dan memastikan perut rakyat kenyang, tanpa merasa perlu menyalakan kamera.
Kita harus menuntut agar bencana kembali menjadi momen introspeksi nasional, bukan ajang festival visual. Biarlah lumpur di Sumatera tetap menjadi lumpur yang menuntut kerja nyata, bukan menjadi bedak bagi wajah-wajah politik yang haus validasi. Karena pada hari penghakiman sejarah, yang akan bicara bukan jumlah followers, melainkan tanah yang basah oleh keringat kerja, bukan oleh air mata buatan untuk kepentingan konten kreatif.
Itu saja!***
Catatan Kaki
[1] Burke, E. (1757). A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. London: Dodsley.
[2] Kant, I. (1790). Critique of Judgement. Oxford University Press.
[3] Debord, G. (1967). The Society of the Spectacle. Buchet/Chastel.
[4] Baudrillard, J. (1981). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
[5] Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Viking Press.
[6] Levinas, E. (1961). Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. Duquesne University Press.
[7] Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2011). The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder. Wiley.
[8] Sontag, S. (2003). Regarding the Pain of Others. Farrar, Straus and Giroux.
[9] Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2009). The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. Free Press.
[10] Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
[11] Benjamin, W. (1935). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Schocken Books.
[12] Eco, U. (1986). Travels in Hyperreality. Harcourt Brace Jovanovich.
[13] Suler, J. (2004). “The Online Disinhibition Effect”. CyberPsychology & Behavior.
[14] Han, B. C. (2015). The Burnout Society. Stanford University Press. (Serta karyanya Saving Beauty mengenai estetika digital yang dangkal).
[15] Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.
[16] Heidegger, M. (1927). Being and Time. Harper & Row.
[17] Baudrillard, J. (1970). The Consumer Society: Myths and Structures. Sage Publications.
[18] Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
[19] Han, B. C. (2017). In the Swarm: Digital Prospects. MIT Press.
[20] Debord, G. (1988). Comments on the Society of the Spectacle. Verso.
[21] Foucault, M. (1976). The Will to Knowledge: The History of Sexuality Volume 1. Penguin.
[22] Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1944). Dialectic of Enlightenment. Herder & Herder.
[23] Sartre, J. P. (1943). Being and Nothingness. Philosophical Library.
[24] Weil, S. (1951). Waiting for God. Putnam.
[25] Byung-Chul Han. (2012). The Transparency Society. Stanford University Press.
Rujukan Ilmiah
Stone, P. R. (2006). “A Dark Tourism Spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions.” CUSTOS.
Sontag, S. (2003). Regarding the Pain of Others. Farrar, Straus and Giroux. (Membahas bagaimana foto penderitaan bisa mematikan rasa empati jika dikonsumsi sebagai tontonan).
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. (Membahas bagaimana individu melakukan pertunjukan peran di depan publik).
Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. (Analisis psikologis tentang bagaimana teknologi menjauhkan kita dari empati nyata).
Postman, N. (1985). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. (Argumen fundamental tentang bagaimana media mengubah diskursus serius menjadi hiburan).
Crary, J. (2013). 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. (Membahas bagaimana setiap detik kehidupan manusia dipaksa menjadi produktif dan terekam dalam sistem kapitalisme digital).
Sartre, J. P. (1943). Being and Nothingness. (Analisis tentang “The Look” atau Tatapan orang lain yang mengubah manusia menjadi objek).
Manovich, L. (2001). The Language of New Media. (Penting untuk memahami bagaimana estetika digital mengonstruksi realitas baru).
Fisher, M. (2009). Capitalist Realism. (Bagaimana segala aspek kehidupan, termasuk bencana, diserap ke dalam logika pasar dan citra).
Sontag, S. (1977). On Photography. (Esai klasik tentang bagaimana fotografi mengubah cara kita melihat dunia dan penderitaan).
Baudrillard, J. (1995). The Gulf War Did Not Take Place. (Membahas bagaimana perang/bencana diproduksi sebagai peristiwa media yang terputus dari realitas fisik).
Girard, R. (1972). Violence and the Sacred. (Membahas peran “kurban” dalam stabilitas sosial—dalam hal ini, korban bencana menjadi kurban bagi stabilitas citra politik).
———
*Gus Nas Jogja, budawayan.