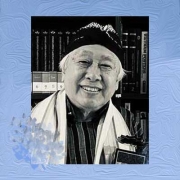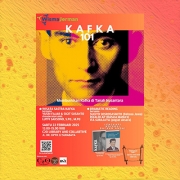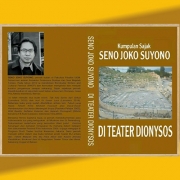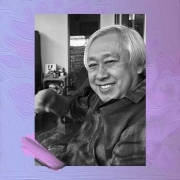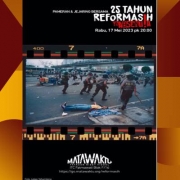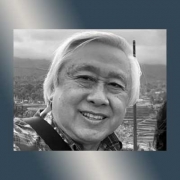Rusaknya Bahasa: Epistemologi Krisis dan Semiotika Absurditas
Oleh: Gus Nas Jogja*
Esai ecek-ecek ini saya tulis sebagai sebuah tinjauan filosofis terhadap Katastropi Linguistik yang belakangan ini marak di seluruh platform media, yang pada akhirnya saya simpulkan sebagai Panggung Kekacauan dari Logos Universal ke pekikan Ad Hominem.
Bayangkan saja, sebuah panggung debat di media elektronik, disiarkan langsung tanpa sensor. Di tengah perdebatan tentang Demokrasi Pancasila, tiba-tiba seorang panelis yang acapkali mengaku Profesor dan Filosof, memotong argumen lawan dengan nada merendahkan:
“Anda ini bicara apa? Argumen Anda ngawur! Sebaiknya Anda sadar, Anda itu cuma Bajingan Tolol yang merusak negara ini dengan logika dangkal Anda! Persis seperti mantan Presiden dan Presiden yang sedang berkuasa!”
Kalimat ini, yang segera menjadi soundbite viral, adalah manifestasi paling vulgar dan nyata dari apa yang saya sebut sebagai Katastropi Linguistik kontemporer—sebuah cermin bobroknya nalar dan akal si pengucap.
Filsafat Barat sejak Abad Pencerahan (Aufklärung) didasarkan pada Epistemologi Korespondensi, di mana Bahasa (Logos) dipercaya sebagai cermin yang transparan, mampu merefleksikan Realitas (Physis). Semiotika di era itu stabil: tanda memiliki hubungan yang mapan dengan yang ditandai. Krisis bahasa kontemporer yang saya ilustrasikan di atas menunjukkan bahwa saat ini kita telah jauh meninggalkan idealisme tersebut, menggantikannya dengan kekerasan verbal yang nihil makna.
Mari kita bedah persoalan serius ini dalam perspektif Katastropi Linguistik Historis dan Dekonstruksi Nalar oleh Trauma.
Jika kita membaca sejarah dengan teliti, keyakinan epistemologis pada nalar dan bahasa yang stabil hancur total pada abad ke-20. Peristiwa-peristiwa seperti Perang Dunia dan Holocaust adalah Katastropi Linguistik yang menunjukkan kegagalan nalar untuk mengendalikan diri dan kegagalan bahasa untuk merepresentasikan trauma.
Nalar Gagal dikarenakan Rasionalitas Pencerahan justru menjadi alat efisien dalam perencanaan kehancuran massal. Nalar instrumental memakan Nalar moral.
Adanya Pengkhianatan Bahasa, manakala kosakata terasa hampa di hadapan skala horor, sementara bahasa juga dikorup menjadi alat totalitarianisme.
Selain itu, hadirnya Semiotika Absurditas, dimana Tanda-Tanda yang Berkarat bermunculan. Krisis representasi akal sehat ini melahirkan era sastra Absurditas yang dipelopori oleh Samuel Beckett, yang menyaksikan pemutusan hubungan antara penanda dan petanda (the arbitrary nature of the sign), dengan ucapan:
“Estragon: I can’t go on like this. / Vladimir: That’s what you think.”
–Samuel Beckett [1]
Dialog Beckett tersebut adalah kegagalan epistemologis yang sempurna. Komunikasi adalah loop tanpa pengetahuan, di mana bahasa ada, tetapi fungsinya untuk menyampaikan makna telah lumpuh.
Kegagalan berbahasa dengan baik itu menurut saya diakibatkan adanya Semiotika Disrupsi, yaitu ketika Tanda Vulgar hadir menggantikan fungsi Nalar.
Di era disrupsi saat ini, Katastropi Linguistik bermutasi. Kerusakan bahasa ditandai oleh Semiotika yang bertujuan menghapus wacana rasional, seperti yang diilustrasikan oleh frasa penghinaan vulgar. Frasa seperti “Bajingan Tolol” berfungsi sebagai:
1. Semiotika Ad Hominem Total: Ini adalah pernyataan performatif yang menghancurkan pelaku wacana, bukan argumennya. Ini adalah jalan pintas linguistik menuju kemenangan diskursif.
2. Pelarian dari Akal: Penggunaan tanda-tanda yang mengandalkan agresi emosional untuk mengakhiri diskusi adalah bukti paling nyata dari pelarian dari akal sebagaimana ditegaskan oleh Emmanuel Kant dalam frasa Sapere Aude!. Pengucap menolak tanggung jawab intelektual untuk menyusun argumen yang logis dan persuasif.
Dekonstruksi yang menjadi narasi post modernisme menyoroti penjara-nya bahasa. Filosof Jacques Derrida berargumen bahwa realitas selalu sudah dikonstruksi oleh sistem linguistik dan wacana:
“Il n’y a pas de hors-texte.”
Tidak ada yang di luar teks.
–Jacques Derrida [2]
Implikasi epistemologisnya ialah, pengetahuan dicapai dengan mengurai bagaimana bahasa kita sendiri menciptakan dan menyembunyikan asumsi kekuasaan, bukan dengan mencerminkan realitas yang independen.
Sebagai pengurai benang kusut ini saya menawarkan Sastra Pembebasan, dimana Hermeneutika Pluralitas Epistemologis dihadirkan di setiap Panggung Dialog
Penting saya tegaskan, bahwa respon etis terhadap rusaknya bahasa adalah Sastra Pembebasan terutama di era Post Truth saat ini. Sastra ini menolak Narasi Besar tunggal yang diciptakan oleh Nalar Pencerahan dan menuntut Pluralitas Epistemologis: pengetahuan harus dicari dalam fragmen, hibriditas, secara obyektif, dan menggelar karpet merah pada suara-suara yang selama ini dipinggirkan.
Jika bangsa ini tidak ingin terperosok di comberan budaya olok-olok yang mengakibatkan Kebangkrutan Objektif Nalar, maka kita perlu kembali pada Khittah Nalar Budi Pekerti.
Budaya mengolok-olok atau mocking culture dan merendahkan orang lain yang kini mendominasi diskursus publik, bagi saya hal ini merupakan epilog yang tragis dari Katastropi Linguistik historis. Fenomena ini menandai titik terendah dari kemunduran epistemologis dan filosofis, yang disebut Kebangkrutan Objektif Nalar Sang Pengucap.
Ini bukan sekadar masalah etika atau kesopanan; ini adalah Kegagalan Fungsi Nalar itu sendiri.
1. Kegagalan Objektif: Nalar, menurut definisi Pencerahan, adalah kapasitas untuk berpikir secara logis dan menyusun argumen yang valid. Ketika seorang individu memilih untuk mengganti argumentasi atau (logos) dengan caci-maki atau (ad hominem), ia secara objektif telah menanggalkan fungsi fundamental dari nalarnya. Ia memilih “semiotika agresi” di atas “semiotika persuasi”, secara efektif menyatakan bahwa kemampuan rasionalnya telah habis atau tidak relevan bagi tujuan komunikasinya.
2. Perusakan Bahasa Secara Akut: Implikasi dari kebangkrutan nalar ini adalah perusakan bahasa secara akut. Bahasa yang seharusnya berfungsi sebagai medium kompleks untuk menavigasi perbedaan ideologis kini direduksi menjadi senjata biner: “Saya benar, Anda salah” –yang direpresentasikan oleh caci-maki. Kata-kata kehilangan nuansa, kapasitas untuk mediasi, dan kemampuan untuk membangun jembatan. Bahasa dibelah dua, antara Bahasa Kepongahan yang merendahkan dan Bahasa Korban yang diolok-olok, menghancurkan ruang publik sebagai arena untuk dialog yang rasional.
Rusaknya bahasa memaksa kita meninggalkan Epistemologi Korespondensi Pencerahan. Bahasa adalah medan perang—bukan lagi cermin transparan—di mana setiap tanda harus dipertanyakan bukan hanya apa yang diwakilinya, tetapi bagaimana ia digunakan: apakah untuk membangun wacana rasional, ataukah, seperti tanda-tanda di era disrupsi, untuk menandai keruntuhan nalar dan bobroknya akal.
Itu saja!
Catatan Kaki
[1]. Beckett, Samuel. Waiting for Godot. Paris: Les Éditions de Minuit, 1952, Act I.
[2]. Derrida, Jacques. De la grammatologie. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967, hlm. 227.
Daftar Pustaka
1. Beckett, Samuel. Waiting for Godot. Les Éditions de Minuit, 1952.
2. Derrida, Jacques. Of Grammatology. Diterjemahkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Johns Hopkins University Press, 1976.
3. Horkheimer, Max, and Adorno, Theodor W. Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press, 2002.
4. Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. 1781.
—–
*Gus Nas Jogja, budayawan.