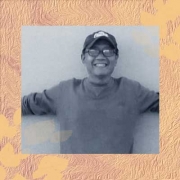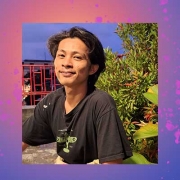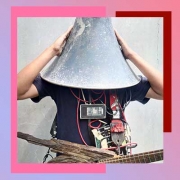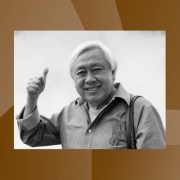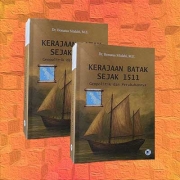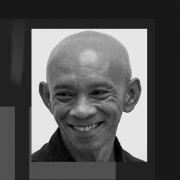Seni Abad 21: Membosankan Atau Membebaskan?
Oleh Eko Yuds
Seni modern hidup di antara kebebasan dan kebingungan. Ia tak lagi terikat oleh bentuk, gaya, atau pusat, tetapi juga kehilangan arah dan makna. Dari kardus sabun Warhol hingga mural di jalanan Yogyakarta, seni abad 21 menatap dunia tanpa peta—kadang membosankan, kadang membebaskan. Inilah zaman ketika karya bukan lagi sekadar benda, tetapi pernyataan kesadaran manusia tentang dirinya dan dunianya.
Di sebuah galeri kecil di Manhattan tahun 1964, seorang pengunjung berdiri lama di depan tumpukan kardus sabun Brillo Boxes. Tidak ada cat minyak, tidak ada kuas, tidak ada ekspresi romantis seperti pada lukisan klasik. Hanya kardus sabun yang persis seperti di supermarket. Tapi di dinding tertulis: Andy Warhol, Brillo Boxes, 1964. Pengunjung itu adalah Arthur C. Danto, seorang filsuf dan kritikus seni yang kemudian menulis kalimat legendaris: “Inilah akhir seni” (Danto, 1997). Kalimat itu bukan keluhan, tapi sebuah penanda zaman. Ia menandai akhir dari satu cara dunia memahami seni—bukan kematian, melainkan kelahiran bentuk kesadaran baru.
Sebelum momen itu, sejarah seni dianggap berjalan seperti garis lurus: dari klasik ke modern, dari realisme menuju abstraksi. Setiap masa memiliki ukuran yang menentukan apa yang disebut indah dan bermakna. Tapi Warhol meruntuhkan semua itu. Ia menunjukkan bahwa keindahan bukan lagi soal bentuk, melainkan soal kesadaran. Kardus sabun bisa menjadi karya seni karena ia membawa gagasan tentang dunia konsumsi, banalitas, dan citra manusia modern yang kehilangan makna. Sejak saat itu, seni tidak lagi bicara tentang wujud, tapi tentang kesadaran yang melahirkannya.
Arthur Danto menyebut masa baru ini sebagai post-historical condition—masa setelah sejarah, ketika seni berhenti bergerak menuju satu arah tertentu dan mulai menjelajah ke segala penjuru (Danto, 1997). Abstrak, realis, instalasi, dan digital hidup berdampingan tanpa harus saling menyingkirkan. Dunia seni tidak lagi memiliki peta tunggal; ia menjadi semesta terbuka yang penuh kemungkinan. Namun kebebasan ini datang dengan harga. Bila semua benda bisa disebut seni, apa arti seni itu sendiri? Danto menulis bahwa seni “telah membebaskan dirinya dari sejarah, tetapi kehilangan kompasnya.” Dunia kehilangan narasi besar yang dulu menuntunnya.
Hans Belting, sejarawan seni asal Jerman, melihat gejala yang sama, tapi dari arah berbeda. Dalam Art History After Modernism, ia menulis bahwa sejarah seni Barat telah mencapai ujungnya (Belting, 2003). Kini kita hidup di masa setelah seni (after art). Pusat dunia seni tidak lagi di Eropa, melainkan menyebar ke berbagai belahan dunia. Pameran di Lagos, Tokyo, dan Yogyakarta kini sama pentingnya dengan yang di Paris atau New York. Dunia seni telah menjadi multipolar. Ini, bagi Belting, adalah tanda kematangan baru: setiap budaya menulis sejarahnya sendiri, setiap identitas menyumbang cara pandang baru terhadap dunia visual.
Namun pluralitas ini membawa dilema baru. Tanpa pusat, seni kehilangan arah moral dan spiritualnya. Banyak karya lahir hanya demi tampil berbeda, bukan karena dorongan makna. Danto menyebutnya pluralism without principle—kebebasan tanpa pijakan. Seni menjadi permainan bentuk, bukan pencarian kesadaran. Dan ketika kapitalisme global masuk, seni dengan mudah berubah menjadi komoditas. Lukisan menjadi investasi, galeri menjadi pasar. Nilai estetika berubah menjadi nilai tukar. Brillo Boxes yang dulu lahir sebagai kritik terhadap budaya konsumsi kini justru menjadi simbolnya. Danto menulis, “Seni telah bermetamorfosis menjadi bahasa kapital” (Danto, 1997).
Namun di tengah arus pasar yang deras, masih ada suara yang mengingatkan bahwa seni bukan sekadar kebebasan ekspresi, melainkan tanggung jawab makna. Salah satunya datang dari pemikiran Islam modern, khususnya dari Seyyed Hossein Nasr—filsuf dan teolog yang banyak menulis tentang hubungan antara seni, spiritualitas, dan kesadaran. Dalam Islamic Art and Spirituality, Nasr menegaskan bahwa seni sejati adalah “refleksi dari al-Haqq,” Kebenaran yang memancar dari Tuhan (Nasr, 1987). Ia menyebut seni Islam sebagai bentuk dhikr visual—pengingat akan Yang Satu di tengah keragaman bentuk. Setiap lengkung kaligrafi dan simetri geometris, kata Nasr, adalah cermin dari kesempurnaan Ilahi. Seni yang kehilangan kesadaran transendentalnya mungkin tetap indah, tapi hampa dari ruh.
Jika Danto berbicara tentang akhir sejarah seni, dan Belting berbicara tentang pluralitas budaya, maka Nasr berbicara tentang hilangnya qiblat spiritual dalam seni modern. Ia menulis bahwa seni yang tercerabut dari akar ilahinya akan kehilangan daya penyembuhannya. Kebebasan tanpa arah hanyalah bentuk baru keterasingan. Dalam pandangan Nasr, “seni tidak pernah berakhir selama manusia masih mencari yang suci melalui bentuk” (Nasr, 1987). Di sinilah seni modern dan spiritualitas bersinggungan. Seni boleh kehilangan sejarahnya, tapi ia tak boleh kehilangan jiwanya.
Pandangan Nasr ini memberi keseimbangan yang lembut pada kebebasan yang digambarkan Danto dan Belting. Jika Danto menandai akhir sejarah, dan Belting merayakan keberagaman, Nasr mengingatkan tentang pentingnya arah batin. Seni modern mungkin telah kehilangan pusat, tapi manusia masih membutuhkan poros makna yang menuntun penciptaan. Dalam konteks ini, seni Islam memberi pelajaran berharga: kebebasan tidak berarti tanpa arah; ia adalah kebebasan yang sadar akan asalnya.
Gagasan Nasr menemukan resonansi kuat dalam pengalaman seni Indonesia. Di negeri ini, seni tumbuh dari akar spiritual dan sosial yang dalam. Lukisan Nyoman Masriadi, misalnya, memotret manusia modern dengan tubuh kekar tapi mata kosong—sebuah satire tentang kekuasaan tanpa jiwa. Sementara mural Taring Padi di Yogyakarta menampilkan keberanian rakyat kecil dengan humor, protes, dan doa yang dicat di dinding. Di tangan mereka, seni bukan hanya estetika, tapi kesadaran sosial dan spiritual. Seperti yang diyakini Nasr, seni menjadi bentuk dzikir kolektif—cara manusia mengingat kemanusiaannya di tengah hiruk-pikuk dunia.
Namun kini kita hidup di era yang lebih rumit lagi: era digital dan kecerdasan buatan. Seni tak hanya berpindah medium, tetapi berpindah kesadaran. Karya lahir bukan dari tangan manusia, tetapi dari algoritma. Lukisan dibuat oleh mesin, puisi diciptakan oleh kecerdasan buatan. Pertanyaan lama Danto muncul kembali dalam bentuk baru: jika semua bisa mencipta, apakah manusia masih memiliki tempat dalam seni? Apakah kreativitas masih bermakna ketika direplikasi oleh kode? Dunia seni digital, NFT, dan media sosial mengubah segalanya—seni menjadi gambar bergerak, pesan viral, atau bahkan investasi kripto. Di sini, keaslian dan etika kembali dipertanyakan. Siapa yang benar-benar mencipta?
Namun mungkin justru di tengah derasnya arus teknologi inilah, seni menemukan wajah barunya. Dalam ruang virtual, seniman tidak lagi berbicara kepada segelintir elit, tetapi kepada seluruh dunia. Seni menjadi dialog terbuka, melampaui ruang dan waktu. Seperti yang diyakini Nasr, “keindahan sejati tak terikat bentuk, ia hadir di mana pun manusia mencari kebenaran.” Maka, bahkan karya digital pun bisa menjadi ruang spiritual, jika lahir dari kesadaran.
Kebebasan seni abad 21 membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kedewasaan baru. Ketika semua batas dibuka, tanggung jawab berpindah ke tangan seniman dan penonton. Kita harus belajar membaca makna di balik kekacauan bentuk. Seni pasca-modern tidak lagi hanya memanjakan mata, tapi menggugah kesadaran. Danto menyebut seni masa kini sebagai “filsafat yang diwujudkan dalam benda.” Seni menjadi cara berpikir, bukan sekadar cara membuat. Ia mengajak kita bertanya, bukan sekadar kagum (Danto, 1997).
Akhir seni, dalam pandangan Danto, bukanlah kematian, melainkan transformasi. Setelah kehilangan bentuk dan arah, seni kembali ke asalnya: kesadaran manusia. Ia membosankan bagi mereka yang mencari bentuk, tapi membebaskan bagi mereka yang mencari jiwa. Di tengah dunia yang bising oleh citra, seni masih menjadi ruang hening untuk merenung. Seperti kata Nasr, “keindahan sejati adalah cahaya yang menuntun manusia pulang” (Nasr, 1987).
Kini, mungkin kita perlu berdiri lagi di depan tumpukan Brillo Boxes Warhol, bukan untuk menertawakannya, tapi untuk mendengarnya. Sebab di balik tumpukan kardus biasa itu, tersembunyi pelajaran luar biasa: bahwa makna selalu lahir dari cara kita memandang. Danto menunjukkan kebebasan, Belting menunjukkan keragaman, dan Nasr menunjukkan arah. Ketiganya saling melengkapi. Ketika kebebasan menemukan kesadaran, dan kesadaran menemukan Tuhan, seni tidak berakhir—ia pulang ke sumbernya: pada penciptaan yang hidup di antara tangan manusia dan cahaya Ilahi.
——
(TitahManahWening): Jakarta, 2 November 2025
Referensi:
- Danto, Arthur C. (1997). After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History. Princeton University Press.
- Belting, Hans. (2003). Art History After Modernism. University of Chicago Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1987). Islamic Art and Spirituality. State University of New York Press.
…………..
*Eko Yuds, Teaterawan