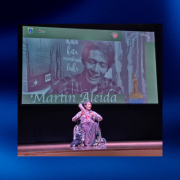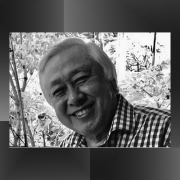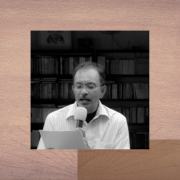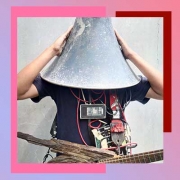Suluk Estetik Kuswaidi Syafi’ie: Puisi sebagai Peta Ontologis Relasi Tuhan–Manusia
Oleh: Abdul Wachid B.S.*
I. Pengantar: Menempatkan Kuswaidi Syafi’ie dalam Lanskap Puisi Sufi Indonesia
A. Latar Persoalan
Sepanjang sejarahnya, puisi religius Indonesia lebih sering tampil sebagai getaran: suara yang muncul dari lubuk kerinduan, kegentaran, atau pengakuan diri di hadapan Yang Maha Lembut. Pada banyak penyair, pengalaman spiritual hadir sebagai kilatan: intensitas rasa, bukan sebagai perjalanan ruh yang bertahap. Pengalaman itu hadir, namun tidak ditata sebagai jalan, sebagaimana laku sulukyang mengenal maqām dan ḥāl.
Sejak masa Balai Pustaka dan Pujangga Baru, pola tersebut tampak jelas. Madah Kelana karya Sanusi Pane dan Nyanyi Sunyi (1937) karya Amir Hamzah mengungkapkan kerinduan metafisis yang hening dan pekat, tetapi tidak membangun struktur perjalanan ruhani. Pada Angkatan 45, Chairil Anwar melalui “Doa” menghadirkan pergulatan eksistensial yang kuat, namun puncak batin itu tetap berdiri sebagai momen tunggal, bukan bagian dari lintasan spiritual yang berurutan.
Perubahan penting muncul pada Angkatan 66. Abdul Hadi W.M., lewatCermin (1975) dan Meditasi (1976), memperkenalkan kosmologi tasawuf ke dalam puisi modern Indonesia. Di tangan Abdul Hadi, puisi menjadi medium metafisika dan pengetahuan ruhani. Namun, sekalipun wacana sufistiknya utuh, puisinya tampil sebagai percikan makrifat (bening dan kontemplatif), tanpa membangun struktur tahapan yang menyerupai suluk.
Pada dekade 1970–1980-an, sufisme dalam puisi tampil lebih membumi. Emha Ainun Nadjib melalui 99 Untuk Tuhan (1980) menawarkan spiritualitas komunikatif, sementara D. Zawawi Imron dalam Celurit Emas (1986) menautkan tanah kelahiran dengan pasrah dan syukur. Namun keduanya tetap bergerak dalam pola ungkap, bukan pola perjalanan ruhani yang sistematik.
Memasuki Angkatan 2000, penyair seperti Mashuri dalam Dangdut Makrifat (2018) dan M. Aan Mansyur dalam Melihat Api Bekerja (2018) memperkuat spiritualitas melalui fragmentasi imaji dan eksperimen bentuk. Tetapi karakter umumnya masih sama: puisi religius modern Indonesia kerap lebih menangkap momen daripada menyusun jalur.
Dalam lanskap semacam inilah posisi Kuswaidi Syafi’ie menjadi berbeda dan penting. Ia tidak menulis pengalaman ruhani sebagai serpihan, tetapi menuliskannya sebagai suluk.
Tiga bagian yang kerap dianggap sebagai “trilogi ruhani” (Dermaga, Samudera, dan Pulau Impian), sebenarnya merupakan struktur internal buku Tarian Mabuk Allah (Yogyakarta: Pustaka Sufi, Cetakan III, 2003). Ketiganya bukan tiga buku terpisah, melainkan tiga maqām yang saling melanjutkan:
1. Dermaga — titik asal, pra-eksistensi;
2. Samudera — gelombang ujian eksistensial;
3. Pulau Impian — persandingan maknawi, kedekatan ruh.
Struktur bertahap ini menghadirkan sesuatu yang langka dalam sejarah puisi sufistik Indonesia modern: peta perjalanan, bukan sekadar ekspresi spiritual. Metafora-metafora Kuswaidi tidak berfungsi sebagai ornamen retoris, melainkan sebagai penanda arah; tiap kata diletakkan sebagai batu jejak seorang sālik yang menempuh jalan.
Nada puisinya seperti ruang khalwat: tenang, jernih, ditata dengan kesadaran ontologis. Ia menghindari gemerlap retoris untuk memberi jalan bagi makna yang bekerja secara perlahan, bersih, dan menghujam.
Dari situ muncul persoalan utama esai ini: Mengapa puisi sufistik Indonesia cenderung fragmenter, dan bagaimana Kuswaidi (melalui konsistensi estetik dan ontologisnya) mengubah puisi menjadi suluk: peta perjalanan ruh menuju Tuhan?
B. Tesis Esai
Dengan memperhatikan konteks sejarah dan dinamika estetika tersebut, tesis utama esai ini bahwa Kuswaidi Syafi’ie mengembalikan puisi sufi Indonesia kepada fungsi asalnya sebagai suluk (narasi perjalanan ruh yang bertingkat) sehingga puisi tidak hanya menjadi ungkapan rasa, tetapi beroperasi sebagai peta ontologis relasi manusia–Tuhan. Puisi baginya adalah jalan pengetahuan, bukan semata medium ekspresi. Tesis tersebut terbukti melalui tiga ranah.
1. Ranah Struktural
Pola “Dermaga–Samudera–Pulau Impian” membentuk kerangka perjalanan ruh: titik asal, fase ujian, dan momen persandingan. Struktur bertahap ini menempatkan pembaca seakan berjalan dalam lintasan maqām dan ḥāl.
2. Ranah Estetik
Perangkat puitik seperti invokasi, repetisi bernuansa zikir, metafora cahaya, serta gerak vertikal (turun–naik) tidak berfungsi sebagai ornamen,melainkan sebagai penanda spiritual yang mengarahkan pembaca pada kedalaman makna.
3. Ranah Teologis
Konsep-konsep seperti tajallī, fanā’–baqā’, dan ma‘rifat terjalin secara organis dalam bahasa, menjadikan puisi sebagai instrumen epistemik: cara mengetahui Tuhan melalui bahasa yang bening.
Untuk menegaskan keunikan ini, kajian membandingkannya dengan beberapa figur utama. Abdul Hadi W.M., melalui Cermin dan Meditasi,memancarkan estetika sufistik yang kuat, tetapi puisinya cenderung berupa kilatan makrifat, bukan perjalanan yang berjenjang. Sutardji Calzoum Bachri, lewat trilogi O Amuk Kapak (1981), membebaskan kata menuju asal-usulnya, namun pendekatannya lebih dekonstruktif daripada konstruksi suluk. Emha Ainun Nadjib, melalui karya-karya seperti “M” Frustasi dan Sajak-sajak Cinta (1976) serta 99 Untuk Tuhan, menghadirkan spiritualitas komunikatif yang reflektif dan membumi, tetapi tidak menyusun struktur perjalanan ruh.
Melalui pembandingan ini tampak bahwa sumbangan estetik-spiritual Kuswaidi terletak pada kemampuannya menata spiritualitas menjadi metodologi estetik, menjadikan puisi bukan sekadar ruang kontemplatif, tetapi jalan yang dapat dilalui: sebuah suluk yang memadukan struktur, rasa, dan hikmah. Kontribusi ini menjadikannya salah satu suara paling khas dalam perpuisian sufistik Indonesia modern.
II. Puisi sebagai Suluk: Trilogi Dermaga – Samudera – Pulau Impian
Puisi-puisi Kuswaidi Syafi’ie dalam Tarian Mabuk Allah adalah salah satu pencapaian paling jernih dalam tradisi perpuisian sufistik Indonesia kontemporer. Karya ini tidak dibangun sebagai kumpulan puisi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu bangunan ruhani tiga tingkat: Dermaga, Samudera, dan Pulau Impian, masing-masing berisi 33 puisi. Sejak awal, Kuswaidi menegaskan bahwa ketiga bagian ini adalah “suatu kesatuan, merupakan puisi utuh”, yang ia tulis dalam keadaan salik (pengelana batin) yang sedang mendengar “alunan firman-firman-Nya”.
Struktur tiga bagian ini bukan sekadar pembagian teknis, melainkan peta ontologis yang menjawab tiga pertanyaan paling fundamental dalam tasawuf: Dari mana ruh manusia berasal? Untuk apa ia menempuh hidup? Dan ke manakah ia akan kembali? Dalam catatan pengantarnya, Kuswaidi menyebut Dermaga sebagai gambaran pra-eksistensi ruh; Samudera sebagai fase pengabdian total; dan Pulau Impian sebagai persandingan dan kebahagiaan ruhani yang tak terkatakan.
Dengan demikian, Tarian Mabuk Allah tidak sekadar membicarakan Tuhan; ia mengajak pembacanya menempuh jalan pulang: sebuah suluk estetik, yang di dalamnya puisi berfungsi sebagai jalan, bukan sekadar bahasa.
A. Argumen: Puisi sebagai Suluk yang Utuh
Untuk memahami trilogi Dermaga–Samudera–Pulau Impian, kita perlu menempatkan Kuswaidi Syafi’ie sebagai penyair yang tidak menulis puisi dari “luapan rasa”, tetapi dari kesadaran perjalanan ruh yang bertahap. Inilah yang membedakan dirinya dari banyak penyair sufistik lain yang bergerak pada simbol-simbol emosional. Pada Kuswaidi, struktur perjalanan lahir-batin sangat jelas: ada asal, ada tajrīb (ujian–penyucian), dan ada liqa’ (perjumpaan).
1. Dermaga: Kesadaran Asal Ruh
Bagian Dermaga memotret saat sebelum segala sesuatu bermula: periode pra-eksistensi yang dalam tasawuf dikenal sebagai ‘ālam al-arwāḥ. Puisi-puisi pembukanya menggambarkan momen ketika Tuhan “mengandung” ruh manusia dalam sunyi yang mutlak (“Dermaga 1”) :
Kekasih duhai Kekasih!
Ketika itu sendiri Engkau mengandungku
Saat waktu beku di telapakMu
…..
Tak ada air api tanah dan udara
Bahkan sunyi pun tak menjelma
…..
Kuswaidi menulis bukan dengan bahasa simbolis, tetapi dengan kesadaran kosmologis bahwa ruh manusia berasal dari hadirat hakiki sebelum dunia tercipta. Di sinilah Dermaga menjadi “titik mula” suluk: tempat manusia menyadari asal kehadirannya sebelum terlempar ke dunia.
2. Samudera: Fase Ujian dan Penyucian
Jika Dermaga adalah asal, maka Samudera adalah fase tajalli: tempat ruh diuji, diguncang, dan dilemparkan ke berbagai kerumitan dunia untuk menemukan kembali arah pengabdiannya. Puisi-puisi dalam bagian ini penuh dengan luka, kegagalan, kejatuhan, dan pengakuan kerendahan diri. Kuswaidi menulis (“Samudera 16’):
…..
Kutabrak bongkahan batu dan kejenuhan
Hingga berkali-kali
Sampai kepalaku pecah
Dan sukma menunjukkan jalan yang lain.
…..
Di sinilah tampak bahwa baginya dunia bukan sekadar ruang pengalaman, melainkan madrasah ruhani. Kesalahan, penderitaan, bahkan keputusasaan adalah bagian dari penyucian. Manusia, dalam pandangannya, harus benar-benar “tak berdaya” agar dapat dituntun.
3. Pulau Impian: Persandingan Ruhani
Pada bagian terakhir, Pulau Impian (“1”), perjalanan ruh mencapai puncaknya. Di sini bahasa Kuswaidi tidak lagi bergerak dalam diksi luka atau perjuangan, tetapi dalam diksi kedekatan, keteduhan, dan kemesraan ruhani:
Kekasih duhai Kekasih!
Seluruh sembah puji kusampaikan kepadaMu
Yang telah sudi mengundangku
Ke keteduhan pulau impian
Di mana kupu-kupu dan bunga abadi
Dalam persandingan hakiki
…..
Inilah fase liqa’, perjumpaan yang melampaui kata-kata. Setelah ujian, guncangan, dan penyucian, manusia mencapai maqām fana’ (lenyap) dan baqā’ (kekekalan dalam Diri-Nya). Puncaknya, sang salik tidak lagi mencari atau meminta; ia hanya “bertawakkal secara total”, sebagaimana diungkapkan dalam puisi Dermaga ke-31:
…..
Kini aku tak lagi berdebar memandangMu
Kini aku tak lagi butuh mendekatMu
…..
Trilogi ini dengan demikian merupakan struktur suluk: asal ruh → penyucian → persandingan. Struktur seperti ini (jelas, bertahap, dan memiliki dasar metafisika), nyaris tidak ditemukan dalam sejarah perpuisian Indonesia. Di sinilah letak keistimewaan dan jejak unik estetik Kuswaidi Syafi’ie.
B. Bukti Puitik
Trilogi Kuswaidi Syafi’ie (Dermaga, Samudera, Pulau Impian) menjadi peta perjalanan ruhani. Setiap bagian tidak berdiri sendiri, melainkan saling menegaskan maqām suluk. Bukti puitik berikut menunjukkan keteraturan simbolik dan progresi spiritual yang konsekuen.
1. Dermaga: Titik Asal Ruh
Bagian Dermaga (“1”) merepresentasikan pra-eksistensi ruh atau al-dzuhr al-awwal, di mana manusia berada dalam sunyi dan kesadaran mutlak sebelum lahir ke dunia. Kuswaidi menulis:
…..
Ketika itu sendiri Engkau mengandungku
Saat waktu beku di telapakMu
Menggenggam ‘sejarah’ dan ‘masa depan’
Tak ada air api tanah dan udara
Bahkan sunyi pun tak menjelma
…..
Puisi ini memperlihatkan kesadaran kosmologis: ruh manusia belum berinteraksi dengan dunia materi, hanya “tersimpan” dalam kesadaran Tuhan. Kata “mengandung” menunjukkan dimensi penyelenggaraan Ilahi, bahwa manusia berasal dari kehendak hakiki sebelum segala wujud terbentuk. Kuswaidi menegaskan pengalaman spiritual ini melalui simbol-simbol ruang dan waktu yang dibekukan, menandai titik mula perjalanan suluk.
Pada bait terakhir Dermaga (“1”), Kuswaidi menggambarkan hubungan langsung ruh dengan Tuhan:
…..
Hanya Kau bersemayam di atas ‘arsy sendirian
Mendendangkan lagu-lagu kasmaran
Di sini, Dermaga bukan sekadar tempat fisik, melainkan locus of the soul, titik awal untuk refleksi eksistensial dan meditasi batin.
2. Samudera: Fase Ujian dan Penyucian
Bagian Samudera (“1”) memvisualisasikan maqām perjalanan: ujian, penderitaan, dan purifikasi. Pada tahap ini, ruh diuji melalui guncangan metaforis dan simbolik yang menunjukkan keterasingan dan kerendahan manusia. Kuswaidi menulis:
Kekasih duhai Kekasih!
Kini aku terlahir lagi
Entah yang ke berapa kalinya
Bermata buta, Bertelinga tuli
Bermulut bisu, Bernafas dungu
Tercampak di rimba hutan yang ultraheterogen
Tak mampu lagi mengeja huruf dan sandi
Yang Kau tebarkan di 1000 penjuru mata angin
…..
Simbol “mata buta, telinga tuli, mulut bisu” menandakan ketidakmampuan awal manusia menghadapi firman Ilahi. Samudera adalah madrasah batin, di mana keterbatasan manusia dihadapkan pada kebesaran Tuhan, sehingga muncul pengabdian total.
Di puisi lain, Dermaga “16”, Kuswaidi menekankan perjuangan batin yang melelahkan:
…..
Kutabrak bongkahan batu dan kejenuhan
Hingga berkali-kali
Sampai kepalaku pecah
Dan sukma menunjukkan jalan yang lain
Proses ini menegaskan bahwa kesadaran spiritual diperoleh melalui pengorbanan dan ujian, sesuai maqām sufistik klasik: ketakutan, harap, dan cinta.
3. Pulau Impian: Persandingan Ruhani
Pulau Impian (“1”) menandai puncak suluk, persandingan ruhani (liqa’). Kuswaidi menulis:
Kekasih duhai Kekasih!
Seluruh sembah puji kusampaikan kepadaMu
Yang telah sudi mengundangku
Ke keteduhan pulau impian
Di mana kupu-kupu dan bunga abadi
Dalam persandingan hakiki
…..
Bahasa Kuswaidi di sini mengalir dalam keheningan, kesyahduan, dan kepuasan ruhani, berbeda dari kegelisahan di Samudera. Persandingan ini menandai maqām fana’–baqā’: lenyapnya ego individu dan keberadaan yang utuh dalam Tuhan. Puisi lain (Pulau Impian “31”) menegaskan totalitas pengalaman ini:
…..
Kini aku tak lagi berdebar memandangMu
Kini aku tak lagi butuh mendekatMu
Inilah totalitas tawakkalku
Inilah totalitas keislamanku
…..
Bukti puitik ini menunjukkan bahwa trilogi Kuswaidi membentuk satu kesatuan estetika dan spiritual, bukan sekadar himpunan puisi. Dari Dermaga ke Pulau Impian, pembaca mengalami proses ontologis, emosional, dan batiniah yang menyeluruh.
C. Elaborasi: Trilogi sebagai Struktur Sufistik
Trilogi Dermaga, Samudera, Pulau Impian dalam Tarian Mabuk Allahkarya Kuswaidi Syafi’ie bukan sekadar pengelompokan puisi berdasarkan tema. Susunan ini membentuk struktur naratif dan spiritual yang menyerupai kitab sufistik klasik, menunjukkan progresi maqām yang sistematis: dari pra-eksistensi (Dermaga), melalui ujian dan purifikasi (Samudera), hingga persandingan dan fana’–baqā’ (Pulau Impian). Hal ini jarang ditemukan dalam puisi Indonesia modern, di mana pengembangan spiritual jarang dibingkai secara konseptual dan sistematis.
Struktur trilogi ini menyerupai risalah sufistik klasik seperti Risālah Qusyairī atau Fushush al-Hikam karya Ibnu ‘Arabī, yang menguraikan maqām atau tahapan spiritual secara berjenjang. Kuswaidi tidak hanya menyusun puisinya berdasarkan tema, tetapi juga menata pengalaman batin secara progresif, sehingga pembaca dapat mengikuti perjalanan spiritual penyair dari titik nol pra-eksistensi hingga puncak maqām spiritual.
1. Dermaga: Titik Awal dan Pra-Eksistensi
Dermaga (“1”) menandai titik awal perjalanan roh, ketika eksistensi manusia masih dalam potensi sebelum lahir ke dunia jasadi. Dalam puisi-puisi bagian ini, Kuswaidi menekankan kesendirian roh dan ketergantungan penuh pada Firman Tuhan:
…..
Tak ada air api tanah dan udara
Bahkan sunyi pun tak menjelma
Karena segalanya belum bermula
…..
Dermaga berfungsi sebagai simbol pra-eksistensi (keadaan di mana roh menunggu manifestasi dunia material), serta kesadaran awal yang murni. Bagian ini menghadirkan atmosfer kontemplatif, menyiapkan pembaca untuk menyelami perjalanan batin yang lebih kompleks di tahap berikutnya.
2. Samudera: Ujian, Pembersihan, dan Transformasi
Samudera (“1”) merepresentasikan fase ujian spiritual dan purifikasi batin, di mana manusia dihadapkan pada kesulitan, kebingungan, dan ketidakpastian. Kuswaidi menulis:
…..
Kini aku terlahir lagi
Entah yang ke berapa kalinya
Bermata buta
Bertelinga tuli
Bermulut bisu
Bernafas dungu
Tercampak di rimba hutan yang ultrahetrogen
…..
Pada tahap ini, penyair menggambarkan kesadaran akan keterbatasan diri dan perlunya berserah total kepada Tuhan. Samudera menjadi metafora ujian yang membentuk karakter spiritual, di mana setiap penderitaan, kebingungan, atau kegagalan menjadi sarana untuk menapaki maqām ma’rifat. Puisi-puisi bagian ini menekankan bahwa transformasi batin terjadi melalui pengalaman ekstrem, selaras dengan prinsip sufistik klasik: manusia hanya dapat memahami hakikat Tuhan setelah melewati proses purifikasi dan ujian.
3. Pulau Impian: Persandingan, Fana’, dan Baqā’
Pulau Impian (“31”) merupakan puncak perjalanan spiritual, di mana manusia mengalami persandingan langsung dengan Tuhan. Kuswaidi menulis:
…..
Inilah totalitas tawakkalku
Inilah totalitas keislamanku
…..
Pada tahap ini, konsep fana’–baqā’ menjadi nyata: hilangnya kesadaran diri (fana’) berpadu dengan keberadaan abadi dalam Tuhan (baqā’). Pulau Impianmelambangkan keutuhan spiritual dan kesatuan dengan yang absolut, di mana segala dualitas duniawi sirna dan penyair mencapai maqām tertinggi. Struktur ini menegaskan bahwa trilogi ini bukan hanya estetis, tetapi juga esoterik, menunjukkan kesinambungan perjalanan batin dari awal hingga akhir yang terarah dan reflektif.
4. Signifikansi Trilogi dalam Konteks Sastra Indonesia
Susunan trilogi ini menunjukkan bahwa Kuswaidi berhasil mengintegrasikan estetika puisi modern dengan tradisi sufistik klasik, yang menekankan progresi maqām dan pengalaman batin secara sistematis. Hal ini jarang ditemui dalam puisi Indonesia modern, di mana penyair cenderung menulis puisi spiritual secara fragmentaris atau tematis tanpa menata perjalanan batin secara berjenjang. Trilogi ini menegaskan bahwa puisi dapat menjadi medium refleksi spiritual sekaligus struktur naratif yang memandu pembaca melalui maqām sufistik, dari kesadaran awal hingga puncak pengalaman mistik.
III. Intensitas Dialog Langsung “Aku–Engkau”: Memadatkan Ekstase menjadi Struktur Estetik
Dalam Tarian Mabuk Allah, Kuswaidi Syafi’ie menghadirkan pengalaman spiritual melalui dialog berulang antara subjek penyair dan Tuhan. Penggunaan frase repetitif “Kekasih duhai Kekasih!” bukan sekadar retorika emosional, melainkan mekanisme estetik yang memadukan ekstase spiritual menjadi bentuk yang dapat dibaca. Puisi tasawuf di sini bukan hanya ungkapan perasaan, melainkan struktur yang menata intensitas pengalaman batin.
A. Argumen: Hilangnya Jarak Ontologis
Repetisi frasa ini menegaskan kaburnya batas antara “Aku” manusia dan “Engkau” Ilahi, menyerupai konsep jam’ dalam sufisme: penyatuan perspektif antara hamba dan Pencipta. Pengulangan menciptakan ritme internal puisi yang menyatukan pengalaman waktu dan ruang, membangun ekstase yang terstruktur.
Contoh dari bagian Dermaga (“1”) :
Kekasih duhai Kekasih!
Ketika itu sendiri Engkau mengandungku
Saat waktu beku di telapakMu
Menggenggam ‘sejarah’ dan ‘masa depan
…..
Frasa ini menunjukkan bahwa penyair tidak sekadar berbicara kepada Tuhan, tetapi menyelami keberadaan Tuhan yang memelihara dan mengandungnya. Pengalaman temporal yang melampaui linearitas (“waktu beku”) menandai fenomena khas ekstase sufistik.
Pengulangan frasa serupa dalam bagian Samudera (“1”) menegaskan proses lahir kembali spiritual:
Kekasih duhai Kekasih!
Kini aku terlahir lagi
Entah yang ke berapa kalinya
Bermata buta
Bertelinga tuli
Bermulut bisu
Bernafas dungu
Tercampak di rimba hutan yang ultrahetrogen
Tak mampu lagi mengeja huruf dan sandi
Yang Kau tebarkan di 1000 penjuru mata angin
Di Pulau Impian (“1”), dialog ini mencapai klimaks estetis, menampilkan persandingan hakiki:
Kekasih duhai Kekasih!
Seluruh sembah puji kusampaikan kepadaMu
Yang telah sudi mengundangku
Ke keteduhan pulau impian
Di mana kupu-kupu dan bunga abadi
Dalam persandingan hakiki
Frasa ini menegaskan ekstase sufistik sebagai ruang estetik, di mana kedekatan spiritual dapat dibaca dan dirasakan.
B. Bukti Puitik
Trilogi Kuswaidi membangun kohesi pengalaman spiritual melalui:
1. Dermaga: Kesadaran pra-eksistensi dan ketergantungan total pada Tuhan.
2. Samudera: Fana manusia di hadapan Ilahi, transformasi batin melalui ujian dan keterasingan.
3. Pulau Impian: Persandingan hakiki, klimaks pengalaman sufistik dan estetika puitik.
Repetisi frasa “Kekasih duhai Kekasih!” menyatukan seluruh trilogi menjadi struktur estetik yang memampatkan ekstase spiritual.
C. Analisis Reflektif-Argumentatif
Analisis puisi Kuswaidi dapat dikelompokkan dalam lima aspek utama:
1. Struktur Linguistik dan Ritme Sufistik
Pengulangan frasa menciptakan ritme meditatif yang menegaskan kesadaran transenden waktu dan ruang, menempatkan “Aku” melampaui linearitas temporal. Contoh dalam Dermaga “1”:
Kekasih duhai Kekasih!
Ketika itu sendiri Engkau mengandungku
…..
2. Ekstase Spiritual sebagai Tema Utama
Bagian Samudera (“1”) menampilkan pengalaman fana manusia, di mana identitas individu dilunturkan untuk mencapai ma’rifat:
Bermata buta
Bertelinga tuli
Bermulut bisu
Bernafas dungu
…..
3. Metafora dan Simbolisme
Pulau Impian (“1”) menjadi simbol persandingan hakiki:
…..
Ke keteduhan pulau impian
Di mana kupu-kupu dan bunga abadi
Dalam persandingan hakiki
…..
Metafora ini menghadirkan pengalaman spiritual secara langsung, memungkinkan pembaca merasakannya, bukan sekadar memahaminya.
4. Kesatuan Trilogi dan Perjalanan Spiritual
Trilogi membangun progresi sufistik:
Dermaga: Pra-eksistensi, kesadaran awal.
Samudera: Pengabdian total, ekstase, fana.
Pulau Impian: Persandingan hakiki, klimaks pengalaman spiritual.
Koherensi trilogi menegaskan puisi sebagai struktur pengalaman sufistik yang diestetikakan.
5. Argumen Reflektif
Puisi Kuswaidi adalah medium estetika untuk menegaskan hubungan manusia–Tuhan. Repetisi, simbolisme, dan ritme puitik memampatkan ekstase sufistik menjadi pengalaman imersif dan intens, yang dapat dibaca, direnungkan, dan dirasakan.
IV. Keberanian Mengekspresikan Ma’rifat: Puisi sebagai Teologi Cermin
Puisi-puisi Kuswaidi Syafi’ie dalam Tarian Mabuk Allah menempuh jalur yang jarang dilakukan penyair kontemporer: mengekspresikan ma’rifat(pengenalan hakikat Tuhan) melalui bahasa puitik yang jernih, konkret, dan mudah dihayati. Trilogi Dermaga, Samudera, dan Pulau Impian menampilkan perjalanan spiritual dari keterasingan eksistensial hingga persandingan hakiki dengan Tuhan. Dalam konteks ini, puisi bukan sekadar ungkapan estetika atau emosi, tetapi medium reflektif dan teologis, yang mengubah abstraksi metafisika menjadi pengalaman konkret yang puitis.
A. Argumen: Teologi Cermin dalam Bahasa Puitik
Kuswaidi menuliskan teologi cermin dengan bahasa langsung, gamblang, dan jernih: langkah yang jarang ditempuh penyair lain. Dalam tradisi sufistik, manusia dianggap sebagai cermin sifat-sifat Tuhan; Kuswaidi menghadirkan konsep ini bukan sebagai istilah teknis atau simbol sulit, melainkan sebagai pengalaman estetis yang dapat dibaca dan dirasakan. Contoh dari bagian Dermaga “7” :
“Aku rindu wajahKu sendiri”
FirmanMu mempesona
“Karena itu Kuletakkan secuil jiwaKu
Persis di hadapanKu
Sebagai cermin agar tak pilu”
Bait ini menunjukkan interaksi personal antara jiwa dan Ilahi, di mana “cermin” berfungsi sebagai simbol refleksi diri yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Pengalaman ma’rifat muncul sebagai pengalaman visual dan emosional yang dapat diakses pembaca.
Keberanian Kuswaidi juga terlihat dalam penghilangan dualitas:
“Di dalam diriKu tak ada perbedaan
Api menyatu dengan air
Atas menggumpal dengan bawah
Dan merah sama dengan hijau”
…..
(Dermaga “19”)
Bait ini menegaskan kesatuan hakiki, di mana segala oposisi duniawi dilebur, menandakan pengalaman ma’rifat yang menyeluruh. Puisi menjadi medium untuk menyalurkan pengalaman sufistik secara reflektif, memungkinkan pembaca masuk ke ruang spiritual yang biasanya dicapai melalui meditasi mendalam.
B. Bukti Puitik: Ekspresi Ma’rifat yang Gamblang
Bahasa Kuswaidi sederhana namun padat makna, menyajikan pengalaman spiritual sebagai citraan puitik konkret. Contoh lain dari Dermaga (“7”):
“Aku rindu wajahKu sendiri”
FirmanMu mempesona
“Karena itu Kuletakkan secuil jiwaKu
Persis di hadapanKu
Sebagai cermin agar tak pilu”
Bait ini menegaskan implementasi teologi cermin Ibn ‘Arabi: manusia sebagai refleksi sifat Ilahi. Kesadaran simultan antara identitas diri dan keberadaan Ilahi memungkinkan ma’rifat muncul secara visual dan emosional.
Di bagian Samudera (“30”), Kuswaidi menekankan pengabdian total dan fana:
Kekasih duhai Kekasih!
Dalam keadaan berjubah gila
Kulebur kebahagiaan dengan dukana
Hingga ketiadaan dan kekosongan menganga
Mengisyaratkan adaMu semata
(Telanjang raga telanjang jiwa
Tercengang pada hakekat Mahanyata)
Proses fana ini menunjukkan bagaimana manusia menjadi cermin kesatuan hakiki, membiarkan dualitas hilang dan sepenuhnya terserap dalam pengalaman Ilahi.
Pada Pulau Impian (“20”), ma’rifat dicapai melalui persandingan hakiki dengan Tuhan:
Kekasih duhai Kekasih!
Walau begitu banyak kafilah pencintaMu
Kutahu cintaMu kepadaku
Tidak akan pernah terbagi
Karena hakekat keutuhanMu
Tak akan pernah terkurangi oleh apa pun
…..
Bait ini menegaskan pengalaman ma’rifat yang personal, total, dan menyeluruh, sekaligus menampilkan keutuhan Ilahi yang tak terbagi.
C. Pembahasan: Perjalanan Spiritual dan Medium Puitik
Trilogi Kuswaidi membagi pengalaman sufistik menjadi tiga tahap:
1. Dermaga: Kesadaran awal, pengenalan diri, dan refleksi hakikat Ilahi. Manusia menjadi cermin sifat Tuhan, pengalaman ma’rifat hadir secara konkret.
2. Samudera: Pengabdian total dan ekstase spiritual. Fana manusia memungkinkannya menyatu dengan Ilahi, meleburkan dualitas, dan menegaskan kesatuan hakiki.
3. Pulau Impian: Persandingan hakiki dengan Tuhan, di mana cinta Ilahi absolut dan total. Manusia menjadi medium refleksi sifat Ilahi, tanpa kehilangan identitas spiritualnya.
Melalui ketiga tahap ini, Kuswaidi menunjukkan keberanian teologis: mengekspresikan gagasan metafisika yang kompleks ke dalam bahasa yang jernih dan puitis. Puisi menjadi medium pengalaman ma’rifat yang konkret, emosional, dan estetis, memungkinkan pembaca merasakan ekstase spiritual secara langsung, bukan sekadar memahaminya secara konseptual.
V. Puisi sebagai “Ontologi Rasa”: Filsafat Islam yang Mengalir sebagai Pengalaman Batin
Puisi Kuswaidi Syafi’ie dalam Tarian Mabuk Allah menghadirkan pengalaman metafisika Islam melalui bahasa rasa, bukan konsep akademik. Dalam karyanya, pengalaman batin manusia (rasa, syukur, rindu, dan pengosongan diri) menjadi medium untuk menyentuh hakikat Tuhan. Dengan demikian, puisi berfungsi sebagai ontologi rasa: filsafat yang hidup, mengalir, dan dapat dirasakan, sekaligus menjadi panduan batin bagi pembaca yang menempuh jalan spiritual.
A. Argumen
Puisi Kuswaidi Syafi’ie menampilkan cara unik dalam menyampaikan konsep-konsep metafisika Islam, seperti tajalli (manifestasi Tuhan), asma’ (nama-nama Tuhan), dzat (Hakikat Tuhan), Kun (perintah mencipta), dan jamal–jalal(keindahan–kekuasaan Tuhan), tanpa memaparkannya secara teoretis atau akademik. Alih-alih menjadi teks kering yang bersifat konseptual, puisinya dialirkan sebagai pengalaman batin yang afektif. Hal ini menjadikannya bukan hanya sebagai puisi religius, tetapi juga filsafat yang hidup dan dapat dirasakan langsung melalui “rasa” atau pengalaman batin pembaca.
Kuswaidi memindahkan abstraksi metafisika menjadi sesuatu yang dialami, dirasakan, dan diserap melalui perasaan. Sebagai contoh, ia menulis:
…..
Tak ada air api tanah dan udara
Bahkan sunyi pun tak menjelma
…..
(Dermaga, “1”)
Dan:
…..
“Di antara kaf dan nun
Kuciptakan rahaim bagi segalanya
KuasaMu menggegar tak tertabiri apa pun”
…..
(Dermaga, “3”)
Dua kutipan ini menegaskan bagaimana gagasan metafisika yang tinggi, yang biasanya bersifat spekulatif atau filosofis, dialirkan ke pengalaman batin, sehingga pembaca dapat “merasakan” eksistensi Tuhan melalui intensitas pengalaman rasa, bukan sekadar memahami secara intelektual.
B. Bukti Puitik
Dalam puisi-puisi Kuswaidi Syafi’ie, pengalaman metafisika Islam diwujudkan melalui bahasa batin yang intens dan puitis. Hal ini terlihat jelas pada bait-bait yang menggambarkan pengalaman “tajalli” atau manifestasi Tuhan dalam kesadaran batin penyair. Sebagai contoh, Kuswaidi menulis:
Ombak lautMu menderu-deru
Ngungun dalam kemabukan cinta
Yang teramat indah sekaligus mengerikan
…..
(Dermaga, “11”)
Kalimat ini tidak hanya mengekspresikan pengalaman pencerahan spiritual, tetapi juga memperlihatkan bagaimana konsep metafisika (cahaya, tajalli, kehadiran Tuhan, yang biasanya abstrak) diubah menjadi pengalaman afektif yang dapat dirasakan pembaca. Kata “indah sekaligus mengerikan” menegaskan intensitas tajalli; bukan sekadar pengamatan pasif, tetapi keterlibatan seluruh jiwa.
Lebih lanjut, Kuswaidi menegaskan pengalaman–penciptaan-Ilahi melalui bait lain:
…..
Sejak semula mulutku suling firmanMu
Membelai lembah-lembah dan bebukitan
Dengan rinai syahdu suara Daud
…..
(Dermaga, 16)
Di sini, firman Tuhan dialami bukan sebagai teks atau konsep, tetapi sebagai aliran batin yang hidup melalui tubuh manusia. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana puisi berfungsi sebagai ontologi rasa: manusia mengalami realitas Tuhan secara langsung melalui indera batin dan pengalaman puitik.
Kedua kutipan ini menegaskan strategi Kuswaidi dalam menyampaikan filsafat Islam yang mengalir: metafisika yang tinggi tidak hanya dijelaskan, tetapi dialami. Pengalaman spiritual yang dihidupkan melalui bahasa puitis memungkinkan pembaca turut merasakan keterhubungan antara manusia dan Tuhan, sekaligus memahami konsep-konsep seperti tajalli, Kun, dan jamal–jalaldalam konteks yang emosional, bukan semata-mata rasional.
Dengan demikian, puisi Kuswaidi tidak hanya menjadi karya sastra, tetapi juga medium filsafat hidup: menghidupkan pengalaman batin, memanifestasikan kesadaran metafisika, dan memungkinkan rasa sebagai jalan untuk memahami hakikat Tuhan.
C. Pembahasan
Puisi Kuswaidi menunjukkan bahwa pengalaman batin dapat menjadi wahana filsafat Islam yang mengalir, bukan filsafat akademik yang kering. Hakikat Tuhan dan realitas manusia dipahami melalui rasa yang hidup, bukan hanya melalui akal. Contoh, dari Dermaga “7”:
“Aku rindu wajahKu sendiri
Karena itu Kuletakkan secuil jiwaKu
Persis di hadapanKu
Sebagai cermin agar tak pilu”
Bait ini memindahkan kesadaran Ilahi ke ranah pengalaman manusia melalui metafora cermin. Jiwa yang diletakkan sebagai cermin menunjukkan hubungan reflektif antara manusia dan Tuhan; manusia menjadi medium penghayatan tajalli Ilahi. Rasa rindu dan kehadiran jiwa menjadikan metafisika konkret, dapat dirasakan pembaca, sekaligus menekankan totalitas pengabdian dan kesadaran spiritual.
Lebih lanjut, pengalaman afektif ini melibatkan seluruh dimensi eksistensi manusia:
Sebagai setetes air
Aku juga ikut melambung
Menuju kebiruan dan kebeningan langit
O di manakah langitku duhai Kekasih
Jika tidak bertapa dalam diriMu?
…..
(Dermaga, 16)
“Setetes air” melambangkan kecilnya manusia di hadapan kebesaran Ilahi, sementara langit yang dibayangkan hanya dapat dicapai melalui keterhubungan batin dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan filsafat yang dihadirkan Kuswaidi mengalir, dialami, dan menyatu dengan seluruh sensasi batin manusia.
Dengan demikian, puisi-puisi Kuswaidi menjadi “ontologi rasa”: realitas Tuhan dan manusia tidak hanya dipahami, tetapi dihayati. Setiap kata, metafora, dan citraan berfungsi sebagai medium pengalaman batin, memungkinkan pembaca mengalami konsep metafisika seperti tajalli, Kun, jamal–jalal, dan asma’ secara langsung. Proses ini menjadikan puisi sebagai filsafat hidup: menuntun pembaca untuk tidak hanya mengerti Tuhan secara intelektual, tetapi juga merasai keberadaan-Nya melalui pengalaman spiritual yang personal dan afektif.
VI. Perpaduan Tradisi Pesantren dan Estetika Modern
Dalam karya Kuswaidi Syafi’ie, tradisi pesantren bukan sekadar latar pendidikan atau identitas, tetapi menjadi pondasi spiritual yang melahirkan estetika puisi. Puisi-puisinya menampilkan integrasi antara figur Qur’ani, bahasa Arab klasik, dan bahasa Indonesia modern yang lentur. Transformasi ini menciptakan jembatan antara kesalehan tradisional dan kepekaan modern, sehingga pembaca dapat menyelami pengalaman sufistik tanpa merasa teralienasi oleh bahasa atau konsep klasik. Kuswaidi tidak hanya mengulang kisah-kisah religius; ia menafsirkan pengalaman spiritualnya secara personal dan kontemporer, membuktikan bahwa tradisi pesantren dan inovasi modern dapat bersinergi harmonis.
A. Argumen
Kuswaidi menyatukan tiga dimensi utama dalam puisinya:
1. Kisah Qur’ani sebagai medium pengalaman batin
Figur-figur seperti Ibrahim, Ayyub, Nuh, dan Isa muncul sebagai simbol pencarian spiritual dan pengorbanan. Misalnya, dalam Samudera “23”:
Kuundang topan yang menghantam perahu Nuh
Kupanggil kobaran api yang menjilat Ibrahim
Kuseru 20 tahun derita Ayyub
Kuingin selaksa kepedihan Ya’kub
Kudamba seluruh genangan airmata Isa
…..
Kutipan ini menampilkan pengalaman religius yang intens, di mana kisah klasik Qur’ani menjadi medium refleksi afektif dan estetis.
2. Bahasa Arab klasik sebagai simbol metafisik
Kata-kata seperti arsy, nur, ruh, dan istilah sufistik menegaskan kedalaman spiritual. Dalam Dermaga “1”: “…// Hanya Kau bersemayam di atas ‘arsy sendirian / Mendendangkan lagu-lagu kasmaran”.
Bahasa Arab ini menjadi jembatan antara pengalaman mistik dan bahasa modern, memungkinkan pembaca kontemporer merasakannya secara afektif.
3. Bahasa Indonesia modern yang lentur
Bahasa sehari-hari dipadukan dengan istilah klasik, menghasilkan pengalaman komunikatif dan memikat. Contohnya dalam Pulau Impian “4”: “…/ Di kesunyian jiwaku / Ada getar rindu yang tak mungkin berakhir / Ada mekar senyum yang tak mungkin beku / Ada gerlap cahaya yang tak mungkin redup / Ada taman kenangan yang tak mungkin sirna/...”
Bahasa modern memungkinkan pembaca merasakan emosi dan pengalaman spiritual secara langsung, tanpa kehilangan resonansi religius yang mendalam.
Gabungan tiga dimensi ini membuktikan bahwa Kuswaidi membangun ruang estetika yang menyeimbangkan tradisi pesantren dengan ekspresi modern, sehingga karya-karyanya tetap relevan bagi pembaca kontemporer tanpa mengurangi akar spiritualnya.
B. Bukti Puitik
Beberapa kutipan dari ketiga bagian puisi menunjukkan konsistensi integrasi ini:
1. Dermaga:
“Kutelusuri jejak Ibrahim dalam kobaran sunyi” (Dermaga “23”)
Figur Qur’ani ditempatkan dalam pengalaman kontemporer, bahasa modern kutelusuri menghidupkan narasi spiritual.
2. Samudera:
“…/ Dalam keadaan berjubah gila / Kulebur kebahagiaan dengan dukana / Hingga ketiadaan dan kekosongan menganga / Mengisyaratkan adaMu semata/ …” (Samudera “30”)
Pengalaman sufistik ekstrem ini menggabungkan paradoks antara gila dan bahagia, ketiadaan dan keberadaan, dengan tetap menjaga konteks spiritual Qur’ani.
3. Pulau Impian:
“…/ Walau begitu banyak kafilah pencintaMu / Kutahu cintaMu kepadaku / Tidak akan pernah terbagi / Karena hakekat keutuhanMu / Tak akan pernah terkurangi oleh apa pun//…” (Pulau Impian “20”)
Penyair menekankan pengalaman personal modern, tetapi tetap berpijak pada kesalehan tradisi: keutuhan cinta Ilahi sebagai pusat seluruh pengalaman manusia.
C. Analisis Mendalam
1. Akar pesantren yang kuat
Simbol-simbol Qur’ani dan bahasa Arab klasik menegaskan bahwa karya Kuswaidi tumbuh dari pondasi spiritual yang kokoh. Tradisi pesantren memberikan kedalaman otentik, menjadikan puisi medium ma’rifat dan pengalaman batin, bukan sekadar hiburan estetis.
2. Keberanian inovatif
Dengan bahasa Indonesia modern yang fleksibel, Kuswaidi mengkomunikasikan pengalaman sufistik yang kompleks. Pembaca kontemporer tidak teralienasi oleh istilah klasik, tetapi merasakan intensitas pengalaman spiritual secara langsung.
3. Dialog klasik-kontemporer
Integrasi figur Qur’ani, simbol Arab, dan bahasa modern menciptakan ruang estetika trans-temporal. Tradisi pesantren dan inovasi modern bukan oposisi, tetapi saling memperkaya. Hal ini membuktikan bahwa puisi religius dapat relevan bagi pembaca modern tanpa kehilangan kedalaman tradisi.
Puisi Kuswaidi Syafi’ie memperlihatkan kesadaran estetika yang matang, di mana pengalaman spiritual dipadukan dengan inovasi bahasa, menjadikan karya yang kaya, hidup, dan penuh resonansi batin.
VII. Gaya Puitik: Ekstase, Kesunyian, dan Ontologi
Puisi-puisi Kuswaidi Syafi’ie dalam Tarian Mabuk Allah menghadirkan pengalaman batin yang intens, di mana ekstase dan kesunyian menjadi medium dialog dengan Kekasih Ilahi. Ritme askensional (ascensional rhythm), metafora vertikal, dan invokasi berulang bukan sekadar hiasan puitik, melainkan sarana eksistensial untuk menegaskan kesatuan jiwa dengan Tuhan: “…// Hanya Kau bersemayam di atas ‘arsy sendirian / Mendendangkan lagu-lagu kasmaran”(Dermaga “1”).
Kuswaidi membangun keseimbangan antara kemabukan ekstase spiritual dan fondasi ontologis yang kuat, menuntun pembaca pada refleksi mendalam. Kesunyian yang ia hadirkan bukan kekosongan pasif, melainkan ruang batin untuk pengalaman ontologis dan kontemplatif.
A. Sintesis Mistisisme dan Kesadaran Metafisik
Gaya puitik Kuswaidi merupakan sintesis antara pengalaman mistik dan kesadaran metafisik. Ia menampilkan beberapa strategi puitik:
1. Invokasi berulang, menegaskan intensitas doa dan permohonan.
2. Ritme askensional, mengangkat jiwa menuju kesadaran absolut.
3. Metafora vertikal, menghubungkan langit, tajalli, dan arsy sebagai simbol ketidakbergantungan manusia terhadap materi.
4. Dialog batin intens, memungkinkan interaksi langsung dengan Kekasih Ilahi.
Dimensi vertikal ini menguatkan pengalaman mistik secara konkret, seperti terlihat dalam kutipan berikut: “…// Hanya Kau bersemayam di atas ‘arsysendirian / Mendendangkan lagu-lagu kasmaran” (Dermaga “1”).
Di sini, ‘arsy bukan sekadar simbol metafisik, melainkan titik fokus ascensional yang mengundang pembaca menapaki pengalaman ontologis serupa.
Invokasi berulang juga memperlihatkan ketekunan spiritual penyair:“Kekasih duhai Kekasih! / Kini aku terlahir lagi / Entah yang ke berapa kalinya/ …” (Samudera “1”)
Ritme batin yang naik seolah membawa pembaca mengikuti perjalanan jiwa menuju kesadaran absolut.
B. Metafora dan Kontradiksi Puitik
Pengalaman batin semakin diperkuat melalui metafora dan kontradiksi khas Kuswaidi:
1. “…/ Menuju kebiruan dan kebeningan langit/ O di manakah langitku duhai Kekasih/ …” (Dermaga “16”)
Menegaskan orientasi vertikal dari bumi menuju langit, simbol tajalli dan pengangkatan jiwa.
2. “Ombak lautMu menderu-deru/ Tak terbilang tahun tak terbilang abad/ Ngungun dalam kemabukan cinta/ Yang teramat indah sekaligus mengerikan//…” (Dermaga “11”).
Menunjukkan intensitas ekstase batin; pengalaman spiritual tidak selalu nyaman, tetapi penuh ketegangan ontologis.
3. “Sebagai setetes air / Aku juga ikut melambung / Menuju kebiruan dan kebeningan langit/…” (Dermaga “16”).
Menegaskan perpaduan askensional dan ekstase, di mana subjek penyair lebur dalam keseluruhan kosmik sebagai bentuk penyatuan dengan realitas transenden.
Kuswaidi menyeimbangkan diksi sufistik yang pekat dengan fondasi metafisik yang kokoh, sehingga puisinya tidak jatuh menjadi sentimental atau hiper-emotif.
C. Kesunyian sebagai Medium Ontologis
Kesunyian yang dihadirkan Kuswaidi menjadi medium untuk refleksi ontologis. Dalam bagian Pulau Impian, ia menulis: “…/ Di kesunyian jiwaku / Ada getar rindu yang tak mungkin berakhir / Ada mekar senyum yang tak mungkin beku/ …” (Pulau Impian “4”).
Kesunyian di sini bukan sekadar diam, melainkan sarana untuk merasakan ekstase dan penyatuan dengan yang Mahatinggi. Ekstase, kesunyian, dan ontologi berpadu membentuk sintesis utuh, menantang pembaca merenungkan keberadaan manusia di hadapan realitas transenden.
Dengan demikian, gaya puitik Kuswaidi Syafi’ie menekankan pengalaman spiritual sebagai perjalanan batin yang kompleks, di mana estetika lahir dari tradisi pesantren dan tafsir kontemporer, serta menghadirkan pengalaman mistik yang dapat dihayati secara langsung oleh pembaca.
VIII. Kesimpulan: Sumbangan Estetik-Spiritual Kuswaidi bagi Puisi Indonesia
Kuswaidi Syafi’ie menegaskan bahwa puisi tidak sekadar medium simbolisme spiritual, tetapi dapat berfungsi sebagai suluk batin: jalur pengalaman ontologis yang menuntun pembaca pada pertemuan dengan Kekasih Ilahi. Dalam karya-karyanya, bahasa bukan hanya sarana komunikasi, melainkan medan eksistensi: tempat ekstase berpadu dengan kesunyian, ritme askensional membimbing jiwa, dan metafora vertikal menghubungkan manusia dengan realitas transenden. Setiap bait, setiap pengulangan invokasi, menegaskan dialog batin yang intens, sekaligus menuntun pembaca pada kontemplasi spiritual yang mendalam.
Estetika Kuswaidi lahir dari sintesis tradisi pesantren, pengalaman sufistik, dan kesadaran modern. Puisinya menunjukkan bagaimana ekstase batin dapat diwujudkan secara puitik tanpa kehilangan keteguhan metafisik. Misalnya, ungkapan “…// Hanya Kau bersemayam di atas ‘arsy sendirian / Mendendangkan lagu-lagu kasmaran” (Dermaga “1”) tidak sekadar simbol, tetapi titik fokus pengalaman ontologis, mengajak pembaca menapaki ruang spiritual yang konkret dan terasa.
Kesunyian yang hadir dalam karya-karya Kuswaidi, misalnya di Pulau Impian “4”, menjadi medium di mana ekstase dan kesadaran iman saling meneguhkan: “…/ Di kesunyian jiwaku / Ada getar rindu yang tak mungkin berakhir / Ada mekar senyum yang tak mungkin beku/…”.
Dari sisi kontribusi terhadap puisi Indonesia, Kuswaidi memperluas batas kemungkinan bahasa puitik dengan menjadikannya sarana pengalaman metafisis yang dapat dirasakan, bukan sekadar dipahami. Ia menekankan bahwa estetika puitik dan pengalaman spiritual dapat menyatu secara harmonis, menciptakan karya yang indah secara linguistik sekaligus menggetarkan batin. Melalui puisi-puisinya, pembaca diajak memasuki ruang di mana kata menjadi jembatan menuju Tuhan: sebuah tradisi sufistik yang jarang dijumpai dalam puisi kontemporer Indonesia.
Dengan demikian, sumbangan Kuswaidi bersifat ganda dan mendalam: ia menghadirkan estetika puitik yang memikat sekaligus memperkaya tradisi spiritual dalam sastra Indonesia modern. Puisi-puisinya menjadi bukti bahwa pengalaman batin dan refleksi ontologis dapat diwujudkan melalui bahasa, menjadikan karya-karyanya sumber inspirasi sekaligus model estetika-spiritual bagi generasi penyair selanjutnya.***
Daftar Pustaka
Aan Mansyur, M. 2015. Melihat Api Bekerja. Makassar: Gramedia.
Al-Qusyairi, Abu al-Qasim. 1983. Risālah Qusyairī. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Bachri, Sutardji Calzoum. 1981. O Amuk Kapak. Jakarta: Sinar Harapan.
Blog Kepada Puisi. 2013, Juli 8. “Kuswaidi Syafi’ie: Tarian Mabuk Allah.” Diakses dari https://kepadapuisi.blogspot.com/2013/07/tarian-mabuk-allah.html?m=1
Chittick, William C. 1989. The Sufi Path of Knowledge: Ibn ‘Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany: State University of New York Press.
Faruk, Dr. 2003. “Kesendirian dan Kebersamaan” [Prolog]. Dalam Tarian Mabuk Allah: Kumpulan Puisi Tasawuf oleh Kuswaidi Syafi’ie, xx–xxi. Yogyakarta: Pustaka Sufi.
Hadi W.M., Abdul. 1976. Meditasi. Jakarta: Balai Pustaka.
Hadi W.M., Abdul. 1984. Cermin. Jakarta: Budaya Jaya.
Hadi W.M., Abdul. 2004. Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas: Esai-esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa. Yogyakarta: Matahari.
Ibn ‘Arabī, Muhyiddin. 1990. Fusūs al-Hikam. Beirut: Dar Sadr.
Imron, D. Zawawi. 1986. Celurit Emas. Surabaya: Penerbit Bintang.
Kuntowijoyo. 1975. Suluk Awang-Uwung. Jakarta: Budaya Jaya.
Mashuri. 2018. Dangdut Makrifat. Yogyakarta: Basabasi.
Nadjib, Emha Ainun. 1980. 99 Untuk Tuhanku. Bandung: Pustaka Salman ITB.
Pane, Sanusi. 1931. Madah Kelana. Jakarta: Balai Pustaka.
Schimmel, Annemarie. 1975. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Syafi’ie, Kuswaidi. 2000. Munajat Bukit Cahaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafi’ie, Kuswaidi. 2002. Menggenggam Batu Jadi Permata: Relasi Allah dan Manusia dalam Puisi-puisi Muhammad Iqbal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafi’ie, Kuswaidi. 2002. Pohon Sidrah: Kumpulan Puisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafi’ie, Kuswaidi. 2003. Tarian Mabuk Allah: Kumpulan Puisi Tasawuf. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Sufi.
—-
*Abdul Wachid B.S., Penyair, Guru Besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.