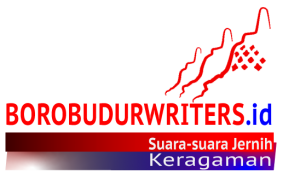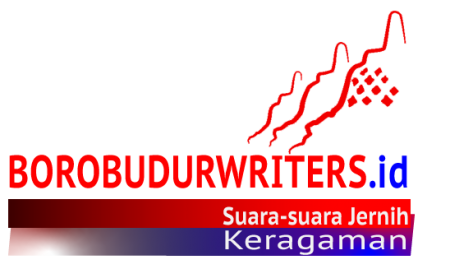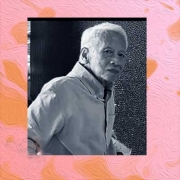Teguh Trianton dan Estetika Babad Batin: Puisi sebagai Sejarah Kesadaran Manusia
Oleh: Abdul Wachid B.S.*
1. Pendahuluan: Babad Sebagai Laku Kesadaran
Di tengah arus perpuisian kontemporer yang seringkali mengedepankan bentuk eksperimen atau permainan bahasa sebagai tujuan estetis, muncul sebuah korpus yang dengan tenang (hampir ritual) menulis kembali sejarah batin. Babad Tulah (Magelang: Tidar Media, 2020) karya Teguh Trianton, Babad Tulah hadir bukan sekadar sebagai kumpulan sajak; ia tampil sebagai suatu usaha penulisan ulang (rekonstruksi) atas luka, cinta, dan silsilah batin yang menegaskan kembali bahwa puisi bisa berfungsi sebagai arsip jiwa. Dalam pengantarnya sendiri Trianton menyebut kata rekonstruksi dan menegaskan kepentingan gramatika serta diksi demi agar “sajak mesti dapat menyampaikan sesuatu”. Dari sini muncul pernyataan tesis esai ini: bahwa karya Trianton menegakkan sebuah estetika yang layak kita sebut babad batin; bentuk penulisan yang menukar kronik politis atau genealogis menjadi kronik kesadaran, dan menempatkan puisi sebagai medium sejarah jiwa yang bergerak dari luka menuju penebusan.
Pendekatan penulisan Trianton mengundang kita melihat puisi bukan hanya sebagai fragmen perasaan, melainkan sebagai laku: sebuah praktik sadar yang menyeret pengalaman personal ke dalam bidang sejarah. Konsep babad di dalam tradisi Jawa menunjuk pada tradisi menulis sejarah dan silsilah yang sarat nilai moral, ritual, dan simbolik; tetapi ketika babad dibawa ke ranah batin, ia mengambil fungsi ganda: sebagai arsip ingatan kolektif sekaligus ladang ritual penyembuhan. Tafsiran ini mendapat sandaran konseptual bila kita menengok kembali gagasan-gagasan tentang memori dan narasi dalam teori kontemporer: misalnya ketika Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting menegaskan bahwa ingatan kolektif selalu terjalin dengan narasi yang memproduksi identitas (Ricoeur, 1991: 52). Dalam bahasa lain: menulis ingatan adalah menulis diri; menulis sejarah batin adalah menulis kemungkinan penebusan. Trianton melakukan hal yang serupa; ia menulis supaya luka dapat dibaca, ditaburi bahasa, dan kemudian, bila mungkin, ditambal lewat bahasa yang menebus.
Salah satu ciri yang membuat praktik penulisan Trianton berbeda adalah kesadaran tata bahasa sebagai medium rohani. Di pengantar Babad Tulah Trianton menyatakan bahwa sajak-sajaknya telah mengalami “rekonstruksi gramatikal” demi memperbaiki tegur sapa dengan pembaca. Pernyataan ini lebih dari soal teknis: ia menunjukkan keyakinan bahwa gramatika yang jelas menimbulkan keterbukaan makna; bahwa kata yang tertata rapi membuka jalan bagi pembaca memasuki ruang batin yang disakralkan. Di titik ini kita menemukan resonansi dengan gagasan Gaston Bachelard, The Poetics of Space (1994: 8), yang menempatkan ruang puitik sebagai lokasi imaji dan ingatan; ruang yang bukan hanya dipenuhi benda, melainkan juga gema sejarah batin yang memungkinkan ziarah imajinatif. Trianton menata kata seperti memperbaiki jalan di sebuah sendi memori; pembaca lalu dapat berjalan, tersesat, dan menemukan kembali diri di dalam sajak.
Bagaimana puisi Teguh Trianton membangun estetika babad batin melalui pilihan bahasa, jaringan citra, dan penataan tema-tema eksistensial (luka, cinta, penebusan)? Esai ini akan membaca Babad Tulah sebagai satu korpus yang sengaja menata fragmen-fragmen kehidupan (kereta, kopi, sungai, nisan, doa) menjadi babad yang berfungsi ganda: dokumenter dan sakral. Fragmen-fragmen itu, pada pembacaan Trianton, bukan kebetulan semata; mereka adalah alat genealogis yang mengubur dan sekaligus menyalakan masa lalu. Puisi seperti “Babad Tulah”, “Cinta adalah Luka”, “Dzikir Ikan”, dan sejumlah sajak lain berperan sebagai pasal-pasal kecil yang merajut silsilah batin; menghidupkan kembali istilah lokal seperti tulah, pamori, dan ritual sehari-hari menjadi tanda yang memanggil sakralitas.
Pendekatan esai ini bersifat interdisipliner: hermeneutika teks puitik dipadukan dengan teori memori dan kajian budaya lokal agar kita dapat menilai secara kritis sekaligus merasakan secara puitik apa yang dilakukan Trianton. Pembacaan akan bersifat kontekstual-lokal (mengaitkan teks dengan tradisi babad Jawa dan pengalaman Banyumas–Purwokerto) sekaligus bersifat universal (menghubungkan luka dan penebusan dengan kategori pengalaman manusiawi yang lebih luas). Esai ini mengadopsi pembacaan perhatian-tinggi terhadap detail bahasa (diksi, enjambement, ritme) sebagai tanda-tanda estetika yang membawa muatan etis dan ritual. Dengan demikian pendahuluan ini menempatkan pembaca pada dua tuntutan sekaligus: memahami Babad Tulah sebagai karya yang lahir dari akar lokal, dan mengakuinya untuk berbicara pada kondisi kemanusiaan yang lebih luas: sebuah babad batin yang menuliskan sejarah kesadaran manusia.
2.Teguh Trianton: Antara Laku Menulis dan Laku Menyadari
Membaca puisi Teguh Trianton tanpa menilik latar biografisnya adalah seperti menatap sebuah rumah tanpa mengetahui sejarah pembangunan fondasinya. Trianton lahir dan tumbuh di Banyumas–Purwokerto, sebuah ruang yang secara historis, kultural, dan religius sarat dengan praktik simbolik, ritual, dan cerita rakyat. Ruang ini bukan sekadar latar geografis, tetapi juga menyediakan jaringan pengalaman yang memengaruhi estetika dan tema puisi-puisinya. Ia menempuh pendidikan formal, mengajar di universitas, dan aktif menulis, namun sekaligus menjadikan pengalaman empiris sehari-hari (perjalanan kereta api, hujan, kopi, sawah, dan interaksi sosial) sebagai bahan refleksi batin. Dari titik ini, kita bisa memahami bagaimana laku menulis Trianton bersandingan dengan laku menyadari: menulis menjadi sarana sadar akan diri, ingatan, dan lingkungan.
Trianton sendiri menegaskan dalam pengantar Babad Tulah bahwa sajaknya mengalami proses rekonstruksi gramatikal, yang bukan hanya soal memperindah bahasa, tetapi sebagai ikhtiar memperbaiki “tegur sapa” dengan pembaca. Pernyataan ini menekankan bahwa menulis bagi Trianton adalah bentuk kesadaran yang aktif: setiap diksi, setiap enjambement, adalah bentuk dialog batin dengan pembaca dan sekaligus dengan dirinya sendiri. Konsep ini selaras dengan gagasan Mikhail Bakhtin dalam The Dialogic Imagination (1981: 279), yang menekankan bahwa bahasa selalu dialogis, bahwa makna muncul dalam interaksi teks dengan pembaca, dan bahwa penulis menulis sebagai respon terhadap dunia serta pengalaman orang lain. Dalam konteks Trianton, dialog ini bersifat ganda: ia menulis untuk melacak jejak batin sendiri sekaligus memanggil pembaca masuk ke dalam pengalaman spiritual dan reflektif itu.
Refleksi empiris yang diarahkan ke batin terlihat jelas dalam puisi “Ibu Menanam Kaki” (2019):
Ibu tidak pernah mengajariku merajang wortel,
tapi aku diam-diam mendekat, mengamati pisau
yang digunakan mengiris cabai dan bawang merah;
sampai mataku berair ketir.
…..
Observasi sederhana tentang ibu yang menanam cabai dan bawang diubah menjadi refleksi batin yang memuat gagasan tentang kerja, pengorbanan, dan kesinambungan hidup. Trianton tidak sekadar menulis apa yang dilihat; ia menulis untuk menyadari nilai-nilai yang tersembunyi di balik tindakan sehari-hari. Dengan demikian, puisi menjadi arsip batin yang mengaitkan pengalaman empiris dengan refleksi moral dan spiritual, yang khas bagi estetika babad batin.
Puisi lain, “Saat Cinta Sampai Stasiun” (2019), menunjukkan bagaimana pengalaman lokal dan sosial diarahkan ke refleksi eksistensial:
Aku mencintaimu dengan berjalan kaki
dari debar jantung menuju stasiun kereta; api,
dari stasiun ke tempat cinta dinyatakan
tanpa kata-kata.
…..
Di sini, perjalanan fisik dari satu ruang ke ruang lain disandingkan dengan perjalanan batin menuju pengakuan dan penerimaan cinta. Menulis menjadi metode epistemologis: pembaca diajak menelusuri peta kesadaran batin yang bersumber dari pengalaman konkret sehari-hari.
Laku menulis Trianton juga menekankan hubungan antara empiris dan spiritual. Dalam puisi “Vertigo” (2026-2020), misalnya:
apabila kepala telah diguncangkan
dengan guncangannya;
yang diam.
keseimbangan adalah; kursi-kursi sempoyongan,
tanah yang menari-nari, pohon berjalan sendiri-sendiri
langit turun merendah, matahari berpindah dari sisi ke sisi,
…..
Puisi ini bukan sekadar deskripsi gejala vertigo, tetapi refleksi tentang ketidakseimbangan batin dan eksistensial, di mana pengalaman fisik menjadi metafora bagi kesadaran manusia yang diguncang oleh peristiwa dan trauma. Pengalaman empiris (kepala yang diguncang, pohon, langit, matahari) diubah menjadi laboratorium batin untuk menafsirkan realitas psikologis dan spiritual.
Selain itu, Trianton memperlakukan menulis sajak sebagai metode untuk menyadari diri. Dalam “Aku Kangen Nafasmu” (2026-2020):
…..
lalu, kau pun memberikan nafasmu
untuk kuhirup seolah itu nafas terakhirmu
yang ingin kau tunaikan
untuk mengisi debar yang kosong
di paru dan takbirku
…..
Ia menulis tentang interaksi manusia sebagai pengalaman eksistensial yang menghubungkan tubuh, rasa, dan jiwa. Proses penulisan menjadi sarana memahami luka, kehilangan, dan cinta, sekaligus menata fragmen pengalaman menjadi narasi simbolik yang memberi kesadaran reflektif.
Pendekatan Trianton ini selaras dengan gagasan Paul Valéry dalam The Art of Poetry (1958: 22), bahwa puisi adalah laboratorium pemikiran batin: “Poetry is a form of knowledge; it organizes experience and consciousness” (“Puisi adalah bentuk pengetahuan; ia menata pengalaman dan kesadaran”). Trianton membuktikan hal ini melalui praktik sajak yang reflektif dan konseptual, di mana setiap citraan dan bahasa memuat sejarah lokal sekaligus universalisme pengalaman batin.
Dengan demikian, memahami Trianton tidak cukup hanya membaca puisinya; pembaca harus menelisik biografi kreatifnya dan laku menulisnya sebagai bentuk babad batin. Keterkaitan erat antara pengalaman ruang sosial, refleksi spiritual, dan rekonstruksi sajak membentuk corak khas puisi Trianton: ia menulis untuk menyadari, menyadari untuk menulis, dan keduanya menuntun pembaca menelusuri sejarah kesadaran manusia melalui pengalaman sehari-hari, simbol, dan refleksi batin.
3. Estetika Babad Batin: Bahasa Sebagai Ziarah
Bagi Teguh Trianton, puisi adalah bentuk ziarah batin yang menempuh sejarah manusia melalui bahasa. Konsep ini sejalan dengan makna babad dalam tradisi Jawa, yang tidak semata-mata kronik peristiwa, tetapi genealogis dan spiritual: rekaman perjalanan hidup, konflik, cinta, dan pengorbanan manusia. Zoetmulder dalam Kalangwan (1985) menegaskan bahwa babad merupakan catatan sejarah yang berlapis, menghubungkan peristiwa dengan nilai moral dan ajaran spiritual. Hal ini diperkuat oleh Mulder (Mysticism in Java, 1999) yang menekankan bahwa babad tidak hanya memotret sejarah sosial, tetapi juga perjalanan batin manusia. Trianton mengambil warisan ini sebagai pijakan estetikanya, meminjam struktur genealogis babad untuk menulis puisi yang menjadi arsip reflektif batin.
Bahasa puitik Trianton berfungsi sebagai sarana mengingat dan menebus masa lalu, seperti gagasan Paul Ricoeur dalam Memory, History, Forgetting (1991: 43) tentang poetic memory. Ricoeur menekankan bahwa memori puitis memungkinkan penulis tidak sekadar merekam, tetapi juga menafsirkan kembali pengalaman masa lalu, menyusunnya menjadi makna yang relevan bagi kesadaran kini. Trianton mewujudkan gagasan ini dalam sajaknya, di mana citraan sehari-hari (hujan, kopi, kereta, pohon bambu) diubah menjadi arsip reflektif tentang pengalaman manusiawi dan spiritual.
Puisi “Babad Tulah” (2020) menjadi contoh paling jelas. Misalnya:
…..
Seperti percuma. Kau mesti terus menjaga api pada
tungku yang dingin, lantaran suluhnya urung dinyalakan.
Sampai hangus batinmu oleh titah yang kau terima
sebagai tuah paling magma…..
Bahasa di sini sarat simbol: “tungku yang dingin” dan “tuah paling magma” bukan hanya deskripsi fisik, tetapi metafora sejarah batin, penderitaan, dan tanggung jawab manusia terhadap warisan moral. Trianton menulis ulang pengalaman yang bersifat genealogis (mewarisi perintah, kesalahan, dan luka masa lalu) menjadi refleksi sadar tentang bagaimana manusia menata kesadaran batin. Ini adalah praktik ziarah bahasa, di mana penyair mengunjungi memori, menafsirkan pengalaman, dan menghadirkan makna baru.
Puisi “Vertigo” (2016-2020) juga menegaskan peran bahasa sebagai sarana ziarah batin: “…../ suara adalah; telinga yang menghunus dengung, / seperti kawanan kolibri berputar, / berpusar dalam perut yang pasang, / yang surut bersamaan. / …..” Trianton mengambil pengalaman fisik (vertigo) dan menafsirkannya secara batin, menghubungkan rasa tak seimbang dengan pengalaman eksistensial manusia. Bahasa lirikal, dengan enjambement dan citraan yang kompleks, menjadi alat untuk menelusuri kesadaran dan penderitaan manusia, menegaskan bahwa puisi bagi Trianton adalah pengalaman reflektif, bukan sekadar deskripsi estetis.
Selain itu, “Ziarah” (2009-2020) menegaskan dimensi spiritual bahasa Trianton: “peradaban di tubuhmu/ mengundangku hijrah/ berpulang menyusuri sungai / riwayat yang telam lama padam”. Bahasa di sini berfungsi sebagai medium spiritual yang menautkan pengalaman empiris (tubuh, hijrah, sungai) dengan dunia batin, menjadikan puisi sebagai perjalanan kontemplatif. Trianton menulis bukan sekadar untuk menceritakan peristiwa, tetapi menulis ulang kesadaran manusia tentang cinta, kehilangan, dan transformasi batin.
Dengan demikian, babad batin pada Trianton merupakan praktik estetika yang menggabungkan sejarah genealogis, pengalaman empiris, dan refleksi batin. Bahasa puitik menjadi ziarah: melalui kata, citraan, dan struktur sajak, pembaca diajak menelusuri pengalaman yang sarat makna, dari luka hingga penebusan. Estetika ini menegaskan bahwa puisi bukan hanya cermin peristiwa, tetapi laboratorium kesadaran manusia, di mana setiap kata adalah langkah ziarah menuju pemahaman diri dan dunia.
4. Genealogi dan Sejarah Lirikal: Puisi Sebagai Arsip Jiwa
Salah satu karakter khas puisi Teguh Trianton adalah penulisannya sebagai bentuk genealogi batin, di mana sejarah kecil manusia diurai melalui pengalaman sehari-hari yang intim. Tradisi babad dalam kebudayaan Jawa selama ini dikenal sebagai penulisan sejarah dan silsilah keluarga, yang menghubungkan masa lampau dengan identitas kolektif masyarakat (Zoetmulder, 1985; Mulder, 1999). Trianton mengambil konsep ini, tetapi menafsirkannya secara batiniah: genealogi tidak hanya mengacu pada garis keturunan atau fakta historis, melainkan pada perjalanan kesadaran individu, di mana setiap pengalaman menjadi fragmen arsip jiwa yang tersimpan dalam puisi.
Dalam puisi “Ibu Menanam Kaki” (2019), Trianton menulis:
…..
Pagi-pagi aku melihat ibu meninggalkan dapur,
bergegas ke halaman istana negara, bertani;
menanam dua kaki pada petak kecil berisi semen.
Kutipan ini memperlihatkan bagaimana puisi menjadi arsip kesadaran yang menggabungkan memori personal dengan konteks sosial dan historis. “Dua kaki pada petak kecil berisi semen” dan “nisan tertanam di sawah” menjadi simbol sejarah kolektif dan spiritual, di mana pengalaman empiris (aktivitas ibu, sawah, sungai) diserap menjadi ingatan lirikal. Trianton merekonstruksi setiap fragmen ruang dan waktu untuk membentuk arsip batin, sehingga puisi berfungsi sebagai rumah kesadaran yang menyimpan memori personal dan kolektif sekaligus.
Konsep sejarah lirikal ini selaras dengan gagasan Gaston Bachelard dalam The Poetics of Space (1994: 8), yang menekankan bahwa ruang bukan sekadar geometri, tetapi wadah imajinatif bagi kenangan dan pengalaman batin. Dalam konteks Trianton, “dusun”, “halaman”, dan “dapur” bukan sekadar setting, tetapi ruang di mana pengalaman batin, pengamatan, dan refleksi sejarah berlangsung. Puisi menjadi medium di mana ruang dan kenangan saling berinteraksi, menghasilkan catatan puitik yang berfungsi sebagai arsip jiwa.
Contoh lain terdapat dalam puisi berikut ini, di mana pengalaman sederhana (kudi, pohon bambu) ditulis ulang sebagai fragmentasi sejarah batin:
Belah Bambu
meski kudi berpamor
pada perut dan pohon bambu
menerima qada-nya
tapi,
hidup tak elok
jika harus belah bambu.
Purwokerto, 2019
Puisi ini memperlihatkan bagaimana Trianton menyisipkan peristiwa sehari-hari ke dalam kerangka simbolik yang lebih luas, menandai nilai-nilai kehidupan, pilihan moral, dan kesadaran manusia dalam menghadapi qada dan qadar. Dengan cara ini, puisi Trianton bukan hanya merekam pengalaman, tetapi menulis ulang kesadaran manusia tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan dunia.
Dengan demikian, Babad Tulah tidak sekadar menceritakan manusia, tetapi menulis batin yang terus menuliskan dirinya sendiri. Genealogi yang dihadirkan Trianton bersifat introspektif dan spiritual: puisi menjadi arsip sejarah batin, arsip kesadaran kolektif yang menautkan pengalaman empiris, ingatan, dan refleksi moral. Trianton mengundang pembaca untuk memasuki ruang intim ini, menelusuri fragmen kehidupan yang menjadi jejak kesadaran manusia, sekaligus menyadari bahwa setiap pengalaman (luka, cinta, dan penebusan) menjadi bagian dari sejarah batin yang abadi.
5. Spiritualitas Bahasa: Dari Gramatika ke Makna Transenden
Dalam puisi Teguh Trianton, bahasa bukan sekadar medium komunikasi, melainkan sarana spiritual untuk menata kesadaran batin. Penyair itu sendiri menegaskan dalam pengantar Babad Tulah bahwa sajaknya mengalami proses “rekonstruksi gramatikal”, yang bukan semata soal memperindah bahasa, tetapi sebagai ikhtiar mencapai kejernihan batin dan makna transenden. Dengan kata lain, gramatika (struktur, urutan kata, dan sintaksis) bagi Trianton bukan hanya alat linguistik, melainkan tatanan jiwa, tempat pengalaman batin, luka, dan penebusan berpadu dalam bentuk estetis.
Salah satu ciri khas puisi Trianton adalah enjambement, yang berfungsi menciptakan ketegangan antara baris dan bait serta membuka ruang refleksi di antara kata-kata. Misalnya, dalam puisi “Aku Kangen Nafasmu” (2016-2020), ia menulis:
lalu, kau pun memberikan nafasmu
untuk kuhirup seolah itu nafas terakhirmu
yang ingin kau tunaikan
untuk mengisi debar yang kosong
di paru dan takbirku
…..
Perpindahan baris ini menimbulkan efek “ruang hampa” yang membiarkan pembaca mengalami jeda, menghayati ketegangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Kesenyapan di antara baris menjadi bagian dari makna transenden: pembaca tidak sekadar membaca, tetapi merasakan denyut batin yang tersirat. Teknik ini menegaskan pandangan Paul Valéry dalam Poetry and Abstract Thought bahwa keteraturan bahasa berhubungan erat dengan keteraturan batin: “A well-constructed poem is a laboratory of the mind”; “Puisi yang terstruktur baik adalah laboratorium batin” (1957: 46).
Selain enjambement, Trianton menggunakan pergeseran diksi untuk menghadirkan lapisan makna tambahan. Misalnya dalam “Aku Mungkin Kopi” (2016-2020):
aku mungkin kopi atau kau yang gula
saat gelas yang cangkir membikin pertemuan
di luar rencana, pada air mengepul
pada putaran sendok waktu aku serahkan
takdirku tanpa upacara
…..
Perpindahan metafora dari kopi ke gula, dari gelas ke takdir, tidak sekadar imaji estetis, tetapi menandai pergeseran kesadaran: bahasa memandu pembaca menembus pengalaman empiris menuju refleksi spiritual. Kata-kata menjadi jembatan antara dunia material dan kesadaran transenden, di mana “pertemuan” bukan hanya fisik, tetapi juga simbolik dari interaksi batin manusia.
Trianton menegaskan pula bahwa sajak mesti dapat menyampaikan sesuatu, yakni makna yang jernih dan relevan bagi pembaca. Dalam “Dzikir Ikan” (2018), misalnya, kesederhanaan diksi justru menekankan transmisi spiritual: “aku tak perlu / melafal apapun / pada bening udara / lewat kepak sirip / menenggelamkan diri / berdiam dalam rongga / air mengambangkan / nama-namamu”.
Bahasa yang sederhana namun sarat simbol ini memperlihatkan bahwa struktur gramatikal, enjambement, dan pilihan diksi menjadi instrumen meditasi, menuntun pembaca pada perenungan batin dan pengalaman transenden.
Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa bagi Trianton, spiritualitas bahasa dan gramatika saling terkait. Rekonstruksi gramatikal bukan semata soal teknik, tetapi sarana menyalurkan pengalaman batin, menyampaikan luka, cinta, dan penebusan. Puisi Trianton bukan hanya dibaca; ia dihidupi, dijadikan medium ziarah batin dari kata ke makna, dari bentuk ke pengalaman transenden.
6. Kesimpulan: Puisi Sebagai Sejarah Kesadaran Manusia
Membaca Teguh Trianton pada akhirnya membawa kita pada satu kesadaran penting: bahwa puisi, dalam penghayatannya, bukan sekadar bentuk ekspresi, melainkan cara manusia membangun sejarah batinnya sendiri. Babad Tulah dan puisi-puisi Trianton lainnya memperlihatkan bahwa kesadaran manusia tidak ditulis oleh waktu semata, tetapi oleh bahasa: bahasa yang dipilih, diolah, dan dijernihkan melalui proses kontemplasi.
Puisi-puisi Trianton bekerja sebagai arsip kesadaran, bukan karena ia menghimpun peristiwa, melainkan karena ia menghimpun cara manusia memahami peristiwa itu. Ketika dalam “Aku Kangen Nafasmu” penyair menuliskan “nafas yang saling dipertukarkan,” yang disampaikan bukan hanya kerinduan, tetapi cara batin menata pengalaman kedekatan dan kehilangan; sebuah gerak kesadaran yang hanya mungkin ditangkap melalui bahasa puitik.
Demikian pula “Dzikir Ikan” bukan sekadar meditasi air: ia adalah bentuk kesadaran yang kembali kepada kesenyapan, “berdiam dalam rongga,” untuk menemukan kembali nama-nama yang menghidupi batin. Bahasa yang bening dan struktur yang bersahaja menandai bahwa puisi adalah disiplin ketenangan: laku mengembalikan pikiran pada hakikat.
Hal yang sama terbaca dalam “Ibu Menanam Kaki”, tetapi kesimpulan yang dapat ditarik di sini bukan lagi tentang biografi atau etnografi batin, melainkan bahwa pengalaman sehari-hari hanya menjadi berarti sejauh ia membuka kemungkinan tafsir. Air mata yang “berair ketir” bukan sekadar sensasi fisik, melainkan pengetahuan sunyi tentang pengorbanan, kesabaran, dan pembentukan diri. Dengan demikian, yang ditulis oleh puisi-puisi Trianton bukan objek, melainkan cara jiwa menjadikan objek itu bermakna.
Pada titik inilah estetika babad batin menemukan tempatnya: Trianton menulis bukan untuk mengabadikan kejadian, tetapi untuk mengabadikan cara manusia mengalami kejadian. Babad dalam pengertian ini bukan lagi catatan sejarah luar, melainkan sejarah gerak kesadaran: sejarah yang tidak linear, tetapi melingkar, karena manusia terus-menerus belajar membaca luka, cinta, dan penebusan dalam dirinya.
Dengan demikian, puisi Trianton mengingatkan bahwa sejarah manusia tidak hanya tersimpan dalam arsip nasional, prasasti, atau dokumen publik. Ia juga tersimpan dalam helai-helai sajak yang tampak sederhana: dalam jeda baris, dalam kata yang dipilih dengan cermat, dalam kesenyapan yang menyiratkan doa. Di sanalah sejarah batin manusia direkam.
Bagi Trianton, puisi adalah laku kesadaran; bagi pembaca, puisi adalah ajakan untuk ikut serta dalam laku itu. Sajak-sajaknya membuka ruang bagi kita untuk menyadari bahwa yang paling manusia dalam diri kita bukanlah peristiwa yang kita alami, tetapi cara kita menafsirkan dan menuliskannya dalam batin. Karena itu, estetika babad batin tidak berhenti pada penyairnya; ia menjadi kemungkinan bagi siapa saja yang membaca.
Puisi, melalui Trianton, memperlihatkan dirinya sebagai sejarah kesadaran manusia: sejarah yang tidak selesai ditulis, tetapi selalu sedang ditulis ulang di dalam diri kita.
***
Daftar Pustaka
Bachelard, Gaston. 1994. The Poetics of Space. Boston: Beacon Press.
Bakhtin, Mikhail. 1981. The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: University of Texas Press.
Mulder, Niels. 1999. Mistisisme Jawa. Yogyakarta: LKiS.
Ricoeur, Paul. 1991. Memory, History, Forgetting. Chicago: University of Chicago Press.
Trianton, Teguh. 2020. Babad Tulah. Magelang: Tidar Media.
Valéry, Paul. 1957. Poetry and Abstract Thought. Princeton: Princeton University Press.
Zoetmulder, P.J. 1985. Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta: Djambatan.
—
*Abdul Wachid B.S., Penyair, Guru Besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.