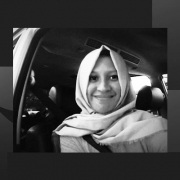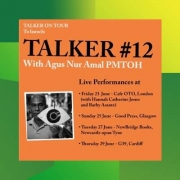Karna, Soeharto & Pahlawan
Oleh: Purnawan Andra*
Pahlawan dalam Bayang-bayang Kekuasaan
Setiap kali bulan November tiba, kita kembali memperingati Hari Pahlawan denganupacara, karangan bunga, dan pidato yang menekankan pentingnya mengenang jasa para pejuang. Namun, dari tahun ke tahun, makna “pahlawan” sepertinya kian mengabur. Ia berubahdari semangat yang hidup menjadi serangkaian upacara simbolik. Sementara di ruang publik, muncul kembali perdebatan lama: siapa yang layak disebut pahlawan, dan untuk kepentingansiapa gelar itu diberikan.
Maka ketika kabar tentang pengusulan kembali Soeharto sebagai pahlawan nasionalmuncul ke publik, yang sesungguhnya diuji bukan sekadar memori tentang masa lalu, tetapi carakita memahami arti “pahlawan” dalam kehidupan bersama. Perdebatan itu memperlihatkanbahwa kepahlawanan di Indonesia kerap lahir bukan dari keberanian moral, melainkan darimekanisme legitimasi. Dalam hal ini, kisah Karna dalam Mahabharata menjadi cermin yang menarik tentang bagaimana kekuasaan menciptakan pahlawannya sendiri.
Strategi Ideologis
Dalam kisah epik besar India itu, Karna diangkat menjadi Adipati Angga oleh Duryudanabukan karena darah bangsawan, tapi karena keberanian dan kemampuan memanahnya yang menandingi Arjuna. Penobatan itu sering dibaca sebagai penghormatan terhadap keutamaan, padahal ia merupakan langkah politis.
Duryudana membutuhkan Karna untuk menandingi Pandawa, dan penobatan itu menjadicara meneguhkan kekuasaannya. Maka, sejak awal, “kepahlawanan” Karna lahir dari strategipatronase. Ia bukan semata pahlawan karena keberanian, tetapi karena kekuasaan membutuhkanfigur heroik yang mampu menjustifikasi eksistensinya.
Seperti ditulis Michel Foucault dalam Wacana Kuasa/Pengetahuan (2017), kekuasaantidak hanya bekerja melalui dominasi, melainkan juga melalui produksi pengetahuan, termasuktentang siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang disebut pengkhianat. Narasi kepahlawanan, dalam pengertian ini, adalah bentuk pengetahuan yang digunakan kekuasaan untuk mengaturpersepsi publik.
Duryudana menciptakan Karna bukan hanya sebagai sekutu militer, tetapi juga sebagaisimbol moral bagi kerajaannya. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan mitos. Dan agar mitos itu kuat, maka ia harus tampak etis.
Kesetiaan Karna pada Duryudana kerap ditafsirkan sebagai bentuk kehormatan bagiseorang yang tertolak dari tatanan sosial. Namun dalam konteks kekuasaan, kesetiaan itu bukansekadar pilihan etis, melainkan strategi ideologis. Dengan menjadikan kesetiaan sebagai nilaitertinggi, kekuasaan memperoleh moralitas (palsu) untuk menutupi dominasi.
Kesetiaan semacam ini bukan cermin integritas, melainkan mekanisme kontrol. Iamerupakan cara halus untuk membuat kekuasaan tampak sah dan tak terbantahkan. Dalam logikaini, kesetiaan adalah topeng yang menutupi ketidakadilan, dan pahlawan menjadi alatpembenaran bagi penindasan yang dibungkus dalam bahasa moral.
Dalam konteks Indonesia, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasionalmencerminkan logika yang sama. Bahwa kepahlawanan yang dibentuk bukan oleh kebajikanmoral, tetapi oleh mekanisme kekuasaan.
Narasi tentang “Bapak Pembangunan” bekerja seperti narasi Duryudana terhadap Karna, dengan mengubah kekuatan politik menjadi keutamaan moral. Dalam versi resmi sejarah, Soeharto bukan sekadar penguasa, melainkan penyelamat bangsa dari kekacauan. Padahal, di balik citra stabilitas itu, tersimpan represi, pembungkaman, dan luka yang belum selesai.
Dalam Komunitas-komunitas Terbayang (2008), Benedict Anderson mengingatkanbahwa bangsa dibangun melalui narasi yang dipilih secara selektif. Pahlawan menjadi bagianpenting dari narasi itu. Bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena mereka diperlukan untukmeneguhkan imajinasi kebangsaan.
Dengannya, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan bukanlah tindakan netral, melainkanupaya politik untuk mengukuhkan memori tertentu. Ia menjadi strategi simbolik dalam perangingatan, ketika negara berusaha mengatur ulang siapa yang layak dikenang dan siapa yang dibiarkan hilang dari sejarah.
Kepahlawanan, dalam logika seperti ini, bukan representasi nilai-nilai moral universal, melainkan simbol untuk melanggengkan narasi politik tertentu. Gelar “pahlawan nasional” sering kali lebih politis daripada etis, termasuk menjadi cara bagi rezim untuk menulis ulangsejarah.
Jacques Derrida dalam Of Grammatology (1997) menyebut bahwa setiap penulisan selaludisertai penghapusan, setiap yang ditinggikan menuntut yang disingkirkan. Maka, ketika namaSoeharto diajukan, yang terhapus bukan hanya sisi kelam Orde Baru, tetapi juga suara para korban yang tak pernah benar-benar dipulihkan.
Perspektif Kultural
Dalam perspektif kultural, ini menyingkap cara kerja mitos kepahlawanan dalamkebudayaan kita. “Pahlawan” diimajinasikan bukan sebagai subjek moral yang menegakkankebenaran, melainkan sebagai figur yang menstabilkan tatanan. Ia menjadi jembatan antarakekuasaan dan keinginan kolektif akan ketertiban.
Dalam kondisi politik yang semakin militeristik, pengusulan Soeharto bisa dibacasebagai tanda kembalinya imajinasi Orde Baru. Yaitu ketika ketertiban lebih dihargai daripadakebebasan, dan keberhasilan pembangunan dianggap lebih penting daripada keadilan.
Karna dan Soeharto sama-sama hidup dalam struktur yang memuja kesetiaan danhierarki. Dalam masyarakat seperti itu, kritik sering kali dianggap pengkhianatan, dan kesetiaanmenjadi alat untuk menundukkan penilaian moral. Itu sebabnya Derrida mengajarkan kita untukmembaca ulang teks dan simbol.
Bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membuka lapisan makna yang tersembunyi. Dekonstruksi terhadap mitos kepahlawanan berarti mengungkap bagaimana bahasa“jasa” dan “pengorbanan” sering dipakai untuk menutup mata terhadap kekerasan yang dilakukan atas nama bangsa.
Dengannya, kasus pengusulan Soeharto seharusnya menjadi pengingat bahwakepahlawanan di masa kini tidak bisa lagi didasarkan pada logika kekuasaan. Belajar dari sejarahOrde Baru, kita melihat bahwa stabilitas tanpa keadilan hanya melahirkan ketakutan, danpembangunan tanpa kebebasan hanya memperpanjang ketimpangan.
Karena itu, makna pahlawan hari ini seharusnya tumbuh dari keberanian menegakkankeadilan, melindungi yang lemah, dan memperjuangkan kebenaran. Nilai-nilai itulah yang semestinya dijadikan ukuran, bukan sekadar jasa politik atau keberhasilan ekonomi.
Maka, ketika kita memperingati Hari Pahlawan atau memperdebatkan nama besar sepertiSoeharto, yang seharusnya kita tanyakan bukan siapa yang layak diberi gelar, melainkanpahlawan seperti apa yang ingin kita teladani ke depan. Sebab masa depan bangsa tidak akanditentukan oleh siapa yang paling berjasa di masa lalu, tetapi oleh siapa yang berani menjaganurani dan menegakkan kebenaran di masa sekarang.
—–
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.