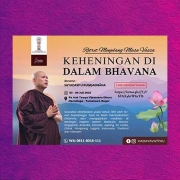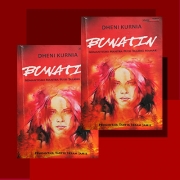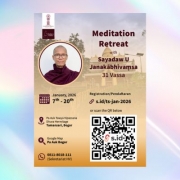Multikulturalisme dan Manusia Indonesia
Oleh. Mudji Sutrisno SJ.*
Apa itu budaya dan bagaimana sebuah budaya berkembang dalam sebuah masyarakat? Apa dan bagaimana pertemuan antar budaya? Bagaimana sejarah kehidupan multikultur di Indonesia? Akan seperti apa kehidupan multikultur di Indonesia menghadapi globalisme? Apa dan bagaimana peran pendidikan dan kaitan akademisi dalam menghadapi tantangan multikulturalisme? Sebagai sebuah diskursus yang relatif baru di Indonesia, begitu banyak hal yang belum jelas berkaitan dengan multikulturalisme. Sidik Permana dari Transformasi mencoba memperbincangkannya bersama Prof. Dr. F.X Mudji Sutrisno SJ. Ditemui di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, di bilangan Cempaka Putih, Jakarta, kami mewawancarai beliau lebih dari satu jam dalam sebuah perbincangan yang sangat menarik. Sebagai seorang Rohaniawan dan Budayawan, beliau memang sangat pas dalam membicarakan topik ini.
Budaya dan Pertemuan Antar Budaya
“Bicara budaya, maka kita harus melihat unsur fundamental dari sebuah budaya, yaitu nilai. Nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok serta dijadikan acuan tindakan maupun pengarti arah hidup. Lewat kebudayaanlah, lalu nilai ini ditumbuhkan dan dibatinkan. Maka, kebudayaan petani atau agraris dengan keteraturan musin hujan saat tanam dan musim panas saat tunai, serta rutin teraturnya matahari terbit di pagi hari di daerah tropis khatulistiwa dan terbenam di petang hari, membuahkan penghayatan nilai-nilai keteraturan pada warganya,” demikian Mudji Sutrisno mengawali perbincangannya.
Menurut Mudji, Dalam analisis historis, suatu kebudayaan muncul, yang menandai dimulainya sebuah peradaban, yaitu ketika manusia menghadapi situasi sulit yang menantang hingga tumbuh kegiatan-kegiatan kreatif untuk melakukan usaha yang tak terduga dalam proses challenge and response. Bila sikap kreatif ini terus dijaga, akan tumbuh respons yang makin optimum. Rangsangan-rangsangan kebudayaan terus diasah dan dipertajam, yang secara lahir berupa penguasaan keadaan luar dan secara batin berupa artikulasi diri dalam self determination yang progresif. Terdapat proses etherealization, yaitu ikhtiar-ikhtiar untuk memusatkan energi kebudayaan pada optimalisasi tantangan-tantangan yang semakin halus atau spiritualisasi dari kebudayaan. Peradaban akan runtuh bila gagal memunculkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Puncak keruntuhan akan terjadi bila ada disintegrasi peradaban, di mana kesatuan sosial pecah dan ketidakmampuan kebudayaan memberi respon kreatif pada tantangan jaman, jelasnya.
Mudji selalu merumuskan budaya dalam, dua arah. Segi pertama dilihat dari dinamikanya, yang melihat budaya sebagai kemampuan dari individu atau subyek budaya. Budaya bukan hanya kemampuan bernalar yang membuat kognisi, tapi juga kemampuan untuk merasakan yang menimbulkan estetika, dan yang sangat penting adalah untuk mengartikan hidup dalam pondasi yang paling dalam, yaitu religiositas. Tiga kemampuan ini dalam subyek atau pelaku kebudayaan akan selalu berusaha untuk mampu mengartikan pergulatan-pergulatan yang disodorkan kepada dia setiap hari sampai akhirnya dia akan bisa berupaya dan mencari makna untuk hidupnya. Ini dinamika pertama, artinya ini adalah kebudayaan subyektif dari pelakunya. Arah yang kedua, atau sering disebut sebagai kebudayaan obyektif, yaitu seluruh jagad makna atau arti, yang secara de facto dihidupi dan diacu untuk menafsirkan dan sekaligus memberi arah permaknaan dalam realitas hidup sehari-hari kelompok orangnya. Dengan kata lain, budaya itu suatu yang dinamis, yaitu ketika orang bisa mengambil dari kebudayaan itu makna hidup atau perjalanan hidupnya.
Dalam kasus pertemuan antar budaya, Mudji melihat ada beberapa model yang berlaku, diantaranya adalah model relasi kekuasaan yang ada di situ, artinya relasi siapa yang paling sah memberi makna di situ. Ketika relasi kekuasaan itu ada dalam kekuasaan yang mengabsahkan tradisi tulisan misalnya, lebih tinggi, lebih obyektif dari tradisi lisan, di situ sudah terjadi penjajahan perumusan. Di situ lalu kita lihat permasalahan poskolonial yang terjadi akhir-akhir ini. Kenapa? Karena semua tradisi kelisanan yang sesungguhnya oleh lokalitas itu dipandang kebenarannya dan betul-betul suci, karena itu dihayati sebagai living wisdom dan living law, acuan budaya yang dihidupi, semua itu menjadi nomor dua dan disepelekan ketika orang masuk dalam tradisi budaya tertulis. Padahal sesungguhnya, jelas Mudji, budaya tulisan itu hanyalah sebuah bentuk lain dari sebuah perumusan. Sekarang dipertanyakan lagi ketika orang memasuki tradisi kelisanan sekunder atau kelisanan kedua, yaitu ketika televisi dan media elektronika mencanggihkan lisan-lisan yang akhirnya menjadi budaya talk show atau omong-omong. Di situ timbul persoalan, yaitu ketika kita membaca pembabakan kebudayaan itu linear atau garis lurus, meskipun semestinya tidak linier, orang-orang yang menganut kebudayaan tulisan akan menganggap kebenaran tertulis lebih tinggi daripada budaya lisan. “Kalau kita cermati,” tambahnya lagi, “banyak local wisdom yang berupa budaya lisan, yang karena dinamika kekuatan dan kekuasaan budaya modern, ‘terpaksa’ mengikuti budaya tertulis. Permasalahan menjadi lebih kompleks untuk bangsa ini karena sebelum itu terbentuk kita sudah kena terpaan kelisanan kedua atau sekunder itu tadi,” ujar Mudji.
Budaya tertulis itu adalah budaya modern, yang menurut Habermas, awalnya bersumber dari pencerahan. Pencerahan itu bermula ketika orang berpikir rasional, logis, dan rumusannya itu ditulis. Sisi positif budaya tulisan ini, menurut Mudji, dia mendisiplinkan kerangka berpikir, membentuk orang sekaligus merinci dan merumuskan secara nalar, dan tertulis, sehingga otentik. Sementara kelemahan dari tradisi lisan adalah ketika orang yang menguasai dan mengetahui tradisi tersebut, meninggal dunia. Kita tidak akan pernah bisa meneliti atau mencek lagi pengetahuan yang dia miliki. Dalam temu budaya yang akhirnya menjadi multikultur, baik tradisi lisan maupun tulisan, sama-sama sah untuk mengatakan kebenaran. Ketika kebenaran ini akan diuji akhirnya ada konsensus dalam peradaban modern yang tertulis, supaya kita punya bukti, untuk dibuat kontrak tertulis. Kontrak tertulis ini, yang menurut Habermas, akan menjadi sumber penjajahan ketika orang yang hidup dalam tradisi lisan dipaksa, tanpa melibatkan kemerdekaan mereka untuk mengiyakan, untuk mengikuti budaya tulisan, seperti contohnya dengan keharusan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol.
Ketika kecenderungan ini terjadi, Mudji melihat multikulturalisme berkembang sebagai “sekolah” yang menaruh perhatian pada pentingnya studi keragaman sumber-sumber serta kantong-kantong budaya yang secara de facto menjadi oasis penghayatan hidup dan acuan makna penganutnya dalam penghayatan jagat nilai kelompoknya. Studi ini semakin berkembang seiring dengan memadatnya kesadaran terhadap keterbatasan tradisi-tradisi besar, yang menurut Mudji, setelah krisis tafsir kebenaran tunggal yang ternyata ambruk dalam rasionalisme demokratis serta krisis-krisis dehumanis teknologi instrumental yang membuat hidup menjadi sempit atau disempitkan, baik secara ekonomis atau teknis. Kondisi inilah yang melahirkan gelombang kesadaran local genius yang menghormati kesamaan pencarian dan perumusan hak tiap identitas etnik, tradisi budaya yang beragam, baik lisan maupun tertulis, atas kebenaran dan merumuskannya secara sah untuk memaknai hidup. Dengan kata lain, lanjut Mudji, Multikulturalisme yang ideal mensyaratkan keragaman dan kemajemukan local genius atau local culture atau lokalitas dengan rumusan lisan atau tulisan kebenarannya bertemu dan punya hak untuk membuat kontrak dan konsensus mana yang disepakati untuk menyatukan kebersamaan dalam identitas multikultur itu sendiri.
Mudji kemudian menjelaskan, “Dalam tataran negara-bangsa, mereka yang identitasnya masih etnik, di mana etnisitas itu kemudian berkembang menjadi nasionalitas, harus ada kesepakatan bahwa nasionalitas itu tidak mencekik yang etnisitas. Dari situlah kemudian nasionalitas ini dirumuskan bersama dalam sebuah nation state. Dalam perspektif ini, unsur penentu konsensus berdirinya negara bangsa ini adalah kesederajatan subyek-subyek penyusunannya. Bila kontrak itu dirumuskan dalam sebuah konstitusi, sebelumnya harus ada kesepakatan bersama dari seluruh etnisitas yang terlibat. Jadi syarat kedua multikulturalisme adalah partisipasi dari semua ethnic identity penyusunannya.
Sejarah Bangsa Indonesia dalam Perspektif Multikulturalisme
Mudji melihat sejarah Indonesia terdiri dari dua bagian besar. Bagian pertama adalah “sejarah besar” yang ditulis oleh kaum literasi dan kaum intelektual. Sedangkan bagian lainnya adalah “sejarah kecil”, yaitu lokalitas dari setiap etnik yang ada di Indonesia. Sejarah ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kebudayaan dan kemerdekaan kita, yaitu apakah kemerdekaan kita adalah hasil kerja keras kaum “sejarah besar” yang tercerahkan, para pendiri bangsa, kaum “sekolahan”, atau sesungguhnya dibantu dan ditentukan oleh sejarah-sejarah kecil, yaitu lokalitas itu tadi.
Seorang antropolog asal Amerika, George Kahin, mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena para literati betul-betul memakai persyaratan modern dan kekuatan rasionalitas untuk mengalahkan kolonialisme. Jadi selama 300 tahun lebih kita dijajah, kunci terpokok dari terjadinya kondisi itu adalah bahwa kita tidak mampu menguasai rasionalitas dari para penjajah kita. Segera setelah akhirnya kita menggunakan strategi diplomasi dan menguasai rasionalitas, yaitu dengan jalan pendidikan, perjuangan kita berhasil. Sehingga, yang sebelumnya perjuangan kemerdekaan menggunakan emosionalitas, dan memakai sejarah-sejarah kecil tadi, ternyata kita malah dibodohi dan di ‘divide et empera‘ kan oleh kaum penjajah. Kemerdekaan kemudian berhasil kita raih karena kaum literati dan tercerahkan mulai mengatur hidup bersama, tidak dengan kebijaksanaan etnik masing-masing. Namun menurut Mudji, tesis ini mendapat kritikan dari murid Kahin sendiri, yaitu Benedict Anderson. Menurut Anderson, revolusi Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa keikutsertaan seluruh rakyat. Dan persatuan seluruh rakyat tersebut dipicu oleh 3-4 tahun penjajahan Jepang yang sangat menindas. Masih menurut Anderson, hal itu memperlihatkan populisme dari sejarah kecil yang menyatu.
Realitas yang terjadi dalam sejarah bangsa, menurut Mudji adalah, pada tahun 1942-1945 kaum literati dengan pemikiran rasionalitas dan kerangka bernegara yang canggih memang tidak dapat disangkal menjadi motor penggerak utama bangsa ini menuju kemerdekaan. Namun tanpa kekuatan massa populis waktu itu, kemerdekaan tidak akan bisa kita peroleh. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1965 dan 1998, artinya ketika momentum dari sebuah gerakan terjadi, tanpa dukungan massa populis yang besar, perubahan atau reformasi tidak akan terjadi. Namun Mudji melihat bahwa sekarang sulit untuk mengulang ketiga momentum besar itu. Hal ini disebakan ketanpapamrihan rakyat dalam ketiga momentum tersebut dikecewakan lagi dalam empat tahun terakhir. Dengan kata lain, sesungguhnya baik sejarah besar maupun kecil sekarang ini mengalami krisis kepemimpinan untuk bergerak secara bersamaan. Kondisi ini menurut Mudji, menunjukkan bahwa sekarang tengah terjadi neofeodalisme dalam ekonomi-politik-kebudayaan. Sehingga demokrasi pun dihayati dengan semangat nilai feodal dan paternalistik. Dengan mengutip Clifford Geertz, Mudji mengatakan bahwa transformasi budaya mengasilkan involusi budaya di mana dualisme feodal dan modern terus menerus menjadi kendala proses integrasi nilai maupun budaya. Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa, kondisi yang ada sekarang ini sesungguhnya merupakan cara untuk mempertahankan status quo dari kelompok elite priyayi yang diuntungkan oleh struktur yang ada, ujarnya. “Inilah yang membuat sekarang kita sangat rindu pada sosok Bung Karno, Bung Hatta, rindu pada sosok negarawan yang hingga sekarang masih belum kita temukan.”
Kondisi menurut Mudji diperparah dengan sistem dan hasil pendidikan selama 40 tahun terakhir yang sangat buruk. “Coba kita lihat sekarang,” kata Mudji, begitu banyak anak-anak muda, mahasiswa, yang dihantam atau dipotong. Semua kekritisan dihabiskan. Sistem pendidikan kita menjadikan orang-orang hanya penurut dan pembeo. Sementara kaum literati dan akademisi tahu, karena partai politik hanya dijadikan alat oleh rezim orde baru atau Soeharto untuk kelanggengan kekuasaannya, mereka memilih untuk berada di luar partai politik. Hingga akhirnya partai politik tidak memiliki kaum leterati yang memiliki pemikiran kritis dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Agama dan Budaya
Menurut Mudji, budaya lebih luas daripada agama. Mengapa? Karena budaya adalah bahasa agama yang kemudian dikontekstualkan, atau disebut sebagai inkulturasi agama. Artinya, hanya agama yang masuk melalui budaya yang dihayati oleh masyarakat lokal yang akan diterima, la memberikan contoh bagaimana agama Islam yang masuk melalui jalan damai, melalui perdagangan yang nyaman dan egaliter, memiliki akar yang sangat kuat yang kemudian menjadi Islam kultural. Mudji menekankan bahwa agama itu mampu membuat teologi yang damai dalam multikultur atau kemajemukan adalah dengan dilihat dari kemampuan agama tersebut menjadi agama kultural, menjadi agama yang ada di Indonesia mampu menjalin kerjasama humanisasi dalam permasalahan sosial konkrit di Indonesia, “hal di atas akan menjadi kunci ketika agama-agama di Indonesia menghadapi salah satu penyakit agama, yaitu formalisme. Penyakit lain agama yang ada di Indonesia ini, menurut Mudji adalah ritualisme yang tidak sehat. Kita lihat bagaimana pada hari Jumat mesjid-mesjid penuh, juga gereja penuh pada hari Minggu, namun di luar waktu itu orang kehilangan penghayatan akan agamanya. “Dalam kerangka ini, hubungan agama dan budaya adalah pencarian bahasa-bahasa budaya emansipatif. Kerjasama kemanusiaan, terutama yang dilakukan di daerah konflik, pengungsi, kaum dhuafa, sangat melegakan karena ternyata anak-anak muda yang sangat menyadari masalah ini,” ujarnya. Mereka anak-anak muda menangkap teori sosiologis yang diberi acuan dan sumber semangat dari agama untuk menolong sesamanya dan dipraktekkan dalam tingkat kemanusiaan yang sama.
Kapitalisme Global dan Multikulturalitas Indonesia
Bagaimana kita, dengan multikulturalitas yang kita punya, menghadapi globalitas?
Menyinggung tentang globalisme yang tengah mengalir deras mengisi setiap sisi kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai bangsa, Mudji mencermati bahwa globalitas yang tengah berjalan ini bercirikan materialistis dan kapitalistis, di mana semua direduksi, dimurahkan dan dimaterialkan. Globalitas, lanjutnya lagi, telah menciptakan kolonialisme kultural, di mana negara-negara maju dengan teknologi tinggi dan kekuatan ekonomi kapitalisnya menjajah negara-negara dengan identitas etnis. Maka yang terjadi adalah hegemoni tafsir kebenaran dengan kuasa absolut. Apalagi ketika analis bangunan realitas menunjukkan bahwa material ekonomi yang ditentukan oleh hubungan produksi dan kepemilikan kapital menentukan secara langsung bangunan atas yang berupa ideologi, agama, seni dan kebudayaan, di sini praktis kebudayaan hanyalah cermin ketimpangan hubungan kelas yang tertindas secara ekonomi dan penindasnya terungkap dalam relasi penjajahan kultural, mulai dari kolonialisme pikiran, simbolik dan seni. Menurut Mudji, kondisi yang sekarang kita hadapi persis sama sebenarnya dengan bagaimana dulu para pendiri ini menghadapi kekuasaan kolonial yang modern. Pada saat itu mereka mempelajari kemodernan itu sampai ke dasar-dasarnya. Maka, cara pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah belajar sampai ke kedalaman globalisasi. Jangan kita jauh-jauh menolak tanpa tahu kedalamannya,” ujarnya.
Mudji melihat ada dua hal utama yang berkaitan dengan globalisasi, yaitu pertama, mereka tidak mengenal batas teritorial negara lagi, jadi sudah lintas batas. Kedua, ruang pribadi dan ruang publik sudah dicampurkan. Artinya ketika mereka dengan hyper reality-nya masuk ke kamar-kamar pribadi kita, dengan dukungan kapitalisme dan modernisme yang kuat, mereka mengobrak-abrik ruang pribadi dan ruang publik kita. Sehingga bila kita cermati, dahulu kebudayaan memiliki nilai leisurebukan berarti waktu luang, yaitu waktu hening untuk mengolah, merenungi ke mana hidup kita, hidup bangsa ini, untuk lebih memantapkan identitas diri, visi dan misi hidup kita. “Namun, sekarang nilai itu tereduksi dan disempitkan menjadi hanya pleasure, yakni kenikmatan saja,” jelasnya.
Menghadapi kondisi ini, menurut Mudji, muncul dua kelompok ekstrem dalam masyarakat kita. Pertama adalah kelompok yang tidak ingin kehilangan identitas, sehingga kemudian mereka kembali ke kitab sucinya masing-masing. Dari kelompok inilah muncul golongan fundamentalis, yang seperti katak di bawah tempurung, mengeras di dalam, lalu keluar dalam bentuk kekerasan. Sehingga untuk mengadili yang lain, mereka meminjam tangan Tuhan. Kelompok kedua adalah mereka yang sama sekali ikut saja dengan arus globalisasi, dengan segala kesenangannya. Supaya tidak terjebak pada dua kelompok ekstrem ini, selain mempelajari globalisasi itu hingga ke dasarnya, kita harus dapat mempraktekkan betul kombinasi, mana yang pada semangatnya tetap multikultur, tapi kendaraannya menggunakan fasilitas globalitas itu sendiri. la memberi contoh bagaimana seniman-seniman dan para etnomusikolog tari musik Indonesia sangat survive, bahkan etnomusik semakin mendunia. “Kondisi ini memperlihatkan,” lanjutnya lagi, “bahwa thesis Habermas tepat, yaitu bahwa yang penting adalah kita ingat bagaimana kemodernan dan globalitas itu memiliki sisi-sisi dehumanis yang harus kita tolak. Dengan demikian, yang kita butuhkan dalam multikulturalisme dan multikultur adalah bagaimana lingkup pencerdasan dan kesadaran untuk merdeka bisa berkembang secara tepat seperti dikatakan oleh Paulo Freire, dari kebudayaan bisu, pasif, penurut, pembeo, tertindas selama lebih dari 30 tahun di bawah rezim orde baru, kembali kepada kebudayaan nusantara yang multikultur dan kreatif.
Pendidikan yang Local Based
Mudji Sutrisno menggarisbawahi, bahwa sekarang ini adalah masa transisi, yaitu ketika multikulturalisme akan diterjemahkan dengan lokalitas yang bernama otonomi daerah. Ketika lokalitas otonomi daerah ini hanya dirumuskan secara politik dan ekonomi yang sempit, yang terjadi adalah bagi-bagi rejeki untuk tiap daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, bila kita ingin keluar dari kondisi tersebut, multikulturalisme dalam lokalitas harus diterjemahkan secara kultural, ujarnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan atau mapping local genius dalam seni dan juga muatan lokalitas yang ada di daerah tersebut, beserta kreator dan kantong-kantong seninya. Selain itu juga, dimulai dari tingkat pendidikan dasar harus ditanamkan kesadaran membaca dan kecintaan pada sastra.” Jelasnya.
“Sehingga saya optimis, bila peta sudah ada dan ada orang yang memberi muatan pada lokalitas-lokalitas tersebut, selanjutnya yang kita butuhkan adalah orang yang gigih menanamkan kegemaran membaca dan menulis, la memberi contoh Taufiq Ismail, yang tengah menyebarkan “virus” membaca pada kalangan generasi muda. Dan seharusnya, tambahnya lagi, hal-hal seperti ini dapat dimulai dari pendidikan dasar. Sehingga nantinya, pelajaran bahasa Indonesia harus lebih diarahkan pada apresiasi sastra, bukan pada linguistik yang terlalu formal. Selanjutnya, yang kita butuhkan selain perintis atau inisiator itu tadi adalah kerangka pentahapan pendidikan yang transformatif, ujarnya.
Peran Kaum Cendikiawan dan Akademisi
Peran kaum akademisi secara konkrit dan kontekstual tentunya adalah mereka secara serius mengajar di Perguruan Tinggi, penyebar ide pencerahan dan transformasi. Mereka seharusnya memberi ‘prognosis’, melihat ke depan dan memberi masukan tentang apa saja yang harus disiapkan untuk itu.
Namun, Mudji mengakui bahwa hal ini sulit dilakukan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan struktur pendidikan yang membuat sulit bagi para akademisi memperoleh penghidupan yang layak. Akibatnya mereka lebih memilih bekerja di luar Perguruan Tinggi dan menelantarkan pencarian-pencarian dan penelitian yang dalam model pendidikan tinggi di luar negeri jalan terus.
Kunci semua ini adalah selalu memperhatikan bagaimana pendidikan dan substratum atau lapangan kebudayaan disiapkan untuk itu. “Sekarang coba kita lihat lapangan-lapangan kebudayaan yang disiapkan sekarang ini,” kata Mudji, “mana yang tidak habis oleh kapitalisme, yang tidak habis oleh persaingan materialisme dalam bentuk capital, hingga semua tereduksi menjadi hanya soal uang dan uang? Kondisi ini sangat mengerikan untuk sebuah komersialisasi dan kapitalisasi dari seluruh kampus dan perguruan tinggi. Saya kira akan semakin sulit bagi kita menemukan cendikiawan semodel Prof. Soejatmoko misalnya, yang selalu menjadi semacam budayawan atau ‘nabi’, yang memiliki perhatian yang sangat luas terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat.”
“Hal terpenting dari seorang cendikiawan pada masa sekarang ini adalah bagaimana tetap menjadi cendikiawan yang kritis, di manapun tempat perjuangannya, dia harus tetap menjadi akademisi. Dia juga dituntut harus memiliki kesadaran multikultur, sehingga dia sadar betul bahwa Indonesia ini, sebelum distrukturkan oleh rasionalitas nation-state, sudah mempunyai kebudayaan lokal. Yang secara kultural adalah majemuk, yang tinggal menunggu pengolahan dan sumbangan dari masing-masing lokalitas ini sampai menemukan Indonesia ini siap ke depan menghadapi globalitas dengan entitas kebudayaannya. Namun, dalam merumuskan hal tersebut harus dijaga agar jangan sampai terjadi hegemoni atau penindasan, sebab hal tersebut akan merumuskan yang lain di luar dirinya sebagai obyek, yang artinya malah anti multikultur dan juga anti-demokrasi,” jelasnya.
Mudji Sutrisno menandaskan, adalah sesuatu yang sangat ironi, di tengah kekayaan ini, bila terhadap masalah kepentingan ekonomi saja dan terhadap tantangan kapitalisme global membuat kita terpuruk. Mudji melihat bahwa ada something wrong dari kaum akademisi yang tidak mampu merumuskan bagaimana politik ekonomi atau strategi ekonomi untuk mengolah seluruh kekayaan ini. Permasalahannya, apakah semua ini hanya persoalan text book thinking saja? Multikulturalisme sesungguhnya bereaksi terhadap text book thinking yang sedang ada di tingkat elit, untuk kembali kepada local wisdom, demikian Mudji Sutrisno.
Diambil dari Transformasi, Vol. 3. No. 1, Januari – Maret 2003.
***
Kepustakaan:
1. Geertz, Clifford, 1975 (1973), “The Interpretation of Cultures“, London, Hutchinson.
2. Giddens, Anthony 1991, “Modernity and Self Identity“, Stanford Uni. Press.
3. Habermas, Jurgen 1978, “Knowledge and Human Interest“, London, Heineman.
4. Horkheimer, Max and Adorno Theodor, 1972 (1974), “Dialectic of the Englightment“, London.
5. Parsons Talcott, 1969 (1973), “The Structure of Social Action“, New York, Tree Press.
6. Parsons Talcott, 1970 (1951), “The Social System“, London Rontledge and Kegan Paul.
7. Van Gennep, Arnold, 1960 (1908), “The Rites of Passage“, London Rontledge and Kegan Paul.
8. Van Peursen, “Strategi Kebudayaan” terjemahan Dick Hartoko, 1972.
9. Kymlicka, Will, 1995, “Multicultural Citizenship,” New York, Univ. Press.
——–
*Mudji Sutrisno SJ. Budayawan.