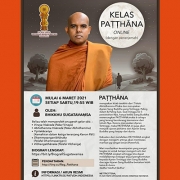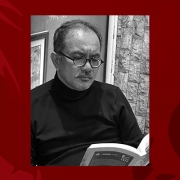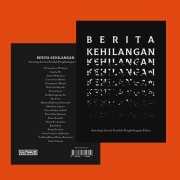Sastra Sebagai Cetak Biru: Literasi Humanitarian dalam Ekosistem Kebudayaan
Oleh: Gus Nas Jogja*
Di antara denting gong yang mengambang di udara senja dan bisikan daun lontar yang mengering, terukir sebuah peta yang tak kasat mata. Ia bukanlah peta geografis, melainkan sebuah cetak biru, sebuah arsitektur jiwa yang menjadi fondasi bagi ekosistem kebudayaan Nusantara. Peta ini, yang selama berabad-abad diwariskan dari mulut ke mulut, dari syair ke serat, dari hikayat ke pantun, adalah apa yang kita sebut sastra. Namun, sastra di sini bukanlah sekadar tumpukan kata yang indah; ia adalah manifestasi dari sebuah literasi yang paling mendalam: literasi humanitarian. Sebuah kemampuan untuk membaca bukan hanya teks, melainkan hati manusia, alam semesta, dan bahkan bisikan Ilahi.
Esai ini akan menelusuri bagaimana sastra Nusantara, melalui lensa epistemologi, ontologi, dan kosmologi yang unik, berfungsi sebagai panduan transendental untuk memahami dan mengamalkan kemanusiaan sejati, memelihara sebuah peradaban yang berakar pada empati, harmoni, dan kearifan spiritual.
Epistemologi Nusantara: Sastra sebagai Peta Jalan Menuju Pengetahuan Batin
Epistemologi, ilmu yang menelisik tentang hakikat pengetahuan, dalam konteks Nusantara bukanlah sekadar tentang verifikasi empiris atau logika rasional. Ia adalah sebuah perjalanan batin, sebuah pencarian akan ilmu hakikat yang melampaui data inderawi. Dalam tradisi Nusantara, pengetahuan yang paling berharga bukanlah yang bisa dihafal dari buku, melainkan yang diresapi dan menyatu dengan jiwa. Sastra menjadi medium utama dalam transfer pengetahuan transenden ini. Ia tidak mengajarkan secara didaktis, melainkan melalui metafora, simbol, dan alegori yang memaksa pembaca atau pendengar untuk berenang di lautan makna yang tak terhingga.
Bayangkan kita berada di sebuah pagelaran wayang kulit. Di balik kelir, dalang bukanlah sekadar pencerita. Ia adalah guru epistemologis. Setiap tokoh yang dimainkan, dari Arjuna yang menuntut ilmu sejati hingga Bima yang menggenggam kebenaran di dalam dirinya, adalah representasi dari sebuah tahapan pencarian pengetahuan. Serat Wulangreh karya Pakubuwana IV, misalnya, bukanlah sekadar nasihat moral, melainkan sebuah peta jalan spiritual yang mengajarkan tentang etika batin, kerendahan hati, dan pentingnya mencari guru spiritual yang sejati. Pengetahuan tentang alam semesta, tentang hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, tentang arti hidup dan mati, tidak diajarkan melalui kuliah di universitas, melainkan melalui bait-bait tembang macapat yang meresap ke dalam sanubari.
Sastra dalam konteks ini berfungsi sebagai “cermin jiwa” yang memantulkan kembali siapa kita sebenarnya. Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam diri, mengenali kekurangan, dan memulai sebuah proses transformasi. Literasi humanitarian dimulai di sini, di titik nol pengetahuan diri. Seseorang tidak bisa benar-benar berempati kepada orang lain jika ia tidak memahami kompleksitas jiwanya sendiri. Sastra Nusantara, dengan segala metafora dan simbolnya, adalah alat untuk mengasah mata batin ini, untuk memahami bahwa di balik topeng kehidupan sehari-hari, setiap manusia adalah sebuah alam semesta yang penuh dengan misteri, keindahan, dan kerapuhan.
Ontologi Nusantara: Sastra sebagai Jembatan Antar Keberadaan
Ontologi Nusantara adalah sebuah tarian di antara dua dunia: Jagad Alit (dunia mikro, diri manusia) dan Jagad Ageng (dunia makro, alam semesta). Realitas tidak terbatas pada apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan. Ia adalah sebuah kain tenun kosmik yang menghubungkan manusia, alam, leluhur, dan entitas spiritual. Sastra, dalam konteks ini, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan semua keberadaan ini, memberikan bahasa dan narasi untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang tak terlukiskan.
Dalam epik-epik seperti Ramayana dan Mahabharata versi Jawa dan Bali, kita melihat bagaimana dewa-dewa dan raksasa bukanlah entitas yang sepenuhnya terpisah dari manusia. Mereka adalah personifikasi dari kekuatan-kekuatan yang bersemayam di dalam diri kita sendiri: kebaikan, nafsu, dan ambisi. Perjuangan para pahlawan adalah perjuangan internal, sebuah upaya untuk mencapai manunggaling kawula gusti, sebuah konsep ontologis yang paling mendalam, di mana kesadaran manusia menyatu dengan kesadaran Ilahi. Sastra memberikan gambaran visual dan narasi bagi konsep-konsep abstrak ini, menjadikannya mudah dipahami dan dihayati.
Lebih jauh, sastra Nusantara juga memberikan tempat yang sakral bagi alam. Dalam cerita rakyat, gunung bisa berbicara, sungai bisa mengalirkan kebijaksanaan, dan pohon bisa menyimpan rahasia para leluhur. Animisme bukanlah sebuah takhayul, melainkan sebuah pengakuan ontologis bahwa setiap entitas memiliki jiwa dan tempatnya dalam tatanan kosmik. Sastra, dengan merangkul alam sebagai karakter utama, menumbuhkan sebuah etos humanitarian yang melampaui batas spesies. Ia mengajarkan bahwa kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari alam, bahwa merusak hutan sama dengan melukai diri sendiri. Kesadaran ini, yang berakar pada ontologi yang holistik, adalah fondasi bagi sebuah peradaban yang berkelanjutan, sebuah peradaban yang tidak hanya peduli pada manusia, tetapi juga pada seluruh ekosistem kehidupan.
Kosmologi Nusantara: Sastra sebagai Ritme dan Harmoni Ilahi
Kosmologi Nusantara melihat alam semesta sebagai sebuah simfoni yang berirama, sebuah lingkaran yang berputar tanpa henti yang disebut Cakra Manggilingan. Hidup bukanlah sebuah garis lurus, melainkan sebuah siklus yang berulang: kelahiran, pertumbuhan, kematian, dan kelahiran kembali. Ada takdir, namun ada pula ruang untuk pilihan. Ada kebaikan, namun kejahatan juga memiliki tempatnya dalam menjaga keseimbangan. Sastra, dengan strukturnya yang berulang, temanya yang universal, dan simbol-simbolnya yang abadi, merefleksikan kosmologi ini.
Struktur pantun dengan pola a-b-a-b, misalnya, adalah manifestasi dari ritme kosmik itu sendiri. Ia mencerminkan harmoni antara sebab dan akibat, antara awal dan akhir. Dalam sebuah Macapat, setiap pupuh (bait) memiliki aturan metrum dan jumlah suku kata yang ketat, menciptakan sebuah melodi yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga meniru ritme alam semesta. Gending-gending (melodi gamelan) yang mengiringi pertunjukan wayang juga memiliki siklusnya sendiri, yang menandai setiap tahapan cerita—dari sebuah awal yang tenang hingga konflik yang memuncak, dan resolusi yang membawa kedamaian. Sastra mengajarkan kita untuk tidak takut pada siklus ini, melainkan untuk menari bersamanya.
Pemahaman kosmologis ini secara langsung membentuk literasi humanitarian. Ia mengajarkan sumarah, sebuah sikap pasrah yang bukan berarti menyerah pada nasib, melainkan sebuah penyerahan diri yang utuh pada irama kosmik. Ia menumbuhkan ketabahan dalam menghadapi penderitaan, karena penderitaan dipandang sebagai bagian dari sebuah proses transformasi. Ia mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada kesuksesan, karena kesuksesan hanyalah sebuah fase dalam siklus kehidupan. Dengan memahami ini, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh secara spiritual, tetapi juga lebih berempati terhadap penderitaan orang lain. Kita melihat setiap kejatuhan bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai sebuah jembatan menuju kebangkitan.
Sastra sebagai Cetak Biru Peradaban di Era Digital
Di era yang terfragmentasi oleh informasi dan terperangkap dalam kecepatan digital, sastra Nusantara menawarkan sebuah oasis. Ia adalah sebuah cetak biru, sebuah panduan untuk menemukan kembali kemanusiaan kita yang hilang. Sastra mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan menjadi perenung, menjadi pemikir, dan yang paling penting, menjadi manusia yang sadar akan tempatnya dalam ekosistem kehidupan yang lebih besar.
Literasi humanitarian yang diwariskan oleh sastra Nusantara adalah sebuah hadiah yang tak ternilai. Ia adalah kemampuan untuk membaca dan memahami orang lain tidak dari status media sosial mereka, melainkan dari kedalaman jiwa mereka. Ia adalah kemampuan untuk berempati tidak hanya pada sesama manusia, tetapi juga pada seekor kupu-kupu yang jatuh, sebuah sungai yang tercemar, dan sebuah gunung yang lelah.
Maka, sudah saatnya kita melihat sastra Nusantara bukan sebagai relik masa lalu yang hanya pantas di museum, melainkan sebagai sebuah alat profetik yang relevan untuk masa kini dan masa depan. Ia adalah sebuah monolog tentang kemanusiaan yang tak pernah usai, sebuah deklarasi bahwa kebenaran yang paling agung tidak akan pernah bisa direduksi menjadi data. Ia adalah bisikan yang abadi, sebuah ajakan untuk kembali ke rumah—ke dalam diri kita, ke dalam alam semesta kita, dan ke dalam narasi besar yang telah menenun kita semua.
***
Catatan Kaki:
Epistemologi Nusantara: Studi tentang cara mengetahui yang berakar pada pengalaman batin dan spiritual. Konsep ini menolak gagasan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui metode empiris dan rasionalitas Barat.
Ontologi Nusantara: Pandangan tentang realitas yang holistik, di mana dunia fisik dan spiritual saling terkait dan tidak terpisahkan. Konsep ini mendasari kepercayaan pada kesatuan antara manusia, alam, dan Ilahi.
Kosmologi Nusantara: Pemahaman tentang alam semesta sebagai entitas yang hidup dan berirama, berputar dalam siklus abadi. Konsep ini tercermin dalam berbagai praktik budaya, dari seni hingga ritual, yang bertujuan untuk mencapai harmoni dengan kosmos.
Literasi Humanitarian: Kemampuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, belas kasih, dan tanggung jawab sosial, yang melampaui batas-batas individu dan budaya.
Cakrawala Sastrawi: Sastra Nusantara, seperti kakawin, serat, hikayat, pantun, dan tembang, adalah media utama untuk mewariskan nilai-nilai filosofis, spiritual, dan etis secara turun-temurun.
Rujukan Ilmiah:
Moertono, Soemarsaid. State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Cornell University Southeast Asia Program, 1968. (Karya ini mengkaji filsafat Jawa dan kosmologinya).
Geertz, Clifford. The Religion of Java. University of Chicago Press, 1960. (Meskipun kontroversial, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang sinkretisme agama dan kosmologi Jawa).
Florida, Nancy K. Javanese Literature in Surakarta Manuscripts: Introduction and Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Karaton Surakarta Archives and the Reksa Pustaka Library at Mangkunagaran. Cornell University Southeast Asia Program, 1993. (Karya ini menyajikan studi terperinci tentang sastra Jawa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya).
Mulder, Niels. Mysticism in Java: Ideology in a Religious Tradition. Amsterdam University Press, 2005. (Buku ini mengupas tentang dimensi spiritual dan mistik dalam kebudayaan Jawa).
Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Balai Pustaka, 1984. (Sebuah rujukan klasik untuk memahami struktur budaya, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang mendasari peradaban Jawa).
Suryo, F. S. Filsafat Jawa: Pandangan Hidup Jawa. Kanisius, 1988. (Kajian yang mendalam tentang filsafat hidup yang tersembunyi dalam berbagai artefak budaya Jawa).
Susanto, A.B. Sastra Jawa sebagai Warisan Budaya Bangsa: Dari Ronggowarsito hingga Emha Ainun Nadjib. Mizan, 2012. (Buku yang menelusuri evolusi dan relevansi sastra Jawa dalam konteks modern).
Hardjono, Djoko. Manusia dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, 1986. (Karya ini membahas tentang hubungan antara manusia dan alam, yang relevan dengan ontologi dan kosmologi Nusantara).
HM. Nasruddin Anshoriy Ch. Strategi Kebudayaan: Titik Balik Kebangkitan Nasional, UB Press, 2013. (Buku ini menjelaskan bahwa kebudayaan Indonesia memiliki keberagaman yang harmonis, yang diwujudkan dalam konsep “Rumah Budaya” yang didirikan atas empat pondasi utama: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
—–
*Gus Nas Jogja. Budayawan.