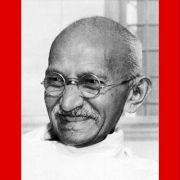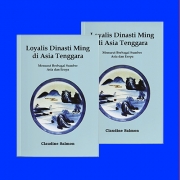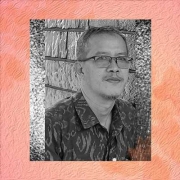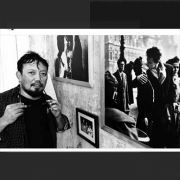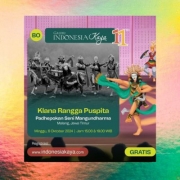Seni Pertunjukan Kemanusiaan Kontemporer
Oleh Purnawan Andra*
Jumat 26 September 2025 lalu, suasana Bundaran UGM mendadak ramai oleh suara yang tak biasa. Bukan deru kendaraan, bukan pula orasi lantang, melainkan suara panci, wajan, dan kaleng yang dipukul berulang-ulang oleh sekelompok ibu-ibu.
Sekilas, pemandangan itu mungkin terlihat sederhana, bahkan lucu bagi sebagian orang: ibu-ibu membawa alat dapur ke jalan raya. Tetapi, kalau kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan, bunyi-bunyian itu bukan sekadar riuh tanpa makna. Ia adalah jeritan, protes, sekaligus pertunjukan yang lahir dari kedalaman pengalaman sehari-hari.
Kajian Pertunjukan
Richard Schechner, seorang pemikir penting dalam Performance Studies: An Introduction (2002), pernah menyampaikan bahwa sebuah pertunjukan itu tak terbatas pada teater atau panggung seni. Segala bentuk tindakan sosial yang punya struktur ekspresif, simbolik, bahkan dramatik, bisa dibaca sebagai pertunjukan.
Jika kita menggunakan perspektif tersebut, apa yang dilakukan ibu-ibu di Bundaran UGM jelas bukan sekadar aksi politik biasa. Mereka sedang mementaskan sebuah drama sosial yang lahir dari tubuh, dari emosi, dan dari benda sehari-hari yang biasanya hanya akrab di dapur.
Di sini, panci dan wajan mendapat makna baru. Roland Barthes dalam Mythologies (1957) menjelaskan bahwa benda sehari-hari bisa bermetamorfosis jadi tanda ideologis. Panci biasanya kita bayangkan identik dengan dapur, kerja rumah, dan peran domestik perempuan.
Tapi ketika dipukul di jalan, di depan publik, panci itu berubah jadi simbol perlawanan. Ia seperti mengumumkan bahwa dapur sudah meluber ke jalan, dan urusan “domestik” kini tak bisa dipisahkan dari politik.
Bunyi yang dihasilkan pun menarik untuk dilihat dari sisi musikalitas. Theodor Adorno dalam Philosophy of New Music (1949) bicara tentang disonansi sebagai cermin masyarakat yang tak harmonis. Dentuman panci yang serampangan, tanpa ritme teratur, mungkin terdengar bising.
Tetapi justru di situlah letak kekuatannya. Ia merepresentasikan kegaduhan sosial, rasa marah, dan keresahan yang tak bisa lagi dirapikan dengan harmoni. Disonansi ini menjadi bahasa politik, sebuah pesan bahwa ada yang tak beres, sesuatu yang berjalan di luar koridor, dan tengah rusak di masyarakat. Dan suara ibu-ibu ini adalah cara untuk mengingatkan kita.
Praktik Politik
Lebih jauh, musikolog Selandia Baru, Christopher Small dalam Musicking (1998) menambahkan perspektif lain. Baginya, musik bukan benda, melainkan sebuah aktivitas. Bahwa proses bermusik itu berarti membangun sebuah relasi sosial.
Dalam konteks aksi panci itu, jelas sekali yang terjadi bukan sekadar “bunyi” tapi juga ikatan. Ketika satu panci bersuara, panci lain menjawab. Ritme spontan itu menciptakan solidaritas, rasa “kita bersama”. Bahkan bagi orang yang lewat, suara itu memaksa untuk berhenti sejenak, menoleh, dan bertanya: ada apa di sini?
Dalam konteks itu, dentuman panci bukan cuma protes, melainkan (meminjam logika Small) praktik musicking sebagai praktik politik di mana ibu-ibu saling menanggapi dentuman panci, membentuk ritme spontan yang menciptakan solidaritas. Dalam momen itu, musik menjadi cara untuk hadir bersama, untuk menyuarakan keresahan kolektif.
Hal ini menjadi menarik, ketika tubuh para ibu itu sendiri berubah fungsi. Teoritikus teater dan performance studies Jerman, Erika Fischer-Lichte dalam The Transformative Power of Performance (2008) menyebut bahwa dalam pertunjukan, tubuh bisa mengalami transfigurasi. Ia bisa menanggalkan makna sehari-hari dan menjadi medium ekspresi politik.
Tubuh yang biasanya dipandang “hanya ibu rumah tangga” di situ menjadi tubuh perlawanan, tubuh yang menantang negara dan modal. Aksi itu seperti berkata: jangan remehkan kami, tubuh ini bisa berdiri di jalan dan bersuara lantang!
Jika ditarik ke tradisi seni politik, apa yang ibu-ibu lakukan di Bundaran UGM itu sangat dekat dengan gagasan Augusto Boal dalam Theatre of the Oppressed (1974). Dramaturg asal Brasil ini percaya teater harus menjadi alat bagi mereka yang tertindas, bukan hiburan elit. Teater bukan sekadar panggung, tapi juga bisa hadir di jalan, di pasar, bahkan di bundaran. Dalam konteks ini, maka aksi ibu-ibu memukul panci ini bisa dilihat sebagai versi kontemporer dari teater tertindas itu: tanpa naskah, tanpa aktor profesional, tapi penuh dengan kebenaran dan energi politik.
Namun, yang membuat aksi ini begitu kuat justru kesederhanaannya. Mereka tidak perlu sound system besar, tidak perlu tata lampu, apalagi kurator. Mereka cukup membawa panci, wajan, dan peralatan dapur lainnya.
Simbol ini sederhana, tapi justru karena itu ia kuat. Semua orang tahu panci, semua orang bisa membayangkan dentumannya. Ia bukan simbol elitis yang jauh, tapi simbol sehari-hari yang dekat dengan hidup banyak orang.
Mengekpresikan Kemanusiaan
Dari sini kita bisa melihat bahwa seni pertunjukan kontemporer sebenarnya tidak selalu lahir dari galeri atau gedung pertunjukan. Ia bisa lahir di jalan, di bundaran, bahkan dari alat dapur. Seni ini bukan soal estetika murni, tapi soal bagaimana manusia mengekspresikan kemanusiaannya dalam kondisi yang penuh ketidakadilan. Dan bukankah itu yang membuat seni tetap relevan—ketika ia mampu merespons zaman, berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh banyak orang?
Di sisi lain, aksi ibu-ibu di Bundaran UGM ini juga mengajak kita merenungkan kembali batas antara seni, politik, dan kehidupan sehari-hari. Kita sering berpikir seni itu dunia yang eksklusif, butuh ruang khusus, butuh “pakar” untuk menafsirkan. Tapi suara panic-panci yang dipukul itu membuktikan bahwa seni bisa hadir di mana saja, dan justru menjadi lebih kuat ketika lahir dari pengalaman hidup nyata.
Lebih jauh, aksi itu juga membuka ruang tafsir soal peran perempuan. Selama ini, dapur sering dianggap ruang yang “apolitis”. Tapi lewat panci yang dibawa ke jalan, ibu-ibu itu menunjukkan bahwa yang disebut urusan domestik tak pernah bisa dipisahkan dari urusan politik.
Ketika tanah dirampas, harga-harga naik, atau lingkungan rusak, siapa yang pertama kali merasakan dampaknya kalau bukan mereka yang setiap hari mengelola dapur? Dengan kata lain, aksi panci ini juga merupakan pengingat bahwa politik itu tidak abstrak, tapi menubuh dalam keseharian.
Mungkin ada yang menganggap aksi ini sekadar riuh sementara, tak akan mengubah banyak hal. Tetapi, jika kita jujur, seni dan politik memang sering bekerja dengan cara yang sama. Mereka tak selalu memberi jawaban langsung, tapi menggerakkan perasaan, menanam kegelisahan, dan memaksa kita berpikir ulang.
Suara panci mungkin hilang setelah lalu lintas kembali ramai. Namun gema simboliknya tetap ada, menempel di ingatan kita, bahwa ada sekelompok ibu yang berani melawan, dengan cara yang sederhana tapi penuh makna.
Inilah seni pertunjukan yang paling murni, yang lahir dari situasi ketika manusia mengungkapkan kemanusiaannya dengan cara yang paling dekat, paling jujur, dan paling kontekstual.
Suara pukulan panci di Bundaran UGM tak hanya pantas dilihat sebagai protes politik, tapi juga sebagai seni pertunjukan kemanusiaan kontemporer. Sebuah seni yang tidak lahir di galeri, melainkan di jalan. Bukan dari seniman profesional, tapi dari ibu-ibu yang muak dengan ketidakadilan. Dan mungkin, justru di situ kita bisa menemukan kemanusiaan yang paling tulus: keindahan yang lahir dari keberanian untuk bersuara, meski hanya dengan panci.
——
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.