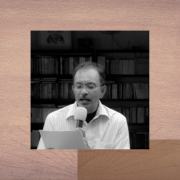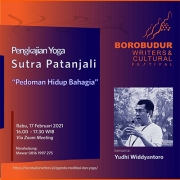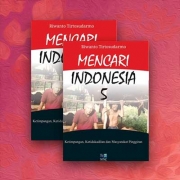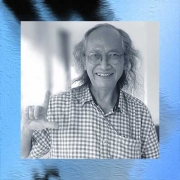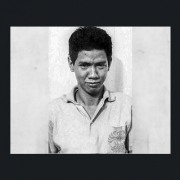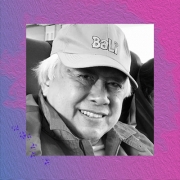Estetika Ciuman, Imajinasi yang Digugat, dan Demokrasi Takut Simbol
Oleh Purnawan Andra
Ketika seorang mahasiswi seni rupa ITB dihadapkan pada ancaman pidana karena menggubah meme dua tokoh elite nasional Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang berciuman, pertanyaannya bukan lagi semata soal kesusilaan atau pelanggaran hukum. Negara seperti memberi sinyal bahwa simbol tak boleh disentuh. Bahwa dalam demokrasi yang katanya terbuka, estetika justru jadi medan paling sensitif.
Kita tidak sedang menyaksikan penegakan hukum, tapi pertempuran tafsir: antara kebebasan dan ketakutan terhadap citra. Mengapa ciuman—sebuah gestur yang telah lama dimaknai ganda dalam sejarah seni dan budaya—justru menjadi pemicu paranoia negara?
Diskursus Estetika
Dalam seni rupa dan diskursus estetika, ciuman bukanlah tindakan biologis semata. Ia adalah simbol—sekaligus paradoks. Ia bisa menjadi simbol kekuasaan, penaklukan, rekonsiliasi, atau bahkan bentuk kekasaran kultural yang disamarkan sebagai afeksi.
Dalam karya pelukis Austria Gustav Klimt yang berjudul der Kuss (Jerman atau The Kiss dalam bahasa Inggris – 1907-1908), ciuman adalah ekstase sekaligus keterikatan. Dalam The Lovers (1928) karya pelukis Prancis Rene Magritte, wajah pasangan yang saling berciuman justru ditutupi kain, seolah menyiratkan alienasi dalam kedekatan.
Dalam konteks politik, ciuman bahkan telah lama digunakan sebagai simbol ironi kekuasaan—seperti mural terkenal My God, Help Me to Survive This Deadly Love (1990) karya Dmitri Vrubel yang menggambarkan pemimpin Jerman Timur Erich Honecker dan Leonid Brezhnev dari Soviet sedang berciuman bibir. Gambar itu bukan pelecehan, tapi komentar visual terhadap relasi kekuasaan yang terlalu intim, nyaris incestual, dan karenanya tidak sehat bagi publik.
Dalam konteks meme SSS, ekspresi visual itu menampilkan relasi kuasa antara dua figur politik dalam gestur paling personal—bukan untuk menampilkan erotisme, melainkan untuk menggarisbawahi keterhubungan kekuasaan yang dianggap “terlalu mesra.” Ini adalah satire visual. Ia tidak menuduh, tetapi bertanya. Tidak menghasut, tetapi menyindir.
Namun justru pada titik simbolik inilah negara panik. Ia membaca tubuh secara literal, bukan metaforis. Ia melihat ciuman sebagai pornografi, bukan ironi. Di sinilah kita melihat krisis simbol dalam demokrasi Indonesia: negara kehilangan kemampuan membaca representasi.
Politik Visual dalam Demokrasi
Filsuf Prancis Jacques Rancière menyatakan bahwa politik sejati muncul ketika terjadi redistribusi dari yang dapat dirasakan—yakni saat batas-batas siapa yang boleh berbicara, mencipta, dan terlihat digugat. Dalam konteks ini, meme SSS adalah upaya menyuarakan keresahan melalui media visual. Ia tidak hadir dalam debat politik formal, tetapi lewat bahasa yang lebih dekat dengan generasinya: satir, meme, dan estetika tubuh.
Meme sebagai medium visual khas zaman digital mengungkap absurditas politik yang dirasakan generasi SSS, mahasiswa seni. Persis seperti grafiti-grafiti perlawanan di tembok-tembok kota, meme itu adalah “catatan liar” atas kekuasaan yang terlalu steril di atas panggung formal.
Estetika dalam demokrasi bukan hanya soal keindahan, tapi tentang siapa yang punya hak untuk merepresentasikan kenyataan. Ketika mahasiswa menciptakan imaji kuasa dalam format ciuman, ia sedang menciptakan ketidakteraturan indra: ia mengganggu, memancing tawa getir, dan membuka ruang tafsir baru. Ia melawan estetika hegemonik negara—yang selama ini hanya ingin citra seragam, khidmat, dan terkontrol.
Sejarah seni perlawanan mencatat banyak ekspresi yang pada masanya dianggap ofensif. Ingat karya Guernica (1937) oleh Pablo Picasso, yang menggambarkan kekejaman perang dalam gaya kubistik yang menyesakkan. Atau The Third of May 1808 (1814) oleh pelukis Spanyol Francisco Goya—lukisan eksekusi yang brutal tapi jujur. Seni selalu memiliki peran untuk menggugat, bahkan jika menggugah rasa tidak nyaman.
Dalam perspektif cultural studies, meme adalah wujud paling mutakhir dari “kreativitas rakyat” (vernacular creativity). Ia hadir bukan sebagai karya seni agung, melainkan bentuk artikulasi keresahan harian. Stuart Hall menyebut budaya sebagai arena kontestasi makna; dan dalam dunia digital, meme adalah senjata kecil untuk mengusik narasi besar yang hegemonik.
Meme SSS adalah ekspresi dari generasi muda yang makin kehilangan ruang. Ia tumbuh di masa ketika ruang kampus direpresi, media dibungkam, dan forum publik diganti baliho. Maka, satu-satunya arena terbuka yang tersisa adalah media sosial—tempat di mana gambar dan simbol berbicara lebih tajam dari ceramah.
Dalam masyarakat digital, di mana narasi bersaing dalam kecepatan dan kelincahan, meme menjadi bentuk ekspresi politik generasi muda. Ia bukan petisi atau pamflet, tetapi ironi visual yang memadukan humor dan kritik.
SSS, sebagai mahasiswa seni, tidak berbicara dalam bahasa hukum, tapi dalam bahasa budaya. Ia mengekspresikan kegelisahan politik bukan lewat forum kampus, tapi lewat meme. Meme itu mengolok, tetapi juga menyingkap. Ia mengaburkan batas antara publik dan privat, simbol dan tubuh, kekuasaan dan imajinasi. Ini bukan bentuk penghinaan, melainkan bentuk perlawanan semiotik.
Dalam konteks ini, meme bukan lagi sekadar hiburan. Ia adalah “pernyataan estetika” generasi yang frustrasi, sekaligus penolakan atas estetika kekuasaan yang kaku, formal, dan tak tersentuh. Dan tentu saja, ini tak cocok dengan logika negara yang masih ingin mengendalikan narasi melalui lembaga resmi dan simbol sakral.
Dan inilah yang gagal dibaca negara: bahwa dalam medan simbolik, makna selalu jamak. Bahwa tidak ada simbol yang sakral tanpa bisa ditafsir ulang. Negara, dengan menggugat meme sebagai pelanggaran hukum, justru memperlihatkan kepanikan terhadap hilangnya kontrol atas tafsir.
Demokrasi Tidak Panik
Negara yang benar-benar demokratis tidak takut pada imajinasi. Ia tidak panik melihat parodi, tidak terguncang oleh simbol yang dibalikkan. Justru, keberanian membiarkan tafsir berkembang adalah salah satu indikator kematangan demokrasi.
Sebaliknya, negara yang trauma terhadap simbol menunjukkan kelemahan: bahwa ia tidak percaya pada warganya untuk membedakan satire dan hasutan, bahwa ia lebih memilih membungkam daripada berdialog. Respon aparat terhadap meme ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya ingin mengontrol tindakan, tetapi juga citra dan perasaan publik.
Hal ini ironis jika kita mengingat ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia. Apa artinya ambisi itu jika ruang ekspresi dibatasi, simbol dibekukan, dan tafsir disentralisasi? Ibu kota kebudayaan dunia bukan hanya soal gedung kesenian atau festival budaya, tapi keberanian membiarkan seni menjadi gugatan, bukan sekadar hiasan.
Apa yang kita saksikan hari ini bukan demokrasi estetis, melainkan estetikokrasi: sistem di mana estetika hanya boleh muncul jika mendukung kuasa. Di dalamnya, seni dikurasi oleh penguasa, simbol dikendalikan oleh negara, dan imajinasi disensor oleh hukum.
Dalam estetikokrasi, simbol ciuman menjadi ancaman karena ia membongkar keintiman kuasa yang selama ini diselubungi oleh formalitas. Dalam estetikokrasi, kritik yang datang dari humor atau satire dianggap lebih berbahaya dari ujaran kebencian yang terang-terangan. Dalam estetikokrasi, kreativitas generasi muda direduksi menjadi “penghinaan” jika tidak sesuai dengan moral penguasa.
Tapi justru di sinilah seni menemukan keberaniannya. Di saat negara hanya menyukai kesenian yang patuh, imajinasi yang liar menjadi bentuk pembangkangan yang paling murni.
Jika Indonesia ingin menjadi bangsa besar dalam kebudayaan, ia harus berani menjadi besar dalam tafsir. Demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi tentang keberanian memberi ruang pada imajinasi yang tak tunggal. Seni harus bisa berbicara dalam berbagai bahasa—termasuk dalam ironi, satir, bahkan absurditas.
Meme yang dibuat SSS, betapapun kontroversialnya, adalah bagian dari perbincangan itu. Ia adalah tanda bahwa rakyat masih punya rasa, bahwa mahasiswa masih mau berpikir visual, dan bahwa demokrasi belum sepenuhnya mati.
Yang mengkhawatirkan bukanlah meme itu, tetapi negara yang takut membacanya.
—
*Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.