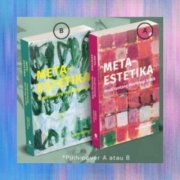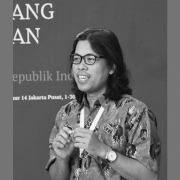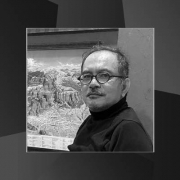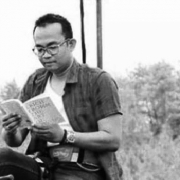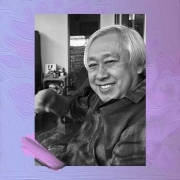Tubuh Tari Arjuna, Estetika Nusantara dan Gender sebagai Konstruksi Budaya
Oleh Purnawan Andra*
Dalam diskusi webinar bulanan Relevansi dan Aktualisasi Budaya Panji bertema “Transgender dalam Cerita Panji” yang diselenggarakan Komunitas Seni Budaya BrangWetan pimpinan Henri Nurcahyo pada hari Rabu (30/4/2025), terjadi diskusi menarik tentang pokok pembahasan yang “tidak biasa” ini.
Hadir sebagai narasumber budayawan Seno Gumira Ajidarma dan peneliti transgender Dede Oetomo serta diikuti oleh beberapa nama penting dalam kebudayaan seperti Lydia Kieven (arkeolog, peneliti Panji dari Jerman), Noriah Mohamed (Universiti Sains Malaysia), Ninuk Kleden (antropolog Universitas Indonesia), dan Rohmat Djoko Prakosa dari STKW Surabaya, “memperkarakan” ekspresi estetis gender cerita Panji (baca: tradisi Nusantara) sebagai medan makna yang mengalami proses konstruksi budaya.
Pada akhir diskusi, Seno Gumira (yang menyajikan hasil penelitiannya berjudul “Orientasi Seksual Panji: Konstruksi Budaya dalam Intermediasi” yang dimuat di portal Borobudur Writers & Cultural Festival ini) menegaskan kreatifitas dan daya adaptasi yang membuktikan kecerdasan sekaligus kedewasaan masyarakat Nusantara dalam memaknai gender melalui ekspresi seni budaya yang dikreasikannya.
Dalam konteks pembahasan tentang gender (cross dan atau trans-), maskulin-feminin, pun tentang seksualitas sebagai wacana, pada titik ini kita bisa jadi teringat pada Arjuna. Tokoh ini, dalam epos Mahabharata dan pewayangan Jawa, disebut sebagai lelananging jagad—”lelaki utama jagad raya.” Gelar yang tidak hanya menunjuk keunggulan fisik, tapi juga kehalusan budi, kejeniusan strategi, kehebatan spiritual, dan tentu, daya pikat seksual.
Namun ketika tubuh Arjuna dimunculkan dalam praktik estetika tradisi, terutama dalam seni tari klasik Jawa, sesuatu yang paradoksal terjadi: di (keraton) Yogyakarta, Arjuna ditarikan oleh lelaki dengan karakter alusan (lembut, halus, tidak agresif), sedangkan di (keraton) Surakarta, justru ditarikan oleh perempuan. Pun kadang sebaliknya – sesuatu yang kadang masih saja berlangsung hingga kini.
Maka muncul pertanyaan: di mana sebenarnya letak maskulinitas utama itu? Apa makna dari maskulinitas jika ia dapat dinegosiasikan melalui tubuh dan ekspresi gender yang cair?
Diskursus Maskulinitas
Diskursus maskulinitas ini tidak lahir di ruang kosong. Ia hadir sebagai refleksi atas ketegangan antara mitos dan tubuh, antara gagasan dan ekspresi performatif. Arjuna, sang “lelaki utama”, adalah tokoh yang menghabiskan banyak waktunya bertapa, berpuasa, dan menolak kekuasaan demi mencapai puncak spiritualitas. Ia bukan pemimpin politik seperti Yudhistira, bukan juga pemusnah musuh seperti Bima.
Arjuna adalah figur estetik sekaligus erotik. Ia dikisahkan punya ratusan istri dan kekasih, namun juga digambarkan sebagai pria yang lembut, bahkan feminin dalam banyak versi pewayangan Jawa. Ia adalah penggoda sekaligus yang digoda. Ia “lelaki” yang tidak maskulin dalam pengertian patriarkal-modern.
Dalam tradisi tari Jawa (Yogyakarta-Surakarta), karakter alusan sangat menonjol dalam representasi Arjuna. Tubuh penari lelaki dibentuk untuk menampilkan sikap halus, tidak agresif, penuh pengendalian diri, dan gestur yang hampir feminin.
Penari Arjuna tidak berjalan tegap penuh otot, melainkan mengalir, menunduk, bersikap sumeleh. Bahkan dalam bedhaya, tari keraton yang sakral dan penuh nuansa spiritual, gestur Arjuna serupa dengan gerak tubuh perempuan. Apa artinya ketika “lelaki utama” diwujudkan dalam tubuh yang justru menjauh dari stereotip maskulin?
Di wilayah kebudayaan lainnya, Arjuna kerap kali juga diperankan oleh perempuan. Secara teknis, tubuh perempuan dianggap lebih pas untuk menampilkan gestur alus dan artikulasi gerak yang halus.
Namun hal ini bukan sekadar soal teknik. Ketika perempuan memerankan tokoh yang secara simbolik dianggap puncak dari kejantanan, maka tubuh itu menjadi medan tafsir baru. Perempuan tidak sekadar “meniru” dan “menyerupai” laki-laki; ia menjadi lelaki utama dalam versi yang paling disakralkan dalam kosmologi pewayangan.
Maka gender di sini bukan esensi, tapi performa. Dan performa selalu bisa dinegosiasikan, ditransformasi. Ini menggugat asumsi dasar tentang maskulinitas. Dalam struktur budaya patriarkal modern, maskulinitas sering dilekatkan pada tubuh biologis laki-laki yang kuat, dominan, dan agresif.
Tapi tubuh Arjuna dalam tari membantah itu. Ia lemah lembut, tidak dominan, bahkan cenderung pasif. Jika maskulinitas adalah konstruksi budaya, maka tradisi pertunjukan Jawa telah sejak awal menyajikan gagasan maskulinitas yang cair, ambigu, dan kompleks. Maskulinitas bukanlah soal testosteron atau suara berat, melainkan tentang narasi, posisi sosial, dan tafsir simbolik.
Sistem Tafsir yang Lentur dan Performatif
Dalam konteks sekarang, hal ini menjadi sangat relevan dan kontekstual. Wacana gender dan identitas seksual semakin menantang batas-batas lama antara maskulin dan feminin. Representasi Arjuna sebagai tokoh yang bisa diperankan siapa saja—lelaki halus, perempuan, bahkan tubuh transgender—membuka ruang bagi pembacaan baru terhadap tubuh dan kuasa.
Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa budaya lokal sebenarnya tidak selalu kaku dan biner dalam memahami gender. Justru melalui estetika tubuh dan narasi epik, masyarakat tradisi telah lama mengoperasikan sistem tafsir yang lentur dan performatif.
Dalam konteks kajian budaya (cultural studies), wacana tubuh Arjuna menjadi penting sebagai titik kritik terhadap dominasi wacana gender Barat yang kerap memaksakan oposisi biner. Konsep Judith Butler dalam Gender Trouble (1990) tentang gender sebagai performatif membantu menjelaskan bagaimana maskulinitas Arjuna bukanlah entitas tetap, melainkan hasil repetisi kultural yang dinamis.
Tari tradisional Jawa, dalam hal ini, adalah teknologi budaya yang mereproduksi sekaligus menggugat gender. Ia tidak sekadar mempertontonkan karakter, tetapi mewujudkan tafsir gender dalam level simbolik dan afektif.
Lebih lanjut, pendekatan queer dalam cultural studies juga membuka kemungkinan membaca tubuh Arjuna sebagai tubuh trans. Bukan hanya karena bisa diperankan siapa saja, tapi karena ia secara naratif juga mengalami “transisi” identitas: dari ksatria perang menjadi pertapa, dari penakluk wanita menjadi Begawan Mintaraga, dari maskulin ke feminim dalam banyak level.
Dalam beberapa lakon wayang, Arjuna bahkan menyamar sebagai perempuan atau hidup sebagai pelayan istana perempuan, seperti saat menjadi Wrahatnala. Tubuh Arjuna adalah tubuh yang tidak pernah tetap, selalu dalam ambang, selalu menjadi sesuatu yang lain dari dirinya semula.
Dalam tradisi Nusantara sendiri, praktik trans-gender bukan hal asing. Di Bugis kita mengenal bissu, imam sakral yang melampaui batas lelaki-perempuan. Di Banyuwangi ada seblang—roh yang merasuk tubuh anak perempuan untuk menghadirkan kuasa transenden.
Dalam konteks ini, tubuh sebagai medium spiritual dan kultural tidak pernah sepenuhnya tunduk pada norma biologis. Maka pembacaan Arjuna sebagai figur trans bukanlah pemaksaan wacana kekinian ke dalam tradisi, melainkan penggalian kembali terhadap cara tradisi itu sendiri memahami kelenturan identitas dan tubuh.
Problem Kontekstual
Namun di sinilah juga muncul problem: jika tradisi Jawa telah mengenal fleksibilitas gender, mengapa praktik sosialnya tetap konservatif dan patriarkal? Mengapa tubuh perempuan dalam kehidupan sehari-hari tetap mengalami subordinasi, kekerasan, dan kontrol?
Jawabannya mungkin karena seni dan kehidupan tidak selalu berjalan paralel. Dalam seni, tubuh bisa menjadi apa saja; dalam kehidupan sosial, tubuh dibatasi oleh norma, agama, dan institusi. Maka perlu ada kerja politik budaya yang serius untuk menjembatani fleksibilitas estetika dengan pembebasan tubuh yang nyata.
Arjuna, dalam hal ini, bisa menjadi simbol subversif. Ia adalah tokoh yang membuka kemungkinan untuk menggugat norma gender, termasuk dalam konteks seni pertunjukan masa kini.
Ketika seniman muda menampilkan Arjuna dengan tubuh transgender atau membongkar narasi “lelaki utama” melalui tafsir queer, mereka tidak sedang menghina tradisi, melainkan meradikalisasi potensinya. Mereka sedang menunjukkan bahwa tradisi tidak harus normatif. Ia bisa menjadi ruang kritik, ruang tafsir ulang, ruang kemungkinan.
Dalam dunia yang terus bergerak menuju pengakuan atas keberagaman identitas, Arjuna perlu dibaca ulang. Ia bukan hanya pahlawan epik, tapi juga simbol ambiguitas gender.
Tubuh Arjuna adalah tubuh yang bisa melampaui biner, tubuh yang menolak fiksasi. Ia adalah “lelaki utama” bukan karena tubuhnya maskulin, tapi karena ia mewakili kompleksitas manusia yang utuh: spiritual, erotik, strategik, sekaligus penuh laku pengendalian diri.
Maka jika ada krisis maskulinitas hari ini, mungkin itu karena kita terlalu lama memaksa maskulinitas menjadi satu bentuk tetap—kuat, keras, dan dominan—padahal dalam tubuh Arjuna, maskulinitas justru halus, lentur, dan membuka ruang bagi kehadiran yang lain.
Justru dalam keretakan antara citra dan tubuh itulah, kita bisa melihat potensi politis dari estetika. Tradisi bukanlah kuburan nilai, melainkan taman tafsir. Dan tubuh Arjuna adalah bunga yang mekar dengan segala ambiguitas, kelenturan dan potensi kontesktualisasi pemaknaannya.
—
*Purnawan Andra, alumnus Jurusan Tari ISI Surakarta. Bekerja di Direktorat Bina SDM, Lembaga & Pranata Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.